Perayaan HUT Totamana, 9 Mei 2017. Kredit foto: Kabar Pugay
AWAL bulan Juli 2016, telpon genggam saya bergetar. Tertulis nomor baru. Saya beranikan diri menganggat telpon. Terdengar suara sopan di ujung sana, “Syalom ade, ini Kaka Frans. Kaka ingin minta bantuan ade untuk menulis pengantar di buku kaka. Ini buku tentang teologi lokal kitong di Suku Mee (komunitas yang berada di kawasan Paniai, kini juga di kabupaten baru yaitu Dogiyai dan Deiyai, termasuk di Nabire).” Saya merespon cepat, “Baik kaka. Ade siap. Apakah kaka bisa kirimkan naskah lengkapnya kah? Agar ade lihat,” sambung saya. Frans Bobii lalu menjawab, “Kaka kirim tempo (cepat). Nanti kaka telpon kalau su (sudah) kirim email. Kaka minta ade pu (adek punya) email.” Tidak sampai seminggu, email yang berisi naskah lengkap saya terima di email dua kali berturut-turut.
Saya tentu saja penuh penasaran membuka halaman demi halaman dari naskah bukunya. Pada bagian pengantar buku sudah dijelaskan maksud Kaka Frans menuliskan buku ini:
Ini adalah sebuah sejarah teologi lokal diajarkan secara turun temurun bertahun-tahun dalam perkumpulan manusia kuno asal suku Mee yang berdomisili di kampung Tadauto, Debey, Deiyai, Papua. Tampaknya sangat gila dari sudut pandang masa kini, tetapi sebuah perbandingan tinggi yang luar biasa dari seorang sosok Waodeyokaipouga membuat sejarah adalah orang beriman.
…
Ini adalah buku tentang rahasia mistis dan supernatural. Saya berupaya mencoba untuk menggali apa sebenarnya dalam semua ungkapan di balik ajaran Wodeyokaipouga Bobii, selama bertahun-tahun sebelum agama tertulis memasuki wilayah Paniai pada umumnya. Sesuatu tentang arus spritualitas bawah tanah yang berbeda itu memiliki kesamaan dalam sebuah fokus cara kerja supranatural di dunia.
Saya melihatnya sedang berimajinasi. Kaka Frans sedang memulai gerakan untuk menggali teologi lokal (pribumi) yang sangat kaya dan berdampak besar bagi kehidupan agama dan sosial budaya di tanah Papua. Gerakan teologi pribumi inilah yang kemudian terus tergerus tertelan hadirnya “peradaban” melalui “pengagamaan” orang-orang Papua. Meski pengaruh kehadiran agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam tak terbantahkan, eksistensi teologi-teologi pribumi yang “membadan” dalam ingatan dan kehidupan orang Papua—dalam berbagai bentuknya—tak akan pernah lekang. Kaka Frans melalui bukunya ini memulai dari Tanah Meewo, pertiwi orang Mee.

(Alm) Fransiskus IGN Bobii pada masa hidupnya sebagai Kepala Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Papua (foto: Tabloid Jubi).
Buku ini ahirnya terbit dengan judul Wodeyokaipouga Bobii, Nabi yang Terlupakan. Sayangnya, Fransiskus IGN Bobii, begitu nama lengkapnya, setelah menerbitkan buku ini akhirnya meninggal dunia pada Jumat, 17 November 2017 di Rumah Sakit Umum Siriwini, Kabupaten Nabire. Ia terakhir menjabat sebagai Kepala Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Papua. Sebelum terjun menjadi birokrat, Frans Bobii adalah seorang wartawan dan penulis buku yang produktif. Beberapa karyanya diantaranya, Menuju Nabire Baru bersama A.P. Youw; Prospektif Adama Youw Merintis Nabire; Quo Vadis Rakyat Papua di Era Otsus; Manusia Mee dalam Proses Pembangunan Bangsa Indonesia; Deiyai dalam Proses Pembangunan Bangsa, Herman Tillemans, Awepitoo, dan terakhir adalah Wodeyokaipouga Bobii, Nabi yang Terlupakan.
Frans Bobii menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1998, saat menginjak semester III di Institut Pastoral Indonesia (IPI) Filial Jayapura. Frans Bobii yang kelahiran 8 Agustus 1976 itu tertarik pada dunia jurnalistik setelah membaca banyak buku panduan tulis-menulis kala itu. Ia mengakui bahwa dunia kewartawanan menuntut kita senantiasa berpikir untuk mencurahkannya dalam bentuk tulisan. Tidak sekadar bicara. Meski telah menjadi pegawai di pemerintahan, ia tidak melupakan kebiasaannya menulis.
Sekalipun banyak tugas pemerintahan dalam pelayanan kepada 18 ribu jiwa, namun saya luangkan waktu juga untuk menulis
Tidak heran, meski telah menjadi kepala distrik, tulisan-tulisannya tetap hadir. Buku-buku pun terus bermunculan yang membuktikan semangat menulisnya tidak hilang. Meski beralih dari “Kuli Tinta menuju Kuli Pemerintah”,[1] hingga akhir hayatnya Frans Bobii menunjukkan kegelisahannya. Salah satu hal yang membuatkan gelisah adalah fenomena teologi pribumi di daerahnya sendiri.
Esai ini awalnya adalah pengantar saya untuk buku Wodeyokaipouga Bobii, Nabi yang Terlupakan. Saya menambahkan kenangan saya, sekaligus kehormatan saat diminta menulis pengantar bukunya, pada bagian awal esai ini. Pada beberapa bagian lainnya saya menambahkan informasi seputar Wodeyokaipouga Bobii yang keseluruhannya berasal dari naskah awal.
Gerakan Wodeyokaipouga Bobii
Adalah di Kampung Tadauto, Debey, Deiyai Papua kisah ini berawal. Sosok yang menginspirasi kelahiran gerakan teologi lokal bagi orang-orang Mee itu adalah Wodeyokaipouga Bobii. Ia kemudian menciptkan komunitas bernama Komunitas Wodeyokaipouga, yang mempelajari ajaran-ajaran tentang teologi lokal yang kontekstual. Teologi inilah yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum agama samawi hadir. Dalam horizon yang lebih luas, ajaran teologi-teologi lokal yang “membadan” dalam kehidupan komunitas penganutnya adalah ekspresi teologis (kepercayaan) sekaligus kebudayaan tentang Ugatamee (Tuhan dalam bahasa Mee). Ajaran-ajarannya tidaklah berada di awang-awang namun memiliki relasi historis dengan kehidupan sosial budaya mereka secara luas.
Buku yang ditulis oleh Frans Bobii ini membawa kita untuk menyelami pengalaman religius yang dialami oleh Wodeyokaipouga Bobii, salah satu penggerak agama lokal di Kampung Tadauto, Debey, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua. Pada masyarakat Mee, filosofi kehidupannya bersandar pada pondasi Totamana, terdiri dua kata: Tota=sudah ada, telah ada; mana=berita, suara, kabar, sehingga secara harafiah dapat dijelaskan sebagai suatu yang sudah ada sejak sebelumnya. Totamana bisa diartikan sebagai suatu kabar yang sudah ada sejak lama. Sementara Touyemanaterdiri dari tiga kata: Tou=tinggal, berdiam, duduk; Ye=suatu keheranan, heboh; dan Mana=suara, kabar, berita. Touyemana dengan demikian adalah sebuah pandangan hidup yang berprinsip pada mendudukkan sesuatu pada tempat semula, sebagai ajakan moral, agar tetap dan akan hidup. Toutamana terdiri dari kata: Tou=tinggal, berdiam, duduk; Ta=keheranan terhadap suatu; dan Mana=berita, suara, kabar. Jadi Toutamana mengandung arti bahwa suatu kabar gembira itu ada sepanjang sejarah hidup manusia. Sementara Tounemana terdiri dari kata Tou=tinggal berdiam, duduk tersembunyi; Ne=perintah atas dirinya untuk tinggal; dan Mana=Berita, kabar, suara. Dengan demikian Tounemana adalah suatu hukum yang tidak mau pergi dan mengikat kepada manusia sebagai penganutnya (Bobii, 2016).
Dalam konteks yang lebih luas, Bobii (2016) melanjutkan bahwa menurut ajaran agama pribumi, Totamana mengungkapkan kerinduan akan Tuhan melalui beberapa ungkapan secara spontan, walaupun mereka belum mengenalnya, dan mengetahui melalui tanda-tanda alam yang terjadi dalam situasi hidup Mereka. Misalnya mengenal Tuhan berdasarkan tanda-tanda alam yang diwujudnyatakan melalui ada sesuatu yang menjadikan dunia dan manusia (kokeewadome, kokaumiyomee), artinya di atas langit ada orang yang mencipta dan di dalam tanah ada manusia yang sedang mengayomi kita manusia. Berbagai bentuk pujaan dan doa serta kepercayaan mengawasi mereka.
Filosofi dan fondasi kehidupan orang Mee dalam hubungannya dengan Ugatame (Tuhan) inilah yang dijadikan dasar oleh Wodeyokaipouga Bobii untuk menyebarkan karya teologis sekaligus juga karya sosialnya. Simaklah bagaimana pandangan Wodeyokaipouga Bobii tentang Tuhan Allah dalam bahasa Mee:Edoga puki paki ko uwo eguu na beu momogi na beu, yitiyouto, yimuna beu kidi tota. Uwo modo kiyake toba yokaa pamakita.Toba mado kiyake udi yoka pamakita. Udi modoo kiyake me yokaa woo pamakita. Okai kii me kidiki ekako enato bapa. Yamake epa ugaina epi. Maki ugaina epi. Maikai ugaina epi, kiyake ugatame ekaa motita (Bobii, 2016).
(Bagi Wodeyokaipouga Bobii, Allah pada mulanya air. Air itu bersih dan murni dan tidak ada ujung dan pangkalnya. Air itu mengandung dan melahirkan berudu. Berudu mengandung dan melahirkan udang. Udang mengandung dan melahirkan manusia. Manusia itu disebut Enato Naitai (Bapak Tunggal/Bapa Yang Esa). Dia yang berkuasa menciptakan langit, bumi dan lautan dan segala yang ada di dalamnya, maka Dia di beri julukan Ugatame (Allah menurut Suku Mee) artinya Pencipta.
Nilai-nilai filosofis dari ajaran Wodeyokaipouga Bobii diikuti dengan menerjemahkannya dalam syair doa-doa dalam lagu. Di dalam lagu-lagu yang diajarkannya bermakna pujian, penyembahan, dan juga lagu yang memohon keselamatan jasmani rohani, kerinduan akan memperoleh hidup yang kekal, dan juga memuji kekuatan Allah. Ayat-ayat teologi lokal yang di ajarkannya di mulai dari kisah penciptaan dan diakhiri dengan ajakan merendahkan diri mengikuti Tuhan (Bobii, 2016).
Selain dalam karya teologis, Wodeyokaipouga Bobii juga berkarya secara sosial. Diantaranya adalah kegiatan pembersihan dan pemagaran lingkungan sejak tahun 1940-an. Sebelumnya ajarannya dimulai sejak tahun 1920-an.Wodeyokaipouga Bobii mengejawantahkannya menjadi dua belas jenis kegiatan yang dikenal dengan sebutan Gaa bado wiyamagati kouko tenayaikai. Kedua belas macam kegiatan itu diantaranya; pemagaran lingkungan, pembersihan lingkungan, pembangunan rumah berpola asrama, pesta bersama atau makan bersama, lbadah bersama atau sembahyang bersama, pembuatan kolam sampah, pembuatan tempat toilet, perkebunan, pertanian, perikanan darat, reboisasi atau penghijauan, serta pengumpulan dana. Jangan dilupakan pula adalah kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi komunitasnya dalam program perkoperasian masyarakat. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu telah ditetapkan tiga jenis kegiatan yaitu usaha bersama, pengumpulan dana dan pengadaan kios koperasi masyarakat (Bobii, 2016).
Kerangka kerja teologis dan sosial yang diterapkan oleh Wodeyokaipouga Bobii tentunya mengalami tantangan terutama dari Ogai (orang luar/asing) yang selalu berpandangan bahwa hanya merekalah yang memiliki kebenaran. Dalam konteks transformasi sosial budaya yang terjadi, pengaruh penginjilan, gereja, dan pendidikan sangatlah penting perannya. Dalam catatan Bobii (2016), tahun 1965 merupakan tahun peradabaan baru yang mengubah tatanan sosial budaya masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pihak gereja Katolik dan Kigmi membuka sekolah SD YPPGI di Widuwakiya dan SD YPPK di Wagomani. Yohanes Gobay (Mantan Ketua Wilayah GKII Papua, Pdt. Yohanes Gobay, S.Th), ditugaskan sebagai guru pertama di SD YPPGI Widuwakiya setelah selesai dari SGB (sekolah Guru Bawah). Sementara di pinggiran Danau Tigi terdapat SD YPPGI Bomou, SD YPPGI Onago, SD YPPGI Gako Kebo dari kalangan Gereja Kingmi waktu itu sudah dibuka. Setelah orang Debey belajar membaca dan menulis, mereka yang bisa membaca dijadikan tenaga pengajar bagi warga buta aksara (Bobii, 2016).

Buku Wodeyokaipouga Bobii, Nabi yang Terlupakan (foto: Istimewa).
Pada momen ini sebenarnya sudah terjadi fragmen-fragmen perubahan di tengah komunitas Wodeyokaipouga Bobii saat merespon hadirnya agama, birokrasi, pendidikan, dan tentu saja perubahan yang dibawa oleh arus migrasi manusia di seluruh pelosok tanah Papua. Menarik untuk mencermati dalam studi-studi selanjutnya tentang bagaimana arus transformasi ini direspon oleh para penganut teologi-teologi lokal.
Gerakan Teologi Lokal (Pribumi)
Menyelami gerakan-gerakan teologi lokal di tanah Papua sangatlah menarik. Tidak terkecuali gerakan Wodeyokaipouga Bobii yang memiliki akar sejarah budaya dan hidup dalam keseharian masyarakat Mee. Masyarakat penganut teologi lokal ini mengalami totalitas pergumulan manusia dengan Tuhan mereka dan juga lingkungan sosial budaya yang membentuknya. Pada tataran inilah sangat penting memperhatikan konteks sosial, termasuk di dalamnya kondisi kehidupan komunitas dari berbagai bidang kehidupan yang mendasari ekspresi teologis mereka.
Jika kita menelisik lebih dalam, keberagaman teologi lokal atau agama-agama pribumi di tanah Papua mengundang kesalahpenamaan sebagai “ajaran sesat” atau menghadap-hadapkannya dengan agama samawi yang hadir belakangan untuk membawa “terang” dan “peradaban”. Perspektif ini sangat melecehkan karena seolah-olah sebelumnya dengan teologi pribumi/lokal, komunitas pendukungnya berada dalam “kegelapan”. Dalam wacana yang lebih luas, seperti ditengarai oleh Giay (1995:281), aspek kekuasaan juga terjadi dalam bidang agama saat diberlakukannya pemaksaan terhadap kebijakan sosio-religius, politik, ekonomi dari luar dengan pendekatan yang konfrontatif. Komunitas-komunitas teologi pribumi inilah yang sering menjadi korbannya. Komunitas penganutnya diberlakukan secara tidak manusiawi, misalnya rumahnya dibakar, dipenjarakan, dan mengalami kekerasan secara psikis.
Saya meyakini—seperti juga yang dilakukan oleh Giay (1995) bahwa sangatlah penting untuk memahami kemarahan, tangisan, serta keresahan dari para komunitas agama pribumi ini. Namun, itu saja tidak cukup. Langkah ke depan yang harus dilakukan adalah memahami gejolak mereka untuk melangkah ke depan. Pandangan teologis dari ajaran teologi-teologi pribumi ini tak bisa diabaikan apalagi disingkirkan. Melalui pemahaman terhadap perspektif teologi lokal, kita akan dibawa menyelami dunia kosmologis dan imajinasi-imajinasi manusia tentang Tuhan, dunia, dan sudah tentu kehidupan itu sendiri.
Oleh sebab itulah mengembangkan sikap yang apresiatif, terbuka, toleran, serta mengedepankan pendekatan dialog teologis sangatlah penting dilakukan. Selain akan mengembangkan pemikiran untuk terbuka terhadap pandangan teologis berbeda, yang lebih penting adalah memperkaya pengetahuan teologis maupun sosio-kultural terhadap sejarah dan perkembangan teologi-teologi lokal. Inspirasi dan pengetahuan teologis dan sosial budaya akan membawa kita kepada pemahaman tentang dinamika teologis maupun sosio-kultural orang-orang Papua yang sedang berubah. Transformasi (perubahan) sosial-budaya yang tak terhindarkan di tanah Papua menuntut pemahaman yang utuh dan penghargaan terhadap keberadaan komunitas teologi lokal (pribumi) ini.
Kekayaan pengetahuan teologis dan sosio-budaya di tanah Papua sangatlah penting untuk dituliskan. Dalam perspektif antropologis, memahami dunia berpikir teologi pribumi orang Papua juga berarti memahami laku hidup itu sendiri. Meski konteksnya akan terus berubah, memahami fondasi kosmologi teologi pribumi Papua dan ekspresi-ekspresi kebudayaan menjadi hal yang sangat penting.
Benny Giay, pendeta dan intelektual Papua jauh sebelumnya menulis disertasi doktornya yang berjudul ”Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya” di Vrije Universiteit, Belanda. The Netherlands pada tahun 1995. Ia menulis gerakan perlawanan Wege Bage pada masyarakat Mee di Pegunungan Tengah Papua yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Zakheus Pakage. Ia bersama komunitasnaya menolak ogai, penyiar agama Kristen berkebangsaan Barat dan atau orang dari luar Papua. Giay (1995:277) yang melakukan studi mendalam tentang Zakheus Pakage dan Wege Bage mengungkapkan bahwa sangat penting melihat bagaimana respon teolog pribumi dan gerakan keagamaannya dalam meletakkan dasar bagi pengembangan teologi pribumi. Perintis gereja pribumi juga merumuskan Kekristenan sesuai dengan aspirasi dan kerangka berpikir sosial-keagamaan dari kelompok masyarakatnya.
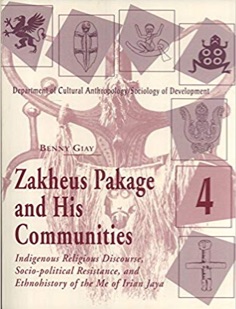
Disertasi Benny Giay tentang gerakan Wage Bage dari para pengikut Zakheus Pakage (1995) (foto: istimewa).
Zakheus Pakage ketika datang dari Makassar Agustus 1950 membuat suasana berubah. Sebelumnya, hingga tahun sebelum Agustus 1950, masyarakat Suku Mee menolak Ogai dalam semua bentuk kebijakannya. Masyarakat ingin mengikuti ajaran Zakheus yang kemudian membentuk kampung-kampung Kristen menurut teologi dan kerangka pikir sosial keagamaan pribumi (orang Mee). Kampung-kampung Kristen dan pengikut Zakheus inilah yang kemudian dinamakan Wege Bage oleh Ogai yang berarti orang-orang yang mengganggu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Transformasi yang terjadi adalah pertemuan antara teologi pribumi yang dikembangkan oleh Zakheus dengan teologi Kristen dan Ogai yang bertujuan untuk mencegah orang Papua dari cengkeraman penguasa kegelapan dan membawanya ke terang injil (Giay, 1996:40). Transformasi lainnya adalah eksistensi Hai dan Wege Bage di tengah transformasi sosial budaya yang berlangsung pada masyarakat Mee. Pada interkoneksi teologi pribumi dan transformasi sosial yang berlangsung inilah dinamika dan kebudayaan rakyat Papua akan terbentuk.
Refleksi
Saya ingin menutup esai sederhana ini dengan sebuah pertanyaan tentang imajinasi-imajinasi perubahan dan respon dari komunitas teologi lokal. Di tengah situasi transformasi sosial budaya yang tak terhindarkan, memperhatikan ajaran-ajaran teologis dan praktik-praktik ritual dan sosial budaya dari komunitas agama pribumi menjadi sangat menarik. Fragmen tersebut akan memberikan gambaran jejak perubahan sosial budaya yang terjadi. Dari pemaparan singkat ini kita diharapkan dapat memahami bagaimana pandangan religi telah hidup di tengah masyarakat dan memengaruhi kehidupan banyak orang. Namun, kita semestinya harus terus berefleksi bahwa keseluruhan pengalaman religi dari manusia adalah merupakan jejak historis sekaligus juga budaya yang patut dipahami dan dihargai untuk penghormatan terhadap Tuhan dan manusia itu sendiri.***
Mnukwar (Kampung Lama)/Manokwari, Juli 2016
I Ngurah Suryawan, antropolog yang menekuni studi tentang Papua. Bukunya (cetak ulang), Jiwa yang Patah: Rakyat Papua, Sejarah Sunyi, dan Antropologi Reflektif (akan terbit 2019).
Daftar Pustaka
Giay, Benny, 2000. Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
Giay, Benny, 1986. Kargoisme di Irian Jaya. Sentani: Region Press.
Giay, Benny. 1995. ”Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya” PhD Dessertation Vrije Universiteit The Netherlands.
Giay, Benny. 1996, “Pembangunan Irian Jaya dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Antropologi” makalah dalam Simposium Masyarakat dan Pembangunan di daerah Irian Jaya yang dilaksanakan BPC GMKI Jayapura tahun 1996.
Giay, Benny. 1996a, “Masyarakat Amungme Irian Jaya, Modernisasi dan Agama Resmi: Sebuah Model Pertemuan” Majalah Deiyai Januari-Februari 1996.
Giay, Benny, 1996b. ”Masyarakat Amungme (Irian Jaya), Modernisasi dan Agama Resmi: Sebuah Model Pertemuan” dalam Kisah dari Kampung Halaman. Yogyakarta: Interfidei.
Kamma, F. C., Koreri, 1972. Messianic Movements in The Biak-Numfor Area, The Hague, Martinus Nijhoff.
Radongkir, Daniel Charles Elisa. 2001. “Transformasi Gerakan Koreri pada Orang Biak di kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (Suatu Tinjauan Antropologis)” Skripsi pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.
Rutherford, Danylin. 2000. “The White Edge of the Margin: Textuality and Authority in Biak, Irian Jaya, Indonesia” dalam American Etnologist Vol. 27, No. 2 (May, 2000), pp. 312-339
Strelan, J. G. dan Godschalk, J. A.,
1989. Kargoisme di Melanesia,
Jayapura : Pusat Studi Irian Jaya.
—————
[1] Tabloid Jubi menulis profilnya dengan judul: “Fransiskus Bobii: Dulu Kuli Tinta Kini Kuli Pemerintah” (19 September 2011). Lihat https://tabloidjubi.com/arch/2011/09/19/frans-bobii-dulu-kuli-tinta-kini-kuli-pemerintah/ (diakses 8 Januari 2019)






