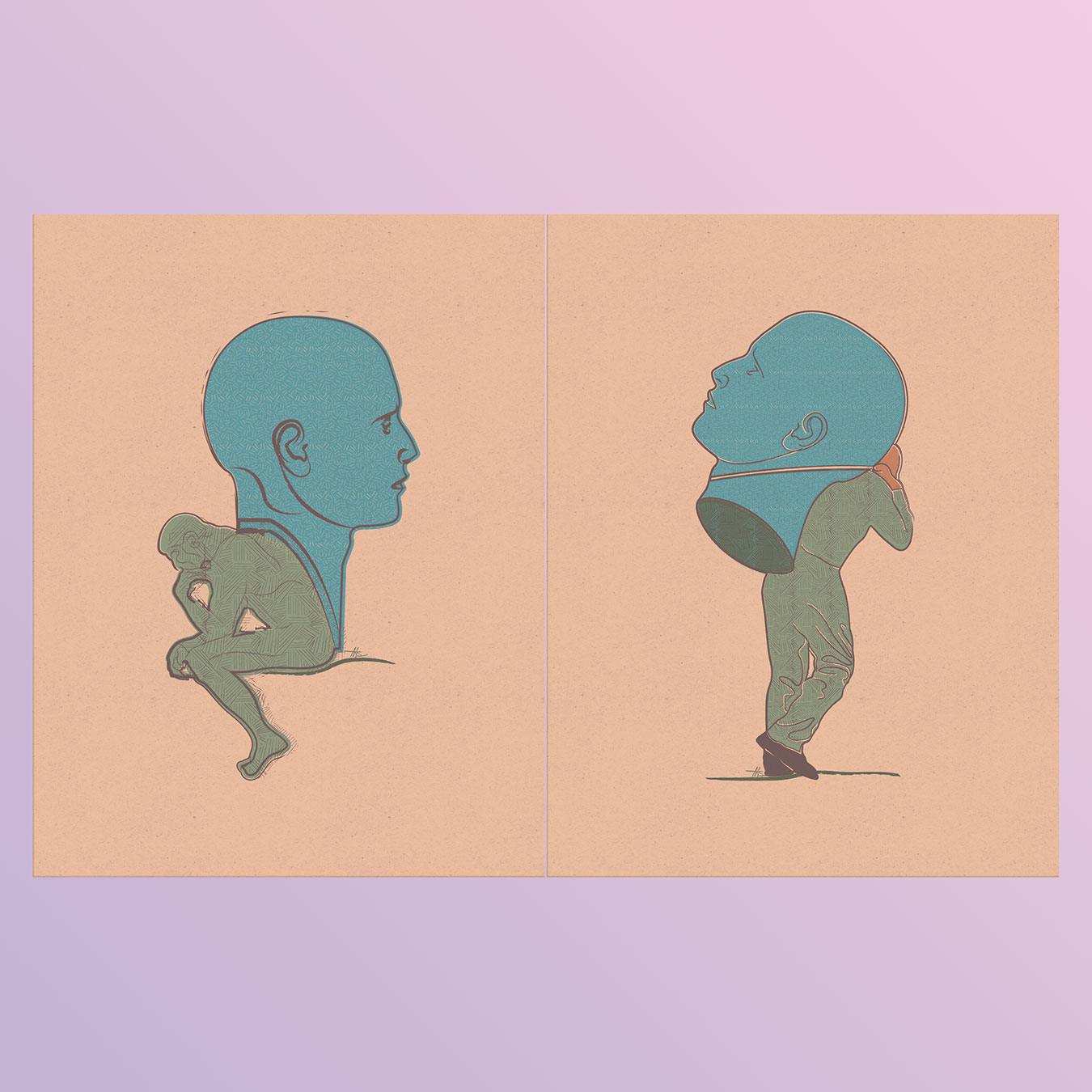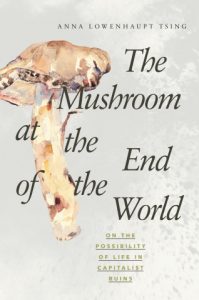
Judul Buku: Mushroom at the End of the World: on the Possibility of Capitalist Ruins
Penulis: Anna Lowenhaupt Tsing
Penerbit: Princeton University Press, 2015
Tebal: xii + 323 halaman
PERTANYAAN tentang bagaimana suatu barang diproduksi hingga sampai ke tangan seorang pembeli/pemakai/konsumen menarik minat banyak antropolog dalam satu dekade terakhir. Istilah global life of things—atau yang saya terjemahkan sebagai rantai kehidupan komoditas—menarik karena proses pelacakan akan membawa kita ke pemahaman yang lebih kompleks tentang komoditas itu sendiri. Ia tidak hanya menanyakan aspek materialisme-ekonomi suatu barang (seperti kampanye “berapa harga sepatumu?” untuk menunjukkan nilai lebih yang dihisap dari buruh), tetapi menilik relasi komoditas yang lebih kompleks.
Buku Mushroom at the End of the World (selanjutnya disebut Mushroom) karya Anna Tsing kurang lebih melakukan hal tersebut lewat salah satu komoditas primadona dari Jepang: jamur matsutake.
Petualangan jamur matsutake—dari tumbuh hingga sampai ke tangan para konglomerat sebagai hadiah simbolik para elite—jauh lebih kompleks dari yang orang bisa duga. Ia melibatkan para ahli dari pusat riset jamur di Cina, negara-negara Skandinavia, Amerika Serikat, Jepang; juga terkait dengan hutan-hutan pinus yang harus ada walau mengindikasikan hutan yang “gersang”; serta para imigran dan pencari jamur asal Asia Tenggara di Oregon, Amerika Serikat, yang berusaha mengubur masa lalu perang dan konflik etnis.Ditulis dengan liris dengan bab-bab yang singkat, Mushroom berfokus pada konsep salvage capitalism (kapitalisme penyelamatan). Salvage capitalism menerangkan bahwa pasar tidak hanya menghasilkan barang melalui penambahan nilai semata, tetapi mencerabutnya dari produksi spontan dari alam. Ada proses pendalaman kapital dan nilai lebih di dalamnya. Proses ini membutuhkan kerapuhan atau situasi prekariat dari komponen yang terlibat dalam produksi, termasuk si jamur.
Ulasan ini dibagi menjadi tiga bagian: bagian pertama menyusun ulang secara deskriptif proses produksi matsutake yang mengembara dari hutan-hutan yang meranggas; kedua adalah analisa teoritik Tsing terhadap proses yang ia jabarkan; bagian ketiga adalah kritik terhadap konsep, perlakuan, dan penjelasan Tsing tentang proses produksi tersebut.
I.
Matsutake tidak hanya simbol kultural Jepang. Ia juga menjadi penanda modernitas karena pertama kali dicatat dalam puisi Jepang kuno abad ke-18—abad ketika pertambangan tradisional muncul. Matsutake hanya bisa tumbuh di hutan yang pernah dijamah manusia (hlm. 3-4). Jamur matsutake tumbuh di antara pohon-pohon yang dibabat habis, juga bersamaan dengan menjamurnya pohon-pohon pinus yang mendiami hutan-hutan yang telah rusak.
Legenda pasca Perang Dunia II di Jepang bahkan mengatakan jamur ini adalah yang pertama tumbuh setelah bom nuklir menghancurkan Hiroshima (hlm. 4).
Namun matsutake tak selamanya gampang dicari. Jamur ini semakin sulit ditemui pada tahun ‘70an, ketika kerusakan lingkungan yang bahkan tidak mampu ditembus oleh ekosistem hutan pinus semakin akut. Era ini sekaligus menandai perdagangan global jamur matsutake dan kolaborasi pasar jamur di berbagai belahan dunia semisal Swedia, Laos, hingga Amerika Serikat.
Persoalannya, kolaborasi ini tak bebas nilai. Di dalamnya terdapat sejarah yang kelam; imperialisme dan penghancuran. Hal ini Tsing kemukakan ketika menjelaskan pemetik jamur di salah satu wilayah penyuplai jamur paling besar, Oregon, negara bagian di Amerika zona pantai barat.
Para pemetik di Oregon menjual jamur yang berhasil mereka kumpulkan ke para pembeli sebelum dikirim ke penadah. Para pembeli menggunakan sistem “tiket terbuka”, dimana para pemetik berhak mendapatkan kelebihan uang jika harga pertama yang ia pakai berubah menjadi lebih banyak. Misalnya, jika pemetik menjual di hari Rabu pagi seharga 15 dolar per lima kilogram jamur, dan di hari Rabu sore harganya jadi 25 dolar per lima kilogram, maka si pemetik berhak atas kelebihan 10 dolar. Tsing melihat proses ini sebagai kebebasan ekonomi baik untuk pemetik maupun para pembeli yang berusaha bersaing dengan pembeli lainnya (hlm. 75).
Para pemetik tidak terlalu memahami pasar matsutake di Jepang yang masif dan elite. Dalam rekaman Tsing, para pemetik ini “memiliki fantasinya sendiri tentang Jepang yang mereka juga belum tentu pahami. Dunia matsutake mereka terlepas dari semua itu: sebuah praktik kehidupan yang memahami barang yang menjadikan mereka penyuplai” (hlm. 58). Kemana boks-boks jamur dibawa setelah itu, para pemetik di Oregon tidak mengetahuinya.
Dengan demikian, ada patahan antara segmentasi pasar jamur di Amerika dan Jepang, yang itu menciptakan keberagamannya sendiri namun tetap menjadi bagian ekonomi global bernama kapitalisme (ibid).
Mayoritas pemetik jamur adalah imigran dari Asia Tenggara seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tsing masuk lebih dalam ketika bicara soal imigran pemetik jamur ini. Ia beralih ke pembahasan mengenai sejarah berlumuran darah Amerika yang membabi buta membombardir negara asal para pekerja.
Memang tak semua imigram Asia Tenggara memilih bekerja di sektor ini. Ada pula, banyak malah, komunitas Jepang-Amerika di Oregon yang memilih mendirikan restoran.
Terputusnya orang Jepang-Amerika dari memori kolektif soal jamur matsutake di Oregon bukan tanpa sebab. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari Perang Pasifik. Komunitas Jepang-Amerika menutup ingatan kultural di bawah teror anti-Jepang pasca Pearl Harbor dibom pada 1943. Tidak hanya dijebloskan ke kamp konsentrasi, harta hingga tanah (untuk berkebun) mereka dijarah kala itu. Mereka kemudian takut menjadi “Jepang”. Hal ini diakomodasi oleh semangat Protestanisme-Evangelis Amerika Serikat dengan politik asimilasi.
Orang-orang Jepang pada akhirnya meninggalkan bahasa dan budaya mereka untuk menjadi “Amerika”; matsutake menjadi fragmen kecil dan sebatas dipetik untuk acara keluarga atau jadi hadiah kecil untuk kerabat (hlm. 103-105).
Di sisi lain, bekerja sebagai pemetik jamur juga memberi makna baru bagi mereka, yang tampaknya bernada positif—hal ini juga dirasakan para pemetik kulit putih yang sebagian besar adalah veteran perang di Timur Tengah dan bahkan Vietnam. Tumbuhnya jamur dan mekanisme pasar yang begitu kecil (hlm. 79-80) adalah penyembuh luka dan/atau justru membuka ingatan akan tanah yang dulu pernah mereka tinggali.
Keberadaan para pemetik ini juga hadir bersamaan dengan para penadah, atau middlemen. Para penadah atau perantara ini adalah stop terakhir sebelum jamur masuk ke arena para eksportir. Dalam lingo kapitalisme Amerika, orang-orang di tengah ini sebetulnya tidak begitu disukai. “Demam kuning” atau kode untuk semangat anti-Cina dan Jepang pasca migrasi besar-besaran rakyat Tiongkok setelah jatuhnya kekaisaran hingga kebangkitan Mao Zedong; atau pasca pemboman Pearl Harbor, adalah penyebabnya. Namun matsutake, menurut Tsing, membuat apa yang dilakukan penadah jadi narasi kecil tersendiri yang unik.
II.
Di awal tadi disebutkan bahwa Mushroom berfokus pada konsep salvage capitalism atau kapitalisme penyelamatan. Tsing menjelaskan ini sebagai “penciptaan nilai kapitalis dari rezim nilai non-kapitalis” (hlm. 128).
Kapitalisme kontemporer rupanya tidak terlalu tertarik menyeragamkan semua lini produksi—setidaknya demikian yang coba diargumenkan Tsing dalam bukunya. Ia justru membuka ruang untuk corak produksi non-kapitalis tumbuh dan berkembang, berjalan di satu titik, tanpa merampas apa yang, misalnya, orang-orang etnis Hmong dan Mien punya.
Ringkasnya, yang terjadi pada kapitalisme penyelamatan bukan penguasaan, tapi pembiaran, karena yang non-kapitalis ini turut membantu pembangunan pasar tadi.
Konsep salvage accumulation menjadi sentral dalam argument Tsing karena ia berupaya memperlihatkan kemungkinan hidup di bawah kapitalisme tanpa menjustifikasikan kapitalisme itu sendiri. Ada ruang-ruang yang tidak mampu dijamah oleh kapitalisme, dan justru dibiarkan karena ia bertumpu pada yang non-kapitalis tersebut untuk tetap hidup. Di ruang non-kapitalis inilah orang-orang berorganisir dan hutan dan jamur hidup sebagaimana mereka ingin hidup; terasing atau bahkan tidak peduli terhadap ingar bingar pasar.
Lewat konsep tersebut Tsing berhasil mengurai mekanisme terpenting di dalam kapitalisme: penerjemahan. Bagi Tsing, kapitalisme adalah sebuah mesin penerjemah dalam memproduksi kapital dari berbagai bentuk kehidupan (hlm. 133). Namun selayaknya terjemahan, tidak ada yang sempurna dan presisi. Proses ini dipenuhi tambalan—dari jamur yang tetap tumbuh dan tidak tunduk pada perkembangan teknologi (sampai hari ini jamur matsutake tidak bisa ditanam secara sintesis) hingga sistem open ticket di tengah hutan Oregon.
Namun proses terjemahan ini harus melalui dua hal yang Tsing anggap paling penting: alienasi dan akumulasi (hlm. 133). Alienasi menciptakan ketercerabutan suatu barang dan terus menyeretnya ke nilai tukar yang tak habis-habis. Akibatnya, alienasi pun menciptakan akumulasi, dan akumulasi kemudian menerjemahkan kepemilikan menjadi kekuasaan (ownership into power) karena agregat dari seluruh nilai yang dirampas dalam suatu barang berubah menjadi kuasa atas nilai.
Tsing menggunakan “kontigensi (atau kemungkinan-kemungkinan dari) pertemuan” (contingencies of encounter) sebagai titik awal menganalisa kapitalisme (hlm. 142). Pertemuan-pertemuan dari sebuah kejadian (imigran Asia Tenggara dan matsutake, para periset jamur dari Korea Utara dan Jepang) tidak bisa dianggap sebagai konsekuensi logis-linear semata, karena ia bukan hal yang semata-mata repetitif. Bertemunya banyak kejadian untuk mendorong proses yang lebih besar (perdagangan jamur) justru membuka ruang pemahaman baru bagaimana keadaan dapat berubah dan mengubah seluruh rangkai produksi.
Lebih jauh, pendekatan Tsing di atas dapat mengantarkan kita ke narasi-narasi kehidupan yang terus tumbuh, walaupun tidak kekal, dan kemunculan-kemunculan hal baru di bawah panji kapitalisme yang semakin menggurita. Hal ini dimungkinkan karena aransemen narasi manusia dan non-manusia yang begitu kompleks ini adalah cerita tentang penggabungan, perubahan, dan penglarutan. Yang jelas, ujar Tsing, ia tidak pernah berhenti dan terus melanjutkan hidupnya (hlm.158).
Dari melacak pertemuan-pertemuan yang bisa terjadi karena satu komoditas seperti matsutake, Tsing juga mengingatkan kita bahwa alienasi tanpa institusi yang kokoh dapat terjadi. Tsing menyebut proses ini dapat terjadi melalui latent commons (kepemilikan bersama laten) (hlm. 255). Ada tiga karakter yang menempel dalam latent commons:
- Kepemilikan bersama yang laten ini tidak hanya digunakan oleh manusia, tetapi juga non-manusia. Itu sebabnya matsutake juga dianggap sebagai aktor yang memiliki peran sama pentingnya dalam menggenerasikan proses perdagangan dirinya sendiri. Ia harus tumbuh di pepohonan tertentu; ia hanya akan muncul di temperatur tertentu; dan ia hanya akan makan nutrisi dari mineral batu yang dibawa organisme lain ke sekitar jamur.
- Kolaborasi dalam produksi kepemilikan bersama yang laten ini belum tentu menguntungkan semua pihak. Nematoda yang menyerang pepohonan pinus akan berakibat buruk pada jamur matsutake sementara nematoda justru datang karena nutrisi dari batu yang juga menjadi makanan jamur. Semua ini juga berefek kepada para pemetik jamurnya dan proses ekspor yang diatur oleh kuota—mereka jelas akan merugi dalam hal ini.
- Kepemilikan bersama yang laten ini tidak dapat diinstutionalisasikan dengan baik. Fakta bahwa jamur matsutake belum bisa ditanam di luar habitat naturalnya meski telah diriset ratusan tahun (sejak awal sejarah Edo) adalah salah satu contohnya. Pasar matsutake termasuk salah satu pasar jamur yang sangat bergantung pada seluruh ekosistem penunjang, tanpa teknologi mutakhir apa Kasus di mana komoditas ini kerap kali menjadi langka atau malah jatuh harga sering terjadi.
- Hanya karena karakternya yang tak dapat diatur, kepemilikan bersama ini tidak dapat membebaskan kita. Ada upaya untuk menguasai komoditas seperti matsutake untuk menjadi simbol politik/utopia komunitas tertentu, tapi sejauh ini upaya tersebut gagal. Ia akan terus ada dan berlanjut, sesuai mekanismenya, tanpa mempedulikan mereka yang memberi nilai pada komoditas tersebut.
III.
Ada beberapa hal yang rasanya perlu diproblematisir lebih jauh dari klaim-klaim besar lagi teoritik yang genial dari Tsing. Tiga hal yang akan saya soroti di sini adalah konsep “aransemen polifonik”; “alienasi non-manusia”; dan “skala horizontal.”
Antropolog tersebut, layaknya Tania Li dalam analisanya terhadap lanskap politik hutan, menggunakan konsep “aransemen polifonik” (“polyphonic” assemblage). Konsep assemblage yang paling otoritatif dikembangkan oleh duo filsuf Perancis, Deleuze dan Guattari, dalam A Thousand Plateaux. Kata sifat “polifonik” disematkan ke dalam aransemen (terjemahan saya untuk assemblage) untuk memperlihatkan heterogenitas struktur social dan hilangnya kesatuan dalam sebuah aransemen yang berlapis-lapis. Permasalahannya, konsep assemblage ala Deleuze-Guattari sudah menjelaskan hal tersebut tanpa tambahan adjektif tertentu. Aransamen menurut mereka adalah “konstalasi” yang tidak linear, dan memiliki artikulasi satu sama lain, di tengah sekumpulan elemen heterogen (Deleuze & Guattari 2005, hl. 312, 350).
Jika dalam aransemen polifonik ala Tsing apa yang “politik” menjadi kabur di antara narasi “estetik” dan “puitik” dalam melihat ko-eksistensi manusia, pasar, jamur, dan hutan, aransemen ala Deleuze-Guattari justru melihat stratifikasi sebagai luaran maupun yang mempertahankan struktur sosial yang menopangnya (dalam hal ini kapitalisme dan modernitas).
Walau Tsing beberapakali menyebut bagaimana matsutake dihasilkan dari para pekerja kulit putih miskin (anti-modernitas dan anti-liberal, alias konservatif, bukan dalam pemahaman liberal di Indonesia) dan para imigran Asia Tenggara, hingga sampai dengan harga bombastis dengan monopoli pasar jamur di Jepang, cerita tersebut lebih terlihat sebagai sesuatu yang puitik alih-alih penanda ketimpangan kuasa.
Tentu tidak ada yang salah dalam narasi estetika dan puitik dalam etnografi seperti yang Tsing lakukan, tetapi konsep aransemen yang tidak linear bukan berarti melupakan medan dan permainan kekuasaan di dalamnya.
Terakhir mengenai konsep aransemen polifoniknya. Tsing mengatakan bahwa teoretisasinya “menangkap aktor-aktor non-manusia” (hlm. 23) walaupun sejak awal, tidak ada sentimen antromorfis di dalam konsep awal assemblage ala Deleuze dan Guattari (Deleuze & Guattari, hlm. 310-312).
Konsep “alienasi-non manusia” (hlm. 121) juga dikemukakan Tsing sebagai pengembangan alienasi Marx. Saya tidak terlalu familiar dengan antropologi, tetapi dalam Grundrisse, alienasi paling pertama manusia justru tidak dari kerja (labor), tetapi tercerabutnya manusia dengan alam, vice versa. Hal ini juga digali dengan baik di tiga ratus halaman mengenai ground rent atau sewa tanah di Capital III dimana ekosistem tanah teralienasi baik dari proses produksi agrikultur manusia maupun ketika sebuah pabrik menentukan lahan tempat ia beroperasi hingga, konsekuensinya, menentukan harga produk barang (spatial fix, lihat Harvey 2001; Marx [1981] 1991, hlm. 752).
Skala horizontal yang menjadi kritik Tsing untuk melihat menjalarnya sistem kapitalisme (hlm. 37-38) juga dibahas oleh David Harvey dalam Spaces of Hope (2000). Hanya karena ia horizontal, bukan berarti ia tidak memiliki skala (hlm. 42). Skala horizontal memang belum banyak digali banyak akademisi dan pemerhati studi tersebut.
Skala sendiri tidak hanya unit pengukuran. Menurut Neil Smith, skala adalah resolusi geografis dari proses kontradiktif dari kompetisi dan ko-operasi (Smith 1993: 99). Dengan demikian, skala tidak lagi persoalan pengukuran, tetapi lebih kepada dampak perubahan ruang (dalam artian abstrak); ia adalah elemen relasional dalam pertemuan kompleks yang memuat ruang, tempat, lingkungan—dan apa pun yang membuat geografi di mana kita tinggal dan belajar (Marston 2000: 221). Tetapi, juga tidak melulu sebuah pengukuran kaku akan dampak; jika ia bekerja secara horizontal, ia akan turut mengubah pola sebuah sistem (misalnya kapitalisme) bagi si penerimanya (dalam hal ini matsutake, orang-orang imigran Asia Tenggara, sistem Open Ticket, dll) (Roswaldy 2018). Artinya, kritik Tsing terhadap skalabilitas belum terlalu tajam karena didasari dari definisi skala yang memang sudah berubah.
Kritik ini tentu bukan hanya sekedar argumen membosankan tentang orisinalitas. Akan tetapi ia justru keluar dari harapan akan pemahaman yang lebih dalam tentang kapitalisme dan relasi komoditas.
Tsing memberikan contoh yang amat baik dan sangat penting dalam melihat suatu komoditas yang lebih dari sekedar proses uang-kapital-uang (M-C-M’). Dalam proses tersebut ada banyak ruang tempat orang memaknai apa arti perdagangan global ini bagi mereka dan di mana mereka berada; termasuk mereka yang non-manusia. Namun seluruh peristiwa tersebut bisa lebih dari sekedar cerita yang apa adanya. Dalam narasi aransemen misalnya, walaupun benar analisa totalitas tidak mampu menjawab dengan baik kompleksitas kapitalisme hari ini, ia tidak bisa menelurkan analisa tentang bagaimana ia tetap mempertahankan struktur dan kuasa (Stewart 2018).
Dalam Ordinary Affect, Kathleen Stewart melakukan etnografi ke aktivitas reguler masyarakat di Amerika, sembari tetap melihatnya sebagai domain-domain dimana kapitalisme, seksisme, dan rasisme bertahan dan dipertahankan. Kencan buta yang gagal, para orang kulit putih pemarah di selatan Amerika, tetap diposisikan sebagai domain kekuasaan; ia puitik dan tetap politis. Narasi yang politis ini tidak dijamah dengan baik dalam buku Mushroom walaupun di awal Tsing mengingatkan bahwa bukan tujuan utamanya untuk berkontribusi kepada narasi besar mengenai kapitalisme.
Walaupun bagi Tsing mencoba memahami kapitalisme dengan melihatnya melalui aransemen dan sejarah multi-tujuan aneh, tapi saya melihatnya sebagai kewajaran. Hanya saja, saya agak mempermasalahkan nosi prekariaritas yang tampak jelas dan menjadi motor penggerak pertemuan-pertemuan dan mozaik kapitalisme di kasus matsutake.
Prekaritas selalu menjadi petulangan (hlm. 163), menurut Tsing. Tetapi petualangan yang bagaimana? Apakah ini petualangan avonturir yang bebas nilai? Setidaknya dari pemaparan hidup pekerja Asia Tenggara di Oregon, jelas prekaritas ini tidak netral. Tsing memang mengimplikasikan prekaritas dalam nilai tertentu, tetapi narasi puitiknya dapat mengaburkan hal tersebut.
*
Bagaimanapun, saya tetap memberi rating yang tinggi untuk Mushroom. Kontribusi metodologisnya tidak terbantahkan. Dan sumbangan metodologis jelas turut mendorong kita mempertanyakan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Tsing menunjukkan bahwa kadang iblis memang ada di detail yang seringkali terlupakan dari narasi besar; baik jargon perkembangan/pembangunan, utopia, maupun revolusi.
Jika kita menuju “perubahan” dan “perkembangan” pun (apa pun artinya dua kata tersebut), kita tetap harus melewati proses panjang berliku yang semakin terjal, di bawah reruntuhan -isme yang mencekik; kapitalisme, rasisme, kolonialisme, seksisme, dan lain sebainya. Menelusuri reruntuhan untuk menunjukkan arena permainan kekuasaan global dan hal-hal yang tidak tampak menentukan justru sama pentingnya (hlm. 213) dengan menelusuri sistem dan pola yang sudah terlihat dan terus berkembang.***
Perdana Putri adalah mahasiswa dokoral di department of Sociology, Northwestern University, AS.
Referensi tambahan:
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. 2005. A Thousand Plateau: Capitalism and Schizophrenia. University of Minnesote Press: Minneapolis.
Marston, Sallie A. 2000. “The Social Construction of Scale.” Progress in Human Geography 24(2): 212-242.
Marx, Karl. 1981 [1991]. Capital III. Penguin Books: London.
Roswaldy, Perdana. 2018. “Re-scaling Modernity: Jumping, Difusing, and Bending” (tidak untuk dipublikasikan. Hubungi penulis untuk mendapat manuskripnya)
Smith, Neil. 1992. “Geography, Differences, and Politics of Scale.” Pp. 57-79 in Postmodernism and Social Science, edited by J. Doherty, E. Graham, & M. Malek. Palgrave Macmillan: New York.
Stewart, Kathleen. 2018. Ordinary Affect. Duke University Press.