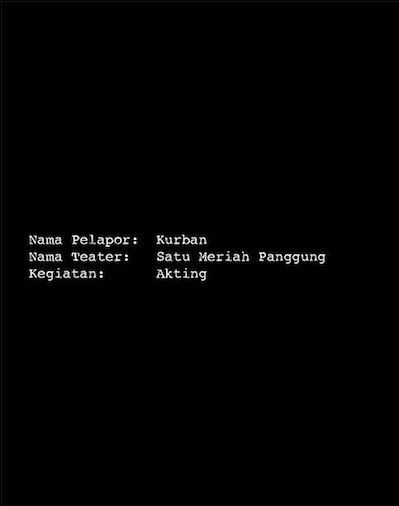Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
SAYA tak gemar suudzon. Drama Ratna Sarumpaet, yang tak kalah recehannya dengan serial televisi Tanah Air kegemaran kalian, konon, merupakan bagian dari persekongkolan yang lebih besar. Fadli Zon terlibat. Prabowo Subianto mengetahui dan memberi restu. Anies Baswedan punya andil. Para minions—Dahniel Anzar Simanjuntak, Rachel Maryam, Sandiaga Uno, Fahira Idris, Amien Rais, Hanum Rais dkk? Tentu saja, mereka dengan sukarela melibatkan diri.
Gerombolan si kampret, konon, merencanakan drama operasi plastik tersebut dari jauh-jauh hari. Ratna Sarumpaet, juru bicara gerombolan, akan menjalani sedot lemak. Foto “babak belurnya” selepas operasi akan disebar gerombolan seiring cerita ia diteror oleh orang-orang suruhan rezim. Selanjutnya, ia akan pergi ke Chili untuk menghadiri pentas Franki Raden didanai Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia tak akan pulang dengan dalih ketakutan kembali ke Indonesia.
Dampaknya? Ratna Sarumpaet bukan saja tidak akan diperiksa. Ia akan menjadi eksil sekaligus monumen kebengisan rezim. Seorang disiden yang sama gagahnya dengan Ai Weiwei, Vaclav Havel atau, nama yang lebih akrab, Rizieq Shihab.
Namun, sebelum ada bukti apa pun yang mengemuka ke publik—atau saya dengar lewat seseorang terpercaya—saya sungkan berkomentar. Teori konspirasi ini masih sama masuk akalnya dengan teori bahwa Ratna Sarumpaet dibisiki oleh setan atau digelitiki tuyul. Lebih-lebih, teori konspirasi tersebut digadang ke mana-mana tak lain oleh gerombolan si cebong.
Seperti yang saya bilang, saya tak gemar berburuk sangka.
Kendati demikian, berkat drama recehan tersebut, kita kian insaf dengan satu teknik yang diulang-ulang para politisi untuk menggayung perhatian khalayak. Teknik yang klise, menjemukan, tapi entah mengapa tak pernah gagal menggugah pemirsanya: menagih rasa iba.
Gerombolan si kampret bukan penemunya, tentu.
***
Anda bersimpati dengan underdogs. Mereka yang kalah dalam hidup. Mereka yang memanggul ketidakadilan-ketidakadilan dunia kendati tak pernah memintanya.
Haru Urara, seekor kuda pacuan dari kota pesisir Kochi, Jepang, telah mengikuti lebih dari seratus kali perlombaan pacuan kuda. Tak ada satu pun yang dimenangkannya. Kuda pacuan yang payah seharusnya dijagal. Akan tetapi, Haru Urara, yang namanya berarti lompatan yang jaya, justru menjadi cerita yang mengundang simpati seantero Jepang ketika pemiliknya kasihan dengannya dan namanya diangkat surat kabar.
“[Haru Urara] adalah contoh yang baik dari pantang menyerah,” ujar Junichiro Koizumi, Perdana Menteri Jepang waktu itu.
Di pacuan ke-106 Haru Urara, Joki paling andal di Jepang, Yutaka Take, menyatakan akan memenangkan sang kuda. Orang-orang dari segala penjuru datang ke kota Kochi yang mungil. Mereka semua mempertaruhkan uangnya untuk kemenangan Haru Urara. Haru Urara tak menang. Ia menyelesaikan pertandingan di urutan ke-10. Namun, sang joki mengajak Haru Urara mengitari lapangan setelah pertandingan—hal yang biasa hanya dilakukan oleh pemenang. Para penonton tetap bahagia karena menyaksikan Haru Urara yang tak menyerah.
Pacuan kuda Kochi yang di ambang kebangkrutan, berkatnya, selamat dan masih beroperasi hingga hari ini.
Cerita yang tidak asing? Tentu saja. Keibaan terhadap mereka yang kalah, bahkan yang bukan manusia sekalipun, menjadikan kita manusia. Cerita ihwal pengemudi ojek daring yang dizalimi pemesannya tak pernah gagal mengundang rasa kasihan dan membuat kita ekstra-awas dengan perlakuan kita sendiri terhadap mereka. Koin untuk Prita adalah cerita lain tentang keibaan yang acap dibajak untuk kampanye memalukan potensi transformasi positif media sosial.
Atau kalau Anda mau tahu dampak yang lebih kolosal dari simpati terhadap underdogs, Indonesia sendiri adalah contoh paripurnanya. Republik di kurun revolusi giat menggalang dukungan untuk menghalau agresi Belanda, lengkap dengan balatentaranya yang perkasa, dengan memosisikan dirinya sebagai Daud yang menghadapi Goliat. Sang liliput yang harus tegak menantang segala kemustahilan.
“Ini tahun 1776 [tahun puncak perjuangan kemerdekaan AS] di Indonesia,” tulis Sudarpo Sastrosatomo, staf pemerintahan Indonesia yang ditempatkan di New York, dalam naskah yang dibagikannya untuk para wartawan, pejabat, serta delegasi PBB.
Dan persoalannya, tidak ada yang lebih sadar dengan daya dari rasa iba ketimbang politisi. Betul, politisi—seseorang yang mencari nafkah dengan mengaduk-aduk perasaan khalayak, acap secara tak bertanggung jawab, vulgar, dan menjijikkan.
Anda, oleh mereka, biasanya tidak dituntun untuk bersolidaritas dengan pihak yang benar-benar membutuhkannya. Anda diarahkan untuk iba dengan mereka—orang-orang kaya, berkuasa, oportunis yang mampu melalap semua kesenangan hidup yang ada. Atau, kalau Anda tak terkecoh dengan siasat ini, Anda akan dibawa untuk iba dengan diri Anda sebagai mayoritas yang dizalimi. Bukan dizalimi oleh mereka, elite 0,00001 persen yang menguasai harta dan takhta dengan cara-cara tak wajar, melainkan oleh minoritas yang secara imajiner mencemari dan mengancam identitas mayoritas.
Dan bagian terpentingnya, lantas, Anda harus menyerahkan kekuasaan kepada mereka yang akan secara gaib mengembalikan kedaulatan Anda sebagai mayoritas. Kedaulatan yang sama imajinernya dengan ancaman yang mereka bentangkan, tentu.
***
Roger Money-Krle, seorang psikoanalis, mengunjungi Berlin pada tahun 1932. Dalam kesempatan tersebut, kawannya, seorang diplomat, mengajaknya untuk mengunjungi apel Partai Nazi. Hitler dan rekannya, Joseph Goebbels, pada kesempatan tersebut, berpidato membakar para pendengarnya.
“Sepanjang sepuluh menit penuh kami mendengar penderitaan orang-orang Jerman sejak perang,” tulis Money-Kyrle dalam makalahnya, “Psikologi Propaganda”. “Monster tersebut [Partai Nazi] nampak berkubang dalam sebuah orgy mengasihani diri sendiri.”
Pidato para juru propaganda Nazi, menurut Money-Kyrle, tidak menakjubkan. Namun mereka piawai membuat para pendengarnya merasa terzalimi, dan merasa harus berbuat sesuatu untuk mengembalikan takdir jaya bangsa Jerman yang sudah direnggut dari mereka. Bangsa Jerman menjadi bahan tertawaan di Barat, ujar para propagandis. Kejayaan masa silam mereka raib. Kenaasan ini merupakan tanggung jawab orang-orang Yahudi dan sosial-demokrat.
Dan kita tahu cerita selanjutnya.
Keampuhan retorika mengiba-iba para politisi hari-hari ini, artinya, bukan tanpa preseden. Kita punya preseden yang bahkan merupakan monumen moreng penanda abad ke-20: bangkitnya Nazi. Dan persekusi-persekusi paling buruk rupa zaman kita pun lumrahnya tak pernah jauh-jauh dari retorika semacam.
Persekusi Muslim di Sri Lanka? Cek. Kekisruhan yang membidik kelompok Muslim di kota Kandy dan Ampara disulut oleh kasak-kusuk pemilik restoran Muslim membubuhkan obat mandul ke makanannya yang akan mencegah umat Buddha mayoritas beranak-pinak.
Persekusi orang Tionghoa di Indonesia? Cek. Kerusuhan yang berujung pemenjaraan Ibu Meiliana dimulai dari kabar “orang Cina melarang azan.”
Persekusi orang Rohingya? Cek. Mereka dilekatkan dengan teroris yang membahayakan umat Buddha-Myanmar mayoritas.
Semua selalu dimulai dari ajakan mayoritas untuk mengasihani dirinya sendiri. Ajakan yang manjur bukan saja untuk mengajak orang-orang memilih politisi tertentu melainkan juga memungkinkan perisakan manusia dalam skala yang spektakular.
“Tetapi, Bung Geger, kalau rasa iba memang dorongan yang sekuat itu, orang-orang tertindas sudah seharusnya dari dulu menang dong? Sebaliknya, banyak orang kini dicabuli oleh penguasa. Tanah-tanah diserobot dalam sengketa lahan. Pejabat dan pengadilan yang korup acap berpihak kepada korporat perampas hak warga. Aktivis dibungkam atau, bahkan, dibunuh. Semua bergeming seakan kehidupan baik-baik saja.”
Nah, ini dia ironi paling kentara dari politisasi rasa iba. Saking berjejalnya kenyataan hidup yang menagih belas kasihan kita, pemandangan mengiba-iba yang tersaji ke depan mata kita akibatnya adalah yang sudah terseleksi. Syarat seleksinya? Dalam konstelasi media dan politik kita yang norak sekarang ini, ia harus nyambung dengan ingar bingar politik para mahapatih yang tak berselera itu. Ia mesti menceritakan bagaimana kubu mahapatih yang satu menginjak-injak kubu mahapatih yang lain. Ia mesti merupakan narasi bagaimana Islam dinistakan atau kesatuan terancam, terlepas Islam atau kesatuan tak lebih dari avatar para oligark dan kekuasaan yang dipertaruhkan di antara mereka.
Akhirnya, potret mengibakan yang diperoleh kebanyakan orang bukanlah kesulitan orang banyak itu sendiri melainkan Rizieq Shihab yang, katanya, dipersekusi rezim dan hidup jelas-jelas lebih dari berkecukupan di hotel paling mewah Mekkah. Dan bukan hal yang mengherankan bila selanjutnya potret yang kita peroleh adalah Ratna Sarumpaet yang “babak belur,” bukan potret warga yang benar-benar babak belur dihajar aparat.
Saya jadi ingat sepotong syair Sutardji. Bunyinya, “yang tertusuk padamu berdarah padaku”.
Sajak ini elok. Hanya saja, di hari-hari yang menggemaskan ini, tak salah rasanya sedikit menatanya ulang:
yang tertusuk pada orang-orang kaya sompret ini
berdarah pada kalian***