Judul Buku: Depoliticing Development: The World Bank and Social Capital
Penulis: John Harriss
Penerbit: New Delhi, Leftworld Books
Tahun terbit: 2001
Jumlah hlm: 145 hlm
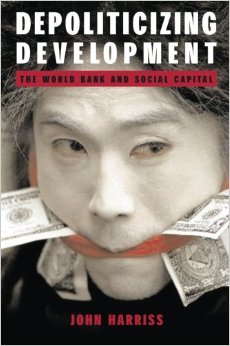
DUDUK di satu sesi simposium tahun 2000an silam, untuk pertama kalinya saya mendengar konsep “modal sosial”. Simposium Internasional Antropologi itu berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang peneliti menyajikan bukti-bukti tentang kuatnya modal sosial di wilayah penelitiannya, satu tempat di Sumatera Utara. Saya cukup takjub waktu itu. Dalam pemaparannya, peneliti tersebut mengatakan bahwa dengan memenuhi tiga elemen pembentuk modal sosial, kelompok masyarakat bisa maju. Betapa mudahnya, demikian menurut pikiran sederhana saya waktu itu. Seusai sesi itu, saya mencari makalah sang peneliti dan menggandakannya. Tak lama setelahnya, berulang kali saya melihat (kadang membaca) esei atau potongan buku tentang modal sosial.
Di lingkaran praktisi pembangunan, konsep itu juga ramai dibicarakan dengan nada positif, meskipun heboh itu berlangsung sebentar saja. Orang-orang di lingkaran praktisi pembangunan kemudian sibuk membicarakan kata-kata kunci lain: partisipatif, tata kelola pemerintahan, penghidupan, kebencaan, kerentanan, ketangguhan, lalu entah apa lagi. Di Indonesia, rentetan buzzword–kata atau frasa yang sedang naik daun—dalam praktik dan kajian pembangunan datang dan pergi seperti fesyen, dengan sedikit peluang untuk memahaminya lebih dalam. Buzzword baru bisa saja memuat unsur-unsur yang nyaris sama. Tetapi di Indonesia, bungkusan baru menggantikan yang belum lama sebelum orang memahaminya dengan baik. Banyak dari kita bahkan hanya berkesempatan menggunakan bungkusan itu sebagai barang jadi, berupa framework, untuk kita terapkan sebagai pelaksana dalam pelbagai program pembangunan.
Menariknya, setelah redup tertelan gelombang fesyen baru, sebagian orang masih menggunakan modal sosial dalam bentuk yang nisbi sama ketika pertama kali ia muncul. Meskipun sudah terbit sekian banyak kritik terhadapnya, pertarungan definisi dan kerangka teoritis berlangsung panjang—sebagian setelah menemukan kelemahannya di lapangan, sebagian orang sepertinya masih setia pada bentuk aslinya. Pada tahun ketika saya duduk di simposium itu, istilah itu sedang menerima curahan kritik di mana-mana. Salah satunya dari John Harriss lewat buku Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital.
Pada kesempatan ini saya akan mengurai kritik-kritik Harriss di buku itu. Saya membaginya menjadi empat bagian. Empat poin yang saya tekankan di sini tidak mencakup seluruh kritik Harriss terhadap penggagas teori modal sosial, Robert D. Putnam, dan pengikutnya, tetapi hanya bagian dari kritik yang berhubungan dengan aspek politis dari konsep dan teori modal sosial. Menurut saya, inilah inti dari kritik Harriss: bahwa Putnam (1) mengabaikan ‘muatan’ (tujuan dan ideologi) modal sosial; (2) mengabaikan konteks relasi kuasa, ketimpangan dan eksklusi; (3) salah jika beranggapan bahwa hanya masyarakat yang dapat memperbaiki negara dan tidak sebaliknya; dan secara praktis (4) modal sosial adalah mesin anti-politik.Untuk membantu membayangkan kemungkinan-kemungkinan dampak penerapan modal sosial secara global, saya memadukan ulasan teoritis ini dengan ilustrasi. Tapi sebelumnya saya akan meringkas dulu gagasan-gagasan dasar modal sosial versi Putnam dalam bukunya Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000). Setelah membahas itu, kita lihat bagaimana Harriss menelusuri asal-muasal gagasan Putnam.
Gagasan Putnam tentang Modal Sosial
Di bagian awal Depoliticizing Development, Harriss mengenalkan definisi modal sosial versi Robert Putnam: “kesaling percayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi sebuah masyarakat dalam menggerakkan tindakan bersama yang terkoordinasi.” (hlm. 2) Tiga unsur yang membentuk “modal sosial” itu Putnam anggap sebagai prasyarat yang harus ada agar sekelompok masyarakat dapat bergerak dalam jumlah besar, untuk menjalankan tindakan kolektif (collective action).[1] Modal sosial, bagi Putnam, dapat meningkatkan keterlibatan masyakarakat dalam kegiatan sosial sukarela (‘civic engagement’ atau ‘civil involvement’). Sebaliknya, keterlibatan semacam ini akan meningkatkan modal sosial. Dengan kata lain, gagasan Putnam tentang modal sosial membentuk lingkaran: keterlibatan—modal sosial—keterlibatan. Tautologi semacam ini, menurut Harris, merupakan salah satu kelemahan logika dalam teori modal sosial Putnam.
Putnam kemudian menghubungkan modal sosial dengan demokrasi dan pembangunan: bahwa semakin tinggi modal sosial, akan semakin baik demokrasi berjalan, dan pembagunan (ekonomi) pun lebih maju. Lewat bukunya, Making Democracy Work, terbit 1993, Putnam mencontohkan kontras modal sosial di bagian utara dan selatan Italia. Ia menyebutkan bahwa rendahnya keterlibatan sukarela (civic engagement) atau asosiasi warga di Italia selatan berbanding lurus dengan “keterbelakangan” dan rendahnya kualitas demokrasi, sedangkan di utara situasi sebaliknya terjadi. Dengan demikian, mengikuti tautologi di atas, tempat seperti Italia selatan yang “terbelakang” akan terperangkap dalam “lingkaran kejam” (vicious cycle): “Organisasi sosial diperlukan untuk kemajuan masyarakat, tapi kelemahan institusi sosial semacam itu membuat sebuah masyarakat sulit beralih menjadi lebih maju.” (hlm. 27).
Putnam melihat modal sosial sebagai “modal” (sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu). Modal sosial bisa digunakan oleh kalangan miskin untuk keluar dari ketertinggalannya.Warga miskin dapat menggunakan jaringan dan kesaling percayaan, misalnya, untuk mendapatkan modal produksi atau akses terhadap lahan garapan. Karena itu, Putnam menyarankan pemerintah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok mandiri warga di kawasan-kawasan berpenduduk miskin untuk meningkatkan modal sosial mereka (hlm. 7).
Gagasan semacam ini dengan cepat menarik perhatian lembaga-lembaga pembangunan Internasional seperti Bank Dunia. Mereka segera mengumumkan modal sosial sebagai “mata rantai yang hilang” (missing link) dalam pembangunan, alasan mengapa pembangunan kurang berhasil, bahkan gagal di masa-masa sebelumnya. Seorang spesialis Bank Dunia yang terinsiprasi Putnam menulis, “tanpa organisasi-organisasi warga, kalangan miskin akan kekurangan modal sosial, yang kemudian melemahkan kegiatan politik dan ekonomi.” Tetapi, dalam rekomendasi kebijakannya, sang spesialis melangkah lebih jauh, “kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan pada kerja-kerja mandiri di level lokal ketimbang melakukan redistribusi sumber daya ekonomi dan sosial secara merata.” (hlm. 29) Gagasan ini kelak menjadi salah satu landasan program-program good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan participatory (partisipatif) di negara-negara berkembang.
Lewat Depoliticizing Development, Harriss mengajak kita untuk melihat sejumlah masalah mendasar dalam konsep “modal sosial” versi Putnam ini. Ia menunjukkan mengapa konsep ini sebaiknya kita curigai.
Empat Kritik Harriss
#1 Mengabaikan muatan modal sosial
Muhammad Yunus meraih Nobel Perdamaian tahun 2006. Beberapa hari setelahnya saya mendengar kuliah Aswani Saith, seorang ahli ekonomi politik, dosen Institute of Social Studies, Den Haag. Berkomentar tentang peristiwa itu, ia bilang, “Yunus adalah orang yang tepat pada waktu yang salah.” Saya bengong. “Mengapa begitu?” lanjut Saith, “Saat ini, model Grameen Bank racikan Yunus sudah diadopsi lembaga-lembaga keuangan besar, lewat program-program kredit mikro (microcredit) atau layanan keuangan mikro (microfinance). Melihat rendahnya persentase kredit macet yang dihasilkan model lembaga keuangan mikro Yunus, bank-bank komersial besar tentu tergoda. Mereka segera mengucurkan dana besar untuk melebarkan daya jangkau model itu. Memang kelompok-kelompok kecil model Grameen Bank hanya meminjam receh bila dibandingkan para kreditur kelas kakap. Tapi bayangkan bila ada jutaan kelompok semacam itu di sekian banyak negara berkembang, dengan tingkat pengembalian kredit nyaris seratus persen, mereka bisa mengumpulkan uang besar bagi bank-bank besar,” Saith melanjutkan. “Jadi, sebenarnya, yang terjadi adalah: golongan paling miskin di antara paling miskin diminta bekerja lebih keras untuk menambah modal para kapitalis bank global.”
Model Grameen Bank mengandalkan “modal sosial”. Orang-orang yang nisbi setara secara finansial—sama-sama miskin—berkumpul untuk mengelola lembaga keuangan kecil. Sebagian besar di antaranya adalah kelompok perempuan, yang kerap tidak dapat mengakses bank. Setiap anggota, dengan aturan tertentu, bisa meminjam uang lalu menyicilnya dengan bunga, sementara anggota kelompok lain dan para fasilitator membantu memastikan agar sang peminjam sanggup membayar cicilan. Tekanan terhadap sang peminjam juga berasal dari fakta bahwa uang itu, bila pembayaran cicilan lancar, juga akan dipinjamkan kepada anggota kelompok lain. Di sini ada norma, kesaling percayaan dan jaringan yang memastikan model kredit mikro ini bisa bergerak. Kedekatan mereka membangun kesaling percayaan, menempa norma resiprositas (saling bantu, saling memberi) dan jaringan di antara anggota kelompok. Tapi, yang tak mereka sadari, untuk siapa mereka sebenarnya bekerja dengan berusaha keluar dari kemiskinan—lewat jerat utang baru! Ini butuh lebih dari sekadar “modal sosial”.
Menurut Harriss, ketika membahas modal sosial, Putnam tidak menunjukkan bagaimana muatan (tujuan dan ideologi) sebuah kelompok atau asosiasi warga bisa membuatnya berbeda dari kelompok lain (hlm. 28).Artinya, kita bisa punya banyak asosiasi warga di satu tempat, dan itu bisa dilihat sebagai indikasi modal sosial yang kuat di tempat tersebut. Tapi, bagaimana bila satu kelompok mendominasi yang lain? Bagaimana, misalnya, membentuk rasa saling percaya dan norma saling membantu antara klub-klub golf dengan kelompok-kelompok warga miskin yang akan digusur oleh pembangunan lapangan golf baru?
Menanggapi kritik ini, para pengikut Putnam lantas menyebutnya sebagai “sisi gelap” modal sosial. Lalu mereka memberi solusi: yang lemah bisa membangun lingking capital atau jembatan untuk menghubungkan mereka dengan pihak yang kuat. Tapi bagaimana bila tujuan dan ideologi keduanya bertolak belakang atau malah bertabrakan? Bagaimana membangun rasa percaya dan norma saling bantu antara lingkaran-lingkaran elit bankir global yang hendak mempertahankan keuntungan dengan warga miskin yang tereksploitasi oleh tujuan itu? Lihatlah apa yang mereka lakukan kelompok terhadap orang-orang miskin di negara miskin via program microfinance, mereka bahkan memanfaatkan pahlwan orang-orang miskin itu!
Bila bisa terbentuk, linking capital antara kelompok kuat dan lemah hanya dapat terjadi lewat hubungan timpang seperti patron-klien atau buruh-majikan, atau “golongan paling miskin di antara paling miskin diminta bekerja lebih keras untuk menambah modal para kapitalis bank komersial global.” Jembatan ini sepertinya bisa membantu orang berjalan memunggungi demokrasi. Padahal buku yang melambungkan Putnam dan modal sosialnya diberi judul Making Democracy Work.
Menurut saya setidaknya ada dua cara bagaimana Putnam mengabaikan muatan modal sosial. Pertama, Putnam melihat modal sosial sebagai “penyebab asali” dari sebuah kondisi. Modal sosial seolah terbentuk dengan sendirinya, dan menyebabkan maju tidaknya pembangunan dan demokrasi. Dengan cara itu, Putnam luput menanyakan mengapa modal sosial menjadi kuat atau lemah di satu masyarakat, dan tidak demikian di tempat lain. Karena itu, ulasannya jarang dibawa ke pertanyaan mengapa modal sosial terbentuk, untuk tujuan apa?
Kedua, ketika membahas modal sosial dalam keterlibatan sosial masyarakat, Putnam seringkali hanya merujuk pada asosiasi yang bersifat rekreatif, semisal kelompok pencinta burung atau klub olahraga, atau yang cenderung non-politis seperti asiosiasi orangtua murid. Dengan deskripsi seperti itu, Putnam berusaha membawa diskusi tentang modal sosial ke wilayah kegiatan yang lebih bersifat rekreatif atau sampingan, sekaligus menghindar dari membicarakan tujuan ekonomi politik dari kelompok-kelompok yang biasanya memainkannya.Tujuan satu kelompok kepentingan bisa saja bukan untuk kebaikan seluruh warga. Sulit membantah bahwa anggota kelompok mafia, misalnya, punya modal sosial kuat di dalam lingkarannya.Tapi bagaimana dengan tujuannya? Bagaimana dengan lingkaran oligarki atau kelompok elit lain yang hadir di pelbagai tingkatan?
#2 Mengabaikan relasi kuasa, ketimpangan dan eksklusi
Masih berhubungan erat dengan soal di atas, modal sosial juga dengan mudah bisa meminggirkan konteks relasi kuasa yang ada dalam masyarakat. Bila kelompok yang berkuasa punya modal sosial yang kuat, mereka akan berusaha mempertahankannya. Menurut beberapa studi yang dikutip Harriss, dalam menilai pembangunan dan demokrasi, sorotan harus mengarah pada ketimpangan. Sebab ketimpangan justru menyebabkan asosiasi-asosiasi lokal didominasi oleh kelompok elit lokal untuk menguatkan kepentingan mereka (hlm. 9). Dengan kata lain, modal sosial yang mengandung sekat antarkelompok, bisa tampak mekar dalam bentuk banyak asosiasi, tetapi pembangunan dan demokrasinya sebetulnya sedang berjalan mundur.
Dalam keadaan timpang, kelompok yang tereksklusi biasanya lebih memilih mengikuti kalangan elit lokal. Penelitian David Mosse di India Selatan menampilkan bagaimana kerja-kerja kolektif dalam ritual merawat dan mensucikan tempat penampungan air menjadi alat legitimasi dominasi kelompok elite lokal.[2] Kerja kolektif itu melibatkan kalangan kasta rendah. Mengapa mereka melibatkan diri merawat ketimpangan yang merugikan mereka? Sebab mereka tidak ingin kehilangan “belas kasih” para elit dari kasta berkuasa, agar mereka tetap bisa mengakses sumber daya yang dikuasai kelas penguasa itu —meski dalam batasan yang dimungkinkan bagi mereka. Maka, modal sosial bisa tampak mekar, tapi kenyataannya demokrasi sedang mengkerut.
Penggambaran modal sosial yang lepas dari konteks relasi kuasa inilah yang bisa menimbulkan asumsi sederhana bahwa sekadar “berkelompok itu baik bagi orang miskin”. Asumsi ini luput memeriksa watak kelompok di mana mereka tergabung. Di titik ini tampak bahwa argumen Putnam dan pengikutnya juga buta kelas. Kelompok warga dilihat sebagai sesuatu yang tidak bermasalah, dan keterbelahan sosial berdasarkan struktur kelas, gender, kondisi fisik dan lainnya, diabaikan. Kesimpulan Putnam bahwa Italia selatan terkurung dalam keterbelakangan karena kurangnya modal sosial (dalam bentuk kurangnya keterlibatan dalam berbagai asosiasi), mengabaikan penyebab struktural yang menciptakan keterbelakangan tersebut, yaitu ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya. Padahal, ketimpangan itulah yang menyebabkan kurangnya “modal sosial”.
Untuk membuktikannya, Harriss mencontohkan sebuah kajian yang dilakukan di Kerala, sebuah negara bagian di India. Kajian itu dilakukan setelah terselenggaranya program reforma agraria yang mengakhiri ketimpangan kronis kepemilikan tanah di Kerala. Menggunakan metodologi yang mirip dengan yang dipakai Putnam di Italia (dengan indeks kewargaan komunitas), kajian itu menemukan bahwa Kerala punya “modal sosial” paling tinggi, melampaui seluruh negara bagian di India. (hlm. 12).
Dengan menepis relasi kuasa dan ketimpangan yang dihasilkannya, Putnam pun luput mengurai bagaimana eksklusi yang bisa mengikuti menguatnya modal sosial. Ia tidak menjelaskan mengapa modal sosial yang kuat di satu kelompok tidak dapat digeneralisasi menjadi modal sosial bagi semua warga. Putnam tidak memberikan gambaran bagaimana rasa saling percaya atau norma resiprositas di satu kelompok dapat diangkat menjadi sesuatu yang berlaku secara lebih universal —berlaku untuk seluruh warga, sesuatu yang dibutuhkan untuk demokrasi dan pembangunan yang lebih baik.[3] Sebagai aset, modal sosial dapat digunakan untuk mengakses sumber daya tertentu oleh sebuah kelompok dan mengeksklusi kelompok lain. Menurut Mancur Olson, seorang peneliti tindakan kolektif ternama yang dikutip Harriss, kelompok kepentingan yang terorganisir baik tak punya minat untuk bekerja bagi kebaikan seluruh masyarakat.
Lantasapa solusinya? Bagi Harris, kepercayaan yang berlaku lebih umum dapat berlangsung bila ditopang oleh aturan-aturan yang dikeluarkan lembaga negara. Aturan hukum ini bisa menimbulkan rasa percaya kepada seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang tak dikenal karena ada lembaga yang akan memberi sanksi bila seseorang melanggar aturan. Keberadaan dan penegakan aturan bisa mengatasi rasa saling tidak percaya antar kelompok sosial, dan sebaliknya membangun rasa saling percaya di luar kelompok. Lembaga negara yang terpercaya bisa membangun rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat. Dengan cara serupa, norma resoprositas bisa diangkat oleh negara menjadi lebih umum lewat program-program redistribusi sumber daya, yang dapat mengurangi bahkan menghentikan proses pemiskinan yang dapat menghasilkan kelompok-kelompok yang tereksklusi.
Usulan Harris ini merupakan kebalikan dari argumen Putnam dan pengikut-pengikutnya, yang segera kita lihat di bawah.
#3 Masyarakat bisa perbaiki negara, tidak sebaliknya
Ceara adalah satu negara bagian di timur laut Brasil, kawasan miskin tempat sembilan negara bagian berada.[4] Dua gubernur muda dari satu partai politik silih berganti memenangkan pemilihan demokratis dan membawa perubahan besar di Ceara. Persaingan politis yang sehat menimbulkan keharusan bagi pihak yang menang untuk menyenangkan konstituen. Begitu salah satu dari mereka menjadi gubernur pada 1987, kebijakan pro-poor dan reformasi pengorganisasian kerja-kerja program segera bergerak.
Di sektor kesehatan, misalnya, pemerintah negara bagian mengangkat 7300 “agen kesehatan masyarakat” sebagai bagian dari upaya mengatasi menurunnya pendapatan akibat kekeringan, sekaligus menjalankan program-program pencegahan baru. Diselia oleh ratusan perawat, para pekerja non-profesional ini ditempatkan di daerah asal masing-masing. Metode pengangkatan langsung oleh negara bagian ini punya dua kelebihan. Di satu sisi para pekerja itu terlepas dari pengaruh elite kabupaten/kota yang masih merawat relasi patron-klien; di sisi lain mereka lebih mudah mengadaptasi program dengan situasi setempat karena bekerja di daerah masing-masing. Awalnya mereka tidak diterima baik oleh rakyat karena trauma masa lalu. Tetapi pelan-pelan mereka mengetuk pintu demi pintu untuk memberi pelayanan sembari membangun kepercayaan rakyat. Bersama dengan meningginya rasa saling percaya itu, kolaborasi negara-rakyat bertumbuh. Program demi program pun sukses. Pada 1993, Ceara menerima Maurice Pate Prize, untuk program-program pendukung anak, dari UNICEF.
Publikasi kinerja para agen kesehatan masyarakat melalui media juga menjadi penyokong penting. Publikasi ini membuat mereka tahu apa yang diharapkan oleh rakyat; bagian mana yang dihargai oleh rakyat, mana yang tidak. Akhirnya,bersama keberhasilan di sektor lain, ukuran pembangunan manusia negara bagian itu yang tadinya jeblok melonjak pesat. Ringkasan cerita tentang Ceara ini dijadikan contoh oleh Harriss untuk menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan, dan padatnya “modal sosial” (kolaborasi dan saling percaya), bukan hanya karena kerja masyarakat, tetapi karena kerja sama negara dan masyarakat. Tapi Putnam punya pandangan sebaliknya.
Bagi Putnam, modal sosial di masyarakat menyumbang kepada baiknya kinerja negara, dan tidak ada arus sebaliknya. Argumen Putnam sangat berpusat-masyarakat. “Andil pemerintah terhadap terbentuknya modal sosial dilupakan dan kausalitas hanya berlangsung satu arah yaitu dari masyarakat, khususnya asosiasi sukarela yang bersifat horizontal, kepada kinerja pemerintah [dan] bekerjanya demokrasi.”(hlm. 28). Kembali ke contoh Italia utara vs. selatan, Putnam menunjukkan bahwa Italia utara bisa maju karena banyak warga yang tergabung dalam berbagai bentuk asosiasi, dengan demikian modal sosial mereka tinggi, dan itu menjelaskan mengapa kinerja ekonomi dan negara menjadi baik.
Mengutip beberapa kajian kritis terhadap sejarah Italia versi Putnam, Harriss menyimpulkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Kajian sejarah Sidney Tarrow mengungkap bahwa perbedaan civic community antara utara dan selatan Italia sebagaimana dibuat Putnam merupakan hasil dari kejadian-kejadian historis yang berlangsung belum lama (bukan sejak Masa Pertengahan seperti dikatakan Putnam) dan berhubungan dengan proses-proses pembentukan negara modern. Sehingga, menurutnya, bukan civicness yang menyediakan lahan subur tempat bertumbuhnya berbagai struktur negara, tetapi sebaliknya. (hlm. 36) Ketika Putnam dan koleganya menemukan bahwa civic community kuat di daerah-daerah Partai Komunis Italia, mereka menyimpulkan bahwa itu terjadi karena Partai Komunis Italia menyemai di lahan subur modal sosial. Padahal menurut penelitian Tarrow, perbaikan kinerja pemerintah dan keterlibatan aktif warga didorong oleh partai-partai kiri setelah Perang Dunia II (hlm. 37). Sementara di AS (yang juga jadi contoh kasus Putnam), menurut Theda Skocpol, pertumbuhan asosiasi sukarela juga tercipta mengikuti pola pembentukan negara ketimbang kelemahan negara.
Tentang ini, Harriss mengutip Skocpol:
“Sejak awal terbentuknya AS, institusi pemerintahan dan politik yang bercorak demokratis mendorong berkembangnya kelompok-kelompok sukarela yang terhubung dengan gerakan sosial regional dan nasional, dan juga kian terkait dengan jaringan organisasi trans-lokal yang paralel dengan struktur lokal-nasional struktur negara AS. Gerakan-gerakan reformasi moral, asosiasi petani dan buruh; persaudaraan berbasis ritual, gotong-royong dan pelayanan; asosiasi perempuan independen; kelompok-kelompok veteran; dan banyak asosiasi etnis dan Afro-Amerika —seluruhnya berjumpa dalam bentuk asosiasi tipikal AS.” (hlm. 50).
Akhirnya, mengutip kesimpulan penelitian Samuel Bowles, Harriss mengajukan poin tentang pentingnya posisi ketimpangan organisasi rakyat dan bagaimana peran negara di dalamnya. Menurut Bowles, di daerah-daerah dengan pendapatan terdistribusi lebih setara, pastisipasi rakyat di gereja, jasa-jasa pelayanan lokal, kelompok-kelompok politis, dan organisasi rakyat lainnya, lebih tinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan-kebijakan negara yang meningkatkan kesetaraan pendapatan dapat memperbaiki keterlibatan rakyat mengelola kehidupan bersama mereka (hlm. 57-58). Sejalan dengan contoh Kerala di atas, ketimpangan hanya bisa diatasi oleh gerakan rakyat yang bekerja lewat tindakan politis mendesak negara untuk melakukan perubahan struktural, dalam kasus itu reforma agraria.
#4Modal sosial sebagai mesin anti-politik
Lesotho 1990an. Setiap tahun lebih dari setengah pria negeri itu menempuh perjalanan maha berat menyeberangi perbatasan Lesotho menuju Afrika Selatan untuk bekerja sebagai buruh tambang ilegal. Tambang di sana hanya mempekerjakan pria. Mereka bekerja di sana sepuluh sampai sebelas bulan setiap tahun. Di kampung, mereka tidak hanya meninggalkan keluarga, tapi juga ternak di tengah padang gembalaan tradisional milik bersama. Pola ini sudah berlangsung lama, sejak banyak dari tanah pertanian mereka dirampas penjajah Belanda pada pertengahan abad 19. Tanah subur yang dapat ditanami tinggal 10 persen dari luas negeri pegunungan itu, sisanya hanya cocok untuk menggembala ternak.
Lalu datanglah orang-orang proyek pembangunan, sebagian adalah orang-orang dengan itikad baik. Mereka melihat ternak di Lesotho sebagai potensi “pembangunan” karena luasnya padang gembalaan yang “kurang produktif”. “Sektor” ternak ini, menurut mereka, dapat dikembangkan sebagai “industri” untuk menjadi pemasukan alternatif bagi pekerja migran. Mereka kemudian menjalankan program “pembangunan” untuk ternak komersial. Menurut mereka, Lesotho hanya butuh jalur pasar yang tepat dan meningkatkan produktivitas ternak sampai ke level komersial. Mereka kemudian melatih orang-orang beternak intensif: membentuk kelompok peternak, pelatihan, pengenalan bibit unggul, dan menutup sebagian kawasan penggembalaan yang dimiliki bersama (enclosure) untuk intensifikasi ternak; dan meyakinkan warga menjual ternak mereka yang “non-produktif”.
Nyatanya, bagi orang Lesotho ternak adalah simbol dan tabungan, bukan komoditas. Ternak menjadi simbol keberadaan para pria di kampung (selagi pergi) dan tabungan untuk menutupi kebutuhan konsumsi di masa krisis. Ternak bukan alternatif pemasukan tapi konsekuensi dari pendapatan mereka sebagai buruh migran. Mereka menjual tabungan itu ketika upah mereka memburuk di Afrika Selatan, dan membeli lagi ketika upah mereka sedang membaik. Bagi mereka, ternak bukan “sektor” atau “industri” untuk dikembangkan lewat program pembangunan, tetapi lebih mirip barang konsumsi atau dana pensiun (untuk dijual bila seorang pekerja migran tak bisa kembali bekerja karena cedera, usia, atau dipecat). Ternak itu pada akhirnya akan habis dijual untuk konsumsi.
Akhirnya tidak banyak yang bersedia terlibat. Pagar-pagar kawasan intensifikasi ternak dirobohkan, kantor dibakar, pekerja proyek diancam. Segelintir orang yang hendak bergabung mengurungkan niat, khawatir dianggap pengkhianat karena menyetujui penutupan lahan gembalaan bersama dan melakukan penjualan “ternak non-produktif” yang punya fungsi sosial (dipinjamkan ke kerabat atau tetangga untuk membajak kebun selama pemiliknya bekerja di luar negeri). Proyek itu gagal, terhenti sebelum waktunya.
Ini salah satu contoh dari sekian banyak proyek pembangunan yang dijalankan lembaga-lembaga internasional di Lesotho, negara yang dalam dua dekade sampai awal 1990-an menerima sangat banyak tamu: 72 agensi internasional dari 26 negara yang diceritakan oleh James Ferguson, seorang antropolog pembangunan, dalam artikel yang berjudul The Anti-Politic Machine: “Development” and Bureaucratic Power in Lesotho.[5] Harriss meminjam frasa Ferguson itu ketika melihat berderet kelemahan konsep modal sosial. Ia pun tiba pada kesimpulan bahwa modal sosial versi Putnam dan pengikutnya dapat dilihat sebagai mesin anti-politik.
Gagalnya pembangunan di Lesotho diumumkan sebagai akibat dari absennya skema perencanaan yang baik, lemahnya tatanan kelembagaan dan kurangnya pelatihan bagi para birokrat, lemahnya “pola pikir” dan keterampilan masyarakat yang tidak memanfaatkan sumber daya alam. Intinya, berhasil gagalnya pembangunan tidak ada urusannya dengan politik. Sebaliknya, Ferguson mengungkap bahwa proyek-proyek pembangunan itu justru secara tidak langsung memperdalam birokratisasi dan kendali negara yang waktu itu dikuasai rezim militer dan klik mereka. Uang dan wewenang proyek banyak dibelokkan untuk menguatkan partai penguasa. Slogan partai berkuasa dicetak dalam dokumen program yang dibagikan kepada.
Membaca uraian Ferguson, modal sosial ala Putnam tampak pucat. Putnam tak akan punya peluang sukses di Lesotho dengan usulan “mengangkat pentingnya ‘asosiasi sukarela’ dalam keterlibatan warga dan meminggirkan perlunya tindakan politis.” (hlm. 13). Putnam dan koleganya,yang sangat tertarik pada kepadatan asosiasi sukarela, menyarankan bahwa tujuan asosiasi seperti itu tidak mesti politis. Sudah cukup bagi Putnam bahwa “tergabung dalam kelompok paduan suara atau klub penonton burung bisa melatih disiplin diri dan apresiasi terhadap kesenangan terlibat dalam kolaborasi yang sukes.” (hlm. 25). Persoalan pada modal sosial bagi Putnam melulu perihal “sosial” yang tidak termasuk politik. Dia menempatkan kurangnya ethos (tindakan kolektif untuk kebaikan bersama ketimbang hanya untuk kepentingan keluarga) sebagai penyebab keterbelakangan; sementara buruknya kondisi material hilang dari timbangan. Sungguh sulit menghindar dari pikiran bahwa “pola pikir” Putnam ini juga dibawa agensi-agensi pembangunan internasional ke Lesotho, dan ke banyak negara lain.
Mesin anti-politik ini juga menyebabkan mengapa ukuran-ukuran yang diterapkan Putnam dan pengikutnya untuk menilai modal sosial tidak dapat menangkap vitalitas politik yang bersifat demokratis. Di AS, misalnya, keterlibatan dalam tindakan kolektif warga bermekaran: dengan penuh hati, konfliktual dan tidak selalu damai (agak beda dengan klub penonton burung atau paduan suara). Vitalitas semacam ini tidak selalu bergantung pada asosiasi-asosiasi sukarela, sebagaimana yang digambarkan Putnam sebagai perwujudan padatnya modal sosial. Asosiasi semacam itu jarang menjadi wadah sosial bermakna sebagaimana gerakan-gerakan sosial yang berfokus pada satu atau serangkaian isu bersama.“Gabungan antara asosiasi, rapat umum, partai politik dan gerakan sosial, pada pertengahan abad 20, telah memberdayakan warga dan membantu menyokong bertumbuhnya demokrasi.”[6] Demokrasi tidak lahir dari asosiasi-asosiasi relawan ala Putnam, tidak dari modal sosial yang mengandung sekat dan buta relasi kuasa.
Dari mana datangnya pandangan Putnam?
Akar pandangan Putnam, menurut Harriss, datang dari James Coleman. Sosiolog AS ini berpandangan bahwa “aktor punya prinsip tindakan yang sederhana, yaitu memaksimalkan realisasi dari kepentingan” (hl.18). Pandangan ini melihat tindakan sosial hanya sebagai tindakan individual berdasarkan “pilihan rasional” untuk meraih manfaat sebesar mungkin bagi dirinya. Seseorang bergabung dalam sebuah tindakan kolektif karena “insentif” keuntungan pribadi. Dengan demikian, modal sosial dilihat sebagai aset yang berguna bagi keuntungan seseorang dalam pertukaran antar-kepentingan. Kepercayaan dan norma resiprositas dalam jaringan antar-individu akan membentuk “asuransi” antar-individu, memudahkan seseorang untuk memberi atau menerima informasi dan mengurangi ongkos transaksi. Maka, membangun modal sosial adalah “invenstasi” individual.
Pikiran semacam ini langsung melempar kita ke akhir abad 18, ketika Jeremy Bentham sedang memoles “prinsip utilitarianisme”. Bagi Bentham, fitrah manusia adalah berusaha memaksimalkan kesenangan dan meminimalisir derita dirinya masing-masing; bahwa setiap individu bertugas mengusahakan kesenangan masing-masing (sehingga fungsi negara hanya memastikan bahwa derita setiap individu terminimalisir —terutama karena pengejaran kepentingan pribadi yang kebablasan).
Pandangan Coleman juga membawa kita ke Adam Smith yang melihat individu hanya sebagai manusia ekonomi. Bagi Smith, setiap individu selalu punya kecenderungan tak terhindarkan untuk berdagang; bahwa tidak ada makan siang gratis. Dalam buah tangan Smith sendiri: “Bukan dari kebaikan tukang si jagal hewan, si pembuat roti, atau sang penyuling bir kita mengharapkan makan malam kita, tetapi dari penghargaan atas kepentingan pribadi mereka.”[7] Maka, setiap individu bergabung ke dalam satu kelompok karena melihat ada keuntungan pribadi yang bisa mereka peroleh dari sana. Setiap orang masuk ke “pasar” dengan membawa “barang dagangan” masing-masing. Dengan kata lain, Coleman memasang kacamata ekonomi klasik (dimana Bentham dan Smith adalah dua di antara pengusungnya) untuk melihat fenomena sosial berupa bergabungnya individu-individu dalam “asosiasi-asosiasi sukarela”.
Tindakan beralaskan rasionalitas atau utilitarianisme bukan khayalan, ia benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Setiap orang yang sudah dapat berpikir sendiri kemungkinan besar pernah melakukannya. Soalnya, oleh Adam Smith, Bentham, Coleman hingga Putnam, tindakan sosial manusia dilihat secara sempit, hanya terjadi karena alasan rasional-utilitarian. Ini keliru. Erik Olin Right menulis bahwa masih banyak jenis tindakan sosial lain yang dilakukan manusia, seperti tindakan habitual (berbasis kebiasaan), normatif, kreatif, atau yang berbasis moral.[8] Manusia bukan sekadar individu egois yang tidak akan bertindak kecuali melihat ada keuntungan bagi dirinya.
Tumpukan penelitian tentang gerakan sosial dan tindakan kolektif bisa membantah Coleman, juga Putnam dan pengikutnya, dengan mudah. Orang menempuh macam-macam risiko atau pengorbanan untuk sebuah komitmen bagi orang banyak. Orang bisa membela kepentingan orang lain karena komitmen pada kesetaraan, semisal para pria —yang diuntungkan oleh pranata patriarkis—yang justru mendukung gerakan feminis. Orang juga bisa bekerja untuk kepentingan bersama seperti petani yang bahu-membahu membangun irigasi agar semua petani di hamparan itu (termasuk yang tidak ikut kerja) bisa menanam di musim kemarau. Sebagian lainnya juga bertindak karena kebiasaan atau adat, atau mengikut kepercayaan agama, meskipun itu mengorbankan kesenangan pribadi.
Manusia bukan pedagang individualis. Manusia bisa berhimpun untuk melakukan tindakan kolektif bagi kemaslahatan bersama. Berkelompok mungkin baik bagi orang miskin, tapi bukan dalam model “modal sosial” yang disarankan oleh Putnam dan para pengikutnya. Akhir kata, lewat Depoliticizing Development, Harriss mungkin hendak mengirim wanti-wanti tentang hal ini kepada orang-orang yang mengurusi pembangunan.
Nurhady Sirimorok, peneliti, tinggal di Makassar
[1] Tetapi, mengutip sebuah kajian, Harriss mengungkap bahwa ketika mengulas modal sosial Putnam sebenarnya hanya bicara tentang norma dan jaringan, dan tidak termasuk nilai. Sehingga modal sosial, secara aktual dalam penerapannya oleh Putnam, hanya berarti “keanggotaan dalam kelompok” atau “asosiasi sukarela” (Depoliticizing Development, hlm. 8). Penyembunyian “nilai” ini punya dampak teoritis yang akan kita lihat di bawah.
[2] Mosse, David. 2006. ‘Collective Action, Common Property and Social Capital in South India: An Anthropological Commentary.’ Economic Development and Cultural Change 54(3): 695-724
[3] Putnam memang tidak mendefinisikan apa itu “kepercayaan”, melainkan hanya menggambarkan bagaimana itu berlangsung di antara kelompok-kelompok warga.
[4] Lebih jauh mengenai Ceara lihat Judith Tandler. 1997. Good Government in the Tropics. Baltimore: John Hopkins University Press; Harriss mengulas kasus ini secara ringkas dalam Depoliticizing Development, hlm. 67-69
[5] James Ferguson dan Larry Lohmann. 1994. “The Anti-Politic Machine: “Development” and Bureaucratic Power in Lesotho”. The Ecologist.Vol. 24(5). Artikel ini merupakan ringkasan sebagian argumen utama buku James Ferguson The Anti-Politic Machine: “Development”, Depoliticizing, and Bureaucratic Power in Lesotho. University of Minnesota Press. Terbit pada tahun yang sama.
[6] Rotberg dalam Depoliticizing Development, hlm. 51.
[7] Smith dalam Richard Peet dan Elaine Hartwick. 2009. Theories of Development: Contentions, Arguments, and Alternatives. New York: The Guilford Press. Hlm. 31. Pembahasan mengenai ekonomi klasik dalam tulisan ini mengutip Bab 2 dari buku ini.
[8] Erik Olin Wright. 2011. “Commentary: Sociologists and Economists on ‘the Commons’”. Dalam Pranab Bardhan and Isha Ray (eds). The Contested commons; Conversation between Economists and Anthropologists. Blackwell.






