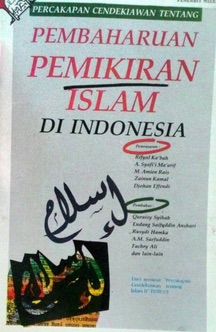PADA kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, perihal relasi Islam rahmatan lil alamin dan kapitalisme. Sebelumnya kita telah melihat Islam rahmatan lil alamin secara semantik dan mendudukkannya dalam konteks historis hari ini melalui kritik atas tendensi Liberalisme Islam yang mensejajarkan dan mengoperasikan Islam rahmatan lil alamin dalam sistem kapitalisme. Bahkan secara spesifik telah kita tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin tidak pernah bisa compatible dengan kapitalisme kapanpun dan dimanapun (fi kulli zaman wa makan). Maka tiba saatnya kini kita mulai suatu pengantar penyelidikan teoritik terhadap apa yang disebut dengan ‘kategori-kategori diskursif’ yang selama ini dianggap mapan (fixed) dalam diskursus pemikiran Islam Indonesia —terutama sekali pada proyek Pembaruan Pemikiran Islam selama rentang waktu empat dekade terakhir ini, yang mendapati kebuntuan teoritiknya dalam Liberalisme Islam— sebagai jalan kelahiran pemikiran Islam Indonesia yang bersih dari residu liberalisme.
Sebelum kita lanjutkan, perlu kiranya diperjelas apa yang dimaksud dengan kategori-kategori diskursif? Mengapa kita harus memulai tugas ini lewat sebuah kritik dan dekonstruksi terhadap berbagai kategori-kategori diskursif tertentu dalam pemikiran Islam Indonesia dalam rentang historis tertentu? Saya memaksudkan kategori-kategori diskursif tertentu pemikiran Islam adalah satu ikat konsepsi teoritis yang terdiri dari terma-terma yang saling terkait satu dengan lainnya, yang keberadaannya menjadi rajutan teoritik proyek perselingkuhan Islam dengan Neoliberalisme di Indonesia, yang diklaim sebagai formula satu-satunya bagi umat Islam untuk keluar dari kubangan kejumudan, ketertindasan dan keterbelakangan, seperti: rasionalisme Islam, modernisme Islam, pembaruan Islam, moderatisme Islam, hingga Liberalisme Islam.
Terma-terma tersebut hingga sekarang terus direproduksi minus kritik dan dibayangkan sebagai satu abstraksi teoritik bebas nilai dan hampa sejarah. Kategori-kategori diskursif tersebut juga diletakkan pada posisi singular dan terisolasi dari berbagai tegangan maupun gesekan antar kelas, dan antara kekuatan dominan dan perjuangan rakyat. Seolah-olah semuanya adalah cipratan kebajikan hidup yang turun di suatu zaman yang beku, tak ada jerit tangis anak kehilangan bapaknya yang mati bersimbah darah oleh bedil para perampas tanah di ladang mereka sendiri, atau tak ada jutaan hektar hutan yang disulap menjadi Hutan Tanaman Industri, Perkebunan sawit, dan ladang-ladang pertambangan.
Dari sinilah kategori-kategori diskursif tersebut dimapankan, berkalu sekali untuk selamanya. Sehingga lupa mengajukan kritik untuk apa dan untuk siapa semua proyek pemikiran tersebut, dan dimana posisinya dihadapan kapitalisme, yang sekarang dalam bentuk Neoliberalisme. Misalnya mengenai rasionalisme Islam: Apa itu rasional? Rasio macam apakah yang dimaksud? Rasio instrumental atau rasio transendental, atau rasio yang bagaimana? Rasional untuk apa dan untuk siapa? Mengenai modernisme Islam. Apa itu modernisme Islam? Apa bedanya dengan modernisme Cartesian, atau Kantian? Seperti apakah kategori kejumudan dan kemajuan? Apa kategori sebuah masyarakat Islam bisa dikatakan maju? Maju dari apa, untuk apa dan untuk siapa?. Mengenai moderatisme Islam: Apa itu pengertian moderat? Pada konteks apakah moderasi bisa dioperasikan. Pada semua aspek, atau cukup pada aspek-aspek tertentu saja? apakah yang dimoderasi? Apakah moderasi sebagai kategori ontologis atau epistemologis, atau bukan keduanya? Moderat sebagai substratum yang menjadi landasan semua aspek kehidupan atau hanya salah sebuah tindakan etis saja? Apakah moderasi itu mutlak atau kondisional? Moderat pada hal apa dan untuk siapa? Mengapa moderasi yang selalu berelasi dengan keadilan seringkali dihindari sebagai tindakan etis yang melengkapi kajian ekopol? Mengenai pembaruan Islam: Apakah yang disebut dengan pembaruan pemikiran Islam? Apa yang diperbarui? Mengapa harus diperbarui? Apakah benar itu pembaruan, dari unthinkable to be thinkable, yang sama sekali baru? Untuk apa, dan untuk siapa pembaruan tersebut? Benarkah yang selama ini dimaksud sebagai penyegaran pemikiran Islam sungguh-sungguh segar? Apa kategori segar? Apakah liberalisme itu segar? Segar dari apa, untuk apa dan untuk siapa? Dll.
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting untuk diajukan agar proyek pemikiran tidak terjatuh menjadi sekedar mantra dan sebagai prolegomena penyilidikan teoritik lebih lanjut. Melalui itu, kita akan tahu di posisi manakah semua nosi, atau kategori-kategori diskursif tersebut dipijakkan kakinya, pada tuan-tuan tanah penghisap petani, pada investor yang membabat jutaan hektar hutan dan mengusir masyarakat adat dari tanahnya, atau pada jutaan rakyat yang berjuang hidup mati melawan penghisapan. Bahkan, kedepan juga sangat diperlukan adanya suatu ikhtiar sebagaimana dilakukan oleh Wijaya Herlambang, yakni membongkar pertalian politik maupun ekonomi, kapitalisme dengan pemikiran Islam di Indonesia pasca 65. Mengapa misalnya, pendulum pembaruan Islam berujung pada Liberalisme Islam. Mengapa Islam menjadi mandul dihadapan mesin penghancur yang tengah ganas-ganasnya dioperasikan di Dunia Ketiga pasca kemerdekaan melalui agenda pembangunan.
Dari semua narasi pembongkaran selubung politik di balik proyek pemikiran Islam tersebut, dalam hemat saya tugas yang pertama dan paling utama adalah pembersihan atas tendensi Liberalisme Islam di Indonesia. Dari sinilah kita bisa meletakkan “Islam rahmatan lil alamin” sebagai senjata perlawanan terhadap kapitalisme. Sehingga kelak seluruh narasi perjuangan, dan perlawanan kaum muslim Indonesia terhadap kapitalisme memperoleh pendasaran teologis dan teoritisnya. Yakni terbitnya suatu perlawanan dengan kata “tidak” yang solid. Sebuah kata “tidak” tanpa kata “tetapi” di belakangnya, yang akan menjadi perkakas perlawanan kaum muslim terhadap mobilisasi kapital yang terus merangsek, merampas ruang hidup rakyat atas nama pembangunan. Sedemikian, tanpa pembersihan atas tendensi Liberalisme Islam, “Islam rahmatan lil amalin” sebagai senjata perlawanan terhadap kapitalisme mustahil diwujudkan. Maka, kritik di sini harus dipahami sebagai logika menjebol dan membangun. Suatu ikhtiar kerja teoritik tanpa akhir untuk mengaktualisasi dan mematerialkan Islam lebih dari sekedar abstarksi ahistoris. Karena tugas kita saat ini adalah mematerialkan Islam dalam drama sejarah perjuangan manusia tertindas.
Jadi, adalah keniscayaan melakukan klarifikasi teoritik atas “Islam rahmatan lil alamin” dengan mengajukan kritik pada tafsir mapan atasnya, yang selama ini menjadi seolah-olah simetris dengan “liberalisme” yang tanpa disadari telah menjadi wabah yang menjangkiti kerangka pikir intelektual Islam Indonesia selama ini. Tak heran, jamak kita jumpai frase rahmatan lil alamin seringkali beriringan dengan terma liberal yang dibayangkan telah terang pada dirinya. Bahkan menjadi mantra yang berulang-ulang dirapalkan, bak dukun yang hendak mengusir hantu ke luar jendela, tapi tanpa disadari olehnya, bahwa mantra tersebut sejatinya adalah hantu itu sendiri yang telah mendaging dalam kesadaran diri sang dukun. Alih-alih mengusir hantu, justru makin melekatkan sang hantu pada diri dukun tersebut. Maka, bukannya membebaskan justru membelenggu. Bukannya mencerahkan justru membuat makin gelap cakrawala.
Setidaknya ada dua kritik fundamental yang telah kita ajukan pada Liberalisme Islam. Pertama, mengenai kategori rahmatan lil alamin, yang telah dipereteli universalitasnya menjadi beberapa aspek saja: moderasi dan toleransi. Persis pada titik inilah mereka tengah menihilkan progresifitas rahmatan lil alamin yang hanya diberhentikan pada persoalan politik pengakuan (recognition), dalam wujud dan rupa dialog antar agama dan iman (inter-religious and inter-faith dialogue) yang dicerabut dari konteks konsolidasi kapital di berbagai belahan dunia yang mencipta ketimpangan, dan krisis sosial-ekologis dengan menjarah jutaan hektar tanah petani dan masyarakat adat yang merupakan ruang hidup dan pembentuk identitas mereka. Dengan ini, Islam rahmatan lil alamin dimandulkan dan dijadikan sebagai penyedia jasa berbagai teror-teror korporasi yang jauh lebih mematikan ketimbang teror agama. Bahkan teror-teror korporasi inilah yang sebenarnya membidani lahirnya teror agama sebagai tragedi kemanusiaan abad 21. Hampir semua kajian mengenai terorisme, atau dalam banyak kajian mengenai ekstrimisme beragama di Indonesia tidak pernah dibaca sebagai entitas yang dideterminasi secara langsung oleh reorganisasi ruang neoliberalisme. Kedua, menguji posibilitas dan imposibilitas Islam rahmatan lil alamin dalam sistem kapitalisme. Sebagaimana kita tahu, di Indonesia, liberalisme Islam seringkali secara salah kaprah dipertukarkan dengan liberasi (liberation). Melalui pengaburan kategoris semacam itulah kapitalisme diselundupkan ke jantung Islam sebagai seolah-olah Islam itu sendiri.
Di sinilah momentum pentingnya menjadikan Islam rahmatan lil alamin sebagai senjata perlawanan dengan membongkar terlebih dahulu kategori-kategori diskursif yang terlanjur dianggap mapan dan belum terang dimana kakinya dipijakkan. Alternatifnya, bisa dengan memberi makna baru atas kategori-kategori diskursif tersebut untuk konteks historis hari ini, dan juga menambahi dengan kategori-kategori diskursif lainnya, yang selama ini dipandang secara minor dan diasingkan dalam percakapan akademis Islam, seperti: Jihad, perlawanan, solidaritas, sosialisme dan kolektivisme.
***
Tidak bisa dipungkiri, para perapal mantra liberalisme Islam, selama ini sangat alergi dengan terma Jihad, perlawanan, solidaritas, sosialisme dan kolektivisme. Sekonyong-konyong mereka akan menganggapnya sebagai subversif, bahkan secara sinikal dianggap tidak identik dengan Islam yang dibayangkan oleh mereka sebagai ramah dan toleran, welas asih dan penuh ampunan. Tapi di sini, kita tak boleh percaya begitu saja pada asumsi-asumsi tersebut yang seringkali ditempatkan secara ahistoris. Terlebih dulu harus dibuka selubung kepentingan politiknya. Akhirnya kita tahu maksud dari semuanya adalah welas asih pada Aburizal Bakrie, dan toleran pada seluruh kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.
Kita tak perlu heran, jika sangat sulit kita dapati terma-terma: Jihad, perlawanan, solidaritas, sosialisme dan kolektivisme tersebut, menjadi kata-kata kunci yang menjadi penerang jalan logika berpikir dalam lapisan gagasan para perapal mantra Liberalisme Islam. Bahkan kita tak akan menemukan porsi yang memadai untuk menganalisis kapitalisme, atau neoliberalisme dalam gejala pemikiran Islam Indonesia mutakhir. Lebih ironi lagi, para liberalis Islam di Indonesia secara picik dan memalukan menganggap perlawanan yang belakangan marak di banyak kantong-kantong serikat tani sebagai kurang Islami, tidak welas asih, dan mengumbar kekerasan. Padahal justru dengan melawan itulah para petani tengah mempraktikkan sebaik-baiknya nilai welas asih Islam untuk keberlangsungan hidup, dan kelestarian bentang alam hutan maupun gunung yang tengah terancam dieksploitasi. Kalau saja para eskponen Liberalisme Islam berani jujur, mereka akan mengatakan bahwa bukan petani atau jutaan rakyat manapun yang berlawan yang sedang mengumbar kekerasan, melainkan rezim neoliberal yang disebut sebagai imperialisme baru lah sejatinya pengumbar nafsu merampas dan mengobarkan peperangan. Melalui peralatan tempur canggihnya, seperti tank M1A2 Abrams, tank M1A3 Bradley, pesawat anti tank A-10 Thunderbort II, serta dukungan helikopter serbu AH-64, Amerika Serikat membombardir secara brutal dan meluluhlantakkan kota-kota di Irak dengan dalih menegakkan demokrasi liberal dan melucuti senjata pemusnah massal. Begitupun dengan penghancuran ruang hidup rakyat di Indonesia. Tidak segan-segan kekuatan militer dipakai sebagai jalan memuluskan perampasan. Peristiwa 65 menjadi salah satu monumen kekerasan kapitalisme di Indonesia yang paling keji.
Memang tak bisa dipungkiri bahwa kegamangan atau keengganan mengoperasikan terma Jihad dan perlawanan juga akibat dari aksi-aksi brutal terorisme yang mengatasnamakan Islam. Meski demikian, memilih membekukan terma tersebut sebagai sekadar menjadi milik kaum teroris, justru makin melegitimasi kekerasan terorisme, dan kejahatan korporatisme kapitalisme yang membidani teroisme di satu sisi, dan menenggelamkan aspek progresif dalam Islam di sisi lainnya. Sebagai akibatnya, Islam seperti tak punya formula atas berbagai peristiwa aktual yang menimpa umatnya yang mengakibatkan lahirnya situasi dilematis, antara fatalisme yang menerima segala persoalan sebagai ujian hidup dari Allah yang harus diterima dengan lapang atau justru menerima kapitalisme sebagai jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengentaskan berbagai persoalan yang membelenggu kaum muslim.
Entah diakui atau tidak, agenda pemikiran Islam tengah menghadapi tantangan serius sebagai akibat dari terjadinya serangkaian mutasi historis, dalam rupa ekspansi kapitalisme global dalam mencari ruang-ruang baru akumulasi kapital, yang belakangan dimatangkan oleh Paul Krugman dengan teori geografi ekonomi barunya. Ekspansi kapital global, telah mengakibatkan terjadinya sebuah krisis teoritis dalam jantung pemikiran Islam Indonesia secara umum, yang sejauh ini mempostulatkan ‘rasio’ secara ahistoris dengan mengabaikan kerangka basis posisi-posisi kelas yang sedang terus menerus bertarung hidup dan mati berebut ruang hidup. Sementara kita saksikan dunia, khususnya Dunia Ketiga seperti Indonesia, tengah dilanda gelombang besar globalisasi ekonomi yang menjarah seluruh penjuru bumi melampaui batas-batas negara demi kepentingan produksi dan akumulasi kapital telah memblokir petani dari sumber daya yang selama ini menopang hidupnya, yakni tanah. Melalui itu mereka diubah menjadi buruh upahan di pabrik-pabrik kapitalis di mana hasil kerja mereka dihisap (profit dan surplus value) secara terus-menerus.
Liberalisme Islam beserta serentetan kategori-kategori diskursifnya, alih-alih menjadi antidote atas racun neoliberalisme, justru menjadi varian neoliberalisme. Pasalnya formula yang mereka tawarkan selama ini sebagai penangkal racun, sebenarnya merupakan racun itu sendiri bagi rakyat Indonesia, dan kaum muslim khususnya. Apa solusi yang mereka ajukan. Sudah bisa ditebak: mensinergikan antara penghisap dengan yang dihisap. Tepat pada titik ini, Liberalisme Islam yang mulanya bertujuan menghalau fatalisme beragama yang tampil dalam wajah konservatifisme beragama, pada akhirnya mempunyai corak berpikir yang hampir serupa dengan kaum fatalis. Bila Islam liberal menganggap ekspansi kapital sebagai jalan memodernisasi umat Islam, maka Islam fatalis mengira ekspansi kapital sebagai takdir dari Allah yang tak bisa ditampik keberadaannya.
Adalah hal yang mustahil mendamaikan hubungan konfliktual antara penghisap dengan yang dihisap. Kaum borjuis menghendaki akumulasi kapital sebesar-besarnya melalui kerja buruh atau melalui penjarahan ruang hidup diluar mode produksi kapitalisme, sebagaimana ditunjukkan oleh Rosa Luxemburg bahwa akumulasi kapital mempunyai dua hal yang saling terkait satu sama lain yakni pasar komoditi dan tempat nilai lebih (surplus value) diproduksi seperti di pabrik, pertambangan, dan lahan pertanian, dimana penghisapan terjadi secara langsung dan vulgar. Aspek lain dari akumulasi kapital adalah penjarahan kapitalisme terhadap mode produksi non kapitalis, melalui kolonialisme, yang dilakukan dengan jalan kekerasan, pemaksaan, dan penipuan secara terang-terangan.[1] Persis sebagaimana kita saksikan hari ini.
Dalam drama politik internasional praktek-praktek kotor ini masih terus dilakukan, khususnya oleh Amerika Serikat yang menciptakan malapetaka kemanusiaan di Timur Tengah hingga sekarang. Yang ironinya, malapetaka kemanusiaan tersebut seringkali dilihat sebagai semata-mata akibat dari kegagalan beragama di Timur Tengah, yang mengakibatkan kaum muslim terjebak pada politik sektarianisme. Pembancaan semacam itu tidak sepenuhnya keliru, tapi menganggapnya sebagai faktor penentu jelas salah besar dan ahistoris. Karena bagaimanapun juga, sejak tahun 50-an Amerika Serikat telah menempatkan Timur Tengah sebagai kawasan yang esensial bagi kontrol ekonomi, militer dan politik atas dunia, karena kawasan tersebut memiliki kandungan cadangan minyak paling besar di dunia, dengan itu Amerika telah memulai serangkaian operasi rahasia dan terbuka di kawasan itu pada tahun 1950-an. Salah satu operasi terpentingnya adalah penggulingan Mossadegh, seorang pemimpin Iran yang terpilih secara demokratis, karena ulahnya menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak milik asing.[2] Bahkan, segera setelah perang Irak terjadi, Halliburton, sebuah perusahaan milik wakil Presiden Cheney, meraup perolehan hampir satu milyar dari kontrak-kontrak minyaknya. Dimana antara tahun 1940 dan 1967, kontrol perusahaan-perusahaan AS atas cadangan minyak Timur Tengah naik dari 10 persen menjadi 60 persen, sementara cadangan minyak yang berada di bawah kontrol Inggris merosot dari 72 persen pada tahun 1940 menjadi 30 persen pada tahun 1967.[3]
Demi untuk mengukuhkan dominasinya atas kawasan Timur Tengah, AS membentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara lainnya sebagai anggotanya. AS menjual perlengkapan militernya pada negeri-negeri tersebut sebagai suatu back-up bagi kekuatan AS di kawasan tersebut (transfer persenjataan senilai bersih $42 milyar — $23 milyar diantaranya ke Arab Saudi— berlangsung sepanjang tahun 1990-an). kekuatan-kekuatan AS ditempatkan sebagai penjaga di kawasan tersebut sepanjang tahun 1990-an dan gudang-gudang besar perlengkapan senjata dibangun di Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi yang memungkinkan AS memiliki kemampuan bergerak langsung.[4]
Dengan demikian, kapitalisme tak akan segan-segan menggunakan kekuatan militernya secara unilateral bila kepentingan ekonominya terancam, termasuk juga di Indonesia. Apakah dengan demikian kita mesti mentolerir segala penjarahan atas bumi, dan air Indonesia seperti saat ini melalui investasi. Apakah dengan investasi tersebut, lantas dengan sangat ajaib, atas seizin Allah, kaum muslim akan keluar dari kubangan pengisapan. Tentu sama sekali tidak.
***
Disinilah perlunya rahmatan lil alamin menjadi landasan aksiomatik sekaligus kompas perjuangan kaum muslim, dimana terma jihad, dan perlawanan bisa dioperasikan di dalamnya untuk membela kaum Mustadh’afin[5] (yang dibuat lemah atau tak berdaya) dengan melepas belenggu mereka dari cengkeraman kaum Mustakbirin. Sebagaimana hadis Nabi,
“Barangsiapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, baginya ganjaran seperti haji mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman—menutup rasa lapar, membebaskan dari kesulitan atau membayarkan hutang”.[6]
Dalam Al-Qur’an secara terang benderang disebutkan bahwa menolong dan membela yang lemah, yakni kaum mustadh’afin adalah tanda-tanda orang yang takwa.[7] Sementara mengabaikan nasib mustad’afin, acuh tak acuh terhadapnya, enggan memberi pertolongan pada mereka akan menyebabkan seorang muslim menjadi pendusta agama, dan shalatnya akan membawa kecelakaan.[8] Dan Allah sendiri yang menjerumuskannya ke dalam neraka Saqar.[9]
Mustadh’afin bukanlah orang Sunni, orang Syi’i, orang Kristen, orang katolik, orang Yahudi, orang Budhis atau orang ateis. Melainkan siapapun yang dilemahkan secara struktural melalui kebijakan-kebijakan, melalui serangkaian perampasan ruang hidup yang terjadi secara legal tapi tidak berkeadilan. Sementara kaum Mustakbirin bukanlah orang Sunni, orang Syi’i, orang Baha’i, orang Yahudi, orang Budhis, atau orang ateis tapi siapapun yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai kaum penumpuk harta,
“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”[10]
Allah menyebutkan penyebab kemiskinan adalah kecenderungan untuk tidak memuliakan anak yatim, tidak adanya usaha bersama untuk membela orang miskin, kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber daya (at turats) secara rakus dan kecintaan yang berlebih-lebihan pada harta benda.[11]
Penggunaan terma Jihad dan perlawanan, bukan berarti tanpa resiko disalahpahami, karena bagi sebagian besar orang Barat, sebagaimana pernah dikatakan oleh Huston Smith, tidaklah mudah memahami Islam yang tidak memisahkan antara Iman dan politik. Bahkan banyak orientalis yang menuduh bahwa Islam mengobarkan kebencian dan peperangan. Mereka menuduh Nabi sebagai pelaku pelecehan seksual dan menyebarkan agama melalui pedang. Saking mengada-ngada nya hingga merangkai kisah fiktif yang menggambarkan Nabi dan para sahabatnya tak lebih dari kawanan manusia gurun bengis yang menunggangi kuda dengan tangan kanan memegang pedang dan tangan kiri memegang Al-Qur’an. Terang saja kisah fiktif semacam ini sekarang menjadi lelucon karena tidak ada dalam sejarahnya umat Islam, apalagi Nabi, memegang Al-Qur’an dengan tangan kiri. Tapi memang tidak bisa dipungkiri jika Nabi Muhammad seorang jenderal yang memimpin perang. Dalam sejarah Nabi (sirah nabawiyah), Ibn Hisyam menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melakukan ghazwah atau perang sebanyak 27 kali sepanjang hidupnya.[12] Nabi berperang bukan untuk mengobarkan kekerasan, melainkan kondisi objektif yang menuntunnya untuk bertindak demikian. Sebagaimana pemuda dan pemudi di Palestina yang harus angkat senjata di negerinya.
Persitiwa Fath al-Makkah merupakan eksperimentasi politik Nabi yang menunjukkan betapa tidak ada pertumpahan darah, pembunuhan anak-anak dan orang-orang yang tak berdosa dalam perjuangan Nabi. Ini berdasarkan pada konsep Islam tentang perang (The Islamic concept of war), yang memerintahkan selama perang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, atau membunuh orang yang sudah menyerah, tidak diperbolehkan merusak tempat-tempat Ibadah, simbol-simbol atau ritus-ritus sakral dan lain-lain. Sehingga tak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat menyerang kelompok-kelompok agama yang berbeda, menghancurkan Gereja dan Sinagoge. Karena yang dilawan bukanlah agama melainkan kebatilan dan ketidakadilan. Maka ketika ada kaum muslim yang memerangi kelompok agama tertentu yang berbeda dengan dirinya, sesungguhnya ia telah offside dari Islam. Dengan sendirinya ia telah kufur pada kebenaran Islam.
Inklusifitas dan toleransi beragama sangat dijunjung tinggi pada zaman Nabi, yang kemudian ditransformasikan pada zaman sahabat, terutama pada masa Sahabat Umar bin Khattab pada masa penaklukan Palestina. Sejarah mencatat bahwa Umar masuk Gereja dan memberikan pidato yang melarang tentaranya untuk merusak bangunan-bangunan suci dan simbol peradaban yang ada di Palestina. Jangankan merusak, mencela saja dilarang dalam Islam.
Dengan mengoperasikan kembali terma Jihad dan perlawanan akan sangat berperan besar pada pelurusan pengertian distorsif atas terma tersebut, baik yang telah secara keliru dipraktikkan oleh kaum ekstrimis Islam maupun propaganda anti Islam yang dihembuskan oleh media-media kapitalis selama ini. Jihad tidak identik dengan kekerasan. Perlawanan tidak otomatis hendak mengobarkan peperangan. Namun yang paling penting dari keduanya adalah kesanggupannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya sikap abu-abu atau posisi syubhat politik yang seringkali menelikung perjuangan dari dalam, yang melalui itu semua pemikiran dan front politik Islam progresif bisa ditegakkan pancangnya di bumi Indonesia.
Mengapa kita melawan kapitalisme? Semata-mata hendak mewujudkan Islam sebagai rahmat seluruh alam. Sebagai jalan welas asih pada semua manusia yang dirampas hak-haknya. Sebagai jembatan cinta kasih pada keberlanjutan hidup yang adil dan setara, hidup tanpa pengisapan dan perampasan. Dengan demikian, tanpa tedeng aling-aling, dengan lantang harus kita katakan bahwa Liberalisme Islam Indonesia telah menempatkan “Islam rahmatan lil alamin” tak lebih hanya sebagai hamba investasi. Naudzubillah Mindzalik***
Jombang, 6 Februari 2017
————-
[1] Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, (London: Routledge, 2003), hal. 432.
[2] David Harvey, New Imperialism, (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 20.
[3] Ibid., hal. 19.
[4] Ibid., hal. 22.
[5] Kata Mustadh’af berasal dari akar kata dha’fun yang berarti lemah. Dhu’afa (bentuk tunggalnya dha’if) berarti orang lemah. Yang membedakan antara Mustadh’afin dan Dhu’afa adalah, kalau Mustadh’afin berarti orang-orang yang dilemahkan (the oppressed) sementara Dhu’afa berarti orang-orang lemah (the weak).
[6] HR. Ibn Hajjar al-Asqhlani dalam Nashaih al-‘ibad, (Bandung: Al-Ma’arif, tth), hal. 4.
[7] QS. 2:197; QS. 3:134; QS. 76:8-9; QS. 70:24; QS. 51:19.
[8] QS. 107.
[9] QS. 74:42.
[10] QS. 104: 1-3.
[11] QS. 89:15-20.
[12] Berikut merupakan 27 peperangan Nabi sepanjang hidup yang dijalaninya: Perang Badar, perang Uhud, khandak, Quradidhah, Al-Mustaliq, Khaibar, Fath Makkah (Penaklukan Makkah), Hunain, Thaif, Waddan, Buwath, Al-Qusyairah, Badar Kubra, Bani Sulaim, As-Sawiq, Ghafatan, Bahran Ma’dan, Hamra’ul Asad, Bani Nadhir, Al-Riqa, Badar Terakhir, Daumatul Jandal, Bani Lahyan, Dzu Qarad, Hudaibiyah, Umrah tertunda, dan Tabuk. Lih. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam al-Mu’afiri, As-Sirah al -Nabawiyah li Ibn Hisyam, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 594-595.