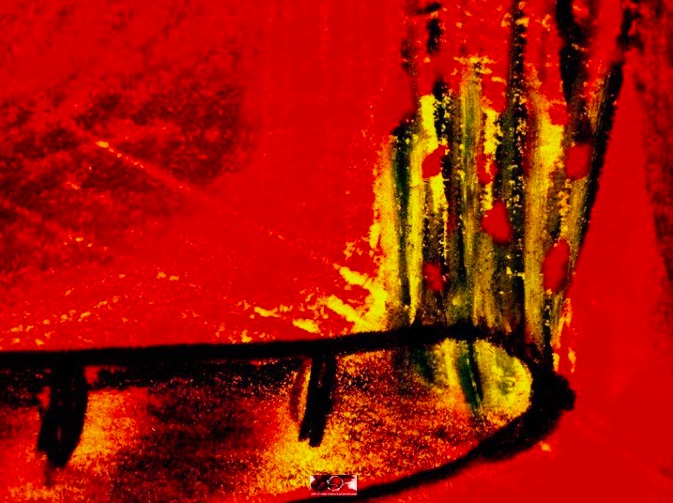
Ilustrasi oleh Andreas Iswinarto
HISTERIA anti komunis datang lebih cepat tahun ini. Bila biasanya ‘dirayakan’ menjelang tanggal keramatnya pada 30 September/1 Oktober, maka tahun ini sudah memanas sejak pertengahan April. Elit-elit politik maruk kuasa segera sibuk membangunkan rakyat dengan alarm tanda bahaya kesukaan mereka: ancaman dan hasutan. Menyanyikan dengan semangat ‘lagu-lagu kebohongan’ bahkan dalam versi yang terdengar paling bodoh sekalipun. Persoalannya bukan kurangnya intelektualitas para provokator anti komunis kambuhan ini. Faktanya, mereka tahu dari pengalaman, bahwa tak ada hukuman dan konsekwensi serius apapun yang menanti tindakan mereka. Korban persaingan elit selalu bisa dicari dari kalangan rakyat yang mudah ditumbalkan.
Tahun ini perayaan mengusir hantu komunis terlaksana lebih cepat setelah pemerintah Jokowi secara agak mengagetkan menyelenggarakan Simposium Tragedi 1965. Sebuah acara yang memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pertemuan yang difasilitasi, bahkan dibiayai, oleh pemerintah – lewat Kantor Menko Polhukam — dengan menghadirkan dua kalangan yang dianggap paling bertentangan dalam tragedi 1965. Mereka yang dianggap mewakili dan membela korban tragedi 1965 datang dari komunitas penyintas dan keluarganya, organisasi-organisasi advokasi Hak Asasi Manusia. Sementara dari kalangan yang berseberangan turut diundang kalangan militer hingga komunitas keluarga korban G30S. Bahkan turut menjadi tim pengarah acara adalah Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo, yang merupakan anak dari Jenderal Sutoyo, salah seorang yang terbunuh dalam G30S.
Segera histeria anti komunis menyalak kencang melalui media, menyatakan penolakan fasilitasi pemerintah terhadap aktivitas yang memungkinkan pembicaraan publik soal 1965 di luar pola yang dibangun sejak Orde Baru. Tentu kita tidak bisa mengabaikan sama sekali bahwa Abdulrahman Wahid alias Gus Dur, selaku Presiden kedua pasca Soeharto lengser, pernah mendorong niat serupa dengan mewacanakan penghapusan Tap MPRS 25/1966 yang melarang PKI dan penyebaran Marxisme Leninisme. Sayangnya sejarah mencatat upaya tersebut gagal bergulir jauh karena elit-elit politik keburu mengkudeta Gus Dur. Berbagai pemerintahan sesudah Gus Dur memilih tidak keluar dari pola menjadikan persoalan 1965 sebagai masalah yang pembahasannya merupakan privelese elit politik saja.
Di masa lalu bila masyarakat awam membicarakan, apalagi berupaya mencari solusi penuntasan dilema politik terkait tragedi politik 1965, maka ganjaran hukum yang keras sudah siap menanti. Tetapi sejak masa pasca 1998, secara bertahap kemungkinan untuk terus mempertahankan pola represif itu tampaknya terus menerus berkurang relevansinya. Ditandai oleh beberapa aturan hukum yang terkait tindakan represif yang biasa dilakukan sudah mulai dapat dihilangkan – misalnya pembatasan kuasa untuk pelarangan buku, atau pun kesempatan bagi mantan anggota PKI untuk menggunakan hak pilih dan dipilih. Walau pun begitu, bukan berarti seluruh stigma dan intimidasi ala pola pengendalian politik warisan rezim Orde Baru terkait isu PKI dan hantu komunis sudah hilang.
Pemilu 2014 lalu, dengan segala keterbatasannya, telah membuka ruang bagi kemunculan formasi elit politik baru. Mewujud dalam figur Jokowi yang menunjukkan, dalam berbagai kesempatan, kepentingannya untuk tidak selalu dikendalikan oleh formasi-formasi elit politik yang sudah berkuasa lama dan berjaringan dengan akar klas penguasa dari jaman Orde Baru. Penggambaran barusan tentang Jokowi tidak berarti ia dan formasi politik yang sedang dibangunnya sekarang bebas sama sekali dengan kekuasaan oligarki yang sudah ada. Penggambaran tentang Jokowi di atas pun tidak berupaya menyiratkan bahwa formasi poltik yang dibangunnya sekarang punya jaringan yang berakar pada gerakan rakyat – terlepas metode pelibatan aktivis-aktivis gerakan sosial dalam posisi-posisi kekuasaan. Singkatnya, yang hendak diargumentasikan oleh tulisan ini bahwa ada kepentingan dari formasi politik Jokowi saat ini untuk keluar dari pola konvensional penanganan ‘masalah 1965’.
Kepentingan politik Jokowi belum tentu sama persis dengan kepentingan politik gerakan sosial yang progresif untuk menuntaskan pelanggaran HAM. Kepentingan politik Jokowi tentu lebih terkait dengan kalkulasi memperkuat dan mempertahankan kekuasaan atas negara. Metode penyelesaian yang diarahkan untuk melakukan rekonsiliasi tanpa proses pengadilan hukum memberikan indikasi tentang salah satu perbedaan yang mencolok. Kepentingan dari upaya memulai penuntasan ‘masalah 1965’ jelas punya dimensi pragmatis untuk mengurangi semaksimal mungkin dominasi elit-elit politik lama yang akan terus menggunakan stigma PKI untuk menyerang rival politik dalam berbagai kontestasi politik – termasuk dalam pemilu 2019 mendatang, sebagaimana sudah terjadi di pemilu 2014 lalu. Bila proses rekonsiliasi yang mereka harapkan terjadi maka dapat diklaim sebagai bukti prestasi kerja pemerintahan dan akan memperbesar dukungan publik pada saat dibutuhkan.
Adalah wajar pelaku-pelaku politik bertindak berlandaskan kepentingan-kepentingan mereka yang konkret. Namun kepentingan dan rencana politik akan ditentukan sifat dan hasilnya lewat momen pertarungan politik yang nyata juga. Sebagai contoh, kepentingan politik Jokowi lewat inisiatif simposium terbukti segera direspon oleh gerakan histeria anti komunis yang aktif melakukan serbuan fitnah, hasutan dan mobilisasi massa. Tujuan repon tersebut adalah menetapkan batas dari kemungkinan rekonsiliasi versi pemerintah Jokowi, bila tidak mungkin menggagalkannya. Rekonsiliasi buat mereka harus lah dilakukan bersamaan dengan penguatan politik sektarianisme demi fasilitasi kelompok-kelompok paramiliter reaksioner. Politik kiri harus tetap dipertahankan sebagai kambing hitam abadi buat seluruh permasalahan yang dihasilkan oligarki dan kepentingan ekonomi politik yang menyertainya. Kambing hitam yang dapat digunakan untuk sebagai cap bagi berbagai bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan sosial yang mereka alami. Artinya kepentingan nyata dari kelompok yang mendukung histeria anti komunis juga sangat lah nyata, bukan sekedar romantisme ketinggalan zaman atau kurangnya intelektualitas.
Kini yang menjadi ujian dalam momen sekarang ini adalah apakah kaum progresif dan demokrat di era paska otoriter ini dapat mengukuhkan kepentingan mereka juga lewat respon yang memaksa pemerintah Jokowi tidak tunduk pada batasan yang diinginkan kelompok-kelompok reaksioner itu. Apakah kita dapat merespon secara cerdik dan jitu peluang yang bergulir dari langkah pemerintah membangun pola baru dalam membahas dan mencari solusi atas “tragedi 65”. Formula agenda dan strategi memanfaatkan momentum yang bergulir dari inisiatif simposium pemerintah harus dijangkarkan pada kepentingan generasi baru untuk bebas dari beban intimidasi dan hegemoni Orde Baru. Pada generasi muda juga lah kita menemukan arena pertarungan utama antara kepentingan bebas atau terus tersandera ‘histeria anti komunis dan kebangkitan PKI’. Simposium seperti yang digulirkan pemerintah dengan memberi ruang masyarakat membahas dan mencari solusi secara aman atas ‘masalah 1965’ harus dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. Generasi muda harus lebih diberikan peran untuk terlibat, sekalipun mereka bukan lah korban atau pelaku langsung dari tragedi 1965.
Kenyataan tentang kepentingan politik yang konkrit harus disadari oleh kalangan progresif. Dengan menyadari bahwa dalam kenyataan politik saat ini kalangan gerakan rakyat masih tidak terorganisir baik, bahkan tidak memiliki pewadahan yang memadai untuk memenangkan kepentingan-kepentingannya. Akibatnya kalangan gerakan belum merespon dinamika yang bergulir terkait ‘histeria 65’ berdasarkan perumusan kepentingan politik yang terformalisasikan dengan baik dan terwujud dalam tindakan-tindakan politik yang konsisten dapat didukung massa secara luas. Bukan berarti kalangan gerakan sama sekali tidak melakukan apa-apa dalam momen sekarang ini, tapi harus dengan jujur diakui bahwa karakternya masih bersifat defensif dan tidak terkonsolidasi. Kapasitas yang sejauh ini bisa dibangkitkan oleh komite-komite aksi yang sudah bergerak memprotes fitnah dan intimidasi gerakan masih jauh tidak sepadan dibandingkan gerakan kaum ‘pemelihara hantu komunis’. Artinya masalah pewadahan dan mobilisasi harus segera menemukan solusi dan strategi yang dapat didukung massa secara luas, terutama di kalangan generasi muda.
Berharap ‘histeria anti komunis’ ini usai begitu saja dengan bersikap pasif dan atau defensif jelas bukan pilihan yang strategis. Menertawai kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan tokoh-tokoh gerakan histeria anti komunis mungkin berguna untuk mengusir paranoid atas intimidasi mereka. Akan tetapi yang jauh lebih dibutuhkan segera adalah konsolidasi gerakan yang kuat, yang bisa memaksa negara menjamin kebebasan rakyat membahas dan mencari solusi ‘masalah 1965’ secara aman dan demokratis. Jaminan yang harus dibuktikan dengan tersedianya lebih banyak lagi ruang aman bicara dan mencari solusi soal tragedi 65 di seluruh Indonesia. Jaminan yang harus bisa dinyatakan secara terbuka oleh kepala negara kepada seluruh warganya.***





