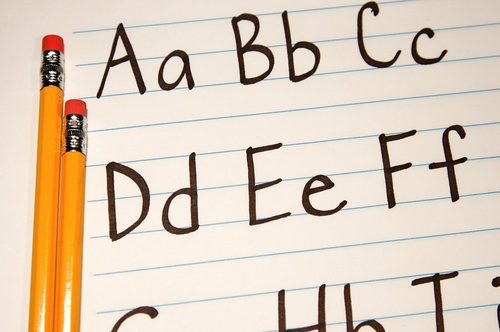KITA sudah memasuki 50 tahun pembantaian ‘65. Ini prahara yang paling bergelimang korban nyawa dalam sejarah Indonesia. Tak terhitung banyaknya pengakuan dari para korban dan pelaku kekejian. Namun, kita hanya seperti memasuki labirin gelap, tanpa ada pengadilan yang dilaksanakan. Kita masih berada dalam pertarungan bahasa yang belum juga kunjung selesai.
Di jalan-jalan Solo, kita menemukan berbagai spanduk antikomunis. Ini hanya sekelumit bukti tersurat dan pasti bukan yang terakhir.
Ada yang kita lupakan: bahasa.
Dalam tragedi ’65, politik bahasa punya dampak yang mengerikan bagi orang Indonesia. Akibat politik bahasa, meminjam Ariel Heryanto (2015: 5), kita memasuki terowongan ‘amnesia [berkelanjutan] publik Indonesia tentang sejarahnya sendiri yang kompleks’.
Politik bahasa nasional yang turut mengaburkan sejarah ini adalah cerita yang cukup panjang. Pada 1972, Ejaan yang Disempurnakan (EyD) menggantikan ejaan Suwandi. Ilmuwan politik Ben Anderson membacanya sebagai motif pemisahan yang tegas antara apapun yang ditulis sebelum dan sejak rezim militeristik Orde Baru, dengan dalihnya kerjasama dengan Malaysia. Singkatnya, EyD bertujuan menutup pintu gerbang sejarah dari para pelakunya. Belakangan, pokok yang sama juga ditekankan lagi oleh Joss Wibisono dalam buku Saling-Silang Indonesia-Eropa: Dari Diktator, Musik, Hingga Bahasa (2012).
Bagi Orde Baru, akan berbahaya jika generasi muda melek sejarah, khususnya narasi ‘sejarah’ yang memang dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan seperti kisah ‘G 30/S [PKI]’. Mereka akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Soeharto ternyata tidak ada bedanya dengan kolonial Belanda, bahkan jauh lebih buruk, lebih sadis, lebih tak manusiawi. Dus, generasi pasca-1965 pun dibungkam sejak cara bertuturnya.
Strategi ini sungguh ampuh, karena bagaimanapun orang berpikir dalam batas-batas bahasa. Apa yang tidak terlintas dalam bahasa kita, akan sulit terlintas pula di pikiran. Ini sama saja dengan berusaha melupakan orang yang tidak pernah kita temui. Dan ini terbukti benar.
Pengguna EyD akan dengan sendirinya tidak betah membaca buku dan sumber tertulis lain yang tidak ditulis dalam EyD. Mereka bukan saja tidak doyan sejarah, namun juga kesulitan membaca bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah, yang adalah bacaan-bacaan lama non-EyD.
Tentu bukan hanya ejaan. Eufemisme juga diperkenalkan dengan agresif. Dalam ranah kajian sosial, misalnya, konsep ‘kelas’ dihapuskan pada masa Soeharto. Rejim Orde Baru juga ‘mengganti semua istilah yang lazim mereka [para ilmuwan sosial] gunakan dengan bermacam istilah baru yang dianggap lebih sesuai oleh rezim’ (Hilmar Farid, 2006). Kata ‘buruh’ yang terasosiasikan dengan kelas proletar diganti dengan ‘karyawan’ atau ‘pekerja’ yang lebih bernuansa berkompromi dan penurut. Kata ‘Tionghoa’ diganti ‘Cina’. Termasuk, kata ‘long march’ dan ‘demonstrasi’ diperlunak dengan istilah ‘unjuk rasa’ yang tak mempunyai nilai konseptual, kecuali luapan emosi picisan.
Dengan demikian, para ilmuwan itu sudah harus berkompromi sejak dalam pikiran ketika menyampaikan gagasannya. Kata-kata yang sebenarnya hendak disampaikan tidak dapat benar-benar seperti apa yang ingin disampaikan oleh karena pembatasan bahasa atau pengeditan pikiran. Implikasi yang ditimbulkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan pewarisan sejarah itu sendiri pada akhirnya cacat sejak sebelum lahir dan sebelum terwariskan dalam bentuk ilmu.
Saya teringat kisah Guru Alfonso dalam cerpen Pelajaran Sejarah karya Seno Gumira Ajidarma (1994). Sang Guru Alfonso hendak mewariskan ilmu sejarah insiden Santa Cruz di Dili 1991 pada murid-muridnya. Masalahnya, pengetahuan tersebut tidak ada di buku sejarah resmi pemerintah dan terlarang ditulis apalagi dibuat pelajaran bagi para siswa. Padahal, Guru Alfonso percaya bahwa perbaikan masa depan hanya akan terjadi jika murid-muridnya mampu memahami sejarah, terutama yang menghantui kehidupan mereka.
Demikianlah, pada jam pelajaran sejarah, suatu siang di bulan November, Guru Alfonso membawa murid-murid kelas VI ke sebuah pekuburan. Murid-murid bermata ‘bulat dan besar’ yang biasanya nakal itu mendadak terdiam. Mereka tahu, meski selalu samar-samar, bahwa telah terjadi ‘sesuatu’ di pekuburan itu tapi tak boleh terkatakan apalagi menjadi ilmu. Guru Alfonso kepalanya dipukul dengan popor senjata sampai berdarah dan pura-pura mati agar selamat. Tentu saja, di pekuburan itu, banyak orang tua dan sanak keluarga para murid meninggal mengenaskan.
Peristiwa Santa Cruz ini jauh melampaui bahasa. Tetapi toh, Guru Alfonso harus berjuang melawan segala trauma demi pewarisan sejarah yang tak boleh terputus. Karena ‘hanya dengan suatu cara berbahasa yang saling bisa dimengerti sejarah mereka bisa dihayati.’***
Tulisan aslinya berjudul ‘Bahasa Indonesia dan Amnesia Sejarah’. Sebelumnya diterbitkan di LPM Kentingan, 16 Oktober 2015. Dimuat ulang untuk tujuan pendidikan.