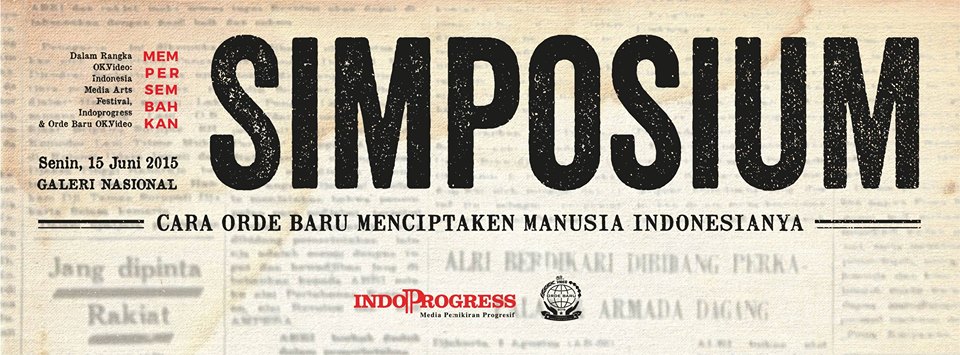Sebuah catatan—sekaligus advertorial—tentang “Simposium Orde Baru: Cara Orde Baru Menciptaken Manusia Indonesianya” dalam rangka ORDE BARU OK. VIDEO: INDONESIA MEDIA ARTS FESTIVAL
BERTO TUKAN melangkah meninggalkan sebuah rumah gedongan di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dengan getir. Beberapa saat kemudian ia mengaku, ia telah patah arang saat itu. Kami, selaku teman dan rekan kerja, malah tertawa. Pahit.
Ini artinya rencana kami bakal runyam.
Seminggu sebelumnya, Berto jauh lebih sumringah. Ia berhasil membujuk Daoed Joesoef, bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada penghujung dekade 1970an, untuk menjadi salah satu pembuka Simposium “Cara Orde Baru Menciptaken Manusia Indonesianya”. Tak heran kalau Berto girang. Ini tangkapan besar. Daoed Joesoef adalah salah satu figur paling dahsyat dalam jajaran intelektual-teknokrat Orde Baru. Sebelum menjabat sebagai Menteri P & K, Daoed juga ikut mendirikan Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think-tank papan atas kepercayaan Orde Baru. Di bawah tangan besinya sebagai Menteri P & K, Daoed mencanangkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan sebagai upaya depolitisasi mahasiswa.
Kami berbesar hati. Seno Gumira Ajidarma, sastrawan yang tenar dengan kredo “ketika jurnalisme dibungkam, sastrawan bicara” dalam melawan represi Orde Baru, sudah menyanggupi untuk menjadi pembicara dalam pembukaan Simposium. Dengan kesanggupan Daoed, maka pembukaan keduanya akan sangat rancak. “Intelectual deathmatch,” celetuk Mochamad Abdul Manan Rasudi ketika itu.
Namun, hati kami yang besar meletus tertusuk jarum ketika Berto memberi kabar tentang (rencana) pertemuan keduanya dengan Daoed.
Sehari sebelum pertemuan kedua, Berto menerima telpon dari Daoed yang kebakaran jenggot. Pasalnya sepele, tapi runyam. Ketika itu, panitia ORDE BARU OK. VIDEO selaku penyelenggara festival mengirimkan Memorandum of Understanding (MoU) kepada Daoed untuk acara yang akan diadakan pada tanggal 15 Juni. Ini praktek lumrah. Ketika dua pihak melakukan kerjasama, perlu jelas hak dan kewajibannya.
Namun, tanpa dinyana, hal ini menyinggung perasaan Daoed. “Dia bilang, MOU itu bikin kerja intelektual kayak buruh kontrak,” demikian bunyi pesan singkat Berto dalam grup Whatsapp kami. Jelas kami terbelalak. Kok bisa?
Namun kami tak membuang waktu untuk terkesima. Kami hanya punya tujuh hari sebelum acara dihelat. Kalau Daoed membatalkan kehadirannya, bahaya. Poster dan publikasi sudah kadung disebar.
Berto segera meminta maaf. Pihak ORDE BARU OK. VIDEO pun sigap membuat surat resmi permohonan maaf. Barangkali masih ada harapan Daoed senang dan jadi datang. Berto dan koordinator program ORDE BARU OK. VIDEO pun bersepakat akan menandangi rumah Daoed untuk meminta maaf. Namun sia-sia. Ketika Berto dan Camel, sang koordinator program itu, bertandang ke kediaman Daoed pada siang yang laknat itu, sang empunya rumah menolak untuk bertemu.
*
Sudah lewat tujuh belas tahun, Orde Baru tak pernah benar-benar mati. Kita masih bisa menunjuk relik-relik Orde Baru berkeliaran di layar kaca atau muncul di tajuk utama koran pagi. Daoed Joesoef hanya salah satunya. Kemilaunya pun sudah redup. Pengaruhnya tak sebesar dulu. Ia pun sudah terlalu renta. Yang berkibar hari ini adalah pengusaha, politisi, dan tentara yang mulai berkiprah di tahun 1970an.
Dalam benak banyak orang, Reformasi hanyalah peralihan tongkat estafet kekuasaan; dari Negara monolitik, kepada pluralitas oligarki. Kita tahu masalah-masalah ini—kita hidup di dalam masalah-masalah ini—dan kita sudah jenuh. Bagi sebagian orang yang nostalgis, kejenuhan ini diarahkan pada agenda Reformasi itu sendiri, sambil memimpikan kembalinya stabilitas ekonomi-politik Orde Baru yang dihancurkan oleh Reformasi. Sebagian lain mengutuki Orde Baru atas kebobrokan Indonesia hari ini sambil menawarkan solusi yang sama sekali berlawanan dari keadaan yang diciptakan Orde Baru. Jika Orde Baru menciptakan pemerintahan terpusat korup, yang represif, maka yang seharusnya terjadi adalah emansipasi dalam transparansi dan pembagian kekuasaan yang saling mengimbangi. Jika Orde Baru melakukan depolitisasi habis-habisan, maka jalan keluarnya adalah mempersenjatai rakyat dengan politik.
Di tengah dua solusi grusa-grusu ingin mengubah bangsa itu, barangkali kita perlu berhenti sejenak untuk mencerna realitas dan berpikir. Orde Baru tidak bisa berkuasa selama 32 tahun tanpa mencetak subjek-subjek yang klop dengan roda gerigi pemerintahan yang ia jalankan. Subjek-subjek ini tentunya dicetak secara massal; melalui pendidikan, kontrol atas informasi, seni tinggi maupun populer, hingga tata cara orang bercinta (baca: Keluarga Berencana, KB). Tak seperti monumen-monumen pengaturan seperti ritual menonton G30S/PKI atau instansi pemerintahan layaknya Departemen Penerangan, subjek-subjek Orde Baru ini tidak serta merta luruh ketika rezim itu tumbang. Yang diciptakan oleh Orde Baru bukan hanya gedung dan jalan raya, museum dan kurikulum; Orde Baru juga menciptakan manusia—kebudayaan manusia Indonesia.
Tak banyak yang benar-benar berniat untuk mengurai tuntas warisan-warisan kultural Orde Baru yang masih berurat kuat di masa ini. Padahal, warisan-warisan inilah alasan birokrasi kita carut-marut—lantaran dikelola PNS “dinosaurus” yang terbiasa di-emong Orde Baru tanpa punya indikator kerja yang jelas. Korupsi, masalah yang kini jadi perhatian nasional, jarang dibicarakan dalam konteks historiko-kultural, untuk melihat dorongan-dorongan kultural apa yang memungkinkan itu terjadi.
Barangkali, benang kusut Reformasi bisa mulai kita urai dengan cara ini.
*
Simposium “Cara Orde Baru Menciptaken Manusia Indonesianya” adalah sebuah kerjasama antara IndoPROGRESS dan ORDE BARU OK. VIDEO. Melalui empat panel, simposium ini berusaha menggali realitas kebudayaan Orde Baru serta menarik relevansinya pada kebudayaan kita hari ini. Panel-panel ini disusun untuk mengetengahkan bagaimana Orde Baru membuat “cetakan-cetakan” serta subjek manusia seperti apa yang muncul (atau, diharapkan muncul) melalui “cetakan” tersebut. Hal ini akan dibicarakan misalnya, dalam panel IV, “Televisi Orde Baru dan Keluarga Indonesianya”, yang membahas bagaimana Negara berusaha menancapkan gambaran tentang keluarga kepada publik melalui monopoli penyiaran TVRI.
Tentu sebuah sistem, betapa pun kompleks dan komprehensif ia dirancang, memiliki celah-celah yang bisa ditembus dan disiasati—semakin represif sebuah sistem, maka semakin lebar pula celah bagi perlawanan. Pembahasan tentang bagaimana struktur Negara Orde Baru menciptakan manusia juga akan diimbangi oleh narasi tentang resistensi dan perlawanan. Panel I yang bertajuk “Budaya (Musik) Pop: Menjauh dari Media Arus Utama” mengetengahkan bagaimana resistensi itu terjadi di ranah musik era Orde Baru yang sarat dengan intervensi modal.
Panel-panel yang kami suguhkan ini tentunya masih jauh dari cukup untuk memetakan bagaimana subjek Orde Baru dibentuk dan dilawan. Namun setidaknya upaya ini bisa memantik ingatan kita untuk kembali menginterogasi sejarah; untuk kembali mempertanyakan hal-hal yang kita anggap lumrah dan terberi. Dengan kembali menghadirkan ingatan tentang Orde Baru serta meninjau warisan-warisannya di masa kini, barangkali kita bisa mendapat terang jalan Reformasi yang sedang kita tempuh dan memikirkan solusi-solusi yang lebih jitu. []