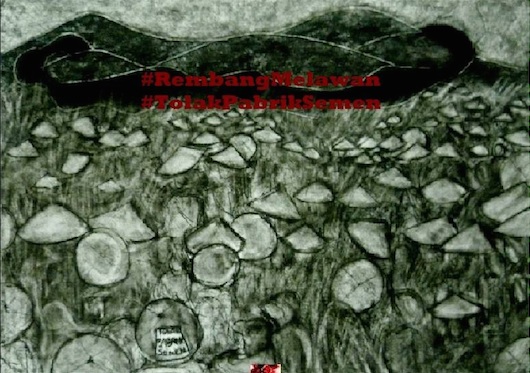PARA Ibu dari Rembang, ditemani mahasiswa, menggeruduk Universitas Gajah Mada (UGM). Mareka marah pada dua akademisi UGM, Eko Haryono dan Heru Hendrayana, dari Kehutanan dan Geografi, yang bersaksi membela pendirian PT. Semen Indonesia di PTUN Semarang. Mereka adalah wakil terdepan warga Rembang yang sudah 282 hari (per 24 Maret) mendirikan tenda di lokasi tempat pendirian pabrik semen milik PT. Semen Indonesia.
Tak banyak perlawanan warga terhadap perampasan hak agraria, yang dalam banyak kasus jauh dari kota apalagi kilat cahaya media, sanggup bertahan. Sekalipun harapan mungkin samar, ancaman mati dan represi tak henti, yang dengar dan beritakan tak sebanyak dan seriuh akrobat para elit yang sedang ‘bertengkar’, tetapi keteguhan adalah prinsip yang tak melulu seukuran kalah menang.
Penggerudukan para Ibu ke kampus UGM ini sekilas tidak sekeren pendudukan mahasiswa mahasiswi LSE-Inggris, York-Kanada, Toronto-Kanada, dan Universitas Amsterdam-Belanda baru-baru ini atas kampus mereka. Namun pesan yang disampaikan bertujuan sama: kampus harus membebaskan, jangan jadi stempel komersialisasi, jangan akademisi jadi tukang stempel korporasi. Pesan ini penting di era ketika pendidikan tinggi hari ini makin jauh dari kepentingan publik dan digantikan oleh kepentingan privat, bertujuan bukan untuk pembangunan sosial-kemanusiaan dan mengasah pikiran kritis, melainkan untuk profit perusahaan.
Kampus dan akademisi adalah think tank yang turut mendesain arah dan kebijakan publik. Mereka tidak pernah netral dan bebas kepentingan. Kajian akademik atas pembuatan dan perubahan UU selalu melibatkan peran perguruan tinggi. Rencana revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003 misalnya, menggandeng lima Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian komprehensif. Di masa makin kencangnya neoliberalisasi ekonomi, kampus adalah alat legitimasi pasar yang paling mumpuni. Kasus pencemaran Teluk Buyat (2004) oleh PT. Newmont Minahasa Raya, dirasionalisasi dan dibela oleh akademisi dari Universitas Sam Ratulangi, namun oleh akademisi dari kampus yang sama pula PT. NMR digugat karena pencemarannya. Karena perguruan tinggi adalah arena perebutan legitimasi teoritik atas kebijakan tertentu, maka pertempuran di arena ini harus dimenangkan untuk kepentingan publik.
Komersialisasi kampus memang belum panjang usianya di negeri ini. UU PT adalah tonggaknya dan Universitas Gajah Mada, juga Universitas Indonesia, adalah laboratorium percobaannya. Sejak itu mayoritas mahasiswa lebih senang Starbucks masuk kampus dengan manis, sehingga wajar kaget ketika Ibu-Ibu Rembang menggeruduk gedung rektorat. Tak sedikit mahasiswa-mahasiswi itu berencana meraih gelar Master di Universitas-universitas terkemuka di luar negeri tanpa mengerti mengapa angka pengangguran lulusan perguruan tinggi justru semakin tinggi dan lilitan hutang mereka semakin banyak.
Pendidikan tinggi yang dikomersialisasi saat ini, jika tidak banyak diinterupsi, hanya akan memproduksi akademisi tukang stempel korporasi, dan mahasiswa-mahasiswi yang sibuk mengurusi karirnya sendiri. Padahal peran akademisi dan mahasiswa mesti tidak seremeh itu. Mereka bisa mendorong demokratisasi kampus, berpihak pada kepentingan publik, serta membangun solidaritas sesama.
Toh lagi pula, tak semua akademisi akan diterima jadi stempel korporasi, karena untuk membela kepentingannya, korporasi hanya membutuhkan segelintir akademisi, yakni yang paling pandai dan logis. Sama halnya mahasiswa-mahasiswi yang sebagian besar tidak akan memiliki karir cemerlang karena terbatasnya lapangan kerja, tingginya persaingan, terbatasnya kesempatan dan rendahnya tingkat upah.
Dari sinilah titik berangkat membenahi pendidikan tinggi kita. Sebelum membuat semakin banyak mahasiswa dan civitas akademika berani beraksi, pertama-tama mereka perlu dibuat menjadi tahu, untuk kemudian ragu atas fondasi mereka berdiri. Dan jalan untuk membuat mereka berkepentingan hingga turun aksi hanyalah dengan mengusik ketenangan akademik dengan berbagai cara yang paling santun hingga paling berani. Hanya untuk satu tujuan: membuat kampus berpihak pada mayoritas yang sengsara, pada korban, pada hak azasi manusia, pada kebebasan dan kreativitas berpikir, pada akses yang semakin terjangkau dan pengetahuan yang semakin membebaskan.
Indonesia memiliki pengalaman unik, karena peran sejarah mahasiswa lebih kesohor saat menggugat kekuasaan politik nasional ketimbang kuasa kapital dan politik di kampus. Di tengah semakin sedikitnya partisipasi politik mahasiswa, maka dibutuhkan strategi pembangunan gerakan yang lebih tenang dan membumi tanpa kehilangan radikalisasi untuk tujuan menggugat kekuasaan. Serangan vertikal yang efektif membutuhkan tekanan horizontal yang luas dan beragam. Artinya, bagaimana membuat lebih banyak elemen akademik berkepentingan dan ikut resah pada situasi pendidikan dan lingkungan sosial politik masyarakat. Tidak cukup dari satu sisi dan isu, harus dari banyak sisi yang berkaitan langsung dengan dunia akademik: kurikulum, kebebasan akademik, tujuan pendidikan, tingkat kesejahteraan pekerja akademik, biaya dan fasilitas pendidikan, hingga perlindungan perempuan dari kekerasan di lingkungan akademik. Pokoknya, semua hal yang mengusik elitisme kampus.
Membantu Ibu-ibu Rembang dan mendukung perjuangan darurat agraria adalah satu hal. Mengonsolidasikan kalangan akademisi kampus yang kritis terhadap komersialisasi adalah hal lain. Keduanya berhubungan dan keduanya menguntungkan. Ini bukan pekerjaan mudah. Tak sedikit yang sudah menyerah karena sulitnya melawan birokrasi internal kampus dan konservatifnya iklim akademik, namun jalan lain yang lebih mudah pun tidak ada. Gugatan harus dilancarkan dari dalam dan luar kampus.
Tak mesti punya keberanian yang sama dengan para Ibu, apalagi ketika memang belum berani. Saat ini sudah lebih banyak yang ikut mendukung tagar #RembangMelawan, membuat aksi solidaritas di beberapa tempat dengan baragam cara, menandatangani petisi, menulis kisah-kisahnya, atau sekadar mengaguminya di dalam hati. Memang belum cukup, sama sekali belum cukup untuk melawan kuasa kapital atas pikiran dan masa depan kita semua. Ini bukan kerja heroisme sehari dua hari. Duaratus delapan puluh dua hari mewakili puluhan tahun negeri ini ada dibawah kuasa kapital atas semua aspek kehidupan. Darurat agraria adalah seruan yang penting disambut, diikuti oleh darurat pendidikan dan ketenagakerjaan.
Ribuan mil di negeri bekas penjajah, Belanda, para mahasiswa dan pengajar sedang mendiskusikan masa depan pendidikan tinggi mereka di Maagdenhuis yang mereka duduki. Kita memang masih jauh dari taraf itu. Tetapi kerja sudah dimulai. Jaringan kampus semakin meluas, kerja diskusi dan kerja aksi antar elemen akademik yang berani maju melawan komersialisasi, dengan gerakan sosial yang sedang bertarung mempertahankan ruang hidup dari kuasa kapital di sektor agraria, pendidikan dan ketenagakerjaan menanti.***