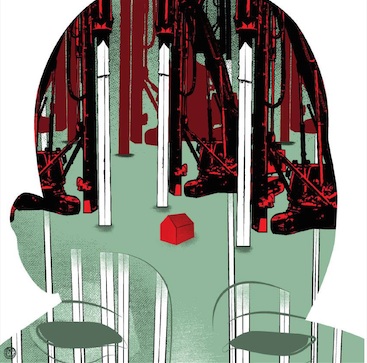Tanggapan Untuk Musa Maliki
DALAM tulisan terdahulu di IndoPROGRESS[1], saya telah menjelaskan tentang bagaimana mengarahkan kritik terhadap dunia pendidikan di Indonesia, secara lebih khusus yang menyasar level pendidikan tinggi. Melalui artikel pendek tersebut, saya menggarisbawahi poin-poin penting terkait kritik dunia pendidikan di Indonesia.
Pertama, yaitu kemestian dan kemendesakan untuk mengintegrasikan kritik terhadap dunia pendidikan secara radikal dan holistik. Artinya, pendidikan tidak bisa dipandang sebagai bagian terpisah dari intervensi-intervensi ekonomi-politik. Diskursus tentang kebuntuan filosofis dan degradasi kualitas pendidikan di Indonesia, sudah mesti dilakukan dengan melihat bahwa pendidikan adalah medan pertarungan ideologis terhadap akses sumber daya sosial. Mereka yang melakukan kritik terhadap kondisi pendidikan di Indonesia hari ini sudah mesti keluar dari perangkap-perangkap borjuisasi yang kental dengan heroisme dan ilutif.
Tawaran saya yang kedua adalah bagaimana integrasi secara radikal dan holistik di atas dapat membuka ruang untuk merumuskan kembali filosofi pendidikan di Indonesia. Menemukan kembali pegangan-pegangan filsafat dan ilmiah yang menjadi arah kemudi pendidikan kita. Mempertanyakan dan menemukan kembali pendidikan sebagai ruang memanusiakan manusia yang kemudian tidak alienatif dan terintegrasi dengan aktifitas harian (daily life activities). Sebuah temuan yang tidak mungkin datang dari hasil plagiat atas kritik-kritik sejenis yang lahir dan tumbuh dalam kenyataan historis di tempat lain. Melainkan ia mesti merupakan sesuatu yang berakar dan merupakan hasil dialektika kritis di Indonesia sendiri.
Artikel Musa Maliki[2] yang didedikasikan mendebat argumentasi-argumentasi Regit Ageng Sulistyo[3], justru dalam pandangan saya tidak mendorong diskursus ini ke arah tersebut. Sebaliknya kritik Maliki justru kembali mempertontonkan kebuntuan-kebuntuan yang berkarakter apologetik. Alih-alih menawarkan cara pandang baru, narasi Maliki justru kembali tenggelam dalam pengingkaran-pengingkaran filosofis yang tidak bisa dibiarkan.
Tulisan ini bermaksud untuk membongkar sifat-sifat fatalis dan pembiaran-pembiaran yang cenderung mengadvokasikan kepasrahan total terhadap rekuperasi pendidikan sebagai alat produksi tenaga kerja semata.
Kecacatan Argumentasi Maliki
Maliki memulai artikelnya dengan sebuah kecerobohan. Ia menuduh Regit melakukan interpretasi terhadap hasil riset orang lain dengan metode yang tidak dijelaskan (paragraf 1, kalimat 4). Padahal jika ia membaca secara teliti, Regit adalah salah satu orang yang ikut melakukan riset tersebut bersama dengan Dodi Mantra dan Reza Istefi (paragraf 4, kalimat 1).
Kecerobohan tersebut dilanjutkan dengan fatalisme Maliki yang pertama dalam tulisan tersebut. Yaitu keinginan untuk ‘menyelamatkan negara’ dari ‘tuduhan’ Regit. Ia menganggap bahwa menyebut Indonesia sebagai negara kapitalisme adalah sesuatu yang tidak berdasar dan terlalu terburu-buru. Maliki berbalik menuduh Regit tidak menyediakan basis analisis yang mendasari kesimpulan tersebut. Sementara di saat yang bersamaan ia juga tidak menawarkan penjelasan filosofis terkait pembelaannya. Dalam artikelnya, Maliki hanya mengemukakan argumentasi-argumentasi moralis yang sama sekali tidak empirik.
Fatalisme tersebut dimulai dengan kegagalan interpretasi Maliki terhadap tulisan Regit. Ia tidak memahami latar belakang tulisan tersebut yang berupaya mendebat kekeliruan Yoga Prayoga.[4]
Regit bertujuan untuk mendorong kritik artifisial Prayoga yang hanya sekedar menyalahkan kehadiran lembaga bimbingan belajar sebagai penyebab degradasi kualitas intelektual mahasiswa. Lebih lanjut, Regit menolak argumentasi eskapik Prayoga yang berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan seorang Anies Baswedan. Argumentasi Regit, menyerahkan logika pendidikan sepenuhnya ke tangan aparatus negara, akan membuat pendidikan kemudian diarahkan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Penolakan Regit tersebut didasarkan pada tesis bahwa institusi pendidikan yang dikendalikan negara jelas akan berorientasi pada pemenuhan spot kosong lapangan pekerjaan. Sementara mereka yang sedang duduk di bangku belajar akan didesain sebagai subyek-subyek pekerja melalui pendisiplinan.
Pendapat dalam artikel Regit sebenarnya bukanlah sesuatu yang orisinil. Kita dapat dengan mudah menemukan benang merah ketika membaca kembali tulisan fenomenal Nicos Poulantzas yang berjudul Political Power and Social Classes. Dalam tulisan tersebut, Poulantzas mengajukan klaim bahwa setiap moda produksi yang hari ini berkembang dan menggerakkan negara, dapat dimengerti secara teoritik dalam pengertiannya mengenai interrelasi antara level ekonomi, politik dan ideologi.[5]
Contohnya dapat dilihat dari struktur ekonomi dalam moda produksi kapitalisme yang tersusun atas relasi sosial produksi dan kekuatan-kekuatan produktif seperti yang telah dijelaskan dalam The Capital.[6] Lebih lanjut Poulantzas mendefinisikan bahwa, struktur-struktur politik dalam sebuah moda produksi dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang terinstitusionalisasi di dalam negara. Sementara struktur ideologi dalam sebuah moda produksi mengacu kepada dua hal: pertama, merujuk kepada kesadaran subjektif dari setiap aktor sosial secara individual; sementara yang kedua mengacu kepada sistem nilai kolektif yang yang eksis di dalam sebuah kelompok masyarakat.[7]
Suksesnya sebuah moda produksi sangat bergantung dari integrasi ketiga struktur tersebut di setiap level. Namun Poulantzas menggarisbawahi bahwa fungsi-fungsi normal dari struktur-struktur tersebut dapat terganggu oleh kontradiksi yang dihasilkan melalui “praktik-praktik kelas”. Hal tersebut merupakan efek dari “dislokasi struktural yang diakibatkan oleh perjuangan kelas” dan “pembangunan yang tidak merata di struktur-struktur tersebut yang juga berpengaruh terhadap level-level formasi sosial.[8]
Negara, dalam moda produksi kapitalisme dipandang Poulantzas umumnya berfungsi untuk melayani “the regulating factor of its global equilibrium as a system”.[9] Untuk menjaga keseimbangan tersebut, Poulantzas menemukan bawah ada tiga jenis “praktik-praktik kelas” yang membutuhkan pengaturan dan kontrol negara.
Pertama, Poulantzas berpendapat bahwa level ekonomi dalam moda produksi kapitalistik relatif otonom terhadap level politik dan ideologi. Karena relativitas otonom tersebut keseimbangan tidak hanya dipengaruhi oleh level ekonomi, tapi diharuskan untuk menjadi tanggung jawab negara dalam mengurusnya. Itu mengapa negara kemudian, dalam pandangan Poulantzas, berfungsi secara umum untuk mengatur faktor kohesi antar level dalam formasi sosial.
Kedua, dipengaruhi oleh kenyataan soal kenyataan-kenyataan politik, Poulantzas menemukan bahwa dalam moda produksi kapitalistik negara memberi perhatian utama pada level ekonomi, proses kerja dan produktivitas tenaga kerja.
Ketiga, negara dalam analisis Poulantzas bertugas untuk meredam konflik politik kelas dalam rangka mempertahankan kepemimpinan politik. Terganggunya kepemimpinan politik akan berimbas kepada level-level struktur lain dalam masyarakat. Itu mengapa negara kemudian memberlakukan hukuman, mencegah revolusi dan memata-matai segala potensi gangguan politik tersebut.
Tiga hal di atas kemudian diimplementasikan melalui tiga fungsi sub-sistem dalam negara; aparatus judisial, arapatus ideologi dan aparatus administratif politik. Dalam masyarakat kapitalistik, aparatus judisial tampak melalui perangkat aturan dan perundang-undangan. Melalui institusi-institusi dan aparat hukum. Sementara aparatus administratif politik dapat dilihat pada birokrasi, sistem kepartaian dan kepolisian. Sedangkan aparatus ideologi menampakkan wajahnya melalui institusi agama dan institusi pendidikan.
Inilah awal muasal tesis Regit tersebut, yang gagal dipahami oleh Maliki.
Fatalisme kedua dalam artikel Maliki adalah pendapat bahwa pemerintah Indonesia memiliki tujuan mulia untuk menyejahterahkan mayoritas warga negaranya. Tesis prematur Maliki tentang ‘niat mulia’ pemerintah tersebut jelas sekali berkarakter apologetik dan eskapik. Padahal jauh di masal lalu, Marx dan Engels dalam Communist Manifesto secara skeptis telah menganggap pemerintah sebagai “a committee for managing the common affairs of the whole bourgeouisie”.[10] Meyakini pemerintah terdiri dari mereka yang memiliki niat baik, tidak hanya merupakan argumentasi moralis namun juga sama sekali tidak ilmiah. Sebab hal tersebut dilandaskan pada kesengajaan untuk mengacuhkan basis historis-antropologis bagaimana negara itu dibentuk, dijalankan dan berkembang seiring perkembangan corak produksi masyarakat.[11]
Dengan melompat-lompat dari Hardt dan Negri, Aretxaga, Abrams serta Foucault (paragraf 5 dan 6), Maliki berkelit sembari melakukan atraksi spekulatif dengan mengajukan tesis bahwa negara adalah sesuatu yang ‘tidak jelas secara fakta, tetapi praktek dan diskursifnya terasa nyata’ (paragraf 7, kalimat 2).
Meminjam narasi-narasi besar tersebut, Maliki melanjutkan kerancuannya dengan memberikan dua definisi terpisah tentang pendidikan di ‘dua corak negara’. Pertama adalah ‘pendidikan sebagai alat untuk akumulasi kapital negara’ di bawah rezim kapitalistik (paragraf 8, kalimat 3). Kedua soal ‘pendidikan sebagai alat politik untuk mencapai kesadaran tinggi terhadap politik’ dalam negara yang bercorak demokrasi (paragraf 8, kalimat 4).
Dari situ kita dapat menemukan bagaimana kerancuan cara berpikir Maliki. Tampak jelas bahwa ia belum paham dan belum sanggup untuk mendefinisikan secara jelas apa itu negara dan apa itu kapitalisme. Ketidakpahaman dan ketidaksanggupan tersebut akhirnya bermuara pada klaim-klaim serampangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam tulisannya.
Maliki dalam artikelnya jelas meracau soal definisinya tentang negara. Ia mengartikan asal-usul negara dan sistem negara secara sembrono dan seenak perut tanpa didukung landasan teoritik. Hal ini membuat tulisan tersebut justru terjebak dalam argumentasi asal-asalan yang bertendensi untuk mencegah upaya-upaya mendefinisikan negara dan melihat aktivitas negara secara kritis. Artikel Maliki tidak hanya mewartakan kebingungan, tapi juga bertujuan memukul mundur progress diskusi tentang dunia pendidikan di Indonesia, terlebih khusus yang menyasar level perguruan tinggi.
Poin kebingungan berikut yang tampak jelas dalam artikel Maliki adalah ketidaktahuannya yang mendasar mengenai apa itu kapitalisme. Hal tersebut berujung pada keputusan Maliki untuk membaptis kapitalisme sebagai corak pemerintahan yang dapat dihadapkan vis a vis dengan demokrasi (paragraf 8).
Pendapat salah kaprah tersebut dengan mudah digunakan untuk pembenaran apologetik bahwa negara demokrasi tidak memiliki sifat-sifat kapitalistik. Atau dapat ditarik lebih jauh dengan mengajukan tesis serupa bahwa pemerintahan yang demokratis secara otomatis tidak memiliki corak ekonomi yang akumulatif, eksploitatif dan diskriminatif yang merupakan ciri-ciri kapitalisme. Benarkah demikian?
Lalu bagaimana Maliki menggunakan argumentasinya tersebut untuk menjelaskan eksploitasi buruh murah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia? Bagaimana memandang negara demokrasi seperti Indonesia justru terus mengedepankan pendekatan opresif yang diskriminatif terhadap bangsa Papua? Atau benarkah tidak ada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dalam sistem ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia?
Tentu saja kesimpulan yang didasarkan pada kebingungan filosofis, ketidakpahaman akan aspek historis serta kekacauan penggunaan terma-terma, secara logis akan bermuara pada logika yang banal dan sesat. Itu mengapa argumen-argumen Maliki tidak dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Alih-alih menawarkan kelanjutan diskusi secara ilmiah, tulisan Maliki justru lebih tampak sebagai labirin. Kebingungan-kebingungan mendasar yang dibangun Maliki di atas ketiadaan upaya serius untuk menstrukturkan kritiknya terhadap tulisan Regit, karena terlanjur ditenggelamkan oleh lautan niat mulianya yang ingin mengatakan bahwa tidak ada manufakturisasi pendidikan di Indonesia.
Maliki secara semena-mena menjustifikasi argumen-argumen banalnya ke dalam khotbah-khotbah yang sama sekali tidak masuk akal. Di tengah kekacauan struktur berpikir tersebut, ia menuliskan harapannya tentang kemunculan ‘intelektual sejati yang tidak hanya akan sekedar menjadi pelengkap pembangunan’ (paragraf 11, kalimat 3) lengkap dengan argumentasi-argumentasi apologetik di bagian tengah tulisan menjadi menutup dini tulisan tersebut (paragraf 12 dan paragraf 13).
Gambar diambil dari http://occupydesign.org.uk
Kapitalisme Kognitif dan Dunia Pendidikan
Maliki sempat mengutip Foucault dalam tulisannya (paragraf 6). Anehnya ia kelihatan jelas tidak memahami bahwa Foucault juga adalah orang yang sama yang berbicara mengenai hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang kemudian digunakan sebagai alat kontrol melalui institusi-institusi sosial, termasuk di dalamnya institusi pendidikan.[12]
Buktinya adalah ketidakpahaman Maliki terkait tesis-tesis Regit mengenai tiga undang-undang pendidikan[13] yang bertujuan mendisiplinkan pelajar menjadi subjek pekerja. Proses pendisiplinan tersebut mensyaratkan transformasi institusi pendidikan yang awalnya merupakan ruang belajar kritis menjadi pabrik yang mencetak tenaga kerja siap pakai di pasar kerja.
Transformasi tersebut dapat dilacak ke belakang pasca terjadinya krisis sosial di era Fordisme, yang memaksa kapitalisme mengaransemen kembali pembagian kerja (division of labour) dan modalitas pelipatgandaan kapital (the modality of capital volarisation). Pada tahapan ini, terjadi peningkatan peran pengetahuan dan pekerja kognitif (cognitive labour) yang dianggap menjadi faktor utama dalam perubahan sifat dasar dan relasi kapital dan tenaga kerja di periode yang kemudian disebut sebagai pasca-Fordisme. Penataan kembali tersebut membuat terjadi signifikansi atas peran pengetahuan yang dikenal sebagai knowledge-based economy yang kemudian didefinisikan sebagai kapitalisme kognitif, yang juga mengubah bentuk-bentuk properti dan juga pengertian tenaga kerja (labour).[14]
Dalam kapitalisme kognitif, kerja adalah aktivitas yang menyatukan sekaligus pikiran dan tindakan yang secara erat bertaut dan melekat namun sama sekali berbeda dari segala jenis aktivitas repetitif dan alamiah yang dilakukan oleh makhluk hidup lainnya.[15]
Penjelasan mengenai fase baru kapitalisme ini juga sebenarnya telah dijelaskan oleh Hardt dan Negri dalam Empire dan Multitude, yang ironisnya dikutip Maliki (paragraf 5). Penjelasan Hardt dan Negri tersebut merupakan pendalaman atas konsepsi Marx mengenai “kecerdasan umum” (general intellect) dalam tulisannya yang berjudul Fragment on Machine, yang belum sempat dipublikasikan ketika ia masih hidup.[16] Sederhananya, kecerdasan umum tersebut mengacu kepada seperangkat pengetahuan, kompetensi, kemampuan linguistik dan cara untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berada di dalam masyarakat, namun semakin tersedia dalam takar yang berbeda-beda banyak kurangnya di “setiap orang”.
Argumen pendukung lain datang dari Virno[17] dan Larazzato,[18] yang menguatkan tesis Hardt dan Negri dengan menjelaskan bahwa dalam fase pasca-Fordisme, kapitalisme telah bergerak melampaui kenyataan-kenyataan fisikal sebatas penghisapan atas nilai lebih kerja. Bila di masa Fordisme, hubungan buruh dan bos sering hanya dilihat selama delapan jam kerja, maka kapitalisme kognitif telah lebih jauh bergerak maju dengan mengacu pada keahlian pekerja dan kemampuan konseptual dan membuat keputusan. Yang mana hal-hal tersebut melampaui batasan jam kerja formal karena mencakup seluruh waktu hidup seorang pekerja.
Artinya kemampuan bicara, kemampuan membangun relasi pertemanan atau jaringan, kemampuan responsif terhadap situasi yang tidak terduga yang dimiliki seseorang, telah dikonstruksikan sepanjang masa hidupnya dan menjadi lebih dari sekedar tenaga kerja dalam pengertian tradisional.
Tesis Marx mengenai “kecerdasan umum” ini semakin menemukan kebenarannya semenjak internet ditemukan.
Hari ini kemampuan kognitif tersebut oleh Boutang sebagai ‘modal intelektual’. Modal ini bukan merupakan jenis modal yang habis setiap hari sehingga perlu diisi ulang. Ia berbeda dengan tenaga fisik pekerja yang memerlukan waktu istirahat untuk memulihkan tenaga. Sebaliknya, modal jenis ini terus meningkat secara kualitas dan kuantitas seiring frekuensi pemakaiannya. Itu menjelaskan mengapa ketrampilan yang digunakan terus menerus justru berkembang lebih baik dan seiring dengan itu juga mengakumulasi nilai jualnya.[19]
Boutang lebih lanjut menjelaskan bahwa ‘modal intelektual’ ini adalah sesuatu yang bersifat sosial dan bukan sesuatu yang privat. Modal jenis ini hanya dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi dan kooperasi. Modal hanya dapat terwujud dan berkembang dalam sebuah jaring yang luas.[20]
Di sinilah kemudian kita dapat menemukan letak institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam kapitalisme pasca-Fordisme. Yaitu sebagai tempat dimana ‘modal intelektual’ dilatih secara terus menerus agar meningkat secara kualitas, namun tanpa perlu mengeluarkan biaya. Sebaliknya, justru menarik bayaran dari mereka yang ingin mendapatkan akses terbatas demi mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan nilai ‘modal intelektual’ ketika menghadapi pasar kerja. Semakin spesifik dan semakin terbatas jenis pelatihan tersebut, maka semakin mahal biaya yang harus ditebus oleh mereka yang berkeinginan mengasah ‘modal intelektual’nya. Bentuk komodifikasi pengetahuan, yang kemudian dapat menjelaskan mengapa sebuah program reguler jauh lebih murah dari program sejenis yang diberi label ‘internasional’.
Institusi pendidikan di periode pasca-Fordisme ini kemudian mereplikasi sifat dan karakteristik pabrik. Namun perbedaan mendasarnya terletak pada siapa yang dieksploitasi di dalamnya. Di pabrik-pabrik tradisional, penghisapan dilakukan terhadap buruh dengan tetap membayar (meski) sedikit agar para buruh tersebut dapat beristirahat dengan tenang dan dapat dipastikan ia kembali bekerja. Sementara dalam institusi pendidikan, penghisapan dilakukan terhadap pelajar (unpaid labour) yang ironisnya mesti membayar untuk merasakan segala bentuk penyiksaan, hukuman, pendisiplinan dan pemenjaraan.[21]
Kenyataan-kenyataan ini yang berupaya disangkal oleh Maliki dalam artikelnya dengan berkelit bahwa ‘hakikat pendidikan adalah untuk menopang institusi’ (paragraf 9), sehingga kemudian mengadvokasikan ‘agar tidak terburu-buru menjustifikasi apakah pendidikan kita market oriented atau knowledge oriented’ (paragraf 12, kalimat 2). Maliki kemudian melengkapi semua itu dengan argumen apologetik bahwa ‘terletak pada masing-masing orang untuk menentukan apakah dia akan melawan sistem, atau melakukan rekayasa atau mengambil celah masuk di antara keduanya’ (paragraf 12, kalimat 3). Yang disimpulkan Maliki melalui pembacaan imbisil atas tulisan Regit.
Menolak Apologetisme
Meski berupaya mengelak, namun jelas bahwa tujuan artikel Maliki bukanlah untuk melakukan konfirmasi atas argumen-argumen yang diajukan oleh Regit. Sebaliknya, tulisan tersebut adalah sebuah pembelaan membabi buta atas serangan Regit terhadap dunia pendidikan Indonesia yang khususnya menyasar UU No. 2. Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian direvisi menjadi UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan sebenarnya, artikel tersebut ditujukan untuk menepis kritik yang dialamatkan kepada Jokowi-JK dengan alasan bahwa rezim tersebut belum layak dikritik karena umurnya yang masih muda (paragraf 13, 17 & 19).
Kritik Regit dianggap tidak ‘melalui pertimbangan multi aspek dan kompleksitas permasalahan’. Maliki yang mencoba tampak bijaksana, mengatakan bahwa ‘melayangkan kritik adalah sebuah kewajiban’ namun di saat yang bersamaan menjustifikasi bahwa kritik Regit ‘dilakukan secara serampangan dan dengan pemikiran yang tertutup’ (paragraf 19).
Maliki menutup mata pada kenyataan bahwa Jokowi-JK menandai kepemimpinannya dengan skandal dalam dunia pendidikan. Bahwa rezim yang masih bau kencur ini pula yang di awal pemerintahannya telah membagi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan menjadi dua unit kementerian dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan kepada publik.[22] Jokowi yang dibela Maliki, telah dengan tegas menggariskan bahwa urusan pendidikan di Indonesia tidak terletak pada masalah filosofis, tapi semata-mata pada persoalan efektivitas manajemen. Sehingga degradasi kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat diselesaikan dengan menunjuk dua orang menteri, dan bukan perumusan basis filosofi pendidikan.
Dalam artikelnya, Maliki tidak henti-hentinya memperlihatkan watak apologetismenya dengan cara terus-menerus mempertontonkan comotan-comotan bombastik untuk menutupi ketidakmampuannya berargumentasi (paragraf 14, 15, 16). Ia lalu menutup artikel tersebut dengan sebuah perayaan atas narasi Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai hal yang lebih mendesak untuk disikapi ketimbang secara jernih memeriksa kembali bangunan filosofis pendidikan kita (paragraf 17, 18 & 20). Seruan rentan yang sebenarnya lemah semenjak Maliki lebih mengedapankan respon-respon glamor yang moralis dengan berharap bahwa pendidikan yang dikompetisikan akan tetap mampu ‘melahirkan figur-figur inspiratif yang dapat melakukan perubahan’ (paragraf 20, kalimat akhir).
Eskapisme dalam tulisan Maliki didasarkan pada ketidaktahuan yang dibungkus sebagai nasehat-nasehat kebijaksanaan yang justru menyesatkan. Ironisnya, artikel tersebut sama sekali tidak lucu. Saya pada akhirnya hanya memiliki dua pilihan rasional yang tersedia saat membaca tulisan Maliki. Pertama, membiarkannya berlalu seperti sikap kafilah menghadapi gonggongan anjing. Kedua, mengambil sikap tegas untuk memeriksa dengan pembedahan serius untuk mencegah repetisi argumen-argumen sejenis di masa mendatang.
Tanggapan terhadap Maliki juga tidak lahir dalam semangat idealistik. Setidak-tidaknya, berupaya membersihkan kritik-kritik terhadap dunia pendidikan hari ini dari anasir-anasir moralis dan spekulatif. Intinya, menolak semangat apologetik dalam diskursus seperti ini karena bertendensi menerima dan kemudian merasionalisasi begitu saja segala sesuatu tanpa pemeriksaan yang teliti. Menolak kepasrahan-kepasrahan filosofis yang fatalis dalam dunia pendidikan, karena inilah penentu masa depan sebuah komunitas. Setidaknya, jika pendidikan kemudian adalah zona merdeka terakhir yang tersisa, kita tidak menyerahkannya dengan percuma. Tapi dengan perlawanan yang sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya.***
Penulis adalah peneliti lepas dan mahasiswa pasca-sarjana di Mahasarakham University, Thailand.
————
[1] Andre Barahamin, Kegalauan Kritik Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia (Harian IndoProgress, Januari 2015) accessed Februari 3, 2015 https://indoprogress.com/2015/01/kegalauan-kritik-terhadap-pendidikan-tinggi-di-indonesia/
[2] Musa Maliki, Tentang Negara dan Kritik Prematur Atas Manufakturisasi Pendidikan (Harian IndoProgress, Februari 2015) accessed Februari 3, 2015 https://indoprogress.com/2015/02/tentang-negara-dan-kritik-prematur-atas-manufakturisasi-pendidikan/
[3] Regit Ageng Sulistyo, Kemerosotan Intelektual Mahasiswa, Praktek Pendisiplinan Manusia dan Produksi Pengetahuan Secara Otonom (Harian IndoProgress, Januari 2015) accessed Februari 3, 2015 https://indoprogress.com/2015/01/kemerosotan-intelektual-mahasiswa-praktek-pendisiplinan-manusia-dan-produksi-pengetahuan-secara-otonom/
[4] Yoga Prayoga, Mahasiswa, Lembaga Bimbel dan Menteri Pendidikan (Harian IndoProgress, Januari 2015) accessed Februari 3, 2015 https://indoprogress.com/2015/01/mahasiswa-lembaga-bimbel-dan-menteri-pendidikan/
[5] Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes. (London: New Left Book & Sheed & Ward, 1973)
[6] Karl Marx, The Capital, trans. Ben Fowkes (London: Penguin, 1992)
[7] Poulantzas, Political Power, 42.
[8] Poulantzas, Political Power, 41.
[9] Poulantzas, Political Power, 45.
[10] Karl Marx dan Friedrich Engels, The Communist Manifesto (London: Pluto Press, 2008)
[11] Sebagai perkenalan, Maliki bisa dimulai dengan membaca F. Engels, “The Origins of Family, Private Property and the State”.
[12] Mungkin Maliki perlu membaca tulisan Foucault yang berjudul “Discipline and Punish: The Birth of Prisons”
[13] Pasal 36 Ayat (3) Huruf f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 16 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[14] Yaan Moulier Boutang, Cognitive Capitalism: New Great Transformation, (Amsterdam: Multitudes, 2007)
[15] Carlo Vercellone, “The Hypothesis of Cognitive Capitalism” dalam Towards a Cosmopolitan Marxism, Historical Materialism Annual Conference, (London: Birkbeck College and SOAS, 2007)
[16] Catatan-catatan Marx tersebut kemudian dikumpulkan (termasuk Fragment on Machine) dan diterbitkan dengan judul Grundrisse.
[17] Lebih lanjut baca Paolo Virno, “On General Intellect” di http://libcom.org/library/on-general-intellect-paulo-virno
[18] Lebih lanjut baca Mauricio Lazzarato, “On General Intellect” di http://libcom.org/library/general-intellect-common-sense
[19] Boutang, Cognitive
[20] Boutang, Cognitive
[21] Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of Prisons, trans. Allan Sheridan (London: Penguin Books, 1995)
[22] Tarli Nugroho & Andre Barahamin, “Regarding Research and Our Higher Education” dalam ASEAN Classroom Program (ACP) Faculty of Education, Maharakham University, Thailand (Maharakham: Mahasarakham University, September 2014)