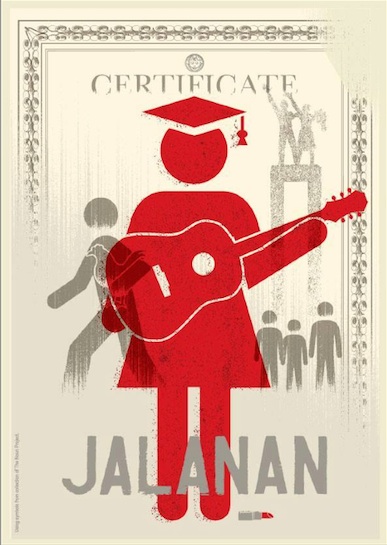Pertama perkenalkan nama saya Dimas Fauzi Hidayat. Saya mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya, suatu universitas yang terlalu “ribet” di dalam kampus itu sendiri karena adanya persaingan antar golongan memperebutkan kekuasaan itu sendiri. Dari segi akademis juga teori-teori tentang ideologi Marxis dan nilai-nilainya masih sangat dibungkam dan tidak bisa dikembangkan. Kami seperti tidak diajari berpikir kritis dan para pemikir beraliran “kiri” hanya bisa bergerak di bawah tanah. Namun, dengan kehadiran IndoPROGRESS ini semakin membuka pemikiran kita tentang Marxis[me] (sic!) itu sendiri dan mulai dirasakan dengan manfaatnya seperti tujuan IndoPROGRESS yang dikemukakan Mas Windu saat diskusi pemikiran kritis di Malang beberapa minggu yang lalu. Dan di kampus sendiri, kita tidak bisa mengakses web IndoPROGRESS karena menurut Dikti termasuk web terlarang. Ya stigma 1965 tidak bisa hilang seperti asap.
Seperti yang kita tahu saat ini memang Indonesia sedang panas-panasnya dengan politik karena sudah dekat dengan pemilihan presiden baru yang akan berlangsung Juli nanti. Dengan begitu artikel yang dikemukakan oleh IndoPROGRESS juga mengangkat isu tersebut. Terlebih lagi maneuver-manuver para politisi yang lebih memilih ke kubu pelanggar HAM dan gaya wakil dari moncong putih yang sangat kerakyatan seperti mengangkat arti dari Marxis itu sendiri dari eksploitasi. Memang untuk celah mengritik wakil dari moncong putih tersebut nyaris tidak ada dan si pelanggar HAM seperti terbuka lebar pintu kritikan dari segi Marxist. Tapi dari sini terlihat seperti adanya ketidaknetralan dari pihak IndoPROGRESS itu sendiri, di mana artikel yang diterbitkan seperti sebuah propaganda untuk mendukung si moncong putih tersebut. Saya melihatnya menjadi suatu alat propaganda bagi para pembaca IndoPROGRESS untuk mendukung salah satu partai karena bahasan yang diangkat berisi tentang si pelanggar HAM tersebut. Buat saya itu menjadi sangat bias. Maksud email ini saya berikan adalah saya berharap IndoPROGRESS menjadi suatu web dengan pemikiran netral. Dalam artian kritis terhadap kedua belah pihak. Karena mengingat IndoPROGRESS sendiri pernah ‘menyindir’ Jokowi saat menjabat gubernur DKI (saya lupa artikel yang mana tapi ada). Memang kemanusiaan harus diperjuangkan namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dengan si moncong putih. Saya berharap IndoPROGRESS lebih netral dan menjadi lebih baik lagi. Sekian tulisan ini saya sampaikan. Jika ada salah kata atau menyinggung pihak IndoPROGRESS mohon maaf karena saya juga baru mengerti sedikit tentang Marxisme. Terima kasih, semoga IndoPROGRESS berhasil memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan karena jutaan manusia pernah dibinasakan oleh saudaranya sendiri karena perang ideologi di negara yang, katanya, menganut nilai demokrasi, kebebasan berpikir dan berpendapat.
Dimas Fauzi Hidayat
————
BUNG Dimas yang baik,
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas surat yang Bung kirimkan kepada kami. Sudah tentu kami merasa senang atas surat Bung, dan karenanya kami ingin berdiskusi dengan Bung melalui surat balasan ini.
Pertama-tama, kita perlu membaca realitas yang ada dengan lebih mendalam dan kritis. Fenomena kampus yang ‘ribet’ dengan berbagai macam pertarungan antar kekuatan politik untuk menduduki posisi-posisi penting di kelembagaan mahasiswa, kelembagaan fakultas, atau pun birokrasi kampus, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ini ada bahkan di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Secara umum, ada kekuatan politik yang berlibat dalam pertarungan tersebut, salah satunya untuk mengambil keuntungan finansial dari posisi yang seseorang dapatkan. Tetapi ada juga kekuatan politik yang masuk di dalam pertarungan tersebut untuk tujuan-tujuan politik tertentu, dengan memanfaatkan dana-dana yang disediakan universitas. Pengalaman sejarah gerakan mahasiswa di periode Orde Baru justru masuk ke dalam pertarungan tersebut agar bisa mendapatkan ruang untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan kritis. Dalam hal ini, rata-rata aktivis gerakan mahasiswa periode 1990an adalah juga aktivis penerbitan pers mahasiswa. Persoalannya sekarang adalah realitas itu hidup di seputar kita, dan seharusnya kita tidak perlu gerah karenanya. Justru kita seharusnya melihat realitas pertarungan politik di kampus sebagai peluang dan tantangan untuk memahami apa sebenarnya ‘politik’ dalam gagasan-gagasan mereka yang bertarung, dan kemudian bagaimana Bung memosisikan diri dengan ‘politik’ tadi. Dari sana, kita bisa belajar mempelajari realitas secara kontekstual dan dialogis.
Hal kedua adalah perihal Marxisme di kampus-kampus di Indonesia. Memang hampir semua kampus di Indonesia tidak bisa menerima kehadiran Marxisme sebagai salah satu alat analisis di dalam ilmu-ilmu sosial. Lebih-lebih, kehadiran Marxisme sampai dengan saat ini, masih selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 1965 dan Partai Komunis Indonesia. Sebagai akibatnya, di dalam hampir seluruh kajian ilmu sosial di Indonesia, begitu minim terdapat analisis kelas-kelas sosial masyarakat Indonesia. Sementara realitas sosial yang berjalan di luar kampus hampir selalu mencerminkan kontradiksi kelas-kelas sosial tersebut. Fenomena ketidakadilan, fenomena penggusuran tanah, fenomena uang kuliah yang mahal, fenomena harga bahan pangan yang tinggi sementara kaum tani semakin miskin, fenomena upah pekerja yang rendah, fenomena ketidakmampuan orang-orang Indonesia bersaing di tingkat internasional, semuanya adalah fenomena kelas-kelas sosial yang bergerak secara historis.
Problematikanya kemudian, oleh karena Marxisme dilarang diajarkan di kampus-kampus, maka yang berkembang adalah ilmu-ilmu sosial yang tidak mampu menganalisa masyarakat secara tajam. Sebagai contoh, fenomena kemiskinan dilihat sebagai akibat dari berkembangnya pemahaman bahwa orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang malas bekerja. Tetapi tidak pernah diupayakan untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana seseorang bisa menjadi miskin dari tinjauan historis. Katakanlah, kita lahir dari keluarga miskin, lalu dari SD sampai SMA kita bersekolah di sekolah negeri yang murah meriah. Begitu masuk universitas, orang tua kita tak sanggup membayar biaya kuliah, dan kita harus mencari sekolah tinggi yang berbiaya murah dengan kualitas yang rendah juga. Sehingga, karena kita lahir dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang pas-pasan maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan pekerjaan selayak lulusan universitas negeri yang berbiaya mahal. Nah, di situlah titik Marxisme dimulai. Bagaimana mungkin manusia-manusia yang secara biologis memiliki struktur tubuh dan pikiran yang sama ketika dilahirkan tetapi secara historis kemudian berkembang menjadi yang miskin, bau kecut, bahasanya kacau, dan kurang santun di satu sisi; lalu di sisi yang lain ada manusia yang tampangnya keren, klimis, penuh wewangian, sepatunya dari sirip ikan hiu, sabuk celananya dari kulit ular, sampai kacamatanya berbalut platina. Seperti ungkapan Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, ‘tanggal kelahiranku sama dengan Ratu Juliana, tetapi nasib membawa kami ke jalan yang berbeda. Ia ratu penguasa tanah jajahan, aku rakyat yang dijajah olehnya.’ Celakanya, sejarah kemudian berbicara bahwa manusia-manusia bersepatu sirip ikan hiu itu menjadi kaya raya oleh karena kerja jutaan orang yang bekerja keras 12 jam per hari dengan menu sarapan nasi, garam, dan gorengan setiap hari. Pada titik itulah, upaya memahami masyarakat secara mendalam dalam Marxisme tidak pernah menjadi netral.
Ilmu-ilmu sosial tersebutlah yang selalu mengajarkan supaya Bung bersikap netral, bijak, berjarak terhadap realitas. Sementara seperti apa realitasnya juga kurang dipahami dengan baik. Pun terhadap realitas yang berlaku saat ini, realitas Pilpres 2014. IndoPROGRESS melalui kajiannya akhirnya mengerti siapa Jenderal Prabowo dan siapa Jokowi. Jendral Prabowo kondang sebagai pelanggar HAM bukan karena dirinya mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi fakta-fakta keterlibatannya di dalam berbagai aktivitas pelanggaraan HAM sudah tersedia dalam dokumen-dokumen Komnas HAM dan dokumen-dokumen HAM Pelapor Khusus PBB serta Komisi Tinggi HAM PBB sejak tahun 2000. Kehadirannya dalam kancah politik bukan baru-baru ini saja ditentang, tetapi sudah sejak lama dipersoalkan oleh para aktivis pembela HAM. Tahun 2009, ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai cawapres Megawati, banyak protes bermunculan dari kalangan aktivis tersebut. Tahun 2004-2009 ada sekian banyak upaya yang dilakukan oleh para aktivis HAM agar ada mekanisme-mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berujung pada upaya pembentukan UU Pengadilan HAM dan UU tentang Komisi Rekonsiliasi Nasional. Ada sekian banyak film dokumenter yang dibuat oleh para aktivis HAM tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu maupun pada periode sesudahnya. Termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk merawat keluarga korban pelanggaran HAM 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Timor Leste, Penculikan, Kerusuhan ‘98, Semanggi, Trisakti, Papua, Aceh, dsb. Mengapa? Karena mereka saksi-saksi dari adanya tindakan-tindakan kekerasan oleh negara.
Jadi pengetahuan kami tentang siapa Prabowo, dan siapa jendral-jendral jagal haus darah adalah hasil dari pembacaan dokumen-dokumen resmi tersebut dan dialog dengan korban-korban kekerasan negara, bukan dari cerita-cerita konspirasi yang kondang di media sosial twitter. Sehingga, bukan karena Prabowo menjadi capres maka ia disebut sebagai pelanggar HAM atau Jagal. Sejarah berulang kali mencatat bahwa Prabowo kerap menyelesaikan persoalan-persoalan konflik sosial dengan cara-cara yang melanggar HAM, salah satunya dengan memanfaatkan statusnya sebagai aparat negara. Sehingga, oleh karena pengetahuan kami tentang penderitaan keluarga korban, oleh karena pengetahuan kami tentang operasi-operasi militer yang menjagal rakyat Indonesia, kami memang harus tidak netral. Kami memang harus berpihak pada keluarga korban, dan karenanya kami menentang kehadiran Prabowo sebagai calon presiden.
Kami tidak ingin negeri ini dipimpin oleh seorang jagal, itu sama arti dengan menghadirkan Soeharto dalam bentuk yang lain. Karenanya, kenetralan kami adalah keberpihakan kami pada upaya membongkar kebenaran yang dipalsukan, mengungkap kebenaran-kebenaran melalui metodologi analitik dan fenomenologi yang ditujukan untuk mencerdaskan kesadaran politik rakyat. Kami tahu ada banyak jenderal haus darah di kubu Jokowi, dan mereka pun akan kami desak untuk mau mengakui kekuatan rakyat. Kami akan menuntut mereka untuk bersedia diadili, ikut membantu proses pengadilan dengan menguak bukti-bukti lain serta bersedia meminta maaf di hadapan korban kekerasan negara. Bagi kami, keadilan yang utama dan terutama adalah bagi korban kekerasan negara dan tidak ada dalam benak kami keadilan buat jenderal haus darah. Jadi jangan pernah mengira bahwa kami sedang mendapat kenikmatan di ranjang para jenderal haus darah.
Hal ketiga, persoalan dukungan terhadap Jokowi bukan berarti dukungan terhadap PDIP. Tolong dibedakan. Kami mendukung Jokowi karena dia pemimpin yang mengupayakan proses demokrasi yang dialogis. Dan karenanya dia perlu dikawal, diingatkan, dan diberikan masukan agar idenya tentang demokrasi dialogis menjadi pola politik nasional. Sementara PDIP ya PDIP. Dia adalah partai orde baru yang memiliki cabang sampai ke tingkat anak ranting, dengan spektrum politik yang dinamis dan tidak seragam. Mendukung Jokowi tidak sama dengan menyembah dan mencium kasut Ibu Mega, tetapi mencari celah ruang politik di tingkat akar rumput untuk mempropagandakan gagasan-gagasan kreatif yang mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat demi pemberdayaan dan pembebasan masyarakat dari kapitalisme, sampai ke tulang sumsum kesadaran politik rakyat. Kami tahu benar ada banyak oknum PDIP yang korup dan kerap berlaku seperti preman yang gemar kekerasan. Tetapi kami tahu juga bahwa banyak dari kalangan PDIP di tingkat akar rumput yang masih memiliki semangat untuk memperjuangkan ide-ide Soekarno yang berpihak pada kaum yang dipinggirkan. Keragaman seperti itu yang tidak kami temukan di partai politik yang lain yang sibuk menanamkan kesadaran kepada rakyat bahwa berpolitik itu sama dengan belanja suara dan loyalitas (baca: wani piro).
Bung Dimas, sebaiknya Marxisme yang Bung pelajari tak perlu lagi diributkan di kampus karena sudah jelas kampus Brawijaya masih alergi terhadap Marxisme. Coba saja Bung mulai beraktivitas bersama kaum yang dipinggirkan. Mulai dengan berdialog dengan mereka, membantu mereka memecahkan persoalan-persoalannya. Nanti dari sana Bung akan dapat sendiri gagasan Marxisme yang orisinal. Sebab Marxisme yang mengeram di dalam kampus itu Marxisme barber shop (tukang cukur). Ia dianggap sebagai Marxisme ketika ia sesuai dengan kehendak para birokrat kampus, yang sok netral tetapi berpihak kalau ada proyek dari Pemerintah Daerah setempat ataupun dari para pengusaha terkemuka. Kenetralan mereka yang palsu dan jorok moralnya yang harus digugat, bukan keberpihakan kami yang kemudian dipertanyakan. Karenanya Bung, tugas utama Marxisme itu adalah mengorganisasikan pikiran, bukan menghafal kutipan-kutipan moral Marx ataupun seruan-seruan Lenin dari ufuk awal abad ke 20 yang belum kenal laman-laman media sosial Facebook dan Twitter.
Terakhir Bung Dimas, ketika Sartre menulis tentang intelektual dia tidak pernah membayangkan intelektual itu sebatas pengamat, atau wasit pertandingan olahraga. Bagi Sartre, intelektual adalah teknisi data yang memiliki kemampuan menafsirkan hubungan antar data untuk melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Sudah tentu itu pengetahuan yang membebaskan rakyat. Sementara, pengamat politik masa kini sekedar menafsir-nafsir sampai dia tidak tahu apakah dia sedang bersolek ataukah sedang mengajarkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan jadi pengamat, Bung Dimas, tetapi jadilah aktivis politik progresif.***
Anom Astika, Anggota dewan redaksi IndoPROGRESS