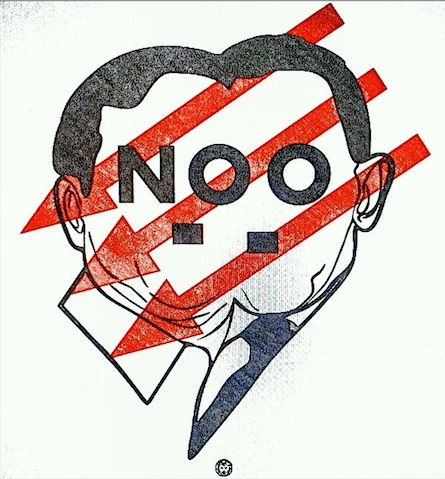ADA seribu satu argumen menolak fasisme. Namun apa yang sering mencuat adalah argumen berbasis pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka argumen ini, fasisme keliru karena melanggar HAM (antara lain, diskriminasi rasial, penghapusan kebebasan berpendapat dan berserikat). Masalahnya, penolakan atas fasisme dengan argumen berbasis HAM mengandaikan sejumlah prasyarat yang belum tentu terpenuhi dalam kerangka berpikir rakyat banyak. Buat aktivis LSM dan gerakan sosial, argumen berbasis HAM tentu masuk akal dan dapat menjadi alasan yang memadai untuk menolak fasisme. Namun, belum tentu demikian bagi rakyat banyak yang tidak mendalami diskursus HAM dan lebih berpikir dalam kerangka kesejahteraan ekonomi yang diresapi semangat kebangsaan. Buat rakyat yang berpikir seperti itu, politik fasis bisa saja ditatap dengan segenap aura emansipatoris. Betapa tidak? Fasisme selalu menjanjikan pengamanan ‘kepentingan nasional’ yang segera diidentifikasi oleh rakyat sebagai ‘kepentingan rakyat.’ Karena itu, kritik atas fasisme yang hendak menghasilkan gema di benak rakyat banyak mesti tak berhenti di wilayah argumen HAM, tetapi menyelam ke dalam tataran argumen ekonomi-politik—ke dalam misteri ekonomi-politik dari ‘kepentingan nasional.’
Apabila fasisme adalah sejenis ‘populisme’ itu adalah karena ‘kepentingan bangsa’ disamakan dengan ‘kepentingan rakyat.’ Inilah yang membuat Nazi mengklaim dirinya sebagai kelompok ‘nasionalis’ yang juga ‘sosialis,’ yang bekerja demi kepentingan rakyat tertindas. Ciri ‘sosialis’ dari Nationalsozialist mengemuka, antara lain, dalam 25 program Partai Nazi di tahun 1920. Setidaknya ada tiga butir dari 25 program tersebut yang memiliki warna ‘sosialis:’
o Butir 13: “Kami menuntut nasionalisasi seluruh industri”
o Butir 17: “Kami menuntut reforma agraria yang sesuai dengan kepentingan kami, pembuatan hukum bagi pengambil-alihan tanah demi kepentingan publik, penghapusan segala pajak tanah dan pelarangan segala bentuk spekulasi finansial atas tanah”
o Butir 21: “Negara akan berusaha meningkatkan kesehatan nasional dengan melindungi ibu dan anak, dengan melarang pekerja-anak.”
Namun apabila diperhatikan dengan lebih jeli, tiga butir tersebut hanya memiliki warna ‘sosialis’ sejauh sebagai slogan. Rumusannya memang sosialis, tetapi substansinya jauh dari itu.
Apa yang dinyatakan sebagai nasionalisasi, nyatanya mengemuka sebagai ‘Aryanisasi,’ yakni pengambilalihan kapital dan infrastruktur industri dari tangan para pemilik non-Arya ke tangan bangsa Arya. Dan apa yang terjadi di balik Aryanisasi ini bukanlah pengambilalihan industri ke dalam tangan rakyat Jerman-Arya, melainkan ke tangan segelintir pengusaha pendukung partai Nazi. Franz Leopold Neumann, salah satu dari sedikit ekonom Mazhab Frankfurt, menulis dalam karya klasiknya, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, bahwa sebagian perusahan yang dinasionalisasi nyatanya diambil-alih oleh perusahaan milik Hermann Goering, petinggi Nazi dan jenderal Angkatan Udara Jerman yang juga menjabat Menteri Ekonomi merangkap Menteri Kehutanan.1 (Neumann 2009: 297). Nampak bahwa ‘kepentingan bangsa’ sebenarnya hanya eufemisme dari ‘kepentingan kapitalis-birokrat’, jauh dari urusan ‘kepentingan rakyat’.
Demikian pula dengan butir 17. Sekilas program itu mirip dengan pasal 33 ayat 3 UUD ’45 kita yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun substansi dari butir 17 program partai Nazi adalah formasi elit tani dan tuan tanah yang mudah dikendalikan partai.2 Harga komoditas tani yang dihasilkan para tuan tanah itu diproteksi dengan pemilikan tanah sampai ratusan hektar. Petani-petani kecil terpaksa menjual tanahnya dan bekerja pada elit tani tersebut. Hal yang serupa terjadi juga dengan butir 21 tentang pekerja-anak. Melalui operasi Heu-Aktion di tahun 1944, 40-50.000 anak kecil berusia 10-14 tahun dari Polandia hingga Ukraina diculik untuk dididik ke dalam budaya Jerman-Arya (disebut juga sebagai ‘Jermanisasi’) dan sebagian dijebloskan ke berbagai kamp kerja-paksa. Mekanisme kerja-paksa inilah yang merupakan sumber keuntungan perusahaan-perusahaan besar Jerman pada masa itu, seperti Deutsche Bank dan Siemens.
Kesimpulannya, tak ada sosialisme dalam Nasional-Sosialisme. Dari segi ekonomi-politik, yang terjadi hanyalah perampokan dan penghisapan berkedok ‘kepentingan bangsa.’ Perekonomian Nazi bahkan merugikan rakyat Jerman sendiri. Tampilan bahwa seolah terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan volume perdagangan, sebenarnya hanyalah efek temporer yang tercipta dari, dan senantiasa mensyaratkan, ekonomi perang, perampasan dan kerja-paksa. Apabila fasisme seakan tampak anti-kapitalis, itu bukan karena fasisme adalah sejenis sosialisme, melainkan karena fasisme menghendaki akumulasi kapital tanpa mekanisme kompetisi pasar. Di sinilah juga terletak esensi dari program ‘nasionalisasi’ à la fasis: pengambil-alihan sarana produksi bukan demi kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan kapitalis-birokrat atau kapitalis-militer yang diidentifikasi sebagai ‘kepentingan nasional.’ Inilah yang dipercayai Nazi sebagai program ‘nasionalisasi spritual’ yang dikontraskan dengan ‘nasionalisasi materialistik’ kaum komunis.3 Retorika anti-asing yang jamak terdengar di kalangan fasis di berbagai belahan bumi adalah variasi dari logika ‘nasionalisasi spiritual’ tersebut.
 Apa yang terjadi di Jerman bisa juga terjadi di Indonesia. Dalam orasi yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh di Gelora Bung Karno, yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Prabowo juga memainkan retorika anti-asing.[4 ‘Masalah inti adalah bahwa sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik, ini adalah keliru, tidak sesuai dengan UUD ‘45. Dan karena keliru; kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kita sekarang hanya menjadi pesuruhnya bangsa lain,’ ujar Prabowo disambut sorak sorai puluhan ribu buruh. Ia juga mencitrakan-dirinya sebagai sosok yang anti terhadap sistem outsourcing dan membela kepentingan buruh. ‘Saya lima tahun yang lalu mungkin satu-satunya pimpinan politik yang tanda tangan kontrak di depan serikat pekerja untuk menentang outsourcing di Republik Indonesia,’ demikian aku Prabowo. Di panggung GBK, ia juga menyepakati sepuluh tuntutan buruh yang diajukan KSPI. ‘Saya didatangi oleh pemimpin-pemimpin kalian. Mereka minta saya terima tuntutan-tuntutan buruh. Dan saya baca, dan saya lihat: tuntutan-tuntutan ini adalah sah! Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia! Tuntutan ini adalah janji UUD ’45!’ pekik Prabowo diiringi dengan gemuruh dan seruan-seruan: ‘Hidup Prabowo!’
Apa yang terjadi di Jerman bisa juga terjadi di Indonesia. Dalam orasi yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh di Gelora Bung Karno, yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Prabowo juga memainkan retorika anti-asing.[4 ‘Masalah inti adalah bahwa sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik, ini adalah keliru, tidak sesuai dengan UUD ‘45. Dan karena keliru; kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kita sekarang hanya menjadi pesuruhnya bangsa lain,’ ujar Prabowo disambut sorak sorai puluhan ribu buruh. Ia juga mencitrakan-dirinya sebagai sosok yang anti terhadap sistem outsourcing dan membela kepentingan buruh. ‘Saya lima tahun yang lalu mungkin satu-satunya pimpinan politik yang tanda tangan kontrak di depan serikat pekerja untuk menentang outsourcing di Republik Indonesia,’ demikian aku Prabowo. Di panggung GBK, ia juga menyepakati sepuluh tuntutan buruh yang diajukan KSPI. ‘Saya didatangi oleh pemimpin-pemimpin kalian. Mereka minta saya terima tuntutan-tuntutan buruh. Dan saya baca, dan saya lihat: tuntutan-tuntutan ini adalah sah! Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia! Tuntutan ini adalah janji UUD ’45!’ pekik Prabowo diiringi dengan gemuruh dan seruan-seruan: ‘Hidup Prabowo!’
Dalam suasana yang penuh persetujuan terhadap dirinya itu, Prabowo ikut terbawa suasana dan meneruskan retorika populisnya dengan bercerita tentang betapa busuk dan pembohongnya para elit politik Indonesia saat ini dan partai-partai politiknya. Ia sampai memberikan usul: ‘Mungkin partai-partai politik harus membubarkan-diri semua, habis itu kalian saja ambil-alih itu semua.’ Usulan pembubaran partai-partai politik memang punya gema fasistik, sekalipun usulan itu dilontarkan dengan retorika palsu tentang pemerintahan buruh. Mengapa itu adalah retorika palsu? Sebab kedatangan Prabowo di GBK adalah untuk mengikat apa yang ia sebut ‘komitmen politik’ antara KSPI dan Partai Gerindra. Artinya, usulan agar buruh mengambil-alih seluruh kekuasaan partai-partai politik dapat dibaca sebagai usulan pengambil-alihan kekuasaan partai-partai politik ke tangan Gerindra atas nama ‘kepentingan buruh.’
Problem utama dari semangat kebijakan Prabowo, sebagaimana problem utama kebijakan fasis, adalah eklektisisme atau sikap mencampur-campurkan segala pendekatan sejauh terdengar membela ‘kepentingan nasional.’ Berikut ada tiga contoh inkonsistensi gagasan yang muncul dari kecenderungan eklektik tersebut:
o Dalam orasinya di GBK, Prabowo mencitrakan diri sebagai penentang outsourcing garda-depan. Padahal, perusahaannya yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan (bisnis satpam), PT. Gardatama Nusantara, adalah salah satu pemain dalam bisnis outsourcing keamanan yang profil perusahannya menyebut dengan eksplisit: memiliki “keahlian dalam hubungan dengan buruh” (maksudnya spesialis union-busting?).5
o Dalam orasinya di GBK, Prabowo berteriak-teriak anti-neokapitalisme dan anti-neoliberalisme. Padahal, dalam pertemuan dengan Hatta Radjasa, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap MP3EI6 yang topangan argumennya terletak pada debottlenecking alias deregulasi dan privatisasi—kunci utama dari segala varian kebijakan neoliberal.
o Dalam orasinya di GBK, Prabowo berseru menyatakan kesahihan sepuluh tuntutan buruh dan kesesuaiannya dengan ‘janji UUD ‘45’. Padahal, hingga acara berakhir, Prabowo sama sekali tidak meneken persetujuan programatik atas tuntutan tersebut.7 Bahkan Ketum Gerindra, Suhardi, menyatakan di depan wartawan bahwa ‘ada tim yang memilih mana yang benar-benar bisa dilakukan.’8 Artinya, sepuluh tuntutan tersebut tidak betul-betul sahih di mata Prabowo.
Bagaimana mungkin anti-outsourcing jika perusahaannya sendiri bergerak di bidang outsourcing? Bagaimana mungkin antikapitalisme dan menyepakati sepuluh tuntutan buruh jika pada saat yang bersamaan mendukung deregulasi dan privatisasi? Eklektisisme semacam ini mencerminkan kekacauan berpikir yang serupa dengan 25 program Partai Nazi: bukan sosialisme, bukan juga sosialisme-pasar, melainkan kapitalisme-negara yang hanya bisa digerakkan oleh senjata dan retorika.
Apa yang ditawarkan Prabowo bukanlah ‘Sosialisme Indonesia,’ melainkan ‘Nasional-Sosialisme Indonesia.’ Inilah yang agaknya berhasil ditangkap oleh salah seorang buruh yang terlibat dalam aksi di GBK kemarin. Prabowo tengah meradang: ‘Tadinya saya selalu dapat sms: “Pak Prabowo, kalau bicara jangan keras-keras, harus sopan, harus santun.” Tapi saya ngga mengerti istilah “santun.” Kalau maling ya maling. Betul?’ Sontak kaum buruh mengiyakannya: ‘Betul!’ ‘Ada ngga istilah yang santun untuk “maling,” istilah santun untuk “rampok?”’ tanya Prabowo. ‘Bangsat itu! Brengsek!’ seru salah seorang buruh yang tertangkap suaranya di video. Prabowo terus melaju kencang: ‘Kalau rampok ya rampok! Kalau maling ya maling! Kalau tukang bohong ya tukang bohong!’ Di titik itu, seorang buruh tak dikenal dan tak terekam wajahnya bertanya: ‘Kalau pembunuh…?’ Saya pikir-pikir, jitu juga pertanyaan seorang buruh anonim itu. Kalau perampok disebut perampok, maling disebut maling, masa pembunuh disebut presiden?***
6 Mei 2014
1 Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, (Chicago: Ivan R. Dee & United States Holocaust Memorial Museum), 2009, h. 297.
2 Ibid.,h. 394-395.
3 Ibid., h. 270.
4 Lih. “Orasi Politik Prabowo Subianto pada Hari Buruh 1 Mei 2014” dalam http://www.youtube.com/watch?v=UH73XrMKxUI
5 http://prabowosubianto.info/aktivitas-bisnis-prabowo-subianto-pt-gardatama-nusantara-jasa-keamanan.html
6 http://www.rmol.co/read/2013/02/04/96901/Prabowo-Subianto-Dukung-Proyek-Hatta-Rajasa,-MP3EI
7 http://www.merdeka.com/politik/usai-orasi-di-gbk-prabowo-lupa-teken-kontrak-politik-buruh.html
8 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/01/183114/2570898/1562/prabowo-tunggangi-may-day-ini-kata-ketum-gerindra