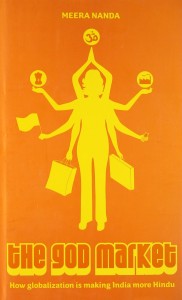 Judul buku: The GOD MARKET How Globalization Is Making India More Hindu
Judul buku: The GOD MARKET How Globalization Is Making India More Hindu
Penulis : Meera Nanda
Penerbit : Monthly Review Press, NY, 2011
Tebal : xxxix+237 h.
TERUS merebaknya aksi-aksi kekerasan (fisik maupun ideologis) bermotif agama di tanah air, telah membuat banyak pihak terperangah. ‘Kok bisa dalam era demokrasi, kekerasan sektarian seperti ini terus berlangsung?’ ‘Mengapa mereka mengatasnamakan Islam dalam tindakan kekerasannya?’ ‘Di tangan mereka, Islam telah berganti rupa menjadi agama yang cupet dan paranoid. Apa-apa yang berbeda langsung dituding kafir, liberal, komunis, sesat, lalu difatwa haram untuk selanjutnya tinggal menunggu hari penjagalan.’
Fakta-fakta telanjang ini pada akhirnya makin menguatkan stereotype atau klaim tentang Islam sebagai agama yang anti HAM, anti kebebasan dan demokrasi, dan lebih khusus lagi anti peradaban. Tapi yang menarik, para pendukung Islam Politik malah tidak keberatan dengan klaim semacam itu. Mereka bahkan yakin bahwa Islam memang berbeda dengan nilai-nilai sekuler yang datang dari Barat. ‘Islam punya nilai sendiri yang lebih agung dan mulia dari nilai-nilai yang lain karena berasal langsung dari Tuhan dan dipraktekkan secara sempurna oleh Rasul Muhammad dan para sahabatnya.’
Sampai di sini, diskusi menjadi sia-sia belaka. Lebih tepatnya, tak ada lagi diskusi kecuali prasangka berdasarkan atas klaim superioritas masing-masing pihak. Pada aras verbal terjadi perang klaim: ‘Islam tidak kompatibel dengan modernitas dan demokrasi’ di satu sisi, dan ‘Sekularisme dan liberalisme diharamkan dalam Islam’ di sisi lain. Tapi, klaim memang tidak menunjukkan sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan. Dalam klaim yang dibutuhkan adalah setuju atau menolak, sekaligus secara politik gagal dalam merespon kebangkitan gerakan politik berbasis sentimen komunal ini.
Gerakan struktural vs kultural?
Di tengah-tengah kebuntuan teori dan praktek politik tersebut, buku Meera Nanda ini sangat relevan untuk dibaca. Dalam bukunya ini, Nanda memotret tentang bangkitnya fundamentalisme dalam agama Hindu, yang mewujud dalam gerakan bernama Hindutva. Menurut Nanda, Hindutva adalah ideologi tentang India sebagai sebuah negara Hindu yang mengeksklusi agama-agama minoritas lainnya, terutama Islam dan Kristen. Karena Hindu adalah agama mayoritas penduduk India, maka sepatutnyalah nilai-nilai Hinduisme menjadi dasar pijak acuan bermasyarakat dan bernegara rakyat India. Dengan kata lain, Hindutva ini adalah sebuah gerakan nasionalis Hindu.
Dengan klaim superioritas kulturalnya di hadapan kultur minoritas lainnya, maka Hindutva, menurut ilmuwan sosial terkemuka India Prabhat Patnaik, memenuhi semua syarat untuk disebut sebagai sebuah gerakan fasis: fasis dalam ideologinya, fasis dalam dukungan kelasnya, fasis dalam metodenya, dan fasis dalam program-programnya.[1] Di samping klaim superioritas kulturalnya, Patnaik juga menunjukkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen radikal dalam Hindutva terhadap fasilitas-fasilitas keagamaan umat Islam maupun Kristen. Misalnya, penghancuran masjid tertua di India, Babri, yang terletak di Ayodhya, Uttar Pradehs pada 6 Desember 1992.
Tetapi sebagai sebuah gerakan nasionalis Hindu, apa yang paling mendasar dari Hindutva, menurut Nanda, bukanlah pertama-tama atau semata-mata pada aspek politik dari gerakan ini, atau sebagai sebuah proyek keagamaan (religious project), tapi melihat Hindutva sebagai sebuah proyek kultural (cultural project). Sebagai sebuah proyek kultural, tujuan utama Hindutva adalah menghindunisasikan budaya publik dan menanamkan pemahaman ‘modern’ tentang Hinduisme (yang sebagian besar berasal dari pemahaman anti-pencerahan abad ke-19, teosofikal, dengan perspektif orientalis) ke dalam pori-pori negara dan masyarakat sipil, tanpa secara langsung mengeliminir undang-undang sekuler demokratik dalam konstitusi India (p.xxi).
Melalui proyek kultural ini, ada dua tujuan yang hendak dicapai: pertama, menjadikan Hindu, yang merupakan agama mayoritas, sebagai basis bagi identitas kolektif dan sumber utama bagi nilai-nilai dan tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh bangsa India; kedua, mengijinkan ruang-ruang kelembagaan dari agama mayoritas ini – jaringan kuil, ashram, sekolah-sekolah keagamaan, universitas, dan gurukuls, yayasan-yayasan rumah sakit, dll – memperoleh bantuan dana dari negara, sambil tetap mempertahakan wataknya sebagai sebuah lembaga agama. Gagasannya adalah menghapuskan garis pembatas antara ruang relijius dan ruang politik atau menyingkirkan pembedaan antara pemujaan terhadap Tuhan dan pemujaan terhadap bangsa (op.cit).
Penekanan Nanda pada proyek kultural dari Hindutva ini penting sekali bagi kita untuk menjadi bahan perbandingan. Sering sekali kita dengar dari kalangan Islam moderat dan liberal, bahwa gerakan Islam di Indonesia harusnya mengambil jalur kultural, dengan merujuk pada dua sosok intelektual Islam terkemuka, Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jalur kultural dianggap tepat karena berlangsung moderat, luwes, dan berwajah ramah di tengah-tengah kenyataan masyarakat yang plural, ketimbang jalur struktural yang ditempuh oleh kalangan Islam politik yang memunculkan wajah Islam yang garang, haus kekuasaan, dan serba tolak. Dalam bahasa Cak Nur, jalur kultural ini adalah penerimaan dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa paksaan atau tanpa adanya undang-undang formal. Inilah Islam yang hanif, Islam yang inklusif. ‘Islam Yes, Partai Islam No,’ slogan Cak Nur. Karena itu, bagi penganjur jalan kultural, terma ini dipakai untuk dilawankan dengan penganut jalan struktural, tanpa menimbang bahwa sebenarnya jalan kultural itulah yang patut diperhatikan lebih serius.
Menjamurnya sekolah-sekolah Islam, bank-bank Islam, busana muslim, musik Islami, novel Islami, film Islami, rumah sakit Islam, rumah makan Islam, bisnis Islami, etika Islam dalam pergaulan (misalnya yang coba diundangkan lewat undang-undang anti-pornografi), sains Islami, pengajian-pengajian terbuka di ruang publik, pers Islam, dsb-dsb, sesungguhnya merupakan wujud konkret dari gerakan kultural ini. Gerakan kultural ini memang tidak mengandalkan otot dan pedang, tidak membuat kaki lawan gemetar dan berkeringat dingin, tapi dengan efek yang lebih luas dan dalam ketimbang gerakan struktural karena ia memanfaatkan atau berdamai dengan badan sekuler agar roh islamisnya bisa beraktivitas secara leluasa.
Aspek menarik lainnya dari kalangan Islam moderat dan liberal, dihadapkan pada proyek kultural ini, adalah mengafirmasinya dengan menggunakan konsep sekuler cultural studies dan teori pasca-modernisme. Proyek kultural tersebut dipandang sebagai perayaan dari kepelbagaian, manifestasi dari local narrative dan the others. Dan, seperti diutarakan Nanda, karena tujuan dari proyek kultural ini adalah hegemonisasi superioritas kultural dari agama mayoritas, maka ketika mayoritas umat Islam diam atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), misalnya, kalangan Islam moderat dan liberal hanya bisa mengeluh.
State-temple-corporate complex
Nanda melihat bahwa kebangkitan fundamentalis Hindu ini sebenarnya juga terjadi pada agama-agama lainnya. Karena itu ia kemudian mengajukan pertanyaan yang menarik: ‘mengapa di era globalisasi, teknologi supercanggih, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sikap keberagamaan yang sektarian dan fundamentalis ini justru ikut tinggi?’ Fakta ini menurut Nanda telah membantah tesis Max Weber bahwa dalam dunia yang semakin modern, tidak ada lagi kebutuhan akan kekuatan magis atau kekuasaan misterius. Semuanya digantikan oleh alat-alat teknik dan perhitungan-perhitungan yang akurat (p. 103). Apa yang terjadi sekarang adalah alat-alat canggih semakin menjadi kebutuhan, perhitungan-perhitungan yang akurat tetap dilakukan dan pada saat yang sama, orang semakin saleh, semakin rajin ke tempat-tempat ibadah, dan tak lupa bersedekah. Lalu, bagaimana menjelaskan fakta ini?
Di sini Nanda mengatakan ada dua pendekatan yang popular digunakan saat ini untuk menjelaskan gejala tersebut: pertama, penjelasan dari sudut kemakmuran ekonomi yang digagas oleh sosiolog terkemuka dari universitas Harvard, AS, Pippa Noris dan Roland Inglehart, yang mengatakan bahwa level kepercayaan di era modern, masyarakat post-industrial berhubungan sangat kuat dengan level ‘ketidakamanan eksistensial/existential insecurity.’ Dari pemetaan relijiusitas dilawankan dengan data pendapatan dari masyarakat di Eropa, Jepang, dan Amerika Utara, keduanya menyimpulkan bahwa ‘kalangan miskin dua kali lebih relijius ketimbang kalangan kaya.’ Di Amerika Serikat, misalnya, sebanyak dua pertiga (66 persen) kalangan miskin mendatangi gereja secara reguler, sementara kalangan kaya hanya sekitar 47 persen.
Tetapi, menurut Nanda, kesimpulan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat India, dimana justru kalangan kaya yang lebih relijius ketimbang kalangan miskin. Mengutip data National Election Survey 2004, ditemukan bahwa 60 persen kalangan Hindu kaya dan kelas menengah melakukan ritual (puja) di kuil setiap harinya. Sementara dari kalangan sangat miskin hanya 34 persen yang melakukan puja setiap harinya, dan kalangan miskin jumlahnya hanya sekitar 42 persen (p.xxix).
Penjelasan lainnya mengemukakan, meningkatnya relijiusitas di era modern ini sebagai sebuah reaksi pertahanan diri terhadap gempuran modernisasi dan westernisasi. Nanda mengutip Pavan Varma, yang mengatakan bahwa agama kini telah menjadi tempat mengasingkan diri (escape from freedom) dari perasaan keterasingan warga kota yang kesepian, yang tercerabut dari kehidupan lamanya, komunitas kecilnya yang hangat dan bersahabat di pedesaan (p.104). Kehidupan perkotaan yang keras dan kompetitif, telah membuat penduduk baru ini menderita stres dan traumatik, dan pada agamalah, pada ritual-ritualnya, dan pada para pendetanyalah, kehidupan lama yang damai dan nyaman bisa mereka reguk kembali. Dan tentu saja kedamaian dan kenyamanan model ini bersifat ilusif, instan, dan memabukkan.
Tetapi Nanda rupanya tidak puas dengan kedua pendekatan ini dalam menjelaskan kemunculan Hindutva. Karena itu, ia mengajukan sebuah pendekatan baru untuk menjelaskan kebangkitan Hindutva, yang disebutnya state-temple-corporate complex. Nanda berargumen bahwa kemunculan Hindutva beriringan dengan kian terintegrasinya ekonomi India dengan ekonomi neoliberal global, yang jejaknya bisa ditelusuri pada reformasi ekonomi di era pemerintahan Indira Gandhi (1977-1991), yang kemudian dipertegas di masa kepemimpinan perdana menteri Rajiv Gandhi pada 1984. Pada tahun 1991, India secara resmi menganut kebijakan neoliberal dalam arah pembangunan ekonominya. Tahun 1991, oleh intelektual neoliberal paling terkemuka, Gurcharan Das, diklaim sebagai ‘tahun kemerdekaan India yang kedua … sebuah revolusi ekonomi …. yang lebih penting ketimbang revolusi politik yang digagas oleh Jawaharlal Nehru pada 1947’ (p. 37).
Segera setelahnya, serangkaian kebijakan khas neoliberalisme, seperti liberalisasi pasar, deregulasi, privatisasi, dan pemotongan anggaran publik segera diberlakukan (Nanda menggunakan istilah 4D: deflate, devalue, denationalize, dan deregulate, p. 23). Intinya adalah memberikan pasar kebebasan untuk bekerja tanpa adanya intervensi dari negara. Lalu, apa hubungannya dengan kebangkitan Hindutva? Di sini, Nanda menemukan fakta bahwa serangkaian kebijakan neoliberal itu telah memungkinkan masuknya para kapitalis dalam dunia pendidikan, dengan menginvestasikan uangnya di sektor ini. Dalam hal ini peran pemerintah, terutama di masa kekuasaan Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang dianggap menyuarakan kepentingan Hindutva, adalah meloloskan undang-undang yang memungkinkan berlangsungnya komersialisasi pendidikan di semua level, khususnya pendidikan tinggi. Privatisasi pendidikan ini, bisa dianggap sebagai kebijakan BJP yang paling penting (p.41). Dampaknya luar biasa. Jika pada 2000 jumlah universitas yang secara utuh dimiliki swasta hanya berjumlah 21, maka pada 2005 jumlahnya melonjak menjadi 70 dan meningkat lagi menjadi 117 pada 2007 (p. 49).
Tetapi apa yang lebih penting, privatisasi pendidikan rupanya tidak hanya menjadi ladang bisnis menggiurkan, melainkan juga menjadi ajang untuk memasarkan Tuhan dan manusia-manusia yang dianggap seperti Tuhan (p.49). Sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang dibangun pihak swasta ini kemudian mulai mengintrodusir nilai-nilai Hindu dalam kurikulum mereka, yang kemudian digabungkan secara serampangan dengan ilmu-ilmu sains terapan dengan alasan bahwa ajaran Hindu sangat sesuai dengan perkembangan sains. Tetapi, ada alasan lain yang lebih mendasar, Hinduisme bukan saja sekadar agama di antara agama-agama lainnya di India, tapi lebih dari itu adalah sebuah etos nasional, atau sebuah cara hidup, dimana semua orang India harus belajar mengapresiasinya dalam kehidupan sehari-harinya (p. 64). Dari sinilah kemudian, Nanda mengantar kita untuk menunjukkan tali-temali hubungan state-corporat-temple complex serta persekutuan tidak suci antara kalangan Hindutva Neoliberal dan Non-Hindutva Neoliberal.
Ia memberikan beberapa contoh kasus yang sangat detil dalam buku ini. Saya ambil satu contoh saja: Pada 2006, pemerintah Orissa memberikan lahan kepada AOL Foundation seluas 200 ha di pinggiran ibukota Bhunbaneswar untuk pendirian Sri Sri University of Art of Living. Universitas ini direncanakan untuk menggabungkan subyek-subyek tradisional seperti Aryuveda, yoga, dan ilmu-ilmu vedic dengan kurikulum reguler ilmu sosial modern dan teknik. Tetapi, persetujuan AOL Foundation dengan pemerintah Orissa ini terbilang kecil dibandingkan dengan persetujuan pemerintah Orissa untuk menyediakan lahan seluas 800 ha bagi pembangunan Vedanta University. Universitas Vedanta ini dibiayai oleh Anil Agarwal, seorang multibilioner pemilik Vedanta Resources, sebuah grup perusahaan baja dan tambang yang berkantor pusat di Inggris, melalui yayasan Anil Agarwal Foundation (p. 132).
Dari kasus Orissa ini tampak bahwa tanpa campur tangan aktif negara dalam meloloskan undang-undang privatisasi pendidikan, penyediaan lahan-lahan maha luas untuk pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang dibiayai oleh korporasi, maka akan sangat sulit bagi kalangan Hindutva untuk berkembang. Adalah keliru mengatakan bahwa dalam era neoliberalisme negara absen dalam tata kelola pasar, yang benar adalah negara memutar haluan ekonomi dan politiknya ke arah pelayanan kepentingan perluasan dan pengamanan tata kelola neoliberal. Struktur ekonomi-politik baru inilah yang menjelaskan, mengapa di era pemerintahan Jawaharlal Nehru yang berorientasi sosialis, gerakan Hindutva ini tidak bisa berkembang. Dan tidaklah heran bahwa sejak tahun 1991, seluruh warisan kebijakan ekonomi-politik Nehruvian dieliminasi seluas-luasnya.
Tetapi Nanda mengingatkan bahwa hubungan antara Hindutva Neoliberal dan Non-Hindutva Neoliberal, tidak selalu berada dalam garis kepentingan yang sama. Misalnya, ketika sayap kanan dari Hindutva mulai melancarkan aksi-aksi kekerasannya terhadap kalangan agama minoritas, maka kalangan Non-Hindutva Neoliberal ini mendesak BJP untuk mengambil posisi liberal klasik tentang hak-hak individu dan kebebasan, pemerintahan yang kecil, serta pemisahan yang tegas antara agama dan negara (p. 56). Ketika usaha mereka di BJP gagal maka banyak dari kalangan ini mulai secara serius berpikir untuk mendirikan kembali partai lama Swatantra Party (p. 58). Dalam kasus ini, maka kedua belah pihak dalam waktu-waktu tertentu saling berhadap-hadapan secara diametral.
Tetapi, karena mereka membagi visi dan ideologi yang sama tentang jalan kapitalisme-neoliberal, maka perbedaan dan pertentangan di antara mereka hanya berlangsung di aras politik kekuasaan, saling berebut pengaruh di kalangan elite bisnis dan kekuasaan, sembari membagi ketakutan yang sama pada munculnya perjuangan berbasis kelas yang menentang orde kapitalisme-neoliberal.
Berbasis kelas menengah
Perbincangan tentang gerakan Islam Politik secara umum di Indonesia, selalu melihat bahwa basis pendukung utama dari gerakan ini adalah dari kelas bawah, rakyat miskin, atau kalangan preman. Secara kasat mata, memang begitu adanya sehingga memunculkan istilah ‘Premanisme Agama dan proponennya disebut Preman Berjubah.’
Tetapi, studi Nanda, dan juga intelektual muda Amerika Serikat yang lagi bersinar terang saat ini, Deepa Kumar dari Rutgers University, menemukan bahwa basis utama pendukung Islam Politik (dalam studi Kumar) maupun Hindutva (dalam studi Nanda) adalah dari kalangan kelas menengah. Mengapa kelas menengah? Nanda menjawab, karena merekalah penerima keuntungan terbesar dari reformasi neoliberal di atas, dan merekalah yang menjadi juru kampanye utama ke seluruh penjuru negeri tentang kebudayaan baru yang konsumtif ini (p. 65).
Tapi, siapa kelas menengah ini? Untuk menghindari kebingungan dan kesalahpahaman, Nanda membagi terminologi kelas menengah ini atas dua: kelas menengah lama atau tradisional dan kelas menengah baru. Yang pertama terdiri dari pemilik toko kecil, pegawai pemerintah, guru, wartawan, dan petani pemilik tanah kecil. Adapun kelas menengah baru ini merujuk pada pekerja-pekerja kerah putih di industri teknologi informasi, perbankan, akuntansi, asuransi, hotel-hotel, dan pariwisata. Bagi Nanda, kelas menengah baru inilah yang paling bersemangat menempatkan India ke dalam peta global sebagai kekuatan dunia yang sedang bangkit (p. 66). Secara politik, kelas menengah ini telah memutuskan ‘No’ untuk politik sosialis dan elemen-elemen rasional dari warisan Nehruvian (p. 67).
Jadi, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka para pendukung utama neoliberal (baik Hindutva Neoliberal maupun Non-Hindutva Neoliberal), datang dari kelas menengah dan atas. Dalam kasus Indonesia, bisa dicek dari kelas mana aktivis inti dari gerakan ini, baik yang Islamis Neoliberal maupun Non-Islamis Neoliberal. Sebagai contoh, dari studi yang dilakukan oleh Vedi R. Hadiz, basis massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) datang dari kalangan terdidik, perkotaan, dan kelas menengah.[2] Lalu, kenapa banyak massa pendukung gerakan FPI, misalnya, datang dari kalangan termiskin, yang sebenarnya adalah korban dari kebijakan neoliberal? Bagaimana menjelaskan ini?
Di sini, Nanda mengatakan bahwa ‘dengan absennya institusi-institusi dan agen-agen yang kuat yang bisa menawarkan alternatif sekuler non-neoliberal, telah menyebabkan ruang publik India modern mengalami persilangan antara simbol-simbol religius dan ritual-ritual kegamaan dari agama mayoritas (p. 65). Tidak adanya kekuatan tandingan tersebut membuat massa, yang sebenarnya menjadi korban kebijakan neoliberal, akhirnya terseret pada propaganda-propaganda keagamaan dari kalangan Hindutva. Dengan mengatakan bahwa India adalah negara Hindu yang modern, kuat, dan kaya, maka mereka melihat agama-agama minoritas sebagai ancaman, nanah busuk dalam tubuhnya, sehingga harus dikeluarkan dan dimusnahkan. Konflik vertikal/struktural dibelokkan menjadi konflik horisontal/kultural.
Konteks Indonesia
Buku Meera Nanda ini sungguh penting (kalau tidak bisa dibilang ‘wajib’) dibaca oleh mereka yang ingin mengerti dan melawan purifikasi, moralisasi, dan agamisasi ruang dan kehidupan publik di Indonesia. Fokus perhatian yang selama ini tertuju pada aspek kekerasan (proyek politik) dari kelompok semacam FPI, perlu ditimbang ulang secara serius. Justru buku ini memberikan perspektif tambahan bahwa proyek kultural untuk menghegemoni ruang dan kebijakan publik justru diberikan perhatian yang lebih serius, karena jalan kultural ini membonceng institusi-institusi sekuler untuk diisi dengan nilai-nilai keagamaan yang puritan dan reaksioner.
Secara akademik dan metodologis, buku ini menawarkan perspektif ekonomi-politik dalam kajian Islam Politik di Indonesia. Sejauh pengetahuan saya, analisa ekopol yang serius tentang keberadaan Islam Politik Indonesia baru dilakukan oleh Hadiz. Absennya analisa kelas dan perjuangan kelas dalam kasus kekerasan berbasis keagamaan ini, telah menyebabkan kita bingung dalam menentukan kawan dan lawan dalam perjuangan membebaskan ruang publik dari kungkungan dan tindasan state-corporate-temple complex.
Namun demikian, dari analisa kelas itu pula kita tahu bahwa pendekatan state-corporate-temple-complex yang disodorkan Nanda ini tidak bisa semena-mena diterapkan dalam pembacaan kita terhadap gerakan Islam Politik di Indonesia. Ada dua kasus yang bisa menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap pendekatan itu. Pertama, dalam kasus PKS di atas, studi Hadiz menunjukkan bahwa kegagalan PKS dalam memperoleh suara yang signifikan pada pemilu 2009, misalnya, karena PKS hidup dalam sistem demokrasi elektoral yang bersifat predatoris, ketidakmampuannya dalam memenangkan dukungan dari kalangan borjuasi besar yang umumnya dikuasai oleh etnis Tionghoa, serta adanya saingan yang kuat dari lembaga-lembaga kegamaan lama seperti NU dan Muhammadiyah dalam aktivitas-aktivitas sosial-kemasyarakatan. Sehingga, walaupun PKS telah mengendurkan tuntutan untuk pembentukan negara Islam dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, serta telah mengadopsi kebijakan-kebijakan neoliberal dalam program ekonominya, mereka tetap saja minoritas secara politik.
Fenomena ini jelas berbeda dengan gerakan Hindutva yang mendapat dukungan dari borjuasi besar India yang secara kultural tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal serupa juga terjadi dalam kasus Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki, yang walaupun Islamis tetapi mampu meraih dukungan dari borjuasi besar Turki yang juga secara kultural tidak berbeda dengan mereka.
Kedua, dengan penerapan sistem desentralisasi maka kita temukan adanya beberapa daerah yang menerapkan perda-perda syariah. Artinya, benar bahwa secara nasional kelompok Islam Politik gagal dalam menguasai pemerintahan dan merealisasikan agenda-agenda politiknya, namun di tingkat lokal mereka terbukti sukses mewujudkan agenda-agendanya tersebut. Bagaimana menjelaskan ini dari perspektif Nanda?
Dengan mengambil studi kasus Aceh, saya ingin mengatakan bahwa penerapan perda syariah di provinsi itu lebih bermakna sebagai mekanisme kontrol dan represi terhadap potensi perlawanan sosial dari rakyat Aceh sendiri terhadap pemerintah lokal yang menerapkan kebijakan neoliberal. Sekadar mengingatkan, Aceh adalah sebuah wilayah yang hubungannya dengan pemerintah pusat, lebih sering ditandai oleh konflik sosial dan politik ketimbang kerjasama dan perdamaian. Studi Graham K. Brown[3] menunjukkan bahwa akar dari hubungan yang konfliktual itu adalah pada lebarnya kesenjangan ekonomi akibat proses pembangunan yang diterapkan Orde Baru. Aceh, sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia, ternyata juga adalah salah satu provinsi termiskin. Kenyataan ini jelas tak bisa diterima oleh penduduk lokal, yang kemudian terekspresikan dalam tuntutan untuk merdeka dari apa yang mereka sebut sebagai ‘kolonialisme Jawa.’
Kita semua tahu, rezim Orde Baru kemudian merespon tuntutan merdeka tersebut dengan sebuah operasi militer yang berdarah-darah. Sementara akar masalah, berupa kesenjangan penguasaan akses ekonomi, sama sekali tidak dibereskan. Akibatnya, rezim Orba gagal memadamkan perjuangan menuntut kemerdekaan tersebut, sampai kemudian Soeharto jatuh pada 1998 dan jalan damai penyelesaian konflik menjadi opsi yang paling realistis.
Setelah proses perdamaian Helsinki, Aceh kemudian memperoleh status otonomi khusus. Para kombatan turun gunung, rakyat bersuka, proses politik mulai digelar, lalu hasil pun dicapai. Namun, walaupun menggunakan hukum Syariah, mekanisme dan desain pemerintahan sepenuhnya berbentuk demokrasi elektoral. Pertanyaan kemudian, apakah imajinasi politik untuk bisa mengelola kekayaan alam secara adil dan mensejahterahkan kehidupan penduduk lokal terpenuhi? Sebagai provinsi yang kaya sumberdaya alam, apakah pemerintahan baru ini mampu mensejahterahkan rakyatnya, seperti tuntutan mereka ketika melawan rezim Orba? Kenyataannya dengan kandungan SDA yang begitu tinggi, [4] ‘Kemiskinan di Aceh berada pada urutan ketujuh di Indonesia atau peringkat satu untuk wilayah Sumatera’ ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh berada pada kisaran 19,48 persen. Angka ini berada jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 12,36 persen.[5]
Menariknya pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, minimnya lapangan kerja, dan rendahnya etos kerja. Kesimpulan ini menarik karena pemerintah lokal saat ini persis mengulang kesimpulan Seoharto dan para intelektualnya, ketika memulai proses pembangunan di Aceh saat itu, dan terbukti keliru. Lalu kenapa pemerintah Aceh pasca Helsinki ini kembali mengulang-ulang mantra-mantra modernisasi pembangunan a la rezim Orde Baru?
Di sini kita mesti menempatkan motif utama dibalik pengkambinghitaman sikap budaya rakyat Aceh itu untuk membenarkan beroperasinya kebijakan neoliberal. Ini tampak dari berbagai pernyataan pejabat lokal bahwa untuk menghela laju pembangunan ekonomi Aceh tidak bisa diserahkan pada dinamika lokal, melainkan harus meminta bantuan korporasi keuangan internasional (IFC) yang merupakan bagian dari Bank Dunia.
‘Aceh saat ini butuh investor asing untuk membawa modal, teknologi tepat guna, untuk membantu meningkatkan nilai produk-produk kami. Kepada mereka yang melakukan investasi minimum Rp. 5 milyar, kita siap untuk membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak lokal,’ demikian janji Said Yulizal, direktur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), kabupaten Aceh Besar.
Jika dilihat lebih detil lagi, maka sebenarnya SDA Aceh itu telah dikapling-kapling baik oleh perusahaan-perusahaan multinasional, seperti ExxonMobil yang menguasai PT Arun LNG, maupun oleh para pengusaha nasional seperti Arifin Panigoro, Surya Paloh, Tommy Winata, Siti Hartati Murdaya, Aburizal Bakrie, bahkan mantan kombatan GAM seperti Muzakkir Manaf.[6] Bersama-sama dengan para elite oligarki ini, elite politik lokal Aceh mengeksploitasi SDA Aceh yang kaya raya tersebut untuk kepentingan mereka.
Lalu, apa pentingnya penerapan Syariat Islam jika ia tidak bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan sosial tersebut, yang menurut Brown, merupakan dasar perlawanan Aceh terhadap pemerintah pusat di masa lalu? Saya ingin mengajukan pernyataan yang berbeda, bahwa karena ketimpangan penguasaan dan distribusi kekayaan SDA itu terus berlangsung, maka potensi perlawanan kini mengarah pada elite lokal di Aceh.
Pada titik inilah, menurut saya, pemerintah dan elite lokal Aceh menjadikan Syariat Islam sebagai alat untuk mengontrol dan menundukkan potensi perlawanan rakyat terhadap ketimpangan sosial-ekonomi akibat pemberlakuan kebijakan neoliberal. Dari perspektif pemerintah Aceh, karena rakyatnya berpendidikan rendah, tidak punya motivasi berprestasi, dan karenanya rawan akan tindakan kriminal, maka melalui seperangkat kebijakan hukum Syariah, rakyat Aceh harus didisiplinkan kehidupan sosialnya. Pembangkangan terhadap UU yang ditetapkan oleh sebuah lembaga politik ini, lalu diabstraksikan sebagai pembangkangan terhadap perintah Allah, kitab suci, Nabi, dan hadis-hadisnya. Dan tentu saja pembangkangan itu patut diganjar menurut hukum yang ditafsirkan sebagai suci, dan melalui ganjaran itulah kehidupan sosial didisiplinkan. Siapa yang berani membangkang dan melawan dicap sebagai sesat, kafir, anti-Islam, dihukum, dst. Dengan tradisi beragama yang kuat di Aceh, ancaman dan tuduhan sesat tentu saja akan dihindari semaksimal mungkin.
Di sinilah mekanisme pendisiplinan sosial itu bekerja, karena UU tersebut berimplikasi politik yang sangat luas. Melalui kontrol ketat atas tubuh, cara berpakaian, dan berperilaku, yang diimbangi dengan hukuman, maka rakyat dibikin tak berdaya dan pada saat yang sama pemerintah Aceh leluasa memberikan konsesi-konsesi kemudahan bagi beroperasinya sistem neoliberal.***
Penulis adalah editor IndoPROGRESS. Beredar di twitterland dengan ID @coenpontoh
[1] Prabhat Patnaik, Facism of Our Times, Social Scientist Vol. 21, Nos, 3-4, March-April, 1993.
[2] Vedi R. Hadiz, No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia, Indonesia 92 (October 2011), Cornell University Southeast Asia Program, p. 3
[3] Graham K. Brown, Horizontal Inequalities, Ethnic Separatism, and Violent Conflict:The Case of Aceh, Indonesia, Human Development Report, 2005.
[4] Laporan kementerian energi dan Sumber Daya Alam (2007), misalnya, menyebutkan bahwa Aceh diperkirakan memiliki kandungan emas 20 juta ton, 600 juta ton tembaga, 32 juta ton platinum, 32 juta ton merkuri, 53.000 ton timah, 350,000 ton biji besi, 6.4 juta ton besi, dan 600 juta ton molybdenum. Lihat Andi Haswidi, ‘Aceh province moves to exploit natural-resource potential,’ Jakarta Post, Thusday, April 19, 2007.
[5] ‘Aceh termiskin se-Sumatera,’ Waspada Online, Thursday, 28 June 2012,
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=251946:aceh-termiskin-se-sumatera&catid=13:aceh&Itemid=26
[6] Untuk laporan lebih detil mengenai ekonomi-politik penguasaan SDA Aceh ini, lihat Goergo Junus Aditjondro, Profiting From Peace: The Political Economy of Aceh’s Post-Helsinki Reconstruction, Working Paper #3, INFID, 2007.






