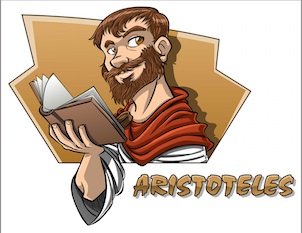RIUH rendah kampanye ada di sekitar kita. Berbagai diskusi, pendapat, imajinasi masa depan tak terkira terbang berhamburan di sekitar kita. Menghadapi keadaan seperti itu, terkadang muncul pertanyaan di benak kita—setidak-tidaknya saya—untuk apa berpolitik. Salah satu jawaban yang lugu untuk itu barangkali diberikan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles jawabannya sangatlah sederhana; tujuan politik adalah menghantarkan manusia pada hidup yang baik.
Kenapa demikian? Bagi Aristoteles, perbedaan manusia dan binatang yang asali terletak pada kemampuannya berbahasa. Melalui bahasa manusia mampu membeda-bedakan, melihat dan merundingkan tentang yang baik. Tapi namanya juga bahasa, ia menjadi begitu berkembang dan teruji jika tidak dalam soliluki, melainkan dalam perkumpulan politik. Politik, dengan demikian, haruslah mempunyai sesuatu yang penting yang tidak dimiliki di dalam kegiatan yang lainnya, sehingga hanya di sanalah kealamiahan manusia dimungkinkan teraktualisasi. Tetapi, apakah yang dimaksud Aristoteles sebagai ‘hidup yang baik’ yang menjadi tujuan politik itu?
Aristoteles tak pelak lari ke masalah moral. Baginya, kehidupan moral bertujuan pada kebahagiaan. Orang dengan keutamaan/orang berbudi luhur menurutnya adalah orang yang menempatkan kesenangan dan kesedihan pada hal yang benar. Lebih jauh, keutamaan moral ini muncul dari sebuah kebiasaan; dengan demikian melalui tindakan praktis. Dengan mendalami kebiasaan yang bajik/bijak, kita akan mampu memahami aksi-aksi yang bijak. Hal ini perlu dibedakan dari taat pada hukum. Hukum mengatur sesuatu yang singular, sedangkan kebajikan moral berurusan dengan yang partikular. Demikian Aristoteles, ‘Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan pertanyaan tentang apa yang baik bagi kita tidak memiliki suatu kepastian, lebih dari masalah-masalah kesehatan… Agen-agen sendirilah yang dalam setiap kasus harus mempertimbangkan apa yang sesuai dengan kesempatan, seperti yang terjadi juga dalam seni pengobatan atau navigasi’ (sebagaimana dikutip Sandel, 2010).
Keutamaan moral dengan demikian tidak terletak semata pada kebiasaan yang baik. Lebih jauh, keutamaan moral menyangkut melakukan hal yang baik pada orang yang benar, pada taraf yang benar, pada waktu yang benar, dengan motif yang benar dan dengan cara yang benar. Keutamaan moral dengan demikian membutuhkan sebuah keputusan tertentu, sebuah kemampuan atau pengetahuan yang dalam bahasa Aristoteles disebut ‘kebajikan praktis.’ Kebajikan Praktis ini adalah kapasitas untuk beraksi yang rasional dan benar dengan penghormatan pada kebaikan manusia.
Kebajikan praktis adalah nilai moral dengan implikasi politik. Orang dengan kebajikan praktis dapat mempertimbangkan dengan baik apa yang baik, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh penduduknya, dan untuk kemanusiaan secara keseluruhan. Pertimbangan, dengan demikian, menyangkut sesuatu aksi yang patut diambil sekarang dan di sini dengan melihat atau mempertimbangkan kebaikan manusia yang tertinggi yang bisa dicapai di bawah keadaan tertentu.
Teranglah di dalam politik (polis) orang bisa mencapai keutamaan ini. Tujuan dari menjadi warga negara (atau tujuan dari politik), demikian Aristoteles, memang adalah demi mencapai keutamaan. Karena di dalam politiklah kebiasaan yang memungkinkan adanya keutamaan moral dan tindakan-tindakan bajik bisa dilakukan. Orang yang baik, dengan demikian, adalah dia yang menggunakan dengan sepenuhnya kealamiahannya yang membedakannya dengan binatang, yakni kepenuhannya dalam mengelaborasi kemampuan berbahasanya menuju keutamaan hidup. Orang yang baik adalah orang dengan keutamaan hidup yang hanya mungkin didapatkan melalui aktivitas langsung, terjun di dalam polis.
Alasan bahwa esensi politik adalah hidup yang baik menurut Aristoteles adalah pertama hukum-hukum polis menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membentuk karakter yang baik, dan menempatkan kita pada keutamaan warga negara. Kedua kehidupan sosial memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas untuk mempertimbangkan dan dengan kebajikan praktis kita menjadi baik dalam mempertimbangkan sesuatu dengan memasuki arenanya; menjadi warga negara. Bagi Aristoteles, tujuan politik lebih tinggi daripada memaksimalkan keuntungan (utilitas) atau memberikan aturan yang adil untuk mengejar kepentingan individu. Hal ini, sebaliknya, merupakan ekspresi alami kita, sebuah kesempatan bagi berlangsungnya kapasitas manusia, merupakan aspek penting dari kehidupan yang baik.
Tetapi pertanyaan tak urung mengemuka. Tujuan politik yang dipikirkan Aristoteles ini berada dalam sebuah sistem politik yang diskriminatif. Kita tahu, di Yunani Kuno, tempat lahirnya cikal bakal demokrasi itu, tidak semua orang bisa berpartisipasi dalam politik. Setidaknya anak-anak, perempuan, dan budak tidak punya hak suara. Demokrasi di Yunani dengan demikian bisa dikatakan sebagai keadilan di atas keringat dan tenaga beribu budak. Sebuah keadaan politik yang tidak manusiawi untuk masa kita bukan?
Menjawab itu, Aristoteles tak kalah tak manusiawi-nya. Ia menerima perbudakan sejauh budak adalah orang-orang yang secara alamiah dilahirkan dalam kapasitas tersebut. Jika budak didapatkan dari rampasan perang, ia justru menolak. Alasannya sederhana. Budak dari rampasan perang atau tahanan perang sesungguhnya orang merdeka yang dirampas kemerdekaannya.
Tentu saja argumen Aristoteles ini bermasalah. Bagaimana mungkin seorang manusia secara alamiah lahir sebagai budak? Bukankah manusia lahir sederajat? Adalah Engels dalam Anti-Duhring yang, seingat saya, menegaskan bahwa pada suatu masa perbudakan sah-sah saja sebagai sebuah sistem kehidupan bersama. Dalam konteks waktu seperti itu, tak ada perihal tak berperikemanusiaan yang boleh kita jadikan tolok ukur penilaian. Sekarang bayangkanlah sebuah masa ketika tidak ada kran air, tidak ada sistem pompa air, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin seorang Aristoteles bisa berfilsafat jika tidak ada orang lain yang mengurusi air mandinya?
Demikian, Aristoteles di zaman arkhaik. Namun setidaknya dari pemikiran pada masa masyarakat dan sistem kehidupan yang masih sederhana itu pun kita jadi tahu bahwa ada di antara mereka yang layak diberi amanah mengatur polis dan ada yang tidak.***