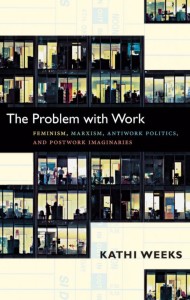Judul Buku: The Problem with Work :Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries
Penulis: Kathi Weeks
Penerbit: Duke University Press, 2011
Tebal: 287 halaman
‘Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda
yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor,
tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin,
yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa.’
(Seno Gumira Ajidarma, Cerpenis)
BICARA soal kerja dan berbagai lika-liku serta romantika yang melingkupinya, saya jadi teringat pada kutipan dari seorang cerpenis terkenal Seno Gumira Ajidarma, yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial –setidaknya yang muncul dalam linimasa twitter akun saya- belakangan ini. Kata-kata itu seperti merangkum isi cerita teman-teman saya seputar dunia kerja, tepatnya, dunia kerja yang berlokasi di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Kerja yang begitu melelahkan, upah yang tidak sepadan, macet, kereta dan transjakarta yang selalu penuh manusia pekerja dan hidup yang membuat frustasi. Berbagai masalah tersebut, tentu saja, bukan hanya dihadapi oleh mereka yang bekerja di ‘kantoran,’ tapi juga kelas pekerja lainnya yang bekerja di pabrik, di mall, dan di institusi-institusi lainnya. Sayangnya, semua cerita dan keluhan itu hanya berakhir sampai di What’s Happening-nya twitter atau What’s on your mind-nya facebook masing-masing akun rakyat pekerja.
Selain itu, ada hal lain yang menjadi kekhawatiran saya: ketika kesadaran semacam yang ditunjukkan lewat kata-kata Seno Gumira itu hanya berakhir pada redemption yang lebih bersifat individual, tergantung pada masing-masing individu/pada mereka yang bekerja. Padahal, masalah-masalah kerja yang mengalienasi kelas pekerja yang ditampilkan dalam syair tersebut bersifat sangat politis.
Problem atau masalah yang berkaitan dengan kerja, termasuk keterasingan kerja, merupakan masalah politik, bukan masalah moral, gaya hidup, atau pilihan masing-masing individu pekerja. Keluhan mengenai kehidupan/dunia kerja yang dihadapi oleh hampir sebagian besar pekerja dari semua level dan sektor, sebagaimana yang dituangkan melalui syair itu memang penting. Namun, bagaimana melakukan analisis atasnya sehingga menemukan formulasi politik yang tepat dalam usaha untuk mengubah dan bahkan mentransformasikannya, juga tidak kalah pentingnya. Disinilah, perjuangan politik (baik di ranah intelektual maupun praktik politik) memainkan peranannya yang teramat penting.

Kerja itu Persoalan Politik!
Salah satu subyek atau tema yang jarang hadir dalam teori-teori politik akhir-akhir ini justru merupakan tema yang bersentuhan langsung dengan persoalan yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari, yakni kerja. Tema inilah yang dibahas dengan cukup mendalam oleh Kathi Weeks dalam bukunya The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries ini. Dalam buku ini, dengan menjadikan Amerika Serikat sebagai lokus utama penelitiannya, Weeks menguraikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerja, termasuk mengenai persoalan housework (kerja domestik), jam kerja, dan kaitannya dengan agenda perjuangan politik feminis. Dalam hal ini, Weeks banyak mengangkat diskusi mengenai gagasan para Marxis otonom mengenai refusal of work (penolakan atas kerja) dan juga diskursus para feminis Marxis mengenai housework (kerja domestik).
Menurut Weeks, terdapat dua alasan mengapa perhatian pada kerja sangatlah kecil dalam teori politik. Pertama, hal tersebut terjadi akibat dari adanya mekanisme privatisasi kerja, dimana kerja hanya dipahami sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan, sekadar untuk mendapatkan penghasilan dan bukan sebagai sebuah konvensi sosial. Jadi, mereka yang bekerja hanya fokus memberikan perhatiannya pada soal-soal yang berkaitan dengan kerja (secara individual). Kerja masih diletakkan di area privat, tidak dipandang sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah cara hidup. Tempat kerja dipahami sebagai tempat yang privat, seperti rumah tangga, daripada sebagai bagian dari struktur sosial. Selain itu, kerja juga masih dipahami sebagai pilihan individual daripada sebagai sebuah kekuatan politik. Privatisasi kerja ini, menurut Weeks, telah membuat pasar kerja yang tengah berlaku sekarang ini, yakni Labour Market Flexibility (LMF)/pasar tenaga kerja fleksibel, berjalan dengan baik.
Dalam buku ini, Weeks memajukan gagasan Marx mengenai kerja, yang menurutnya, bukan hanya gagasan untuk membuat kerja menjadi publik, tapi juga untuk mempolitisasi kerja. Usaha untuk membuat kerja menjadi publik dan politis ini merupakan hal yang sangat penting, karena bagaimanapun kerja bukanlah sekedar aktivitas/praktik ekonomi. Kerja merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam ekonomi, sosial, politik, dan bahkan keluarga. Terlebih, kerja upahan bukan ditujukan untuk memproduksi kekayaan tapi untuk menumpuk nilai lebih bagi sebagian kecil orang.
Ada dua analisis utama yang digunakan Weeeks untuk melawan depolitisasi kerja yang telah berlangsung melalui mekanisme privatisasi kerja tersebut, yakni pertama, masyarakat kerja (the work society); dan kedua, etika kerja (the work ethic). Pada review ini, saya akan membahas terlebih dahulu yang kedua.
Mengenai etika kerja, Weeks mengemukakan etika kerja yang berlaku secara umum di Amerika Serikat. Weeks banyak melakukan analisis atas teori Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism mengenai etika kerja Kristen Protestan. Menurut Weeks, konfrontasi atas etika kerja dominan yang berlaku merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Etos kerja selalu menjadi diskursus yang bersifat individual, sebagaimana mekanisme pendisiplinan yang berlaku dalam kerja yang membentuk subyek sebagai individu yang produktif.
Dalam menjelaskan etika kerja ini, Weeks menekankan bahwa kerja upahan bersifat hirarkis dan oleh karena itu melibatkan perintah dan kontrol di dalamnya, dan menciptakan disiplin di tempat kerja.[1] Etika kerja pun dikonstruksikan secara gender dan dalam perspektif feminisme, termasuk yang dikemukakan oleh Betty Friedan dalam Feminine Mystique, seorang perempuan dapat menemukan identitasnya hanya dalam kerja yang memiliki nilai nyata bagi masyarakat – kerja bagi yang mana, biasanya, dibayar oleh masyarakat. Berbagai etika kerja yang dikemukakan para feminis, kemudian diadaptasi melalui etika kerja yang hampir dikenal secara luas, bahwa perempuan harus memiliki akses yang sama dengan laki-laki untuk dapat terlibat atau melibatkan diri dalam kerja upahan.
Mengenai persoalan kelas, menurut Weeks, analisis kelas bisa dilakukan jika didasarkan pada kerja. Kerja merupakan titik masuk ke lapangan analisis kelas, dimana kita mungkin bisa melakukan proses analisis kelas secara lebih baik, lebih mendalam, serta lebih relevan dan dalam prosesnya, mungkin mendorong pembentukan formasi kelas yang belum terbentuk.[2] Selain itu, posisi-posisi khusus dari kelas pekerja atau komposisi dari kelas pekerja mungkin juga muncul dari politik atas kerja (politics of work).
Kemudian, dalam menjelaskan masyarakat kerja (the work society) atau konsep kerja dalam masyarakat, Weeks menekankan kembali bahwa kerja upahan merupakan moda/corak produksi kapitalis, oleh karenanya kerja upahan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi kapitalisme. Masyarakat dibentuk agar mereka dapat menciptakan generasi yang siap kerja dan negara, dalam hal ini negara neoliberal, menjalankan fungsinya untuk mempertahankan kepemilikan pribadi dengan baik. Dalam analisisnya mengenai konsep kerja dalam masyarakat ini, Weeks juga menekankan analisisnya ke wilayah konsumsi yang, menurutnya, melibatkan lebih banyak orang karena di wilayah itulah reproduksi kapital terjadi. Dalam hal ini, etika melawan dalam bentuk boycott, menurut Weeks, meningkatkan imajinasi ekonomi politik dalam menentukan politik atas kerja dan menemukan alternatif dari postwork.
Kerja Domestik dan Gerakan Feminis Marxis
Masih terkait masyarakat kerja atau konsep kerja dalam masyarakat, Weeks menjelaskan pandangannya mengenai kaitan/hubungan antara kerja dan gender, khususnya mengenai pembagian kerja secara gender di rumah dan pembagian kerja secara gender di tempat kerja. Selain itu, ia juga menjelaskan signifikansi kerja baik dalam dimensi produksi maupun reproduksi. Menurut Weeks, identitas dan hirarki dari kedua hal tersebut (kerja produksi dan reproduksi) ditentukan secara gender. Weeks juga menjelaskan kaitan/hubungan titik produksi dengan pembagian kerja secara gender dengan merujuk pada Michael Burawoy dalam bukunya Politics of Production, dimana pembagian kerja secara gender di berbagai titik produksi telah menghasilkan definisi mana pekerjaan yang lebih cocok bagi laki-laki dan mana pekerjaan yang lebih cocok bagi perempuan. Dalam hal ini, Weeks menekankan bahwa kerja bukannya berjalan tanpa nilai.
Weeks kemudian menguraikan dua strategi utama feminis yang telah berlangusng selama ini mengenai kerja. Pertama, memperluas akses perempuan terhadap kerja upahan; dan kedua, membuat kerja domestik (housework) yang merupakan unwaged labor atau kerja yang tidak diupah menjadi caring work atau kerja perawatan. Dalam uraiannya, Weeks menyoroti kegagalan dari kedua strategi tersebut. Kritiknya terhadap feminis, menurutnya, seharusnya para feminis juga memperjuangkan working demands atau tuntutan kerja yang bukan hanya berfokus pada for more money (lebih banyak upah) tapi juga for less work (lebih sedikit kerja). Pada isu for more money, tuntutan ditujukan untuk peningkatan pendapatan dasar (basic income); sementara untuk isu for less work, tuntutan ditujukan untuk jam kerja yang lebih singkat/pendek (shorter hours). Pada titik ini, Weeks menekankan perhatian utamanya pada wages for housework atau upah untuk kerja domestik, seperti para feminis Marxis lain pada umumnya, semisal Silvia Federici[3] atau yang lebih dulu darinya, Maria Mies.[4] Kritik yang berkembang seputar ide ini biasanya diungkapkan oleh para feminis yang memiliki kecenderungan politik yang berbeda, misalnya bahwa upah dalam housework malah melanggengkan beban kerja perempuan. Kritik itu mungkin ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar menurut saya.
Dalam hal ini, Silvia Federici lebih tajam dalam melakukan analisis mengenai posisi kerja domestik dalam kapitalisme dibandingkan dengan Weeks. Menurut Federici, pembongkaran posisi kerja domestik dalam kapitalisme, harus ditujukan untuk menghancurkan rencana kapitalis atas perempuan.[5] Dalam kaitan dengan itu, yakni penghapusan beban social necessary labour time yang meninggi akibat kerja domestik yang dibebankan pada perempuan.[1] Perempuan yang selalu diilusi dengan heroisme, bahwa perempuan mampu menjalankan tugas dalam rumah tangga selain sebagai juru masak, perawat, dan sebagainya tidak lain merupakan proyek kapitalisme yang berkelindan dengan patriarki untuk melanggengkan pembebanan housework (kerja domestik dan reproduksi) pada perempuan. Proposisi ini menunjukkan keterbatasan teoritis Weeks yang otonomis, dimana kerangka ini tidak pernah memeriksa relasi apa yang membuat kapitalisme bisa bekerja.
Sementara itu, saya lebih bersepakat jika kerja domestik dijadikan sebagai tanggung jawab negara dimana yang mengerjakan housework nantinya tidak atau bukan lagi perempuan, melainkan juga laki-laki.[6] Dalam konteks Indonesia, fenomena ini, khususnya kota-kota besar, dapat kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Para pekerja di wilayah Jakarta, misalnya, kebanyakan menggantungkan urusan makannya pada warung-warung makan dan urusan cuci mencucinya pada tempat-tempat laundry, dimana yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik tersebut kebanyakan malah laki-laki. Hanya saja, problemnya, ini masih menjadi tanggungan masing-masing individu dan bukan ditanggung oleh negara. Dan tentu saja, hal ini bisa menjadi agenda penting yang bisa diperjuangkan para feminis dan kaum sosialis ke depan.
Penolakan atas Kerja: Konsep Kerja dalam Tradisi Marxis Otonomis
Dalam penjelasan berikutnya, Weeks mengangkat konsep lain mengenai kerja yang berakar dari tradisi Marxis otonomis[7], yakni konsep refusal of work (penolakan atas kerja). Dalam konsep ini, persoalan pada kerja terletak pada kenyataan bahwa kerja telah mendominasi hidup kita, menghabiskan ruang dan waktu hidup kita sebagai pekerja. Sehingga dalam konsep ini, perjuangan mengenai keselamatan kerja, bukan hanya terletak pada bagaimana agar kita bekerja pada kondisi/lingkungan yang lebih baik, akan tetapi bagaimana agar kita punya waktu untuk memiliki kehidupan di luar dunia kerja. Mengenai hal ini, Weeks mengaitkannya dengan freedom (kebebasan) yang, menurutnya, bersifat sosial dan bersifat politik. Apa yang dapat dilakukan secara kolektif untuk mencapai kebebasan dalam kaitannya dengan kerja yang mengontrol ruang dan waktu hidup. Weeks memaksudkan kebebasan dengan mencontohkan feminisme gelombang kedua tahun 1970an, dimana tujuan dari gerakan feminis pada saat itu bukan lagi persamaan atau equality antara laki-laki dan perempuan, melainkan pembebasan perempuan. Dalam kerangka ini, menurut Weeks, teori feminis mengangkat problem politik sebagai sebuah cara menuju kebebasan.
Konsep penolakan atas kerja ini menjadi analisis kritis dan strategi politik yang fundamental dari tradisi Marxis otonomis. Dalam hal ini, poin krusial dan link esensial bagi penolakan atas kerja ialah bahwa kerja – bukan kepemilikan pribadi, pasar, pabrik, atau keterasingan dari kapasitas kreatif kita- dipahami sebagai basis utama dari relasi kapitalis, lem yang melekatkan sistem sebagai sebuah kesatuan. Maka, setiap transformasi yang berarti dari kapitalisme membutuhkan perubahan yang substansial dalam organisasi kerja dan nilai sosial dari kerja.[8] Menurut Weeks, kritik dari Marxis otonomis berbeda dengan kritik yang diajukan oleh Marxis humanis, dimana kritik atas kerja dari Marxis humanis menekankan pada kerja yang membebaskan, sementara kritik Marxis otonomis menekankan pada bebas dari kerja.
Dalam menjelaskan konsep dari penolakan atas kerja ini, Weeks menggunakan/merujuk pada berbagai analisis dari para Marxis otonomis seperti Antonio Negri dan juga menantu Marx, Paul Lafargue, yang menulis buku the Right to be Lazy atau Hak untuk Malas. Penolakan atas kerja, menurut Weeks, bukanlah penolakan atas aktivitas dan kreativitas secara umum ataupun dalam produksi secara khusus, akan tetapi, titik tekannya terletak pada bahwa perjuangan untuk meningkatkan kualitas kerja harus diiringi dengan usaha untuk mengurangi kuantitas kerja.[9] Menurut Weeks, konsep ini menghadapi tantangan dari realita kerja yang terjadi saat ini, setidaknya, relevansinya pada perhatian utama dan agenda feminis.
Politik Antikerja dan Jam Kerja yang Lebih Pendek
Lokus dari antiwork politics (politik antikerja) dan postwork imaginaries (imajinasi setelah kerja) ialah shorter hours (jam kerja yang lebih pendek). Menurut Weeks, isu mengenai jam kerja yang lebih pendek ini telah menjadi agenda politik dan intelektual di AS secara lebih luas. Dalam uraiannya mengenai jam kerja yang lebih pendek ini, Weeks meletakkan fokus analisisnya pada 3 (tiga) hal utama yang telah menjadi agenda perjuangan politik feminis selama ini. Pertama, Less Work and More Family (Kerja Lebih Sedikit, Lebih Banyak untuk Keluarga). Kedua, Less Work for ‘What We Will’: Decentering the Family (Kerja Lebih Sedikit untuk ‘Apa yang Kita Inginkan’: Tidak Memusatkan pada Keluarga). Dan ketiga, Beyond Work Ethics and Family Values (Melampaui Etika Kerja dan Nilai-nilai Keluarga).
Mari kita bahas satu per satu. Pada pendekatan pertama, Less Work and More Family ini, Weeks mendasarkan analisisnya pada apa yang pernah diungkapkan oleh Arlie Russell Hochschild, yang menyatakan bahwa pusat dari perjuangan untuk jam kerja yang lebih sedikit ialah untuk membuat atau menciptakan waktu yang lebih banyak untuk keluarga, untuk menciptakan apa yang dikenal sebagai work and family balance. Menurut Weeks, work dan family balance ini merupakan prioritas politik yang diakui baik oleh kaum kiri maupun kanan. Namun, terdapat keterbatasan dari analisis pengistimewaan keluarga untuk atau sebagai dasar dari pengurangan jam kerja, yakni bahwa idealisasi kehidupan keluarga sebagaimana diungkapkan Hochschild dan juga pembagian kerja secara gender dalam keluarga tradisional, merupakan hal yang problematis dalam pejuangan politik feminis itu sendiri.
Pendekatan kedua, Less Work for ‘What We Will’: Decentering the Family, dapat ditemukan pada The Post-Work Manifesto karya Stanley Aronowitz, yang didalamnya memusatkan tuntutan pada jam kerja 30 jam per minggu, 6 (enam) jam kerja tanpa pengurangan upah, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari visi postwork yang lebih luas dan agenda yang di dorong penulisnya sebagai respon atas situasi ekonomi yang sedang terjadi dan kecenderungannya di Amerika Serikat. Singkatnya, ‘jam kerja yang lebih singkat, upah yang lebih tinggi, dan yang terbaik dari semua, kemampuan kita untuk mengontrol lebih banyak waktu dari waktu kita sendiri’ merupakan prioritas yang diangkat dalam manifesto tersebut.
Berkaitan dengan itu, jika kita tengok kembali slogan gerakan 8 jam kerja, ‘8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk apa yang kita inginkan,’ slogan ini menekankan bagian ‘apa yang kita inginkan’ sebagai waktu untuk menikmati waktu luang kita (leisure time). Berbeda dengan pendekatan work and family balance, pendekatan ini menekankan perhatiannya bahwa 8 jam untuk apa yang kita inginkan dapat di luar dari atau bukan bagian untuk tanggung jawab utama atas keluarga, tapi juga ada prospek untuk kesenangan atau kebahagiaan yang lain. Hanya saja, menurut Weeks, pendekatan pengurangan jam kerja ini mungkin bisa berlaku maksimal untuk laki-laki, tapi mungkin tidak selalu untuk perempuan. Intinya, menurut Weeks, poinnya adalah bahwa setiap yang dihitung sebagai waktu kerja harus menyertakan atau memasukkan perhitungan atas sosially necessary unwaged labor, dan setiap gerakan untuk mengurangi waktu kerja harus menyertakan atau memasukkan sebuah tantangan pada keberadaan organisasi dan distribusinya. Tesis Weeks adalah bahwa waktu kerja –termasuk waktu penuh, paruh waktu, dan lembur- dikonstruksikan secara gender, berdiri dan dirawat melalui diskursus mengenai keluarga ideal yang heteronormatif yang berpusat pada sebuah pembagian kerja tradisional secara gender.
Sementara itu, pada pendekatan ketiga, yakni pengurangan waktu kerja Beyond Work Ethics and Family Values, Weeks mengungkapkan pandangan Valerie Lehr yang menulis Queer Family Value: Debunking the Myth of the Nuclear Family. Menurut Lehr, pengurangan waktu kerja seharusnya dapat digunakan bukan untuk membawa negara ke kehidupan masyarakat, tapi menggunakan kekuasaan negara guna membuat warganya memiliki sumberdaya yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan-pilihan yang benar-benar nyata yang mereka inginkan. Jadi, baik The Post-Work Manifesto maupun Queer Family Values: Debunking the Myth of the Nuclear Family, menurut Weeks, menuntut jam kerja yang lebih pendek bukan atas nama keluarga tapi atas nama kebebasan dan otonomi. Bukan kebebasan dan otonomi yang menekankan pada individualitas, tapi pada kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar dapat dimiliki oleh diri kita sendiri sebagai manusia, dimana usaha menuju ke sana dilakukan secara kolektif. Dalam hal ini, penekanan Lehr pada waktu kerja yang singkat, berbeda dengan Aronowitz, yakni bahwa waktu di luar waktu kerja digunakan sebagai waktu untuk menjalin hubungan, waktu untuk membuat kembali dan menemukan kembali hubungan sosial, perhatian, dan keintiman.
Imajinasi Setelah Kerja
Persoalan tentang kerja bukan hanya persoalan tentang waktu dan energi, tapi juga persoalan imajinasi sosial politik. Dalam hal ini, waktu kerja yang lebih pendek/singkat harus dapat memungkinkan kita untuk benar-benar dapat menggunakan waktu luang kita untuk apa yang kita ingin, lepas dari bayang-bayang etos produktif atau tidak produktif, apakah untuk keluarga ataukah bukan, dan seterusnya. Waktu kerja lebih pendek/singkat harus selalu diperjuangkan untuk dapat memancing imajinasi yang lebih jauh, yang lebih besar lagi mengenai apa yang harus dilakukan setelahnya. Terkait dengan artikulasi berbagai tuntutan gerakan feminis, Weeks mengusulkan bukan hanya tuntutan mengenai kerja yang lebih baik (upah) tapi juga kerja yang lebih sedikit. Selain itu, tuntutan akan lebih banyak waktu bukan hanya membiarkan ruang dimana kita sekarang menemukan sebuah kehidupan di luar kerja upahan, tapi juga untuk menciptakan ruang yang dapat membentuk subyektivitas baru, kerja baru, ethic di luar kerja, dan praktik baru dari kepedulian dan sosialisasi. Dengan memetakan tuntutan untuk jam kerja yang lebih pendek/singkat dalam termin lebih tanpa akhir dan dengan tujuan yang lebih luas, dengan menuntut lebih banyak waktu untuk ‘apa yang kita inginkan’- dan menolak dorongan untuk melakukan apa yang harus dilakukan- kita dapat menciptakan sebuah koalisi yang lebih progresif dan melangsungkan diskursus-diskursus yang lebih demokratik.
Tentu saja akan banyak yang menyatakan bahwa berbagai tuntutan mengenai basic income dan waktu kerja yang lebih pendek ini merupakan utopia atau hal yang tidak mungkin. Dalam menjawab ini, Weeks mengemukakan berbagai argumen yang mendukung bahwa utopia itu penting dan dibutuhkan. Bahwa para anti-utopia, seperti yang dapat kita lihat pada kaum neoliberal- memang menginginkan there’s should be no alternative atau there is no alternative (tidak ada alternatif). Sementara, mereka yang disebut sebagai para utopian, percaya bahwa dunia yang baru dan lebih baik adalah mungkin. Lagipula, bahkan feminisme, menurut Weeks, telah lama berhubungan dengan utopianisme, jika dilihat dari perspektif para anti-utopia neoliberal. Jadi, tuntutan basic income dan shorter hours ini berpotensi sebagai mekanisme yang efektif untuk meningkatkan pemikiran kritis, menginspirasi imajinasi politik dan menciptakan tindakan kolektif. Menurut Weeks, yang bahaya dari cita-cita dan harapan bukanlah bahwa kita mungkin menginginkan terlalu banyak, tapi bahwa kita tidak cukup menginginkannya. Dengan demikian, feminis seharusnya mempertimbangkan bukan untuk lebih sedikit menuntut, tapi untuk lebih banyak menuntut.
Saya sendiri lebih bersepakat jika berbagai cita-cita dan tuntutan yang ada bukan hanya menjadi sekadar proyek utopis yang berfungsi untuk memberikan stimulus bagi munculnya imajinasi politik yang lebih maju. Saya lebih setuju bahwa stigma ke-utopis-an dari sebuah cita-cita, tuntutan dan harapan, dapat dibantah dan dilawan dengan perjuangan melalui program politik yang jelas. Dalam hal ini, keberadaan partai politik Kiri yang kuat sangat lah penting untuk dapat memperjuangkan, apa yang mereka, kaum neolib, sebut sebagai utopia.***
Bacaan tambahan:
Federici, Silvia. Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. 2012. Oakland, California : PM Press.
Mies, Maria. Patriarchy and Accumulation on a World Scale : Women in the International Division of Labour. 1998. London : Zed Books, Ltd.
[1]Kathi Weeks. The Problem with Work : Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. 2011. London : Duke University Press, hlm. 57.
[2]Ibid., hlm. 20.
[3]Federici, Silvia. Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. 2012. Oakland, California : PM Press.
[4] Mies, Maria. Patriarchy and Accumulation on a World Scale : Women in the International Division of Labour. 1998. London : Zed Books, Ltd.
[5]Federici, Silvia. Op.Cit.
[6]Hasil diskusi dengan kawan-kawan Partai Rakyat Pekerja (PRP) : Moh. Zaki Hussein, Irwansyah, Ruth Indiah Rahayu, dll.
[7] Marxis otonomis, menurut Weeks, ialah kaum Marxis yang otonom dalam relasi organisasi baik dengan eksternal maupun di antara mereka sendiri dan yang terpenting, para Marxis otonomis adalah para Marxis yang otonom vis-à-vis dengan kapitalisme.
[8] Kathi Weeks. Op.Cit., hlm. 97.
[9] Ibid., hlm. 109.