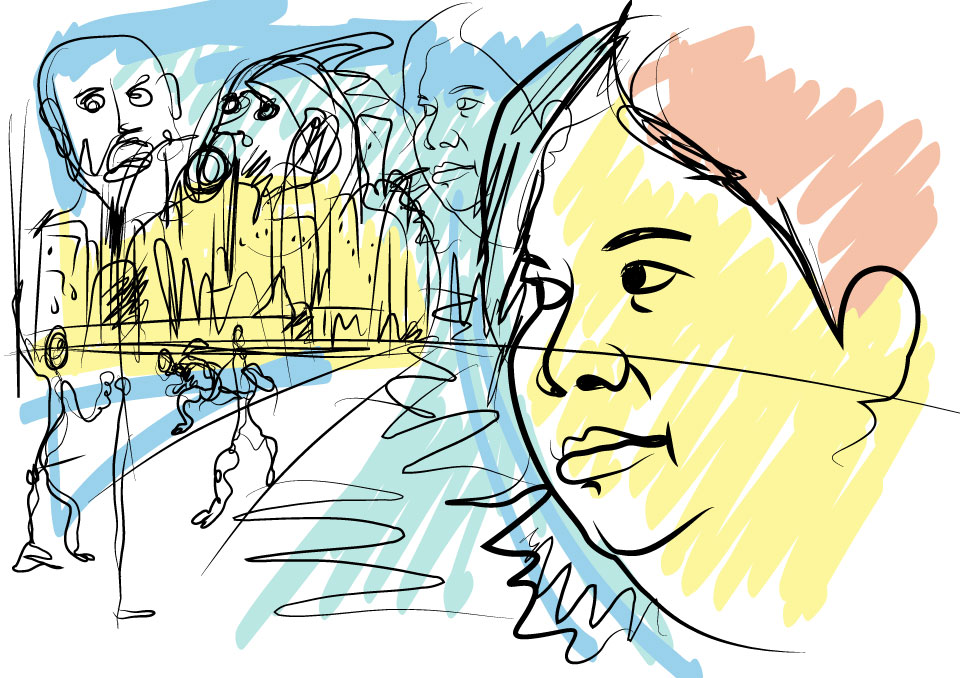TIDAK dapat dipungkiri bahwa kota adalah salah satu entitas yang berkaitan sangat erat dengan pengalaman modern kemanusiaan. Walau demikian, bukan perkara mudah untuk memahami hubungan keduanya. Alienasi atau keterasingan manusia dalam pengalaman berkota menunjukkan bahwa hidup di kota tidak bermakna memiliki kehidupan di kota itu sendiri. Penyakit akut perkotaan seperti kemacetan, banjir, minimnya penghijauan, masalah perumahan layak, kriminalitas, dsb membuat mudah untuk menyimpulkan bahwa kota yang dihidupi warganya adalah kota yang tidak manusiawi. Tidak heran jika kemudian kondisi alienatif ini menciptakan kesadaran palsu di kalangan warga bahwa situasi berkota mereka adalah sesuatu yang terberi, ‘udah dari sononye’ dan tidak dapat diubah lagi.
Tetapi kesadaran manusia adalah produk hubungan sosial, karena itu sikap apatis ini tentu saja dapat diubah. Problem mendasar dari sikap apatis adalah minimnya imajinasi serta produksi pengetahuan akan kota itu sendiri. Kemunculan kota beserta dinamikanya, adalah bagian tak terpisahkan dari relasi sosial warga kota itu sendiri. Disinilah menjadi penting untuk membuka ruang diskursus perkotaan baru di luar dominasi pengetahuan kota yang ada selama ini. Untuk mengelaborasi problematika ini, pada edisi kali ini Fathimah Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR) melakukan perbincangan dengan Irwansyah – akrab dipanggi dengan Jemi – dosen di Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang juga mengajar dalam unit Politik Perkotaan. Berikut petikannya:
Bagaimana pendekatan politik perkotaan membantu kita dalam memahami permasalahan urban di Indonesia sekarang ini?
Seharusnya sangat membantu. Politik perkotaan pada dasarnya bertanya atau mencoba menjawab persoalan kekuasaan di perkotaan. Bahkan studi politik itu sendiri, sejak awalnya adalah studi mengenai kekuasaan di ruang kota. Ini, misalnya, tampak, jika kita kembali ke teks-teks demokrasi Yunani, politik itu ada di Polis (kota).
Ada banyak pendekatan politik perkotaan yang berkembang. Misalnya pendekatan pluralis dan elitis yang dengan asumsi masing-masing yang bertolak belakang bertanya mengenai ‘siapa berkuasa/memerintah di kota.’ Pendekatan yang lain sudah melampaui pertanyaan siapa berkuasa, dan lebih memfokuskan pada bagaimana dinamika relasi kekuasaan di perkotaan beroperasi seperti pada ‘urban regime’ dan ‘growth machine.’ Ada pula pendekatan yang melihat kekuatan politik kota pada kuasa komunitas atau gerakan sosial. Sebetulnya, tidak tepat juga mengatakan sepenuhnya bahwa berbagai pendekatan tersebut sebagai sifat yang eksklusif menjadi milik politik perkotaan, karena ia selalu memiliki lintasan dengan ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, ekonomi, dan lain-lain. Pendekatan-pendekatan politik perkotaan bisa kita khususkan berguna untuk menganalisis persoalan mengenai siapa berkuasa dan bagaimana kekuasaaan berlangsung di ruang kota.
Memahami permasalahan perkotaan atau urban di Indonesia sangat penting karena semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fenomena perkotaan dari waktu ke waktu. Persoalan urban di Indonesia sudah seharusnya lebih dipahami sebagai persoalan relasi kekuasaan yang berlangsung antara negara dan masyarakat, serta di dalam relasi antara masyarakat (kelas-kelas sosial yang ada) dan implikasi yang menyertainya. Sebab, menurut saya, masalah urban bukan semata-mata fenomena yang terkait dengan perencanaan atau soal-soal teknis semata.
Bagaimana neoliberalisme kini mempengaruhi pembentukan ruang kota di Indonesia sekarang ini?
Kalau kita menggunakan perspektif yang lebih mengakomodir penjelasan ekonomi politik dan relasi kekuasaan, jelas bahwa pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan ruang kota di Indonesia terkait dengan faktor perkembangan dan dinamika kapital. Neoliberalisme sendiri adalah satu kecenderungan umum yang menyertai atau mempengaruhi dinamika dan relasi kekuasaan yang mengikuti dinamika kapital di ruang kota.
Kalau kita berefleksi dengan berkaca kepada fakta-fakta historis, kita bisa lihat perkembangan ruang kota yang ada selama 10 sampai 30 tahun ini mewujud dalam semakin besarnya kekuasaaan privat atas ruang-ruang yang ada di kota. Orang sering mengeluhkan mengenai terlalu banyaknya mall, berkurangnya taman, sedikitnya tempat yang bisa dimanfaatkan secara publik seperti museum, gedung pertunjukan, tempat olahraga, taman bermain, dan lain lain. Di saat yang bersamaan, meningkatnya kehadiran yang privat tadi hanya dimungkinkan oleh adanya serangkaian kebijakan dan relasi yang menyertai serta yang mengoptimalkan logika mekanisme pasar dalam praktek pengembangan dan pengelolaan ruang kota. Dan semua itu harus dipahami bahwa menguatnya kepentingan privat mencerminkan kepentingan kelas-kelas kapitalis dan bagaimana ia terepresentasi dalam apa yang dibangun, apa yang dipertahankan, apa yang dihancurkan, dan apa yang digusur di kota. Jadi, jelas dengan pemahaman seperti itu neoliberalisme sangat mempengaruhi pembentukan ruang kota di Indonesia. Pertumbuhan kapital dan logika yang menyertainya adalah penentu sosok kota di Indonesia hari ini. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lain lain.
Persoalan urban di Indonesia sudah seharusnya lebih dipahami sebagai persoalan relasi kekuasaan yang berlangsung antara negara dan masyarakat, serta di dalam relasi antara masyarakat (kelas-kelas sosial yang ada) dan implikasi yang menyertainya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai masih dominannya pendekatan teknokratisme dalam menjelaskan fenomena urban di Indonesia sekarang ini?
Ini tidak terhindarkan. Menurut sejarahnya, pembangunan kota-kota atau pembangunan ruang di kota itu kan terkait dengan konteks historis tertentu, dimana ada suatu fase yang disebut sebagai Orde Baru dengan cirinya pembangunanisme. Bahkan, sebelum itu juga, pembangunan kota pada masa awal kemerdekaan itu berhubungan dengan ide pembangunan satu Negara, dimana fokus utamanya ada pada kekuatan Negara dan aparatusnya, terutama pemerintah. Ketika ide-ide pembangunanisme itu direalisasikan maka terjadi penguatan pada apa yang disebut teknokrat: insinyur, perancang, ahli yang berkaitan dengan dimensi teknis dan fisik dari pembangunan kota. Mengapa? Karena disitulah saluran dari agenda pembangunan perkotaan itu di tumpukan. Dalam pendekatan teknokratik, isu sosial, budaya, itu seringkali baru dilibatkan sebagai satu unsur yang sifatnya menambal atau melengkapi pendekatan teknokratis, karena dianggap adanya ekses-ekses atau masih ada hal-hal di luar perencanaan yang harus juga di antisipasi. Jadi, dengan asumsi seperti ini maka pendekatan yang non-teknokratis itu tidak punya tempat untuk memahami kota. Walaupun, jika kita mau lihat dari sejarah Indonesia merdeka sendiri, literatur awal keksusastraan kita lebih kaya mengenai perkembangan kota. Kalau kita baca karyanya Pramoedya Ananta Toer di tahun 50an, maka sudah ada kesan yang sangat kuat dalam menggambarkan konteks kota-kota besar di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, seperti Cerita dari Jakarta dan Di Sisi Kali Bekasi. Kalau kita baca karya-karya itu, menunjukkan antusiasme yang sangat luas dari orang-orang di luar kubu teknokrasi untuk turut menyumbang pemahaman mengenai kota. Bahkan Jakarta pernah dipimpin oleh seorang seniman yaitu pelukis Henk Ngantung.
Tetapi pasca 65, pemahaman non-teknokratik itu semakin tersingkir dalam pemmbangunan perkotaan. Tidak hanya berkaitan dengan peranan Negara dalam membentuk ruang kota, tapi juga dalam porsi pembentukan kesadaran masyarakat dalam memahami kota. Sampai tahun 80an, misalnya, kita masih lihat film-film Indonesia yang menggambarkan konteks kota dan relasi-relasinya. Seperti film Warkop masih menggambarkan konteks itu. Tapi makin jauh kita makin kehilangan pemahaman non-teknokratik mengenai kota. Itu terjadi sampai sekarang. Saya belum melakukan pemeriksaan yang akurat terkait konstelasi dalam lembaga pengetahuan seperti di universitas, akan tetapi setahu saya, di luar fakultas teknik, rasanya pengetahuan mengenai perkotaan itu berkembang sangat terbatas. Di Ekonomi ada, di FISIP ada, di Geografi ada, tetapi hanya dipelajari dengan sangat terbatas, sangat minor disiplin ilmunya dan produksi pengetahuannya. Ini menyebabkan persoalan yang dibicarakan dalam fenomena perkotaan seperti hanya mengulang-ulang saja. Misalnya, kita bicara tentang penggusuran, tersingkirnya sekelompok masyarakat tertentu akibat gerak pembangunan perkotaan, perebutan ruang (privat dan publik), tetapi dari diskusi dan literatur yang ada itu bersifat repetitif. Kita seperti mengalami kemandegan dalam gagasan yang lebih inovatif dan kreatif dalam memahami dan menawarkan agenda terobosan untuk memecahkan problem sosial dan politik perkotaan. Akhirnya, yang lebih dominan lagi-lagi yang teknokratik karena mereka lebih punya kemampuan praktis untuk beraliansi dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan kapital, karena merekalah yang digunakan dalam pembangunan properti-properti baru, pembangunan infrastruktur publik, dan sebagainya. Karena kalangan di luar teknokratik masih bersifat eksperimental atau parsial saja. Akhir-akhir ini ada beberapa inovasi atau beberapa inisiatif, seperti di kalangan seniman kita lihat banyak agenda di ruang kota. Kalau tidak salah, sejak periode pasca 98 ada banyak agenda seni rupa atau kesenian lain di kota. Tapi masih kita tunggu sejauh mana dia punya kemampuan yang mengarah pada gerakan sosial perkotaan yang signifikan. Sejauh ini harus diapresiasi sebagai munculnya ekspresi yang lebih terbuka dari berbagai kalangan di luar kubu teknokratik untuk menumbuhkan kesadaran terhadap fenomena perkotaan.
Apa signifikansi ruang kota bagi perjuangan kelas sekarang ini?
Jelas signifikan karena perjuangan kelas menempati suatu lokasi tertentu. Perjuangan kelas kan tidak terjadi secara ideal, dia bukan ada di kepala atau di angan-angan. Dia menempati lokasi yang konkret. Orang sering secara kaku memahami bahwa perjuangan kelas itu hanya ada di ruang seperti pabrik karena disitulah produksi dilakukan. Tetapi, kalau kita membaca secara lebih cermat dan membaca kembali tulisan-tulisan yang lebih mutakhir dari pendekatan marxis mengenai perkotaan seperti dari David Harvey, jelas sekali dimensi spasial itu penting. Dimensi ruang kota itu menempati posisi yang penting untuk mereka, karena perkembangan cara produksi dan pembagian kerja dalam produksi secara global itu makin kompleks, sehingga kita tidak bisa membayangkan produksi itu semata sebagai sesuatu yang terisolasi di dalam pabrik dan terpisah dari ruang publik lain seperti ruang kota. Bahkan, di dalam ruang hidupnn seperti kota, kita akan menemukan jaringan yang semakin kompleks dan dinamis itu tadi. Misalnya, Jakarta sebagai agregat bukanlah tempat bagi lokasi produksi di mana pabrik berada. Pabrik semakin lama semakin tersingkir ke pinggir Jakarta. Hanya kawasan Cilincing dan Cakung yang secara administratif ada di Jakarta. Tetapi relasi dari pabrik hingga sirkulasi, yaitu dari tempat barang itu diproduksi sampai barang itu dikonsumsi itu jelas melibatkan ruang kota, di mana di situ juga terlibat di dalamnya peranan pemukiman karena para pekerja itu bertempat tinggal di kota. Maka pengertian kota tidak bisa lagi dibatasi semata dalam pengertian administratif, tetapi juga tidak bisa dipisahkan dari kaitannya yang rumit dan dinamis dengan produksi.
Urbanisasi itu kan proses menjadi semakin urban, menjadi semakin kota. Kota-kota yang sebelumnya tidak dikategorikan urban, seperti Depok, jelas sekarang adalah satu fenomena urban. Di situ kita lihat adanya tempat yang dipilih, menjadi tujuan pemukiman bagi kelas pekerja Jakarta Raya (Jakarta dan sekitarnya). Itu menunjukkan perjuangan kelas hadir juga di sana. Ditentukan dari problem kota yang menyertainya: kemacetan, pertarungan untuk merebut ruang bermukim, ruang berekreasi, ruang berekspresi, dll. Jadi jelas, kota ini sangat signifikan bagi perjuangan kelas.
Dalam prakteknya memang masih ada keterbatasan, tapi bukan sesuatu yang akan bersifat permanen. Misalnya, serikat pekerja masih minim agenda perjuangannya untuk diperjuangkan di level kota yang saat ini berdampak pada minimnya akomodasi kepentingan mereka di luar penentuan upah yang bersifat tahunan. Padahal penentuan upah yang bersifat tahunan itu berkaitan dengan hal-hal lain yang bersifat keseharian di kota. Maka kelemaham ini menunjukkan bagaimana perjuangan kelas itu mengambil tempat di kota dan memberikan dampak kepada aktor-aktor perjuangan kelas itu. Semakin minim kesadaran tentang apa yang dapat diperjuangkan di ruang kota, semakin terbatas juga agenda yang diupayakan sehingga berdampak juga pada capaian yang mungkin dihasilkan, seperti masalah upah tadi.
Minimnya produksi pengetahuan terkait kota dan juga dinamika ruang di dalamnya, itu kan enggak semata-mata terbatas dampaknya kepada institusi pendidikan atau pemerintah saja, tapi pada masyarakat secara luas. Makanya saya gambarkan tadi, di masa awal kemerdekaan kalangan sastrawan punya relasi yang lebih kuat dan berpengaruh pada warganya tentang apa yang mereka sadari dan mereka harapkan dari kota. Sementara, di masa berikutnya, yang berjaya adalah kekuatan kapital dengan karakternya yang neoliberal plus Orde Baru yang gemar melakukan pembodohan dan pengekangan terhadap pengetahuan itu. Pada gilirannya, hal itu berdampak pada kesadaran kelas pekerja, termasuk yang terorganisir. Mereka kelihatannya masih belum secara maksimal melihat lokasi perjuangan kelas mereka di luar lokus produksi yang tradisional seperti pabrik dan tempat kerja, padahal dari sejarah perjuangan kelas pekerja sendiri, seperti perjuangan Komune Paris, adalah ekspresi dari kelas pekerja di masa lalu yang sadar menyadari bahwa lokasi perjuangan kelas itu tidak semata di ruang pabrik tetapi memenangkan ruang hidup mereka secara utuh. Komune Paris adalah satu eksperimen sekaligus ekspresi bagaimana kelas pekerja dalam membayangkan kekuasaan yang baru, kekuasaan yang alternatif sifatnya di luar kediktatoran kapital.
Saya belum melakukan pemeriksaan yang akurat terkait konstelasi dalam lembaga pengetahuan seperti di universitas, akan tetapi setahu saya, di luar fakultas teknik, rasanya pengetahuan mengenai perkotaan itu berkembang sangat terbatas.
Bagaimana kelas pekerja membangun suatu relasi sosial politik yang baru yang bersifat komunal?
Dari berbagai literatur mengenai Komune Paris, kita bisa mengetahui bagaimana kayanya ekspresi kota yang ada di dalam pengalaman monumental kelas pekerja yang singkat tapi penting itu. Selain eksperimen kota yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas pekerja dalam pengalaman Komune Paris, sebetulnya cukup banyak literatur yang menceritakan pengalaman ekspresi politik kelas pekerja di ruang kota lain dalam konteks Eropa. Sayangnya kita masih minim rujukan dalam konteks Indonesia. Ada beberapa kota lain di Eropa yang terbangun sebagai hasil dinamika perjuangan dari kelas pekerja, misalnya di Denmark, ada bagian kota Kopenhagen yang disebut sebagai Christiania, yaitu suatu daerah yang dibebaskan dan dipertahankan oleh kaum anarkis dimana mereka membuat relasi produksi yang baru, cara berekspresi yang baru, dan relasi kekuasaan yang baru juga. Beberapa kota di Spanyol juga pernah mempraktekkan kota dalam tradisi anarkis. Ada yang bertahan lama ada yang tidak. Tapi memang dia jadi satu tantangan karena kritik tentang kesadaran spasial itu yang memang jadi penentu atau pembeda yang signifikan dari eksperimen kelas pekerja dari kota.
Jadi, menurut Anda kesadaran mengenai ruang kota itu lebih penting atau sama penting dengan kesadaran mengenai pabrik sebagai lokus perjuangan kelas?
Ini perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi saya ingin mengambil posisi ruang kota itu tidak bisa dipisahkan dari konsep dan praktek produksi kapitalis. Pemisahan yang simplistis antara pabrik dan kantor yang dibayangkan semata sebagai ruang reproduksi tenaga kelas pekerja itu menyesatkan, karena kita gak bisa bayangkan suatu situasi dimana buruh hanya ada di pabrik saja atau di kantor saja. Dia selalu punya relasi yang dialektis dengan kebutuhannya untuk melakukan pemulihan tenaganya, untuk reproduksi dalam pengertian yang luas. Dan juga dalam keperluannya untuk terlibat di dalam produksi itu sendiri. Mobilisasi dia dari tempat tinggal ke tempat kerja, mana yang lebih penting? Jadi bukan soal yang bisa diurutkan. Buat saya keduanya adalah satu kesatuan, karena produksi kapitalis termutakhir menunjukkan ruang kota dan ruang produksi tradisional seprti pabrik atau kantor itu selalu sebagai satu kesatuan yang dinamis sekaligus rumit: ia selalu bisa dipisahkan tapi sebetulnya selalu dalam satu kesatuan. Itu sebabnya, kita akan melihat problem seperti kemacetan, kemandegan, penolakan terhadap pembangunan berbagai bangunan atau ruang yang ada di kota. Dia tidak bisa dipisahkan secara mekanistik seperti itu
Salah satu bentuk advokasi terkini dalam pembangunan kota adalah diperkenalkannya konsep ‘right to the city.’ Bagaimana Anda melihat konsep ini dalam perjuangan kehidupan kota yang lebih baik di Indonesia?
Hak atas kota sebetulnya suatu norma yang sudah terakomodir di dalam berbagai rumusan hak asasi manusia. Hak atas perumahan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, hak atas kota sebagai suatu gagasan yang membela martabat orang-orang yang disingkirkan di perkotaan, semakin menguat akibat serangkaian pendekatan yang legal-formal mengenai apa hak yang dimiliki orang miskin tanpa identitas dan tanpa status yang jelas terhadap kota. Karena, sebaliknya, dia dianggap sebagai pengganggu ketentraman atas kota, gangguan estetika, dan gangguan kelancaran kota. Kalau kita balik ke dalam konsep Hak Atas Kota yang dicetuskan oleh Henri Lefebvre di Perancis, atau yang digaungkan kembali oleh Harvey, itu kan sebagai semangat yang kuat dari Komune Paris yang saya utarakan sebelumnya, dimana semua orang yang ada di ruang kota itu punya hak untuk turut terlibat secara demokratis dalam membentuk dan membangun kota. Pendekatan yang legalistik, yang abai terhadap rumitnya proses menjadi bagian dari warga kota itu yang dilawan oleh Right to The City.
Semua orang yang memiliki kaitan praktis atas satu kota, punya hak atas kota. Orang yang tinggal di Tanggerang, bekerja di Depok dan banyak beraktivitas di Jakarta, punya hak atas ketiga kota itu. Tapi secara administratif, secara legal formal, melalui proses demokrasi prosedural yang kering seperti hari ini, ya Hak Atas Kota hanya diakui dalam Pilkada salah satu dari ketiga kota tadi. Dalam kenyataannya, itu terjadi pada banyak sekali orang di Jabodetabek. Itulah sebabnya, konsep Hak Atas Kota semakin relevan dipopulerkan dan dimenangkan karena sangat tumpulnya kemampuan demokrasi prosedural sekarang untuk hak warga atas kehidupan kota, karena dia hanya dibatasi pada momen Pemilukada dan kemudian hampir tidak punya kemampuan untuk sungguh-sungguh terlibat secara demokratis dan partisipatif dalam bentuk dinamika kotanya. Karena kenyataan-kenyataan sosial kultural sehari-hari yang membuat mereka tidak punya waktu untuk ada di ketiga lokus pada saat yang bersamaan, yaitu tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat beraktivitas. Jadi, konsep tentang Hak Atas Kota harus dikombinasikan antara karakternya sebagai satu bentuk normatif, yang sebetulnya sudah tertuang dalam banyak rumusan hak asasi manusia, dan sebagai agenda praktis dari warga kota untuk melawan penyingkiran mereka dari demokrasi dan partisipasi kota.
Memperjuangkan ini juga penting dipopulerkan, untuk mencegah aspirasi pembangunan kota yang semata-mata bertumpu pada kenyamanan. Karena kenyamanan selalu bias kepada kelas sosial tertentu. Kenyamanan yang dominan adalah kenyamanan yang merepresentasikan imajinasinya kelas menengah. Kelas menengah seringkali tidak mau peduli dengan sejarah dan dinamika yang menyebabkan fenomena-fenomena dari kota yang mereka alami, seperti dari mana datangnya kemacetan dan proses terjadinya keruwetan pemukiman, darimana terjadinya proses hal-hal yang disebut liar: pedagang liar, gubuk liar dan seterusnya. Itu semua coba diselesaikan dengan satu, menyerahkan kepada ahlinya, kaum teknokrat. Sudah pernah dilakukan di Jakarta dengan bertumpu kepada tokoh-tokoh yang mengaku dirinya paling ahli mengatur kota: sudah terbukti gagal. Sekarang, kenyamanan itu sedang memeluk erat harapan pada tokoh populis seperti Jokowi, yang diharapkan, dengan populismenya, dapat menunjukkan keadilan popular atau keadilan yang lintas kelas. Tapi tentu, kita sadar bahwa yang namanya keadilan yang lintas kelas itu pada akhirnya adalah kemenangan satu kelas sosial kepada kelas sosial lain di dalam konteks kota. Saya tidak bilang seluruhnya merugikan warga miskin, tetapi kita harus hati-hati akan harapan yang seperti itu. Sementara konsep Hak Atas Kota harus diupayakan atas suatu kontra hegemoni baru bagi para pendukung kehidupan kota yang lebih baik, karena harapan itu ditempelkan, ditancapkan pada warga itu sendiri. Dan wargalah yang memang sehari-hari membentuk kota. Kita tahu satu dari tiga penduduk kota-kota di negara berkembang sekarang ini adalah warga yang hidup di kawasan kumuh. Setidaknya itulah yang dikatakan survey UN Habitat tahun 2007. Artinya, mereka yang hidup di kawasan kumuh harus diakui sebagai proporsi yang besar untuk pembentuk kehidupan kota. Tapi, kita juga tahu bahwa hari ini akomodasi terhadap ekspresi dan aspirasi warga kumuh itu sangat minim, bahkan seringkali diproyeksikan sebagai masalah kota. Terus menerus mengabaikan secara demokratis posisi dan kepentingan kaum miskin kota dan penghuni kawasan kumuh itu jelas hanya akan berakibat pada bentuk kota yang semakin tidak demokratis dan semakin tidak adil. Polarisasi akan semakin menonjol, karena penyingkiran itu yang membuat kita menutup mata pada hak-hak dari warga kota yang tidak menguasai akses besar terhadap modal dan memberikan toleransi yang besar pada sektor finansial dan pengembang.
Semua orang yang memiliki kaitan praktis atas satu kota, punya hak atas kota. Orang yang tinggal di Tanggerang, bekerja di Depok dan banyak beraktivitas di Jakarta, punya hak atas ketiga kota itu.
Bagaimana pandangan Anda mengenai keberadaan figur pemimpin populer seperti Jokowi untuk mendorong proses urban yang transformatif di Indonesia?
Dia adalah satu fase dialektis dari politik di perkotaan. Saya katakan ada fase sepenuhnya berharap pada teknokratisme yang terbukti gagal, yang justru dengan itu mensabotase kota itu sendiri dengan menambah kemacetan, keruwetan, dan ketidakmungkinan untuk hidup layak di kota. Antitesa dari teknokratisme itu adalah ‘populisme,’ dalam artian adanya simbol figur yang secara populer diharapkan dan dipercaya dapat mengakomodasi kepentingan lintas kelas dan terutama kebutuhan kelas dominan. Batas dari harapan seperti ini ada di antara dinamika kelas-kelas itu sendiri, karena pada akhirnya, populisme itu tidak mungkin selalu dapat mengakomodir kepentingan semua kelas itu. Semakin kuat dan semakin terorganisir kelas-kelas yang di marjinalisasi di kota, akan semakin memberikan ujian dan tekanan bagi pemimpin populis seperti ini. Hal itu sudah terjadi dalam sikap Jokowi-Ahok saat penentuan upah minimum. Dengan keterbatasan populismenya, dia hanya menetapkan upah sebesar 2,4 juta. Tapi seminggu kemudian, di media massa ia menawarkan gaji Rp. 3 juta bagi gelandangan dan preman. Itu kan menunjukkan batasan kemampuan dia untuk memahami keterkaitan relasi-relasi sosial yang ada di perkotaan. Bukan berarti tokoh populis lebih buruk dari tokoh teknokratis, tetapi jelas kita tidak bisa berharap pada satu kehidupan perkotaan yang lebih adil dan bermartabat hanya kepada kebijaksanaan tokoh populis semacam itu karena dia punya keterbatasan. Ujiannya adalah, pertentangan antara kepentingan kelas sosial yang konkrit, yang tidak bisa selalu diselesaikan dengan diplomasi populer/pejabat yang kelihatan elegan tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.
Sekarang, kenyamanan itu sedang memeluk erat harapan pada tokoh populis seperti Jokowi, yang diharapkan, dengan populismenya, dapat menunjukkan keadilan popular atau keadilan yang lintas kelas.
Bagaimana kita mendefinisikan ‘solidaritas antar kelas’ dalam pengalaman perkotaan sekarang di tengah fragmentasi ruang sosial karena neoliberalisme?
Solidaritas antar kelas jangan dikacaukan dengan populisme. Karena solidaritas antar kelas sosial itu harus punya muara pada bentuk yang konret, yakni menata kembali ketimpangan relasi sosial politik dan relasi sosial produksi yang mengakibatkan ketidakadilan pada mulanya. Jadi, kalau cuma solidaritas dalam artian adanya penggabungan antara kelas pekerja dan kelas menengah dalam wadah-wadah simbolik, itu menurut saya sangat terbatas dan sangat berpotensi tidak akan berkelanjutan. Kalau dia tidak kembali kepada usaha untuk meniadakan akar ketidaksetaraan yang menyebabkan adanya antagonisme kelas. Solidaritas kelas itu lebih mendesak dan lebih konkrit dalam bentuk imperatif atau keharusan politik melakukan redistribusi sosial di kota. Kita kecewa melihat gelandangan ternyata bisa mengumpulkan uang puluhan juta, tetapi kita nyaris tidak pernah secara serius melawan praktek menggelandang itu. Karena kita tahu bahwa itu realitas yang tidak terhindarkan dari pertumbuhan kota yang timpang. Mengatasi melulu dalam pendekatan yang moralis (jangan kasih uang ke pengemis), tapi tidak melakukan redistribusi keadilan sosial di perkotaan itu jelas bukan bentuk solidaritas antar kelas yang berkelanjutan. Kita perlu redistribusi keadilan yang lebih keras, yang lebih tegas di kota. Mengorientasikan pajak yang lebih serius untuk mengoreksi ketidakadilan di kota. Kita harus jujur bahwa kehidupan kota kita saat ini sangat timpang dan tidak adil. Mengatasinya dengan solidaritas antar mereka yang timpang, tetapi mempertahankan relasi yang tidak setara itu adalah suatu bentuk kemunafikan. Solidaritas kelas yang harus diupayakan adalah mengoreksinya, meminimalisirnya, mengecilkan jarak antar kelas-kelas sosial itu dan itu yang belum dengan kuat diupayakan oleh berbagai gerakan sosial selama ini, yang masih terkunci dalam banyak kasus yang saling menyebar itu.
Kedepannya, mau tidak mau, Hak Atas Kota untuk hidup yang bermartabat dan solidaritas antar kelas kuncinya ditentukan oleh bagaimana kita berhasil melajukan redistribusi keadilan dan redistribusi sosial. Kenyataan sosial dimana ada yang punya apartemen yang sangat mahal sementara pada saat yang bersamaan ada orang yang tidak punya tempat tinggal yang layak sama sekali, itu sesuatu yang terus menerus menjadi indikator dari problem solidaritas kelas dan kehidupan kota yang layak.
Bagaimana kita memahami relasi desa-kota dalam pengalaman terkini kapitalisme-neoliberal?
Jadi fenomena hubungan desa-kota, seperti dikatakan kaum marxis, adalah salah satu karakter dari pertumbuhan kapitalisme. Semakin melebarnya kesenjangan antara kota dan desa itu yang menjadi agenda bagi perjuangan perubahan sosial dari kacamata analisa kelas. Yang menarik adalah, desa dan kota bukanlah konsep yang statis. Itu adalah relasi yang memerlukan kepekaan sosial tadi. Banyak daerah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dinamika gerak kapital berubah dari rural ke urban. Tapi apakah otomatis kemudian perubahan spasial itu secara otomatis mengubah perubahan relasi sosial yang ada di dalamnya? Belum tentu. Itulah sebabnya usaha untuk mengatasi perubahan itu dengan menguatkan agenda politik partisipatif. Kita lihat daerah yang tumbuh menjadi urban itu, disitu juga aspirasi konservatif seperti Perda Syariah dan pengekangan lainnya menjadi meningkat. Fenomoena ini terjadi di banyak tempat, ini adalah tanda ketidakpekaan relasi desa-kota tadi. Semakin deras proses pertumbuhan ekonomi berbasis akumulasi kapital, semakin besar juga kesenjangan itu terjadi. Kesenjangan yang tidak selalu menyebabkan sebuah desa menjadi kota, tapi bisa juga mengubahnya menjadi semakin urban tapi belum tentu relasi sosialnya berubah. Atau, jika tempat itu masih tertinggal (rural), juga ada problem pilihan-pilihan sosial kultural yang dipilih oleh warganya yang cenderung berorientasi pada pekerjaan migran. Baik mencari kerja di kota atau menjadi buruh migran di luar negari. Itu, lagi-lagi, terkait dengan relasi desa-kota yang sangat dipengaruhi oleh gerak kapitalis yang saat ini berkarakter neoliberal.
Itu kan kembali lagi kepada argumen atau kepada asumsi saya bahwa fenomena urban atau hidup di kota itu terkait dengan pengetahuan dan produksi pengetahun kita atas kota. Transportasi selalu dikeluhkan, tetapi selalu diselesaikan dengan cara yang teknokratis. Padahal, transportasi atau tindakan bertransportasi adalah selalu fenomena sosial politik. Mereka kan bertransportasi bukan semata-mata ingin mencoba alat transportasi tertentu, tapi karena faktor historis dan dinamika yang terkait dengan proses produksi yang berlangsung di satu masyarakat dan kemudian bentuk atau respon praktis yang kemudian muncul untuk mengatasinya. Sederhananya gini, kita seolah hanya bisa memecahkan masalah transportasi dengan melihat solusinya pada moda transportasinya itu sendiri. Kita jarang melihat dari perspektif bahwa cara orang bertransportasi dapat diorganisir dengan imajinasi di luar yang ada sekarang. Tapi tentu saja, ini membutuhkan pengorganisasian yang jauh berbeda, yang alternatif sifatnya. Misalnya, sekarang beberapa bibitnya mulai diorganisir beberapa warga kota dengan gerakan Nebeng. Tetapi ini skalanya sangat terbatas. Itu menandakan untuk memberikan dampak yang signifikan perlu pengorganisasian yang lebih massal. Implikasi lebih lanjut dari gerakan ini adalah pengorganisasian juga dari jadwal keseharian dari para warga kota, karena tanpa adanya itu akan sulit untuk mendapatkan dampak yang signifikan dari gerakan menggunakan transportasi secara lebih kolektif itu tadi.
Imajinasi tentang bertransportasi dengan kecenderungan kolektif itulah yang harus lebih dioptimalkan. Bukan semata pada jumlah jalan dan alat pengangkutnya. Kita lihat akibatnya apa, ketahanan kepada konektivitas yang memberikan banyak kapasitas kepada PT KAI, baru mengoptimalkan daya angkut dari kereta api sebagai moda transportasi, belum mengoptimalkan cara orang bereaksi secara kolektif terhadap kereta api sebagai moda transprtasi. Bukan cuma kendaraan pengangkut, juga banyak hal yang juga harus diorganisasikan secara alternatif ini: ambulans, kendaraan pengangkut barang, dsb. Itu akan secara progresif atau berkelanjutan mengubah konstelasi dan juga volume orang yang bertransportasi. Transportasi yang dikelola secara mekanisme pasar yang anarkis dapat dikelola kembali. Itu terjadi di kota-kota di belahan dunia lainnya, yang terjadi akibat solidaritas kelas yang berhubungan dengan usaha meredistribusi keadilan sosial dan ekonomi di kota. Penerapan pajak yang tinggi pada motor, parkir, fasilitas yang lebih besar pada bentuk transportasi kolektif itu mengubah cara orang bertransportasi.
Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena menggelandang kaitannya dengan relasi kota dan desa?
Mereka adalah orang yang datang dari desa dan mengetahui secara rasional bahwa di kota ada celah dan peluang untuk mendatangkan profit dari relasi sosial di perkotaan yang timpang. Orang (dua orang gelandangan itu) kan orang-orang yang cerdik dan dengan kecerdasannya menyadari relasi sosial dalam kota itu timpang, sehingga salah satu cara yang dipilih warga kota adalah dengan memberikan sedekah sebagai usaha menambal redisiribusi sosial yang harusnya dilakukan oleh negara. Hal yang serupa juga terjadi pada ‘polisi cepek,’ gelandangan, itu yang oleh Jokowo-Ahok akan digaji. Tapi apakah itu akan memadai kalau redistribusi sosial dan ekonomi di perkotaan lebih mendasar tidak dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme pajak yang kemudian disalurkan pada kepentingan masyarakat miskin?
Apa peran yang dapat dilakukan intelektual dalam mendorong ruang kota yang lebih baik bagi para penghuninya?
Kita konsisten saja dengan diskusi di awal tadi, dimana yang saya soroti adalah tentang minimnya produksi pengetahuan tentang kota. Pengalaman hidup di kota, kesan tentang kota, idealisasi tentang kota, normatif tentang kota, itu satu hal yang jadi defisit akibat peran intelektual yang juga belum maksimal. Kita sebenarnya tidak kekurangan sekolah yang berhubungan dengan perkotaan. Tetapi orientasi yang ada selama ini, itu kan di bawah hegemoni kepentingan industri, kepentingan pasar, sehingga sedikit sumbangannya pada produksi pengetahuan bagi kelompok yang kemudian sering di krimialisasi dan di marjinalisasi. Kurang sumbangan pengetahuan pada dunia kebudayaan, media massa dan dunia jurnalisme dimana orang membaca dan berefleksi di situ. Sumbangan intelektual yang mendesak pertama-tama adalah mengoreksi defisit pengetahuan itu tadi. Defisit yang terjadi, di sisi warga kota yang punya hak atas kota. Sebaliknya, surplus di pihak pengembang dan kubu pemilik modal yang memiliki informasi lengkap tentang pertumbuhan industri di kota, seperti potensi pasar di kota dan seterusnya. Kita di televisi sangat sering disuguhkan pengetahuan yang dibuat sektor properti, seperti pengembang Agung Podomoro grup dan lain-lain. Ada pula acara bedah rumah yang sifatnya justru memberikan ilusi yang sama sekali tidak berhubungan dengan akar masalah dari keterpinggiran warga miskin dan kumuh di perkotaan. Kita saat ini hampir tidak punya tandingan yang memadai melawan produksi pengetahuan kota semacam itu. ***