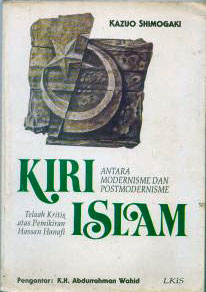Judul buku : Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme
Penulis : Kazuo Shimogaki
Penerbit : Yogyakarta: LKiS, 2012
Tebal : xxiv + 186 hal
MASALAH utama kemanusiaan saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Islam, sebagai agama paripurna yang bukan hanya berisi aturan-aturan mengenai hubungan manusia dan Allah namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, tentu diharuskan untuk menuntaskan masalah kemanusiaan yang ada. Menghadapi realitas seperti ini, Islam diberikan dua pilihan, menjadi seperti yang Marx katakan, candu dan membawa umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bersabar dan ikhlas dengan kondisi ketertindasan yang ada serta pada akhirnya melanggengkan status quo; atau menjawabnya dengan menempatkan Islam sebagai agama pembebasan, agama yang menggali dan mewujudkan makna revolusioner dan berkonsekuensi untuk memihak kepada rakyat yang lemah dan tertindas.
Banyak contoh konkret yang dapat kita temui dalam keseharian, bagaimana praktik beragama hanya sebatas ritual semata dan melupakan aspek sosial dari agama itu sendiri. Bagaimana ustadz-ustadz (dan pemuka agama lain) hari ini sibuk mengutip ayat-ayat yang menjanjikan kenikmatan surga dan hidup bahagia setelah mati kelak kepada para jama’ah/umat, tetapi kemudian setelah mendengar ceramah, para jama’ah kembali ditindas di tempat kerjanya, di pabriknya, di sawahnya, atau di ladangnya. Mereka hanya pasrah, terkunci pada sikap sabarnya karena ingat akan janji surga di kehidupan setelah mati kelak. Sebuah ilusi dan harapan palsu yang menyelubungi penindasan yang ada. Sikap pasif dan apolitis ini juga direproduksi tanpa henti di media massa sebagai aparatus ideologi termaju. ‘Kotak ajaib’ itu telah menjadikan dakwah sekadar ajang komersialisasi agama yang tidak ada bedanya dengan komoditas-komoditas lain. Ustadz pun kemudian dibayar berdasarkan ‘waktu kerja’ mereka berdakwah di layar televisi.
Dalam konteks inilah, buku Kiri Islam: Antara Modernisme dan Posmodernisme karya Kazuo Shimogaki, seorang pemerhati Timur Tengah dari Institute of Middle East Studies International University, menjadi relevan dan patut dibaca sebagai bahan referensi pembacaan terhadap Islam dari perspektif kiri. Buku ini merupakan intisari pemikiran Hassan Hanafi, seorang pembaharu pemikiran Islam sekaligus profesor filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Pemikiran Hanafi muncul, di antaranya sebagai bentuk konfrontasi terhadap kecenderungan kooptasi agama oleh kekuasaan dan praktek keagamaan yang diubah menjadi semata-mata ritus (hlm. 10). Selain itu, menurut Ridwan,[1] sumbangsih terbesar Hanafi adalah dengan membangun tiga langkah proyek besar yang dinamakan ‘Tradisi dan Pembaruan’ yang mencakup: pertama, membangun ‘Sikap Kita Terhadap Tradisi Lama,’ yaitu berkaitan dengan rekonstruksi bangunan teologis dalam tradisi klasik sebagai alat untuk transformasi sosial; kedua, menyatakan ‘Sikap Terhadap Barat,’ yaitu studinya mengenai oksidentalisme; dan ketiga, meretas ‘Sikap Kita Terhadap Realitas’ melalui pengembangan teori dan pengembangan paradigma interpretasi.
Buku ini sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berjudul ‘Kajian Kritis Kiri Islam’ yang merupakan telaah kritis Shimogaki terhadap pemikiran Hanafi. Di bagian ini, Shimogaki mencoba melihat posisi pemikiran, kerangka metodologis, hingga keterbatasan-keterbatasan yang ada di Kiri Islam. Adapun bagian kedua yang berjudul ‘Apa Arti Kiri Islam’ merupakan pemikiran Hassan Hanafi itu sendiri. Di bagian ini kita akan diantarkan untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kiri Islam, baik dari latar belakang penamaan ‘kiri,’ latar belakang sosio-historis, tujuan, hingga proyeksi Hanafi yang menjadikan Kiri Islam sebagai teologi pembebasan. Kedua bagian ini memiliki bab-bab-nya masing-masing yang akan dibahas lebih lanjut. Untuk keperluan review agar lebih tersturktur, penulis akan me-review terlebih dahulu bagian II yang merupakan pemikiran Hassan Hanafi sendiri, kemudian dilanjutkan dengan Telaah Kritis dari Shimogaki yang terangkum dalam bagian I, serta di bagian akhir tulisa ini, penulis akan mencoba untuk menanggapi diskursus yang ada di buku ini serta relevansinya untuk perjuangan kelas di Indonesia.

Kiri Islam: Dari Nama Hingga Revolusi
Nama Kiri Islam merupakan terjemahan dari Al-Yasar Al-Islami, yang merupakan nama dari jurnal ilmiah yang diprakarsai Hassan Hanafi pada tahun 1981. Adapun jurnal ini merupakan kelanjutan dari jurnal-jurnal sebelumnya, seperti Al-Wutsqa dan Al-Manar. Nama Kiri Islam menggambarkan arus yang berkembang dalam pemikiran Hanafi. Kiri adalah nama ilmiah yang dalam terminologi politik mengacu pada kritisisme. Ia juga ada dalam terminologi ilmu kemanusiaan, yang artinya Kiri Islam berada dalam pihak orang-orang yang dikuasai, yang tertindas dan kaum miskin (hlm. 112). Penamaan Kiri Islam, disadari oleh Hassan Hanafi sendiri, akan mendapatkan perlawanan dari kalangan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin (dimana Hanafi muda juga pernah tergabung dalam kelompok ini), yang tentu tidak bisa menerima dikotomi ‘kiri-kanan’ dalam Islam. Terhadap ini, Hanafi menjawab bahwa penamaan tersebut didasarkan pada prinsip, bukan pada realitas. Benar bahwa tidak ada ‘kiri-kanan’ dalam Islam selama yang dimaksudkan berada dalam tataran akidah. ‘Kiri-kanan’ ada selama Islam dan masyarakatnya berada dalam realitas historis dan sistem sosial tertentu. Selama umat Islam ada dalam gerak sejarah dan perbedaan kepentingan, maka umat Islam akan terus berada dalam medan pertarungan. Selain itu, perlawanan datang dari pihak pembela status quo, diantaranya penguasa Mesir saat itu, Anwar Sadat. Bagi mereka, term ‘kiri-kanan’ hanyalah permainan bahasa yang digunakan untuk memecah belah umat. Kiri adalah pengkhianat, pembangkang, penghasut, dan sebagainya. Padahal jelas yang dimaksudkan penguasa bukanlah kekhawatiran terpecahnya umat, melainkan kritik-kritik Kiri Islam terhadap penguasa itu sendiri. Pada akhirnya, Hanafi pun dijebloskan ke penjara oleh rezim Sadat.
Jurnal Kiri Islam diterbitkan dengan tujuan utama merespon kemenangan Revolusi Islam di Iran tahun 1979[2]. Saat itu, rakyat muslim melawan tekanan militer dan menggulingkan rezim Syah atas nama Islam dan kekuatan ‘Allah Maha Besar penumpas kaum otoriter’ (hlm. 118). Pemikiran Kiri Islam sendiri, diakui Hanafi, berakar dari pemikir Islam revolusioner Ali Syari’ati, yang juga pejuang revolusi Islam Iran. Bagi Hanafi, revolusi ini bisa disejajarkan dengan dua revolusi lain, yaitu Revolusi Perancis dan Revolusi Bolshevik, Rusia.
Selain latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang memicu lahirnya Kiri Islam yang jika dirangkum merupakan respon Hanafi atas berbagai kegagalan dalam metode pembaruan masyarakat Islam untuk mengentaskan keterbelakangan dan kemiskinan. Pertama, seperti yang disebutkan di atas, latar belakang lahirnya Kiri Islam adalah kooptasi kekuasaan terhadap agama yang menjadikannya ritual semata, sedangkan di sisi lain keagamaan yang tidak terkooptasi kekuasaan terjebak dalam fanatisme primordial, kejumudan, dan berorientasi pada kekuasaan. Kedua, praktik-praktik liberalisme dan pahamnya yang pernah berkuasa sebelum masa revolusi berakhir, hanya menghasilkan eksploitasi ekonomi golongan lemah, sementara penguasa hanya menjadi kepanjangan tangan kelas elit yang menguasai aset negara. Ketiga, kecenderungan Marxisme yang juga melawan kolonialisme namun belum mampu mengembangkan khazanah ilmu dalam Islam sehingga belum mampu untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Dan Keempat, kecenderungan nasionalisme revolusioner yang membawa perubahan fundamental dalam kebudayaan Arab-Islam dan sistem politik-ekonomi ternyata tidak berumur lama, dan tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim. Dari latar belakang ini, Kiri Islam muncul untuk merevitalisasi khazanah intelektual klasik yang berdimensi revolusioner dan berpijak pada kesadaran rakyat.[3]
Kemudian, dalam bab ‘Menentang Peradaban Barat,’ Hassan Hanafi mencoba mendefinisikan tugas Kiri Islam secara teoritis maupun praxis. Kiri Islam lahir untuk menentang dan menggantikan kedudukan peradaban Barat (hlm. 135). Dalam bab ini, Hanafi menjabarkan bahaya yang ditimbulkan peradaban Barat terhadap dunia Islam (juga dunia Timur secara umum), yaitu imperialisme militer, imperialisme ekonomi (kapitalisme), juga imperialisme budaya. Imperialisme militer mewujud dalam banyaknya pangkalan militer Barat di dunia Islam yang seringkali mengintervensi secara militer (seperti intervensi terhadap Irak yang dituduh memiliki senjata pemusnah massal beserta banyak contoh lainnya); imperialisme ekonomi mewujud dalam korporasi multinasional yang membuat kesenjangan ekonomi semakin tinggi dan penguasaan terhadap sumberdaya alam oleh segelintir orang; serta imperialisme budaya, yang diakui Hanafi merupakan ancaman yang paling berbahaya, karena membuat masyarakat Islam selalu merasa inferior terhadap Barat. Khusus untuk permasalahan terakhir, Hanafi memberikan sumbangsih besar terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya melalui studi oksidentalisme sebagai antitesa terhadap studi orientalisme, yaitu studi yang mengkaji Timur melalui perspektif Barat yang superior.
Perspektif orientalisme menjadikan studi-studi intelektual-akademis mengenai Timur tidak akan pernah seimbang dan hanya melahirkan prasangka-prasangka. Dalam latar historis, kita tahu bahwa orientalisme, walau bagaimanapun, pada mulanya merupakan alat imperialisme yang selalu berusaha mencari sisi-sisi ‘keterbelakangan’ Timur untuk kemudian ‘dimodernkan oleh Barat.’ Meskipun saat ini, dalam perkembangan terakhir, orientalisme mencoba mengubah paradigmanya sebagai sebuah studi atau kajian terhadap Timur yang obyektif, namun kesan superioritas kultural Barat tetap tertanam dalam benak orang-orang Timur.[4]
Studi oksidentalisme yang digulirkan Hanafi, tidak diniatkan untuk dibenturkan secara langsung dengan orientalisme. Lebih dalam dari itu, studi oksidentalisme membawa tawaran epistemologi baru yang memisahkan diri dari pengaruh ideologis maupun prasangka, sehingga lahir studi yang setara antara dunia Timur dan Barat. Dalam Oksidentalisme, posisi subjek dibalikkan sedemikian rupa. Jika dalam studi orientalisme, Barat menjadi subjek yang mengkaji objeknya, yaitu Timur/Islam, maka tawaran dari oksidentalisme adalah posisi Barat dibalik menjadi objek yang diselidiki oleh si subjek, yaitu Timur/Islam. Hal ini penting dilakukan, menurut Hanafi, sebagai upaya penguatan umat Islam yang inferior dari pengaruh hegemoni Barat yang sudah sangat mencengkeram. Dalam studinya mengenai oksidentalisme, Hanafi mencoba membuat wacana keilmuan yang netral. Di sini nampaknya Hanafi mendapat pengaruh dari Michel Foucault, yang melihat relasi yang dekat antara kekuasaan dan kebenaran. Bahwa kebenaran yang dihasilkan oleh kekuasaan dan dominasi cenderung bersifat manipulatif dan ideologis, oleh karenanya harus dibongkar.[5] Perbedaan signifikan antara orientalisme dan oksidentalisme terletak pada titik aksiologis, dimana oksidentalisme tidak dimaksudkan untuk menjadi hegemoni baru sebagaimana yang dilakukan orientalisme melalui kolonialismenya.
Semenjak bab-bab awal, Hanafi selalu menyinggung masalah realitas umat Islam yang terbelakang. Pun dengan pemaparannya tentang oksidentalisme yang baru saja dilewati, dimana Hanafi secara implisit mengatakan bahwa keterbelakangan umat Islam termasuk dalam ranah pemikiran. Lantas, bagaimanakah realitas umat Islam yang sesungguhnya? Pertanyaan ini baru dijawab Hanafi dalam bab ‘Realitas Dunia Islam.’ Tegas dikatakan Hanafi bahwa prolematika umat Islam saat ini adalah imperialisme, kapitalisme dan zionisme di sisi eksternal; serta kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan di sisi internal (hlm. 155). Imperialisme hari ini, tercermin dalam korporasi multinasional yang merupakan ancaman di bidang ekonomi dan bentuk-bentuk westernisasi yang semakin menginjeksi kesadaran umat Islam, diantaranya melalui impor pengetahuan dari Barat. Selain itu, imperialisme militer terlihat nyata dari pangkalan-pangkalan militer asing yang hadir di seantero dunia Arab. Untuk masalah zionisme, saat ini tugas Kiri Islam bukan hanya pembebasan Palestina dari cengkraman Zionis. Lebih dari itu, Kiri Islam juga bertugas untuk menghentikan penyebaran gagasan-gagasan Zionis yang menginginkan penghapusan wacana Palestina dari semua aspek kehidupan. Ancaman eksternal ketiga dunia Islam adalah kapitalisme. Sebagaimana kita tahu, kapitalisme yang mensyaratkan adanya persaingan bebas, akumulasi kapital dan penghisapan nilai lebih bukan hanya akan melangengkan penindasan di muka bumi, lebih dari itu, kapitalisme juga memicu tumbuhnya nilai-nilai destruktif dan hedonisme utilitarian. Untuk permasalahan internal umat Islam, saat ini umat Islam masih berada dalam tahapan masyarakat yang miskin dan terbelakang.
Dengan realitas seperti itu, Hanafi merumuskan misi Kiri Islam sebagai berikut: (1) memanifestasikan keadilan sosial; (2) menegakkan masyarakat yang bebas dan demokratis dimana tiap individu bebas mengeluarkan kritik dan pendapat; (3) membebaskan tanah-tanah kaum muslim dari segala macam kolonialisme imperialisme, termasuk di dalamnya masalah Palestina; (4) membangun Pan-Islamisme; (5) membangun sistem politik nasional yang independen dan mempererat jalinan persahabatan dengan bangsa-bangsa Islam dan Dunia Ketiga, serta; (6) mendukung gerakan revolusioner kaum terjajah dan tertindas. (hlm. 163-164)
Kiri Islam Sebagai Teologi Pembebasan
Memasuki bab-bab akhir, Hanafi menjelaskan apa sebenarnya proyeksi dia tentang Kiri Islam. Hanafi berpendapat bahwa tugas Kiri Islam adalah menguak unsur-unsur revolusioner dalam agama, dan menjeaskan pokok-pokok pertautan antara agama dan revolusi. Dengan kata lain, memaknai agama sebagai revolusi (hlm. 164). Kiri Islam Hassan Hanafi secara keseluruhan terbebas dari pengaruh Barat dan Timur dan merupakan refleksi pemikiran historis yang merepresentasikan suatu gerakan sosial politik yang hanya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (hlm. 176). Dalam bab ‘Integritas Bangsa,’ Hanafi menjelaskan bahwa untuk mencapai transformasi sosial dan menjadikan Kiri Islam sebagai teologi pembebasan, maka yang dibutuhkan adalah terjadinya dialog antara berbagai macam kecenderungan pemikiran dan mencari titik pertemuan di antara kesemuanya. Dalam bab terakhir, Hanafi mencoba memaparkan bagaimana posisi Kiri Islam dihadapan golongan Ihwanul Muslimin, Marxis, Nasseris, dan Liberalis, yang bagi Hanafi, semua aliran tersebut mampu diakomodir di bawah panji Kiri Islam.
Dalam tawarannya dengan golongan Ikhwanul Muslimin, walaupun Kiri Islam mengakui bahwa kecenderungan fundamentalisme mereka masih kuat, tetapi mereka menawarkan dialog untuk mencari persamaan. Karena ’sesungguhnya perbedaan di antara kita hanyalah dalam bentuk, simbol, bahasa, dan metode tidak dalam substansi, isi, makna, dan tujuan akhir.’ Dengan golongan Marxisme, Kiri Islam menegaskan bahwa mereka tidaklah bertentangan. Bagi Kiri Islam, golongan Marxisme masing-masing terikat oleh tanah air dan sama-sama revolusioner. Perbedaan di antara mereka adalah Kiri Islam menggali akar revolusi dari kebudayaan rakyat. Marxisme menginginkan revolusi sekuler, Kiri Islam menginginkan revolusi Islami, hasilnya tergantung rakyat nanti yang memilih. Juga, bagi Kiri Islam, revolusi sekuler yang menurut mereka diinginkan golongan Marxis adalah juga bagian dari revolusi Islam yang merupakan revolusi yang komprehensif, bersifat kerakyatan dan menyejarah (hlm. 173). Bagi golongan Nasserisme, yang ditawarkan Kiri Islam adalah persamaannya dalam agenda-agenda revolusi Arab, seperti memerangi kolonialisme dan zionisme serta memberantas keterbelakangan umat. Yang terakhir, tawaran Kiri Islam atas golongan liberal adalah reformasi terhadap agama dan sikap kritis terhadap kebudayaan barat.
Kajian Kritis Terhadap Kiri Islam: Metodologi Serta Batasannya
Apresiasi tertinggi dari sebuah karya adalah kritik, dan dalam bagian I buku inilah Shimogaki melakukannya. Kritik yang dilakukan Shimogaki lebih dititikberatkan pada masalah metodologi yang dijalankan Hanafi dalam mengembangkan Kiri Islam tersebut. Tentu muncul pertanyaan dari pembaca, bagaimana mungkin kesemua aliran pemikiran tersebut (Islamis, Marxis, Nasionalis-Populistik, dan Liberalis) mampu diakomodir oleh Kiri Islam? Bagaimanakah metode yang dilakukan Hanafi sehingga sampai pada kesimpulan tersebut? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan itulah yang dicoba dijawab Shimogaki dengan memeriksa kerangka metodologi Hanafi, sehingga di akhir bagian ini kita akan menemukan batasan-batasan dari Kiri Islam.
Shimogaki menempatkan pemikiran Hanafi dalam golongan modernis-liberalis, sebagaimana pemikir-pemikir lain seperti Taha Husain atau Luthfi as-Sayyid. Kesimpulan ini didasarkan pada latar belakang pendidikan Hanafi yang merupakan seorang lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, tahun 1966. Universitas Sorbonne merupakan pusat pemikiran modernisme Eropa. Tentu, definisi modernis-liberalis di sini tidak bisa disamaratakan dengan definisi modernis-liberalis a la Barat. Dalam catatatn kaki halaman 4, Shimogaki menulis ‘latar belakang mereka Islam, dengan demikian mereka liberal-modernis Islam.’ Selain itu, Shimogaki juga membagi pemikiran Hanafi menjadi tiga kategori besar dan memiliki kaitan dengan Kiri Islam, yaitu: Hanafi sebagai seorang pemikir revolusioner dengan tesisnya tentang revolusi tauhid;[6] kedua, Hanafi sebagai reformis tradisi intelektual klasik Islam; dan ketiga, sebagai penerus gerakan Al-Afghani, yaitu gerakan modernisasi Islam yang bertujuan melawan dominasi barat dan menyatukan umat Islam.
Meskipun Shimogaki mengklasifikasikan Hanafi sebagai pemikir modernis, namun dalam bagian selanjutnya, Shimogaki juga melihat bahwa Hanafi ‘tidak sepenuhnya modernis’ karena dalam merevitalisasi pemikiran Islam tradisional, terutama dalam interpretasi terhadap teks-teks agama, Hanafi menggunakan pisau fenomenologi yang notabene di dunia Barat digunakan untuk melawan arus modernisme. Hal ini bisa terjadi karena meskipun Hanafi menyerap modernitas dan praposmodernitas, ia belum merambah ke pemikiran paling baru di Barat, yaitu posmodernisme. Pendekatan fenomenologi ini diamini pula oleh Hanafi sendiri, dimana ia menyatakan ‘sebagai bagian dari gerakan Islam di Mesir, dan sebagai seorang fenomenolog, saya tidak punya pilihan lain untuk menggunakan metode fenomenologi untuk menganalisa Islam alternatif di Mesir’ (hlm. 60). Inilah problem yang cukup serius dari pemikiran Hanafi yang akan ditelaah Shimogaki.
Sebelumnya, kebangkitan Kiri Islam dalam ranah intelektual Islam kurang mendapat respon yang baik, bahkan cenderung mengecewakan. Tanggapan terhadap Kiri Islam dari para intelektual lain bisa dilihat dari pernyataan Hahid Hattar bahwa ‘Proyek Hassan Hanafi pasti tidak akan berhasil dalam menghadirkan landasan filosofis atau metodologi yang kuat dalam kajian filosofis. Hassan Hanafi, dilihat dari proposisi metodologisnya, tidak mungkin lepas dari posisinya sendiri.’ Tanggapan negatif juga hadir dari Muhsin Al-Mili, seorang sarjana Islam. Tulis dia,
‘Kiri Islam nampaknya akan menjadi sebuah kekuatan pembaharu dalam gerakan Islam, ia mencoba menyingkirkan hal-hal negatif pada gerakan Islam kontemporer dibidang pemikiran, kebudayaan, dan praktik.… Akan tetapi, Hanafi dibatasi oleh teori, oleh karena itu Kiri Islam idak akan mampu memecahkan sikap-sikap negatif itu, bahkan lebih dari itu, ia justru akan ikut serta dalam membuat sikap-sikap negatif baru…’
Dengan banyaknya tanggapan negatif, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Kiri Islam tidak mendapat respon positif? Apakah karena dunia intelektual Islam mengalami krisis kebebasan sehingga sulit menerima termin-termin yang biasa dipakai dalam kajian kiri sebagaimana yang Hanafi katakan? Ataukah memang ada yang bermasalah dari pemikiran Kiri Islam itu sendiri? Di titik ini, peran Shimogaki yang menelaah batasan metodologi Hanafi menjadi penting.
Dalam halaman 75, Shimogaki dengan satu paragraf pendek sebenarnya telah merumuskan bagaimana keterbatasan pandangan Hanafi. Ia menyebutkan,
‘Hassan hanafi ingin membangun rasionalisme, kebebasan, demokrasi, pencerahan, dan humanisme. Sebagai sebuah konsep yang ideal, kegunaannya jelas tidak diragukan, itu merupakan tulang punggung modernisme. Akan tetapi, beberapa sarjana Barat menggunakan keterlibatan ‘konsep-konsep ideal’ itu dengan kapitalisme, penindasan dan imperialisme.’
Dalam paragraf tersebut jelas bahwa ada yang keliru dengan pemikiran Hanafi. Bahwa pandangan dia terhadap supestruktur (demokrasi, humanisme, rasionalisme) tidak disertai dengan pemahaman bahwa superstruktur itu dikondisikan oleh basis ekonomi. Kemunculan demokrasi liberal di Barat justru merupakan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan akan masyarakat pasar yang menjadi prakondisi bagi lahirnya kapitalisme. Paham ini pula yang pada akhirnya mengharuskan kapital-kapital Barat untuk melakukan ekspansi sehingga terjadilah kolonialisme yang kemudian menghantam dunia Islam dimana Hanafi hidup. Maka, yang keliru dari Hanafi adalah pemahamannya yang tidak relasional antara sistem ekonomi dan non-ekonomi.
Selanjutnya, Shimogaki menerangkan bagaimana analisis Hanafi terhadap Barat yang dia serang. Hanafi menjelaskan bahwa ’lingkungan Eropa menjadi basis lokal bagi kekhasan peradaban Barat dan ia mengandung hakikat bangsa Barbar dengan watak sensasional dan materialistik, liar, dan rasial…’ (hlm. 77). Agaknya tidak sulit mengatakan bahwa apa yang dikatakan Hanafi merupakan pernyataan yang hanya sekedar ‘anti Barat,’ sehingga jauh dari nilai akademis. Pun dengan apa yang dikatakan Shimogaki terkait pernyataan tentang Masyarakat Barat ini. Shimogaki mengatakan bahwa analisa Hanafi cenderung hanya merupakan kritik yang bersifat pribadi sehingga tidak bisa dijadikan kritik yang sungguh-sungguh terhadap kapitalisme dan imperialisme Eropa. Sentimen-sentimen seperti inilah yang kemudian mewarnai pemikiran Hanafi yang sangat kental dengan aroma konfrontatif seperti Islam vs Barat, Keterbelakangan vs Kemajuan, Penguasa vs Yang Dikuasai. Model konfrontatif ini juga tidak disertai dengan analisis yang mendalam (seperti pengertiannya tentang masyarakat Eropa). Model konfrontatif ini tentu membawa pada konfrontasi dikotomik, yaitu pemisahan antara subjektivitas dengan objektivitas yang pada akhirnya, menurut David Bohm, ‘pengelompokkan-pengelompokkan ini akan menyisakan perasaan pemisahan dari orang lain yang tersisa.’ Dan karena konfrontasi inilah, maka metode analisis Hanafi tidak memiliki pijakan relasional, meskipun ia menyerukan revolusi tauhid yang justru secara teoritik bersifat relasional. Ini rupanya yang dimaksud Muhsin Al-Milli bahwa Kiri Islam justru akan membuat krisis-krisis baru.
Tanggapan Atas Buku Kiri Islam
Meskipun banyak keterbatasan (yang sesungguhnya fundamental) yang ditunjukkan oleh Shimogaki dari pemikiran Hassan Hanafi tersebut, namun apa yang dilakukannya tentu harus mendapat apresiasi sebagai usaha revitalisasi pemikiran Islam, terutama perlawanannya terhadap kooptasi kekuasaan atas agama, yang menjadikan agama sebatas ritus yang melanggengkan status quo.
Posisi saya terhadap buku ini, terutama dalam aspek proyeksi Kiri Islam yang ‘menggandeng’ pemikiran-pemikiran lain yang saat itu berkembang, dan kontekstualisasi Kiri Islam terhadap gerakan rakyat di Indonesia dewasa ini, adalah sebagai berikut:
Pertama-tama, anggapan Hassan Hanafi yang meyakini bahwa Kiri Islam mampu untuk memayungi segala aliran pemikiran yang ada, memiliki masalah baik dalam segi teoritis ataupun praksis dalam rangka perjuangan pembebasan Islam. Di bagian ‘integrasi bangsa’ misalnya, Hanafi meyakini bahwa terdapat titik temu antara Kiri Islam dan berbagai aliran pemikiran lain (Marxisme, Liberalisme, Nasserisme, dan Islamis). Saya meragukan keyakinan Hanafi ini, sebab bagaimana cara Kiri Islam ‘memayungi’ beragam pemikiran itu? Di mana titik temu antara Marxisme yang bertujuan untuk mengganti sistem Kapitalisme dengan Komunisme (hapusnya kepemilikan pribadi), misalnya, dengan golongan Nasserisme yang berhenti pada penguasaan sumber daya alam oleh negara? Atau dengan golongan Islamis seperti Ikhwanul Muslimin, yang menekankan pada penyadaran umat dan aplikasi ayat-ayat Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, tetapi secara ekonomi mengadopsi sistem ekonomi neoliberal seperti yang dewasa ini diadopsi oleh rezim Tayip Recep Erdogan di Turki dan rezim Mohamed Morsi di Mesir, yang baru saja dijatuhkan oleh kekuatan rakyat? Apa yang dilakukan Hanafi dalam merespon kritisisme seperti ini adalah mengambil jalan pintas reduksionisme, melalui model konfrontasi dikotomik. Hanafi secara sederhana memasukkan semua golongan yang berbeda ini ke dalam ‘kotak geografis’ dunia Islam yang berkonfrontasi dengan dunia Barat. Akibat reduksionisme itu, menurut saya, pemikiran dan metodologi yang ditawarkan Hanafi pada akhirnya menjadi hal yang utopis.
Selanjutnya, dalam kritiknya terhadap Hanafi, Shimogaki berhenti pada ‘menginterpretasikan Kiri Islam’ namun tidak mencoba menjawab ‘bagaimana cara mengubahnya.’ Hal ini penulis kaitkan dengan relevansinya terhadap perjuangan rakyat dewasa ini. Bagi penulis, Islam, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, masih merupakan sumber mobilisasi massa yang kuat. Dalam sejarahnya pun, Islam pernah mampu menjadi sumbu perlawanan rakyat dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Tercatat bagaimana Sarekat Islam menjadi corong terdepan dalam memobilisasi rakyat melawan penjajahan dengan percaya pada kekuatan sendiri[7]. Atau bagaimana Amir Biki, melalui sentimen agama mampu menggerakkan massa untuk melawan rezim otoriter Suharto dalam peristiwa Tanjung Priok. Tetapi di balik itu, sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada sistem yang baku dalam Islam. Masalah keduniawian, sepanjang tidak bertentangan dengan universalitas dan rumusan-rumusan umum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman (yang juga seringkali disesuaikan dengan kebutuhan penguasa).
Dengan keterbatasan tersebut, yang mungkin dilakukan oleh Islam, terutama dalam rangka perjuangan rakyat dewasa ini, adalah terus menerus menginjeksi kesadaran terhadap massa tentang ketertindasan mereka dan keharusan untuk berlawan. Artinya, perjuangan yang mungkin dilakukan masih berpusar dalam ranah superstruktur. Yang masih belum jelas, bagaimana Hanafi membawa perjuangan rakyat tertindas itu ke dalam ranah perjuangan kelas yang konkrit. Jika Hanafi melihat semua elemen pemikiran dapat dipertemukan untuk dilawankan dengan Barat melalui model konfrontasi dikotomisnya dan itu tentu utopis, maka Marxisme menawarkan metode yang lebih memadai untuk melakukan perubahan struktural yang menjadi tujuan Kiri Islam, yaitu metode materialisme dialektik dan materialisme historis. Dengan demikian, problem yang hadir dalam Kiri Islam dapat diatasi.
¶
Rio Apinio, mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, aktif di Grup Diskusi Serikat Mahasiswa Progresif (Semar) UI. Penulis beredar di twitterland dengan id @rioapino
Daftar Referensi
Ridwan, A. H. Reformasi Intelektual Islam. Yogyakarta: Ittaqa Press. 1998
Roswantoro, Alim. “Studi Oksidentalisme: Mempertimbangkan Hassan Hanafi”, dalam Muhidin M. Dahlan (ed). Postkolonialisme, Sikap Kita Terhadap Imperialisme. Yogyakarta: Jendela. 2001
Shiraishi, Takashi. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di jawa 1912-1926. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1997
Tasmuji. Rekonstruksi Teologi, Oksidentalisme dan Kiri Islam: Telaah Pemikiran Hassan Hanafi ; data didapat dari http://ush.sunan-ampel.ac.id/?p=1582/ ; internet; diakses pada 24 Juli 2013.
[1] A. H. Ridwan, Reformasi Intelektual Islam. Yogyakarta: Ittaqa Press. 1998.
[2] Revolusi Islam Iran dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang menggulingkan Rezim Syah Pahlevi. Syah Pahlevi dianggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Inefisiensi, korupsi, hingga kedekatan dengan Barat dan proyek westernisasi yang dilakukan membuat Pahlevi dicap sebagai boneka barat dan sangat bertolak belakang dengan mayoritas Islam Syi’ah di Iran. Secara resmi Republik Islam Iran yang menggantikan sistem monarki ini berdiri pada 1 April 1979 setelah sebelumnya diadakan referendum nasional.
[3] Tasmuji, Rekonstruksi Teologi, Oksidentalisme dan Kiri Islam: Telaah Pemikiran Hassan Hanafi, data didapat dari http://ush.sunan-ampel.ac.id/?p=1582/ ; Internet; diakses pada 24 Juli 2013.
[4] Alim Roswantoro ‘Studi Oksidentalisme: Mempertimbangkan Hassan Hanafi,’ dalam Muhidin M. Dahlan (ed). Postkolonialisme, Sikap Kita Terhadap Imperialisme. Yogyakarta: Jendela. 2001.
[5] Tasmuji, op. cit.
[6] Revolusi Tauhid yang dimaksudkan Hanafi dititik beratkan pada pengembalian fungsi tauhid yang telah terdistorsi menjadi sebatas pada hubungan antara manusia dan Tuhannya saja. Dengan Revolusi Tauhid, Hanafi mengajak umat untuk mengartikan tauhid secara menyeluruh, yaitu selain meresapi hubungan mereka dengan Tuhan, juga menyadari bahwa hubungan antarmanusia pun merupakan bagian dari tauhid.
[7] Selain Sarekat Islam, banyak contoh-contoh lain yang memperlihatkan bagaimana Islam mampu untuk menggerakkan massa rakyat. Lihat misalnya buku Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 karangan Takashi Shiraishi.