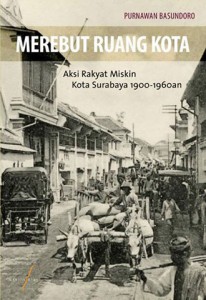Judul buku: Merebut Ruang Kota : Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an
Penulis: Purnawan Basundoro
Penerbit: CV Marjin Kiri, Tangerang Selatan
Tahun terbit: 2013
Halaman: x+337 halaman
31 MEI 2013, Kota Surabaya genap 720 tahun. Tentu ini umur yang cukup tua bagi sebuah kota. Beruntung, bebeberapa waktu lalu, saya sempat mengunjungi Kota berlambang ikan hiu dan buaya itu. Surabaya yang saya saksikan adalah Surabaya yang sarat dengan kontradiksi. Di sepanjang jalan-jalan utama kota, berdiri angkuh mall-mall besar dan gedung-gedung tinggi yang seolah ingin menutupi potret kemiskinan di kota itu. Sayangnya, potret itu malah nampak jelas terlihat, terutama jika kita telusuri kota itu lebih dekat lagi. Misalnya, para tukang becak mengayuh sepeda becak dengan kelelahan di sepanjang Surabaya yang panas membakar; rumah-rumah tak layak huni berdiri di sepanjang kali-kali kecil di jalanan Surabaya, hingga buruh-buruh pabrik yang pulang larut malam demi mengejar target perusahaan. Review kali ini akan membahas aksi rakyat miskin kota di Surabaya pada tahun 1900-1960-an dalam memperebutkan ruang di kota itu.
Perebutan ruang kota, sebagai ruang hidup bagi rakyat miskin, memang merupakan lakon utama dalam proses pembangunan kota. Meningkatnya intensitas penetrasi kapital ke dalam ruang-ruang publik, termasuk yang ada di dalam kota, menjadi faktor utama di era MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pembangunan infrastruktur (termasuk jalan, dll.) demi memuluskan investasi menjadi prioritas dalam MP3EI. Hal ini tentu berkonsekuensi langsung pada perebutan ruang, termasuk ruang kota. Baru-baru ini, misalnya, saya ikut terlibat aktif dalam advokasi penggusuran paksa para pedagang stasiun Jabodetabek yang dilancarkan oleh PT KAI dalam rangka privatisasi transportasi publik demi kelancaran proyek MP3EI. Perebutan ruang nampak jelas di sana. Paradigma pembangunan ala Orde Baru Soeharto, nampaknya masih menjadi satu-satunya paradigma hingga saat ini, termasuk dalam hal penataan ruang kota.
Sejarah Surabaya
Dalam bab 1 yang berjudul ‘Rakyat Miskin dan Ruang Kota: Sebuah Pendahuluan,’ Basundoro mengungkapkan latar belakang mengapa ia mengangkat Kota Surabaya, dan lebih khusus lagi, aksi rakyat miskin di Kota Surabaya dalam perebutan ruang kota. Dengan apik, Basundoro menjelaskan sejarah Kota Surabaya dengan runut. Berdasarakan penelitian yang ia lakukan, Kota Surabaya merupakan kota dengan hinterland yang subur, utamanya pada awal abad 19. Pada masa itu, Kota Surabaya pada mulanya memang tidak diperuntukkan bagi kepentingan penduduk secara umum. Kota Surabaya dirancang untuk kepentingan kolonial. Penduduk bumiputera hanya tinggal di rumah-rumah kumuh yang terdapat di kampung-kampung. Dari sanalah, sejarah keberadaan pemukiman-pemukiman miskin di tengah Kota Surabaya berawal. Keberadaan pemukiman-pemukiman miskin kemudian menjadi salah satu problem perkotaan. Menurut penelitian yang ia lakukan, hal tersebut terkait dengan persebaran kemiskinan dan penciptaan ruang informal yang ditimbulkan kemudian.
Selain itu, dalam bab ini Basundoro juga menjelaskan teori-teori yang menjadi alat analisis yang ia gunakan. Perhatian utama Basundoro diletakkan pada dua hal. Pertama, pentingnya kota sebagai ruang kontestasi; dan kedua, diabaikannya peran rakyat miskin kota dalam sejarah kota, dalam hal ini Kota Surabaya. Dalam buku yang awalnya merupakan disertasinya ini, Basundoro menggunakan teori Antonio Gramsci, seorang Marxis Italia mengenai kelas-kelas yang terpinggirkan (subaltern) yang kemudian secara praksis dikembangkan oleh Gayatri C. Spivak, sebagai pisau analisisnya yang utama. Selain itu, Basundoro juga menggunakan analisis Marx bahwa perebutan ruang bisa dipahami sebagai perebutan alat-alat produksi. Dengan menggunakan teori Gramsci dan Spivak sebagai pisau analisisnya Basundoro menekankan pentingnya peran dan perlawanan rakyat miskin dalam sejarah perkembangan Kota Surabaya.
Dalam buku ini, Basundoro menggunakan teori Gramsci dengan meletakkan aksi rakyat miskin sebagai peristiwa penting dalam sejarah Kota Surabaya. Menurut Gramsci, kelas-kelas tertindas atau subaltern harus melibatkan diri dalam perjuangan kelas sebagai upaya melawan kelas dominan. Dalam hal ini, aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat miskin Surabaya dalam merebut ruang kota selama kurun waktu 1900-1960 mencerminkan apa yang telah ditulis Gramsci dalam teorinya bahwa dominasi dari kelas yang berkuasa dapat dilawan dengan aksi-aksi yang bersifat spontan dan terorganisir. Perlawanan ini menjadi penting, selain sebagai upaya perlawanan terhadap dominasi kelas yang berkuasa, juga sebagai bagian dari perjuangan kelas. Dalam bukunya yang berjudul Passato a presente, Gramsci menjelaskan bahwa kelas-kelas yang tersubordinat harus memiliki kesadaran akan eksistensi dan kekuatan mereka sendiri. Kesadaran tersebut didapatkan setelah mereka sanggup mengamati dan mengevaluasi eksistensi dan kekuatan kelas yang mendominasi. Dalam hal ini, fungsi hegemonik harus dijalankan bahkan sebelum pengambilalihan kekuasaan.[1]
Pada bab 2 yang berjudul ‘Surabaya: Pusat Kemajuan di Ujung Timur Jawa,’ Basundoro menjelaskan seluk beluk Kota Surabaya dengan detil. Dari mulai demografi, penguasaan tanah dan pembagian ruang kota, pemukiman, kondisi rumah-rumah, dan masyarakat Surabaya pada awal abad ke 20 hingga tahun 1960-an. Dalam penelitiannya, Basundoro menemukan bahwa perkembangan Kota Surabaya tidak terlepas dari peran Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Timur Jawa. Selain itu, peran Kota Surabaya sebagai salah satu penghasil utama komoditas tebu pada masa itu, bersama dengan keresidenan Kediri dan Pasuruan, juga menjadi kunci dari perkembangan kota ini. Terlebih juga karena adanya pelabuhan yang memungkinkan distribusi tebu ke pasar internasional.
Pada bagian berikutnya, Basundoro menjelaskan kondisi geografis Kota Surabaya secara detil. Mulai dari batas-batas ruang Kota Surabaya, hingga asal-usul nama Surabaya. Menurut penelitiannya, sebelum tahun 1906, nama Surabaya digunakan untuk tiga kategori administrasi, yakni keresidenan, kabupaten, dan distrik, dimana distrik (kota) Surabaya merupakan ibukota Kabupaten Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1906, Kota Surabaya ditetapkan sebagai gemeente (semacam kotamadya), yang merupakan implementasi dari UU desentralisasi pada masa itu. Sejak itulah, Kota Surabaya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru yang otonom dari pemerintah pusat. Selain itu, aliran Sungai dan Kali Mas yang melewati kawasan Kota Surabaya ketika itu, menjadikan kota ini semakin penting bagi pertanian, transportasi, dan keperluan penduduk lainnya.
Dari segi demografi, penduduk Kota Surabaya sangat heterogen, terdiri atas pendatang dari Eropa, Arab, Cina, Timur Asing, dan beragam suku asal bumiputera. Struktur demografi ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, kepindahan penduduk bumiputera secara besar-besaran ke kawasan perbatasan serta merebaknya penyakit pes, menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penduduk di sana, terutama pada tahun 1907 dimana kematian mencapai 174/1000 (174 per 1000 penduduk). Berdasarkan hasil penelitian Basundoro, Kota Surabaya memang menjadi salah satu contoh penting dari kota-kota yang tidak sehat di Asia, dimana drainase (sistem pembuangan air) yang buruk menjadi kondisi paling umum yang dialami penduduk bumiputera. Namun, kenaikan penduduk akibat migrasi dari luar juga pernah terjadi terutama pada sekitar tahun 1930-an, dimana banyak pendatang dari Cina yang datang untuk bekerja di Surabaya. Di sisi lain, banyak penduduk Eropa yang meninggalkan Surabaya karena derasnya pergerakan kemerdekaan di masa itu.

Ruang di Kota Surabaya Akhir Abad 19 dan Awal Abad 20
Di bagian selanjutnya pada bab ini, Basundoro menjelaskan temuannya mengenai penguasaan dan pembagian tanah di Kota Surabaya. Pada masa kolonial, penguasaan tanah di kota yang telah ditetapkan sebagai gemeente ini dibagi menjadi tiga golongan besar, yakni oleh pemerintah pusat (gouvernement) yang penguasaannya lebih bersifat politis, oleh swasta atau pertikelir, dan oleh Gemeente Surabaya. Dalam hal ini, tanah yang dikuasai pemerintah (gouvernement) serta tanah yang dikuasai masyarakat, sebagian besar digunakan untuk membangun pemukiman-pemukiman yang tersebar di seluruh bagian Kota Surabaya. Sementara itu, tanah-tanah partikelir yang jumlahnya lebih luas dibandingkan dengan tanah-tanah yang dikuasai baik oleh pemerintah (gouvernement) maupun gemeente, digunakan untuk perkebunan tebu dan padi. Lahan-lahan tebu ini kemudian menjadi lahan pemukiman seiring dengan merosotnya produksi tebu pada akhir abad ke-19. Menurut Th. Kal, penjualan tanah di sekitar Kota Surabaya sendiri dimulai sejak Dirk van Hogendorp berkuasa di kota ini, dimana penjualan mulai meningkat pada masa kekuasaan Daendels.
Gemeente sendiri membeli tanah dari pihak ketiga, dimana tanah tersebut kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan untuk membangun pemukiman. Gubeng adalah kawasan pemukiman pertama yang dibangun oleh Gemeente. Namun, selain pemukiman, tanah-tanah gemeente juga digunakan untuk membangun kawasan industri. Di atas semua itu, penguasaan tanah oleh ketiga golongan ini membuat rakyat yang tinggal di atas tanah partikelir berstatus seperti budak. Meskipun gemeente melakukan pembelian ulang atas tanah-tanah partikelir, yang diuntungkan tetap golongan masyarakat Eropa. Di bagian berikutnya, Basundoro menjelaskan temuan antropologisnya mengenai pemukiman di Kota Surabaya. Mulai dari bentuk rumah yang ditinggali oleh penduduk kota itu, hingga arah perluasan kota yang mengikuti jalur Kali Mas. Basundoro menjelaskan, rumah-rumah di desa pertanian menyatu dengan budaya bertani para penghuninya. Arsip-arsip sejarah lain, seperti foto dan lukisan, yang ditampilkan Basundoro dalam bukunya yang kaya ini, juga menunjukkan bahwa pada awal tahun 1920-an, banyak berdiri rumah-rumah orang miskin yang dianggap tidak pantas berdiri di tengah kota. Terakhir, ia menjelaskan arti penting dari kawasan Jembatan Merah yang merupakan simbol atas beberapa hal, termasuk simbol peminggiran masyarakat bumiputera.
Rakyat Miskin Kota di Surabaya
Pada bab 3 yang berjudul ‘Kemiskinan dan Orang Miskin di Kota Surabaya,’ Basundoro menjelaskan berbagai teori mengenai kemiskinan serta menjabarkan proses terbentuknya rakyat miskin di Kota Surabaya pada awal abad ke-20. Ia menyebutkan, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan di Kota Surabaya, yakni perubahan ekologi, migrasi, serta jenis pekerjaan dan tingkat upah.
Pada awal abad ke-19, penduduk yang tinggal di atas tanah partikelir di pinggiran kota Surabaya bekerja sebagai petani. Namun, pembangunan pemukiman dan kawasan industri yang intensif hingga awal abad ke-20, menyebabkan tergusurnya lahan-lahan yang semula merupakan lahan pertanian. Hal tersebut mengakibatkan banyak penduduk yang semula hidup dari sektor pertanian terpinggirkan. Sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor utama pada masa itu. Mereka dipaksa hidup dari sektor non-pertanian dengan pengandaian penguasaan keterampilan ala Barat yang memadai. Oleh karena itu, banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Sebanyak 23.387 orang yang tinggal di atas tanah partikelir tercatat kehilangan tempat tinggalnya, sementara tanah partikelir yang berubah fungsinya terus bertambah. Penduduk yang tersingkir dan tergusur itu kemudian hidup di atas tanah-tanah partikelir yang kosong dan belum dibangun. Sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. Mereka dipaksa hidup dengan bekerja apa saja, yang bahkan tidak sesuai sama sekali dengan latar belakang sosial-kultural mereka, termasuk sebagai pekerja rumah tangga atau di sektor jasa lainnya, seperti jasa pengamanan rumah judi, penjaga malam perusahaan, buruh pelabuhan, dan lain-lain. Kelas buruh miskin telah lahir dari industrialisasi di Surabaya. Penduduk bumiputera memang selalu bekerja sebagai buruh dengan upah rendahan – dengan posisi paling tinggi sebagai mandor – karena pada masa itu pendidikan hanya bisa dijangkau oleh penduduk Eropa. Pada tahun 1930 saja, hanya sekitar tujuh persen atau 20.000 penduduk bumiputera yang dapat mengenyam pendidikan.
Pesatnya industrialisasi yang terjadi di Surabaya semenjak akhir abad ke-19, menyebabkan arus migrasi dari desa-desa ke kota ini tak bisa dihindari. Terlebih, pelabuhan Surabaya, sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Jawa, pada saat itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun 1930, sektor transportasi telah menyerap sekitar 9 persen dari jumlah total tenaga kerja di Surabaya, atau sekitar 12.582 orang. Dengan apik, Basundoro menguraikan kondisi ketenagakerjaan Surabaya pada masa itu, seperti misalnya sistem kerja di pelabuhan yang serupa dengan sistem kerja kontrak outsourcing pada masa sekarang (Ingleson,1986). Dibangunnya jalur kereta api pada masa itu kian menambah deras arus migrasi para pekerja dari daerah-daerah sekitaran Surabaya, seperti Lamongan, Sidoarjo, Gresik, dll. Mereka (para migran) ini banyak terserap di sektor industri logam dan bekerja sebagai buruh kasar.
Pada bagian berikutnya, Basundoro menjelaskan kehidupan para buruh dengan cukup detil, mulai dari upah yang mereka dapatkan (upah harian, upah bulanan) hingga kondisi kerja serta rumah-rumah yang mereka tinggali. Menurut temuannya, buruh di Surabaya pada waktu itu hidup dengan kondisi yang mengenaskan, di los-los pasar dan bahkan di atas kapal-kapal yang berada di pelabuhan. Sementara itu, penduduk bumiputera yang lain pun hidup dalam kemiskinan. Mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pedagang keliling, tukang sol sepatu, dll. Namun, bukan hanya penduduk bumiputera saja yang miskin. Para pendatang yang berasal dari etnis Cina pun banyak yang hidup dalam kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja dari perkebunan dan pertambangan di Sumatera dan Kalimantan. Hanya penduduk dari Eropa yang relatif selalu memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan penduduk bumiputera serta Cina. Kondisi tersebut diperparah pasca krisis tahun 1930 serta Perang Dunia II, dimana terjadi pemiskinan massal ketika Jepang berkuasa di Surabaya. Rakyat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pangan dan sandang mereka. Penduduk yang semula merupakan sopir atau buruh pabrik, kemudian berganti profesi menjadi tukang becak, yang mulai beroperasi di Surabaya sejak 1 Mei 1943.
Gerakan Perlawanan Rakyat Miskin Kota Surabaya
Selanjutnya, pada bab 4 yang berjudul ‘Pengambilalihan Ruang-Ruang Privat oleh Rakyat Miskin,’ dijelaskan bahwa dikuasainya tanah-tanah partikelir secara privat oleh para tuan tanah menjadi kondisi penting dari perlawanan rakyat miskin di Surabaya. Penguasaan tanah-tanah partikelir oleh segelinitir orang telah menciptakan ‘negara dalam negara,’ karena para pemilik tanah partikelir diperbolehkan membuat sistem dan aturan sendiri yang disebut dengan hak pertuanan. Tanah partikelir sendiri terbagi menjadi dua, yakni tanah landerijen yang ditujukan untuk perkebunan, serta tanah merdekan yang diberikan kepada kampung atau desa tertentu karena memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Pada bagian ini, Basundoro menjelaskan dengan rinci batas-batas dari masing-masing kepemilikan tanah partikelir ini.
Para penghuni yang tinggal di atas tanah partikelir secara perlahan mulai digusur dan dengan demikian, mulai melakukan perlawanan atasnya. Gerakan perlawanan ini datang bersamaan dengan munculnya kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat bumiputera. Hal ini menjadi pendorong kuat perjuangan dan perlawanan masyarakat dalam merebut ruang untuk bermukim sebagai hak dasar mereka. Perlawanan dan perebutan ruang dengan cara pendudukan ini dipimpin oleh beberapa tokoh dari Serikat Islam, salah satu partai politik progresif pada masa itu, yakni Prawirodiharjo dan Pak Siti alias Sadikin. Mereka berkeliling dari kampung ke kampung untuk mempropagandakan perlawanan. Tuan tanah ketakutan dan perlawanan tidak bisa dihentikan oleh polisi maupun pemerintah setempat. Mereka pun menggugat dan sidang Landraad memenangkan guagatan mereka. Namun, para penghuni tanah pertikelir menggugat balik dan memenangkan gugatan balik tersebut.
Gerakan para penghuni tanah partikelir ini menjadi gerakan perjuangan rakyat Surabaya terbesar di awal abad ke-20, yang ditandai dengan luasnya pemberitaan mengenai gerakan ini di berbagai harian pada saat itu, seperti Oetoesan Hindia. Gugatan hukum yang telah dimenangkan tak membuat penggusuran atas para penghuni tanah-tanah partikelir berhenti dilakukan. Rakyat miskin terus terusir dari tempat yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun. Kondisi mereka tinggal sangat mengenaskan dan rumah-rumah kumuh mereka yang berdiri di tengah Kota Surabaya menjadi ironi tersendiri. Di sisi lain, gemeente seringkali berpihak kepada para pemilik tanah partikelir dan memilih berhadap-hadapan dengan bumiputera.
Pengambilalihan Ruang Publik
Di bab 5 yang berjudul ‘Dari Jalan ke Makam: Penguasaan Ruang Publik oleh Rakyat Miskin,’ Basundoro menjelaskan ruang-ruang publik seperti jalan, trotoar, hingga makam yang diambil alih dan dijadikan ruang privat, termasuk tempat tinggal dan tempat berjualan. Sambil menunjukkan berbagai arsip primer berupa foto, Basundoro menunjukkan bahwa keberadaan rumah-rumah semi permanen di pinggir jalan merupakan kondisi yang umum ditemui di Kota Surabaya pada tahun 1930-an. Selain itu, rumah-rumah gubuk yang menempel di rumah orang lain, hingga pemakaman yang dijadikan tempat tinggal, merupakan kondisi yang umum ditemui di Surabaya pada waktu itu. Sementara itu, kontrol gemeente sebagai pemerintah kota yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial, terhadap pemukiman-pemukiman liar yang dibangun di jalan, dan bahkan di makam pada saat itu, ditunjukkan dengan adanya penertiban-penertiban. Kondisi kota yang bersih dari pemukiman-pemukiman rakyat miskin yang kumuh, seperti yang kita rasakan hingga kini, merupakan kehendak dari gemeente pada waktu itu.
Penggusuran Rakyat Miskin : Dari Masa ke Masa
Apa yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun-tahun 1900-1960 tersebut merupakan petunjuk penting atas apa yang terjadi pada rakyat miskin di berbagai kota di Indonesia dewasa ini. Kepemilikan tanah secara privat dan eksploitatif oleh segelintir orang, menjadi penyebab utama tergusurnya rakyat miskin dari masa ke masa. Kita dapat membandingkannya dengan masa sekarang, dimana rakyat miskin tersingkir dari ruang-ruang kota dan hanya mendapat sedikit tempat, sementara kelas atas menguasai tanah yang luas dan selalu mendapat perlindungan dari pemerintah. Pemerintah kota yang kita lihat sekarang ini, yang menghendaki kota yang bersih dari pemukiman-pemukiman liar yang kumuh pun, merupakan kelanjutan gemeente pada awal abad ke-20.
Perebutan ruang kota oleh rakyat miskin juga bukan sekedar perebutan ruang untuk tempat tinggal atau bermukim. Lebih dari itu, perebutan ruang kota merupakan perebutan akses atas alat-alat produksi, yakni tanah, yang selama ini dimiliki secara privat dan ekspolitatif oleh segelintir orang. Pesatnya pembangunan di kota-kota besar, seperti yang terjadi di era MP3EI sekarang ini, tentu berkonsekuensi pada semakin terpinggirkannya rakyat miskin dari ruang-ruang yang layak di kota, termasuk ruang-ruang publik yang semakin dihilangkan. Dalam hal ini, Harvey menjelaskan bahwa ruang dan penguasaan atasnya merupakan kunci dari akumulasi kapital. Kepentingan para pemilik modal atas ruang yang berkaitan dengan akumulasi kapital ini, secara langsung mempengaruhi kehidupan rakyat kebanyakan. Maka dari itu, perebutan ruang merupakan salah satu bagian terpenting dari perjuangan kelas.
¶
Fathimah Fildzah Izzati, Anggota Redaksi Left Book Review IndoProgress. Penulis beredar di twitterland dengan id @ffildzahizz
[1] A Pozzolini. Pijar-Pijar Pemikiran Gramsci (trans.). 2006. Yogyakarta : Resist Book. hlm. 80.