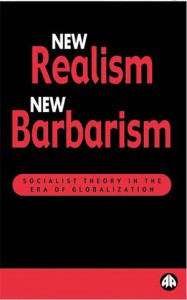New Realism, New Barbarism: Socialist Theory in the Era of Globalization. Pluto Press, London: 1999.
Twilight of Globalization: Property, State and Capitalism. Pluto Press, London: 2000.
The Return of Radicalism: Reshaping the left institutions. Pluto Press, London: 2000.
Pengantar
TRILOGI Boris Kagarlitsky dengan judul di atas adalah sebuah gedoran atas kebekuaan pemikiran yang semakin terkungkung dengan realitas politik global awal abad ke-21, dan menantang pesimisme apakah ada jalan lain di luar keyakinan ekonomi [masyarakat] pasar yang seolah menjadi ‘kenyataan tak terhindarkan’ dari sejarah abad ke-21. Keruntuhan Uni Soviet pada dekade 1980an dan munculnya Republik Rakyat Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mengadopsi sistem pasar dengan kontrol negara seperti membunyikan lonceng kematian cita-cita dan praktek politik ‘kiri’ yang menjadi marak sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Kagarlitsky adalah seorang ilmuwan sosial yang menekuni ilmu sosiologi sebagai bidang keahliannya. Ia juga seorang aktivis politik dan organiser serikat buruh yang sempat mendekam di penjara di masa kekuasaan presiden Rusia pertama pasca perestroika dan glasnot, Boris Yeltsin. Latar seperti itu menjadikan buku ini bukan sekedar sebuah pernyataan-pernyataan politik pengarangnya, tetapi juga kaya dengan nuansa analisis yang menampilkan sebab-akibat mengapa politik kiri di dunia seperti menghadapi takdir untuk menjadi salah satu cerita di museum sejarah abad ke-19 dan ke-20.
Tetapi trilogi ini juga bukan sekedar menawarkan kepada kita sebuah bentuk analisa. Ia pun hadir memberikan dorongan semangat untuk tetap meyakini bahwa ‘keyakinan’ sosialis adalah titik awal dari sebuah agenda gerakan kiri. Keyakinan tentang pentingnya pengaturan sosial terhadap cara produksi material untuk kehidupan orang banyak adalah landasan aksi yang kemudian membentuk pemikiran sosialis, bukan sebaliknya. Marx tidak harus menyelesaikan dahulu Marxisme untuk menjadikannya seorang sosialis revolusioner. Ia terlibat dan aktif sejak usia muda sampai matinya, dengan beragam jenis politik sosialis yang ada dalam masa hidupnya. Dan meskipun ia bersama sahabatnya Engels menyusun sebuah ‘sosialisme ilmiah,’ tapi itu bukan berarti keterputusan hubungan dan kerjasama dengan arus politik sosialis di Eropa pada pertengahan abad 19, dalam menciptakan masyarakat baru yang lebih adil dan manusiawi.

Buku Pertama: New Realism, New Barbarism
Kita mulai dengan buku pertama. Buku itu ditulis dan diterbitkan pada tahun 1999, bertepatan dengan periode krisis di Asia Tenggara yang dianggap sebagai Macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi cepat selama satu dekade. Di situ, Kagarlitsky menarik persoalan selama satu dekade sejak perestroika yang menghancurkan Uni Soviet, sekaligus membahas masalah-masalah yang dihadapi gerakan sosialis di Eropa sejak kemenangan Partai Buruh yang menempatkan Tony Blair sebagai Perdana Menteri, termasuk perkembangan Euro-Communism, gerakan kiri di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia setelah keruntuhan Soviet. Tidak dapat disangkal bahwa krisis yang terjadi di Asia Tenggara menjadi petunjuk tentang ‘kemerosotan standar sosial’ sekaligus pada saat yang sama kemenangan mafia liberalisme Barat di seluruh penjuru dunia. Kehancuran rejim soviet bukan saja mendiskreditkan sosialisme sebagai sebuah praktek politik, tetapi juga mendiskreditkan ideal-ideal demokrasi di berbagai tempat.
Dalam buku pertama ini, kita dihadapkan pada persoalan kerangka strategis dan rumusan teoritis dari politik sosialis di berbagai tempat. Memang tidak dapat disangkal, selama tiga dekade sejak Prancis 1968, terdapat kemajuan pesat dalam teori sosialis—termasuk kemunculan post-modernisme—di lingkungan intelektual dan akademisi dari apa yang disebut sebagai Western Marxisme. Pertumbuhan teori-teori tersebut ditujukan untuk membahas persoalan negara, kelas, partai, dan strategi politik sosialis yang kemudian banyak menghasilkan pemikir-pemikir populer di dunia. Tapi kosmopolitanisme dalam perkembangan teori sosialis harus menghadapi kenyataan bahwa disamping pertumbuhan pesat dalam teori, pada saat bersamaan pengaruh pemikiran dan aksi mereka di dalam realitas kehidupan masyarakat semakin merosot, kalau tidak semakin mandul. Mungkin ironi ini dapat dibandingkan dengan situasi di Indonesia sekarang ini, ketika para intelektual dan akademisi kampus ‘dapat menerima’ gagasan-gagasan teoritis baru dari pemikir sosialis, sebut saja Alain Badiou, tapi pada saat yang sama pembahasan teoritis gagasannya hanya dibicarakan tidak lebih dari sepuluh orang di sebuah cafe kopi atau warung makan. Dan di toko-toko buku kita bisa mendapatkan terbitan dari pemikir-pemikir klasik politik sosialis, termasuk terjemahan Das Kapital dari Marx, tetapi pada saat yang bersamaan, perkembangan sosial sama sekali tidak menunjukkan kaitan gagasan tersebut dengan problem sosial yang muncul.
Kedua, dan yang menjadi pokok pembahasan dalam bagian pertama buku ini, adalah kenyataan bahwa kemunculan politik sosialis dekade 1990an berhasil mendominasi parlemen di Eropa, tetapi pada saat yang sama agenda-agenda politik sosialis ditinggalkan oleh para politisi sosialis yang kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi realitas globalisasi dan dominasi neo-liberal di dalam negara nasional masing-masing. Sebut saja Tony Blair di Inggris, yang mengambil kepemimpinan partai buruh dengan sebuah ‘sosialisme baru,’ memperbaharui partai buruh yang ditinggalkan pengikut tradisionalnya dan memberi enerji baru dinamika politik kiri di Inggris, tetapi dengan cepat meninggalkan janji sosialisme tersebut dengan semakin meninggalkan basis massa pendukung di kalangan serikat buruh. Dalam buku pertama ini, Kagarlitsky menunjukan bahwa ‘lunturnya keyakinan sosialis’ di kalangan pemimpin justru berbanding terbalik dengan ‘meningkatnya harapan’ di kalangan buruh dan kelas menengah di Eropa tentang sebuah alternatif dari kebijakan neoliberal yang mengungkung mereka selama satu dekade.
Jadi, politik sosialis mengalami kemunduran justru ketika golongan kiri berhasil mendominasi pemilihan suara di parlemen dan sekaligus menduduki pemerintahan di Eropa seperti dalam kasus Inggris, Perancis, Italia dan Yunani. Kagarlitsky memandang bahwa persoalan mendasar dari kemunduran ini terletak pada ‘mode berpolitik’ dari golongan kiri yang tidak meyakini agenda-agenda program yang mereka buat sendiri ketika mereka justru memegang pemerintahan. Intimidasi dan dominasi neoliberal membuat mereka secara perlahan meninggalkan agenda-agenda sosialis, justru ketika mereka berada dalam pemerintahan. Kasus Islandia menjadi gambaran menarik dalam uraian Kagarlitsky, dimana negara yang paling tinggi tingkat distribusi kesejahteraannya, paling bersih dari segi lingkungan, justru dirusak oleh politisi sosialis yang membuka investasi pasar modal di dalam negeri melalui swastanisasi perbankan dengan akhir tragis berupa kehancuran perekonomian negara tersebut dalam krisis finansial 2008, seperti yang kita alami belakangan ini (belum diuraikan Kagarlitsky ketika buku tersebut diterbitkan).
Ringkasnya, masalah mendasar dari politik sosialis yang dibahas dalam buku pertama ini adalah masalah dari politisi sosialis yang berganti baju (bandingkan dengan konsep transformismo Gramsci) dan mencuci pemikiran sosialis dalam benak mereka justru setelah menjadi bagian dari politik mainstream. Seolah-olah pikiran sosialis seperti kotoran yang harus ditutupi oleh para politisi itu untuk meyakinkan rekan-rekan mereka di kalangan liberal dengan janji bahwa mereka tidak akan merusak sistem yang menciptakan kemapanan bagi para politisi sosialis tersebut. Mentalitas menghadapi real-politik seperti itu yang merusak politik sosialis dan sekaligus menciptakan persoalan-persoalan mendasar baru.
Seperti menjadi perhatian Kagarlitsky, ketika para politisi sosialis menanggalkan baju mereka, orang-orang biasa yang menjadi pendukung dari cita-cita sosialis dan agenda program yang ditawarkan terperangkap dalam kondisi tanpa alternatif. Gejala politiknya adalah dukungan yang mereka berikan terhadap gerakan politik kanan (seperti Le Pen dan British Nationalist Party dan Nader di Austria), yang mendapatkan massa pendukung dari pemilih-pemilih yang secara tradisional memberikan suara mereka kepada politisi sosialis. Jadi, meningkatnya gerakan ultra-kanan terjadi ketika massa pendukung politik kiri kehilangan kepercayaan dan harapan mereka terhadap gerakan politik yang secara tradisional mewakili mereka. Dan lebih buruk adalah ‘perang’ sebagai jalan keluar dari kondisi krisis tersebut yang memberikan massa pendukung sebuah jalan keluar bersama dan pada saat bersamaan melupakan masalah-masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini kita mendengar kembali gaung Manifesto Komunis dari Marx yang menegaskan bagaimana ‘penghancuran kekuatan-kekuatan produktif’ sebagai jalan lain dari kegagalan politik sosialis pada akhir abad 19 (dan terbukti melalui pengalaman dua kali perang pada awal abad 20 di Eropa). Begitulah tema besar dalam buku pertama tersebut.

Buku Kedua: Twilight of Globalization
Dalam buku kedua, setelah membahas disorientasi politik sosialis yang terjadi sepanjang dekade 1990an, Kagarlitsky membahas tentang masalah-masalah besar yang menjadi ciri abad 21, sebagai tantangan bagi politik sosialis. Untuk membaca buku bagian dua ini, saya akan memulai pembahasan pada pengalaman kontemporer kita di Indonesia terlebih dahulu untuk menempatkan relevansi dalam membaca buku kedua ini.
Buku kedua ini berangkat dalam semangat mempertanyakan bagaimana negara—melalui kebijakan publik—dapat mendorong terciptanya sarana dan prasarana yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik. Selama satu setengah dekade di Indonesia, tidak dapat disangkal posisi ini semakin terpinggirkan. Ada sebuah diktum yang kita ikuti bersama bahwa setelah perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) pada masa awal reformasi politik di Indonesia, negara harus mundur dari serangkaian inisiatifnya dalam bidang perekonomian. Semangat Washington Consensus dalam kaitan ini mendapat ruang gerak bebas di Indonesia, ketika pemerintah dan perekonomian nasional berada pada titik paling lemah. Privatisasi badan-badan usaha pemerintah yang menguntungkan, dan sekaligus pengurangan subsidi negara dalam sektor publik, adalah formula yang ditawarkan dalam semangat tersebut. Memang, dalam waktu beberapa tahun formula ini diyakini telah menjadi resep yang dapat mengobati kelimbungan perekonomian Indonesia.
Bagaimanapun, ada harga yang harus dibayar. Memasuki akhir tahun 2009, publik di Indonesia dikejutkan oleh sebuah vonis yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Propinsi Banten, terhadap seorang ibu dua anak bernama Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik rumah sakit Omni Internasional. Pengadilan menjatuhkan vonis denda 204 juta rupiah dan kurungan penjara terhadap ibu dua anak itu karena keluhan pribadinya yang disampaikan lewat surat elektronik kepada beberapa sahabatnya. Dalam waktu singkat, keluhan pribadi ini beredar melalui jaringan milis dan menjadi pembicaraan publik. Di sini kita mendapatkan konteks masalah yang cukup jelas. Keluhan Prita bukan keluhan individual. Ia mewakili psikologi populer kebanyakan orang di Indonesia, tentang bagaimana kualitas layanan kesehatan yang tetap rendah meskipun mereka sudah membayar mahal biaya kesehatan di rumah sakit.
Omni Internasional memandang keluhan Prita sebagai pencemaran nama baik rumah sakit tersebut. Mereka menuntut Prita. Dan pengadilan pun menjatuhkan hukuman terhadap Prita. Yang tidak disadari Omni Internasional dan Pengadilan Tinggi Banten, Prita tidak sendirian. Lebih dari sejuta orang menyatakan dukungan melalui internet. Di jalanan—dari mereka yang mengendarai mobil pribadi, anak-anak Sekolah Dasar sampai tukang becak—menunjukkan solidaritas dengan mengumpulkan ‘Koin untuk Prita’ yang jumlahnya melebihi vonis denda pengadilan. Solidaritas publik terhadap Prita adalah wujud psikologi popular yang menunjukkan rasa frustasi mereka terhadap lembaga publik yang lebih mewakili kepentingan nama baik sebuah perusahaan dibandingkan persoalan yang dihadapi orang-orang biasa dalam kehidupan mereka. Mereka frustasi dan marah bahwa lembaga publik menjatuhkan hukuman kepada pribadi Prita yang sesungguhnya mewakili keluhan publik. ‘Koin untuk Prita’ adalah perwujudan norma publik—dalam bentuknya yang spontan—ketika lembaga publik dalam pandangan masyarakat menjalankan peran tidak lebih sebagai cabang atau unit usaha sebuah perusahaan. Di sini jelas bahwa ‘keadilan publik’ telah lahir. Mereka juga ingin menghukum Omni Internasional dan Pengadilan Tinggi. Tetapi cara mereka lebih santun.
Kasus yang saya uraikan sekali lagi bersifat anekdotal. Tetapi ini adalah ilustrasi yang hidup tentang posisi publik di dalam republik ini tentang perkembangan-perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya selama satu setengah dekade berselang. Ketika kewenangan dan kemampuan negara dalam ranah publik semakin dilucuti dalam gelora reformasi politik di Indonesia, optimisme dalam bidang politik dihantui oleh rasa frustasi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat yang semakin jauh dari kekuatan yang dapat melindungi mereka. Sebuah cita-cita membangun kehidupan demokratis di Indonesia, pada akhirnya membawa pula kekuatan yang menggeser kepentingan-kepentingan publik ke dalam kepentingan organisasi privat. Tanpa terasa, prinsip-prinsip neoliberal menyusup dalam cita-cita membenahi karakter kekuasaan otoriter dan praktek birokrasi yang mewakili benang kusut kolusi, korupsi dan nepotisme dalam periode pemerintahan sebelumnya.
Para pendukung neoliberalisme—baik di dalam maupun di luar Indonesia—telah menyatakan bahwa problem terbesar yang menjadikan Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi sejak tahun 1996 sampai 1998 adalah over-birokrasi dan over-regulasi. Dalam beberapa hal, argumentasi dan pandangan ini tidak dapat dipersalahkan. Tetapi melebihi apa yang diharapkan pendukung reformasi dan gerakan demokratisasi di Indonesia, mundurnya negara dari banyak kewenangan mengurus sektor-sektor publik yang berkait dengan persoalan-persoalan ‘hajat hidup orang banyak,’ menjadi persoalan penting dalam kehidupan kita selama satu setengah dekade berselang.
Memberikan iklim lebih ramah bagi swasta untuk berkompetisi memberi ‘layanan publik’ dengan cara yang dianggap lebih efisien dan sekaligus menguntungkan dibanding pengelolaan negara, seperti sebuah hukum besi yang tidak bisa lagi ditolak. Argumentasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang rendah dalam pengalaman pemerintahan Orde Baru, menjadi salah satu alasan yang mewakili gagasan mengapa negara harus terus mundur dari campur tangan pengelolaan sektor-sektor publik di Indonesia. Biarkan mekanisme pasar yang menentukan bagaimana publik mendapatkan pemenuhan maksimal kebutuhan mereka dibanding kualitas layanan yang rendah dan fasilitas buruk dari layanan publik yang disediakan negara. Argumentasi pemikiran ekonomi liberal telah meyakini bahwa badan swasta adalah agen yang lebih baik dalam menjalankan kepentingan-kepetingan publik. Tetapi bagaimana persoalan akuntabilitas dan transparansi publik? Kasus Prita Mulyasari menunjukkan kenyataan ketika akuntabilitas dan transparansi itu dipertanyakan, mereka menjatuhkan hukuman lebih berat dibanding ketika publik mengejek dan mencemooh layanan-layanan yang diberikan negara terhadap mereka.
Sebuah ilustrasi lain untuk menutup bagian kecil ini dapat kita lihat dalam perwujudan literer yang ditulis George Orwel dalam 1984. Orwell memberikan gambaran tentang Saudara Tua (mewakili sosok negara dan birokrasi dalam sistem Uni Soviet) yang begitu berkuasa dan tidak meninggalkan pilihan pribadi dan kebebasan individual ‘saudara-saudara kecil,’ membuat mereka putus asa dan frustasi berhadapan dengan wajah birokrasi yang tidak manusiawi. Dalam pengalaman Indonesia pasca reformasi, perbandingan ini mungkin relevan. Birokrasi dan struktur negara yang diwarisi dari pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai Saudara Tua yang menakutkan dan membuat orang frustasi. Elan neoliberalisme mendapatkan kesempatan menyusup dalam semangat jiwa reformasi di Indonesia dengan mendorong pelucutan kekuasaan Saudara Tua, yang kemudiandisingkirkan seperti sosok dinosaurus dalam museum. Perencanaan publik telah digantikan dengan perencanaan privat. Tetapi, bagaimanapun pengalaman selama satu setengah dekade menunjukkan bahwa saudara-saudara kecil kita tidak juga menjadi lebih bebas dan aman, dan tetap diselimuti rasa frustasi dan kecemasan dalam kehidupan mereka.
Pendukung gagasan ini—di dalam dan luar Indonesia—memang tidak menyatakan secara verbal bahwa mereka adalah pembicara canggih yang membawa Indonesia dalam tatanan ekonomi-politik global ketika neoliberalisme adalah norma dominan. Pengalaman satu setengah dekade reformasi menunjukkan, mereka cukup berhasil. Cita-cita dan semangat reformasi tahun 1998 di Indonesia, pada akhirnya tidak lebih sekedar membuat negara mundur ke belakang digantikan kekuatan swasta—mayoritas adalah perusahaan asing atau perusahaan asing dengan mantel nasional—yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional Indonesia. Kinerja pokok ekonomi Indonesia sekarang telah diukur dengan sejauh mana pemerintah berhasil menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim yang ramah terhadap modal asing dengan sedikit mungkin regulasi yang membatasi ruang geraknya, memangkas birokasi dan terutama mengurangi campur tangan negara terhadap sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perencanaan publik diganti menjadi perencanaan swasta.
Kondisi di Indonesia seperti ini menjadi sebuah perbandingan menarik dalam membaca tulisan Kagarlitsky dalam buku keduanya. Di sini, ia menegaskan sebuah kenyataan bahwa pada saat politisi sosialis kekurangan imajinasi dan kreativitas, disibukkan dengan teori-teori yang cuma ada dalam kepala mereka, neoliberalisme dengan cepat menyusup dalam kehidupan masyarakat pada abad 21. Ketika politisi-politisi sosialis mengganti baju mereka, pada saat yang bersamaan orang-orang biasa semakin terhempas dalam kegetiran dan kesulitan hidup sehari-hari, dan ini bukan sebuah cerita dari buku teks atau sekedar angka statistik kemiskinan.
Di sini, Kagarlitsky menawarkan sebuah arahan pemikiran bahwa ketika ‘negara nasional menjadi semakin impoten,’ justru kekuatan neoliberal yang paling dapat meraih keuntungan dibandingkan kehidupan orang banyak dan termasuk juga dari agenda-agenda politisi sosialis. Bahwa ketika organisasi dan birokrasi dianggap sebagai sebuah hambatan, pemenang dari seluruh pertarungan ini adalah IMF dan Bank Dunia, termasuk organisasi-organisasi LSM yang dengan aktif mendorong ‘governance tanpa government’ demi memenuhi target dukungan dana donor bagi organisasi mereka. Organisasi-organisasi itu terus melemahkan negara nasional mereka dengan tuntutan akuntabilitas serta transparansi, dan sekaligus melempangkan jalan bagi organisasi-organisasi privat yang tidak ada sama sekali transparansi dan akuntabilitasnya kecuali kepada para pemilik saham mereka.
Ringkasnya, mengambil kembali kekuatan negara pada tingkat nasional adalah sebuah langkah strategis dalam bentuk politik sosialis di dalam lingkup globalisasi sekarang ini. Meski internasionalisasi kerja sudah terjadi, kasus buruh migran di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan pelindung bagi buruh migran Indonesia selain negara nasional mereka. Di luar itu, tidak ada yang perduli terhadap nasib mereka, dan meskipun perduli, tidak ada mekanisme yang dapat mereka ciptakan.
Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah cara merebut negara nasional itu dalam arahan politik sosialis? Sudah barang tentu ini membutuhkan dialog kita sendiri. Kagarlitsky memang tidak menawarkan apapun terhadap persoalan ini. Kita di Indonesia sesungguhnya telah diuntungkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia dari setiap pasalnya. Tidak ada satu pun pasal dalam konstitusi Republik Indonesia yang memberi dukungan kepada agenda neoliberal. Tetapi, seperti diuraikan dalam buku pertama Kagarlitsky, golongan kiri lebih cenderung berpikir dengan gagasan abstrak dalam buku-buku yang mereka baca dibandingkan melihat realitas langsung masyarakat sekeliling mereka, sebuah pemujaan buku seperti dicetuskan Mao ketika menentang arus dogmatisme dalam tubuh partainya saat itu.

Buku Ketiga: The Return of Radicalism
Dalam buku terakhir ini, Kagarlitsky mulai menjelaskan pengalaman dari strategi-strategi yang muncul dari gerakan sosialis di dunia dalam dua dekade terakhir. Persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dalam buku pertama dan kedua mendapat tempat di latar belakang dalam mengulas strategi-strategi yang muncul dalam gerakan sosialis akhir abad 20 dan awal abad 21, mulai dari gerakan Maois di Nepal, politik buruh di Indonesia, nasib COSATU di Afrika Selatan, sampai gerakan Zapatista di Amerika Latin. Dan sebuah tema dasar dari buku ini membahas tentang bagaimana ‘reshaping the left institutions’ seperti diwakili oleh organisasi serikat buruh.
Sindikalisme yang mewarnai tradisi gerakan buruh dalam dua dekade terakhir menjadi persoalan penting bagi Kagarlitsky. Bagaimana menjadikan serikat buruh sebagai institusi nasional adalah persoalan penting yang menjadi pembahasan pertama dalam buku ini. Pertama, serikat buruh telah menjadi semakin kuno dengan landasan mereka semata-mata pada industri-industri besar yang semakin kehilangan jumlah anggota dan pekerjanya (dengan masuknya komputerisasi dan robotisasi, termasuk teknologi virtual), dan pada saat yang sama muncul buruh temporer, part-time, pekerja rumahan, golongan-golongan baru dari para pekerja yang tidak masuk dalam kategori industri tradisional yang besar. Kedua, serikat buruh juga terlalu disibukkan dengan persoalan diri mereka sendiri tanpa mampu membuat kaitan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ringkasnya, ia tidak mampu menjadi sebuah agen perubahan di dalam masyarakat dan justru semakin menopang bekerjanya sistem kapitalisme.
Menjadikan organisasi buruh sebagai institusi nasional mungkin merupakan gagasan menarik yang ditawarkan Kagarlitsky. Di Indonesia kita mungkin bisa membandingkannya dengan lembaga sosial seperti pesantren yang menjadi wadah sosio-kultural-ekonomi dari para petani di pedesaan dan sekaligus membentuk watak dari orang-orang desa. Persoalannya di sini adalah bagaimana serikat buruh menjadi sebuah institusi dengan tradisi yang mengakar dalam masyarakat, bukan sekedar advokasi dan perlindungan hak-hak kaum buruh (sindikalisme dalam pandangan Kagarlitsky) dan tidak mampu berbuat banyak terhadap masalah-masalah nasional mereka.
Uraian selanjutnya adalah kritik tajam terhadap gagasan-gagasan alternatif yang lahir, mulai dari gerakan lingkungan, gerakan perempuan atau, dengan kata lain, politik identitas yang semakin mendapatkan tempat dengan merosotnya gerakan buruh sebagai basis sosial utama gerakan sosialis abad 19 dan 20. Kagarlitsky dalam ulasan ini juga menjelaskan keruwetan-keruwetan dalam cara berpikir teoritisi kiri dengan agenda sosialis mereka seperti Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau, yang menyarankan hegemoni sosialis dengan kenyataan bahwa sesungguhnya kita tidak mendapatkan apapun dari agenda hegemoni tersebut sekaligus agenda politik sosialis dalam pemikiran politik yang mereka tawarkan. Bahwa radikalisme yang mereka berikan tidak lebih dari sekedar manifestasi politik liberal dengan jargon sosialis, yang sekaligus menjelaskan mengapa mereka bisa populer dan diterima dalam lingkungan akademis karena kemandulan politik dan ideologinya. Serangan tajam juga ditujukan pada organisasi LSM yang menyuarakan advokasi serta pemberdayaan dan pada saat yang sama melemahkan politik sosialis. Kagarlitsky menguraikan ilustrasi-ilustrasi tentang kenyataan tersebut dalam lingkup global, termasuk peran LSM di dunia ketiga yang saat ini lebih terperangkap pada agenda memuluskan organisasi-organisasi privat seperti TNC (transnational corporation) di Indonesia, dengan semakin kehilangan raison d’etre dari visi dan misi yang mereka sampaikan.
Penutup
Triologi Kagarlitsky adalah sebuah bacaan inspiratif. Paling tidak, mendesakkan kepada kita di Indonesia sekarang ini untuk berpikir tentang bagaimana agenda politik sosialis dapat diterapkan.
Pertama adalah ajakannya untuk bisa lebih kreatif dalam berpikir. Kita tidak lagi bisa membaca karya-karya klasik seperti menghapal kitab suci dan merasa memiliki otoritas dalam cara seperti itu. Teoritisi kita harus mampu membedah persoalan-persoalan dalam masyarakat sesuai dengan kondisi empiris dan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan visi ideologi sosialis di dalamnya. Kedua, adalah seruannya untuk memperhatikan sebuah agenda politik ‘nasional’ sebagai titik tolak dalam melawan globalisasi yang mencengkram masyarakat dunia. Ketiga adalah sebuah tawaran keyakinan bahwa kita berjuang untuk prinsip yang kita yakini, bukan sekedar sebuah pengetahuan dalam kepala. Bahwa keadilan sosial dan kemakmuran bersama adalah sebuah prinsip, sebuah nilai dan sebuah cita-cita yang melandasi perjuangan kita dan menciptakan pemikiran-pemikiran baru dalam berbagai bidang pengetahuan, bukan sebaliknya. Dan keempat, adalah tantangan bagi kita untuk dapat mengenal lebih dalam persoalan-persoalan yang ada pada kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus bersentuhan dengan dinamikanya. Politik sosialis tidak akan berjalan hanya dalam sebuah diskursus yang dibuat di atas kertas dan dibahas dari balik meja tanpa persentuhan dengan persoalan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, termasuk dinamika politik yang terjadi.
Membaca Kagarlitsky dalam kaitan ini, mengingatkan kita bahwa Indonesia kehilangan kekuatan Jacobin yang mampu membangun national popular will seperti dipermasalahkan Gramsci dalam The Modern Prince berkait dengan masalah di Italia pada dekade 1920an.
¶
Andi Achdian, sejarawan dan editor Majalah Loka