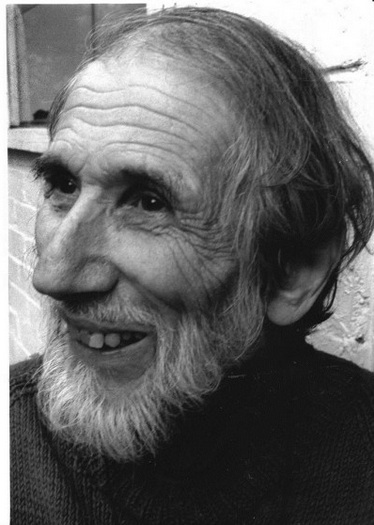BAGI para pengkaji sejarah politik Indonesia modern, nama Herbert Feith adalah salah satu yang tak bisa dilewatkan. Bukunya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, harus diletakkan di tempat teratas sebagai bacaan wajib. Di dalam buku yang memotret pasang surut demokrasi liberal itu, Feith mengkategorikan dua tipe kepemimpinan di Indonesia kala itu. Pertama, pemimpin yang bertipe solidarity-makers (penggalang solidaritas) yang berpusat pada figur Soekarno (Bung Karno). Yang kedua adalah pemimpin yang bertipe administrator yang berporos pada figur Mohamad Hatta (Bung Hatta).
Saya ingin menggunakan istilah kepemimpinan politik untuk tipe pertama dan kepemimpinan teknokratis untuk tipe kedua. Pada tipe kepemimpinan politik, para pemimpin lebih menekankan pada ide, visi, dan semangat. Kemerdekaan Indonesia diraih bukan karena orang Indonesia kala itu telah banyak yang pintar tapi, karena orang Indonesia yang sebagian besar masih bodoh memiliki semangat yang besar untuk merdeka. Semangat untuk merdeka, harga diri yang terhina akibat penjajahan, semangat untuk maju dan sejajar dengan bangsa lain yang telah maju, merupakan senjata utama untuk merdeka dan mengisi kemerdekaan. Ini tercermin dari slogan Bung Karno, revolusi belum selesai.
Sebagai dampaknya, kepemimpinan jenis ini kurang peduli pada hal-hal yang bersifat detail dan konkrit, yang justru menjadi ciri utama kepemimpinan teknokratis. Bung Karno menyindir kepemimpinan tipe administrator ini sebagai Textbook Thinking. Padahal berpikir secara metodologis, ketat pada logika ilmiah, merupakan ciri utama kepemimpinan teknokratis. Ciri lain dari kepemimpinan teknokratis adalah bagaimana ide-ide besar itu bisa diterapkan dalam lapangan praktis. Revolusi sudah selesai, demikian tutur Bung Hatta, sekarang saatnya untuk mewujudkan cita-cita revolusi dalam bentuk yang konkrit, yang riil. Misalnya, bagaimana membangun negeri yang baru merdeka itu dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, bagaimana menanggulangi kelebihan personel dalam tubuh Angkatan Bersenjata, bagaimana menanggulangi inflasi, dst.
Secara ideal, sebenarnya dua tipe kepemimpinan itu tidak terpisahkan. Sebuah pemerintahan sepatutnya dipimpin oleh mereka yang memiliki visi tentang masa depan bangsanya dan sekaligus sadar bahwa ada masalah konkrit yang harus ditanganinya dengan segera. Menyatunya dua tipe kepemimpinan ini, akan menjauhkan sebuah negara terjebak pada demagogi belaka atau sebaliknya pada kepentingan-kepentingan jangka pendek semata. Dan kita tahu, ketika duet Soekarno-Hatta masih utuh, republik yang masih muda belia itu sanggup keluar dari ujian-ujian yang tidak ringan.
Tetapi, sayangnya duet itu tak berumur panjang. Tarikan dari masing-masing kubu begitu kuat, yang sebenarnya berujung pada masalah bagaimana memajukan Indonesia. Salah satu contoh nyata dari konflik keduanya adalah bagaimana membenahi lembaga militer. Soekarno, walaupun setuju dengan tentara yang profesional, sejatinya lebih menekankan pada “bagaimana membentuk tentara yang prorakyat.” Sebaliknya, Hatta lebih menekankan pada terbentuknya “tentara yang profesional” seperti militer dalam tradisi demokrasi Barat. Pertentangan keduanya ini, secara tidak langsung berujung pada meletusnya Peristiwa 17 Oktober 1952. (Catatan: jika kedua Bapak Bangsa ini masih hidup, mereka pasti kecewa melihat bahwa TNI yang ada sekarang bukanlah militer yang pro-rakyat (ide Soekarno) atau militer yang profesional (ide Hatta)).
Sejak duet itu pecah dengan pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden, muncul preseden bahwa antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan teknokratis merupakan dua hal yang berseberangan. Para teknokrat memandang para politisi bekerja berdasarkan kepentingan ideologis dan kepentingan sempit kelompoknya. Mereka dipandu oleh loyalitas kelompok atau lebih tegas lagi pada loyalitas terhadap pemimpinnya. Sementara para politisi menuduh para teknokrat adalah orang-prang yang arogan, merasa paling menguasai masalah, tapi tak mau berkeringat untuk mewujudkan keyakinan-keyakinannya.
Celakanya, konflik antara dua tipe kepemimpinan ini tak hanya terjadi di level politik negara. Di kalangan gerakan, sebenarnya secara diam-diam terjadi konflik yang sengit antara dua tipe kepemimpinan ini. Mereka yang bertipe kepemimpinan politik, lebih dominan bergerak di lingkungan organisasi massa atau partai politik. Sementara mereka yang bertipe kepemimpinan teknokratis, umumnya bergerak di lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka yang di Ormas atau Parpol, selalu berbicara dalam tataran ideologi dan program kerja yang luas. Pertanyaan utama kelompok ini adalah, akan dibawa kemana gerakan ini, kepentingan apa yang berada di balik gerakan, dan bagaimana gerakan merealisasikan tujuan-tujuannya. Sedangkan mereka yang berkecimpung di LSM, sangat menguasai detil persoalan, mereka tidak lagi berbicara dalam tataran makro, tapi sudah menukik pada hal-hal yang mikro. Argumentasinya, kadang-kadang gerakan menang dalam hal ide tetapi ketika ide-ide besar itu hendak direalisasikan dalam kenyataan konkrit, gerakan justru menemui kegagalan yang menyakitkan. Penyebabnya, karena yang detail dan konkrit itu justru sangat dikuasai oleh rezim kapitalis-neoliberal.
Salah satu contoh konkrit konflik laten ini adalah dalam soal anti-militerisme. Mereka yang berkecimpung di Ormas atau di Partai, akan dengan sangat baik menjelaskan mengapa TNI harus dikembalikan ke barak. Mereka bisa menjelaskan dari sudut historis, politik, ekonomi dan kultural. Tapi, bagaimana konkritnya? Mereka akan menjawab, kalau kekuasaan sudah di tangan kita, maka pertanyaan soal “how to” itu pasti akan terjawab dengan sendirinya. Sementara mereka yang berkecimpung di lingkungan LSM, akan tidak puas dengan jawaban seperti itu. Mereka akan memikirkan bagaimana dampaknya secara anggaran, bagaimana mengaturnya secara konstitusional, bagaimana pembinaan personel yang sudah terbiasa bermain politik, bagaimana menghadapi arus balik dari kalangan jenderal reaksioner, bagaimana mencegah agar para politisi sipil tidak lagi menarik-narik tentara ke dalam wilayah politik.
Konflik antara dua tipe kepemimpinan ini, yang saya sebut sebagai ‘Kutuk Herbert Feith,” pelan tapi pasti menjalar semakin luas. Pasang surut kehidupan ekonomi-politik, juga turut menyumbang berkecambahnya konflik laten ini. Dan karena konflik ini bersifat abstrak, walaupun terus-menerus diupayakan untuk menjembataninya, tetap saja masih jauh dari memadai.