Artikel ini sebelumnya telah dimuat di jurnal Spectre (https://spectrejournal.com/the-evolution-of-hayat-tahrir-al-sham-and-syrias-future/). Diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan pendidikan dan pembangunan gerakan anti imperialism.
Pengantar
Pada 24 September 2025, untuk pertama kalinya seorang tokoh Islamis dengan latar salafisme keras—yang biasanya identik dengan kekerasan—berbicara di Sidang Umum PBB dan justru mendapat sambutan hangat, meskipun tetap berhati-hati, dari negara-negara Barat. Fenomena ini seperti “unjuk kekuatan Islam” yang membuat banyak orang bertanya-tanya: apa dampaknya bagi kapitalisme global, terutama setelah dua puluh tahun di mana Barat menempatkan kelompok “salafi-jihadis” sebagai musuh nomor satu? Apa yang sebenarnya berubah di Timur Tengah hingga pergeseran dramatis ini bisa terjadi? Dan apakah sistem kapitalisme global benar-benar mampu “menjinakkan” seluruh spektrum Islamisme—bahkan kelompok yang selama ini dianggap paling ekstrem dan mematikan? Untuk memahami semua itu, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana dinamika Suriah dan perkembangan salafisme membentuk peta politik baru yang memungkinkan kejutan di panggung dunia tersebut.
Empat belas tahun setelah rakyat bangkit melawan rezim Assad yang brutal, pemimpin baru Suriah datang dengan janji membangun negara yang sepenuhnya berbeda dari rezim yang tumbang. Para pemimpin Barat memang tidak sepenuhnya bersemangat, tetapi ada kesan umum bahwa “tidak ada pilihan lain,” sehingga mereka mau tak mau bekerja sama “sejauh pemerintahan al-Sharaa terus menunjukkan komitmen pada integrasi, kesetaraan, dan perdamaian di seluruh negeri.”[1] Meski begitu, jejak lama rezim Baath masih tampak jelas dalam pemerintahan baru, walaupun ada beberapa titik kemungkinan perubahan. Suriah tetap menyebut dirinya “republik Arab,” padahal label itu mengabaikan keragaman etnis yang nyata di negara tersebut. Di sisi lain, konstitusi sementara kini menetapkan fiqh Islam (Islamic jurisprudence) sebagai “sumber utama legislasi,” sebuah sinyal kuat bahwa Suriah bergerak menuju bentuk republik Islam.[2] Arah Islamisasi ini memang belum bisa diprediksi secara pasti, tetapi rangkaian tragedi sektarian—mulai dari pembantaian di wilayah pesisir Suriah hingga kekerasan di Suwayda—memberi tanda bahwa jenis Islamisme tertentu kini tengah berada di atas angin.
Hambatan dalam akumulasi kapital dan persaingan antar kekuatan imperialis kerap membuat para penguasa imperium dan kelas-kelas penguasa lokal memilih strategi “pecah belah dan kuasai” berbasis etnis, sektarianisme, atau identitas lain. Logika ini juga terlihat dalam gelombang kekerasan agama dan etnis pada 2025.[3] Namun, yang membuat situasi sekarang terasa berbeda adalah banyaknya aktor—dan tingkat kekerasan yang mereka siap gunakan—untuk memaksakan pembelahan tersebut. Ini tidak bisa dipahami tanpa menelusuri dinamika rumit gerakan politik-keagamaan. Dengan kata lain, ledakan kekerasan massal tidak hanya dipicu oleh pola akumulasi kapital dan efek lokal dari dinamika sistem dunia, tetapi juga oleh perkembangan internal berbagai gerakan itu sendiri.[4]
Untuk memahami bagaimana kemenangan al-Sharaa akan membentuk hubungan Suriah baru dengan para pemain global dan regional, kita perlu melihat lebih tepat konteks munculnya varian Salafisme yang lebih keras. Di antara negara-negara Sunni, ada dua kekuatan yang kini bersaing memengaruhi arah transisi Suriah. Pertama adalah Turki, yang sempat—meski agak dibesar-besarkan Trump— pada awalnya dipuji sebagai pihak yang memungkinkan HTS (Hay’at Tahrir al-Sham) mengambil alih Damaskus.[5] Peran mediasi Turki sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global dan kawasan, tetapi sekaligus membawa banyak dilema bagi para hegemon dunia. Dari sudut pandang geopolitik luas, pertanyaannya adalah: seberapa jauh pemerintah Turki yang dipimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mampu mengarahkan proses politik di Suriah? Dan apakah HTS—yang kini menjadi aktor berkuasa di Suriah—dapat diarahkan mengikuti jalur politik yang kurang lebih paralel dengan AKP? AKP sendiri berhasil menjinakkan Islamisme bergaya Ikhwanul Muslimin dengan memasukkannya ke dalam struktur negara Turki dan tatanan dunia yang menopangnya. Pertanyaannya sekarang: bisakah kemitraan HTS–AKP melakukan hal serupa terhadap varian salafisme yang lebih keras, dan memasukkannya ke dalam tatanan global yang ada?
Arab Saudi kini bersaing dengan Turki, baik dalam menentukan arah ideologis rezim baru Suriah maupun dalam memperebutkan akses ke sumber daya dan pasar negara itu. Meski Saudi tampak keluar sebagai pemenang sementara setelah kunjungan Trump ke Timur Tengah pada pertengahan Mei, kerajaan ini justru menghadapi dilema yang tidak mudah. Di satu sisi, meningkatnya pengaruh monarki Teluk di Suriah bisa memberi Saudi keunggulan atas Turki. Namun di sisi lain, kedekatan mereka dengan Amerika Serikat serta struktur ekonomi politik mereka sendiri membuat ruang manuver Saudi tetap terbatas—setidaknya untuk sekarang. Ditambah lagi, sejarah panjang Saudi dengan salafisme membuat peta pertarungan ini semakin rumit dan penuh nuansa.
Meski tidak bisa dilihat sebagai dua kubu yang sepenuhnya terpisah, AKP dan HTS berakar pada tradisi yang berbeda dan kerap bersaing: yang satu datang dari model partai Islam berbasis massa ala Ikhwanul Muslimin, sementara yang lainnya tumbuh dari tradisi salafisme. Satu dianggap lebih “moderat,” yang lain lebih kental dengan sektarianisme. Namun pada praktiknya, keduanya sama-sama punya relasi yang tegang dengan kelompok minoritas maupun kekuatan global. Kedua kekuatan ini juga kadang saling bertransformasi, dan pembalikan proses tersebut selalu mungkin, seperti yang terlihat jelas selama dekade terakhir di Suriah. Selain itu, hubungan keduanya dengan tradisi Islamisasi top-down ala Saudi (dan lebih luas lagi, negara-negara Teluk) juga dipenuhi dengan kontradiksi.
Turki dan para sekutunya menginginkan sebuah pemerintahan Islamis di Suriah yang tetap bisa “dikendalikan”, sebuah pemerintahan yang bisa berdamai dengan Israel dan Amerika Serikat, terhubung rapi dengan pasar global serta kapital Turki dan Barat, dan hanya menerapkan tingkat penindasan terbatas terhadap kelompok non-Sunni. Pertanyaannya, apa tanda-tanda bahwa HTS mampu mewujudkan skenario semacam itu? Seberapa jauh HTS dapat menjalankan agenda salafi mereka sendiri jika berhasil berkuasa dengan stabil? Dan jika sudah benar-benar mapan, apakah mereka bisa saja suatu hari berbalik menentang kepentingan Turki, Israel, atau Amerika Serikat? Singkatnya: Bisakah kapitalisme global ”menjinakkan” varian keras dari salafisme ini?
Transformasi Islamisme
Selama lebih dari lima puluh tahun sejak kemunculannya pada 1920-an, Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Islam) asal Mesir telah menjadi sumber inspirasi utama bagi berbagai gerakan Islam di seluruh dunia. Dengan jaringan sosial dan amal yang luas, struktur kader rahasia, jaringan bisnis, program pendidikan informal yang masif, koalisi lintas kelas, hingga pelatihan paramiliter, pola organisasi Ikhwanul Muslimin diadopsi secara luas sebagai model untuk membangun mobilisasi Islam berskala besar.[6]
Namun, dari dekade ke dekade, berbagai strategi yang dicoba oleh kelompok-kelompok yang meniru Ikhwanul Muslimin ternyata tidak membuahkan hasil. Baik bekerja secara bawah tanah, berkompromi dengan rezim otoriter, ikut pemilu, mengangkat senjata, maupun mencoba jalur-jalur lain, semuanya berakhir dengan capaian yang jauh dari harapan.[7] Memang, mereka punya andil dalam proses Islamisasi sosial secara bertahap, tetapi tidak satu pun berhasil meraih dan mempertahankan kekuasaan politik yang stabil dan tahan lama.[8] Tahun 1980-an dan 1990-an bahkan menjadi periode paling suram: Ikhwanul Muslimin di Mesir mengalami pelemahan dan akhirnya dihancurkan, Ennahda di Tunisia ditekan habis-habisan, sementara di Aljazair rezim memaksa kelompok Islamis terjebak ke dalam perang saudara.[9]
Satu-satunya pengecualian atas rangkaian kegagalan itu justru datang dari Turki—melalui AKP, yang ironisnya muncul di luar dunia Arab dan bergerak dalam kerangka yang cukup “sekuler.” Keberhasilan AKP sempat membangkitkan optimisme, tetapi pada akhirnya membuat banyak kalangan Islamis di berbagai negara merasa kecewa. AKP tidak pernah menempatkan penegakan syariah sebagai agenda utama. Padahal, hukum Islam merupakan titik temu penting antara Islamis salafi dan Islamis berbasis massa. Bahkan partai-partai pendahulu AKP yang lebih religius pun tidak menjadikannya prioritas. Selain itu, AKP juga gagal memenuhi salah satu cita-cita sentral Islamisme global: menghadirkan Islam sebagai “jalan ketiga” yang berbeda dari Barat (kapitalisme liberal) maupun Timur (sosialisme negara). Ketika proyek alternatif itu runtuh, banyak orang akhirnya melihat AKP tak berbeda lagi dari kubu Barat yang dulu mereka klaim ingin tandingi.
Secara keseluruhan, AKP mulai kehilangan energi ideologisnya ketika semakin larut dalam tatanan kapitalisme sekuler. Salah satu tanda meredupnya semangat itu adalah menghilangnya debat teologis yang dulu sangat hidup di Turki. Pada 1970–1990-an, perdebatan antara Salafi, Sunni tradisional, Islamis modernis, dan kelompok lain menjadi bagian penting dari perkembangan—dan juga konflik internal—gerakan Islamis. Memasuki 2000-an, isu utamanya bergeser menjadi apakah teologi modernis (baik yang liberal maupun konservatif) bisa diselaraskan dengan tradisi Sunni yang lebih klasik, yang dianut para aktivis, ulama, dan pemimpin spiritual. Selain itu, muncul juga pertanyaan tentang bagaimana menghadapi tantangan salafi dan memasukkannya ke dalam kerangka ideologis yang lebih besar. Sepanjang sejarahnya, baik Ikhwanul Muslimin Mesir maupun gerakan serupa seperti AKP tidak berupaya menyeragamkan teologi Sunni. Berbeda dari kaum Salafi yang ingin memurnikan akidah, kelompok-kelompok ini lebih bertujuan memperkuat identitas Sunni dalam segala variasinya—utamanya menghadapi kelompok sekular, dan kedua menghadapi komunitas non-Sunni. Selama masih ada semangat kebangkitan spiritual yang kuat dalam gerakan, keragaman teologis bukan masalah; bahkan ruang longgar itu memungkinkan aktivitas dakwah salafi dan para figur religius yang lebih tidak konvensional untuk ikut bergerak di pinggiran gerakan.[10] Namun ketika dimensi spiritual dan perdebatan teologis mulai merosot di tahun 2010-an—karena semakin dipakai sekadar sebagai alat konsolidasi negara dan ekspansi bisnis global—kelonggaran itu berubah menjadi “bukti” bahwa Ikhwanul Muslimin dan gerakan serupa sudah melemah. Sebaliknya, salafisme global justru memperkuat budaya debat internal dan meningkatkan kemampuan organisasinya, meski tetap sering terkendala oleh perpecahan yang tak kunjung selesai.
Bahkan sebelum salafisme mengalami “masa keemasan” dalam beberapa tahun terakhir, kekecewaan terhadap jalur Ikhwanul Muslimin sudah melahirkan berbagai pecahan. Terinspirasi oleh tokoh yang kemudian dieksekusi, Sayyid Qutb, dan figur-figur lainnya, sebagian Islamis mulai membentuk kelompok-kelompok kecil yang fokus pada aksi kekerasan, bukan pada pembangunan gerakan massa.[11] Gerakan-gerakan inilah yang kemudian dikenal sebagai “jihadis” atau “salafi-jihadis,” merujuk pada teologi puritan yang menekankan peneladanan tiga generasi awal umat Islam. Yang sebenarnya baru di sini bukanlah salafisme itu sendiri, melainkan keputusan untuk menjadikan kekerasan sebagai strategi utama mereka.
Berbagai aliran pemikiran salafi telah ada selama berabad-abad dan mengambil banyak bentuk organisasi, mulai dari puritanisme keagamaan dan sektarian Ibn Taymiyya, melalui Islamisasi puritan top-down Wahhab (yang menjadi ideologi resmi Arab Saudi), hingga salafisme progresif intelektual modernis seperti Muhammad Iqbal. Bentuk-bentuk lain dari “sensibilitas” salafi yang tidak terorganisir secara khusus juga telah tersebar luas. Memang, seruan untuk kembali ke akar Islam dan memutus hubungan dengan agama tradisional yang dipelajari dari orang tua dan imam yang disetujui pemerintah, kadang-kadang menggerakkan aktivisme akar rumput partai-partai dalam garis Ikhwanul Muslimin.
Apa yang kemudian disebut “salafi-jihadisme” berbeda dari tradisi salafi sebelumnya bukan hanya karena memberi porsi jauh lebih besar pada kekerasan, yang dulu sebenarnya hanya memainkan peran kecil dalam pemikiran salafi, tetapi juga karena pola organisasinya yang mudah terpecah, bergerak seperti kelompok inti kecil perjuangan, dan tersusun dalam sel-sel rahasia. Banyak arus salafisme kontemporer juga mengkritik Wahhabisme dan tradisi terkait karena dianggap tidak cukup tegas dalam menolak fiqih dan teologi Islam yang berkembang setelah tiga generasi pertama. Pendanaan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk memang memperkuat dorongan puritan ini, tetapi sekaligus menimbulkan efek samping: secara perlahan meruntuhkan legitimasi politik dan spiritual kerajaan-kerajaan itu sendiri.
Pada awal kemunculannya, kelompok-kelompok pecahan yang memilih jalur kekerasan ini tidak punya agenda politik yang jelas. Mereka tampak reaktif, defensif, dan hampir tidak memiliki visi positif yang dapat dijual secara luas. Mereka menganggap aksi-aksi pembunuhan tokoh berkuasa, seperti Presiden Mesir Anwar Sadat, serta serangan yang menewaskan tentara Amerika. Bahkan ketika sebagian kelompok Islamis bersenjata berhasil meraih dukungan luas, mereka tetap mengalami kebuntuan politik. Misalnya, Taliban memang tumbuh pesat berkat dukungan Amerika dan negara-negara Teluk serta sentimen anti-Soviet, tetapi ketika akhirnya berkuasa mereka tidak memiliki kemampuan maupun kesiapan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.”
Gerakan-gerakan Islam lain yang mengandalkan kekuatan militer tidak boleh disamakan begitu saja dengan versi salafisme yang mengedepankan kekerasan. Hamas dan Hezbollah, misalnya, sangat berbeda dari segi organisasi maupun teologi. Walau keduanya membangun kekuatan lewat kemampuan tempur, mereka secara serius menggarap layanan sosial, sesuatu yang tidak mengherankan, mengingat Hamas berakar pada tradisi Ikhwanul Muslimin Palestina. Hezbollah juga memiliki ruang lebih besar untuk membangun jaringan bisnis dan berintegrasi dengan negara Lebanon, tetapi tetap terisolasi dan kurang punya daya tarik ideologis di dunia Islam yang lebih luas, terutama karena identitas Syiahnya.[12] Singkatnya, karena lahir dari konteks yang sangat khas, baik Hamas maupun Hezbollah tidak dapat dijadikan model yang bisa direplikasi oleh gerakan Islam lainnya.
Kondisi ini menjadikan al-Qaeda sebagai tandingan utama jalur Ikhwanul Muslimin. Selama beberapa dekade, al-Qaeda membentuk versi paling jelas dari kecenderungan ideologis dan organisasi yang “anti-Ikhwan.” Yang terpenting, mereka melangkah jauh melampaui kondisi sebelumnya, di mana ada salafi yang kebetulan memakai kekerasan atau kelompok bersenjata yang kebetulan berakar pada salafisme. Al-Qaeda memadukan secara tegas jihad bersenjata, puritanisme teologis, praktik takfir (menganggap pihak lain sebagai kafir dengan konsekuensi kekerasan), serta ambisi mendirikan kekhalifahan lintas negara.[13] Di sisi lain, salafisme tetap memiliki arus besar yang tidak masuk kategori “salafi-jihadi,” yang biasanya dibagi para peneliti ke dalam dua kelompok besar, yakni salafi quietist yang menjauhi keterlibatan politik praktis dan perjuangan bersenjata dan salafi politik—meskipun batas di antara keduanya terus berubah dan kerap diperdebatkan.[14]
Walaupun dunia Salafi global sangat beragam, al-Qaeda dan jaringan afiliasinya muncul sebagai sebuah “model” yang bisa dipindahkan ke hampir semua konteks. Dalam hal ini, mereka menjadi tandingan paling menonjol dari model Ikhwanul Muslimin dalam menggerakkan mobilisasi Islam. Penekanan kelompok salafi bersenjata—yang mirip gaya Protestan—pada hubungan langsung antara individu dan pesan Tuhan semakin menguat, pertama oleh budaya pasca-1980-an yang makin individualistis dan terisolasi, lalu oleh internet dan media sosial. Meski strategi mereka brutal, tuntutan puritanisme salafi terhadap para rekrutan terasa menggoda bagi sebagian anak muda yang hidup di dunia abad ke-21: sebuah konteks yang justru membuat jalur “pelan dan bertahap” ala Ikhwanul Muslimin tampak kurang menarik dan tidak memicu adrenalin. Namun tetap ada batas-batas yang tidak dapat ditembus oleh salafisme kekerasan dalam bentuknya yang paling eksklusif dan murni.
Dengan struktur sel yang ketat dan puritanisme ekstrim, al-Qaeda mampu merusak banyak musuh—yang mereka definisikan sangat luas. Tetapi ketika harus membangun sesuatu, bukan menghancurkan, ambisi mereka mendirikan kekhalifahan global tanpa terikat wilayah jelas-jelas masuk wilayah fantasi. Tanpa institusi geografis dan politik yang stabil, al-Qaeda dan kelompok sejenis justru menyulut respons imperialis Amerika dalam skala besar, mendorong kedua pihak ke dalam siklus pembunuhan dan pembalasan yang tak terkendali lintas dunia.

Salafisme dan Bentuk Negara
Dari periode 1990-an hingga serangan 11 September, kekerasan dan aksi balas dendam terjadi secara sporadis, ketimbang meluas melampaui batas-batas teritorial negara dan Kawasan . Namun, 9/11 memberi kaum neokonservatif kesempatan untuk mengubah aturan main. Dengan menyerang Afghanistan lalu Irak, mereka meninggalkan basa-basi liberal tentang moralitas dan hukum internasional, dan beralih ke praktik ekstraksi kekayaan yang lebih terang-terangan.
Tetapi “kemenangan” Amerika di awal abad ke-21 ternyata semu. Serangan neokonservatif memang berhasil mengekstrak sumber daya dan memperkaya oligarki Barat, tetapi gagal menghasilkan pemerintahan pro-Barat yang stabil dan tahan lama—baik di Afghanistan maupun Irak. Lebih buruk lagi, kekacauan yang ditinggalkan justru memperdalam kemarahan publik terhadap para diktator lokal, yang kebanyakan bekerja sama dalam invasi dan proses ekstraksi tersebut.
Ketika Arab Spring meletus, negara-negara Barat melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya, dengan Turki berperan sebagai proxy mereka.[15] Pada 2010–11, para liberal Barat salah membaca karakter rezim Turki, menganggapnya tengah bergerak menuju demokrasi liberal. AKP pun ikut memainkan peran itu, mencoba mengekspor “model Turki,” terutama ke negara-negara yang punya tradisi Ikhwanul Muslimin kuat seperti Suriah, Mesir, dan Tunisia. Di bawah Ahmet Davutoğlu, arsitek kebijakan luar negeri AKP,strategi ekspor ini menghindari agresi langsung dan lebih mengandalkan diplomasi, bisnis, serta kolaborasi politik.
Kegagalan proyek ekspor inilah yang menjadi titik balik bagi Turki dan kawasan. AKP kemudian meninggalkan pendekatan “soft power” dan mulai bersaing sekaligus bekerja sama dengan Arab Saudi dan monarki Teluk dalam mempersenjatai kelompok Islamis. Qatar mendukung Jabhat al-Nusra, sementara Arab Saudi memihak aliran salafi lain seperti Jaysh al-Islam. Pada saat AKP bergerak mendekati lingkaran salafisme bersenjata, kelompok-kelompok salafi bersenjata sendiri justru makin terhubung dengan inti kekuasaan lokal. Contohnya, berbagai cabang al-Qaeda bergabung dengan mantan jenderal dan perwira Saddam Hussein untuk membentuk ISI, yang kemudian berkembang menjadi ISIS. Ketika aliansi itu berubah menjadi sebuah penggabungan penuh, lahirlah sebuah era baru di dunia Arab.
ISIS memang sama-sama puritan dan sebagian besar transnasional seperti al-Qaeda. Namun, berbeda dari al-Qaeda yang menolak konsep negara, ISIS justru melampaui sikap antistatis itu. Meski masih menyimpan ambisi lintas wilayah, ISIS menerima gagasan teritorial yang lebih konkret—terlihat jelas dari namanya: mereka ingin membangun negara Islam di Irak dan Suriah (meski fokus wilayah dan nama organisasi terus berubah), sebagai langkah menuju proyek kekhalifahan global. Ada banyak indikasi bahwa ISIS jauh lebih cepat daripada Taliban atau kelompok salafi bersenjata sebelumnya dalam membangun kembali infrastruktur serta menyediakan layanan sosial di daerah yang mereka kuasai. Singkatnya, kelompok salafi bersenjata mulai belajar bagaimana menjalankan pemerintahan.

Peningkatan Rivalitas Antarkekaisaran, AKP Baru, dan Rezim Salman
Seiring runtuhnya “Erdoğanisme 1.0” selama Arab Spring dan meningkatnya persaingan antarkekuatan besar, Turki terdorong makin jauh bekerja sama dengan kelompok salafi bersenjata. Di saat yang sama, kegagalan berulang imperialisme Barat membuka jalan bagi Rusia untuk masuk lebih dalam ke Timur Tengah. Kehadiran Moskow yang semakin besar kemudian turut memperkuat ambisi Iran. Iran menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari kegagalan Amerika Serikat di Irak dan kawasan sekitarnya. Meski Irak dilemahkan oleh sistem pembagian kekuasaan federal dan kehadiran militer AS yang masih berlanjut, kekuatan politik Syiah yang semakin dominan membantu memperluas pengaruh Teheran. Amerika memang bekerja sama dengan pemerintahan Syiah di Irak, tetapi tetap tidak mampu menahan laju pengaruh Iran seperti yang mereka inginkan. Aktor-aktor lain yang berada di orbit Iran juga memperbesar jangkauan mereka—seperti di Lebanon dan Yaman—selama tahun 2000-an dan 2010-an. Pada akhirnya, sama seperti Amerika Serikat, berbagai kekuatan imperialis dan sub-imperialis ini gagal menanamkan proxy atau sekutu lokal mereka menjadi penguasa yang stabil dan bertahan lama.
Di tengah kekacauan kawasan, bisnis Turki dan jaringan militer-intelijennya justru mengalami lonjakan pengaruh. Irak menjadi salah satu pusat utama ekspansi kapital Turki, didukung oleh hubungan yang makin erat antara Ankara dan para pemimpin suku Kurdi yang berseteru dengan PKK (Partai Pekerja Kurdistan). Turki telah berperang melawan PKK selama lebih dari empat dekade. Meski basis sosial gerilya PKK berada di Turki, pengaruh mereka menyebar ke seluruh wilayah Kurdistan. Di sisi lain, keluarga Barzani—klan Kurdi yang pernah menjadi sekutu Amerika Serikat pada era Perang Dingin dan kini dekat dengan Israel—muncul sebagai pemain kunci dalam blok Kurdi yang condong ke Ankara. Pasukan Barzani, yang sudah lama bekerja sama dengan Turki, kini mengontrol wilayah Kurdi semi-negara di Irak federatif dan membuka pintu bagi bisnis Turki. Namun, Arab Spring juga memunculkan Rojava, wilayah otonom Kurdi di Suriah. Bagi banyak orang di Turki, kemunculan Rojava tidak sekadar perkembangan politik regional,melainkan ancaman eksistensial.
Meningkatnya peluang dan ancaman di kawasan membuat aparatur intelijen dan diplomasi Turki berubah arah. Selama puluhan tahun, struktur “negara dalam negara” di Turki dibentuk oleh nasionalisme Mustafa Kemal yang tidak ekspansionis—meskipun tetap anti-Kurdi—dan selalu memandang curiga gagasan neo-Ottomanisme ala Davutoğlu. Ada beberapa pengecualian, misalnya ambisi “imperialisme lunak” Turki di Asia Tengah yang digerakkan kelompok neofasis seperti Grey Wolves atau MHP (Nationalist Action Party) dalam institusi-institusi resmi setelah 1970, dan tetap disokong sebagian kalangan Kemalis. Namun, ekspansionisme ke Timur Tengah selama ini merupakan batas yang tidak pernah mereka lewati.
Ketika Erdoğan mencari sekutu untuk melawan proxy Amerika di dalam koalisinya sendiri—yaitu jaringan Gülen—ia semakin mendekat kepada Kemalis kanan dan Grey Wolves sepanjang 2010-an. Kudeta oleh kelompok Gülen pada 2016 dan koalisi AKP-MHP yang lahir setelah kudeta balasan hanyalah puncak dari proses panjang ini. Para pendukung Erdoğan tidak hanya mengadopsi bentuk Islamisme yang lebih agresif dan berorientasi imperium, tetapi juga membawa kembali para Kemalis pro-kudeta ke dalam tubuh militer. Hasilnya, terbentuklah koalisi besar antara Islamis, Kemalis sayap kanan yang kini berbau ekspansionis, dan Grey Wolves. Melampaui seluruh preseden sebelumnya, “negara dalam negara” yang telah direkonstruksi ini kini siap unjuk kekuatan militer di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Perkembangan ini juga meredakan krisis akumulasi di Turki. AKP mengikuti pendekatan yang relatif lebih “neoliberal” dan (sepertinya) tidak campur tangan pada 2000-an. Namun, bahkan pada dekade ini, pemerintah menyeimbangkan neoliberalisme dengan kebijakan negara kesejahteraan yang ditargetkan dan lembaga amal semi-resmi yang terhubung dengan AKP. Namun, setelah perlambatan aliran dana global pasca-2008, baik kpendekatan kesejahteraan maupun amal tidak lagi mencukupi; kebijakan pro-pasar mulai secara terbuka merugikan basis pemilih AKP sendiri. Sebagai respons, AKP menjadi semakin bergerak ke arah “kapitalis negara” pada 2010-an. Keterlibatan negara yang intensif dalam ekonomi, termasuk kampanye reindustrialisasi dan re-unionisasi yang dipimpin pemerintah, berjalan seiring dengan militerisasi pada dekade tersebut dan membantu meningkatkan lapangan kerja, setidaknya hingga “belokan ekonomi ortodoks” pada Juni 2023. Meskipun liku-liku ini tidak menciptakan jalur yang berkelanjutan, mereka tetap memperkuat kesejahteraan rakyat, investasi emosional rakyat dalam perluasan kontrol Turki atas wilayah tersebut, dan karenanya (kadang-kadang militan) dukungan rakyat terhadap pemerintah.[16]
Namun, Turki tetap menjadi pesaing tangguh dalam perebutan pengaruh atas Islamisme di kawasan. Di sisi lain, monarki Teluk—dipimpin Arab Saudi—melihat diri mereka sebagai penguasa sah dunia Arab dan Islam. Meski kekuatan mereka bertumpu pada minyak, ekonomi Teluk tidak pernah sekadar “ekonomi rente.” Justru, semakin dalamnya integrasi mereka ke dalam kapitalisme global selama beberapa dekade terakhir menciptakan tekanan sekaligus peluang baru. Di bawah kepemimpinan Raja Salman, Arab Saudi berusaha menjawab tantangan ini melalui reformasi ekonomi-politik di dalam negeri dan langkah-langkah ekspansionis di arena internasional.
Selama kurang lebih dua dekade, Arab Saudi berharap bahwa proyek-proyek raksasa infrastruktur dan konstruksi dapat mendiversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan melemahkan praktik kapitalisme kroni.[17] Namun, gebrakan pembangunan itu tidak pernah menghasilkan lonjakan pertumbuhan PDB seperti yang terjadi di Turki—apalagi memenuhi ambisi besar yang dibayangkan.[18] Ketika harapan pada sektor ini memudar, Saudi—dan kemudian monarki-monarki Teluk lainnya—beralih ke strategi baru: menjadikan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih sebagai fondasi masa depan pasca-minyak mereka.[19] Untuk mengejar ambisi tersebut, mereka menjalin kerja sama erat dengan Tiongkok, langkah yang akhirnya mendorong pemerintahan Biden membatasi secara ketat penjualan teknologi AS ke negara-negara Teluk.
Jika upaya diversifikasi ekonomi dalam negeri belum berjalan sesuai harapan Salman, cerita berbeda terjadi pada sektor finansial dan upaya mengonsolidasikan pengaruh regional. Secara umum, monarki-monarki Teluk berhasil mengalihkan surplus minyak mereka untuk membangun sektor perbankan dan layanan keuangan, bahkan mempercepat proses itu lewat reinterpretasi fiqh.[20] Transformasi finansial ini semakin mengglobal setelah bubarnya Uni Soviet.[21] Kini, bank-bank Teluk mengendalikan sebagian besar arus kapital di Timur Tengah. Akibatnya, setiap konflik atau perubahan batas wilayah di kawasan justru membuka kesempatan bagi Saudi dan monarki Teluk lainnya untuk memperluas kekuatan finansial mereka—sekalian meredakan berbagai kontradiksi dalam perjalanan panjang menuju ekonomi domestik yang tidak lagi bergantung pada minyak.
Tekanan dan peluang yang tumpang tindih ini, ditambah dengan ideologi Wahhabi, mendorong Arab Saudi dan sekutunya untuk bermain api di kawasan. Mereka secara selektif mempersenjatai dan mendukung kelompok-kelompok salafi, tanpa terlalu peduli bahwa ideologi dan senjata kelompok-kelompok ini pada akhirnya bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan mereka sendiri.

HTS dan al-Jolani
HTS menjadi aktor utama dalam proses “menjinakkan” serta mem-mainstream-kan bentuk salafisme kekerasan, sekaligus mendorong “nasionalisasi” agenda salafi bersenjata—sebuah proyek yang rumit karena di kubu HTS sendiri terdapat banyak pejuang internasional. Garis politik baru ini lahir dari proses transformasi internal yang penuh gejolak. HTS dibentuk pada 2017 oleh sosok yang dikenal sebagai “al-Jolani”—nama perang dari al-Sharaa, seorang warga Suriah keturunan Dataran Tinggi Golan yang lahir di Riyadh pada 1982 dan besar di Damaskus. Ia bergabung dengan al-Qaeda pada 2003 dan ikut bertempur di cabangnya di Irak. Setelah ditahan Amerika Serikat antara 2006 dan 2011, ia kembali ke Suriah pada 2012 dan mendirikan Jabhat al-Nusra, cabang al-Qaeda di negara tersebut.
Al-Jolani adalah seorang ahli strategi yang sangat cerdik, tetapi tidak terpaku pada satu pola strategi saja. Pada 2013–2015, ia tampil sebagai salah satu figur paling pragmatis di antara kelompok salafi bersenjata—lebih mau berkoalisi, baik dengan kelompok salafi lain maupun kelompok non-salafi, dan mampu memadukan agenda purifikasi Islam global dengan semangat revolusi demokratis Suriah. Namun, di tahun-tahun berikutnya ia perlahan kembali pada puritanisme lamanya. HTS, yang dibentuk pada 2017 melalui penggabungan berbagai kelompok Islamis di bawah kepemimpinan al-Nusra, mula-mula membedakan diri dari pesaing-pesaing salafi dan Islamis lainnya lewat kekejamannya. Meski begitu, al-Jolani terus bergerak zig-zag dalam strategi: kadang mengadopsi pendekatan pragmatis di waktu dan wilayah tertentu, lalu kembali bersikap puritan, kemudian balik lagi ke pragmatisme.
Sebelum al-Jolani masuk ke gelanggang, al-Qaeda hanya hadir sebagai kekuatan “perlawanan” di Suriah—mengikuti pola lama yang tidak membangun institusi—sementara ISIS (yang awalnya ISI ketika masih berafiliasi dengan al-Qaeda) justru menguasai wilayah-wilayah di Suriah dan Irak. Kehadiran Jabhat al-Nusra mengubah seluruh peta ini. ISI, dan kemudian ISIS, memosisikan diri sebagai musuh sekaligus bagi rezim Assad dan revolusi Suriah. Sebaliknya, Jabhat al-Nusra cenderung tampil sebagai sekutu revolusi, meskipun pada beberapa momen dan wilayah ia pernah bekerja sama dengan ISIS.[22] Saat FSA (Tentara Pembebasan Suriah) dan kelompok-kelompok lain memukul mundur ISIS hingga mereka terkunci di Raqqa dan Deir ez-Zor, Jabhat al-Nusra, yang mulai mengurangi retorika salafi-nya demi citra Sunni-Suriah, mulai merekrut banyak pejuang revolusioner yang kecewa dengan buruknya kinerja FSA. Apalagi, FSA semakin dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan Turki setelah jaringan Erdoğan mengambil alih kendalinya di tengah benturan ambisi antara Turki, Saudi, dan Qatar.
Jabhat al-Nusra sejak awal dideklarasikan sebagai organisasi anti-Turki, anti-Iran, dan anti-Barat, meskipun sesekali menjalin kerja sama taktis dengan Turki. Awalnya mendapat sokongan Qatar, kelompok ini tetap bersikap terbuka menentang Turki pada pertengahan 2010-an, karena sebagian besar salafi bersenjata melihat Turki sebagai negara “sekuler.” Pada masa itu, mereka bahkan secara terbuka melawan FSA yang didukung Ankara.
Sekitar 2015, Qatar, Arab Saudi, dan Turki mulai menyelaraskan strategi mereka dan bersama-sama mengarahkan kelompok-kelompok Islamis bersenjata di Suriah. Tetapi di lapangan, para pejuang justru terpecah karena perbedaan sikap terhadap kepemimpinan koalisi ini. Pada tahun yang sama, Jabhat al-Nusra masih keras menolak kerja sama dengan Turki dan bahkan mengecam Ahrar al-Sham—salah satu kelompok Islamis besar lainnya—karena bersedia melakukannya. Ahrar al-Sham bahkan menulis artikel opini di Washington Post dan Daily Telegraph untuk mencari legitimasi Barat. Sepanjang 2010-an, aliansi, perseteruan, dan konfigurasi ulang hubungan kelompok-kelompok Islamis bersenjata dengan kekuatan regional berubah hampir setiap bulan. Dalam kekacauan itu, sikap anti-Turki Jabhat al-Nusra menjadi salah satu sedikit hal yang tetap konsisten. Namun, ketika berkembang menjadi HTS, organisasi ini mulai lebih fleksibel bekerja sama dengan Turki—meski hubungan tersebut tetap penuh gesekan dan ketidakpercayaan.
Pada tahun 2017, HTS mulai menguasai Idlib, sebuah kota di Barat Laut, Suriah. Walau di banyak wilayah Suriah HTS mewarisi gaya koalisi fleksibel ala Jabhat al-Nusra, pola itu tidak berlaku di Idlib pada tahun-tahun awal kekuasaannya: mereka memerintah dengan tangan besi. Turki, yang saat itu berada dalam ketegangan dengan Barat dan Rusia, pada akhirnya menerima dominasi HTS di Idlib, sementara HTS dengan enggan mengizinkan Turki membangun kehadiran logistik dan militer di kota tersebut. Kedua pihak kadang bekerja sama melakukan operasi melawan pasukan Assad. Namun, ini adalah kemitraan gelap: penuh kecurigaan, manipulasi, dan upaya masing-masing pihak untuk melemahkan satu sama lain. Turki, misalnya, dilaporkan menargetkan dan membunuh para ekstremis dalam struktur komando HTS, dengan tujuan ganda: membuat sikap anti Turki dari organisasi ini berkurang sekaligus untuk melemahkannya.[23] Ketegangan ini sesekali meledak menjadi bentrokan terbuka, seperti pada awal Mei 2020.
Di luar Idlib, hubungan antara Erdoğan dan HTS bahkan lebih rumit. Pada 2018, Turki dan proxy-nya, Tentara Nasional Suriah (SNA), menduduki Afrin, kota dengan mayoritas penduduk Kurdi di bagian utara Suriah dan wilayah sekitar, yang mengakibatkan pembersihan terhadap etnis Kurdi. SNA adalah penggabungan dari sisa FSA yang gagal dengan kelompok Turkmen, faksi Islamis, dan elemen Ikhwanul Muslimin Suriah. Hingga 2022, SNA dan Turki berhasil mempertahankan kawasan itu sebagai zona bebas HTS. Namun, SNA yang dibelit kroniisme dan pertikaian internal membuka peluang bagi serangan HTS yang berulang. Setelah kampanye berbulan-bulan, HTS akhirnya berhasil merebut Afrin dari pasukan yang didukung Turki pada akhir 2022.
Perkembangan ini membawa dampak lebih luas. Kemunduran SNA menjadi bukti tambahan bagi kelompok-kelompok salafi bersenjata di seluruh Timur Tengah bahwa jalur Ikhwanul Muslimin—bahkan dalam versi militernya—hanya menghasilkan korupsi dan kelemahan. Partai AKP di Turki ikut memperkuat kesan ini, karena prioritas utama partai yang mengklaim diri “Islamis” tersebut bukanlah membangun pemerintahan Islam atau sistem demokratis yang stabil di Afrin dan sekitarnya, melainkan agenda anti-Kurdi negara Turki, khususnya menekan Rojava.Dalam situasi di mana Erdoğan beberapa kali mencoba menormalisasi hubungan dengan Assad dua tahun sebelum runtuhnya rezim itu, justru al-Jolani-lah yang tampil di garis depan, mewakili penolakan dari kalangan Salafi maupun kelompok Revolusi Suriah terhadap upaya rekonsiliasi Turki–Suriah itu.[24]
Sementara itu, media Barat sendiri terpecah dalam menilai rekam jejak HTS di Idlib. CNN dan New York Times memberi gambaran yang relatif positif: HTS memang menerapkan hukum Islam pada awalnya, tetapi kemudian melunakkan kebijakan itu. Berbeda dengan narasi yang muncul setelah kejatuhan Assad, media arus utama seperti The Economist masih menyebut al-Jolani sebagai “tiran lain” hingga Maret 2024. HTS juga menahan banyak aktivis dan memperlakukan warga setempat dengan kasar, yang akhirnya memicu gelombang protes tahun lalu.
Dalam perjalanan panjang dari sekadar menguasai kota kecil Idlib hingga akhirnya berhasil merebut Damaskus, al-Jolani harus berperang, menaklukkan, merekrut, dan bernegosiasi dengan puluhan faksi Islamis sebelum akhirnya ia diterima, bahkan didukung, oleh kekuatan regional dan global. Sejak 2020, Idlib tampak menjadi pusat berbagai aktor asing yang berusaha melatih dan memengaruhi kelompok-kelompok Islamis bersenjata. Selain keterlibatan Turki yang sudah diakui secara terbuka, banyak spekulasi beredar mengenai sumber pendanaan internasional, dukungan logistik, dan sejauh mana semua itu berperan dalam memfasilitasi serangan menuju Damaskus. Esai ini tidak bermaksud menentukan mana di antara spekulasi tersebut yang benar. Fokusnya adalah bagaimana pemerintahan HTS dapat membentuk Suriah dan kawasan yang lebih luas, terutama ketika kita mempertimbangkan latar sejarah yang telah dibahas dan dinamika yang muncul setelah serangan ke Damaskus.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Suriah Islamis?
Masa depan dan arah pemerintahan HTS masih diselimuti ambiguitas.
Mereka belum menguasai seluruh Suriah. Israel telah menghancurkan sebagian besar kemampuan pertahanan negara itu. Komunitas Druze dan Kurdi masih bersenjata. Israel, Amerika Serikat, Rusia, dan Turki semuanya memiliki kehadiran militer di wilayah Suriah. Yang tak kalah penting, HTS juga tidak sepenuhnya mengendalikan kelompok-kelompok Islamis bersenjata yang mengaku bersekutu dengannya—meskipun kelompok-kelompok itu secara formal telah “membubarkan diri” dan melebur ke dalam tentara Suriah.Arah strategis regional HTS juga belum jelas. Kunjungan luar negeri pertama al-Jolani adalah ke Arab Saudi dan kemudian ke sejumlah negara Teluk, mengisyaratkan bahwa model dan pelindung utama HTS mungkin lebih condong ke Teluk daripada Turki. Namun, langkah itu bisa pula dibaca sebagai manuver pengalihan untuk menutupi peran dominan Turki di balik layar. (Erdoğan bahkan merencanakan kunjungan balasan pada awal Januari, tetapi menundanya untuk menghindari kontroversi.) Ada juga kemungkinan bahwa, mirip dengan AKP, HTS sedang berusaha memperluas spektrum sekutunya, bukan hanya bergantung pada satu patron. Pada awal 2025, politik Turki, baik pemerintah maupun oposisi, hampir setiap hari memperdebatkan apa arti sebenarnya dari rangkaian kunjungan diplomatik ini.
Dari Desember 2024 hingga awal Maret 2025, muncul laporan yang saling bertentangan tentang bagaimana HTS memperlakukan komunitas Alawite. Meski kelompok Alawite merasa terancam, sebagian besar sumber utama—baik Turki maupun Barat—mengklaim tidak ada insiden besar. Sebaliknya, sumber-sumber oposisi menyebut telah terjadi kekerasan etnis-sektarian bahkan sebelum bulan Maret. HTS dan media arus utama bersikeras bahwa insiden-insiden itu dilakukan oleh kelompok bersenjata liar yang tidak berada di bawah kendali komando mereka.
Salah satu titik ketegangan terbesar dalam rezim baru ini adalah perbedaan antara pejuang Suriah dan para pejuang asing, khususnya dari Chechnya dan Asia Tengah. Walaupun banyak aksi kekerasan dalam bulan-bulan berikutnya tampaknya dilakukan oleh pejuang Suriah yang pro-pemerintah, para pejuang asing inilah yang dituding berada di balik serangan brutal terhadap komunitas Alawite pada pekan-pekan awal kekuasaan HTS, termasuk aksi-aksi simbolis seperti pembakaran pohon Natal di kota-kota yang mayoritas penduduknya Kristen. HTS sulit mengambil jarak dari para pejuang asing tersebut, tetapi pada saat yang sama hampir mustahil memasukkan mereka ke dalam struktur negara salafi “terkendali” yang ingin mereka bangun.
Selain itu, dalam proses pembentukan negara yang begitu rumit ini, sulit memastikan siapa sebenarnya yang mengendalikan siapa. Dewan Nasional Suriah, yang dulunya dekat dengan Turki, didominasi Ikhwanul Muslimin, dan pada 2012 diakui lebih dari seratus negara sebagai pemerintahan sah Suriah—mengumumkan pada pertengahan Februari bahwa mereka akan membubarkan diri. Langkah ini bisa dibaca sebagai bukti tambahan bahwa jalur “Islamis/liberal-demokrat” telah kalah dan kemudian terserap oleh negara baru yang berada di bawah kendali HTS. Secara lebih luas, ini menandai runtuhnya tradisi Islamisme ala Ikhwanul Muslimin dalam panggung politik Suriah.
Setelah memperoleh dukungan Barat dan aliansi Sunni regional, HTS menyelenggarakan konferensi nasional pada hari-hari terakhir Februari tanpa partisipasi Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi, Alawite, dan Druze. Konferensi tersebut tidak mencakup perwakilan dari partai politik, serikat pekerja, atau asosiasi profesional. Ada perwakilan Kristen, mungkin langkah yang dirancang untuk menunjukkan niat baik HTS kepada Barat, tetapi bukan sebagai perwakilan dari kelompok terorganisir mana pun. Konferensi Februari ini mengikuti pertemuan pertama yang lebih terbatas dengan format serupa. Kedua konferensi tersebut mengonfirmasi sifat Sunni-Arab dari rezim yang sedang terbentuk. Kabinet yang dibentuk pada akhir Maret mengikuti pola yang sama: eksekutif baru mencakup individu-individu simbolis dari kelompok minoritas, tetapi berbeda dengan figur HTS di kabinet, individu-individu ini tidak mewakili organisasi atau gerakan apa pun. Sementara itu, Israel memperluas operasi militernya pada Februari, menghancurkan lebih banyak peralatan militer, melampaui wilayah selatan yang awalnya menjadi sasaran setelah jatuhnya Assad.
Pada awal Maret, Islamisasi Sunni mengambil arah yang lebih dramatis, baik di tingkat jalanan maupun institusional.
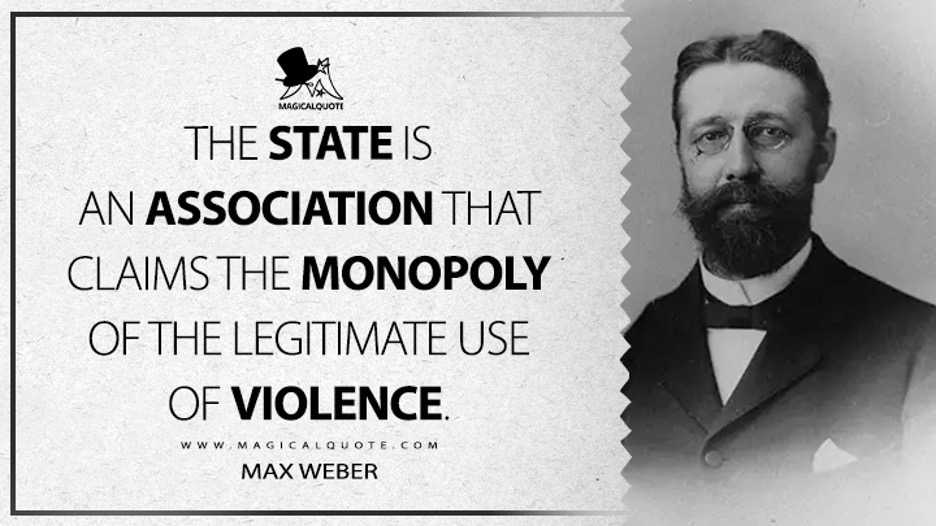
“Monopoli kekerasan yang sah”
Dalam rentang 72 jam pada awal Maret, lebih dari seribu warga Alawite – sebagian besar warga sipil – tewas di wilayah pesisir Suriah. Banyak dari mereka dibunuh dengan metode eksekusi.[25] Kekerasan ini tampaknya merupakan aksi balas dendam, mengingat Assad berasal dari komunitas Alawite. Namun penting dicatat, meski sering digambarkan keliru sebagai “rezim Alawite”, kekuasaan Assad sebenarnya dibangun melalui negosiasi antar beberapa keluarga elite dari berbagai sekte. Alawite memang dominan, terutama di sektor keamanan dan unit militer di sekitar Maher al-Assad, tetapi struktur ini lebih mirip oligarki daripada rezim sektarian murni. Banyak warga Alawite mendukung Assad bukan karena fanatisme sektarian, melainkan karena takut akan alternatif yang mungkin lebih buruk.[26] Di sisi lain, kekuatan regional seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki mendorong politik sektarian Sunni dan Syiah demi memperluas pengaruh masing-masing, dan elite oligarkis Suriah kerap memanfaatkan intervensi eksternal ini untuk memperkuat posisi mereka. Polarisasi ini makin mengeras setelah Suriah beralih dari model korporatis ke ekonomi pasar sejak akhir abad ke-20, sebuah perubahan yang makin dipercepat pada 2000-an. Ketika rezim kehilangan legitimasi ekonomi di mata petani dan kelas pekerja, ia semakin mengandalkan politik etnis dan sektarian untuk mempertahankan kendali.[27]²⁷ Dalam situasi ini, warga Alawite kelas bawah menderita bersama rakyat Sunni kelas bawah; yang diuntungkan hanyalah segelintir keluarga oligarki dan para pendukung internasional mereka. Jadi, meskipun balas dendam buta mungkin ikut memicu pembantaian Maret, terdapat kekuatan struktural yang lebih besar, terkait proses pembentukan negara dan dinamika kekuasaan regional, yang turut menentukan terjadinya tragedi tersebut.
Nama dan gagasan Max Weber, yang sejak lama digemari intelektual Turki, mendadak kembali populer di media pada akhir 2024 hingga awal 2025. Para akademisi, sejarawan militer, jurnalis, dan komentator di TV maupun YouTube terus mengutip definisi Weber tentang negara sebagai “komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli kekerasan yang sah dalam suatu wilayah,” terutama saat membahas pembubaran PKK serta pelucutan senjata puluhan kelompok milisi Kurdi, Islamis, dan kelompok bersenjata lainnya di Suriah.[28] Tanpa menyebut nama Weber secara langsung, media Barat juga memakai kerangka pikir yang sama. Misalnya, pada pertengahan Maret, New York Times menggambarkan rangkaian kekerasan terbaru dengan merujuk pada penjelasan presiden Suriah: bahwa kekacauan itu terjadi karena negara belum mampu memonopoli kekerasan.[29]
Cara pandang ini mengabaikan kritik ilmu sosial selama beberapa dekade terhadap definisi Weber: siapa yang memegang monopoli kekerasan “legitim” dan untuk tujuan apa, atas nama “negara”, sama pentingnya dengan monopoli itu sendiri.[30] Selain itu, dalam kenyataan politik, negara kerap bekerja sama dengan aktor kekerasan non-negara untuk mencapai tujuan mereka, baik selama proses membangun monopoli tersebut maupun setelahnya.[31]
Setelah menonjol sebagai suara moderasi dan pragmatisme di kalangan Salafi bersenjata, al-Jolani menyatakan – pada puncak fase “moderat”nya pada tahun 2015 dan sebelum kembali beralih ke bentuk salafisme kekerasan yang lebih keras – bahwa pasukannya tidak akan menyakiti Alawites selama mereka meninggalkan agama mereka.[32] Bagi salafi bersenjata, kekerasan terhadap Alawites (dan secara umum, Muslim non-Sunni) telah menjadi agenda utama selama bertahun-tahun. Meskipun tujuan al-Jolani mungkin telah berubah, gerakan global ini telah membina kader dan militan yang berdedikasi untuk melakukan kekerasan semacam itu. Sebagian besar militan ini kini menjadi sekutu atau bagian dari pasukan keamanan Suriah baru. Mereka kemungkinan akan menemukan lebih banyak kesempatan untuk mewujudkan tujuan mereka, yang tidak sepenuhnya bertentangan dengan tujuan konstitusi sementara untuk membangun negara Sunni.
Alih-alih disebabkan oleh monopoli kekerasan yang belum lengkap, kekerasan pada bulan Maret justru disebabkan oleh proses monopoli kekerasan yang sedang berlangsung tersebut.
Hampir bersamaan dengan gelombang kekerasan itu, al-Jolani, yang kembali menggunakan nama aslinya, al-Sharaa, setelah merebut Damaskus, mengumumkan konstitusi sementara baru yang menetapkan Islam sebagai sumber utama legislasi dalam pasal keduanya. Konstitusi ini memberikan kekuasaan besar kepada presiden, sambil menjanjikan perlindungan hak-hak perempuan dan minoritas. Media pan-Arab yang pro-HTS, termasuk surat kabar semi-resmi Qatar, memuji klausul-klausul tersebut sebagai bukti bahwa HTS benar-benar telah meninggalkan “ideologi jihad.”[33] Namun, para kritikus menyoroti kontradiksinya: HTS mengawasi salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah Suriah pada saat yang sama ketika mereka menjanjikan jaminan hak-hak tersebut—sehingga implementasinya diragukan akan sesuai dengan retorika.Di pihak lain, sebagian kelompok Druze menolak mengakui konstitusi itu dan secara implisit menyatakan al-Sharaa tidak sah; sebagian lainnya memilih diam. Walaupun terjadi ketegangan antara Druze dan aparat keamanan HTS, skala kekerasan tetap relatif kecil hingga pertengahan tahun. Israel kemudian memosisikan diri sebagai pelindung komunitas Druze, dan Netanyahu beberapa kali berupaya turun tangan saat ketegangan meningkat. Meski dilaporkan ada sejumlah faksi bersenjata yang secara eksplisit mengambil posisi pro-Israel, penerimaan publik terhadap peran Israel sebagai “pelindung” tetap terbatas—hingga bentrokan pada Mei yang menewaskan empat puluh orang dalam dua hari.[34]
Di tengah meningkatnya ketegangan, pada Juli mulai muncul laporan tentang penculikan, penyerangan, perampokan, dan konflik antarsuku antara komunitas Druze dan kelompok Bedouin di Suwayda. Tak lama kemudian, pasukan keamanan yang berafiliasi dengan suku-suku Arab ikut terjun, dan dalam hitungan hari hampir seribu warga Druze dibantai. Pemerintah Suriah baru dan para sekutunya di kawasan, termasuk Turki, menyalahkan Israel, yang memang ikut terlibat dalam sebagian bentrokan itu.
Media Barat menggambarkan situasi ini sebagai akibat kurangnya sentralisasi kekuasaan. Sebuah artikel di New York Times menulis bahwa “militer yang bersatu sangat penting untuk mengamankan kendali negara dan menjaga stabilitas,” seolah-olah Druze yang menolak tunduk dianggap sebagai penghambat tujuan yang dianggap universal itu.[35] Namun, sifat serangan pada Juli, yang sangat terkoordinasi dan bermuatan ideologis, termasuk aksi memaksa warga Druze mencukur janggut mereka secara paksa dan massal, lebih menunjukkan bahwa yang terjadi bukan kekurangan monopoli kekerasan, melainkan proses pembentukan monopoli itu sendiri.
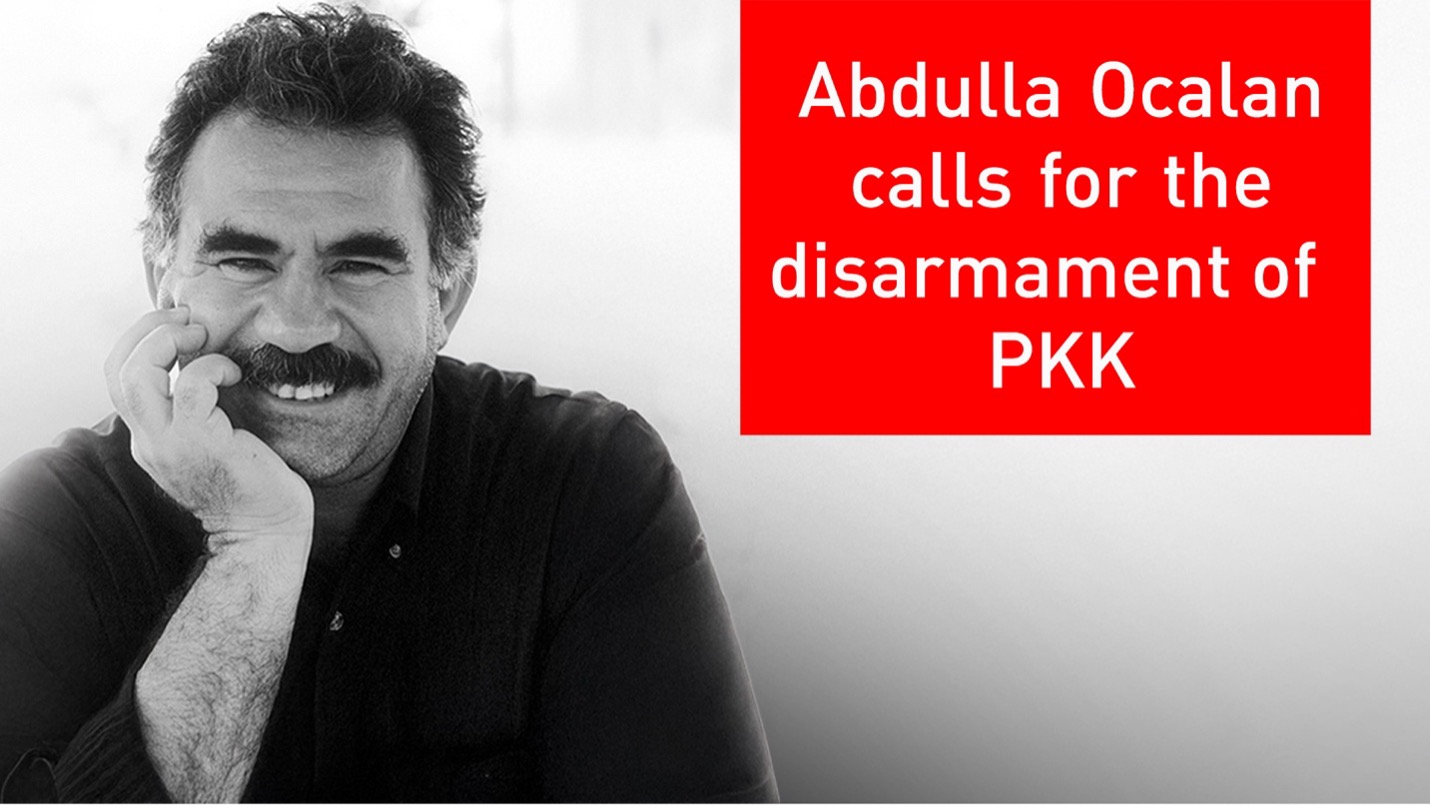
Pertanyaan tentang Kurdi
Keputusan Kurdi Suriah pada pertengahan Maret untuk bergabung dengan tentara nasional menjadi titik balik besar bagi kawasan dan bagi arah perkembangan salafisme itu sendiri. Kecakapan strategis dan diplomatik al-Sharaa kembali terlihat: dalam waktu hanya satu minggu, ia berhasil meraih tiga hal sekaligus—mendapatkan restu (atau setidaknya sikap diam) dari Barat dan dunia Arab untuk konstitusi berbasis fiqh, mencapai kesepakatan dengan Kurdi, dan pada saat yang sama mengawasi pembantaian sektarian. Namun perkembangan setelahnya menunjukkan tantangan besar dalam menerapkan kesepakatan tersebut dengan Kurdi.
Populasi Kurdi tersebar di empat negara.[36] Munculnya administrasi otonom Rojava menghidupkan kembali impian sebagian Kurdi untuk bersatu, sementara bagi yang lain, Rojava menjadi model institusional yang bisa diterapkan di seluruh kawasan, sesuai ideologi dominan gerakan Kurdi saat ini. Para pemimpin dan intelektual Kurdi terus menekankan pentingnya “otonomi”, baik untuk Kurdi maupun untuk kelompok komunitas lain di Timur Tengah. Di sisi lain, sejak awal HTS bersikap kaku terhadap gagasan federasi dan menginginkan negara kesatuan yang berada di bawah kontrol ketat Damaskus.
Pemerintahan Erdoğan ikut campur dalam dinamika ini bahkan sebelum al-Jolani melancarkan serangannya ke Damaskus. Devlet Bahçeli, pemimpin MHP dan mitra utama koalisi Erdoğan, secara mengejutkan mengundang Abdullah Öcalan, pemimpin gerilya yang dipenjara, untuk berbicara di parlemen Turki dan menyatakan bahwa PKK telah “berakhir.”[37] Dengan langkah ini, Öcalan dan para komandan Kurdi pro-Öcalan, yang masih tercantum dalam daftar “teroris” resmi, secara de facto diakui sebagai aktor politik sah. Inisiatif ini tampaknya bertujuan menahan aspirasi politik Kurdi dengan mengampuni Öcalan dan mungkin para pejuang Kurdi lainnya. Sebagai gantinya, kubu Erdoğan diduga berharap mendapatkan dukungan Kurdi bagi rencana presiden seumur hidup, pelucutan senjata kelompok Kurdi (di Turki dan Suriah), serta komitmen terhadap bentuk negara yang tetap tidak federatif di kedua negara. Apakah isu-isu seperti otonomi, hak bahasa dan budaya, atau redefinisi kewarganegaraan non-etnis ikut dibahas masih menjadi bahan spekulasi besar di Turki maupun media Barat dan Arab. Baik pihak Erdoğan, HTS, maupun gerakan Kurdi belum membuka apa sesungguhnya yang dipertaruhkan dalam negosiasi ini.
Sikap Amerika Serikat dalam proses ini masih jauh dari jelas. AS membiarkan Turki mengambil alih Manbij pada Desember 2024, tetapi mereka juga turun tangan untuk melindungi Kobani dari serangan Turki setelah jatuhnya Assad. Bahkan para pendukung Trump, yang biasanya sangat ingin AS keluar dari Suriah, kali ini bersuara lantang bahwa Washington punya kewajiban moral melindungi Kurdi ketika Ankara bersiap melancarkan operasi militer. Meski penuh pertentangan, media pro-pemerintah Turki tetap setia mendukung Trump. Mereka yakin Trump pada akhirnya akan mengabaikan keberatan apa pun dan menghentikan dukungan AS terhadap Kurdi, dan menganggap setiap keraguan di Washington sebagai ulah “Zionis” atau pengaruh jahat lainnya. Mereka pun menunggu penuh harap menjelang 20 Januari, percaya Trump akan segera turun tangan. Namun kenyataannya, Trump memilih bungkam soal isu Suriah; ia lebih sibuk dengan perang di Ukraina, isu-isu domestik, dan obsesinya terhadap Kanada, Greenland, serta Terusan Panama. Pertemuan akhir Maret antara Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menlu AS Marco Rubio, juga tidak memberi petunjuk apa pun tentang posisi akhir Amerika.
Situasi di Kurdistan Suriah sama rumitnya, kalau bukan lebih rumit, dibandingkan dinamika di Turki. Setelah tercapainya kesepakatan antara HTS dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, yang mencakup integrasi SDF ke dalam tentara nasional, sebagian komentator buru-buru menyatakan bahwa era konflik bersenjata telah berakhir. Namun, banyak pihak lain mengingatkan bahwa persoalan sesungguhnya ada pada pelaksanaan kesepakatan yang samar ini. Meski dokumen resmi menyebut integrasi seluruh pasukan dan infrastruktur militer di Suriah, kubu Kurdi tetap berharap dapat mempertahankan bentuk otonomi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun—meskipun istilah “otonomi” kini dihindari secara terbuka. Isu-isu yang dikabarkan masuk dalam agenda negosiasi, seperti pengendalian lokal atas pendapatan minyak dan infrastruktur, serta jaminan posisi tinggi dalam struktur militer, seolah memberi peluang bagi dua kemungkinan: adanya kekuasaan Kurdi yang nyata meski tanpa struktur federasi formal, atau munculnya model pembagian kekuasaan mirip sistem Lebanon.
Sementara itu, Fidan dan kepala intelijen Kalın segera terbang ke Suriah setelah perjanjian ditandatangani, dengan tujuan mencegah terbentuknya otonomi de facto bagi Kurdi. Di dalam negeri Turki, suasana juga berubah cepat: awalnya publik merayakan kemungkinan pelucutan senjata Kurdi, tetapi kemudian suara-suara nasionalis mulai khawatir bahwa masuknya pejuang Kurdi ke dalam tentara Suriah justru bisa membuka jalan menuju lahirnya sebuah Kurdistan. Dengan nada yang lebih hati-hati, Hakan Fidan sendiri menyiratkan bahwa kesepakatan itu mengandung risiko bagi Ankara, terutama menyangkut YPG (Unit Perlindungan Rakyat, komponen utama bersenjata dalam SDF).[38] Dalam konteks serupa, duta besar Turki untuk Damaskus pada 2009–12 menyinggung dalam sebuah majalah Saudi bahwa bisa saja perlahan-lahan muncul suatu bentuk kesatuan Kurdi yang lebih besar di kawasan, serta otonomi Kurdi di dalam Suriah—tanpa menggunakan istilah “federasi” yang sensitif.[39] Selain itu, hanya tiga hari setelah al-Sharaa dan pemimpin Kurdi Mazlum Abdi menandatangani kesepakatan, administrasi Rojava yang dipimpin SDF menolak konstitusi sementara tersebut. Mereka menyebut konstitusi itu sebagai kelanjutan mentalitas Baath, bertentangan dengan semangat Revolusi Suriah, dan gagal mencerminkan aspirasi demokratis serta keberagaman masyarakat Suriah. Kritik tajam ini jelas tidak sesuai dengan ekspektasi kubu Erdoğan dan sekutu Suriahnya, memperlihatkan sekali lagi bahwa keyakinan mereka akan kepatuhan Kurdi dan kemenangan Islamis yang mulus ternyata terlalu berlebihan.
Pada awal musim panas, gelombang euforia baru menyapu kalangan penguasa Turki dan para sekutu internasionalnya. Seruan terakhir Öcalan agar para pejuang meletakkan senjata, ditambah aksi pembakaran senjata secara simbolis oleh para pemimpin puncak PKK, disambut dengan keterkejutan sekaligus tepuk tangan. Namun, bahkan langkah dramatis ini tidak membawa kepastian. Ketahanan struktur bersenjata Kurdi dan otonomi di Rojava, yang masih dekat dengan garis politik PKK, menunjukkan batas-batas nyata dari proses tersebut. Hakan Fidan menggunakan pembantaian terhadap komunitas Druze sebagai peringatan terselubung bagi Kurdi Suriah, menekankan bahwa keberlangsungan hidup mereka bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Tetapi atmosfer ketakutan yang tercipta akibat pembantaian itu justru berbalik menjadi alasan bagi Kurdi untuk mempertahankan hak membela diri secara bersenjata. Setelah melihat apa yang menimpa Druze, Kurdi Suriah semakin enggan menyerahkan senjata mereka. Saat esai ini dituntaskan pada pertengahan November, proses pelucutan senjata di Kurdistan Suriah masih berjalan sangat lambat.

Kenaikan Saudi dan Penyesuaian Kembali Kekuatan Global yang Masih Rapuh
Tidak mengherankan jika serangan HTS ke Aleppo, kota terbesar di Suria, dimulai tepat setelah pemilu presiden Amerika Serikat. Bahkan dengan membaca sekilas media regional, terlihat jelas bahwa Netanyahu, Erdoğan, dan para penguasa monarki Sunni menafsirkan kemenangan Trump sebagai lampu hijau bagi ambisi mereka. Meski serangan itu tidak secara langsung diarahkan atau didorong oleh Washington, kelompok salafi bersenjata jelas memilih momentum tersebut dengan sengaja, melihatnya sebagai masa kekosongan kekuasaan dan, lebih luas lagi, sebagai awal dari sebuah tatanan baru di mana operasi militer aktor-aktor lokal akan menentukan jalannya peristiwa lebih besar daripada sebelumnya dalam era pra-Trump.
Namun, aparat kebijakan luar negeri dan militer Amerika Serikat masih belum satu suara, baik soal apakah mereka merestui kekuasaan Islamis di Suriah, maupun soal sejauh mana mereka ingin mengurangi keterlibatan AS di negara itu. Pemerintahan baru tampak menjalankan strategi campuran tanpa arah atau mandat yang benar-benar jelas. Banyak komentator di media Turki dan Arab meyakini bahwa AS berada di balik kesepakatan HTS–SDF, tetapi kecil kemungkinan Washington sebenarnya mengendalikan proses itu dengan rencana yang kohesif. Pada Februari, Pentagon memberi sinyal bahwa pasukan AS mungkin ditarik. Namun Kepala Intelijen, Tulsi Gabbard, justru bersuara keras menentang HTS dan kelompok Islamis lain, menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi kekuatan demokratis, tidak dapat dipercaya sebagai mitra, dan bahwa Amerika tidak boleh menarik tentaranya dari wilayah tersebut. Setelah pembantaian bulan Maret, Fox News dan media konservatif lain memuji ketepatan peringatan Gabbard, yang memberi isyarat bahwa bahkan di dalam pemerintahan Trump sendiri, serta di antara basis politiknya yang luas, ada potensi penolakan terhadap apa pun rencana Trump untuk Timur Tengah.
Impian Trump sendiri, terlihat dari besarnya kepercayaan yang ia berikan kepada Erdoğan, tampaknya adalah menarik sebanyak mungkin pasukan dan sumber daya Amerika dari Suriah dan kawasan sekitarnya, sambil menyerahkan tugas menjaga kepentingan AS kepada Turki dan Erdoğan (serta, ironisnya, sebagian pemimpin Kurdi yang justru anti-Erdoğan).[40] Ini jelas merupakan pertaruhan yang berbahaya, dan Trump bisa saja mengubah kalkulasinya sewaktu-waktu, sama cepatnya seperti ketika ia berbalik menentang Erdoğan pada 2018. Meski para pendukung Erdoğan telah menaruh investasi emosional dan strategis yang besar dalam Trumpisme, pemerintahan AS sendiri tidak memberikan sinyal yang konsisten. Contohnya, penilaian sangat optimistis dari utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengenai hubungan Erdoğan–Trump, langsung dibayangi oleh penilaian lebih dingin dari tim Menteri Luar Negeri Marco Rubio setelah pertemuan Rubio dengan mitranya, Hakan Fidan.[41]
Perhitungan Trump dan timnya jauh lebih rumit ketika menyangkut hubungan antara Suriah dan Israel. Meski figur-figur paling garis keras di sekeliling Trump tidak mempercayai HTS, sikap baru organisasi itu terhadap Israel setidaknya meredakan sebagian kekhawatiran kubu konservatif. Dari sudut pandang Washington, pemerintahan HTS bisa saja menjadi opsi yang lebih menguntungkan Israel dibandingkan alternatif realistis lainnya. Sejak mengambil alih kekuasaan, al-Sharaa berulang kali menegaskan bahwa ia tidak berminat memulai perang dengan Israel. Belum jelas apakah ia akan sampai pada titik menyerahkan Dataran Tinggi Golan sepenuhnya, tetapi sejauh ini ia hampir tidak bereaksi terhadap perluasan pendudukan Israel atas wilayah Suriah. Keterlibatan Israel yang makin intens dalam isu Druze memang menunjukkan bahwa hubungan “persaudaraan penuh konflik” antara Netanyahu dan al-Sharaa punya batas-batasnya. Namun perlu diingat: al-Sharaa tetap dapat beroperasi sebagai sekutu Turki meskipun sebelumnya (sebagai “al-Jolani”) ia pernah beberapa kali bentrok berdarah dengan pasukan Erdoğan. Walaupun Israel belum sepenuhnya mempercayai HTS, sikap al-Sharaa yang berhati-hati membuat pemerintahan Israel memilih untuk “menghormatinya sambil tetap waspada”, alih-alih segera mendorong penggulingannya, demikian menurut sumber-sumber Israel.[42]
Setidaknya untuk saat ini, Iran menjadi pihak yang paling dirugikan di antara kekuatan regional. Negara itu sudah kewalahan menghadapi dinamika pasca 7 Oktober, dan jatuhnya Assad membuat Teheran kehilangan sekutu pentingnya di Suriah. Lebih dari itu, kejatuhan Assad juga berarti kemenangan bagi kelompok-kelompok anti-Syiah paling fanatik di dunia, mengingat banyaknya pejuang salafi bersenjata yang masuk ke Suriah, sekaligus menandai gagalnya strategi rumit Iran untuk mengelola konflik Gaza sambil tetap mendukung Hamas.[43] Kini, Iran berhadapan dengan semakin banyak seruan perubahan rezim dari Washington, serta ancaman perang yang muncul sesekali.
Kebangkitan al-Jolani juga menjadi pukulan keras bagi para sekutu regional Iran. Hezbollah, yang telah kehilangan jumlah komandan dan prajurit dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bulan-bulan sebelumnya, terpaksa menandatangani gencatan senjata yang merugikan dengan Israel pada 27 November, tepat ketika HTS mulai merebut Aleppo.[44] Lalu pada Januari, Joseph Aoun—yang oleh media pan-Arab Sunni dipuji sebagai figur sangat anti-Hezbollah, terpilih sebagai presiden Lebanon. Meski Aoun berupaya menemukan kompromi dengan Hezbollah (lagi-lagi dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi kelompok tersebut), ia secara bersamaan juga mencoba memulihkan hubungan Lebanon dengan Arab Saudi.
Hasil keseluruhan situasi ini memberi keuntungan tersendiri bagi Arab Saudi. Selain keberhasilan menyingkirkan Assad, kelompok-kelompok arus utama ala Ikhwanul Muslimin (salah satu kekuatan yang paling ditakuti oleh monarki-monarki Arab) gagal memimpin proses transisi kekuasaan. Kini, seorang tokoh salafi berada di pucuk kekuasaan negara baru; secara teologis, ini bisa dibaca sebagai kemenangan bagi Saudi dalam kompetisi ideologi jangka panjang di kawasan. Namun, “salafisme ala al-Jolani” justru pernah menjadi jenis salafisme yang paling merepotkan monarki Teluk selama dekade terakhir, karena puritanismenya yang lebih ketat, tendensinya yang sangat politis, dan implikasinya yang berpotensi anti-negara. Walaupun al-Sharaa tampaknya telah meninggalkan sebagian unsur ideologi lamanya, kecenderungannya untuk berayun dari pragmatis ke puritan dan kembali lagi menjadi pragmatis sudah terkenal, dan itu bisa menimbulkan masalah bagi Saudi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu, meskipun rezim baru masih menindak sebagian pejuang asing, proses memasukkan ribuan lainnya ke dalam Tentara Nasional Suriah, bahkan ke posisi-posisi puncak, sedang berlangsung. Integrasi ini membawa konsekuensi yang belum dapat diprediksi terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan.
Kekhawatiran semacam ini sebenarnya tidak pernah menghentikan Saudi dan monarki Teluk lainnya untuk mendanai kelompok salafi bersenjata di masa lalu, meskipun mereka selalu sadar bahwa senjata tersebut bisa saja suatu hari berbalik mengarah ke mereka sendiri. Karena itu, media Saudi pun menunjukkan sikap yang terbelah. Al-Sharq al-Awsat dan saluran TV al-Arabiya (versi pan-Arab milik Saudi yang menjadi tandingan al-Jazeera) merayakan apa yang mereka sebut sebagai “akhir ideologi dan Islamisme” di kawasan, yang pada dasarnya berarti kemenangan ideologi dan versi Islam mereka sendiri.[45] Namun di saat yang sama, media-media ini juga sering menyuarakan kekhawatiran terhadap “negara-negara pendukung proyek Ikhwanul Muslimin [‘Ikhwani’]” (yakni Turki dan Qatar) dan kemungkinan keduanya dapat menyeret Suriah ke arah yang tidak diinginkan Riyadh.[46]
Tekanan politik dan kekuatan yang berasal dari cadangan minyak Saudi membawa kita pada dilema besar lain bagi kerajaan itu. Setelah berbulan-bulan menolak menurunkan harga minyak, Riyadh akhirnya menyerah pada tekanan Trump, bahkan sebelum ia berkunjung ke kawasan pada bulan Mei. Trump membutuhkan negara-negara Teluk tetap berada di jalur ini untuk menahan inflasi domestik, terutama setelah “Big Beautiful Bill” disahkan pada Juli dan menambah tiga triliun dolar pada utang AS. Sebagai imbalan atas konsesi Saudi tersebut, Trump memberi apa yang diinginkan Riyadh selama lawatannya ke Timur Tengah: ia bertemu langsung dengan al-Sharaa, mencabut sanksi, menjaga jarak dari Netanyahu, dan mempertahankan sikap keras terhadap Hamas. Penghapusan sanksi secara permanen ditautkan pada dua syarat: Suriah harus bergabung dalam Perjanjian Abraham dan mengusir “teroris” Palestina—dua langkah yang jelas menandai kemenangan diplomatik bagi Arab Saudi.[47]
Namun mempertahankan harga minyak tetap rendah dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi pukulan besar bagi agenda pembaruan infrastruktur yang dikejar Mohammed bin Salman. Perubahan sikap Riyadh soal harga minyak adalah harga yang harus dibayar untuk paket kesepakatan yang tampaknya menguntungkan, seperti terlihat dari berbagai langkah pro-Saudi selama kunjungan Trump. Kemenangan diplomatik itu juga disertai kemenangan ekonomi, karena Trump yang disebut-sebut “isolasionis” justru membatalkan kebijakan Biden yang membatasi bantuan teknologi dan penjualan perangkat canggih ke negara-negara Teluk. Meski secara strategis kesepakatan ini terlihat masuk akal bagi Saudi, dampaknya di dalam negeri bisa membuat basis dukungan bagi rezim MBS (Mohammed bin Salman Al Saud) menyusut. Harga minyak yang lebih rendah berpotensi mengganggu banyak proyek pembangunan, termasuk megaproyek infrastruktur dan konstruksi yang masih menjadi sumber penghidupan utama atau tambahan bagi jutaan warga. Sementara itu, manfaat jangka panjang dari teknologi tinggi akan datang terlalu lambat untuk mengimbangi masalah sosial yang mungkin muncul akibat berkurangnya investasi pada sektor konstruksi dan infrastruktur.
Dilema yang dihadapi Saudi juga berdampak pada arah kapitalisme di Suriah. Struktur kelas baru di negara itu memang masih samar karena ekonomi yang sangat kacau, tetapi ada dua proses penting yang mulai terlihat: pertama, pergeseran kekayaan dari kroni Assad ke jaringan bisnis yang terhubung dengan rezim baru; kedua, masuknya kapital Teluk, dipimpin Saudi, untuk mengawasi privatisasi lahan dan aset pemerintah dengan tujuan membentuk “Dubai versi Suriah.”[48] Namun Turki juga sangat bernafsu menanamkan investasi di Suriah pasca-perang. Belum jelas apakah Saudi bisa keluar dari dilema internalnya dan mengalahkan kapital Turki dalam perebutan pengaruh ekonomi ini. Apa pun hasilnya, jika rezim HTS berhasil stabil, kelas berkuasa kemungkinan akan terdiri dari kapitalis yang dekat dengan al-Sharaa dan para pebisnis Sunni asing, yakni versi yang lebih bergantung dari kapitalisme oligarkis era Assad, yang hampir pasti tidak akan mempertimbangkan kepentingan ekonomi kelas-kelas bawah secara serius.
Salah satu pergeseran kekuatan yang paling kurang diperhatikan adalah merosotnya posisi Tiongkok. Model kapitalisme Tiongkok bertumpu pada kelancaran arus energi dan barang di seluruh kawasan sebagai komponen penting dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI)). Meski Beijing belum menanamkan investasi besar di Suriah saat Assad tumbang, pelabuhan-pelabuhan Suriah adalah titik kunci yang menghubungkan jalur perdagangan Asia–Eropa dan rute energi yang ingin diamankan BRI. Karena itu, Tiongkok berkepentingan menjaga stabilitas regional dengan bekerja sama dengan Suriah, Turki, Iran, dan Arab Saudi. Pendekatan Tiongkok ini bukan hal baru: di luar wilayahnya sendiri, Beijing cenderung menghindari peran sebagai hegemon baru dalam pengertian Arrihian (merujuk pada penjelasan Giovanni Arrighi: tidak menawarkan ideologi tandingan yang ambisius, tidak menjual “model China,” dan tidak melakukan intervensi militer langsung.[49] Jika negara-negara Arab bisa membangun posisi politik yang lebih otonom, seperti yang diharapkan sebagian analis Tiongkok, mereka berpotensi menyingkirkan dominasi Barat, Turki, dan Rusia.[50] Dalam skenario itu, Tiongkok bisa tampil sebagai “reluctant hegemon”, satu-satunya kekuatan kapitalis besar yang lebih memilih menumbuhkan konsensus ketimbang menggunakan kekuatan militer di Timur Tengah.[51] Tetapi kenyataannya, satu-satunya aktor regional yang benar-benar mendorong otonomi politik adalah gerakan Kurdi, yang paradoksnya justru bergantung pada kekuatan paling agresif dan intervensionis di kawasan: Amerika Serikat.
Saat ini, kekuasaan al-Sharaa yang nyaris tak terbendung tetap mendapat dukungan implisit dari negara-negara Barat, meski pembantaian terhadap kelompok minoritas jelas membuat antusiasme awal mereka terhadap pemimpin salafi itu meredup. Sikap mendua Barat terhadap seorang presiden Islam ini kembali menunjukkan bahwa—terlepas dari ketegangan berkala antara Trump dan kaum neokonservatif, maupun antara AS dan Uni Eropa—dunia Barat pada dasarnya hanya menginginkan dua hal di Timur Tengah: stabilitas umum, dan ruang untuk memicu konflik ketika hal itu menguntungkan agenda ekstraktif negara atau korporasi tertentu. Sementara itu, tuntutan Musim Semi Arab (Arab Spring) – martabat, roti (penghidupan), kebebasan, dan keadilan sosial – kembali harus ditunda hingga rakyat mampu membangun ulang kekuatan kolektif mereka. Baik Barat, Turki, monarki Teluk, maupun salafisme bersenjata yang kini tampak “jinak” tidak ada yang sanggup, apalagi berniat, memenuhi tuntutan tersebut.
Ada narasi yang mengatakan bahwa al-Sharaa telah “berubah”, bahwa ia mengganti nama, memakai dasi, berhenti menyerukan kekerasan terhadap orang-orang Barat jauh sebelum merebut Damaskus, dan karena itu tak lagi bisa dianggap sebagai “salafi-jihadi.” Tapi narasi semacam ini mengabaikan pola geraknya yang memang selalu penuh kalkulasi. Selama bertahun-tahun, ia sengaja bolak-balik antara puritanisme dan pragmatisme, antara membangun kader fanatik dan membentuk koalisi luas, antara kekerasan brutal dan negosiasi politik. Pendekatan zig-zag inilah yang akhirnya membawanya mencapai salah satu tujuan besarnya: menempatkan HTS sebagai penguasa Suriah. Jika sejarahnya menjadi petunjuk, ia bisa saja kembali mengubah arah kapan pun demi mengejar tujuan jangka panjang lainnya.
Banyak orang – baik dari kanan, kiri, maupun tengah – merasa bahwa HTS kini telah “bertransformasi” menjadi organisasi yang lebih haus kekuasaan ketimbang berorientasi pada misi agama. Bisa jadi memang ke situlah arah besarnya. Namun perubahan ekstrem al-Jolani di masa lalu – melompat dari puritan kekerasan ke aktor politik pragmatis, lalu kembali lagi menjadi puritan – menyisakan kemungkinan lain: bahwa al-Sharaa sebenarnya tetap memegang komitmen religius yang kuat dalam proyek politiknya, dan akan mengeksekusi agenda itu begitu ia melihat peluang yang tepat.
Intinya bukan bahwa “al-Jolani tidak berubah,” melainkan bahwa perubahan yang ia lakukan sebagian besar selaras dengan kebutuhan kapitalisme global ketimbang untuk perjuangan demokratis rakyat Suriah. Selain itu, seperti yang ditunjukkan sepanjang esai ini, ada banyak bukti bahwa ia tetap menyimpan unsur-unsur kunci dari misi ideologis asalnya. Apakah komponen-komponen itu kelak akan bertentangan dengan kepentingan global yang dominan masih menjadi tanda tanya besar. Namun hampir tidak ada indikasi bahwa agenda tersebut suatu hari akan menguntungkan kelas-kelas bawah Suriah.
Empat belas tahun lalu, rakyat Suriah bangkit dengan tuntutan demokrasi. Turki, Arab Saudi, dan negara-negara Barat kemudian berusaha menunggangi tuntutan itu demi akumulasi kapital dan ambisi imperial masing-masing. Tetapi pemenang yang paling tidak terduga dari seluruh proses ini mungkin justru, atau setidaknya berdampingan dengan aktor-aktor tersebut, adalah sebuah bentuk baru Islamisme.***
Cihan Tuğal adalah Profesor Sosiologi di Universitas California, Berkeley, dan ahli tentang gerakan sayap kanan radikal. Ia telah menerbitkan banyak buku dan artikel tentang gerakan dan rezim sayap kanan Turki, Amerika Serikat, Mesir, dan Iran.
[1] Sebagaimana dinyatakan oleh James Jeffrey pada akhir September 2025 — yaitu hanya berselang singkat setelah menyaksikan pembersihan etnis terhadap kaum Alawi dan Druze. Ali Rogin, “Al-Sharaa promises a new video free of its ‘wretched past,’” PBS, September 24, 2025, https://www.pbs.org/newshour/show/al-sharaa-promises-a-new-syria-free-of-its-wretched-past. ames Jeffrey adalah duta besar AS untuk Turki dan Irak pada masa pemerintahan Bush dan Obama, serta perwakilan khusus untuk keterlibatan AS di Suriah pada masa pemerintahan Trump yang pertama.
[2] Deklarasi Konstitusi Republik Nasional Suriah, art III, cl. 1, available at https://constitutionnet.org/sites/default/files/2025-03/2025.03.13%20-%20Constitutional%20declaration%20%28English%29.pdf?utm_source=chatgpt.com. Islamic jurisprudence was already listed as “a major source of legislation” in the constitution of 2012. Constitution of Syria in 2012, art. II, available at https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Syria_Constitution2012.pdf?utm_source=chatgpt.com. This and many other aspects of the constitution and state policies and discourses clearly demonstrate that the Assad regime was not the bastion of secularism some held it to be. Joseph Daher, “How the Assad regime feigns ‘secularism’ while strengthening conservatism,” Syria Untold, January 14, 2022, https://syriauntold.com/2022/01/14/how-the-assad-regime-feigns-secularism-while-strength
[3] Mengenai hubungan antara neoliberalisasi dan konflik sektarian yang terjadi baru-baru ini, lihat Joseph Daher, “HTS’ strategy to Consolidate its power in Syria,” Syria Untold, July 28, 2025, https://syriauntold.com/2025/07/28/hts-strategy-to-consolidate-its-power-in-syria/.
[4] Saya membahas kerangka teoritis untuk klaim-klaim ini dalam sebuah ceramah berjudul ““The Terminal Phase of American Hegemony or Revival of Fascism? Accounting for Violence in the Middle East through a Synthesis of World-Systems Theory and Structural Marxism.” Terkait rekaman video ini tersedia secara online. “Global Political Dimensions of the Turn to the Right,” YouTube video, 34:18–49:15, posted by “globalcriticalstudies,” October 31, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=5OwoKarl9U0.
[5] Jeff Mason, “Trump says Turkey holds the key to Syria’s future,” Reuters, December 16, 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-turkey-holds-key-syrias-future-2024-12-16/
[6] Lihat, antara lain, Francois Burgat and William Dowell, The Islamic Movement in North Africa (Austin: University of Texas Press, 1997); Dominik Mueller, Islam, Politics and Youth in Malaysia: The Pop-Islamist Reinvention of PAS (London: Routledge, 2014), https://doi.org/10.4324/94781315850535; Mohammed K. Shadid, “The Muslim brotherhood movement in the West bank and Gaza,” Third World Quarterly 10, no. 2 (1988): 658–82, https://doi.org/10.1080/01436598808420076; Lorenzo Vidino, 2010, The New Muslim Brotherhood in the West (New York: Columbia University Press, 2010); Mohammed Zahid and Michael Medley, “Muslim Brotherhood in Egypt and Sudan,” Review of African Political Economy 33, no. 110 (2006): 693–708, https://www.jstor.org/stable/4007135.
[7] Hazem Kandil, 2011, “Islamizing Egypt? Testing the limits of Gramscian counterhegemonic strategies,” Theory and Society 40: 37-62, https://doi.org/10.1007/s11186-010-9135-z; Nawaf Obaid, The Failure of the Muslim Brotherhood in the Arab world (London: Bloomsbury Publishing, 2020), https://doi.org/10.5040/9798400649530; Carrie Rosefsky Wickham, 2015, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement – Updated Edition, Princeton University Press.; Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement – Updated Edition, (Princeton: Princeton University Press, 2015), https://doi.org/10.2307/j.ctv7h0t3j.
[8] Salwa Ismail, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the Everyday State (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006).
[9] Olivier Roy, The Failure of Political Islam (Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1998).
[10] Cihan Tuğal, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism (Stanford: Stanford University Press, 2009).
[11] Gilles Kepel, The Prophet and the Pharoah: Muslim Extremism in Egypt (London: Al Saqi Books, 1985).
[12] Hiba Bou Akar, For the War Yet to Come: Planning Beirut’s Frontiers (Stanford: Stanford University Press, 2018).
[13] Shiraz Maher, Salafi-jihadism: The History of an Idea (Oxford: Oxford University Press, 2016).
[14] Roel Meijer, Global Salafism: Islam’s New Religious Movement (Oxford: Oxford University Press, 2014),https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199333431.001.0001.
[15] Cihan Tuğal, The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism, (London: Verso, 2016).
[16] Mengenai kebijakan-kebijakan spesifik yang diterapkan rezim selama pergeseran menuju ‘kapitalisme negara’ ini, lihat Cihan Tuğal, “Politicized Megaprojects and Public Sector Interventions,” Critical Sociology 49, no. 3 (2022): 457–73, https://doi.org/10.1177/08969205221086284.
[17] Mohamed A. Ramady, The Saudi Arabian Economy: Policies, Achievements, and Challenges(New York: Springer, 2010), 335; Sarah Moser, Marian Swain, and Mohammed H. Alkhabba, “King Abdullah Economic City: Engineering Saudi Arabia’s post-oil future,” Cities 45 (2015): 71-80, https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.03.001.
[18] David Cowan, The coming economic implosion of Saudi Arabia: a behavioral perspective(Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 37.
[19] Penilaian ini sama sekali tidak berarti bahwa dorongan pembangunan–infrastruktur itu gagal di semua bidang. Upaya tersebut jelas mendukung tujuan Islamisasi dari atas ke bawah yang diusung rezim, sekaligus memperkuat para kroninya. Lihat Rosie Bsheer, Jadaliyya, “The Property Regime: Mecca and the Politics of Redevelopment in Saudi Arabia,” September 8, 2015, https://www.jadaliyya.com/Details/32436/The-Property-Regime-Mecca-and-the-Politics-of-Redevelopment-in-Saudi-Arabia.
[20] Ryan Calder, The Paradox of Islamic Finance: How Shariah Scholars Reconcile Religion and Capitalism (Princeton: Princeton University Press, 2024), https://doi.org/10.2307/jj.8784660.
[21] Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
[22] Charles Lister, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State, and the evolution of an insurgency (Oxford: Oxford University Press, 2015).
[23] Charles Lister, “Turkey’s Idlib incursion and the HTS question: understanding the long game in Syria,” War on the Rocks, October 31, 2017, https://warontherocks.com/2017/10/turkeys-idlib-incursion-and-the-hts-question-understanding-the-long-game-in-syria/
[24] “Al-Julani embarasses the Syrian opposition in a statement rejecting Turkish normalization with Assad,” Syria TV, January 2, 2023. https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
[25] Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus tidak berhasil memastikan bahwa pembantaian tersebut direncanakan dan dilaksanakan oleh rezim itu sendiri, tetapi menegaskan bahwa pembantaian itu terkoordinasi dan telah direncanakan; kelompok-kelompok yang melaksanakannya pernah diorganisir oleh HTS dalam fase awal sejarahnya; dan pasukan rezim turut berpartisipasi di dalamnya. Laporan itu juga menekankan bahwa pembunuhan masih terus berlangsung, meskipun tidak seintens pada bulan Maret. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Violations against civilians in the coastal and western-central regions of the Syrian Arab Republic (January–March 2025) (Geneva: United Nations Human Rights Council, 2025), available at https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/a-hrc-59-crp4-en.pdf
[26] Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience (Stanford: Stanford University Press, 2011), https://doi.org/10.1515/9780804778411.
[27] Joseph Daher, “Popular Oral Culture and Sectarianism, a Materialist Analysis,” Syrian Untold, October, 31, 2018, https://syriauntold.com/2018/10/31/popular-oral-culture-and-sectarianism-a-materialist-analysis/#_ednref13
[28] Nuri Salık, “Suriye’de Yeni Devletin İnşası,” Türkiye Araştirmalari Vafki, February 19, 2025, https://www.turkiyearastirmalari.org/2025/02/19/yayinlar/analiz/suriyede-yeni-devletin-insasi/; Gültekin Yıldız, “Yeni Bir Devletin İzinde: Suriye’de Yeni Ordu Nasıl Mümkün Olacak?” Perspektif, December 28, 2024, https://www.perspektif.online/yeni-bir-devletin-izinde-suriyede-yeni-ordu-nasil-mumkun-olacak/; Max Weber, [1919], “Politics as a Vocation,” in From Max Weber (Oxford: Oxford University Press), ed. H.H Geerth and C. Wright Mills, 77–128.
[29] Ben Hubbard, “Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence,” New York Times, March 17, 2025, https://www.nytimes.com/2025/03/17/world/middleeast/syria-military-assad.html.
[30] Jennifer Carlson, “Revisiting the Weberian Presumption: Gun Militarism, Gun Populism, and the Racial Politics of Legitimate Violence in Policing,” American Journal of Sociology 125, no. 3 (2019, ): 633–82, https://doi.org/10.1086/707609.
[31] Cihan Tuğal, “The Decline of the Monopoly of Legitimate Violence and the Return of Non-State Warriors ” in The Transformation of Citizenship, Volume 3: Struggle, Resistance and Violence, ed. Juergen Mackert and Bryan S. Turner (Routledge: London and New York: 2017), 77–91.
[32] AFP, “Chief of al-Qaeda’s Syria affiliate pledges no attacks on the West,” Middle East Eye, May 28, 2015, https://www.middleeasteye.net/news/chief-al-qaedas-syria-affiliate-pledges-no-attacks-west.
[33] Muhammad Abu Raman, “Al-i‘lan al-dusturi wa al-qati‘a ma‘a al-idiolojiya al-jihadiyya,” Al-Araby al-Jadid, March 16, 2025, https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
[34] Kareem Chehayeb and Omar Sanadiki, “Syria’s Druze seek a place in a changing nation, navigating pressures from the government and Israel,” AP News, March 10, 2025, https://apnews.com/article/syria-druze-damascus-alsharaa-sweida-war-ace48a6e138dc1197cca77c3d25d829b
[35] Christina Goldbaum and Reham Mourshed, “These Militias Refuse to Join Syria’s New Army,”New York Times, April 1, 2025, updated April 14, 2025, https://www.nytimes.com/2025/04/01/world/middleeast/syria-israel-border.html.
[36] David A. McDowall, 2007, A modern history of the Kurds (London: I.B. Tauris, 2007).
[37] Pemimpin PKK, Öcalan, memulai kiprahnya sebagai seorang Marxis-Leninis pada tahun 1970-an. Setelah awal 1990-an, PKK memprioritaskan pembebasan nasional dan menarik kaum borjuis Kurdi untuk mendukung pemberontakan bersenjata. Setelah dipenjara pada tahun 1999, Öcalan menemukan pemikiran Bookchin di selnya yang berkeamanan tinggi dan meninggalkan Marxisme-Leninisme. Saat ini, gerakan dan organisasi yang terkait dengannya menggabungkan—dengan cara yang tidak merata—komunalisme ala Bookchin, Marxisme-Leninisme, dan nasionalisme emansipatoris.
[38] Haber Merkezi, “Fidan’dan, Colani-Mazlum Abdi anlaşmasına kritik açıklama: Suriye Külterinin haklarının verilmesi hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli,” T24, March 14, 2025, https://t24.com.tr/haber/fidan-dan-sam-sgd-anlasmasi-hakkinda-kritik-aciklama-suriye-kurtlerinin-haklarinin-verilmesi-hem-cumhurbaskanimiz-hem-de-turkiye-icin-fevkalade-onemli,1225921
[39] Ömer Önhon, “Reading between the lines of the Sharaa-Abdi deal,” Al Majalla, March 14, 2025, https://en.majalla.com/node/324731/politics/reading-between-lines-sharaa-abdi-deal.
[40] Fehim Taştekin, a journalist with village-by-village knowledge of especially Northern Syria, as well as ample contacts in foreign policy circles, outlined the apparent parameters of the negotiations between Americans, the Kurds, and Erdoğan. “Dış güçler Erdoğan’ı kurtarıyor mu? İsrail’le kullanışlı gerilim. Suriye’de çatışmasız çakışma,” YouTube video, 22:33, posted by “Fehim Taştekin,” March 25, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=tbhaKd79Kno. Also see Fehim Taştekin, “Trump, Erdoğan ve Putin’in haritaları!” Gazete Duvar, January 9, 2025, https://www.gazeteduvar.com.tr/trump-erdogan-ve-putinin-haritalari-makale-1748317.
[41] “Trump-Erdogan talks ‘great-transformational’ but ‘under-reported’: US Envoi,” Middle East Monitor, March 22, 2025, https://www.middleeastmonitor.com/20250322-trump-erdogan-talks-great-transformational-but-under-reported-us-envoy/; Tammy Bruce, “Secretary Rubio’s Meeting with Turkish Foreign Minister Fidan,” U.S Department of State, March 25, 2025, https://www.state.gov/secretary-rubios-meeting-with-turkish-foreign-minister-fidan-2/.
[42] Yoni Ben Menachem, “Abu Muhammad al-Jolani’s Attitude Toward Israel,” January 2, 2025, Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, https://jcpa.org/abu-muhammad-al-jolanis-attitude-toward-israel/.
[43] Eskander Sadeghi-Bouroujerdi, “On the Brink,” Sidecar (blog), October 7, 2024, https://newleftreview.org/sidecar/posts/on-the-brink.
[44] Suleiman Mourad, “Hezbollah Contained,” Sidecar (blog), December 4, 2024, https://newleftreview.org/sidecar/posts/hezbollah-contained.
[45] Mamduh al-Mahayni, “Al-taknoqrati Ahmad al-Shara‘,” al-Sharq al-Awsat, June 7, 2025, https://aawsat.com/الرأي/5098672-التكنوقراطي-أحمد-الشرع
[46] Mashari al-Dhaydi, “Al-Qaradawi… Khatar al-‘ubur fi al-Ziham,” al-Sharq al-Awsat, June 9, 2025, https://aawsat.com/الرأي/5099395-القرضاوي-خطر-العبور-في-الزحام
[47] Meskipun Kerajaan telah memperoleh keuntungan diplomatic yang jelas, media semi-resmi mereka tetap mengakui kepemimpinan Bersama Turki yang terus berlanjut dalam proses transisi. Lihat, misalnya, “Al-Safir al-Amriki lada Turkiyya yatawalla dawr al-mab‘uth al-khas ila Suriyya,” al-Sharq al-Awsat, May 26, 2025, https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/5146581-السفير-الأميركي-لدى-تركيا-يتولّى-دور-المبعوث-الخاص-إلى-سوريا Selain itu, Turki sekali lagi menjadi pusat dari proses tersebut sejak September hingga awal November, mengisyaratkan bahwa keseimbangan kekuatan antara kedua pihak kemungkinan akan berfluktuasi lebih jauh dalam beberapa bulan mendatang.”
[48] “Syria and Lebanon: Crisis and Crossroads, w/ Nabih Bulos | Connections Podcast with Mouin Rabbani #108,” YouTube video, 1:02:23, posted by “Jadaliyya,” August 14, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=V8kLirM6sF8.
[49] Giovanni Arrighi. 1990, “The Three Hegemonies of Historical Capitalism,” Review 13, no. 3 (1990): 365–408, https://www.jstor.org/stable/i40009226.
[50] Jin Liangxiang, “Illusions Vanish in the Middle East,” China US Focus, March 20, 2025, https://www.chinausfocus.com/peace-security/illusions-vanish-in-the-middle-east.
[51] Ini Adalah harapan Arrighi sendiri terhadap Cina, lihat Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century (London: Verso, 2007). Terkait alasan-alasan struktural mengapa hal ini tidak mungkin terwujud, lihat Ho-fung Hung, The China Boom: Why China Will Not Rule the World (New York: Columbia University Press, 2015), https://doi.org/10.7312/columbia/9780231164184.001.0001.






