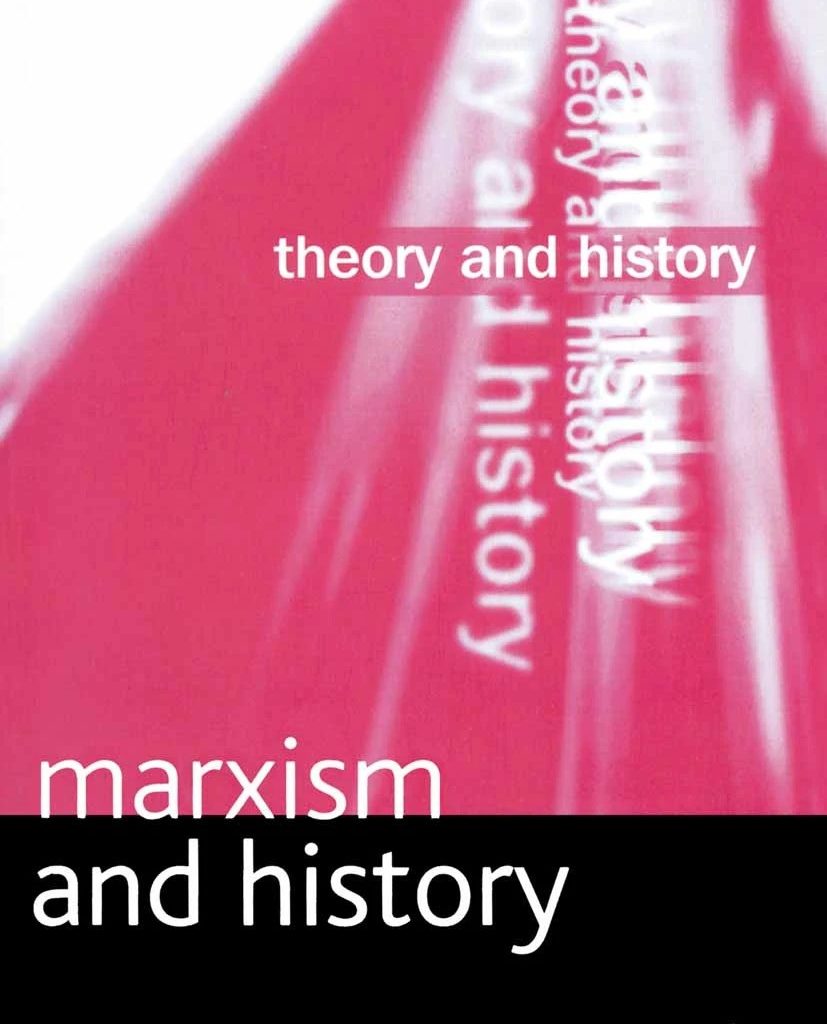Ilustrasi: Marxist.org
Judul buku: Marxism & History
Penulis: Matt Perry
Penerbit: Palgrave
Tahun terbit: 2002
JIKA diramu dalam satu gambaran umum, pengetahuan kita tentang perkembangan historiografi yang diajarkan di Departemen Ilmu Sejarah selalu dimulai dari masa Herodotus dan Thucydides sebagai sejarawan paling awal. Kadang terselip pula materi tentang Ibn Khaldun, lalu berlanjut ke Voltaire. Ada pula penjelasan tentang rasionalisme Descartes yang dibandingkan dengan empirisme David Hume. Karena mata kuliahnya bersifat pengantar, baik historiografi umum maupun dasar-dasar filsafat, pemikiran mereka biasanya disebut secara ringkas. Barulah setelah pertengahan semester, kita mulai memusatkan perhatian pada peran Bapak Sejarah Modern: al-mukarram Leopold von Ranke.
Penekanan Ranke pada penggunaan dokumen sezaman sebagai sumber sejarah dianggap sebagai salah satu titik paling signifikan dalam perkembangan historiografi. Pendekatan ini memberi corak positivis pada disiplin sejarah. Penulisan sejarah harus didasarkan pada sumber yang absah, terutama sumber primer. Itulah pemahaman kunci yang ingin ditanamkan dengan mempelajari Ranke.
Melalui peran historisnya itu, kita kemudian mengenal slogan “no document, no history.” Belakangan, istilah “dokumen” sering dipersempit menjadi “arsip tekstual tertulis yang tersimpan di lembaga kearsipan negara.” Meski Ranke menekankan kritik sumber berdasarkan asal-usul dan konsistensi internalnya, penggunaan sumber-sumber resmi negara membuat karyanya cenderung berperspektif elitis.
Selain itu, Ranke dipandang mendekati sumber dengan tujuan menjelaskan bagaimana satu peristiwa “sesungguhnya terjadi”—wie es eigentlich gewesen. Hasilnya ialah karya-karya naratif yang kurang analitis. Kita diajari bahwa kelemahan ini membuka pintu bagi kritik terhadap pendekatan Ranke. Belakangan, gaya semacam itu dirasa tidak lagi memadai untuk menjawab pertanyaan sejarah.
Empat puluh tahun setelah Ranke wafat, lahirlah satu gerakan penulisan sejarah di Prancis dengan gaya yang lebih analitis. Kelompok Annales muncul pada akhir 1920-an. Penggagasnya ialah Marc Bloch dan Lucien Febvre, sementara tokoh paling terkenalnya tentu Fernand Braudel. Kita belajar bahwa pertanyaan yang diajukan para sejarawan Annales lebih mendalam dibandingkan Ranke. Dengan pendekatan multidisiplin, mereka berusaha menjelaskan kehidupan sehari-hari manusia dalam rentang waktu yang panjang dan dimensi yang luas.
Alur kurikulum di universitas sebagian besar mengikuti urutan semacam ini. Namun sering muncul pertanyaan samar tentang tempat Marx dalam sejarah pemikiran historis, mengingat ia sezaman dengan Ranke dan memiliki banyak karya yang membahas sejarah peradaban manusia. Pembahasan tentang Marx hampir selalu tidak memuaskan. Ia lebih sering diperlakukan sebagai filsuf dengan gagasan yang terlalu abstrak, dan cukup dibahas sambil lalu dengan kritik yang tak tuntas dalam satu pertemuan pengantar filsafat.
Misteri tentang peran Marxisme dalam Ilmu Sejarah dibahas terang-benderang dalam buku karya Matt Perry ini. Ia membaginya ke dalam tujuh bab serta pengantar dengan alur seperti novel. Perry membuka paparan dengan klaim serius: Marx dan Engels tidak pernah memandang sejarah sebagai subdivisi dalam sistem pemikiran mereka, sebab pandangan mereka tentang bagaimana dunia bekerja selalu bercorak historis. Seluruh upaya intelektual keduanya, tegas Perry, ditujukan untuk mengonseptualisasikan dan menjelaskan pengalaman sejarah umat manusia sebagai sebuah totalitas.
Klaim itu ia buktikan dengan menelusuri konsep-konsep kunci pemikiran Marx dan Engels tentang sejarah: materialisme, dialektika, kekuatan produktif dan hubungan produksi, basis dan superstruktur, peran pekerja, perjuangan kelas, gradualisme dan revolusi, fase-fase perkembangan historis, serta hubungan antara struktur dan agensi. Melalui paparan tersebut, Perry menegaskan sanggahannya terhadap kritik yang menilai Marxisme terlalu menekankan determinasi ekonomi dan karenanya bersifat reduksionis.
Pada bab tiga, Perry membahas The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte dan Capital volume I yang sangat kental unsur sejarahnya, bersama The Peasant War in Germany karya Engels serta surat-surat Engels tentang materialisme dialektis. Perry ingin menegaskan kembali bahwa sejarah sama sekali tidak asing bagi Marxisme—keduanya tidak mungkin dipisahkan.
Setelah itu, Perry beranjak ke generasi kedua sejarawan Marxis: Leon Trotsky dengan The History of the Russian Revolution, Antonio Gramsci dengan Prison Notebooks, dan Georg Lukács dengan History and Class Consciousness yang ditulis dalam pengasingan di Wina. Perry tidak hanya menimbang karya-karya tersebut; ia juga membahas konsep-konsep kunci yang berkembang dari tulisan mereka. Sikap serupa ia terapkan ketika menyinggung Christopher Hill dan E.P. Thompson sebagai generasi ketiga.
Bagian paling tegang ialah polemik posmodernisme yang bukan hanya menyerang Marxisme, tetapi juga bangunan disiplin sejarah itu sendiri. Perry menjelaskan argumen posmodern secara teliti sampai pada titik tertentu pembaca dapat merasa bahwa merekalah pemenangnya. Namun paparan itu segera diimbangi dengan kritik Marxisme terhadap posmodernisme, termasuk menunjukkan kelemahan saintifik aliran tersebut.
Perry tidak menghadirkan posmodernisme secara tiba-tiba. Ia menelusuri akar kelahirannya sejak strukturalisme mulai memengaruhi sejarawan Marxis. Ia membahas perbedaan mendasar antara Marxisme klasik dan Marxis-Strukturalis dalam memahami proses sejarah. Meski jelas memihak Marxisme, Perry tetap memberikan apresiasi yang adil kepada kedua aliran itu.
Secara keseluruhan, buku ini layak disejajarkan dengan bacaan penting dalam mata kuliah historiografi atau metodologi. Sebut saja biografi von Ranke karya Andreas D. Boldt serta karya Peter Burke The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–1989. Buku Perry mampu memantik kesadaran baru dalam memandang perkembangan historiografi. Bahkan, tinjauan Perry terhadap Marxisme lebih mendalam dibandingkan cara Burke meninjau Annales.
Kritik terhadap Pergeseran dari Rankean ke Annales
Telah dijelaskan bahwa Ilmu Sejarah—khususnya di Indonesia—sulit lepas dari sosok Ranke. Terinspirasi dari kerja filolog pada teks-teks abad pertengahan, Ranke dianggap sebagai penggagas penggunaan dokumen dalam studi sejarah. Namun kita patut bertanya: benarkah demikian? Apakah benar hanya Ranke yang menggunakan teknik kritik sumber pada masanya? Sikap murid-murid Ranke yang kaku membentuk citra seakan ia sangat saklek. Maka Ranke pun sering digambarkan sebagai penganut empirisme.
Basis karyanya yang berusaha menggambarkan masa lalu “sebagaimana adanya” dari sumber resmi negara menjadikan Ranke sebagai sejarawan aristokrat. Penekanan yang sangat arsip-sentris menghalangi analisis tentang makna dan arah sejarah. Bagi pendekatan Rankean, upaya semacam itu dianggap berpotensi membawa bias subjektif. Kelemahan tersebut mengantarkan Ranke pada pandangan naif bahwa semua zaman sama mulianya di hadapan Tuhan: jede Epoche ist unmittelbar zu Gott—“Every age is equally close to God.”
Dengan demikian, sejarah dipandang sebagai fragmen unik dalam bundel arsip, bukan proses dialektis yang punya arah. Karena itulah Marx menyebut Ranke sebagai bapak sejarawan borjuis profesional.
Empirisme Rankean juga menyimpan kelemahan lain. Orientasi pada arsip resmi membuat sejarah kesulitan menjawab tuduhan tidak saintifik. Ketika interpretasi berupaya menarik hukum umum, ia dituduh subjektif. Maka sejarah yang baik dianggap yang bertumpu pada bukti otentik dan kronologi cermat. Detail monograf seolah menjadi jaminan keilmiahan. Padahal, ketepatan faktual tanpa kerangka dialektis hanya menghasilkan pameran data. Pertanyaan penting tentang konflik, struktur, ketimpangan, serta perubahan sosial tak akan terjawab memadai.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Dalam konteks universitas, kita bisa berdalih bahwa kelemahan itu yang membuat kita diajarkan pendekatan multidisipliner khas Annales. Konsep dari berbagai disiplin dipinjam agar penjelasan sejarah tampak lebih analitis dan ilmiah. Namun kenyataan hari ini menunjukkan hal berbeda. Annales terlalu longgar: tidak semua pendekatan konseptual berpijak pada prinsip-prinsip sains—bahkan ada yang menolaknya.
Contoh dekat ialah polemik penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia. Keilmiahannya diklaim terletak pada komposisi penulis dari 34 universitas. Sementara arah interpretasinya menggunakan pendekatan konseptual untuk memperkuat karakter dan identitas nasional di tengah gempuran globalisasi.
Pertanyaannya: apakah penekanan pada identitas nasional benar-benar kebutuhan mendesak hari ini? Bukankah warga negara secara alami bangga sebagai WNI bila negara hadir menjamin keadilan dan kesejahteraan? Apa gunanya pembahasan panjang tentang identitas bila yang kita saksikan justru korupsi di berbagai level pemerintahan, kriminalisasi lawan politik, miskinnya komunikasi kebijakan, menyusutnya lapangan kerja, serta kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif yang merampas tanah-tanah ulayat? Semua itu adalah gejala pertentangan kelas yang nyata.
Abainya historiografi terhadap persoalan semacam ini membuat masyarakat memandang sejarah sebagai karangan penguasa dan tidak relevan bagi kehidupan sehari-hari.
Di Hadapan Posmodernisme
Selama membaca buku ini, saya teringat satu percakapan dengan kakak tingkat di pelataran FIB suatu kampus di Makassar beberapa tahun silam. Ketika itu kami berdiskusi tentang kecenderungan metodologis dalam penelitian sejarah. Saya menjelaskan bahwa saya menyukai cara pandang Marxis.
Seorang senior menimpali sambil tertawa, “Nanti lama-lama juga pindah ke posmo. Biasanya orang Marxis dulu, baru posmo.”
Percakapan sederhana itu menyisakan kebingungan tentang linimasa yang dianggap niscaya bagi para pembelajar: setelah mempelajari Marxisme, mereka pasti berakhir pada posmodernisme sebagai pendekatan yang lebih adekuat. Benarkah perkembangan intelektual selalu linear? Bukankah tuntutan metodologis ilmu sejarah sebenarnya telah terakomodasi dengan baik oleh Marxisme?
Dalam buku ini, Perry menjelaskan dengan baik posisi Marxisme dalam menghadapi serangan posmodernisme—sebuah pendekatan yang kerap tampil memesona dengan jargon kebebasan, relativitas, dan dekonstruksi. Namun di balik kilau itu, posmodernisme membawa masalah mendasar: ia mempromosikan keraguan sampai mencabut landasan material pengetahuan sejarah.
Perry menunjukkan bagaimana E.P. Thompson mengkritik Louis Althusser, yang mengambil posisi mirip posmo dalam memahami sejarah. Bagi Althusser, pengetahuan sejarah mustahil. Menurut Thompson, Althusser gagal membedakan cara kerja empiris peneliti dari empirisme mentah. Tanpa disiplin prosedural, percakapan tentang masa silam tereduksi menjadi cerita ideologis semata.
Polemik serupa terjadi antara Neville Kirk dan Gareth Stedman Jones serta Patrick Joyce. Kirk menilai keduanya terlalu menekankan bahasa dan diskursus ketika menganalisis sejarah pekerja Inggris abad ke-19, sehingga gagal memperlihatkan bagaimana perubahan sosial-ekonomi membentuk bahasa kelas pekerja. Namun Kirk tetap mengapresiasi temuan bahwa bahasa tidak sekadar refleksi pasif realitas.
Kritik tajam lainnya datang dari Alex Callinicos yang mengecam posmodernisme sebagai warisan anti-Enlightenment Nietzsche. Posisi ini menolak ide kemajuan, sains, dan bahkan menganggap realitas beserta hukum-hukumnya sebagai konstruksi sosial. Callinicos juga mengkritik Hayden White yang menyamakan sejarah dengan fiksi naratif, sehingga tragedi besar seperti Holocaust—atau pembantaian di Gaza hari ini—dapat direduksi sebagai konstruksi teks tanpa kebenaran objektif. Di sini posmodernisme tidak hanya buntu secara epistemologis, tetapi juga keliru secara etis dan fatal dalam berpolitik.
Tawaran Marxisme pada Ilmu Sejarah
Secara keseluruhan, terdapat sejumlah konsep kunci Marxisme yang relevan bagi penelitian sejarah mutakhir di Indonesia. Yang paling vital ialah cara berpikir dialektis dan total. Dialektika berarti melihat sejarah sebagai proses yang bergerak melalui kontradiksi. Totalitas berarti menempatkan setiap peristiwa dalam konteks sistem sosial-ekonomi yang lebih luas.
Perry memberikan beragam contoh, mulai dari The Making of the English Working Class karya E.P. Thompson yang tidak sekadar mendeskripsikan kelas pekerja, tetapi menjelaskan bagaimana kelas terbentuk melalui perubahan relasi produksi. Thompson menegaskan bahwa kelas bukan kategori statis.
Contoh lain ialah The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte yang tidak sekadar mengisahkan kudeta atau motivasi individu Bonaparte. Marx menelaah bagaimana kepentingan kelas hadir dalam proses revolusi dan berkelindan dengan kondisi ekonomi serta pertentangan ideologi.
Dengan cara pandang seperti itu, penulisan sejarah Indonesia tidak akan lagi melihat perpindahan tenaga kerja antarwilayah atau lintas negara semata sebagai gejala kemaritiman atau kurangnya cinta tanah air. Sejarah yang dialektis mengajak kita memahami bagaimana fenomena tersebut berkaitan dengan relasi produksi global—perampasan tanah, upah murah, dan konflik kelas—yang membentuk kehidupan sehari-hari kita.
Dengan demikian, sejarah dapat kembali relevan bagi masyarakat.
Fathul Karimul Khair adalah cucu seorang pelaut dan seorang sejarawan pemula, dengan akun IG: @erikfathul