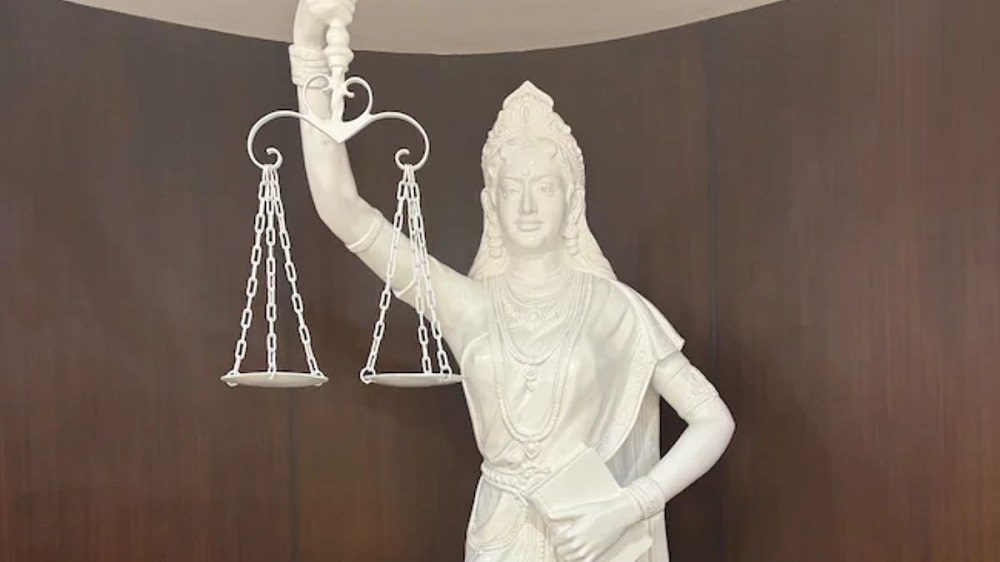Ilustrasi: Lady of Justice/Sahilonline
Hukum, Sosialisme, dan Warisan Ambivalensi
Perdebatan mengenai posisi hukum dalam sosialisme telah menjadi bagian integral dari tradisi intelektual Marxis sejak abad ke-19, dan diskusi ini tidak kehilangan relevansinya bahkan di abad ke-21. Dalam garis besar pemikiran Marxis ortodoks, hukum dilihat sebagai bagian dari suprastruktur yang mencerminkan dan menopang “basis” ekonomi kapitalis, yakni relasi produksi yang eksploitatif. Hukum dipahami sebagai ekspresi dari dominasi kelas yang dilembagakan; sebuah alat legitimasi ideologis sekaligus instrumen represi yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melanggengkan struktur dominasi yang ada.
Pandangan ini menimbulkan konsekuensi logis yang radikal: jika kapitalisme digantikan oleh sosialisme, yakni masyarakat tanpa kelas dan tanpa relasi produksi eksploitatif, maka hukum sebagai cerminan kapitalisme juga seharusnya akan lenyap. Dalam masyarakat sosialis yang ideal, hukum dianggap tidak lagi relevan, karena tidak ada lagi struktur sosial yang perlu dikontrol oleh norma hukum formal. Pandangan ini terkenal dengan rumusan “pemudaran hukum” (withering away of law).
Namun, dalam praktik historis, banyak negara yang mengklaim sebagai negara sosialis justru tetap mempertahankan dan bahkan memperkuat lembaga-lembaga hukum. Uni Soviet, yang kerap dijadikan contoh utama, tetap memiliki sistem hukum formal yang lengkap. Meski konon mengedepankan ideologi proletariat dan partisipasi rakyat, hukum di sana kerap digunakan untuk membenarkan penindasan politik, memenjarakan oposisi, dan menekan kebebasan sipil. Hukum kehilangan daya emansipatorisnya dan berubah menjadi alat kontrol negara atas kehidupan warga.
Kontradiksi ini menunjukkan adanya dilema mendasar: jika sosialisme bertujuan untuk membebaskan manusia dari dominasi dan ketidaksetaraan, maka mengapa hukum justru dikesampingkan atau dilemahkan? Bukankah absennya hukum justru membuka ruang bagi kekuasaan yang tak terbatas? Mengandalkan spontanitas revolusioner atau kekuasaan politik tunggal, tanpa keberadaan institusi hukum yang mengatur dan membatasi, berisiko menciptakan kondisi baru yang lebih represif..
Dalam konteks ini, pendekatan struktural-deterministik Marxisme klasik tampak tidak cukup memadai. Dengan memahami hukum semata-mata sebagai refleksi pasif dari basis ekonomi, pendekatan ini gagal melihat hukum sebagai ruang artikulasi politik dan normatif yang relatif otonom, sebuah arena yang bisa diperebutkan, ditafsir ulang, dan direklamasi untuk tujuan progresif.
Evgeny Pashukanis dan Mimpi Sosialisme Tanpa Hukum
Salah satu pemikir paling penting yang membentuk perdebatan ini adalah Evgeny Pashukanis, seorang ahli hukum Soviet yang mencoba membangun teori hukum Marxis yang konsisten secara metodologis dan ideologis. Dalam magnum opus-nya, The General Theory of Law and Marxism (1924), Pashukanis berargumen bahwa bentuk hukum modern merupakan produk historis dari masyarakat borjuis yang berbasiskan pertukaran komoditas antar individu yang bebas secara hukum, tetapi terpisah secara sosial dan ekonomi.
Menurut Pashukanis, inti dari bentuk hukum adalah bentuk subjek hukum, yakni individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Namun bentuk ini, menurutnya, tidaklah netral: ia lahir dari kebutuhan kapitalisme untuk mengatur pertukaran antar pemilik komoditas. Oleh karena itu, dalam masyarakat sosialis, di mana hubungan sosial tidak lagi dimediasi oleh pertukaran barang dalam pasar, bentuk hukum ini akan kehilangan fondasi historisnya. Hukum tidak akan lagi diperlukan, dan akan mengalami proses “pemudaran” seiring transformasi masyarakat.
Gagasan ini sangat berpengaruh dan mengilhami keyakinan bahwa sosialisme sejati tidak membutuhkan hukum dalam bentuk yang dikenal saat ini. Namun, idealisasi tersebut rapuh ketika diuji oleh kenyataan sejarah. Di bawah Stalin, Uni Soviet justru membangun sistem hukum yang represif dan birokratis, di mana hukum menjadi alat untuk menegakkan kediktatoran partai, bukan sebagai instrumen emansipasi. Ironisnya, Pashukanis sendiri menjadi korban dari sistem tersebut: ia ditangkap, dipaksa mengakui “pengkhianatan,” dan dieksekusi dalam pembersihan politik.
Tragedi Pashukanis menunjukkan bahwa absennya institusi hukum yang kuat dan akuntabel tidak serta-merta membawa kebebasan. Justru sebaliknya, ia membuka jalan bagi kekuasaan yang tak terkendali. Oleh karena itu, pemikiran Pashukanis perlu direfleksikan ulang, bukan untuk ditolak seluruhnya, tetapi untuk diambil pelajaran tentang pentingnya mengembangkan bentuk hukum yang baru, bukan meniadakan hukum sama sekali.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Christine Sypnowich dan Kritik terhadap Abolisionisme Hukum
Kebalikan dari posisi abolisionis ala Pashukanis, Christine Sypnowich, seorang filsuf hukum asal Kanada, menawarkan pendekatan yang lebih dialektis dan progresif terhadap relasi antara sosialisme dan hukum. Dalam berbagai karya pentingnya, termasuk buku The Concept of Socialist Law (1990) dan artikel Law and the Socialist Ideal (2021), Sypnowich menantang asumsi lama bahwa masyarakat sosialis ideal seharusnya tidak membutuhkan hukum. Ia menyatakan secara tegas: “My book challenges the view that an ideal socialist society would have no need of law.”
Menurut Sypnowich, pandangan yang menolak hukum sama sekali adalah keliru karena gagal memahami bahwa hukum juga merupakan wadah artikulasi nilai dan perjuangan politik. Hukum bukan hanya alat dominasi, tetapi bisa menjadi wahana untuk mewujudkan nilai-nilai kesetaraan, solidaritas, dan kebebasan yang substansial. Dengan kata lain, hukum tidak harus netral atau represif—ia bisa dipolitisasi secara emansipatoris.
Dalam kerangka tersebut, Sypnowich mengusulkan pendekatan yang ia sebut sebagai perfeksionisme egaliter (egalitarian perfectionism), yakni pandangan bahwa negara harus secara aktif terlibat dalam memajukan nilai-nilai progresif dalam masyarakat. Negara tidak bisa bersikap netral terhadap ketidaksetaraan struktural, diskriminasi berbasis gender atau ras, atau subordinasi budaya. Hukum dalam masyarakat sosialis, oleh karena itu, harus berpihak secara eksplisit pada kelompok-kelompok tertindas, dan membantu membentuk kondisi sosial yang memungkinkan realisasi kebebasan substantif.
Sypnowich juga menyatakan bahwa supremasi hukum (rule of law) tetap relevan dalam masyarakat sosialis, bukan sebagai fetisisme prosedural seperti dalam liberalisme klasik, tetapi sebagai jaminan kelembagaan atas kesetaraan hak, akuntabilitas kekuasaan, dan partisipasi warga negara. Hukum yang baik, bagi Sypnowich, bukan hukum yang “netral”, tetapi hukum yang mencerminkan aspirasi etis masyarakat yang bebas dari dominasi dan hirarki yang tidak sah.
Dari Alat Represi Menuju Wahana Emansipasi
Kritik terhadap reduksi hukum sebagai ideologi semata mendorong para pemikir Marxis kontemporer untuk melihat hukum secara lebih dialektis. Christine Sypnowich, misalnya, menyodorkan pendekatan yang menyatukan nilai-nilai sosialisme dengan institusi hukum. Ia menolak pandangan bahwa hukum hanya menjadi perpanjangan tangan kapitalisme, tetapi juga tidak terjebak dalam idealisasi liberal. Dalam karyanya, hukum diposisikan sebagai sarana transformasi sosial yang demokratis.
Bagi Sypnowich, supremasi hukum tetap penting dalam masyarakat egaliter. Dalam kerangka demokrasi radikal, hukum bukan sekadar alat pengaturan, tetapi mekanisme untuk menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan setara, memiliki akses terhadap hak, dan dapat menuntut tanggung jawab negara. Hukum menjadi prasyarat institusional bagi terciptanya masyarakat yang bebas dari dominasi.
Salah satu gagasan paling penting dari Sypnowich adalah “perfeksionisme egaliter”, yakni pandangan bahwa negara harus terlibat aktif dalam memajukan nilai-nilai budaya yang progresif. Negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan, diskriminasi, atau budaya patriarkal. Hukum dalam konteks ini bukan hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga menciptakan kondisi substantif bagi kebebasan yang sejati. Misalnya, hukum dapat dipakai untuk mereformasi sistem pendidikan agar membebaskan, atau mendorong pengakuan terhadap kerja reproduktif perempuan.
Gagasan ini bersesuaian dengan pemikiran G.A. Cohen, yang menekankan pentingnya etika sosialisme. Bagi Cohen, sosialisme harus berangkat dari prinsip-prinsip moral seperti solidaritas, kesetaraan, dan kebebasan sejati, bukan sekadar kalkulasi efisiensi struktural. Ia menolak fatalisme struktural Marxis dan justru melihat perubahan sebagai hasil dari komitmen nilai yang diwujudkan dalam kebijakan dan institusi konkret. Dengan begitu, hukum dipahami bukan hanya sebagai produk dari struktur ekonomi, tetapi sebagai ruang politis dan normatif yang harus diklaim oleh gerakan emansipatoris.
Dengan pendekatan ini, hukum dalam sosialisme masa depan dapat diformulasikan ulang sebagai ruang perjuangan, bukan semata instrumen teknokratis. Ia menjadi wahana di mana hak-hak baru dirumuskan, bentuk-bentuk ketidakadilan baru diidentifikasi, dan solidaritas sosial dibangun secara legal dan institusional.
Antara Realitas Historis dan Imajinasi Hukum Masa Depan
Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimana pendekatan-pendekatan ini bisa diterapkan secara konkret? Pengalaman negara-negara yang pernah menerapkan sosialisme memberikan pelajaran penting, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan mereka membangun hukum yang adil. Kuba, misalnya, adalah contoh yang kompleks. Konstitusinya menjanjikan partisipasi rakyat, kesetaraan, dan hak-hak sosial. Namun dalam praktiknya, terdapat represi terhadap oposisi, pembatasan terhadap kebebasan sipil, dan kelemahan dalam sistem peradilan independen. Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa hukum progresif di atas kertas tidak otomatis menjamin emansipasi jika tidak didukung oleh kelembagaan yang demokratis.
Di sisi lain, pengalaman negara-negara Eropa Utara yang mengadopsi prinsip-prinsip sosial-demokrasi menunjukkan bahwa supremasi hukum, partisipasi politik, dan negara kesejahteraan bisa berjalan berdampingan. Meski tidak menyebut diri sosialis, mereka memperlihatkan bagaimana hukum bisa digunakan untuk menstrukturkan keadilan distributif, menjamin perlindungan sosial, dan memperluas hak-hak sipil. Ini menunjukkan bahwa cita-cita sosialisme tidak harus berarti penghapusan hukum, tetapi justru menuntut transformasi radikal atas bentuk, isi, dan orientasi hukum.
Tugas kita hari ini bukan sekadar mengkritik hukum yang ada, tetapi membayangkan hukum yang akan datang: hukum yang tidak lagi menjadi simbol netralitas palsu, melainkan ekspresi dari komitmen terhadap pembebasan kolektif. Kita membutuhkan hukum yang tidak takut berpihak kepada yang tertindas, yang membuka ruang bagi artikulasi politik rakyat, dan yang menjamin bahwa demokrasi bukan hanya prosedur, tetapi juga substansi kehidupan sehari-hari.
Penutup: Mewujudkan Hukum Sosialis yang Emansipatoris
Sosialisme abad ke-21 tidak bisa menghindari pertanyaan tentang hukum. Ia harus mengembangkan bentuk hukum baru yang tidak mengulangi kesalahan otoritarianisme, tetapi juga tidak tunduk pada legalisme liberal yang steril. Supremasi hukum dan nilai-nilai sosialisme bukanlah kutub yang bertentangan, melainkan bisa dan harus saling menopang.
Hukum dalam sosialisme masa depan bukan hanya alat untuk mengatur masyarakat yang sudah adil, tetapi bagian integral dari proses menciptakan keadilan itu sendiri. Ia harus dirancang untuk memperkuat partisipasi, melindungi yang rentan, menantang ketimpangan, dan mewujudkan nilai-nilai emansipatoris dalam bentuk kelembagaan. Dengan membebaskan hukum dari cengkeraman kapitalisme, namun tidak menghapusnya, kita dapat menjadikannya bagian integral dari perjuangan menuju dunia yang lebih setara dan manusiawi.
Daftar Pustaka
Cohen, G.A. Why Not Socialism? Princeton University Press, 2009.
Pashukanis, Evgeny. The General Theory of Law and Marxism. Transaction Publishers, 2002 [1924].
Sypnowich, Christine. The Concept of Socialist Law. Oxford University Press, 1990.
Sypnowich, Christine. Law and the Socialist Ideal. In Research Handbook on Law and Marxism, Edward Elgar Publishing, 2021.
Sypnowich, Christine. GA Cohen: Liberty, Justice and Equality. John Wiley & Sons, 2024.
Wildan Eka Arvinda adalah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung