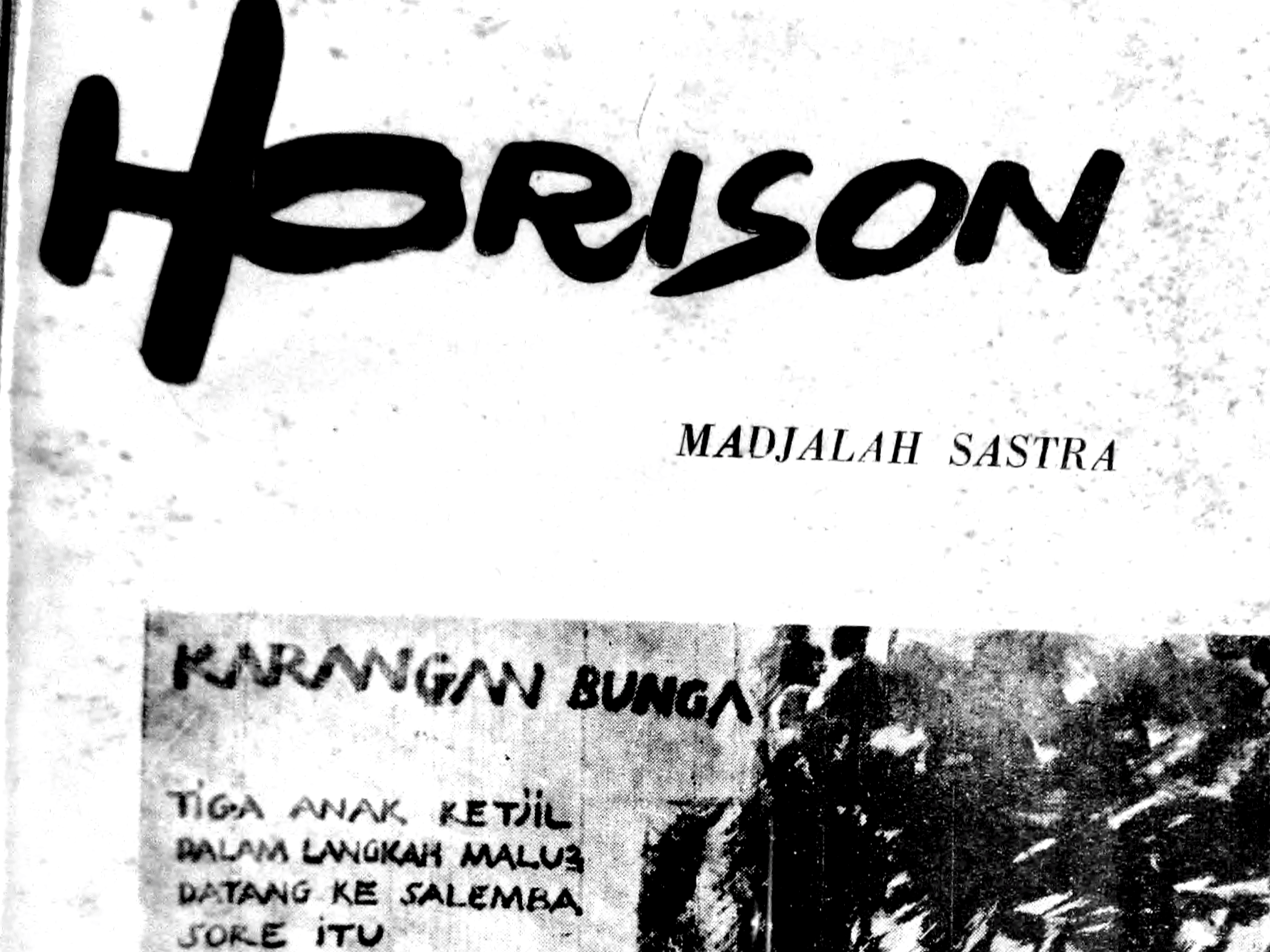Ilustrasi: Wikimedia Commons
ADA sebuah masa ketika siapa pun yang karyanya dimuat di majalah Horison dipercaya telah “dibaptis” menjadi sastrawan Indonesia. Begitulah kiranya “kekeramatan” majalah Horison di masa prime-nya dulu. Kini, bulanan yang didirikan pada 1966 itu tinggal nama belaka. Mereka sempat melebarkan sayap ke ranah digital pada 2016, tepat 50 tahun kelahirannya, tetapi tak ada kabar lagi setelah itu.
Juli 2025, lima dasawarsa dan sembilan tahun berlalu, bisa dikatakan belum ada satu pun majalah seangker Horison. Meski tinggal cerita, kisah epiknya bertahan di sudut-sudut obrolan sastra dan masih terus menyebar, syukur-syukur berkembang. Adalah Horison yang melahirkan sastrawan beken seperti Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi W.M., Umar Kayam, dan beberapa nama lain. Hingga pada satu titik, karena keagungan narasi itu sendiri, kewibawaan Horison laksana mitos saja: bisa dipercaya, bisa tidak.
Tentu saja bisa tidak, sebab kekeramatan itu terasa janggal mengingat terbitnya Horison cenderung merupakan reaksi politis alih-alih buah idealisme sastrawi. Ia lahir setahun setelah kehancuran sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) akibat penyokong Lekra, rezim Orde Lama, runtuh. Ia berawal dari keresahan Mochtar Lubis (sang pembenci Lekra) dan Arief Budiman atau Soe Hok Djin (kakak dari Soe Hok Gie) yang muak dengan pemerintahan Soekarno (Hill, 2011:151). Dengan kata lain: Horison sudah bias sejak pendirinya.
Horison memang menjadi angin segar bagi sejumlah sastrawan, tapi tak lain mereka adalah yang tersingkir dari percaturan sastra di rezim sebelumnya. Mereka adalah para sastrawan yang tak bebas berkarya, seperti kalangan Manifesto Kebudayaan yang mendeklarasikan diri pada 1943 (Hill, 2011:152-153). Horison juga menjadi ajang balas dendam bagi sastrawan yang ngebet karyanya terbit di majalah Sastra, yang sama-sama dikuratori Jassin, yang berhenti terbit pada 1964 akibat diserang Lekra. Horison langsung dianggap penerus Sastra, karena kehadiran Jassin dan banyak memuat karya sastrawan Manifes Kebudayaan (Hill, 2011:152).
Meski Jassin saat itu mulai masyhur sebagai kritikus penting, alasan Mochtar mengajaknya tak jauh dari kesatuan visi mereka: sama-sama membenci Lekra. Dalam ulasannya soal kerja kritik Jassin, Saeful Anwar menulis bahwa Jassin adalah korban “praktik politik yang dijalankan PKI.” Jassin bahkan dipecat dari kerjaannya setelah diserang Lekra, buntut dari beda pendapat; alasan kuat bagi Jassin untuk membenci Lekra. Jangan lupa, Mochtar merupakan ketua Yayasan Obor Indonesia, yayasan yang oleh Martin Suryajaya disebut memasarkan “ide-ide yang ‘secara filosofis’ mempromosikan kapitalisme Barat dan sikap anti-komunis.”
Jassin sendiri adalah penandatangan Manifesto Kebudayaan (Hill, 2011:152). Begitu juga dengan dewan redaksi Horison lainnya: Arief Budiman (juga pendiri Horison), D.S. Moeljanto, dan Zaini. Sementara Taufiq Ismail merupakan sosok yang beasiswanya dicabut oleh negara karena dia mendukung Manifes Kebudayaan, satu hal yang membuatnya otomatis memusuhi Lekra. Barangkali hanya P.K. Ojong yang tak begitu tampak bermusuhan dengan penulis dan organisasi kiri.
Dalam Kata Perkenalan di edisi pertama pun, Mochtar memperkenalkan Horison sebagai wadah sastra yang menyuarakan kebebasan, sebagaimana slogan yang digaungkan oleh para anggota Manifesto itu. Dia secara terang-terangan ingin menggapai cita-cita kebebasan menggunakan sastra. Seolah lebih menampakkan semboyan perlawanan dirinya atas rezim Orde Lama yang barusan tumbang. Mochtar pun lebih cocok dianggap terbakar oleh kebenciannya kepada Orde Lama dan sosialisme, ketimbang keinginan memajukan kesusastraan itu sendiri.
Hal itu sama dengan Jassin (2018:22) tatkala mengukuhkan Angkatan 66, yang lebih menegaskan sebagai upaya “pemberontakan penyair, pengarang, dan cendekiawan, yang dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak wajar”, daripada cita-cita estetis sastrawi. Tak heran jika Angkatan ’66 kemudian dianggap tak terpisahkan dengan majalah Horison. 23 dari 55 nama yang Jassin kukuhkan sebagai Angkatan 66 pernah menerbitkan karyanya di Horison. Dan karya 33 sastrawan pernah ditayangkan di Sastra. Suatu kecenderungan yang sangat jelas kepada kelompoknya sendiri.
Selain itu, pendonor Horison melalui Yayasan Indonesia, yakni Congress for Cultural Freedom (CCF), adalah organisasi yang diam-diam didanai Central Intelligence Agency (CIA) (Hill, 2011:153). Pendanaan ini ditengarai menjadi salah satu upaya Amerika Serikat dalam proyek besar pemberantasan komunisme di seluruh pojok bumi. Namun, Mochtar yang kemudian menjadi anggota Dewan Eksekutif International Association for Cultural Freedom (IACF), penerus CCF, menampik itu. Dia menjelaskan bahwa anggota CCF tak tahu apa-apa soal campur tangan CIA dan upaya pemberangusan komunisme. Di kemudian hari, untuk mengembalikan kepercayaan publik, Mochtar menegaskan bahwa IACF tak lagi di bawah ketiak CIA.
Setelah itu, Horison benar-benar menghilangkan jejak-jejak kaum kiri. Edisi tahun 1969 adalah contoh paling nyata. Nurlan, wartawan dua koran terbitan Lekra, Zaman Baru dan Harian Rakyat, harus mengubah namanya menjadi Martin Aleida agar karyanya dimuat Horison. Martin akhirnya terus menggunakan nama baru tersebut agar terbebas dari diskriminasi Orba. Dwi Kartikasari (2014:453-465) dalam “Pelarangan Buku-buku Karya Sastrawan Lekra Tahun 1965-1968”, menganggap Horison berkenan memuat karya sastrawan kiri asalkan identitas kiri-nya disembunyikan bahkan dihapus.
Jelas sudah bahwa keberadaan Horison dan status “sigma” yang diperolehnya merupakan aji mumpung atas ditindas-asingkannya para sastrawan kiri oleh rezim Orde Baru Soeharto. Horison dan orang-orangnya mengambil kesempatan di saat sastrawan kiri kawakan seperti Pramoedya Ananta Toer, S. Rukiah, Utuy Tatang Sontani, A.S. Dharta, dan Putu Oka Sukanta tengah diasingkan. Di saat yang sama, izin sejumlah surat kabar dan majalah haluan kiri juga dilarang Orba. Dua hal yang secara niscaya membuat Horison tak punya saingan. Hanya ketika 1970-an akhir Horison mulai layu, itu pun bukan karena keberadaan sastrawan atau majalah haluan kiri.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Meskipun di kemudian hari Horison mengkritik pemerintah secara halus terkait pengasingan sastrawan kiri, itu tak lebih dari proyeksi dari isi cerpen-cerpen yang dimuat, bukan sebuah pernyataan sikap resmi (Hill, 2011:158). Kenyataannya, tetap saja, dalam peluncuran wajah baru Horison pada 1982, disusul seminar bertema “Realisme Sosialis dan Humanisme Universal”, sekelompok sastrawan di Horison masih menampakkan alergi mereka terhadap penulis Lekra yang baru saja bebas dari pengasingan. Arief Budiman memang mulai melunak, tapi itu tak melemahkan status Horison sebagai majalah “benteng anti-kiri” (Hill, 2011:152). Posisi itulah yang kemudian menjadikan majalah ini agak meragukan bila harus dianggap sebagai “pembaptis” sastrawan Indonesia. Terlampau banyak bias dari para jajaran redaksinya.
Terkait kekaryaan, Horison pun sebenarnya dihunjam kritik. Tahun 1974 adalah saksi atas tuntutan bertajuk “Pengadilan Puisi” dari sekawanan penulis (Hill, 2011:153). Dalam acara yang selanjutnya ditanggapi kadang serius kadang bercanda itu, mereka menuntut pemberhentian para redaktur dan pembubaran majalah Horison. Redaktur Horison dianggap mementingkan selera pribadi dalam memilih karya, yang akhirnya menghambat perkembangan puisi di Tanah Air.
Walaupun setelah itu satu pentolan acara itu, Slamet Sukirnanto meminta maaf lantaran muncul “Jawaban Atas Pengadilan Puisi” oleh Jassin, M.S. Hutagalung, Goenawan Mohamad, dan Sapardi Djoko Damono, tetap saja, Hamzah Muhammad menilai Pengadilan Puisi sebagai “pelarian dari kejenuhan estetika sastra yang muncul pada kehidupan sosial setelah 1965,” di mana Horison dan Jassin berlakon sebagai agen utamanya. Hamzah juga mengaitkan peristiwa ini dengan pikiran Darmanto Jatman, yang menganggap produsen citra (mitos) “keluhuran” Chairil Anwar adalah Jassin dan Arief Budiman.
Kenyataan bahwa sejumlah cerpen yang membahas peristiwa ’65 terbit di Horison memang tak bisa ditampik. Namun, Wijaya Herlambang dalam wawancaranya berpendapat, alih-alih menjadi bahan pembongkaran peristiwa ’65, cerpen-cerpen itu justru semakin melegitimasinya. Ada rekayasa psikologis yang menimbulkan afirmasi terhadap pemusnahan komunisme (Herlambang, 2013:119), dan menyodorkan penerimaan kepada pembaca bahwa kekerasan itu normal dan alamiah. Bagi Roosa (2003:13), cerpen itu “tidak menampilkan pembunuhan itu sebagai kepedihan bagi korban, tetapi sesuatu yang tragis bagi para pembunuh karena mendamaikan pembunuhan itu dengan nilai-nilai kemanusiaan.” Menjadikan cerita-cerita itu sebagai contoh nyata kekerasan budaya menurut Galtung: normalisasi kekerasan melalui produk-produk kebudayaan.
Teeuw pun sebenarnya pesimis terhadap majalah ini. Dia menulis itu di bukunya Sastra Indonesia Modern II pada 1989, 23 tahun setelah Horison didirikan. Dia menilai masa kejayaan Horison terlalu pendek (Poesponegoro & Djoened, 2022:698). Tahun itu, Horison mengalami kelesuan yang sebenarnya sudah terasa sejak akhir 1970-an (Hill, 2011:155). Bahkan, pada 1982, empat media lain dimintai sumbangan untuk menghidupkan kembali Horison. Bisa jadi Teeuw menilai, dengan umurnya yang pendek, Horison tak seharusnya dipandang sebegitu tinggi sebagai standar mutu sastra kala itu.
Walaupun begitu, satu pendapat muncul dari Kasjianto dalam tesisnya berjudul “Perjalanan Sunyi Menuju Kakilangit: Upaya Horison Membuka Ruang Publik”, yang “meluruskan” stigma terhadap Horison akibat terlontarnya kritik-kritik tersebut. Kasjianto mengatakan bahwa para pengkritik Horison sebenarnya menyimpan rasa iri hati (Poesponegoro & Djoened, 2022:697). Mereka mengkritik, tapi juga mencintainya. Mereka menyerang, tapi dibarengi keinginan karyanya turut dimuat. Anggapan bahwa Horison adalah majalah yang “serius, berwibawa, dan penting,” lanjut Kasjianto, merupakan citra yang diciptakan oleh para pembacanya sendiri.
Begitulah, semua sudah terjadi. Terbentuknya “kanon sastra Horison” pun tak terelakkan dan kanon itulah yang membentuk sastra Indonesia masa kini—bisa jadi yang paling dominan. Entah di lapangan sastra, maupun di judul-judul skripsi dan tesis mahasiswa kampus sastra (di kampus saya: dosen tak jauh-jauh dari nama Umar Kayam, Sutardji, dan sastrawan Manifes Kebudayaan lainnya). Belakangan Pramoedya mulai banyak disebut, tapi tidak dengan kawan-kawan seperjuangannya itu. Penulis kiri tetap meringkuk gosong di tungku-tungku pemberangus komunisme.
Terlepas dari suksesnya konspirasi pembasmian ideologi kiri, penilaian dan pemujian hingga pengagungan yang berlebihan terhadap karya, tokoh sastra, ideologi, atau media sastra (seperti yang terjadi pada Horison) ternyata tampaknya menjadi intrik yang masih umum ditemukan dalam jagat sastra Indonesia.
Tak terkecuali pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon baru-baru ini, bahwa Taufiq Ismail adalah Bapak Sastra Indonesia. Padahal Roosa (2008:50) menyebut Taufiq Ismail (seperti di bukunya sendiri) sebagai salah satu tokoh yang melegitimasi kekerasan ’65. Sehingga “pembunuhan massal antikomunis 1965-66, merupakan tindak pencegahan pembunuhan massal lebih besar yang akan dilakukan kaum komunis.” Ternyata, pengagungan terhadap Taufiq Ismail tidak lepas dari hubungan Fadli Zon sebagai keponakan dari Taufiq Ismail.
Hanya saja, kebanyakan orang stecu saja. Padahal itu menguatkan subjektivitas dan kebiasan dalam iklim kritik sastra di Indonesia.
Daftar Pustaka
Herlambang, Wijaya (2013), Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, Jakarta: Marjin Kiri.
Hill, David T. (2011), Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) Sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jassin, H. B. (2018), Angkatan 66: Prosa dan Puisi, Jakarta: Pustaka Jaya.
Kartikasari, Dwi, “Pelarangan Buku-buku Karya Sastrawan Lekra Tahun 1965-1968”, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No 3, Oktober 2014, 453-465.
Poesponegoro; Marwati Djoened (2022), Sejarah Nasional Indonesia Jilid: Zaman Jepang dan Zaman Republik, Jakarta: Balai Pustaka.
Roosa, John (2008), Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
Roosa, John; Ratih, Ayu; Farid, Hilmar (2003), Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Hilmi Baskoro, sempat menjadi jurnalis Jawa Pos Radar Jember, kini aktif di komunitas sastra Seribu Satu Halaman, Jember.