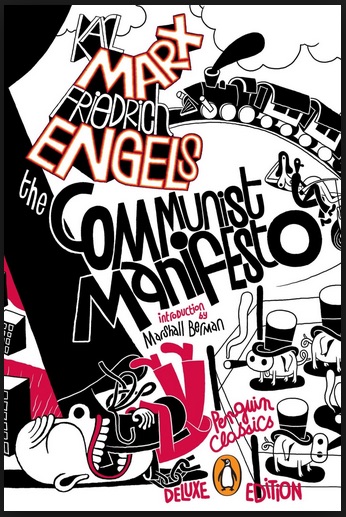Kredit ilustrasi: Philosophers for Change
(Sebuah Prolegomena)
KOMUNISME merupakan ideologi yang paling banyak disalahpahami ketimbang dimengerti. Ia dinyatakan usang, namun buktinya masih relevan hingga sekarang. Ia dinyatakan mati, namun anehnya sampai sekarang masih terus digali.
Demi untuk menunjukkan usangnya Marxisme dan Komunisme, para intelektual liberal mengumbar lelucon: “tak ada yang tersisa dari Komunisme selain sekedar mode anak muda yang gandrung menenteng kitab Marx seperti Das Kapital, yang banyak tak dimengerti oleh para Marxis sendiri”. Untuk menjawab lelucon semacam ini, kita tak perlu mengutip kalimat-kalimat penting Marx. Wajar saja kalau tidak semua kelas pekerja bisa mencerna dan harus mengerti berjilid-jilid kitab Marx, khususnya Das Kapital. Sebab kondisi yang sama juga terjadi di dalam ideologi-ideologi yang lain. Ini tak jauh beda dengan kaum muslim yang sebagian besar tak mengerti isi A-Qur’an dan hadis Nabi, atau kaum Kristen yang tak semuanya bisa memahami Injil dengan baik.
Kemudian timbul pertanyaan, apa yang bisa dipetik dari Marxisme, atau apakah ada gunanya membaca dan memahami karya-karya Marx, khususnya Manifesto Komunis yang tengah kita bicarakan sekarang, sesudah ambruknya Uni Soviet? Kekeliruan dari pertanyaan semacam ini adalah mencampuradukkan antara pemikiran dan sejarah, antara Marxisme sebagai sebuah pemikiran dengan eksperimentasi politik semacam Soviet.
Jaques Derrida (2000) dalam Specter de Marx, mengingatkan perihal pentingnya apa yang disebut sebagai “jiwa marxisme” dengan kritik radikalnya terhadap hukum-hukum kapital untuk memahami kondisi kontemporer seperti sekarang. Ini menandakan bahwa seseorang tak akan mengerti hukum gerak kapital tanpa terlebih dulu memahami marxisme.[1]
Manifesto Komunis (selanjutnya disebut Manifesto) mungkin karya Marx dan Engels yang paling terkenal, baik di kalangan Marxis maupun non Marxis yang tidak mengerti dasar-dasar filsafat Marxisme. Tak heran, kalimat pembuka dan penutup Manifesto: ‘Ada hantu berkeliaran di Eropa –hantu Komunisme’ dan ‘kaum proletar seluruh negeri bersatulah!’ menjadi slogan yang sangat terkenal di luar kelas pekerja dan kalangan Marxis.
Buku tipis yang terbit pertamakali pada 1848 ini, tidak bisa tidak merupakan dokumen politik penting, kalau tidak yang paling penting, yang telah menginspirasi berbagai revolusi dunia, serta perjuangan kemerdekaan warga jajahan dari cengkeraman kolonialisme. Manifesto tak ubahnya bara api yang berkobar-kobar menyambar semangat perjuangan bagi, tidak hanya kelas pekerja, melainkan juga kaum pergerakan nasionalis di hampir semua negeri-negeri jajahan dalam rentang abad dua puluh. Bahkan, bisa jadi, tak ada seorang pun di kalangan pergerakan di negeri-negeri jajahan yang tidak membaca karya Marx dan Engels ini.
Manifesto merupakan pamflet politik, ketimbang sebuah filsafat politik yang mendalam. Karena itu Manifesto ditulis dengan bahasa yang lugas sekaligus memukau yang dengan mudah bisa dicerna siapa saja, sebagai landasan perjuangan politik kaum komunis.
Meski demikian, sebenarnya Manifesto tak hanya ditujukan pada kelas pekerja industrial yang setiap hari merasakan secara langsung penghisapan kapitalisme, melainkan secara universal ditujukan pada siapapun rakyat tertindas di seluruh dunia.
Manifesto bisa diletakkan sebagai simpul yang menyatukan imajinasi kolektif perjuangan rakyat tertindas dari berbagai agama dan etnis di seluruh penjuru dunia. Ia bisa menjadi panji bersama antar agama, antar bangsa dalam mewujudkan cita-cita universal menegakkan keadilan di dunia. Pendeknya, orang-orang tertindas di seluruh dunia (mustadh’afun fi al-ardh) yang dilemahkan oleh relasi produksi kapitalisme bisa menjadikan Manifesto sebagai landasan dan Marxisme sebagai minhaj atau metode perjuangan bersama melampaui sekat partikularitas yang menghambat serta menjadi batas di antara diri mereka.
Sayangnya, pasca peristiwa Madiun 48 dan peristiwa 65, secara aksiologis Islam dan Komunisme selalu dibenturkan dan dianggap tidak compatible serta secara politis dikondisikan untuk selalu berada dalam relasi yang saling meniadakan dan menghancurkan. Seolah-olah keduanya harus berhadap-hadapan. Jauh sebelum kedua peristiwa tersebut, Islam dan Komunisme di Indonesia berjalan beriringan bahkan menjadi bagian dari gerakan Islam (baca: sebelum terjadinya perpecahan di tubuh Sarekat Islam, khususnya afdeling Yogya dan afdeling Semarang). Dalam banyak catatan sejarah, laskar-laskar pemuda kiri dan Islam yang keduanya tumbuh subur di Jawa Timur, bahu membahu ketika melawan Belanda dan NICA dalam pertempuran dahsyat di Surabaya. Bahkan organisasi Pemuda Republik Indonesia, pimpinan Soemarsono yang kelak berubah menjadi Pemuda Rakyat, menjadi salah satu yang terbesar pengikutnya di antara berbagai laskar yang ada.
Lebih jauh ke belakang, di sebuah jaman yang disebut Takashi Shiraishi sebagai “Zaman Bergerak”, Islam dan Komunisme pernah memberi inspirasi perjuangan pada hampir semua kaum pergerakan di Hindia Belanda. Saat itu keduanya menjadi senjata perjuangan kaum pergerakan. Mengingat betapa penting dan berharganya Islam dan Komunisme sebagai senjata perjuangan, maka tak berlebihan Haji Misbach merasa menemukan Islamnya via Komunisme.
***
Berbeda dengan filsuf lainnya yang membicarakan manusia sebagai sebuah ide abstrak, dalam semua karyanya, Marx dan Engels membicarakan manusia konkrit yang dihisap oleh relasi produksi kapitalisme, begitu pula di dalam Manifesto. Bahkan bisa dikatakan dalam Manifesto terdapat pokok-pokok pikiran Marxisme yang paling penting, khususnya perihal perjuangan kelas.
“Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas” demikian bunyi kalimat pembuka bagian satu Manifesto Komunis.[2]
Kalimat ini setidaknya berarti dua hal. Pertama, menjadi inti dari perjuangan komunisme, yakni perjuangan kelas. kedua, menunjukkan kebenaran sejarah yang tak bisa ditampik bahwa drama sejarah manusia sejak masa lampau hingga sekarang adalah sejarah perjuangan antara yang menghisap dan yang dihisap, antara yang menindas dan yang ditindas, lebih spesifik lagi antara majikan dan buruh.
Dalam sejarah Islam, selain etika, drama perjuangan kelas menjadi salah sebuah misi utama Islam untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan di bumi, yang diilustrasikan oleh Ali Syari’ati sebagai pertarungan abadi antara Qabil dan Habil.
Mengenai perjuangan kelas ini, seolah-olah Marx dan Engels hendak mengatakan, “entah kalian setuju atau tidak, suka atau tidak, drama perjuangan kelas, akan terus berlangsung selama keadilan dan kesetaraan belum bisa dipancangkan di bumi.” Dalam bingkai argumen seperti ini, saya berani mengatakan bahwa perjuangan kelas adalah keniscayaan yang harus dipanggul kaum mustadh’afin selama kapitalisme belum bisa dihancurkan.
***
Apa yang terkandung di dalam Manifesto sebagian besar sulit dibantah kebenarannya.
Meski demikian jangan perlakukan ia bak kitab suci atau doktrin yang muncrat dari langit yang otomatis dianggap benar. Tidak, perlakukan ia sebagai kitab yang lahir dari rahim sejarah manusia. Mengapa demikian, sebab hanya dengan cara seperti ini, kita akan tetap menjadikannya sebagai dokumen hidup, alih-alih sebagai monumen mati yang beku.
Bahkan saya sarankan, jangan membacanya dengan penuh keyakinan seperti ketika kita membaca al-Qur’an yang mensyaratkan keyakinan mutlak. Tapi bacalah Manifesto dalam terang kritisisme dan skeptisisme akut. Dan yang paling penting adalah bacalah Manifesto seolah-olah Marx dan Engels tengah berbicara denganmu tentang persoalan dunia yang tengah kau hadapi.
Maka di sanalah kebenaran menyibakkan tabirnya. Apa yang terjadi saat ini dengan sendirinya mengonfirmasi kebenaran Manifesto.
Misalnya, mengenai kaitan antara kemerdekaan dan perdagangan bebas sebagaimana hari ini kita lihat. Manifesto dengan apik menyindir bahwa apa yang kebanyakan orang sebut sebagai kemerdekaan dalam masyarakat borjuis, rupanya hanyalah nama lain dari perdagangan bebas.
“Di dalam hubungan-hubungan borjuis sekarang ini yang dimaksud dengan kemerdekaan ialah perdagangan bebas, pembelian dan penjualan bebas”, demikian kata Manifesto.
Inilah yang tengah terjadi di Indonesia. Hari kemerdekaan yang selalu diperingati dengan parade senjata dan baris berbaris, sesungguhnya tak sedang memperingati apa-apa selain kekalahan demi kekalahan yang disembunyikan. Mengapa? Sebab perdagangan bebas telah menjagal kemerdekaan kita.
Sejak ekonomi Indonesia berbalik ke arah liberal di masa yang disebut dengan era developmentalisme (the decade of developmentalism)[3], sejak itulah kemerdekaan kita sirna menjadi ilusi, diganti dengan lahirnya sejumlah undang-undang dan kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994. Tak berhenti di situ, setelah kejatuhan Suharto, para pemimpin Indonesia yang konon dipilih secara demokratis melalui pemilu elektoral, secara konsisten melakukan privatisasi, deregulasi dan pasar bebas.
Pada masa Megawati, deregulasi di bidang tenaga kerja dilaksanakan dengan UU No. 13 tahun 2003, sehingga sekarang dimungkinkan sistem kerja kontrak dan outsorcing. Masih pada masa Megawati, disahkan UU Migas No. 22 tahun 2001 dan Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004, yang memungkinkan pengusaha swasta untuk memiliki minyak dan air di bumi Indonesia. Sedangkan pada masa SBY, beberapa undang-undang bernafas Neoliberal disahkan, antara lain UU penanaman modal asing No. 25 tahun 2007 dan UU Badan Hukum Pendidikan tahun 2008. Sekarang di masa Jokowi, privatisasi total sudah berjalan dengan mulus tanpa banyak rintangan berarti sebagai akibat dari absennya kekuatan kiri di Indonesia.[4]
Dalam konteks global, untuk menggambarkan kontradiksi dan anomali kapitalisme yang menawarkan kemewahan hidup di satu sisi dan mengakibatkan ketimpangan dan malapetaka di sisi lainnya, saya akan mengutip pidato Wakil Presiden Bolivia Álvaro García Linera,
Kita berbicara mengenai pokok soal ini hanya karena satu alasan, dan ini karena masyarakat yang saat ini ada di dunia, masyarakat yang hari ini kita miliki di seluruh dunia, adalah masyarakat dengan terlalu banyak ketidakadilan, masyarakat dengan terlalu banyak ketimpangan … Hari ini, di dunia kapitalis dalam mana kita hidup ini … sebelas juta anak-anak meninggal dunia setiap tahun karena kekurangan gizi, karena pelayanan kesehatan yang buruk, karena tidak ada dukungan untuk mengobati penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan… Sebanyak seluruh penduduk Bolivia mati setiap tahun, dan setiap tahun lagi. Masyarakat kapitalis ini, yang mendominasi dunia, yang memberi kita penerbangan ke angkasa luar, yang memberi kita internet, memungkinkan 800 juta manusia tidur setiap malam dalam keadaan lapar … Sekitar dua milyar orang di bumi ini tidak mendapatkan pelayanan dasar. Kita punya mobil-mobil, kita punya kapal-kapal terbang, sekarang kita berpikir untuk pergi ke planet Mars, betapa indahnya! Tetapi di sini di atas bumi ada orang-orang yang tidak mendapatkan pelayanan dasar, ada orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan, dan kalau ini tidak cukup, ini adalah masyarakat yang secara permanen dan berulang-ulang menimbulkan krisis, dan krisis menimbulkan pengangguran, memaksa perusahaan-perusahaan untuk tutup. Ada begitu banyak kekayaan, tetapi terpusat di tangan sedikit orang. Dan ada banyak orang yang tidak punya kekayaan dan tidak bisa menikmati apa yang ada. Sekarang ini ada 200 juta orang menganggur di dunia ini.
Itulah masalahnya, ini adalah masyarakat yang menimbulkan begitu banyak kontradiksi, yang menghasilkan pengetahuan, ilmu, dan kekayaan, tetapi yang sekaligus menimbulkan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak pengabaian, dan pada puncaknya, tidak puas menghancurkan umat manusia saja dan melanjutkan menghancurkan alam. Ribuan jenis binatang dan tumbuhan telah dihancurkan dalam masa 400-500 tahun terakhir sejak dimulainya kapitalisme. Hutan menjadi semakin sempit dan sempit saja, lapisan ozone sedang dipertipis, kita mengalami perubahan iklim, gunung-gunung bertopi salju abadi sekarang sedang dalam proses kepunahan. Ketika kita berbicara mengenai sosialisme, kita sedang berbicara mengenai sesuatu yang sangat berbeda dari yang sedang kita alami. Kita bisa memberinya nama yang lain. Kalau orang tidak suka kata sosialisme, mereka bisa menyebutnya komunitarianisme, kalau tidak suka komunitarianisme, mereka bisa menamakannya ‘hidup baik,’ tidak masalah, kita tidak berjuang untuk nama-nama.[5]
***
Mengapa kaum mustad’afin harus melawan, dan siapa yang dilawan? Sebab mereka dimiskinkan dengan dihisap hasil-hasil kerjanya, diinjak-injak kemanusiaannya, dan dihancurkan kampung halamannya. Dan mereka bisa menjadikan Manifesto sebagai senjata perlawanannya.
Jadi, yang dilawan oleh mustadh’afin bukanlah bangsa tertentu, atau agama tertentu, bahkan tidak sedang melawan atau anti terhadap sesuatu yang dikategorikan sebagai asing, melainkan hanya kaum kapitalis, semua kaum kapitalis, yang didefinisikan Marx dalam Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, sebagai kelompok atau pihak yang melalui kapitalnya mempunyai kekuasaan yang bisa mengatur buruh dan produk-produknya, serta mampu membeli semuanya.[6]
Manifesto tak selamaya relevan. Pada suatu masa ia akan kehilangan relevansinya, ketika kapitalisme telah tumbang dan diganti dengan kesetaraan masyarakat tanpa kelas dan tanpa penghisapan.***
Jombang, 18 Oktober 2017
————–
[1] Lebih lanjut lih. Jaques Derrida, Hantu-Hantu Marx, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Bentang, 2000).
[2] Semua kutipan Manifesto Komunis dalam tulisan ini saya ambil dari edisi Indonesia Manifesto Partai Komunis yang diterbitkan Ultimus Bandung, edisi perdana tahun 2015.
[3] Kaum developmentalis memandang kemiskinan disebabkan oleh faktor internal bangsa Indonesia, terutama struktur sosial dan mentalitas masyarakat tradisional yang harus diatasi dengan menapaki pengalaman negara-negara Barat dalam perjalanan menuju masyarakat industri, dengan jalan melakukan modernisasi di segala bidang, yang itu artinya tak lain adalah pelaksanaan kapitalisme yang dianggap manjur dalam pengalaman modernisasi di negara-negara Barat.
[4] Lih. I Wibowo, Negara Centeng, Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 133-134.
[5] Álvaro García Linera, berbicara di acara “El pueblo es noticia” pada Channel 7dan Radio Patria Nueva, 8 Februari 2010, sebagaimana dikutip oleh Marta Harnecker, Sosialisme Abad Keduapuluh Satu Pengalaman Amerika Latin, (Edisi e-book, diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016), hal. 43-44.
[6] Karl Marx & Engels, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, diakses dari https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm pada 14 oktober 2017.