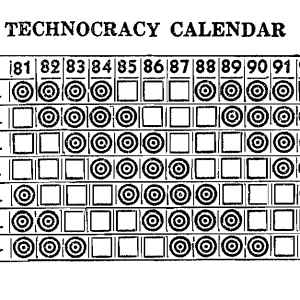Para seniman sayap kiri Rusia, pada periode Lenin, banyak mengklaim bahwa revolusi artistik mendahului revolusi politik. Film sebagai sebuah medium yang mampu merekam “gerak” adalah bahasa sinematografi yang sanggup mengembangkan kodrat artistiknya dalam menyibak selubung “magis” gerak manusia dan bahkan peristiwa. Dalam tradisi montase Rusia, medium film dengan bahasa sinematografinya ini memiliki potensi revolusionernya, melalui cara pandang terhadap realitas dari kemampuannya membawa penonton kepada usaha untuk mengatasi kompleksitas ruang dan waktu dan situasi dalam lokasi-lokasi yang berbeda secara serentak. Sifat transformatif medium film inilah yang kemudian sanggup mematikan seni dramatik dalam tradisi yang klasik, “…karena film mengajarkan kepada kita cara mengatasi tindakan rumit yang berlangsung dalam periode waktu yang berbeda dan lokasi yang berlainan.”[1]
Sementara di sisi lain ada sebuah tradisi realisme, di mana film adalah kemampuan kamera untuk merekam intensitas suatu peristiwa. Gaya tradisi ini adalah kemampuan kamera untuk menyibak realitas melalui bidikan (shot) yang panjang dan intens untuk mengurangi dari sebuah subyek atau peristiwa tertentu. Model gaya sinema ini sepenuhnya menyerahkan gambar pada peristiwa yang berlangsung di hadapan kamera. Pendekatan kamera pada gaya sinema ini menjadi semacam pemerolehan realitas atau pengetahuan secara “sensory” melalui perekaman kamera. Dalam perkembangannya, salah satu perkembangan gaya intensitas kamera ini adalah neorealisme Italia yang berkembang pada masa pasca-Perang Dunia Ke-2.
Sekilas Tentang Neorealisme Italia
Neorealisme adalah sebuah periode bahasa sinema yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi politik yang melingkupi Italia pasca-Perang Dunia II. Hancurnya studio film di Italia pascaperang justru melahirkan sebuah bahasa estetika baru dalam sinema neorealisme. Sutradara macam Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Roberto Rosselini dan lain sebagainya terjun langsung ke lapangan realitas untuk membuat kisah dan sinema berdasarkan bahan baku yang tersedia dalam kenyataan sehari-hari. Ciri kuat gerakan neorealisme Italia ini adalah bagaimana film dibuat dengan latar kenyataan sesungguhnya, dengan latar suasana keseharian di lapangan tempat berlangsungnya pengambilan gambar, serta memanfaatkan para pemain non-profesional yang sedikit-banyak diambil dari situasi setempat berlangsungnya kisah. Salah seorang pemikir dalam gerakan neorealisme Italia, Cesare Zavattini, menyatakan bahwa “Apa yang benar-benar diusahakan bukanlah menciptakan sebuah kisah yang terlihat seperti peristiwa, namun menyajikan realitas yang seolah-olah adalah kisah.”
Perihal mempercayai realitas sepenuhnya sebagai bahan baku estetika sinema pada film-film neorealisme Italia adalah bagian dari kritik atas budaya sinema yang berlangsung sebelumnya, di mana film melulu dibangun berdasarkan ilusi yang seakan-akan merupakan kenyataan. Realisme macam ini diperlihatkan dalam model sinema yang dibangun di studio-studio produksi filem. Menurut kritikus film asal Prancis, Andre Bazin, neorealisme Italia berangkat dari posisi ontologi (realitas) sebelum posisi estetis.
Salah seorang sutradara penting dalam periode neorealisme Italia adalah Luchino Visconti (1906-1976). Cita-cita Visconti terhadap sinema adalah menciptakan “manusia baru”, ia ingin membuat film di luar studio agar bisa menemukan manusia dengan “kemanusiaan”-nya yang sejati. Visconti menyebut karya-karyanya “anthropomorphic cinema”. Semangat Visconti ini adalah usaha-usaha membangun “manusia baru” dengan menghapus dominasi elemen-elemen film yang cenderung menambahkan sesuatu dari manusia pada film. Apa yang sedang digagas oleh Visconti dalam karyanya adalah berangkat dari karakter-karakter manusia yang autentik. Gagasan-gagasan Visconti terhadap kemanusiaan dalam sinema adalah bagian dari bahasa dan bahan baku estetisnya sendiri, yang berdampak pada cara pandang kamera dalam merekam dan merepresentasikan sebuah peristiwa dan manusia.
Realisme dalam “Bumi Bergolak” (La Terra Trema)[2]
“Bumi Bergolak” (1948) adalah satu di antara karya penting Luchino Visconti dari neorealisme Italia. Film ini diadaptasi secara bebas dari karya novel I Malavoglia (1881) karya Giovanni Verga. Judul I Malavoglia (Giovanni Verga) diubah dalam format film oleh Visconti menjadi La Terra Trema (The Earth Trembles/BumiBergolak). Film ini berkisah tentangKeluarga Valastros—nelayan di Aci Trezza, pesisir Timur Sisilia, Italia, dalam tiga alur. Alur pertama adalah tentang ‘Ntoni, anak tertua keluarga Valastros, yang ingin menyelamatkan nasib nelayan dari isapan para tengkulak. Ia memprakarsai pembentukan koperasi sebagai usaha kemandirian bersama para nelayan. Ia menggadaikan rumah untuk memulai usaha sendiri; memiliki kapal, menangkap ikan, dan menjualnya secara mandiri. Alur kedua berkisah tentang keluarga Valastros yang bertahan hidup. Badai laut meluluhlantakkan perahu keluarga Valastros. Tengkulak dan para nelayan lain merasa alam telah melindungi tatanan sosial yang kekal: pengisapan nelayan. Terakhir, alur ketiga berkisah tentang pergulatan keluarga Valastros dalam melawan kaum pemilik modal (tengkulak). Keluarga Valastros harus kehilangan banyak materi dan moril ketika berhadapan dengan tatanan sosial yang menindas. ‘Ntoni pun kembali kepada tengkulak untuk bertahan hidup. Ia menyadari perlunya kolektivitas dalam menghadapi tatanan sosial yang tidak berpihak bagi nelayan.
Novel I Malavoglia sebenarnya sebuah karya yang kurang sukses secara komersial, juga tidak mendapat sambutan yang cukup baik dari kalangan kritikus sastra kala itu. Bahkan Emile Zola pun, yang menjadi panutan Verga, tidak menuliskan kata pengantar yang telah dijanjikannya sebelum buku itu terbit. Beberapa kalangan menganggap I Malavoglia terlalu alamiah dalam penggunaan kata untuk menggambarkan karakter. Novel yang dibuat antara 1870-1880-an ini adalah sastra dengan gaya khas realisme Italia, verismo, yang dipengaruhi naturalisme dan realisme Prancis seperti dalam karya-karya Emile Zola dan Gustave Flaubert. Verismo Verga adalah perseberangan dari pendekatan gaya romantis, yakni gaya yang lebih pada penggambaraan detail berdasarkan empirisme tanpa melibatkan “perasaan” pengarang (author). Verismo memang merupakan usaha penggambaran realitas secara murni. Indra menjadi basis pengetahuan secara murni untuk menggambarkan detail-detail tentang kenyataan yang berlangsung di hadapan pengarang.
Pada film, Visconti menerjemahkan verismo dalam gaya penceritaan yang nyaris tanpa elips. Menurut Andre Bazin, tidak ada aturan suspens kecuali kehidupan itu sendiri. Akibatnya, teknik bidikan gambar (shot), terutama pada ambilan-ambilan di lapangan pantai para nelayan, bidikan di laut, seakan membangun citra terhadap peristiwa, sepenuhnya membuka peluang bagi para penonton untuk turut serta membangun makna di balik kisah.
Pada “Bumi Bergolak”, Visconti sangat pandai mengelola para aktor yang seluruhnya berasal dari penduduk desa nelayan di Pantai Selatan Sisilia. Bahkan ia mampu mengangkat para pemain ini ke dalam “citraan” opera yang cukup aristokrat. Bagi Aristarco, hal ini disebut sebagai derajat-derajat realisme. Verismo membawa sepenuhnya “suspens” kisah kehidupan itu sendiri. Pada 1950-an, setidaknya ada dua posisi pandangan: pertama, Zavattini yang memandang neorealisme sebagai usaha pembebasan realisme, yang disandarkan sepenuhnya pada kamera yang mengurai peristiwa. Melalui hal ini, Zavattini menggali pengetahuan bersama “spectacle”, seolah sebuah cerita tentang orang-orang itu merupakan “cerita” diri mereka sendiri. Kedua, pandangan Guido Aristarco, kritikus Cinema Nouve, yang menyatakan bahwa ada kapasitas sutradara untuk menangkap realitas sehingga membentuk derajat tertentu realisme film. Bagi Aristarco tidak cukup sinema menggambarkan peristiwa yang berlangsung, karena pada tingkat tertentu realisme harus sampai pada dinamika dan motif di baliknya. Perlu bagi realisme untuk menyandarkan dirinya pada sesuatu yang sastrawi. Baginya, hal yang sastrawi dapat menangkap “tingkat kenyataan” sesungguhnya, yang menjangkau dinamika dan motif di balik cerita dalam film tersebut.
Realisme “Keseharian” dalam Bumi Bergolak
Apa yang coba digagas oleh Visconti dalam karyanya, Bumi Bergolak, adalah sebuah usaha menggambarkan kehidupan manusia di dalam lingkungannya yang menindas. “Saya terdorong ke arah sinema, di atas segalanya, kebutuhan untuk menuturkan kisah orang-orang yang hidup, dari kehidupan masyarakat di tengah-tengah sesuatu dan bukan sesuatu diri mereka sendiri. Sinema yang menarik saya adalah sebuah sinema antropomorfik… Signifikasi dari kemanusiaan adalah kehadirannya, hanyalah sesuatu yang dapat mendominasi image. Suasana yang mana hal tersebut menciptakan dan kehadiran yang hidup dari gairahnya memberikan kehidupan dan kedalaman.”[3]
Kekuatan Bumi Bergolak ini, selain menggunakan para aktor yang notabene adalah penduduk nelayan di Pesisir Selatan Sisilia, adalah penggunaan dialek yang berasal dari bahasa lokal setempat. Visconti sanggup membawa para pemain non-profesional yang adalah para penduduk nelayan, dalam sebuah bidikan-bidikan gambar yang puitis. Penggunaan-penggunaan latar situasi sosial masyarakat, suasana pantai, dan alam laut, dibingkai betul oleh Visconti menjadi gambar-gambar yang sanggup memberikan endapan tentang pergulatan manusia terhadap situasi politik dan kehebatan para nelayan dalam mengarungi laut dalam mencari ikan. Semua dirangkum dalam latar keseharian yang berlangsung pada kisah Bumi Bergolak secara gambar.
Satu semangat besar dari gaya neorealisme Italia adalah merujuk pada situasi keseharian yang berlangsung sebagai bahan baku dari kisah yang diangkat ke atas layar. Kekuatan para sutradara neorealisme Italia adalah kemampuannya menghadirkan realitas keseharian, baik melalui latar lapangan tempat berlangsungnya kisah, maupun penggunaan pemain non-profesional yang berasal dari kalangan masyarakat di mana kisah berlangsung. Meski beberapa karya neorealisme Italia—termasuk Bumi Bergolak—diambil dari adaptasi karya sastra, kekuatan penghormatan terhadap “realitas keseharian” masih tetap terjaga.
Bagi seorang Cesare Zavattini, kesetiaan terhadap realitas menjadi kunci penting dalam memandang sinema. Kamera bagi Zavattini justru adalah sarana untuk menyibak realitas yang ada di hadapan manusia. Ia pun sampai berkata “…berikan kami ‘fakta’ apa pun yang Anda suka, dan kami akan mengeluarkan isi perutnya, membuat sesuatu yang layak ditonton.”[4] Zavattini sendiri memang mengakui bahwa realitas dapat dianalisis melalui cara fiksi. Fiksi bisa menjadikan realitas terlihat ekspresif dan alami. Namun, bagi Zavattini, neorealisme adalah sebuah dorongan moral terhadap kemampuan kamera sebagai media yang sanggup membawa sebuah kapasitas asli atau “dokumenteris” dari sebuah kenyataan peristiwa dan manusia. Dalam konteks ini, sinema mampu memberikan semangat “keseharian” karena potensi dokumenteris yang terdapat dalam kodrat sinema. Potensi ini tentu bukan sekadar semangat realitas “keseharian” yang bisa dibawa dalam kodrat sinema, namun juga daya jangkau bahasa sinema yang bisa membawakan pengalaman kepada banyak manusia.
Penutup (Sinema bagi Kalangan Buruh)
Sulit membayangkan bagaimana film sebagai bagian dari kebudayaan bisa memiliki pengaruh penting dalam membangun kesadaran kritis di era kebudayaan massa saat ini. Bahasa film yang berlaku di kalangan buruh, atau kalangan masyarakat luas pada umumnya, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan massa yang berlangsung saat ini, yang tidak mendorong para penontonnya ke arah kesadaran yang kritis. Hal ini menjadikan film sebagai produk kebudayaan “afirmatif” dari kondisi dan situasi kapitalisme yang berlangsung.
Memang seni, khususnya film, tidak menjamin apa pun bagi perubahan sosial, sebagaimana menurut pandangan Mahzab Frankfurt bahwa seni adalah otonomi relatif terhadap situasi sosial-ekonomi-politik. Selain dalam pandangan Marxian sendiri, seni hanya memiliki peran sebagai pendorong proses sejarah. Dalam hal ini, film memiliki konteks sebagai cara pandang dalam melihat realitas. Cara pandang film tentu berbeda dengan cara pandang pengetahuan karena sifat mediumnya dan orang (subjek) di balik semangat artistik bahasa film. Satu-satunya kebenaran yang tersisa dalam film sesungguhnya bukan kebenaran “objektif” dalam tradisi ilmiah, namun kebenaran “filmis” itu sendiri. Setidaknya, seperti apa yang dinyatakan oleh Aristoteles, hal yang tak termaafkan bagi seorang seniman adalah kesalahan yang murni estetis dalam mewujudkan sebuah karya,[5] bukan soal penggambaran tentang realitas yang diungkapkan. Artinya, di sini persoalan-persoalan filmis adalah persoalan yang murni tentang bentuk (form), bukan persoalan isi.
Dalam kerangka artistik, film memiliki potensi transformatifnya pada penggunaan-penggunaan bahasa filmis yang diwujudkannya. Dalam hal ini, mungkin yang bisa direnungkan adalah bagaimana sebuah film mampu membuka selubung realitas yang berlangsung dalam keseharian kaum buruh, khususnya terkait dengan bahasa gambar karena terkait bagaimana sebuah peristiwa atau kenyataan filmis dikonstruksi. Namun semua ideal bahasa sinema tentu sulit diwujudkan karena konteks kebudayaan global yang menyeragamkan bahasa sinema. Adalah hal yang sulit untuk mengolah selubung magis dari bahasa sinema yang berlaku. Dominasi bahasa sinema dalam kebudayaan global telah berlangsung lama dan telah menyatu dengan bahasa tontonan yang menghibur. Tentu menjadi tantangan sendiri bagaimana sinema sebagai bahasa yang memiliki potensi transformatif dan revolusioner sanggup menghadapi bahasa dominan sinema yang ada selama ini.
Bagi dramawan Bertold Brecht, seni pada dasarnya harus menghibur, meski ia bersifat kritis terhadap kenyataan sehari-hari. Tantangan sinema hari ini adalah bukan sekadar mencapai kisah yang menarik semata, melainkan juga mewujudkan kisah yang mampu menggugah kesadaran kritis masyarakat. Semoga film Bumi Bergolak pada acara pemutaran menjelang hari buruh sedunia ini bisa memberikan cara pandang baru, khususnya mengenai sinema sebagai bagian dari kebudayaan kaum buruh yang transformatif.
*Tulisan ini pernah disampaikan dalam diskusi pemutaran film Bumi Bergolak, Kamis 30 April 2015, di Kine Forum.
** Akbar Yumni bergiat di Forum Lenteng, Jakarta. Ia juga editor pada www.jurnalfootage.net. Ia pernah menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang dan saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Ia juga adalah salah satu kurator dalam Arkipel International Documentary and Experimental Film Festival.
***Illustrasi diambil dari http://www.benitomovieposter.com/catalog/terra-trema-la-p-17987.html?language=en
[1] Henri Avron, Estetika Marxis (Yogyakarta: Resist Book, 2010), hlm. 78.
[2] Bab ini dikembangkan dari tulisan “Verismo! Luchino Visconti dalam Bumi Bergolak/La Terra Trema (1948) http://jurnalfootage.net/v4/artikel/verismo-luchino-visconti-dalam-bumi-bergolak-la-terra-trema-1948, diunduh pada 26 April 2015, pukul 19.28.
[3] Dikutip dari Georges Sadoul dalam Dictionary of Film Makers (Diterjemahkan dan disunting oleh Peter Morris) (Los Angeles: University California Press, 1972), hlm. 267.
[4] Cesare Zavattini, Some Idea on Cinema, hlm. 52
[5] Lihat bab Aristoteles dalam Michael Hauskeller, Seni-Apa itu? (Posisi Estetika dari Platon sampai Danto) (Kanisius: Yogyakarta, 2015).