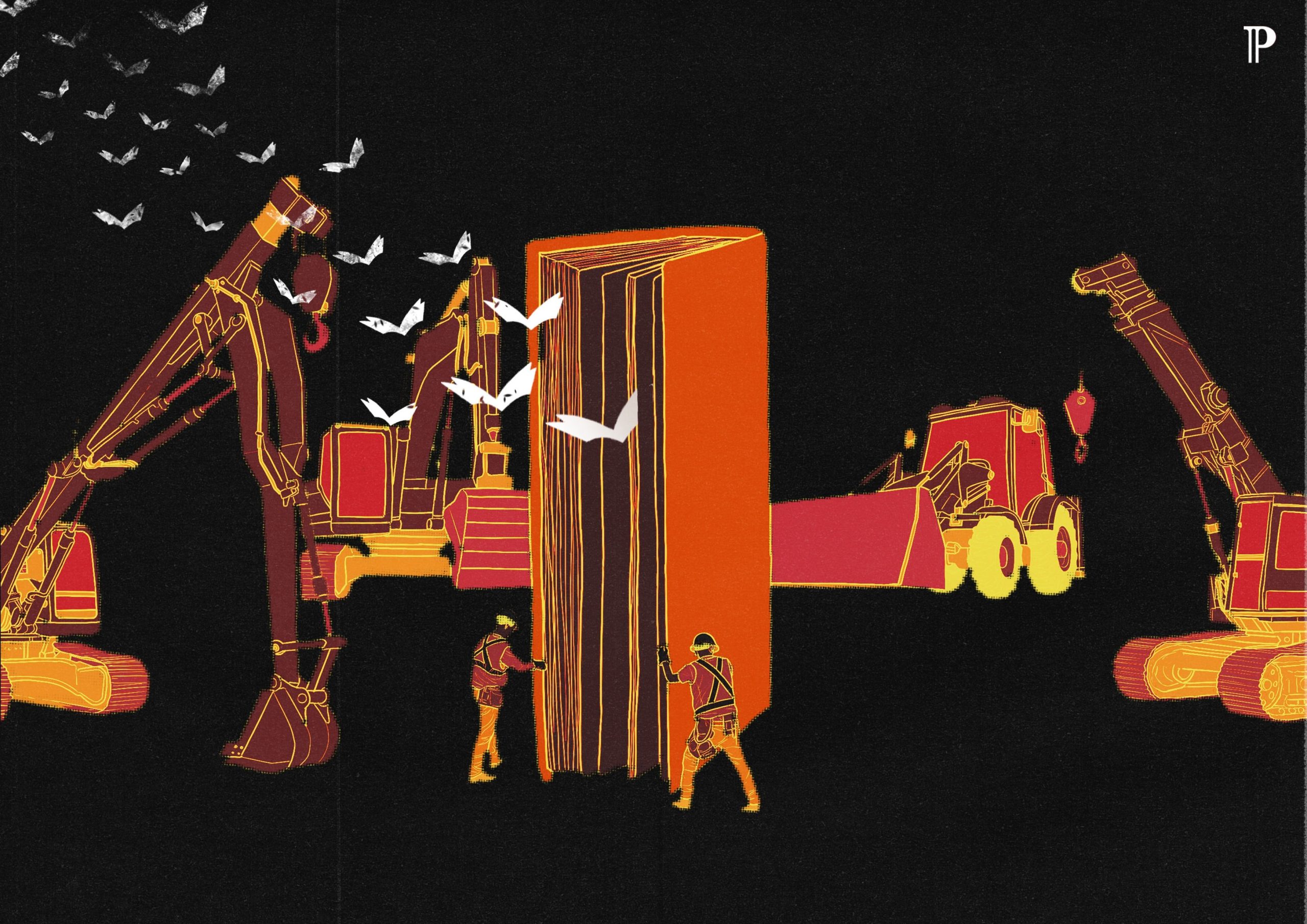Ilustrasi: Ilustruth
TULISAN ini berupaya menjelaskan bagaimana aktor-aktor dari struktur tradisional membuat tafsir tunggal atas “adat” dan mendapatkan posisi dalam pemerintahan neoliberal—khususnya terkait penyediaan lahan untuk investasi produksi. Beriringan dengan “kebangkitan adat” yang dipakai dalam beragam bentuk oleh beragam aktor dari struktur tradisional, tulisan ini hendak melihat hubungan saling klaim antara “hutan negara/tanah negara” dan “hutan adat/tanah adat” dengan politik pembiaran kematian (letting die) terhadap kelas-kelas sosial tak bertanah di pedesaan.
Di lain sisi, tulisan ini menunjukkan bahwa “masyarakat adat” bukanlah kelompok yang “rentan” dan “tak berdaya” terhadap perampasan ruang hidup atas nama pembangunan sebagaimana yang umumnya dipahami—dan karenanya upaya-upaya untuk mengukuhkan “wilayah adat” menjadi jawaban kunci. Sebaliknya, argumen dan upaya tersebut justru menciptakan beragam masalah yang terkait dengan spekulan dan meluasnya perampasan tanah skala raksasa.
Tiga Momen Kunci Pembentukan Biopolitik “Masyarakat Adat”
Di Indonesia, diskusi mengenai “masyarakat adat” setidaknya muncul dalam tiga momen. Pertama ketika pengukuhan “kawasan hutan” terjadi lewat Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tahun 1967. Kedua UU tersebut memberi legitimasi kepada pemerintah lewat Kementerian Kehutanan untuk mendefinisikan hutan, menegaskan batas-batas tanah kehutanan, dan membuat kategori-kategori penggunaannya (lihat Peluso 1995; Bachriadi dan Lucas 2002; Tsing 2002; Warren 2005; Li 2014; Bachriadi 2020). Perkiraan dari Tania Murray Li: sekitar 70% wilayah nasional ditetapkan sebagai “hutan negara” (Li 2014:141). Sementara menurut Bachriadi dan Lucas (2002): sekitar 70% luas “kawasan hutan” terhadap total luas daratan Indonesia terus dipertahankan hingga tahun 90-an
Kedua, di tengah luasnya keberadaan “kawasan hutan” dan beroperasinya industri ekstraktif kehutanan sejak tahun 1970-an. Di momen ini tingkat deforestasi, kerusakan ekologi, dan konflik tenurial (konflik yang timbul dari pertentangan klaim atas penguasaan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam) sudah membesar dari tahun ke tahun (untuk mendapat gambaran umum mengenai tingkat deforestasi, kerusakan ekologi, dan konflik tenurial yang berlangsung di dalam “kawasan hutan”, lihat Dianto Bachriadi, 24.2 Manifesto Penataan Ulang Tanah ‘Kawasan Hutan’, 2020). Alih-alih menciptakan kesejahteraan sosial, pemerintah justru memaksimalkan penggunaan “kawasan hutan” untuk industri kayu, perkebunan skala raksasa, pertambangan, dan transmigrasi.
Oleh pemerintah, hutan sekadar dipahami sebagai pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan (lihat Pasal 1 UU 5/1967) yang tidak terkait dengan relasi sosial-produksi di dalamnya. Pengukuhan “kawasan hutan” membuat Kementerian Kehutanan mempunyai kehendak untuk mengontrol, mengatur, dan membuat proyek-proyek di dalam hutan. Akibatnya, banyak komunitas yang berada dan mengelola serta memanfaatkan hutan selama berabad-abad—seperti yang digambarkan Li (2014) di perbukitan Lauje atau yang digambarkan Duncan (2002) di hutan Halmahera—harus disingkirkan. Bahkan komunitas itu sendiri didiskriminasi sedemikian rupa. Sejak 1969 dan sepanjang tahun-tahun kemudian, misalnya, Orde Baru (Orba) mengampanyekan istilah “primitif” bagi orang/kelompok orang yang berada di dalam “kawasan hutan”. Lalu Departemen Sosial (Depsos) juga membuat program “pembinaan masyarakat terasing”. Ini menandakan suatu babak baru hegemoni kapitalisme kehutanan: setelah hantu komunis, terbitlah “masyarakat terasing” yang harus “dibina” dan “diberdayakan”.
Ketiga, ketika semakin luas pengukuhan “hutan negara”, semakin banyak pula izin penggunaan “kawasan hutan” melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan semakin jelas tumpang tindih atau saling klaim antara negara (“hutan negara”) dan “masyarakat adat” (“hutan adat”) di dalam suatu kawasan yang disebut sebagai tanah kehutanan. Saling klaim tersebut telah memengaruhi berbagai studi mengenai adat dan masyarakat adat (lihat Beckmann 1992; Chanock 1985; Davidson dan Henley 2012; Li 2001;), juga kemunculan gerakan yang mengambil tema-tema adat (Lihat AMAN 2022; BBCNews 2025; Tempo 2025). Di momen ini pun muncul berbagai macam aktor lokal yang menafsirkan “adat” versi sendiri untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka.
Pertanyaan kunci yang akan didiskusikan selanjutnya adalah bagaimana saling klaim itu berlangsung pasca-Orde Baru, ketika kapitalisme neoliberal memungkinkan aktor-aktor tersebut terus bekerja, berubah, dan bergerak masuk ke dalam prinsip-prinsip pro-pasar; dan bagaimana saling klaim “tanah/hutan adat” dengan “tanah/hutan negara” telah membentuk kekuasaan baru (biopower) untuk mengembangkan, mengoptimalkan, mengatur, dan mengamankan kehidupan. Istilah biopower digunakan oleh Michel Foucault untuk menunjukkan suatu kekuasaan baru dari proses biopolitik, yang dipahami sebagai transformasi dan perkembangan historis di mana hak untuk merebut, menindas, dan menghancurkan kehidupan telah membentuk seperangkat mekanisme baru di tubuh kekuasaan (lihat Foucault, 1978-79. ed. Michel Senellart).
Pemindahan Paksa dan Biopower “Masyarakat Adat”
Perkembangan kapitalisme pada umumnya dan khususnya di Indonesia dimulai dengan proyek menggusur para produsen dari tanahnya, yaitu ketika Orba mulai berkuasa. Bahkan riset-riset menunjukkan kaitan antara pembantaian 1965-66 dengan atau sebagai titik berangkat pembangunan kapitalis (lihat Farid 2006; Hammer 2015; Hadiz 2015). Terlepas dari perdebatan yang mengelilinginya, faktanya beragam mekanisme berlangsung dalam bentuk pemindahan paksa melalui program transmigrasi. Alasan di balik pemindahan paksa beragam, namun idenya dapat ditelusuri pada pemikiran seorang ahli agraria internasional, Wolf Ladejinsky. Menurutnya, pelaksanaan land reform di Indonesia tidak berdampak apa-apa sehingga yang diperlukan adalah redistribusi penduduk (Bachriadi & Wiradi 2011:8-9). Gagasan Ladejinsky kemudian berkembang hingga hari ini, berkelindan dengan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat “suku” dalam kelanjutan program transmigrasi.
Pemindahan paksa merupakan manifestasi dari biopower (lihat Laurence 2016). Lihat saja apa yang terjadi di Halmahera, Maluku Utara. Pemindahan paksa dalam bentuk pemukiman kembali (resettlement) di sana telah memapankan definisi dan karakter kelompok masyarakat “suku” Tobelo. Pelabelan tersebut adalah mekanisme untuk menegaskan batas-batas penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah “kawasan hutan”. Alasan di balik proteksi negara terhadap masyarakat “suku” Tobelo yang berada di hutan Dodaga dan hutan Tutuling (lihat Martodirdjo 1994:121) ke dalam proyek-proyek perumahan sosial di Lolobata, Para-Para, Dodaga, lalu kembali lagi ke Lolobata tidak lain adalah “menjaga” lingkungan dan keanekaragaman hayati dari proses pertanian berputar (negara menganggapnya merusak) yang dilakukan oleh mereka (lihat Duncan 2002:349). Ini merupakan momen penting di mana para spekulan tanah muncul dengan proyek-proyek konservasi.
Sebuah dokumen dari Participatory Research in Asia (PRIA) tahun 1993 menyatakan setidaknya 600 ribu orang telah dipindahkan dengan alasan menjaga kawasan hutan lindung. Berbagai studi juga mengungkapkan hal serupa di tempat lain. Dengan dalih pelestarian keanekaragaman hayati—baik sebagai kawasan lindung, cagar biosfer, pusat keanekaragaman tanaman, kawasaan burung endemik, dan kawasan ekologi global (untuk detailnya lihat Hall, Hirsch, & Li, 2020: 112-117)—lahan-lahan telah digunakan oleh berbagai proyek dan telah mengusir jutaan orang di pedesaan.
Kebijakan memindahkan orang/kelompok orang yang dianggap merusak ekosistem hutan di Maluku Utara semakin tegas ketika hutan produksi yang dapat dikonversi dimasukkan ke dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perubahan penetapan luas area “kawasan hutan” KPH pada 2021: dari yang sebelumnya 1,76 juta hektare menjadi 2,27 juta hektare atau 91% dari total luas “kawasan hutan” Provinsi Maluku Utara (lihat KLHK 2023; DJ-PTKL 2023). Setelah satu dekade sejak tahun 2010, “kawasan hutan” dengan status fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) dimasukkan ke dalam area pengelolaan hutan KPH. Dengan demikian, perubahan penetapan luas area KPH pada tahun 2021 (lihat SK 900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021) dapat berlangsung dan memperkuat alasan pengelolaan “hutan lestari”. Pengelolaan “hutan lestari” “…digerakkan oleh wacana upaya-upaya meraih ‘kebaikan bersama’ yang dipromosikan oleh proyek dan wacana konservasi…” (Hall, Hirsch, & Li 2020:99). Kenyataannya, luas status fungsi hutan produksi hanya seluas 1,71 juta hektare. Jadi, fenomena semacam ini, meminjam istilah Bachriadi (2020), adalah pseudo forest atau kawasan hutan yang bukan berbentuk hutan tetapi dikukuhkan sebagai kawasan hutan (Bachriadi 2020:14-15).
Spekulasi tanah kehutanan yang digalakkan oleh pemerintah menemukan hambatan ketika muncul organisasi non-pemerintah (ornop, LSM) yang mempertanyakan keberadaan “hutan adat”. Ornop lingkungan mengidentifikasi pengelolaan hutan berbasis adat dengan pengelolaan hutan berbasis negara (lihat Peluso, Afif, & Rahman 2008). Muncul pula beragam protes yang digerakkan ornop melalui bingkai gerakan “selamatkan hutan”. Namun, dalam perkembangannya, protes-protes lokal melemah bahkan berdamai dan hidup berdampingan dengan proyek-proyek negara. Sebuah studi di Halmahera Utara menemukan bahwa ternyata gerakan adat berkontribusi membuka peluang investasi pengelolaan sumber daya alam bagi siapa saja (Safitri 2019:237). Bahkan fenomena akhir-akhir ini menunjukkan protes-protes itu berkembang sekaligus mempertegas biopower “masyarakat adat” dalam perebutan kawasan industri, di mana mereka dapat memobilisasi sumber dana perusahaan alias CSR.
Kasus di Ternate dapat menjadi contoh. Pada tahun 2009, Sultan Ternate Mudaffar Syah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara untuk mengubah nama Maluku Utara menjadi Maluku Kie Raha. Usulan itu dikatakan untuk membuat negara mengakui tanah ulayat. Meskipun sebelumnya Sultan Mudaffar telah mempertahankan kekuatan ekonominya atas akses tanah karena lolos dari batasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melalui mekanisme transfer pengelolaan tanah ke otoritas adat (Kurniadi 2019:231-234), spekulasi tanah berbasis konservasi dan “wilayah adat” turut memengaruhi tindakan-tindakannya untuk mengubah wilayah provinsi (khususnya akses kontrol terhadap tanah) di bawah otoritas Kesultanan Ternate. Upaya mengubah nama tersebut menguat lagi pada 2022, ketika sejumlah akademisi Maluku Utara melakukan konferensi pers di Ternate. Sampai tulisan ini dibuat, upaya-upaya tersebut masih berlangsung: suatu usaha yang diminati oleh kapitalisme neoliberal, di mana formalisasi dan sertifikasi tanah menjadi agenda utama untuk mempercepat akumulasi kapital.
Agenda Neoliberal: Berebut Tanah dan Politik Pembiaran Kematian
Para spekulan tanah muncul dalam beragam bentuk. Pada intinya, pihak-pihak tersebut beroperasi dalam sistem komodifikasi tanah skala raksasa (lihat Marx 1976; Zoomers 2010; Magdoff 2013). Dengan kata lain, mereka terhubung secara politik dan ekonomi dalam pasar tanah.
Di Maluku Utara, setidaknya ada dua pihak yang beroperasi. Pihak pertama adalah pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka secara luas memanipulasi wilayah kelola KPH Maluku Utara di tahun 2021 dengan dalih mengelola hutan yang inklusif dan ramah lingkungan. Pada faktanya, “kawasan hutan” dengan status fungsi hutan produksi dipakai untuk memaksimalkan penggunaan lahan ke dalam proyek hilirisasi nikel. Hal ini berkelindan dengan tren pelepasan “kawasan hutan” untuk transmigrasi, perkebunan, dan pertanian (sekitar 82 ribu hektare), dan bertambahnya jumlah IPPKH untuk eksplorasi tambang (lebih dari 352 ribu hektare). Sampai 2023, IPPKH untuk operasi tambang hanya 34 ribu hektare (atau sekitar 9,7%) dari total IPPKH yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan tambang di Maluku Utara. Sisanya atau sekitar 318 ribu hektare (atau sekitar 90,3%) belum digunakan untuk kegiatan produksi (lihat KLHK 2023; DJ-PTKL 2023).
Tidak mengherankan jika kemudian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menemukan tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan “kawasan hutan” berstatus hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung (lihat Aman, 3 Maret 2016). Bahkan kasus baru-baru ini, PT Sembaki Tambang Sentosa (STS) dan PT Posision, yang melibatkan lima desa juga beroperasi melalui skema IPPKH (lihat Tempowitnes, 4 Mei 2025; Jatam, 16 Mei 2025; Mongabay, 20 Mei 2025). Itu sebabnya Jatam (2024) menemukan “semangat hilirisasi nikel di Malut ditandai dengan hadirnya 8 smelter yang beroperasi secara masif sejak 2021” (Jatam 2024:7).
Pihak kedua adalah AMAN (lihat Safitri 2019), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) (lihat Peluso, Afif, & Rahman 2008), dan Kesultanan Ternate (lihat Kurniadi 2019). Kadang-kadang mereka saling mendukung, di titik tertentu saling berlawanan. Sejak awal kemunculannya di Maluku Utara, AMAN dan Walhi saling mendukung dalam hal pematokan dan pengukuhan batas-batas wilayah adat (lihat Aman, 30 November 2012; 13 Juni 2013; 18 Oktober 2018). Sementara Kesultanan Ternate sudah beroperasi sejak tahun 1975 dan diformalisasi pada 2009, ditandai dengan munculnya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate. Perda tersebut membagi tujuh kategori tanah adat, dan secara longgar melegitimasi penerbitan cocatu (sertifikat tradisional) oleh Kesultanan Ternate.
Seturut dengan agenda neoliberal di bidang pertanahan, perubahan penetapan dan pengukuhan luas wilayah KPHP, pematokan dan pengukuhan wilayah adat, dan formalisasi tanah-tanah adat melalui legitimasi penerbitan sertifikat tradisional telah mengubah tanah—baik hutan maupun non-kehutanan—menjadi kapital tetap (fixed capital). Dengan mengubah menjadi kapital tetap, tanah akan terserap ke dalam sirkuit kapital dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan kembali nilai gunanya (lihat Harvey 2006). Beriringan dengan itu, kelas-kelas sosial tak bertanah di pedesaan harus bertahan hidup, kekurangan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Di tengah masifnya para pihak saling berebut tanah dan proyek-proyek kapital yang menggusur produsen dari tanahnya, fenomena yang digambarkan Li (2009) sebagai politik “to make live and let die” tersituasikan di Maluku Utara. Ini merupakan kekerasan terselubung yang menyerahkan sejumlah besar orang untuk menjalani hidup yang pendek dan terbatas.
Penutup
Praktik “masyarakat adat” telah membuka peluang bagi masifnya spekulasi dan perampasan tanah skala raksasa di pedesaan. Masyarakat adat tidak lagi dipahami dalam konteks kemunculannya sendiri, di mana tumpang-tindih rezim lahan kehutanan telah menghasilkan pemindahan paksa dan mengubah akses mereka terhadap hutan. Mereka dipahami sebagai suatu kelompok yang alami. Akibatnya, berbagai macam identifikasi mengenai keberadaan mereka dipandang memiliki ciri khas tertentu yang harus dilestarikan. Alasan-alasan seperti itulah yang memberi legitimasi masuknya berbagai macam “proyek”. Kemudian beragam aktor—baik negara, LSM, maupun kelompok “bangsawan”—muncul membawa mereka ke dalam ruang perdebatan politik di perkotaan. Tentu, termasuk juga tulisan ini.
Meskipun begitu, tulisan ini tidak memahami “masyarakat adat” sebagai kelompok yang merujuk pada kelas sosial di pedesaan, melainkan lebih kepada bagaimana kuasa pengetahuan bekerja mengidentifikasi mereka dan diadopsi oleh berbagai kelompok dengan kepentingan yang beragam. Salah satu yang dapat disimpulkan adalah menguatnya spekulasi tanah dan hutan. Sementara kelas sosial pedesaan yang tidak memiliki akses atas tanah secara nyata diabaikan dan tidak populer di perkotaan.
Referensi
Bachriadi, D. & Lucas, Anton. (2001). Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Bachriadi, D. & Wiradi, Gunawan. (2011). Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria.
Bachriadi, D. (2020). 24.2 Manifesto Penataan Ulang Penguasaan Tanah ‘Kawasan Hutan’. Bandung: ARCBooks.
________. (2024). Mafia Tanah di Indonesia: Jalinan Kejahatan Terorganisir, Bisnis, Kekuasaan, Korupsi, dan Maladministrasi, Working Paper ARC No. 4/WP-KTAGS/2024. Bandung: Agrarian Resource Center.
Chanock, Martin. (1985). Law, Custom, and Social Order. Cambridge: Cambridge University Press.
Davidson, Jamie S. & David, Henley. (eds) (2012). The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London: Routledge.
Duncan, Christopher R. (2002). Savage Imagery: (Mis)representations of the Forest Tobelo of Indonesia. Dalam The Asia Pacific Journal of Anthropology, 2(1): 45-46.
________. (2001). Resettlement and Natural Resources in Halmahera, Indonesia. Dalam Conservation and Mobile Indigenous Peoples, ed. Dawn Chatty & Marcus Colchester. New York: Berghahn Books.
Farid, Hilmar. (2006). Indonesia’s Original sin: mass killings and capitalist expansion, 1965-66. Inter-Asia Cultural Studies, 6:1, 3-16.
Hadiz, V. R. (2015). Capitalism, Primitive Accumulation and the 1960s Massacres: Revisiting the New Order and its Violent Genesis. Inter-Asia Cultural Studies, 16(2), 306-315.
Hall, Hirsch, & Li. (2020). Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Yogyakarta: Insist Press.
Hammer, Mathias. (2015). The Indonesian Killings and economic redistribution: a reply to Hilmar Farid. Inter-Asia Cultural Studies, 16:2, 316-326.
Jatam. (2024). Penaklukkan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi.
Kurniadi, Bayu Dardias. (2019). Defending the Sultan’s Land: Yogyakarta, Control over Land and Aristocratic Power in Post-Autocratic Indonesia. Australia: The Australian National University.
Laurence, Mechael R. (2016). Biopolitics and State Regulation of Human Life.
Li, Tania Murray. (2001). Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia’s Forest Zone. Dalam Modern Asian Studies, Vol. 35, 2001, hal. 645-676.
________. (2009). To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations. Antipode, 41(1), 66-93.
________. (2014). Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Magdoff, F. (2013). Twenty-First-Century Land Grabs Accumulation by Agricultural Dispossession. New York: Article in Monthly Review.
Martodirdjo, Haryo. (1994). Organisasi Sosial Orang Tugutil di Halmahera. Dalam Halmahera and Beyond: Social Science Research in the Moluccas, ed. Leontine E. Visser. Leiden: KITLV Press.
Marx, Karl. (1976). Capital Volume I. Penguin Books.
Peluso, Afif, & Rachman. (2008). Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia. Journal of Agrarian Change, Vol. 8, 377-407.
Peluso, Nancy Lee. (1995). Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia. Antipode 27, no. 4: 383-406.
Safitri, Hilma. (2019). Gerakan Masyarakat Adat Dalam Perubahan Agraria di Halmahera Utara. Dalam Ke Timur Haluan Menuju: Studi Pendahuluan Tentang Integrasi Sosial, Jalur Perdagangan, Adat, dan Pemuda di Kepulauan Maluku. Ed. Hikmat Budiman. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Tsing, Anna Lowenhaupt. (2002). Land as Law: Negotiating the Meaning of Property in Indonesia. Dalam Land, Property, and the Environment, ed. F. Richards, 94-137. Berkeley: University of California Press.
Warren, Carol. (2005). Mapping Common Futures: Customary Communities, NGOs and the State in Indonesia’s Reform Era. Development and Change 36, no. 1: 49-73.
Zoomers, A. (2010). Globalisation And the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving The Current Global Land Grab. London: Routledge.
Hasan M. Thaib, biasa dipanggil Ceos, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dan aktif di forum Sekolah Bersama (Sekber) Yogyakarta. Menjadi bagian dari program magang Agrarian Resources Center (ARC) sejak Januari 2021.