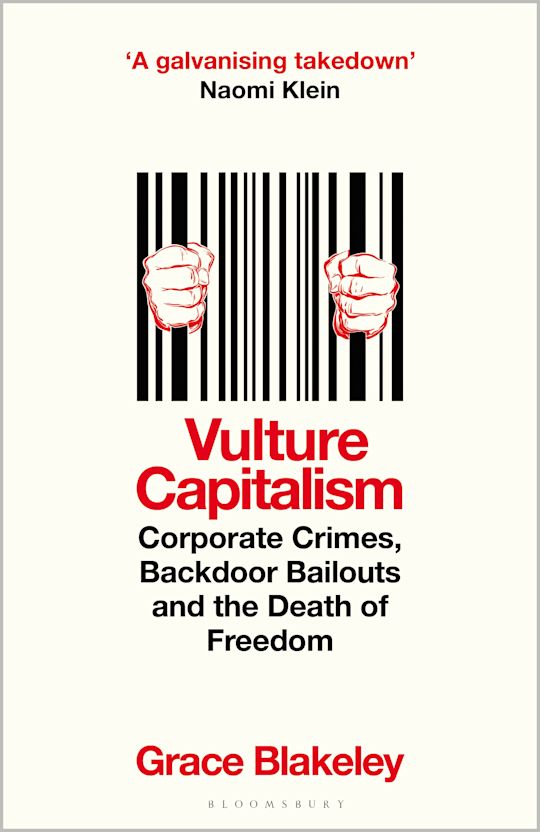Ilustrasi: Wikimedia Commons
Judul Buku: Vulture Capitalism: Corporate Crimes, Backdoor Bailouts and the Death of Freedom
Penulis: Grace Blakeley
Penerbit: Bloomsbury
Tahun Terbit: 2024
PERNAHKAH Anda merasa bahwa sistem ekonomi saat ini lebih mirip dengan permainan monopoli yang dimenangkan oleh segelintir orang, sementara yang lain hanya bisa gigit jari? Buku Vulture Capitalism karya Grace Blakeley hadir pada momen kritis ketika neoliberalisme, yang sebelumnya dipuja sebagai jaminan pertumbuhan, justru memicu krisis ketimpangan dan krisis finansial berulang.
Buku yang diterbitkan Grace Blakeley tahun 2024 ini memberikan penekanan utama bahwa logika kapitalisme secara inheren memicu konsentrasi kekuatan ekonomi. Konsentrasi ini kemudian digunakan untuk memusatkan kekuatan politik, menghasilkan regulasi dan kebijakan yang secara sistematis menguntungkan korporasi multinasional raksasa—yang bisa disebut “Goliath”—serta lembaga finansial besar—“Titan”—yang semakin menguatkan posisi tawar mereka.
Blakeley menegaskan bahwa pasca-krisis 2008, pola ini semakin mengakar di negara-negara Barat dan kini mulai merambah negara-negara berkembang. Bagi pembaca Indonesia, pemahaman ini penting untuk melihat potensi jebakan investasi asing dan praktik ekstraksi yang serupa dengan kerangka “kapitalisme bangkai” (dead capitalism).
Dalam menuliskan bukunya ini, Blakeley memanfaatkan kombinasi data kuantitatif—statistik utang, angka akuisisi perusahaan, angka ketimpangan—dengan narasi kasus: cerita pekerja yang dipecat setelah perusahaan diakuisisi, pemerintah yang harus menanggung utang perusahaan swasta, hingga contoh spesifik dari vulture capitalism beroperasi.
Mitos Freedom dalam Kapitalisme
Grace Blakeley membuka Vulture Capitalism dengan menantang keyakinan populer bahwa kapitalisme identik dengan kebebasan pasar. Menurut Blakeley, gagasan “pasar bebas” hanyalah kabut retoris yang menutupi realitas brutal: pasar modern diorganisir, diatur, dan sering kali dikendalikan oleh korporasi raksasa yang ia sebut “Goliath”, serta lembaga finansial superbesarnya, “Titan”.
Blakeley memanfaatkan beragam literatur ekonomi kontemporer yang mencatat fenomena “kematian persaingan”, kemunculan “era baru Gilded Age”, dan “kapitalisme monopoli baru”. Bagi Blakeley, ini semua adalah perang antara kekuatan oligopoli yang sebagian besar telah menguasai pasar, melawan cita-cita demokrasi; situasi di mana “persaingan oligopoli sedang membunuh kita.”
Saat sebagian besar penelitian selama ini meyakini nilai kapitalisme, tetapi khawatir akan merosotnya tingkat persaingan dan lemahnya penegakan regulasi dan kesepakatan dalam beberapa dekade terakhir, Blakeley justru mengambil sudut pandang bahwa kekuatan monopoli dan konsentrasi ekonomi bukan sekadar kegagalan regulasi, melainkan fitur ontologis dari kapitalisme itu sendiri.
Menurutnya, menganggap pasar “bebas” adalah ciri khas eksklusif kapitalisme merupakan kesalahan konseptual. Di sini, Blakeley membongkar lima wawasan krusial. Pertama, pertukaran pasar (market exchange) bukanlah fenomena baru yang hanya muncul bersama kapitalisme; sepanjang sejarah, hampir setiap masyarakat manusia sudah mengenal mekanisme jual-beli dan barter. Jadi, memosisikan pasar sebagai singularitas kapitalis adalah kesalahan konseptual. Hal ini sebagaimana Blakeley menegaskan penjelasan David Graeber bahwa semua masyarakat manusia sebenarnya telah lama mengenal pasar dan mekanisme pertukaran.
Kedua, apa yang benar-benar menjadi pembeda kapitalisme adalah hubungan spesifik antara pekerja dan majikan. Di situlah Blakeley menegaskan pandangan Leo Panitch dan Sam Gindin bahwa inti kapitalisme terletak pada struktur ketenagakerjaan: pekerja menjual tenaga kerjanya sebagai komoditas, sementara majikan memiliki kontrol penuh atas proses produksi dan surplus nilai. Inilah yang membuat kapitalisme berbeda dari sistem ekonomi lain, meski sama-sama mengenal pertukaran pasar.
Ketiga, hubungan antara pekerja dan majikan ini jauh dari nilai-nilai demokrasi. Blakeley bahkan menyamakannya dengan bentuk totalitarianisme ekonomi. Saat buruh dan karyawannya ditekan untuk bekerja di bawah kondisi yang ditentukan sepihak oleh majikan—dengan ancaman PHK atau pengurangan upah—tidak ada ruang tawar yang setara. Inilah yang membuat kapitalisme memupus ilusi bahwa setiap orang benar-benar “bebas memilih” profesi atau kondisi kerja; kenyataannya, posisi tawar pekerja sangat timpang dan, dalam skala besar, nyaris tak ada sama sekali.
Keempat, sepanjang perluasan pasar kapitalis, peran negara justru semakin besar. Bukan sebaliknya—neoliberal “pasar bebas” tidak pernah membatasi negara, melainkan memperluas jangkauan kekuasaannya. Seiring korporasi dan modal raksasa merambah berbagai sektor ekonomi, negara turun tangan: mensubsidi industri strategis, serta merancang regulasi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan besar.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Blakeley merujuk pada “iron law of liberalism” David Graeber. alih-alih merampingkan birokrasi, setiap perluasan aktivitas pasar justru menambah regulasi, menumpuk pekerjaan administrasi, dan melipatgandakan jumlah birokrat pemerintah. Gagasan ini mengukuhkan bahwa perpanjangan kekuasaan pasar tidak membebaskan individu, melainkan menciptakan belenggu baru berupa birokrasi dan dominasi korporasi.
Iron law ini dijelaskan Blakeley dengan mekanisme utama: bagaimana bank-bank besar dan dana investasi memanfaatkan utang untuk mengendalikan perusahaan dan negara, sering kali dengan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat luas. Krisis utang di negara-negara Amerika Latin dan Afrika menjadi contoh nyata dari fenomena ini.
Kelima, dalam kapitalisme modern, pasar sejatinya diatur dan direncanakan. Konsep “freedom” hanyalah eufemisme retoris yang menutupi praktik otoriter korporasi raksasa. Dalam konteks “mitos freedom”, Blakeley mengkritik retorika laissez-faire yang membayangkan pasar sebagai wilayah tanpa batas di mana individu bertindak rasional demi kebaikan bersama. Fakta di lapangan: “Goliath” korporasi menggunakan kekuatan politik terpusat untuk merancang regulasi yang memperkokoh monopoli mereka, mulai dari pengecualian pajak, lisensi eksklusif, hingga perjanjian arbitrase internasional (ISDS) yang membuat pemerintah gentar memberlakukan regulasi lingkungan atau menaikkan upah minimum.
Dengan demikian, kebebasan sebenarnya hanya milik segelintir elite ekonomi dan politik, sementara mayoritas terbelenggu utang, tarif layanan publik yang semakin mahal, dan pilihan ekonomi yang semakin sempit.
Sistem yang Terencana
Setelah menyingkap ilusi “pasar bebas”, Blakeley menguraikan bagaimana negara dan aktor finansial merancang pasar melalui serangkaian kebijakan dan instrumen perencanaan yang tampak demokratis, tetapi nyatanya memuluskan agenda oligopoli.
Dalam bagian ini, Blakeley memaparkan proses perencanaan ini melalui lensa “bagaimana bisnis besar merencanakan”, “bagaimana bank besar merencanakan”, “bagaimana negara merencanakan”, dan “bagaimana imperium merencanakan”. Untuk memperkaya analisisnya, ia merujuk pada beberapa pemikir ekonomi terkemuka dari dekade 1960-an. Di antaranya adalah John Kenneth Galbraith, seorang keynesian; dan Paul Sweezy serta Paul Baran, dua marxis yang mengkaji bagaimana monopoli telah mengubah kapitalisme menjadi sistem yang lebih terkonsentrasi dan eksploitatif.
Dengan menghubungkan ide-ide ini, Blakeley tidak hanya memberikan konteks historis yang kuat tetapi juga menggarisbawahi bahwa perencanaan dalam kapitalisme modern jauh dari sekadar mekanisme pasar yang spontan—melainkan sebuah proses yang disengaja, sering kali terselubung, untuk kepentingan segelintir elite.
John K. Galbraith memandang bahwa kapitalisme modern sebenarnya berfungsi sebagai sistem ganda: usaha kecil dan menengah masih beroperasi dalam “sistem pasar” di mana persaingan harga relatif berlaku, sedangkan korporasi besar hidup dalam “sistem perencanaan” di mana mereka menegakkan kehendaknya atas pasar lewat persuasi, manipulasi, dan kekuasaan. Blakeley memperdalam analisis ini dengan menyebutkan entitas “Behemoth” berkepala tiga— kesehatan keuangan, industri raksasa, dan aparat negara—yang merencanakan kebijakan ekonomi untuk menguntungkan satu persen terkaya, sekaligus menindas mayoritas. Perencanaan yang digerakkan oleh Behemoth ini terbukti menjadi mesin penggerak kekuatan ekonomi oligopoli dan kekuasaan politik oligarkis. Alih-alih mendorong efisiensi dan inovasi, rencana-rencana strategis tersebut justru menurunkan produktivitas, menghambat investasi swasta, dan menghancurkan usaha kecil yang menjadi tulang punggung “sistem pasar”.
Semakin diperkuatnya cengkeraman korporasi besar atas rantai pasok, semakin sedikit ruang bagi usaha kecil menengah untuk berkembang; padahal di banyak negara, usaha kecil dan menengah masih menyerap daya pekerja terbesar. Dampak langsungnya adalah berkurangnya penerimaan pajak publik karena sejumlah transaksi dialihkan lewat mekanisme offshore atau skema utang, sehingga belanja sosial terpangkas dan layanan publik makin terbatas.
Dengan infrastruktur fiskal yang rapuh, negara terpaksa meminjam lebih besar untuk membiayai program subsidi dan proyek infrastruktur; tetapi, sebagian besar pinjaman itu—melalui jalur bailout—justru mengalir kembali ke kantong investor besar. Blakeley mengilustrasikan bahwa ketika bank besar “too big to fail” diselamatkan, mereka kembali menjual aset bermasalahnya kepada hedge funds dengan potongan kecil, sementara kerugian ditanggung rakyat lewat pajak. Urutan rangkaian ini menegaskan bahwa planning yang dilakukan Behemoth tidak hanya memperkaya elite terkaya, tetapi memelihara struktur oligopoli yang menyuburkan ketidaksetaraan.
Lebih jauh, mekanisme perencanaan yang terpusat memunculkan regulasi yang sejak awal dirancang untuk menahan inovasi atau memanipulasi standar persaingan. Paul Sweezy serta Paul Baran menjelaskan ini sebagai “sales effort”. Perusahaan-perusahaan modern secara diam-diam berkolusi untuk menjaga stabilitas harga, melobi negara untuk mengurangi beban pajak mereka, menekan negara untuk melindungi mereka dari persaingan, dan menekan pemasok yang lebih kecil untuk memasok perusahaan besar dengan kerugian. Dengan kata lain, korporasi modern bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi entitas politik tanpa akuntabilitas demokratis.
Blakeley menjelaskan sebagai alat yang melindungi korporasi besar dengan gambaran pemerintah memberikan subsidi dan tax holiday bagi perusahaan multinasional “bernilai strategis,” sementara UKM yang berpotensi bersaing misalnya produsen energi terbarukan lokal hanya mendapatkan insentif minimal. Akhirnya, inovasi teknologi yang idealnya mempercepat pertumbuhan ekonomi justru direm, karena pasar digerakkan oleh kepentingan korporasi besar yang lebih suka memonopoli sumber daya dan mengatur pasokan agar selalu menguntungkan mereka.
Secara sosial-politik, perencanaan ekonomi terpusat ini menggenjot kesenjangan upah. Ketika perusahaan raksasa mematok tingkat upah rendah, karena mereka sudah menjamin arus kas lewat utang murah dan subsidi negara, pekerja pabrik dan sektor jasa dipaksa menerima gaji stagnan, di tengah harga barang dan inflasi yang terus merangkak.
Ini membuktikan bahwa “perencanaan” bukanlah alat untuk meratakan ekonomi, melainkan sarana untuk meraup keuntungan jangka pendek atas nama efisiensi. Inflasi yang dibenarkan sebagai “akibat global” sesungguhnya tak lepas dari fakta bahwa korporasi besar memasok barang dalam jumlah terbatas, demi menjaga margin keuntungan padahal arus modal lintas batas dan utang murah semestinya menstabilkan harga, bukan menekan daya beli.
Sisi politik dari perencanaan sistem ini juga tidak kalah penting. Ketika oligarki keuangan mendanai kampanye politik secara masif, regulasi yang dihasilkan menjadi saluran petaka: aturan perpajakan dilonggarkan bagi konglomerasi, standar lingkungan dicabut, sementara kebijakan proteksi UKM dilunakkan. Hasilnya, negara kehilangan kedaulatan kebijakan; setiap kali negara hendak mengajukan RUU yang mengancam keuntungan korporasi besar, misalnya menaikkan royalti tambang, serangkaian lobi kuat langsung bekerja, bahkan hingga ancaman arbitrase internasional (ISDS) kepada pemerintah. Ini wujud nyata bagaimana perencanaan oligopoli merembet ke kekuasaan politik, mereduksi demokrasi menjadi formalitas belaka.
Blakeley juga mencatat bahwa di negara berkembang, perencanaan ini semakin mudah diimplementasikan. Pemerintah yang haus investasi sering kali menurunkan standar lingkungan dan memperlemah hak pekerja demi menonjolkan “iklim bisnis ramah investor”. Akibatnya, aktivitas ekstraksi melalui penambangan secara sistematis merusak ekosistem dan memiskinkan masyarakat adat setempat. Kontrak-kontrak konsesi, yang sama sekali tidak memberikan ruang partisipasi bagi komunitas lokal, menjadi instrumen efektif Behemoth untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa beban tanggung jawab sosial.
Dalam praktiknya, skema perencanaan ini berjalan di balik jargon pembangunan. Proyek infrastruktur skala besar, membangun pelabuhan baru, membangun jalan tol, atau megaproyek listrik, sering diiringi kredit murah dari lembaga multilateral. Namun ketika pinjaman ini tidak dikelola dengan baik, yang rugi pertama-tama adalah rakyat: utang publik melonjak, dan proyek infrastruktur belum selesai, meninggalkan utang yang harus dibayar generasi mendatang. Sementara itu, konsesi pengelolaan infrastruktur, setelah negara mengambil sebagian risiko, dijual ke entitas swasta dengan keuntungan berlipat, tanpa mengembalikan proporsi keuntungan yang setara kepada publik.
Pola serupa terlihat di sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika universitas negeri didorong untuk go public atau go private, peran negara melemah dan sektor swasta mengambil alih. Meski dalam narasi awal disebut akan “meningkatkan efisiensi dan akses”, realitasnya biaya kuliah dan biaya pengobatan jadi melambung, memaksa masyarakat menengah ke bawah menanggung beban utang pelajar dan kewajiban asuransi kesehatan. Bukannya membebaskan individu, perencanaan ini malah menciptakan belenggu utang, menegaskan bahwa Behemoth tiga kepala memosisikan rakyat sebagai konsumen sengsara, bukan warga negara yang berhak atas pendidikan dan layanan dasar.
Akhirnya, Blakeley menegaskan bahwa perencanaan Behemoth tak hanya soal mengalokasikan sumber daya demi keuntungan sesaat. Ia adalah instrumen politik yang menghasilkan oligopoli abadi, di mana pemerintahan lokal dan nasional terjebak dalam kebijakan jangka pendek agar modal besar tetap “nyaman” beroperasi.
Hal ini sekaligus menimbulkan paradoks: negara yang tampak kuat secara legal—dengan segudang regulasi—justru menjadi lemah secara substansial, karena semua kebijakan disusun untuk melayani kepentingan korporasi, bukan rakyat. Dengan demikian, “perencanaan” yang dipuja-puji sebagai prasyarat kemajuan ekonomi berubah menjadi alat monopoli, yang menurunkan kemampuan inovasi, mematikan pasar UKM, menekan pendapatan negara, dan pada akhirnya—yang paling pahit—menggerus demokrasi ke akar-akarnya.
Di samping itu, Blakeley juga menyoroti peran utang publik yang meroket: negara-negara yang menerima bailout IMF, setelah berhasil menstabilkan sektor perbankan, wajib menerapkan paket austerity. Bukannya dialokasikan untuk perlindungan sosial, dana publik justru digunakan untuk menutupi utang sektor perbankan yang, ironisnya, segera dijual ke investor swasta.
Konteks Indonesia: Ketidakadilan Struktural dan Ekstraksi Nilai
Di Indonesia, struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pertambangan (nikel, batu bara) dan perkebunan. Investor asing, secara legal atau terselubung, dengan mudah mengakses konsesi pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Perjanjian bagi hasil sering kali timpang: nilai tambang diambil, sementara kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat lokal.
Vulture Capitalism mengingatkan kita bahwa modal predator serupa bisa masuk ke sektor pertambangan: membeli hak eksploitasi murah, lalu mengekspor bahan mentah untuk diolah di luar negeri, menanamkan sedikit nilai tambah, dan pergi begitu kondisi lahan rusak.
Ekstraksi nilai ini menimbulkan ketimpangan yang terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, koefisien gini Indonesia mencapai 0,389—mengindikasikan kesenjangan yang tinggi. Sektor pertambangan, terutama nikel, di satu sisi menciptakan lapangan kerja, tetapi di sisi lain memicu konflik agraria: pelepasan hak atas tanah adat tanpa kompensasi memadai. Investor asing dan konglomerat dalam negeri memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat adat dan petani kehilangan lahan dan sumber penghidupan.
Blakeley menekankan bahwa investor predator sering kali tidak peduli pada eksternalitas lingkungan—karena biaya degradasi tidak langsung ditanggung oleh mereka, melainkan oleh masyarakat dan negara. Di Morowali, Sulawesi Tengah, tambang nikel skala besar telah merusak lahan pertanian, mengotori sungai, dan meningkatkan risiko banjir. Kontras dengan janji “pembangunan” dan “lapangan kerja”, dampak negatif lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi warisan jangka panjang.
Lebih parah lagi, deforestasi masif untuk area tambang memicu hilangnya keanekaragaman hayati. Kontrak-kontrak konsesi biasanya menegaskan “perlindungan lingkungan minimal”, tetapi pengawasannya lemah dan korupsi lokal memudahkan pelanggaran aturan. Investor kemudian menambang dengan cepat ketika harga melonjak, meninggalkan kawah tambang yang tidak direklamasi, serta air lindi yang tercemar logam berat. Lahan kerap diambil murah saat harga nikel rendah.
Dalam bukunya inilah, Blakeley menegaskan: tanpa reformasi pajak sumber daya, pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat hanya menerima porsi kecil, sedangkan pemerintah pusat dan perusahaan asing yang meraup untung besar.
Kesimpulan dan Harapan
Dalam bagian akhir bukunya, Grace Blakeley mengajak pembaca untuk merencanakan mengambil alih kontrol dari euforia investasi asing yang seolah-olah membawa paradigma growth untuk semua. Buku ini menawarkan alarm: ketika modal predator berkuasa, rakyat biasa kehilangan kendali atas sumber daya dan masa depan mereka.
Di Indonesia, di mana tambang nikel, batu bara dan sektor sumber daya alam menjadi ekstraksi kapitalisme, pelajaran Blakeley relevan untuk mendorong perbaikan regulasi, mulai dari royalti berbasis volume produksi, izin lingkungan yang lebih ketat, transparansi kontrak hingga mempertimbangkan pengelolaan yang berdasarkan kepemilikan kolektif.
Peran komunitas lokal dalam melawan vulture capitalism menjadi sangat penting. Blakeley juga menggaris bawahi inisiatif semacam cooperative ownership (kepemilikan koperasi) di mana pekerja turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga ketika terjadi restrukturisasi, setidaknya ada kepentingan kolektif yang melindungi aset dan pekerjaan. Model ini, menunjukkan jalan menuju bentuk ekonomi alternatif di mana nilai diciptakan bersama, bukan diekstraksi secara sepihak oleh investor luar
Meskipun contoh yang dipaparkan didominasi oleh kasus di AS, Eropa dan Amerika Latin, Blakeley menekankan urgensi untuk bertindak. Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan struktural, vulture capitalism akan terus merusak planet dan memperdalam ketimpangan.
Blakeley memberikan optimisme bahwa dengan kesadaran dan aksi kolektif, kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan aksi kolektif, kita dapat memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran kolektif, bukan menjadi incaran vulture capital yang meninggalkan kerusakan.
Faith Liberta A.M., mahasiswa magister Antropologi UGM dan anggota Serikat Tani Mandiri.