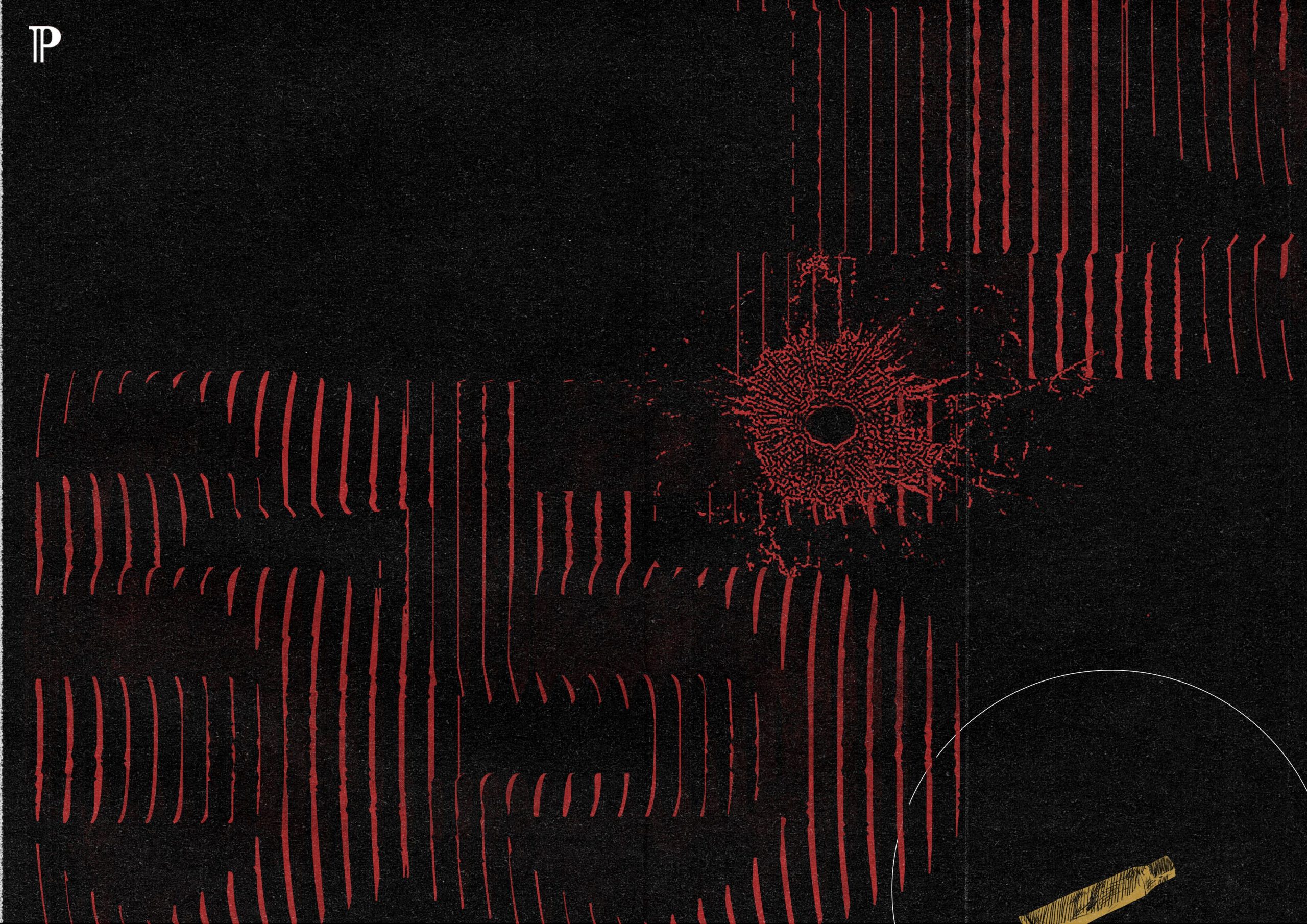Ilustrasi: illustruth
1965 adalah angka bergema, tahun bergejolak dalam dunia yang bergerak. Peristiwa relevan geopolitik apa yang misalnya terjadi pada tahun itu? Dari pelbagai peristiwa yang bisa ditemukan di internet saya ambil beberapa contoh.
Pada Maret 1965, untuk pertama kalinya Amerika Serikat meluncurkan pesawat luar angkasa berawak bernama Gemini. Pada Juni, astronaut Edward White berhasil berjalan menapakkan kaki di angkasa luar. Tiga bulan sebelum itu, dia sudah didahului oleh kosmonaut Rusia Aleksei Leonov, orang pertama yang berjalan di luar angkasa. Program antariksa ini tidak hanya mempersiapkan pendaratan pertama di bulan melainkan juga eksplorasi terhadap planet Mars di tahun-tahun mendatang.
1965 adalah juga tahun ketika Malcolm X ditembak mati, dan enam ratus orang Afro-Amerika bentrok dengan polisi dan tentara dalam sebuah peristiwa yang kemudian disebut Ahad Berdarah (Bloody Sunday). Martin Luther King yang berperan sebagai pemimpin gerakan hak-hak sipil menyelenggarakan tiga mars protes dari Selma ke Montgomery. Mars ini bertujuan untuk meningkatkan tuntutan mereka bagi hak-hak warga Afro-Amerika. Tahun 1965 juga ditandai dengan peningkatan cepat jumlah tentara Amerika di Vietnam Selatan, untuk menyaingi cengkeraman kuat kalangan komunis Vietcong atas warga pedesaan negeri itu. Pada awal tahun, operasi Rolling Thunder bertanggung jawab bagi hujan bom di wilayah itu. Pada paruh kedua 1965 ofensif Amerika terutama terpusat pada operasi marinir Starlite, di selatan Da Nang, dan Piranha, diarahkan pada basis Vietcong di Semenanjung Batangan.
Masih pada tahun itu, Kolonel Houari Boumédienne di Aljazair menjatuhkan Presiden Ben Bella. Di Kongo, Sese Seko Mobutu tampil berkuasa melalui kudeta militer. Pada Agustus, Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia dan di Filipina, pada November, Ferdinand Marcos terpilih sebagai presiden. Di Indonesia, pada 1 Oktober 1965, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan sebagai reaksi terhadap apa yang disebut upaya kudeta Partai Komunis Indonesia yang konon terjadi pada malam hari sebelumnya. Pengambilalihan kekuasaan ini diikuti dengan genosida terhadap siapa saja yang dianggap komunis dan kiri, dan konsolidasi kekuasaan Soeharto. Ini terjadi dengan bantuan Amerika Serikat dan sangat memuaskan pemerintah semua negara Barat.
Rangkaian peristiwa pada 1965 itu menghasilkan rekaman sesaat ketika berlangsung Perang Dingin, yang disebut “dingin” karena dua blok kekuasaan besar pada waktu itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak saling melancarkan perang secara fisik. Walaupun secara ideologis mereka berdua merupakan kutub-kutub yang berlawanan, tetapi keduanya berhasil mencapai kesepakatan untuk bertindak sesuai kepentingan masing-masing dalam keadaan “damai bersenjata”.
Perdamaian yang disesaki senjata itu “dilagakan” bukan cuma di planet bumi, melainkan juga di sekitarnya, di angkasa luar, di mana berlangsung perlombaan teknologi antariksa yang menegangkan. Baik keberhasilan gemilang maupun kegagalan di luar angkasa, demikian pengakuan kedua blok kekuasaan yang saling bersaing, adalah demi melayani kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Di bumi sendiri berlangsung perlombaan senjata-senjata canggih yang hanya bertujuan untuk saling mengejutkan siapa saja, demikian bunyi penjelasan negara-negara yang memiliki senjata-senjata macam itu. Pada saat yang sama pabrik-pabrik senjata masih beroperasi menghasilkan senjata-senjata konvensional. Senjata macam ini bisa dikerahkan untuk merawat perimbangan kekuasaan geopolitik.
Dua blok kekuasaan besar berupaya mencapai keseimbangan itu dengan cara menggapai negara atau pemerintahan negara lain masuk dalam wilayah pengaruhnya, atau membuat negara yang sudah masuk pengaruh tetap ada di dalam wilayah itu. Perimbangan itu bukannya selalu sempurna. Blok kekuasaan yang berupaya mempertahankan kapitalisme tampak lebih tangkas ketimbang kekuasaan besar yang ingin melanggengkan komunisme.
Para pemimpin pemerintahan yang tidak begitu disukai, terutama di “dunia ketiga”, sebagian besar baru membebaskan diri dari kolonialisme, diawasi dengan curiga dan jika perlu akan ditangani. Sebagian besar negara ini bergabung dalam gerakan non-blok dan dengan demikian menggarisbawahi keinginan mereka untuk tidak masuk dalam dua blok kekuasaan yang ada. Amerika menindak tegas pemerintah negara lain yang tidak disukainya. Umumnya tentara nasional setempat dipilih sebagai penindak langsung. Supaya mampu menjalankan tugas ini tentara itu dilatih dan diperlengkapi dalam pelbagai institut militer di pusat kekuasaan. Regime change (pergantian pemerintah) selalu disertai pertumpahan darah.
Begitu terjadi pertumpahan darah sistematis dalam skala besar, orang dihilangkan; mereka yang melakukan perlawanan akan ditangkap dan dipenjara, disiksa, dibiarkan kelaparan. Kalau perlu kalangan yang mbalelo ini juga dideportasi ke wilayah-wilayah yang terpencil jauh dari dunia berpenghuni. Misalnya kamp tahanan di padang pasir Atacama, Cile serta Pulau Buru yang dengan panjang lebar pernah saya sebut dalam dua esai terdahulu.[1]
Banjir darah di dua negara di atas dan di negara-negara lain sedikit banyak berlangsung karena bantuan strategis militer serta nasihat Amerika Serikat. Dalam buku berjudul Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang, wartawan Amerika Vincent Bevins menggambarkan pembentukan secara bertahap dimensi penuh kekerasan Perang Dingin ini, sejak 1950an—misalnya Perang Korea dan campur tangan di Guatemala serta Kuba. Walau demikian, tulis Bevins, adalah kemenangan blok pimpinan Amerika di Brasil (1964) dan Indonesia (1965) yang merupakan awal perkembangan “a monstrous international network of extermination” (jaringan pemusnahan internasional yang mengerikan) dan telah menyebabkan pembunuhan massal sistematis terhadap warga sipil banyak negeri.[2]
Didorong oleh keinginan blok kapitalistis untuk memperluas kepentingan ekonomi dan geopolitisnya, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan itu tak berbatas. Bukannya jumlah korban terlalu banyak tatkala Presiden Brasil João Goulart dicopot dari jabatannya pada 1964. Kudeta itu bahkan tidak butuh pertumpahan darah. Yang terjadi adalah penggunaan kekerasan negara secara perlahan-lahan terhadap siapa saja yang dianggap kiri dan komunis. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada 1970-an dan menjangkau lebih jauh dari kekuasaan Presiden Goulart. Para penggantinya tampil sebagai sekutu yang begitu setia, terampil dan khususnya fanatik dalam melaksanakan pembersihan politik lebih lanjut halaman belakang besar Amerika Serikat, wilayah selatan Amerika Utara.
”Metode Jakarta” seperti tertera pada judul buku Bevins juga diterapkan di negara-negara lain yang merupakan “halaman belakang”, berupa lisensi bagi operasi militer rahasia dengan tujuan memusnahkan secara fisik kalangan komunis.[3] Lisensi itu membuka jalan bagi berarti penggunaan taktik dan metode yang bertujuan untuk menakut-nakuti para penentang elite penguasa dengan cara interogasi yang tidak manusiawi, penyiksaan dan pembunuhan.
Pada paruh kedua 1970-an Amerika Latin merupakan killing zone (zona pembunuhan) yang dikuasai pelbagai diktator militer bekingan Amerika Serikat. Bevins tak hanya berkisah tentang individu-individu yang menjadi korban, terutama di Brasil dan Cile, tetapi juga tentang orang-orang yang mondar-mandir antar-benua dan dengan demikian menjadi saksi jalur komunikasi rahasia antara para pelaku kekerasan.
Pengetahuan tentang teknik-teknik interogasi, penyiksaan dan pembunuhan saling dipertukarkan oleh para pelaku kekerasan dari pelbagai negara. Teknik manakah yang paling efektif? Adakah teknik-teknik baru? Tatkala dalam kepala terbayang bagaimana penyiksaan ini berlangsung di pelbagai negara, dengan perasaan bergidik saya menjadi sadar betapa besar jaringan pemusnahan internasional yang mengerikan itu. Kini akan saya ambil pelbagai contoh dari kamp tahanan di Indonesia dan, seperti dikemukakan Bevins, dari Brasil.
Indonesia. Dia mulai ditahan di Yogyakarta. Dikurung dalam bekas Perpustakaan Jefferson yang diubah menjadi pusat penyiksaan, Tedjabayu beruntung karena menghadapi seorang interogator yang lunak. Sebaliknya, banyak tahanan lain yang disetrum waktu interogasi. Ternyata ini merupakan kebiasaan rutin standar. Karena tertarik pada teknik listrik, Tedjabayu mencari tahu listrik seperti apa yang digunakan dalam penyiksaan ini dan mendapati bahwa yang digunakan adalah listrik arus searah. Listrik seperti ini dibangkitkan dengan cara memutar generator dengan tangan, membuat penyiksaan berkali-kali lebih menyakitkan, berarti “lebih efektif” ketimbang jika digunakan listrik arus bolak-balik. Algojo tampak lebih puas mendengar jeritan pilu pihak yang diinterogasi, setiap kali dia naikkan aliran listrik.[4]
Hampir 10 tahun mereka berada di Pulau Buru. Panas terik matahari tetap menerpa punggung para tahanan politik yang bekerja keras. Lima tahun terakhir kamp diperluas menjadi wilayah berbentuk lonjong dengan panjang mencapai sekitar 30 kilometer. Di situ para tapol harus membangun sendiri 21 unit sebagai tempat tinggal mereka. Tiba-tiba datang hari itu … “Pada hari itu mereka memerintahkan tapol-tapol berkumpul di lapangan dan semua anggota Unit V dihajar habis-habisan. Ada bisik-bisik bahwa para tahanan telah membunuh seorang perwira. Mereka dihajar sehingga paling sedikit ada 13 orang yang tewas di tempat, karena tidak boleh ditolong dan didiamkan di lapangan. Mereka tewas karena kehabisan darah.”[5]
Brasil. Pada 1970 seorang perempuan keturunan Bulgaria, Dilma Rousseff, ditahan karena melakukan “tindakan membakar-bakar massa”. Lebih dari 40 tahun kemudian, dalam masa jabatan kepresidenan pertamanya, Rousseff memberi kesaksian bahwa dia selama berminggu-minggu mengalami siksaan dalam pelbagai cara semasa diktator. Dia digantung secara terbalik, kaki di atas, apa yang disebut metode parrot’s perch (burung beo bertengger). Kemudian mereka memukul patah gigi-giginya menggunakan setrum.[6]
Belum lama berselang baru terungkap bahwa penulis terkenal Brasil Paulo Coelho juga merupakan korban perburuan politik semasa diktator militer. Pada waktu itu dia belum jadi penulis alih-alih seorang pencipta lagu. Sesudah ditahan dia dibawa masuk kamar penyiksaan dengan mata ditutup. Di situ dia mengalami sakit yang tidak terperikan tatkala disiksa dengan aliran listrik yang, dalam kasusnya, melalui kabel yang dilekatkan pada alat kelaminnya. Karena putus asa, dia garuk-garuk sampai kulitnya terkelupas sehingga bercak-bercak besar darah memenuhi sekujur tubuhnya. Tiba-tiba algojo-algojo yang menyiksanya meninggalkan ruangan penyiksaan yang kedap suara, yang terasa semakin mencekam karena tampak lubang-lubang peluru di tembok. Adakah para algojo itu terkejut melihat begitu banyak darah dan menghindari tanggung jawab kalau sampai atasan mempermasalahkannya? Atau sadarkah mereka tiba-tiba bahwa telah menangkap orang yang salah? Adakah kebetulan itu yang telah menyelamatkan Paulo Coelho?[7]
Sangat bisa dibayangkan bahwa akibat siksaan listrik seseorang bisa menjadi hilang ingatan. Di kamp tahanan Pulau Buru terdapat beberapa orang yang sakit ingatan. Sering terjadi bahwa kondisi kejiwaan yang tidak bagus atau depresi telah menyebabkan orang bunuh diri. Kaitan antara keduanya tidak bisa dengan mudah dibuktikan, pasti tidak dalam keadaan ketakutan, stres dan kelaparan terus-menerus. Ancaman berulangnya penyiksaan terus dirasakan para tahanan. Beberapa orang gantung diri di bawah pohon, beberapa yang lain lompat ke laut.
Hilang ingatan untuk selamanya. Itulah hantu paling mengerikan yang bergentayangan di kamp tahanan. Para tapol berbuat apa saja untuk menghindarinya. “Biasa saja”, berupaya menjaga kesehatan otak dengan cara saling bertukar cerita (karena tidak ada buku untuk dibaca), dengan menulis (kalau mereka bisa memperoleh pena dan kertas), dengan berupaya selalu fit (walaupun badan melemah karena kelaparan) dan sebanyak mungkin berburu binatang kecil, sesuatu yang penting supaya bisa memperoleh zat protein yang esensial.[8]
Pada 1970-an Perang Dingin masih terus berkecamuk. Vietnam berhasil meloloskan diri dari jaringan kekuasaan kapitalis. Bagi Amerika, Perang Vietnam yang berlangsung antara 1955 dan 1975 mengakibatkan trauma nasional; puluhan ribu serdadu tewas dan lebih banyak lagi yang mengidap PTSD (gangguan mental akibat peristiwa traumatis) di negeri sendiri. Kekalahan yang memalukan ini dikompensasi dengan ikan besar atau ikan rada kecil yang tersangkut dalam jaringan penguasa dunia kapitalistis, di dalam maupun di luar halaman belakang sendiri. Ikan jumbo untuk tahun 1965, Indonesia, tetap merupakan hasil tangkapan terbesar di luar belahan bumi Amerika sendiri.
Walau begitu, akhir 1975, penggagas Perang Vietnam masih berhasil menangkap ikan kecil dalam jaringan pengaruhnya, di perairan strategis Hindia. Pada Desember 1975, pasukan Indonesia menyerbu wilayah yang waktu itu disebut Timor Portugis dan yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Operasi ini sepenuhnya direstui Amerika Serikat, karena wilayah separuh pulau berbukit-bukit ini, setelah mundurnya penjajah Portugal, terancam menjadi sarang komunisme. Aksi militer kilat ini menjadi berita dunia tatkala terungkap bahwa lima orang wartawan Australia dibunuh di sebuah desa yang terletak pada perbatasan Timor Barat. Di seantero penjuru dunia media massa memberitakan apa yang disebut The Balibo Five (lima orang Balibo).[9] Kemudian berlanjut dengan periode pendudukan militer selama 24 tahun dan selama periode itu seperempat penduduk Timor Leste tewas.
Perimbangan kekuasaan dunia baru mulai berubah menjelang akhir abad silam. Untuk banyak kaum muda, istilah “Perang Dingin” sudah tidak lagi bermakna apa-apa.
Sepanjang dekade 1980-an, dan pasti setelah robohnya Tembok Berlin, puncak kekuasaan blok kapitalistis menguasai arena permainan pada hampir segenap penjuru dunia. Penguasaan dunia itu nyaris terpusat menjadi satu kutub. Pelbagai diktator militer mulai beruntuhan.
Diktator militer Brasil sudah berakhir pada 1985, diktator militer Indonesia dapat bertahan sampai 1998. Mendekati pergantian abad, dengan sorak-sorai meriah, beberapa negara melakukan reformasi politik. Konon dunia akan memasuki “kebebasan demokratis” yang lebih besar. Tapi benarkah pelbagai rezim diktator itu sudah berakhir selamanya dari panggung politik? Akankah tatanan dunia sekarang benar-benar bebas dari ancaman —benar atau rekayasa— yang mewajibkan umat manusia menggunakan senjata fisik atau psikologis?
Penghujung 2015. Pada akhir persidangan selama tiga hari di Den Haag, ketua majelis hakim International People’s Tribunal 1965 membacakan hasil sidang berkaitan dengan tuduhan terhadap negara Indonesia tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966 dan tahun-tahun sesudahnya. Dalam dakwaan dan laporan majelis hakim tertera pembunuhan massal, penahanan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan, kekerasan seksual, perburuan (persekusi) dan propaganda kebencian.[10] Selanjutnya juga tertera keterlibatan Amerika Serikat, Britania Raya dan Australia, masing-masing dalam peringkatnya sendiri-sendiri. Tribunal ini dirancang dalam norma hukum formal, tetapi tidak punya status internasional resmi yang diakui. Tribunal ini bisa berlangsung berkat kerja keras para pakar, dan sukarelawan aktivis, termasuk penulis.
Para penyintas yang sementara itu sudah lansia datang dipapah menjadi saksi di depan tribunal. Dengan meyakinkan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan para hakim dan jaksa penuntut. Salah seorang saksi, pensiunan guru yang sudah mencapai 80 tahun lebih, bertutur tentang penghinaan mendalam yang dialaminya selama interogasi ketika ditahan. “Pak, saya ini tidak melakukan gerilya politik. Saya sudah menemukan posisi yang mapan sebagai mahasiswa dan guru, kenapa gerilya? Buat apa gerilya? Adik saya membutuhkan saya. Tetapi dengan jawaban itu tanpa dinyana kepala saya ditendang, saya ditelanjangi lagi. Dalam keadaan telanjang, saya dipegang, dua orang, saling menghadap … dan mencium kemaluan mereka.”[11]
Karena luapan emosi, baik pada pihak saksi maupun penerjemah, sidang harus dihentikan selama seperempat jam.
IPT yang menyingkap tirai penutup berbagai macam kejadian di Indonesia pada 1965-1966 sedikit lebih jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Joshua Oppenheimer dalam dua film dokumenternya yaitu Jagal dan kelanjutannya Senyap. Rencana melansir bagian tiga seri dokumenter ini, dengan penyesalan besar Oppenheimer, tidak kesampaian. Sang sutradara dilarang masuk Indonesia dan beberapa orang Indonesia yang bekerja sebagai awak film ini, karena alasan keamanan, terpaksa pindah rumah.
Pelbagai kisah tentang kehidupan dalam kamp konsentrasi membangkitkan angan-angan dalam diri saya yang tidak mudah diusir, walau saya tidak mengalami sendiri kehidupan penuh derita itu. Tidakkah hidup di wilayah jauh terpencil, seperti Buru, mirip dengan hidup di planet lain? Pulau itu sulit dijangkau, panas di siang hari tidak tertahan, pagi hari dingin, tanah kering-kerontang dan berkarang, hutan dan semak belukar sarat reptil dan serangga. Lebih dari itu, nyaris tidak ada kontak dengan orang-orang tercinta, keluarga, orang-orang di “dunia biasa”. Ini sama saja dengan hidup dalam pengasingan total.
Malvinas! Demikian Buru sering disebut oleh para penyintas kamp ini.[12] Malvinas bukanlah “planet lain”, melainkan satu tempat yang sama jauhnya dan sulit terbayangkan. Ini adalah sejumput pulau-pulau kecil di bagian lain dunia, yang pada 1982 menjadi penyebab perang antara Argentina dan Inggris: Las Islas Malvinas, orang Inggris menyebutnya kepulauan Falklands. Sedangkan “Malvinas” merupakan semacam kata sandi para penyintas untuk menyebut Pulau Buru, penyatu ingatan dan pengalaman mereka. Kata sandi ini menawarkan ruang aman untuk saling tukar ingatan bersama.
Selain sebagai sandi yang menghubungkan orang, perumpamaan seperti ini juga dapat membantu untuk berkisah tentang kebenaran di balik episode hitam sejarah lewat cara yang terselubung. Dalam film dokumenter pendek bernuansa science-fiction, A Thousand and One Martian Nights (seribu satu malam Mars), seniman Indonesia Tintin Wulia menampilkan beberapa orang penyintas pembunuhan massal di bawah Soeharto.[13] Pada 2165, orang-orang ini berkilas balik menuturkan pengalaman 100 tahun silam. Pada 2065 mereka termasuk ribuan orang anti rezim yang selamat dari kematian karena diasingkan ke planet Mars. Kisah para aktor dan sineas—yang juga cucu salah seorang korban pembunuhan massal—silih berganti dengan film buatan bagian ilmiah NASA yang pada 1965 sudah melakukan penelitian terhadap kemungkinan adanya kehidupan di Mars.
Salah seorang aktor penyintas memulai penuturannya dengan pengalaman yang menyakitkan.
“Saya masih ingat betul itu: kira-kira jam tiga malam saya mendengar teriakan-teriakan Tonwal yang menggedor-gedor barak kami. Dan begitu kami keluar kami digebuki, entah memakai popor bedil atau kayu yang mereka ambil begitu saja. Dan kami sama sekali tidak tahu. Kemudian kami diminta untuk tiarap. Yang saya pikir jangan-jangan ada yang lari. Mars itu tanahnya keras dan tajam, siku saya berdarah-darah. Kalau soal digebuki sih tidak masalah tapi siku kami ini kena keringat, jadinya perih. Tetapi yang paling saya ingat saat itu adalah suasana di mana di tempat gelap, di kegelapan yang pekat itu ada bunyi kelontang-kelontang, misting-misting kami yang selalu kami bawa karena kami harus bekerja.”
“Nah, tiba-tiba teman saya di sebelah itu berbisik dengan tertawa. Bung, ini akan saya jadikan adegan pembukaan dari film saya, nanti. Saya tertawa-tawa sambil bilang: kamu itu bintang film, anak sutradara, pikirannya soal film saja. Kata Tonwal, ‘Cukimai, malam-malam berdiri saya disuruh bangun hanya untuk membangunkan kamu yang malasnya bukan main. Ayo bangun, ini hari apa? Ini hari tanggal ulang tahunmu, tahu?’ Dia bilang itu adalah ulang tahun organisasi kami, yang mereka takuti.”
“Pengalaman saya saat itu digebuki, dipukuli sampai berdarah-darah, kemudian menerima surat dari istri yang menikah lagi, menerima surat dari teman bahwa ‘pacarmu sudah meninggalkan kamu’.”
“Itu betul-betul kejadian sehari-hari yang buat saya merupakan sebuah lelucon saja, lelucon yang harus kita hadapi. Karena seperti yang saya katakan kemarin-kemarin; ad astra per aspera, ke bintang lewat penderitaan.”[14]
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Dan bagaimana dengan kebebasan demokratis pada masa kini? Rezim Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini tidak menjadi lebih ramah. Para komentator politik mengamati dengan mata kepala sendiri mundurnya nilai-nilai dan praktik-praktik demokratis, sejauh itu semua mulai mengakar. Dari meja pemerintahan tampil ke depan aktor-aktor politik dengan lagu-lagu yang senada dengan nyanyian yang sudah pernah terdengar pada paruh kedua abad lalu. Beberapa kambing hitam yang semula dikira sudah terlupakan, antara lain kalangan komunis, ditampilkan kembali. PKI konon kembali bangkit, seperti terlihat pada yel-yel nyaring disuarakan oleh macam-macam geng dan milisi jalanan yang terasa mengancam.
Mengambinghitamkan seseorang tidaklah sulit: stempel PKI bisa terus dicapkan terhadap siapa saja yang dianggap melanggar kepentingan status quo, seperti para buruh yang mogok, petani yang terusir dari tanah mereka, aktivis lingkungan hidup, kalangan LGBT dan oposisi politik. Betul, Presiden Jokowi sudah menyatakan penyesalan atas sejumlah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia, termasuk yang terjadi tahun 1965-1966 dan menetapkan sebuah keputusan untuk menyelesaikannya. Namun, betapa pahit ketika melihat bahwa niat penyelesaian itu baru datang ketika para penyintas langsung sudah tidak banyak lagi. Lagi pula belum terbukti seberapa jauh pemerintahan Jokowi serius dengan niat ini. Keputusan tersebut tidak mencakup pengungkapan kebenaran atas para pelaku kejahatan serta langkah menuju keadilan.
Selain di Indonesia dan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat serta Rusia, disinformasi juga berjaya di Brasil, khususnya pada masa pemerintahan bekas tentara Jair Bolsonaro, sejak akhir 2018 hingga akhir 2022. Bolsonaro memang tidak naik lewat kudeta, melainkan melalui cara “demokratis”, setelah dia dan kaki tangannya menjatuhkan presiden Dilma Rousseff melalui kampanye pemakzulan.[15] Bolsonaro menganggap cara ini harus dilakukan agar Brasil tidak menjadi “Korea Utara kedua”. Demikian katanya kepada wartawan Vincent Bevins pada 2016. Dalam pemilu yang berhasil memenangkannya, terjadi kerusuhan antar-kelompok di jalan-jalan Rio de Janeiro. Laki-laki berbadan gempal menghadapi perempuan-perempuan bertato yang mengenakan emblem calon presiden saingan. Mereka berteriak-teriak, “Komunis! Buang kaum komunis! Enyah, kalian!”[16] Digantikannya Bolsonaro baru-baru ini oleh Presiden Inacio Lula da Silva yang berhaluan sosial demokrat terasa melegakan, walaupun tidak akan serta-merta dapat membendung sentimen dan kekuatan politik para bolsonaristas.
Perubahan politik yang berlangsung dari waktu ke waktu direkam dan diukur, demikian pula kadar demokrasi. Hasil pengukuran bisa berbeda-beda, tetapi runtuhnya demokrasi tidak bisa disebut “sementara”, demikian dilaporkan oleh pelbagai institut internasional independen yang mengamati perkembangan indeks demokrasi. Semakin banyak negara menjadi kurang demokratis. Mungkinkah demokrasi akan sama sekali hilang lenyap?
Perang Dingin telah hidup kembali, demikian kesimpulan beberapa analis. Sejarah berulang, tetapi tidak pernah dalam cara yang persis sama. Walaupun tidak menyenangkan penguasa Indonesia, vonis IPT turut membuka mata kalangan kawula muda perkotaan. Mereka tidak sudi lagi menerima semuanya begitu saja, dan sambil bermimpi hidup dalam dunia yang lebih baik, mereka lawan setiap bentuk penyimpangan, seperti penciptaan dan penyebaran disinformasi. Puluhan tahun silam, banyak di antara kita yang juga sudah mengimpikan hal serupa. Mengimpikan dunia yang lebih baik, di sekitar kita sendiri, di negeri kita dan bagi planet kita.
Dunia yang lebih baik ini konon bukan lagi merupakan impian bagi orang-orang super kaya yang mengangkat dirinya sebagai suhu yang paling tahu soal kemajuan manusia. Apabila semua tempat yang buruk dunia bisa disulap menjadi tempat tinggal nyaman, maka hal seperti itu seharusnya juga bisa dilakukan di angkasa, begitu konon pendapat mereka. Kalau kita harus percaya pada Elon Musk, maka dia akan mengubah Mars menjadi tempat nyaman itu. Bagi saya ini terdengar sebagai keangkuhan yang kejam. Walau cuma dalam angan-angan, sudah terlihat eksesnya berkelebatan dalam bayangan, mayat tahanan yang tak terhitung, budak baru atau orang yang diperbudak, dan mayat-mayat makhluk yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal di planet kita. Serta robot-robot yang mubazir.***
[1] Dua esai itu masing-masing berjudul “Er is geen heden” (tiada hari ini) dan “De geest is uit de fles” (jin sudah keluar dari botol).
[2] Vincent Bevins versi asli bukunya dalam bahasa Inggris, The Jakarta Method, halaman 12.
[3] Dalam esai “Er is geen heden” (tiada hari ini) saya sebut kata sandi “Jakarta” seperti terdengar di jalan-jalan Santiago de Chile.
[4] Tedjabayu, Mutiara di Padang Ilalang, Komunitas Bambu, 2020, halaman 23-24.
[5] Tedjabayu, Mutiara di Padang Ilalang, halaman 183.
[6] Vincent Bevins, The Jakarta Methods, halaman 197.
[7] Vincent Bevins, The Jakarta Methods, halaman 198-199.
[8] Lihat juga esai “De geest is uit de fles” (jin sudah keluar dari botol).
[9] Penjelasan selayang pandang yang bagus tertera dalam buku James Dunn, Timor: A People Betrayed, ABC Books Sydney, 1996.
[10] Ini semua, satu per satu, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti telah disepakati secara internasional. IPT 1965 Foundation, 2016.
[11] IPT 1965 Foundation (2016), halaman 152-153.
[12] Hersri Setiawan, Memoar Pulau Buru, KPG-Gramedia, Jakarta 2016, halaman 438.
[13] Versi terdahulu film dokumenter ini diputar di paviliun Indonesia pada Biennale Venesia tahun 2017, di situ seniman Tintin Wulia merupakan salah satu dari dua kurator yang bertugas.
[14] Titin Wulia, A Thousand and One Martian Nights, film semi-dokumenter, 2017 (peredaran diatur sendiri oleh Tintin Wulia, sebagian disponsori oleh NYC Cultural Affairs).
[15] Setelah Dilma Rousseff dijatuhkan pada 2016, wakil presiden Michel Temer berkuasa sebagai presiden transisi setelah pelantikan Jair Bolsonaro.
[16] Vincent Bevins, The Jakarta Method, halaman 14.
[Esai ini merupakan bab terakhir kumpulan esai Artien Utrecht berjudul “Razende stiltes”, terbitan De Knipscheer, 2022. Diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Joss Wibisono, dengan persetujuan Artien Utrecht yang sudah melakukan aktualisasi]