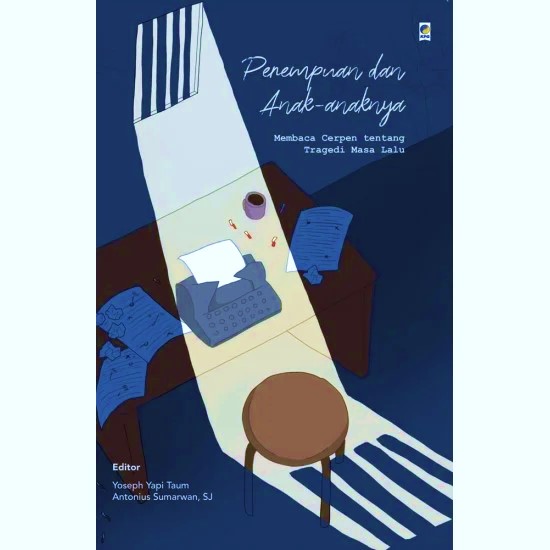
Judul : Perempuan dan Anak-Anaknya: Membaca Cerpen tentang Tragedi Masa Lalu
Editor : Antonius Sumarwan, SJ & Yoseph Yapi Taum
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Kota Terbit : Jakarta
Tahun : 2021
DALAM waktu senggang, selain membaca buku, berkebun, dan menikmati musik (klasik, terutama), salah satu kegemaran saya adalah menulis cerita pendek. Aktivitas ini tentu berlainan dengan kegiatan menulis opini atau kolom yang umumnya memiliki jangka waktu pendek karena menyesuaikan momentum dan aktualitas. Inilah keistimewaan cerita pendek. Prosa sepanjang 1.000-1.500 kata ini cenderung lebih tahan waktu. Penulisannya dapat diulur maupun dipercepat sesuai irama kerja dan mood.
Kelebihan lain cerita pendek yang cenderung tidak dimiliki opini atau jenis tulisan nonfiksi lainnya adalah kebebasan memakai kata-kata, majas, dan metafora sehingga di dalamnya saya dapat mengungkapkan berbagai perasaan yang sulit dinyatakan secara letterlijk: amarah, duka, dendam, penyesalan, dan sebagainya. Emosi-emosi itu, ketika dinyatakan dalam pengandaian, terkadang bisa menemukan ladang subur yang membentuk rangkaian kata-kata dan dengan sendirinya menggerakkan alur cerita.
Cerita-cerita pendek yang saya tulis umumnya bergaya realis, sehingga basis fakta di dalamnya menjadi syarat mutlak. Dengan gaya realis itu, sejak awal saya mendapati kenyamanan mengeksplorasi satu tema dan kerangka besar yang tidak pernah selesai: tragedi 1965. Tema ini saya pilih sebagai napas utama cerita-cerita pendek saya, selain sifatnya yang evergreen, juga tidak pernah surut setiap saya mendapatkan fakta baru—entah dari buku, artikel, video, maupun kesaksian korban. Ia adalah tema yang lentur, menggugah, sekaligus memiliki daya jangkau yang luas.
Dua cerita pendek saya tentang kisah hidup korban tragedi 1965—yang pertama berjudul “Natal Pagi Hardini” dan yang kedua “Doa Sunyi Abdullah Koster”—berhasil memenangkan penghargaan lomba menulis cerita pendek tingkat nasional dari sebuah platform menulis daring. Bagi saya, perhatian dan penghargaan terhadap cerita-cerita pendek tersebut cukup membuktikan bahwa tragedi 1965 beserta sekelumit kisahnya belum lagi surut dalam ingatan orang banyak.
Kendati demikian, masalah bukan berarti lantas menjauh. Tantangan yang saya dapati setiap kali hendak menulis sebuah cerita pendek adalah dua imajinasi liar yang datang tiba-tiba dan cukup membuat saya risau. Imajinasi pertama adalah ketika saya membayangkan karya fiksi ini akan ditanggapi rigid atau dinilai oleh orang-orang yang masih berpikiran dogmatik sehingga bukan mengantar pesan kemanusiaan dan empati terhadap korban, orang-orang itu malah mengasumsikan cerita pendek saya membela PKI dan menyudutkan TNI. Imajinasi ini cukup menghambat proses kreatif penulisan jika tidak segera dilupakan.
Imajinasi kedua, tidak kalah dari yang pertama, adalah imajinasi yang juga lebih sering membuat gamang bahkan membuat saya urung menulis, yaitu bagaimana kalau pembaca tidak paham dengan narasi yang saya tulis? Dibandingkan imajinasi pertama, imajinasi kedua ini terasa lebih faktual, terbukti dalam lingkungan pertemanan di SMA saya.
Teman-teman saya, sebagaimana anak-anak Indonesia pada umumnya—yang baik-baik dan jarang menyentuh buku kalau tidak disuruh—mempunyai pengetahuan sangat dangkal terkait pembantaian massal terhadap orang-orang tertuduh komunis pada 1965/1966. Bagi mereka, ingatan 1965 hanyalah huru-hara sekejap yang menumbalkan tujuh jenderal yang terjadi di Lubang Buaya pada dini hari 1 Oktober. Narasi sejarah yang sejak kecil dicernakan kepada mereka hanyalah “dengan kerja sama rakyat dan TNI, PKI berhasil ditumpas.” Hanya saja, penumpasan yang berdarah dan keji itu sangat sedikit dibahas.
Ketidaktahuan dan ketidakpahaman generasi muda—generasi saya—mengenai peristiwa 1965 (penangkapan, interogasi, pembunuhan, penahanan, pembuangan, dan berbagai dampaknya) rupanya tak hanya menjadi keprihatinan dan kekhawatiran saya saat hendak menulis cerita pendek. Dalam prakata buku ini, Antonius Sumarwan, SJ dan Yoseph Yapi Taum pun menyatakan, alasan mereka menerbitkan kembali cerita-cerita pendek seputar peristiwa 1965 antara lain adalah karena masih kuatnya wacana Orde Baru yang melumrahkan praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang tertuduh komunis atas nama stabilitas dan keamanan. Didikan dan paradigma yang menghalalkan praktik kekerasan itu pula, selain mengakibatkan ketidaktahuan, juga membuat perspektif hak asasi manusia masih cukup awam bagi sebagian besar orang Indonesia dalam meninjau tragedi 1965. Dua keadaan tersebut tentu saja berasal dari monopoli historiografi yang dikerjakan sistematis oleh Angkatan Darat hingga kini.
Sastra Saksi Mata
Ketidaktahuan generasi muda dan masih awamnya perspektif hak asasi manusia dalam meninjau peristiwa 1965 itulah yang hendak dipangkas melalui dua belas cerita pendek dalam buku ini. Keduabelas cerita pendek dalam buku ini secara khusus dipilih hanya yang terbit antara tahun 1966-1970. Tahun-tahun itu, menurut Yoseph Yapi Taum (2015) adalah saat-saat di mana hegemoni Orde Baru masih bertaraf minimum. Cara pandang Orde Baru belum sepenuhnya diterima oleh khalayak umum dan praktik indoktrinasi belum dipakai masif untuk mengendalikan pikiran masyarakat—termasuk imajinasi seorang pengarang.
Sesuai urut judul, kumpulan cerita pendek ini dibuka dengan cerita pendek “Pada Titik Kulminasi” karya Satyagraha Hoerip, dilanjutkan cerita pendek “Perempuan dan Anak-Anaknya” karya Gerson Poyk; “Bintang Maut” karya Ki Panjikusmin; “Sebuah Perjuangan Kecil” karya Sosiawan Nugroho; “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi” karya Zulidahlan; “Domba Kain” karya Ki Panjikusmin; “Perang dan Kemanusiaan” karya Usamah; “Musim Gugur Kembali ke Connecticut” karya Umar Kayam; “Ancaman” karya H.G. Ugati; “Maut” karya Mohammad Sjoekoer; “Bawuk” karya Umar Kayam; dan ditutup dengan “Malam Kelabu” karya Martin Aleida. Cerita-cerita pendek tersebut pertama kali terbit di antara dua majalah sastra prominen kala itu, yakni Horison dan Sastra.
Terdapat tiga cerita pendek yang sebelumnya telah saya akrabi. “Malam Kelabu” karya Martin Aleida yang dimuat di majalah Horison No. 2 Tahun V, Februari 1970; “Bawuk” karya Umar Kayam yang dimuat di majalah Horison No. 1 Tahun V, Januari 1970; dan “Musim Gugur Kembali ke Connecticut” karya Umar Kayam yang dimuat di majalah Horison No. 10 Tahun IV, Agustus 1969.
“Malam Kelabu” mengangkat kisah Kamaluddin Armada, seorang pelaut kelahiran Asahan yang telah siap melamar kekasihnya, seorang putri Solo, namun dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa kekasihnya turut jadi korban pembantaian massal di Solo dan “ikut hilang di tepi Bengawan” bersama ayahnya yang telah menjadi korban lebih dulu.
“Bawuk” mengisahkan perjuangan hidup seorang perempuan tangguh bernama Bawuk, istri seorang petinggi onderbouw Partai Komunis Indonesia yang dalam pelarian sesudah suaminya bergerak klandestin dari satu kota ke kota lain, memilih menitipkan kedua anaknya kepada sang ibu untuk diasuh, sedangkan Bawuk ikut berusaha mencari suaminya yang—kemudian—tewas dieksekusi tentara.
Sedangkan “Musim Gugur Kembali ke Connecticut” membawakan pengalaman Tono, eksponen Lekra dan HSI yang dituduh “revisionis” oleh kawan-kawannya karena ia bosan menulis sesuai tugas politik yang dibebankan kepadanya. Tono sesungguhnya sudah ingin hengkang dari Lekra dan HSI. Terlambat. Gestapu pecah dan nama Tono yang belum menyatakan diri keluar, ditangkap kembali dan ditahan selama 1 ½ tahun sebelum dibebaskan dan menjadi tahanan rumah. Nyatanya, pembebasan Tono bukan akhir cerita. Dengan klaim “PKI Malam” telah beraksi, Tono ditangkap kembali oleh tentara, meninggalkan istrinya yang tengah hamil tua. Tono dieksekusi di perkebunan karet yang dalam citraan Umar Kayam ditamsilkan mirip pohon-pohon musim gugur di Connecticut, Amerika Serikat.
Selain tiga cerita pendek yang pernah saya baca sebelumnya, terdapat tiga cerita pendek lain yang baru pertama kali saya baca dan tanpa ragu saya nisbatkan sebagai cerita pendek yang tidak kalah menggugah. Tiga cerita pendek itu adalah “Pada Titik Kulminasi” karya Satyagraha Hoerip yang secara rinci menggambarkan konflik batin Susetio, seorang guru antikomunis, yang harus mengeksekusi saudara iparnya sendiri karena ideologi yang berseberangan. Susetio sejatinya telah memaafkan perbuatan adik iparnya itu. Hanya saja teman-teman Susetio yang tergulung pendapat umum untuk ikut-ikutan mempersekusi orang-orang komunis menyebabkan Susetio tidak berdaya untuk menolak.
Cerita pendek “Domba Kain” karya Kipanjikusmin kiranya adalah yang istimewa dari cerita-cerita pendek lain. Alurnya sederhana, namun kompleksitasnya di atas rata-rata cerita pendek lain. Mengisahkan tentang Karno, pejuang Konfrontasi Dwikora yang bertaruh hidup-mati sesudah hutan tempatnya bersembunyi diledakkan dengan bom napalm dan menyebabkan wajahnya cacat. Karno selamat. Tetapi ketika kembali ke kotanya, ia putus asa dan gelap mata ketika mengetahui ayah dan adik-adiknya keburu dibantai “segolongan orang yang mencatut nama rakyat dalam menganiaya orang Komunis”. Ia menembak bupati yang ia anggap bersalah sebelum akhirnya menembak kepalanya sendiri.
Cerita pendek yang judulnya dianggit menjadi judul buku, “Perempuan dan Anak-Anaknya” juga menarik perhatian saya karena pendekatannya cukup eksperimentalis. Tokoh A yang setiap kali merasa berdosa sesudah “mengantar jatah”—maksudnya membuang jenazah korban ke sungai atau tempat lain—terutama karena K, musuhnya, yang meninggalkan seorang istri dan lima anak yang kesemuanya masih kecil-kecil. Dengan besar hati, A mendatangi istri K, Hadijah, dan meminta kesediaan Hadijah untuk mencarikan orang tua asuh bagi 5 anak Hadijah dan K, karena Hadijah tak sanggup mengasuh kelimanya. A berkeliling kota untuk mencari orang tua asuh yang bersedia, menghubungi teman-temannya, dan mencari panti asuhan. Nihil. Kesemuanya menyatakan tak sanggup dengan bermacam alasan. Frustrasi, A menghardik Hadijah dan menuding Hadijah sebagai “Gerwani yang materialistis” serta hendak menelantarkan anak-anaknya demi harta. Sikap keras A ini membuat Hadijah jatuh sakit dan meninggal. Hutang budi A kepada lima anak Hadijah dan K membuat ia memilih meninggalkan kota, menumpang dengan kapal, membawa kelima anak kecil itu sebagai anak angkatnya.
Cerita-cerita pendek yang terkandung dalam buku ini, sebagai saksi mata sebuah peristiwa yang menjadi mimpi terburuk bangsa Indonesia, secara halus dan bernuansa, berusaha menuntun pembacanya untuk tidak saja menjadi lebih peka terhadap kisah sejarah yang selama ini ditutup-tutupi, namun juga menstimulus lahirnya pertanyaan, “Harus apa kita sekarang?”
Cakrawala Pembebasan
Buku ini bukan sekadar kumpulan cerita pendek. Inilah letak keistimewaan dan perbedaannya dibanding kumpulan cerita pendek sejenis, seperti Kata-Kata Membasuh Luka karya Martin Aleida atau Cinta, Perang, dan Ilusi karya Asahan Alham Aidit. Buku Perempuan dan Anak-Anaknya tidak sekadar menawarkan fungsi sastra sebagai sarana hiburan, namun juga fungsi sastra yang membentangkan cakrawala harapan (horizon of expectation) yang menstimulus lahirnya tujuan-tujuan baru yang memiliki dimensi penyadaran melalui kisah-kisah di dalamnya.
Ditutup “Gagasan Tindak Lanjut” yang diformulasikan oleh Antonius Sumarwan, SJ, kumpulan cerita pendek ini disertai dengan sebuah penelitian yang menggunakan reader response theory Hans Robert Jauss untuk mengetahui respons pembaca antara sebelum membaca dan sesudah membaca cerita pendek dalam buku ini. Penelitian ini menggunakan kuesioner terlampir yang dapat diisi oleh pembaca secara mandiri atau sesudah membaca cerita pendek ini bersama-sama. Harapannya, dengan membaca dan mendalami cerita-cerita pendek ini menggunakan kerangka riset intervensi dan membandingkannya dengan narasi sejarah resmi, dampak sosial cerita pendek akan menjadi lebih optimal.
Dampak sosial yang dimaksud Antonius Sumarwan bertolak dari tiga langkah. Langkah pertama adalah memindahkan fokus perhatian pembaca dari peristiwa teka-teki di malam 1 Oktober 1965 ke peristiwa yang lebih besar, yaitu serangkaian tindak pelanggaran hak asasi manusia (penangkapan, penyiksaan, eksekusi tanpa peradilan, penahanan, pembuangan, dan lain-lain). Ingatan kita diajak untuk tidak lagi terjebak fantasi berdarah-darah berperangkat tari “Harum Bunga”, lagu “Genjer-Genjer”, aksi-aksi nonsens seperti pencungkilan mata, mutilasi alat kelamin, dan sebagainya, yang selama ini menyesaki memori dan memberati bangsa kita dengan beban yang tak pasti.
Sesudah fokus utama berpindah, langkah selanjutnya adalah memakai perspektif hak asasi manusia dalam membaca cerita-cerita pendek. Perspektif yang dimaksud di sini bukan cuma “memutihkan” dosa-dosa mereka yang dibunuh dan “menghitamkan” Angkatan Darat, melainkan secara lebih terbuka memahami cerita-cerita pendek ini sebagai kisah hidup manusia yang berkejaran dengan maut, keputusasaan, frustrasi, serta kebimbangan. Keterbukaan ini akan mendorong langkah ketiga bekerja dengan maksimal, yaitu membandingkan kisah-kisah saksi mata ini dengan narasi resmi Orde Baru yang selama ini diterima mutlak tanpa pembanding.
Tiga dampak sosial ini diusahakan memiliki dampak lanjutan, khususnya bagi pembaca yang awam terhadap pembantaian 1965, yaitu semakin peduli dan bersedia untuk berpartisipasi dalam kerja-kerja advokasi hak-hak asasi manusia, kesetaraan, dan lingkungan hidup. Pada akhirnya, dari cerita pendek yang mewartakan kesaksian dan protes terhadap pembantaian yang menjadi tonggak rezim fasis-militeris ini, apabila dipahami secara mendalam, diharapkan mengubah cara pandang keseluruhan terhadap peristiwa 1965, atau sekurang-kurangnya mengajak pembaca untuk secara kritis mempertanyakan kembali narasi sejarah Orde Baru yang mendistraksi dan tendensius menutup-nutupi celah pelanggaran hak asasi di tahun 1965/1966.
Dampak jangka panjang kumpulan cerita pendek ini mengingatkan saya pada pendapat Hannah Arendt dalam bukunya Between Past and Future (1993) mengenai pembentukan ingatan kolektif. Hannah berpandangan, ingatan kolektif merupakan alat untuk memutus mata rantai impunitas dan merupakan tanggung jawab kemanusiaan guna membandung kesadaran sosial, struktur yang lebih berkeadilan, dan politik anti-kekerasan yang bersumber dari memori dan narasi korban. Dengan demikian, usaha yang digerakkan dari dimensi penyadaran melalui bacaan cerita-cerita pendek ini ialah memberikan kesempatan untuk “orang-orang kalah” dalam menyatakan diri sehingga sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang.
Relevansi di Tengah Kemarau
Terbitnya Perempuan dan Anak-Anaknya menemukan relevansi di tengah hiruk-pikuk wacana yang diutarakan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Kejaksaan RI, 14 Desember 2020 lalu[1] mengenai rencananya membentuk sebuah tim khusus untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau. Wacana ini ditindaklanjuti dengan penyusunan draft Peraturan Presiden oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia[2] yang mengarah pada pemulihan dan pemberian kompensasi berbentuk santunan seadanya dengan harapan dapat mencapai perdamaian yuridis hitam di atas putih. Sekilas, wacana dan tindak lanjut itu memang cukup membuat dada mongkok. Akan tetapi, cukupkah demikian?
Jawabannya tentu akan variatif. Salah satu jawaban yang disediakan kumpulan cerita pendek ini adalah urgensi perdamaian kultural yang mesti digiatkan terlebih dulu sebelum pernyataan yuridis diteken. Perdamaian kultural itu antara lain mencakup pengakuan resmi negara atas butir-butir kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang diputuskan International Peoples Tribunal 1965[3] tahun 2015 lalu maupun laporan mendalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terbit tiga tahun sebelumnya, disusul tindakan-tindakan kuratif yang dianggap perlu seperti penyelidikan dan pemetaan terhadap korban dan keluarganya yang mengalami stigmatisasi maupun pendokumentasian atas pengalaman korban secara intensif sebagai bahan arsip sejarah. Rangkaian tindakan ini dapat ditutup dengan berbagai tindakan preventif, termasuk menghentikan segala propaganda “Komunis Gaya Baru” atau “Waspadai Laten PKI” dan menulis ulang sejarah berdasarkan fakta-fakta baru yang ditemukan sambil terus mengingatkan, bahwa bukan laten komunis yang harus diwaspadai, melainkan laten berpikir dogmatis-sektarian seperti didikan Orde Baru.
Cita-cita perdamaian kultural ini bukan semata-mata pengungkapan kebenaran demi idealisme “meluruskan sejarah”, namun secara lebih komprehensif, merupakan upaya mengingatkan orang-orang muda untuk tidak mewarisi dendam masa lalu, yang dimulai dengan mendengar kesaksian yang meruntuhkan memori kolektif sebagai dikonstruksikan penguasa selama ini. Perdamaian kultural akan jauh lebih berdampak dalam jangka panjang daripada perdamaian hitam atas putih, karena peranannya yang membebaskan hati nurani generasi muda dari beban sejarah dan teka-teki “siapa-dalang-siapa-korban” yang selama ini diajarkan di kelas-kelas sejarah diniah.
Meski dampaknya yang cukup berpengaruh, Perempuan dan Anak-Anaknya tidak kalis dari kesalahan. Proses penyuntingan yang kurang cermat menyebabkan sejumlah kata-kata tidak baku yang mungkin tidak dimengerti pembaca masa sekarang seperti “finansir” (h.44), “kwantitet” dan “kwalitet” (h.46) masih ditemukan. Selain itu, catatan kaki tentang informasi yang sama dijelaskan berulang kali dengan keterangan berbeda. Misalnya, catatan kaki “CGMI” di halaman 5 sebagai “sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia yang didirikan pada 1956 dan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. CGMI dibekukan oleh pemerintah pada 1 November 1965”.
Sedangkan pada halaman 59, “CGMI” dijelaskan sebagai “Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (Persatuan mahasiswa Komunis Indonesia”. Bagi mereka yang memahami konteks CGMI sebagai organisasi, tentu tidak masalah. Akan halnya, bagi pembaca awam yang tak mendapat pemahaman yang cukup, catatan kaki dengan keterangan berbeda antara organisasi mahasiswa terafiliasi dan persatuan mahasiswa komunis tentu dapat berakibat pada kegagalan memahami konteks.
Di luar aspek-aspek teknis yang menyita perhatian itu, cerita-cerita pendek dalam Perempuan dan Anak-Anaknya, pada akhirnya tetaplah menjadi panggilan yang terus mendengung di relung-relung politik yang hiruk-pikuk dengan kepentingan, namun melupakan identitasnya yang hakiki. Cerita-cerita pendek ini pun menerangi generasi muda—termasuk saya, rekan-rekan dan angkatan saya—akan tugas profetik kami sebagai pelopor untuk Indonesia yang bangun dari mimpi buruk dan beranjak dari perangkap sejarah yang dingin untuk memulai sebuah lembaran baru, di mana nyawa manusia tidak sekadar dijamin, namun diganjar penghargaan setinggi-tingginya.
Kata pembuka buku ini sungguh ingin saya muliakan sebagai penutup tinjauan sederhana ini. Kata pembuka itu mengutip Elie Wiesel, novelis kelahiran Rumania yang pernah menjadi korban holocaust:
Marilah kita berkisah sehingga para eksekutor tidak dibiarkan menjadi pemilik kata terakhir. Kata terakhir adalah milik para korban! (*)
Kepustakaan
Aidit, Asahan Alham. 2006. Cinta, Perang, dan Ilusi: Antara Moskow-Hanoi. Bandung: Lembaga Humaniora.
Aleida, Martin. 2019. Kata-Kata Membasuh Luka. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
Arrendt, Hannah. 1993. Between Past and Future. New York: Penguin Books.
Taum, Yoseph Yapi. 2015. Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
[1] CNN Indonesia, “Jokowi Sebut Kejaksaan Aktor Kunci Penuntasan Pelanggaran HAM”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201214095135-12-581693/jokowi-sebut-kejaksaan-aktor-kunci-penuntasan-pelanggaran-ham (diakses 8 Mei 2021, pukul 17.34).
[2] https://drive.google.com/file/d/1iz44zR-9TlzAzPEYuVnxzzJEinGvdg8b/view?usp=sharing
[3] Helen Jarvis & John Gittings, “Final Report of The IPT 1965”, https://www.tribunal1965.org/tribunal-1965/laporan-sidang/ (diakses 8 Mei 2021, pukul 18.02).





