Pudjiwati Sajogyo (kiri). Kredit foto: Rachmat Marsaoly – WordPress.com
BARANGKALI banyak yang sudah melupakan atau bahkan belum pernah mendengar nama Pudjiwati Sajogyo sebagai salah seorang perintis studi perempuan di Indonesia, khususnya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pudjiwati, guru besar sosiologi pedesaan di IPB, termasuk genre studi perempuan dekade 1970an yang seringkali ditempatkan sebagai genre women and development (paradigma pembangunan yang berupaya mengakui peranan perempuan dalam pembangunan, untuk mengkritik pembangunan yang mensubordinasikan perempuan). Genre women and development dipandang belum radikal dalam menjelaskan penindasan perempuan oleh genre gender and development yang membongkar ideologi gender sebagai sumber penindasan perempuan. Di Indonesia, genre women and development sempat disingkirkan oleh pendukung genre gender and development, dan dianggap representasi dari ideologi perempuan versi Orde Baru. Genre gender and development banyak dipeluk oleh aktivis feminis yang membangun NGO Perempuan sejak pertengahan dekade 1980an, dan selanjutnya cukup berhasil menanamkan cara pandang baru mengenai kesetaraan dan keadilan gender.
Belakangan ini setelah saya membaca ulang laporan penelitian Pudjiwati, saya justru mempertanyakan pandangan saya sebelumnya: benarkah hasil studi perempuan genre women and development di Indonesia kurang radikal? Ketika saya membaca ulang laporan penelitian Pudjiwati antara awal 1980-1990an, saya menemukan temuannya yang radikal, yang menurut saya, masih relevan sebagai persoalan perempuan dewasa ini, tetapi tersingkir dari arus besar studi perempuan yang dipengaruhi oleh studi budaya (cultural studies). Tulisan ini akan menyajikan temuan radikal Pudjiwati mengenai kerja ganda perempuan dalam menyumbang keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kata lain, Pudjiwati berupaya untuk membuktikan besarnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang dihilangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)
***
Pudjiwati Sajogyo telah merintis studi wanita[1] sejak 1978 dan membangun Pusat Studi Wanita (PSW) di IPB sejak 1990an.[2] Keberadaan Pudjiwati sebagai peneliti perempuan yang mengkhususkan pada studi perempuan, berkorelasi dengan “desakan” Konferensi Perempuan Internasional I kepada negara-negara anggota di seluruh dunia agar memerhatikan situasi perempuan yang termarginalkan oleh pembangunan itu sendiri. Sejatinya, kerangka besar yang melandasi studi perempuan yang diampu Pudjiwati adalah mengenai kependudukan yang berkorelasi dengan peranan perempuan dan integrasi tenaga kerja perempuan dalam pembangunan. Pada saat itu tema studi perempuan umumnya berhubungan dengan kependudukan, ketenagakerjaan, migrasi (transmigrasi dan urbanisasi), kerja, keluarga berencana, gizi dan nutrisi, revolusi hijau, dan berbagai ekses pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sosiologi dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang sangat produktif mendukung studi perempuan tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih faktual mengenai realitas perempuan miskin di pedesaan maupun perkotaan.
Apa yang melatari studi perempuan saat itu (secara global maupun di Indonesia) bahwa cuaca pembangunan dan pembangunanisme merupakan hajat global yang mengejutkan masyarakat di negara mantan jajahan selaku penerima pasif. Sementara para ahli dari negara-negara maju yang berupaya untuk memindahkan pengalaman pembangunan di negaranya ke negara mantan jajahan juga mengalami keterkejutan. Bagi masyarakat di negara mantan jajahan –termasuk Indonesia—pembangunan telah merampas tanah, menghilangkan pekerjaan manual di bidang pertanian, mengubah konsep keluarga dan rumah tangga, mengubah relasi-relasi sosial dan ekonomi, mengubah relasi masyarakat dengan teritorialnya, dan lain sebagainya. Pengenalan rasionalitas dan teknologi di bidang pertanian, penyelenggaraan anak (keluarga berencana), dan hajat kehidupan sehari-hari seperti alien yang turun dari langit, yaitu sesuatu yang asing bagi penduduk negara mantan jajahan, termasuk perempuan. Dalam banyak praktiknya, pembangunan telah menyingkirkan perempuan dari hubungan-hubungan produksi pertanian dan yang berhubungan dengan alam. Bagi ahli-ahli pembangunan dari negara maju atau pemeluk ‘teori modern’, pembangunan di negara mantan jajahan yang tidak mengalami kemajuan rasional sebagaimana di Eropa atau AS, melahirkan rasa penasaran yang sangat besar.
Pendeknya urusan pembangunan menjadi lokus penelitian studi perempuan di seluruh dunia yang diangkat oleh feminis genre 1960an dan 1970an, ketika menemukan bukti bahwa pembangunan dalam realitasnya telah menghilangkan perempuan sebagai subyek sosial. Penelitian Ester Boserup yang dibukukan dalam Women’s Role in Economic Development ( 1970) di pedesaan Afrika, telah diterjemahkan oleh Pudjiwati ke dalam bahasa Indonesia menjadi Peranan Wanita Dalam Pembanguna Desa (1985). Kiranya Ester Boserup merupakan salah satu rujukan yang dipergunakan Pudjiwati dalam membangun studi perempuan dan pembangunan.
Selain Pudjiwati, setelah Konferensi Perempuan Internasional I di Mexico City 1975, bermunculan peneliti akademik yang memusatkan studinya pada kategori sosial perempuan dalam konteks pembangunan. Mereka adalah Yulfita Rahardjo, Melly G. Tan, Mayling Oey Gardiner, Saparinah Sadli, TO Ihromi, Kartini Syahrir, dll, yang hasil penelitiannya dimuat oleh Jurnal PRISMA (1976) sebagai edisi khusus. Mereka ini boleh dikatakan sebagai perintis studi perempuan di Indonesia yang berhasil mematahkan asumsi-asumsi dasar perempuan dalam pembangunan mengenai “kerja”, “partisipasi”, “status”, “peranan” dalam unit analisis keluarga dan rumah tangga.
***
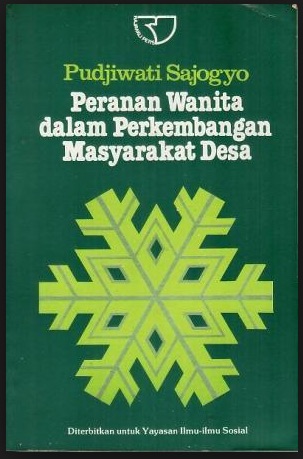 Pada masa pembangunan menjadi hajat pemerintah Orde Baru, perempuan dan laki-laki dimobilisasi untuk berpartisipasi ke dalam pembangunan. Khusus perempuan dimobilisasi untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), melalui program keluarga berencana dan peningkatan gizi dan nutrisi untuk anak. Tetapi terdapat asumsi dalam pembangunan di Indonesia (pandangan arus utama yang direpresentasikan oleh Biro Pusat Statistik/BPS) bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat rendah, terutama dalam hal angkatan kerja. Berangkat dari asumsi dasar pembangunan mengenai partisipasi perempuan yang rendah, Pudjiwati melakukan pelbagai penelitian di pedesaan untuk menguji secara empirik kebenaran asumsi dasar pembangunan tersebut. Maka jika kita pelajari seluruh laporan penelitian Pudjiwati sejak 1978 sampai dengan 1992 (sejauh dokumen yang penulis peroleh) di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, adalah berupaya untuk menguji sejauhmana partisipasi perempuan dalam pembangunan sebagai tenaga kerja.
Pada masa pembangunan menjadi hajat pemerintah Orde Baru, perempuan dan laki-laki dimobilisasi untuk berpartisipasi ke dalam pembangunan. Khusus perempuan dimobilisasi untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), melalui program keluarga berencana dan peningkatan gizi dan nutrisi untuk anak. Tetapi terdapat asumsi dalam pembangunan di Indonesia (pandangan arus utama yang direpresentasikan oleh Biro Pusat Statistik/BPS) bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat rendah, terutama dalam hal angkatan kerja. Berangkat dari asumsi dasar pembangunan mengenai partisipasi perempuan yang rendah, Pudjiwati melakukan pelbagai penelitian di pedesaan untuk menguji secara empirik kebenaran asumsi dasar pembangunan tersebut. Maka jika kita pelajari seluruh laporan penelitian Pudjiwati sejak 1978 sampai dengan 1992 (sejauh dokumen yang penulis peroleh) di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, adalah berupaya untuk menguji sejauhmana partisipasi perempuan dalam pembangunan sebagai tenaga kerja.
Pudjiwati menggunakan konsep “peranan” yang disituasikan ke dalam kegiatan kerja (work) yang mendasarkan pada “pembagian kerja” antara laki dan perempuan dalam keluarga inti. Terdapat dua peranan perempuan pedesaan, pertama, sebagai ibu dan isteri yang melakukan pekerjaan rumah tangga, yaitu pekerjaan reproduksi atau pekerjaan produktif yang tidak secara langsung menghasilkan nafkah, tetapi memungkinkan anggota keluarga lainnya mendapatkan nafkah. Kedua, peranan sebagai pencari nafkah, baik bersifat tambahan maupun utama. Sifat kerja ganda perempuan ini dapat berbeda-beda tergantung pada kekayaan dan pendapatan yang erat hubungannya dengan jangkauan terhadap sumber produksi, terutama tanah.
Dari penelitian-penelitiannya itu Pudjiwati berhasil membongkar asumsi pembangunan yang keliru mengenai (1) definisi kerja perempuan, dan (2) partisipasi dalam pembangunan.
Perlu diketahui bahwa Sensus Penduduk dan BPS mendefinisikan kerja menurut perspektif ekonomi, sehingga apa yang disebut kerja mempunyai implikasi pada pengupahan. Sementara dalam realitasnya, perempuan melakukan kerja ganda, yaitu kerja berupah dan kerja tak berupah (unpaid labour), namun kerja upahan perempuan tampak kabur justru karena tidak merujuk pada satu kategori kerja. Adapun kerja domestik (rumah tangga) seperti mengasuh anak, menyiapkan makanan bagi keluarga, dll, didefinisikan BPS sebagai aktivitas. Secara normatif semua perempuan di pedesaan ketika ditanya tentang kerja, maka akan mengatakan pekerjaan domestiknya ketimbang kerja upahannya. Jawaban ini mengukuhkan penghilangan perempuan dalam kategori BPS tentang kerja.
Tetapi Pudjiwati menilai adanya kekeliruan metode penelitian survey yang dilakukan BPS dalam Sensus Penduduk, sehingga menghilangkan realitas kerja perempuan. Maka, meski tidak menyatakan telah menggunakan metode penelitian survey yang berperspektif feminis, menurut hemat saya, Pudjiwati telah melakukan eksperimen teoritik dan metodologis yang feminis dalam membongkar definisi tentang kerja versi BPS. Secara teoritis, Pudjiwati menggunakan teori Marx mengenai nilai waktu (alokasi waktu) untuk mengukur nilai kerja perempuan (meski tidak disebutkan demikian oleh Pudjiwati). Berdasarkan nilai waktu, curah waktu yang diberikan perempuan untuk kerja domestik maupun kerja upahan telah melebihi curah waktu kerja upahan (perempuan 11 jam dan laki-laki 8 jam untuk realitas di Jawa Barat). Maka tenaga kerja yang telah dialokasikan perempuan untuk keluarga dan pembangunan melebihi yang semestinya dalam konteks partisipasi angkatan kerja.
Selain itu, Pudjiwati menguji nilai kerja perempuan dengan melihat distribusi dan alokasi kuasa antara suami dan isteri berkaitan dengan pembagian kerja dalam keluarga dan rumah tangga serta penghasilan dan pengeluaran (dalam konteks produksi dan konsumsi). Pertanyaannya adalah siapa yang dominan dalam menciptakan norma pembagian kerja dan belanja rumah tangga? Dalam penemuan Pudjiwati, pencipta norma pembagian kerja dan belanja rumah tangga berbeda-beda menurut norma masyarakatnya (bukan pedesaan atau perkotaan), tetapi secara umum laki-laki merupakan pemegang norma, sedangkan perempuan sebagai penentu belanja.
Dengan demikian Pudjiwati telah mengkritik metode survey BPS yang berperspektif nilai pasar (nilai tukar) ketimbang nilai kerja. Pudjiwati telah merekomendasikan perubahan metodologis dalam survey tentang kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan kepada BPS melalui Kementrian Muda Urusan Peranan Wanita (sekarang disebut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Tetapi sampai saat ini, BPS masih bersikukuh menggunakan definisi kerja menurut perspektif pasar, sehingga partisipasi perempuan dalam kerja produktif terlihat rendah. Apabila kerja perempuan dilihat dari nilai kerja maka partisipasi perempuan (termasuk anak perempuan) di pedesaan dalam pembangunan sangat tinggi. Tetapi tingginya partisipasi perempuan dalam pembangunan ini diabaikan oleh BPS, sehingga status dan peranan perempuan seperti tidak berubah (tidak meningkat) dalam pembangunan. Padahal terjadi banyak perubahan sekait dengan status dan peranan perempuan, terutama dalam hal sumbangan kerja upahan dalam era pra-industri menuju industri (perubahan dari pertanian keluarga menuju industrialisasi).
Adapun konsep “integrasi” perempuan ke dalam pembangunan disituasikan ke dalam pengorganisasian orang-orang –baik anggota keluarga maupun anggota sosial— ke dalam kerja kolektif sesuai dengan statusnya (tua, muda, orang tua, anak-anak, ketua marga, dll) dalam mencapai tujuan bersama. Integrasi perempuan ke dalam pembangunan sebenarnya telah menjadi agenda Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Pelita III, dimana pelbagai sektor pembangunan diarahkan untuk kepentingan perempuan pedesaan sebagai prioritas utama. Namun demikian, Pudjiwati menemukan bahwa 40 persen perempuan pedesaan, terutama di Jawa, yang berasal dari rumah tangga miskin dan tidak mempunyai tanah menghadapi masalah gizi dan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Dalam studinya sepanjang 1977-1978 di dua desa di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Pudjiwati menemukan kecenderungan kerja perempuan dari rumah tangga miskin adalah sebagai buruh tani dengan upah rendah tetapi curah waktu tinggi. Adapun kecenderungan kerja perempuan “berada” (dalam arti kekayaan) adalah sektor jasa (berniaga, berjualan) dengan curah waktu rendah. Dengan demikian, integrasi perempuan ke dalam pembangunan di pedesaan, terutama Jawa, sebenarnya belum menjangkau perempuan miskin, sehingga curah waktu kerjanya (nilai waktu) tinggi.
***
Kini pertanyaannya apakah temuan Pudjiwati dalam membongkar asumsi BPS tentang kerja itu dikembangkan sebagai studi perempuan oleh peneliti dan aktivis feminis pada dekade-dekade berikutnya, termasuk pada abad milenium ini? Sependek pengamatan saya, dan ini khas di Indonesia, tidak ada yang melanjutkan pekerjaan Pudjiwati, dalam hal ini mengembangkan temuan-temuannya, termasuk pembongkaran asumsi-asumsi BPS dan pembangunan. Padahal kerja ganda perempuan dan eksploitasi melalui nilai waktu di dalamnya masih berlangsung hingga sekarang dalam transisi agraria menuju urban. Transisi itu menciptakan krisis-krisis dalam ekonomi rumah tangga, dan krisis itu ditanggulangi oleh kerja ganda perempuan.***
—————-
[1] Pada masa Pudjiwati Sajogyo itu menyebut perempuan dengan istilah “wanita” yang umum dipergunakan setelah Indonesia Merdeka. Namun penulis meminta izin untuk menyebut “perempuan” seturut dengan zaman dan pilihan (politik) atas etimologi istilah tersebut. Istilah “wanita” berasal dari bahasa Sanskrit yang diserap oleh Jawa Kuno yang berarti “yang diinginkan” (Zoetmoelder) atau bermakna subordinasi atas sebuah eksisten, sedangkan istilah “perempuan” berasal dari bahasa Melayu yang menunjuk otonomi diri perempuan itu sendiri. Itu sebabnya, gerakan perempuan di Indonesia dekade 1980an dan seterusnya, memilih kembali kepada istilah “perempuan” sebagaimana yang dipergunakan oleh aktivis perempuan pra-kemerdekaan.
[2] Berdasarkan tulisan Pudjiwati Sajogyo “Latar Belakang Perlunya Pendirian Pusat Studi Wanita Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi”, 1991






