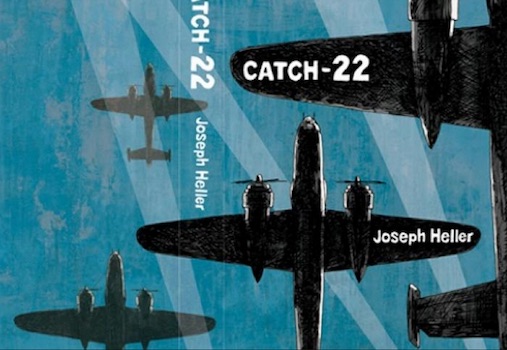CATCH-22 adalah novel satir anti-perang dengan atmosfer cerita yang serupa dengan novel Slaughterhouse-Five karangan Kurt Vonnegut dan film “proto-Tarantino” Cross of Iron besutan Sam Peckinpah. Dalam novel debutan Joseph Heller ini kita menemukan perpaduan antara tawa dan tangis, antara sentimentalitas dan kebiadaban, dalam wujud yang agak ganjil. Catch-22 berkisah tentang kemalangan Yossarian, seorang pilot pesawat pembom pada Perang Dunia II, menyaksikan kawan-kawan satu skuadronnya mati satu per satu walaupun berusaha sekuat tenaga menghindar dari misi-misi militer yang dibebankan ke pundak mereka. Novel ini disebut-sebut sebagai salah satu novel terbaik Amerika Serikat di abad ke-20 (walaupun saya lebih menyukai Slaughterhouse-Five yang prosanya lebih hemat, kental dan halusinatif). Namun kali ini kita tak akan bicara sastra. Kita tidak akan mendekati Catch-22 sebagai karya sastra, melainkan lebih sebagai suatu problem logika.
Ungkapan “catch-22” merujuk pada situasi paradoksal. Pada bab 5 novel dikisahkan perbincangan antara Yossarian dan dokter Daneeka perihal kemungkinan untuk mangkir dari tugas menerbangkan pesawat pembom. Hanya ada satu cara untuk terhindar dari misi militer itu, yakni bahwa yang bersangkutan gila dan mengajukan permohonan ke dokter Daneeka untuk tidak menjalankan misi atas dasar alasan tersebut. Persoalannya, serdadu yang tidak waras tidak pernah meminta izin ke dokter Daneeka. Mereka terus saja menerbangkan pesawat pembom, menjalankan misi, sampai mereka mampus. Sebaliknya, serdadu yang meminta izin ke dokter Danneeka adalah serdadu waras yang berpura-pura gila. Di sini, dengan demikian, kita menemui sebuah dilema. Di satu sisi, permohonan izin untuk terhindar dari misi mengimplikasikan proses pertimbangan rasional dan karenanya juga kewarasan, sehingga serdadu yang meminta izin itu pasti tidak gila. Di sisi lain, serdadu gila—persis karena ia gila—tidak akan berpikir untuk meminta izin dan karenanya terus berperang. Situasi macam inilah yang disebut “catch-22”.
Paradoks “catch-22” dapat dirumuskan secara rapi menggunakan instrumen logika simbolik (untuk mudahnya, cukup sentential logic dalam tata logika analitik). Ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar pilot pembom dibebas-tugaskan:
Syarat 1 : pilot pembom dibebas-tugaskan jika ia gila
Syarat 2 : pilot pembom dibebas-tugaskan jika ia memohon izin dibebas-tugaskan
Kedua syarat tersebut berlaku secara bebarengan. Dengan demikian, apabila kita simbolkan “pilot dibebas-tugaskan” sebagai B, “pilot gila” sebagai G dan “pilot memohon izin dibebas-tugaskan” sebagai I, maka kita dapat merancang persyaratan tersebut dalam bahasa formal berikut:
B ↔ (G ˄ I)
Artinya, “pilot dibebas-tugaskan jika dan hanya jika pilot gila dan ia memohon izin dibebas-tugaskan”. Masalah kemudian muncul dalam konflik di antara kedua syarat tersebut. Apabila kita simbolkan “pilot melakukan pertimbangan rasional” sebagai R, maka implikasi berikut berlaku:
R ↔ ~G
Artinya, “pilot melakukan pertimbangan rasional jika dan hanya jika ia tidak gila”. Implikasi tersebut bertabrakan dengan implikasi berikut ini:
I ↔ R
Artinya, “pilot memohon izin dibebas-tugaskan jika dan hanya jika pilot melakukan pertimbangan rasional”. Di sini masalahnya mengemuka secara utuh:
I ↔ ~G
“Artinya, “pilot memohon izin dibebas-tugaskan jika dan hanya jika ia tidak gila”. Kita dapat meringkas keseluruhan argumen di muka sebagai berikut:
Premis 1: B ↔ (G ˄ I)
Premis 2: R ↔ ~G
Premis 3: I ↔ R
Premis 4: I ↔ ~G
Kesimpulannya, tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik sebab Premis 1 bertentangan dengan Premis 4. Ada kontradiksi antara Syarat 1 dan Syarat 2 dibebas-tugaskannya sang pilot. Kontradiksi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
B ↔ ~B
Artinya, “pilot dibebas-tugaskan jika dan hanya jika pilot tidak dibebas-tugaskan”. Inilah paradoks yang dialami Yossarian ketika ia hendak meminta izin untuk dibebas-tugaskan pada dokter Daneeka. Inilah “catch-22”.
Di sini, sebelum berusaha memecahkan paradoks Yossarian, kita akan memutar agak jauh untuk mempersoalkan konsep kontradiksi itu sendiri. Apa itu kontradiksi? Kita berjumpa dengan kontradiksi manakala kita menemui suatu pernyataan yang disamakan dengan negasinya. “Kucing adalah bukan kucing,” misalnya. Namun kadang kontradiksi juga tersamar; ia bisa menyaru di balik syarat pengertian dari salah satu term. Paradoks Yossarian adalah contoh kontradiksi yang tersamar (dalam konflik antara dua komponen definisi dari suatu hal yang sama). Contoh-contoh lainnya:
- “Tuhan Yang Maha Tahu dapat menciptakan sebuah problem logika paling rumit yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh-Nya” (paradoks Maha Kuasa)
- “Tidak ada pernyataan yang benar” (variasi dari paradoks Penipu)
- “Saat ini hujan, tapi saya tidak percaya itu” (paradoks Moore)
- “Sebuah kapal dapat dirakit-ulang per bagian dengan komponen baru dan tetap menjadi kapal yang sama. Tetapi seluruh bagian sisa peninggalan kapal itu juga dapat dirakit menjadi sebuah kapal yang sama dengan kapal pertama.” (paradoks Kapal Theseus)
Dan masih banyak lagi. Kontradiksi yang terdapat dalam rangkaian kalimat itu dalam arti tertentu dapat dianggap benar. Situasi inilah yang disebut paradoks. Namun sungguhkah ada kontradiksi yang “benar”?
Seluruh aparatus logika Klasik—sistem logika Aristoteles yang dirapikan melalui aljabar Boolean—bertopang pada Hukum Non-Kontradiksi, yakni anggapan bahwa setiap proposisi tidak mungkin benar sekaligus salah. Asas dasar inilah yang belakangan ditantang oleh para logikawan kontemporer. Graham Priest, seorang profesor logika dialetheis sekaligus karatekawan Dan 4 serta praktisi Taichi, memandang bahwa wilayah kerja sistem logika Klasik itu sempit dalam arti berlaku untuk kasus tertentu saja. Sementara, untuk kasus-kasus lain, Hukum Non-Kontradiksi bisa saja tidak berlaku. Dalam salah satu artikelnya dalam buku The Law of Non-Contradiction (Oxford 2004), Priest memvisualisasikan dua semesta logis yang berbeda cakupannya.
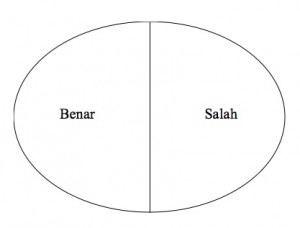
Inilah alam semesta logika Klasik. Setiap proposisi dalam semesta itu digolongkan ke dalam dua kategori besar: benar atau salah. Dalam semesta inilah fungsi kebenaran dari setiap operator logika dan masing-masing proposisi diperiksa dan diklasifikasi seturut dua nilai kebenaran: 1 dan 0. Hukum-hukum silogisme Aristoteles, tabel kebenaran Boolean dan segala tetek-bengek ilmu logika yang dipelajari mahasiswa S1 dalam mata kuliah Logika atau Critical Thinking mendekam dalam semesta jenis ini. Problemnya, menurut Priest, peta semesta logika Klasik ini hanya menggambarkan sebuah provinsi dari alam semesta logika yang lebih besar. Inilah semesta besar itu:

Semesta logika Non-Klasik ini sungguh raksasa. Di dalamnya hiduplah berbagai empat spesies proposisi:
- Himpunan proposisi yang benar
- Himpunan proposisi yang salah
- Himpunan proposisi yang tidak benar dan tidak salah
- Himpunan proposisi yang benar sekaligus salah
Dua himpunan pertama bisa kita cerap dengan mudah. Himpunan proposisi yang benar misalnya proposisi “1 + 1 = 2”, “Jika A = B, dan B = C, maka A = C”, dsb. Himpunan proposisi yang salah misalnya proposisi “1 + 1 = 24”, “Setiap manusia adalah anjing”, dsb. Lalu bagaimana dengan himpunan proposisi yang tidak benar dan tidak salah? Himpunan itu dihuni oleh, misalnya, proposisi tentang masa depan yang belum bisa ditentukan benar/salahnya (“Tahun depan Roberto Bolaño akan bangkit dari kubur dan menerbitan buku-buku filsafat yang banyak salah ketiknya”), kalimat-kalimat non-proposisional (seperti kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru, dsb.) atau proposisi lain yang tidak bisa dibilang benar dan tidak bisa dibilang salah.
Kebaruan yang ditawarkan logika dialetheis Priest terletak pada himpunan proposisi keempat. Logika dialetheis adalah logika yang memberi ruang pada proposisi yang benar sekaligus salah. Contohnya adalah proposisi seperti:
- “Saya berada di dalam sekaligus di luar ruangan”
- “César Aira sedang duduk sekaligus berdiri”
Proposisi semacam itu, menurut Priest, merupakan contoh kontradiksi yang benar. Proposisi pertama, walupun terstruktur secara kontradiktif, bisa dibenarkan untuk kasus di mana kita sedang berdiri di ambang pintu, yakni di titik yang berada di luar sekaligus di dalam ruangan. Demikian pula dengan proposisi kedua, yakni pada momen ketika Aira tengah beranjak dari kursinya. Kasus-kasus itu, serta kasus-kasus lain yang dikelompokkan oleh para filsuf dalam kategori ‘kekaburan’ (vagueness), dapat dipandang sebagai ilustrasi paling mencolok dari keberadaan kontradiksi yang benar, atau dengan kata lain keberadaan proposisi yang salah sekaligus benar. Di pintu gerbang menuju wilayah ini, terpacak pengumuman: “Hukum Non-Kontradiksi tidak berlaku”.
Apa yang dibuat oleh Priest tidak membatalkan seluruh aparatus logika Klasik, melainkan menetapkan batas pada rentang keberlakuannya. Ini mirip seperti yang dibuat Einstein terhadap fisika Newton, yakni dengan menunjukkan bahwa fisika Newtonian berlaku untuk gejala fisik yang melibatkan benda-benda bermassa kecil sementara relativitas berlaku untuk wilayah fisik Newtonian sekaligus wilayah yang lebih besar yang melibatkan benda-benda bermassa fantastis. Seperti halnya fisika Newtonian dijadikan salah satu provinsi dari fisika Einsteinian, demikian pula halnya semesta logika Klasik dijadikan salah satu bagian kecil dari semesta logika Non-Klasik. Yang satu tidak membatalkan yang lain; yang satu mencakup yang lain.
Kendati menolak kemutlakan Hukum Non-Kontradiksi, Priest bukannya terjebak pada mistisisme murahan dan tetek-bengek retorika ketimurannya. Ia membangun suatu sistem logika formal yang sama ketatnya dengan sistem logika Klasik. Kita tentu tak akan membicarakan rincian formalnya di sini. Perlu juga diingat bahwa Priest tidak membenarkan semua jenis kontradiksi. Tetap ada kontradiksi yang keliru secara logis. Ia sendiri belum merumuskan kriteria kunci untuk memilah kontradiksi yang benar dari yang keliru. Namun, sebagai pembelajar Marxisme, kita dapat menimba pelajaran banyak dari pendekatan logika dialetheisnya.
Ciri dari sistem logika dialetheis adalah kemampuannya menangkap gerak sebagai gerak, perubahan sebagai perubahan, tanpa membuatnya menjadi statis seperti halnya sistem logika Klasik. Contoh kasus vagueness di atas menggambarkan kenyataan ini. Paradoks Timbunan (sorites paradox atau paradox of the heap) yang menggambarkan peralihan dari timbunan pasir ke sebutir pasir melalui pengurangan sebutir demi sebutir merupakan contoh lain dari kasus vagueness yang bisa dipecahkan oleh logika dialetheis. Paradoks semacam ini menandai berbagai aspek pemikiran tentang perubahan. Secara filosofis, Marxisme adalah sebuah konsepsi tentang kenyataan yang dicirikan secara esensial oleh perubahan. Marx bicara, misalnya, tentang komoditas sebagai benda sekaligus relasi sosial, tentang nilai sebagai penubuhan kerja, atau tentang kapitalisme yang ditopang oleh semangat akumulasi sekaligus potensi swa-destruksi melalui kelas proletar. Logika Klasik akan mengesampingkan hal-hal ini sebagai metafisika (seperti yang lazim dilakukan oleh para Marxis Analitik dengan mengganti sosiologi dan ekonomi Marxian menjadi sosiologi dan ekonomi borjuis biasa dengan tambahan simpati moral pada kelas pekerja). Logika dialetheis, sebaliknya, justru mampu memberikan justifikasi logis yang koheren dan sistematis bagi aspek-aspek dinamis-dialektis pemikiran Marx itu.
Cukup soal Marx, kini kita akan kembali ke novel Heller. Apa solusi dialetheis untuk “catch-22”? Kita bisa mulai dengan mempersoalkan rentang pengertian dari ungkapan seperti “rasionalitas” dan “kegilaan”. Apakah keduanya sungguh-sungguh asing satu sama lain? Tidakkah, seperti kata sang Dramawan, “Though this be madness, yet there is method in ’t”? Apa yang mau saya katakan adalah, jangan-jangan, terdapat gradasi antara “rasionalitas” dan “kegilaan” seperti halnya tumpukan pasir dalam sorites paradox atau “ambang pintu” dalam proposisi dialetheis: suatu titik di mana rasionalitas dan kegilaan ada bersama-sama. Kita dapat mengartikan-ulang R (“melakukan pertimbangan rasional”) demikian rupa sehingga tidak eksklusif hanya dimiliki orang waras dan dengan begitu menghapuskan kontradiksi antara Syarat 1 dan Syarat 2. Artinya, proposisi…
G ˄ R
…bersifat kontradiktif tetapi benar, sehingga proposisi…
I ↔ R
…tidak bertabrakan dengan proposisi sebelumnya dan, dengan demikian, proposisi…
B ↔ (G ˄ I)
…menjadi dapat dibenarkan. Melalui uraian ini, nampak bahwa “catch-22” merupakan salah satu kasus dari kontradiksi dialetheis. Oleh karenanya, paradoks Yossarian dapat dipecahkan. Ia bisa saja gila dan memohon izin untuk dibebas-tugaskan. Kendati, mesti diakui, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menyia-nyiakan kenikmatan membaca sastra.***
5 Mei 2016