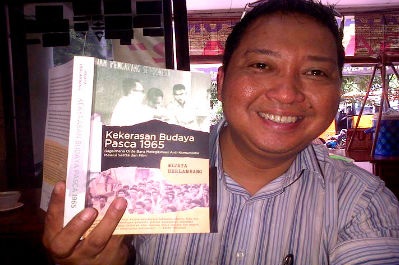SAYA akan mengenang Wijaya Herlambang tanpa melankoli. Sebab ia meninggalkan pada kita setumpuk tugas yang masih belum usai, tugas-tugas yang masih perlu dikerjakan. Oleh karena itu, saya tak akan membuang waktu dengan pertunjukan kesedihan dan parade air mata, melainkan dengan memikirkan tugas-tugas itu. Karya besarnya, Kekerasan Budaya Pasca 1965, telah membukakan ruang penyelidikan yang begitu luas. Melalui tulisan ini, saya akan mengenang Wijaya Herlambang sebagai buku-buku yang akan datang, sebagai kitab-kitab yang belum dituliskan, sebagai sehimpun pekerjaan yang masih harus disudahkan, yang menyusun sebagian jalan menuju sosialisme Indonesia.
Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 memperlihatkan dengan benderang operasi-operasi politik dan ekonomi macam apa yang bermain di balik pengarus-utamaan kultur antikomunis sesudah 1965. Wijaya menyuguhkan pada kita bukti-bukti tertulis dari apa yang selama ini cuma jadi pergunjingan di antara kita, yakni bagaimana persisnya para budayawan PSI dan kaum konservatif bahu-membahu menumpas PKI di lapangan ideologi dan membangun suatu ‘sensibilitas kebudayaan’ baru, suatu ‘pandangan-dunia kultural’ baru yang punya andil dalam mengukuhkan Orde Baru. Lebih dari itu, Wijaya mengajarkan pada kita cara untuk melacak bukti-bukti tersebut sekaligus cara membacanya, menarik kesimpulan kritis darinya. Dengan begitu, Wijaya mengajarkan kita cara untuk menjadi semacam ‘detektif kebudayaan’: membongkar arsip, menelusuri jejaring keaktoran, merekonstruksi argumen estetik dan politik serta mengenali implikasinya dalam kehidupan nyata.
Sumbangsih Wijaya ini penting terutama karena temuan-temuannya tentang politik kebudayaan pasca 1965 juga dapat dipakai untuk menjelaskan panggung politik kebudayaan kita hari ini. Analisisnya atas ideologi ‘humanisme universal’, politik kebudayaan kaum ‘liberal’ dan perkembangannya hingga era Reformasi jelas membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kebudayaan kita hari-hari ini. Dengan kata lain, Wijaya Herlambang menjelaskan pada kita tentang asal-usul ‘hari ini’. Buat saya sendiri, inilah sumbangan terpenting yang ia berikan dalam usianya yang terlalu singkat itu. Melalui capaian itulah juga ia sebetulnya membuka ruang penyelidikan lebih lanjut yang belum tergarap. Dalam kenangan atas sosoknya, saya akan mencoba merinci topik-topik kajian apa saja yang dimungkinkan melalui karyanya tetapi belum atau kurang diolah sejauh ini:
- Akar kolonial dari ideologi ‘humanisme universal’: cita-cita Pencerahan, teosofi Blavatsky, tradisi mistik Islam dan kejawen, dst?
- Kait-kelindan antara konsepsi tentang ‘humanisme’, ‘liberalisme’ dan tradisi lirik dalam kesusastraan dan seni rupa kita: apa kaitan antara kemunculan genre puisi lirik dalam puisi modern kita dan konsolidasi kapitalisme di Hindia Belanda, perkembangan serta dominasi puisi lirik dan apa kaitannya dengan lirisisme abstrak dalam sejarah seni rupa kita, dst?
- Hubungan antara konsolidasi kebudayaan Orde Baru dan menguatnya eksplorasi bentuk dalam puisi dan seni rupa pada dekade 1970-an: adakah keterkaitan antara menguatnya dominasi seni lukis abstrak dan latar ekonomi-politik Orde Baru, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan sufisme dalam praktik kesenian sejak 1970-an, lalu dengan ‘teologi negatif’ yang marak sesudah diterimanya pascamodernisme di era 1990-an: apakah kecenderungan ke arah estetika sufistik (Abdul Hadi WM dan Ahmad Sadali, misalnya) punya akarnya pada pandangan tentang kodrat universal manusia sebagai makhluk moral dan makhluk spiritual, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan euforia penerimaan atas pascamodernisme serta maraknya ‘industri kerukunan antar umat beragama’: sejauh mana gagasan pokok soal kemanusiaan yang menolak politik kelas bersinergi dengan relativisme pascamodern dan maraknya advokasi (maraknya funding) berkaitan dengan multikulturalisme, lalu kemudian pluralisme, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’, politik kebudayaan sosialis-kanan (PSI) dan perkembangan berbagai LSM serta gerakan civil society yang kritis terhadap Orde Baru sejak dekade 1980-an: bagaimana menjelaskan pergeseran perimbangan politik antara kubu sosialis-kanan dan Orde Baru dan dampaknya bagi pembentukan gerakan masyarakat sipil, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan pengarus-utamaan Marxisme ‘gaya Frankfurt’ alias ‘Dilema Usaha Manusia Rasional’ dan segala variasinya: bagaimana para pemikir Katolik mendukung dan mengelaborasi visi ‘humanisme universal’ kemudian menggulirkan sejenis ‘Marxisme humanis’ yang lebih bercorak moralis ketimbang politis, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan kelompok-kelompok studi yang menjadi cikal-bakal PRD (dengan kata lain, gerakan Kiri pasca-1965): sejauh mana Marxisme yang dipelajari dalam berbagai study club era 1980-an telah disaring dan disunting menjadi semacam filsafat etika melalui interaksi dengan elemen-elemen sosialis-kanan dan Katolik dalam gerakan masyarakat sipil (dan karenanya kebencian yang nyaris irasional terhadap Stalin dan karenanya juga kecintaan berlebih terhadap Trotsky–dalam kontras dengan sikap gerakan Kiri pra-1965 terhadap kedua sosok itu), dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan kelompok-kelompok anarkis menjelang dan sesudah 1998: sejauh mana sensibilitas kultural sosialis-kanan (mentalitas antikomunis, antibirokrasi, antinegara) berpengaruh bagi formasi pemikiran anarkisme di Indonesia, dari jejaring dan sumber dana manakah penerbitan terkait anarkisme berasal, dst?
- Hubungan antara ‘humanisme universal’ dan atmosfir kultural dari berbagai kelompok muda-mudi hipster perkotaan: bagaimana menjelaskan keterkaitan antara maraknya sensibilitas liris (atau pandangan-dunia liris) dalam syair-syair lagu band indie di tanah air, dst?
Daftar topik kajian ini masih bisa diperpanjang lagi. Sepuluh topik yang saya sebutkan hanyalah ilustrasi dari keluasan bidang yang mungkin kita kaji bersama berkat penelusuran awal dari Wijaya Herlambang. Oleh karenanya, paling tidak buat saya, mengenang Wijaya adalah mengingat sederet pertanyaan yang melayang-layang di udara dan tumpukan buku yang belum pernah dituliskan.
Selain tentang karyanya, saya juga ingin berbicara tentang sosoknya dalam dunia pergerakan. Wijaya adalah seorang sarjana, scholar, yang juga berani mengambil posisi dan menyatakan keberpihakannya dalam pergulatan gerakan rakyat di Indonesia. Namun yang membuatnya berbeda dari aktivis Kiri biasanya adalah bahwa ia merupakan bagian dari kalangan yang mengambil posisi politik Kiri tanpa tergabung dalam partai-partai Kiri yang ada. Wijaya, dalam arti itu, adalah representasi dari generasi pemikir Kiri masa kini. Ia adalah yang paling senior dari generasi kami—saya dan beberapa kawan muda di IndoPROGRESS dan berbagai kolektif lain—yang mendukung sepenuhnya politik Kiri tanpa pernah tercatat sebagai anggota penuh di salah satu partai Kiri. Dalam perhitungan angkatan kuliah, ia tentu jauh di atas saya: ia masuk kuliah tahun 1993, sementara saya baru tahun 2005. Namun ketakterlibatannya dalam partai Kiri dan keaktifannya dalam percaturan pemikiran Kiri yang baru sejak akhir dekade 2000-an mendekatkannya dengan pengalaman angkatan kami. Kami tidak pernah mengalami split, konflik berlarut-larut dan pusaran permusuhan personal yang mencirikan medan kepartaian Kiri pasca-Reformasi. Kami adalah generasi pasca-perpecahan PRD yang tumbuh matang dalam sebuah situasi yang menyulitkan kami bergabung ke salah satu partai Kiri yang ada (sebab akan terpaksa memusuhi yang lain). Belle Époque kami—Zaman Ideal yang selalu kami kenang tanpa pernah kami alami secara langsung—adalah era pergerakan 1990-an, yakni ketika semua kekuatan Kiri tergabung dalam sebuah partai besar (atau ‘agak besar’) dan berjuang bersama dalam pertarungan hidup-mati melawan Orde Baru. Mungkin saya agak romantik di sini, tapi begitulah gambarannya, setidaknya menurut saya. Era 2000-an, hari ini, adalah era perpecahan yang memusingkan buat generasi kami. Begitulah, sebagian dari generasi kami kemudian memilih menjadi ronin, pendekar tak bertuan, yang siap memasang badan bergelut dengan sarjana-sarjana soska, budayawan-budayawan bermental abon dan babinsa-babinsa kelas menengah—membantu sebisa mungkin gerakan Kiri (menyuplai bahan pendidikan, memenangkan perang ideologi, sesuai bidang keahlian kami) tanpa bergabung ke dalam partai secara formal. Sekali lagi, ini cuma kesan saya; mungkin saya keliru.
Walaupun saya berbicara tentang ‘generasi kami’, ungkapan itu tidak dimaksudkan untuk mengacu pada keidentikan pandangan. Sudah tentu ada beberapa perbedaan, khususnya pada aras taktik gerakan. Saya dan Wijaya berbeda pandangan sewaktu musim kampanye 2014. Saya memilih untuk menjadi relawan Jokowi, sementara ia (dan sebagian gerakan Kiri) menolak untuk memberikan dukungan pada Jokowi ataupun Prabowo. Pertimbangan yang ia berikan adalah bahwa baik Jokowi maupun Prabowo tak punya landasan ideologis yang bisa diidentifikasi sebagai Marxis, dengan kata lain bahwa keduanya sama saja dari perspektif Marxis. Menurutnya, Jokowi tak punya basis massa dengan kekuatan kelas yang jelas dan dukungan terhadapnya hanya akan menguntungkan soska macam GM yang juga mendukung Jokowi.
Sementara pandangan saya berbeda. Pertanyaan kuncinya bukan ‘apa’, tapi ‘bagaimana’. Bukan apa bentuk perjuangan paling ideal yang sesuai dengan pakem Marxisme, melainkan bagaimana perjuangan yang paling efektif dan feasible yang dapat ditempuh dalam kondisi riil yang ada demi perwujudan pokok-pokok Marxisme. Bukan apakah rezim Jokowi dapat mewujudkan cita-cita sosialisme (sudah tentu tidak), tetapi bagaimana caranya untuk mengusahakan supaya melalui rezim itu agenda-agenda politik sosialis bisa memperoleh ruang dan berkembang. Bukan apakah kondisi yang ada sekarang emansipatoris atau tidak (sudah tentu tidak), tetapi bagaimana mengusahakan agar kondisi tersebut menjadi emansipatoris. Bukan apakah saya akan satu kapal dengan kaum soska, tetapi bagaimana supaya agenda Kiri menang melawan agenda soska di tingkat pemerintahan.
Bukan apa, tapi bagaimana—itulah pertanyaan revolusioner zaman kita.
Terhadap posisi Wijaya pun saya tak merasa berlawanan secara total. Saya tidak merasa bermusuhan dengan Wijaya atau kawan-kawan di gerakan yang memilih memperkuat gerakan rakyat dan menolak intervensi elektoral. Pengorganisasian kekuatan politik rakyat tetaplah hal yang sentral dan intervensi elektoral hanyalah salah satu sarana untuk membantu gerakan itu. Untuk mudahnya, saya akan menggunakan sistem klasifikasi yang mudah dipahami guna menerangkan perbedaan ini. Katakanlah ada tiga jenis Kiri:
- Kiri ‘NU’: kaum Kiri yang percaya bahwa otoritas tekstual Marxisme mesti didialogkan dengan konteks spesifik dan Marxisme hanya bisa diwujudkan dengan cara dilahirkan kembali dari nation yang konkrit secara sosio-historis.
- Kiri ‘Muhammadiyah’: kaum Kiri yang percaya bahwa otoritas tekstual Marxisme punya prioritas yang lebih tinggi ketimbang penyesuaian dengan konteks.
- Kiri ‘Wahabi’: kaum Kiri yang percaya bahwa hanya otoritas tekstual Marxisme yang sahih, segala sesuatunya mesti dibuat sesuai dengan citra ideal tentang Soviet sembari menyalah-nyalahkan kenyataan yang ada.
Perbedaan antara saya dan Wijaya (tetapi saya pikir juga perbedaan antara PKI dan partai-partai Kiri sekarang) cuma perbedaan antara Kiri ‘NU’ dan Kiri ‘Muhammadiyah’. Saya cenderung termasuk dalam golongan Kiri ‘NU’ dan Wijaya dalam golongan Kiri ‘Muhammadiyah. PKI dulu juga cenderung akulturatif terhadap konteks politik yang ada (makanya ada tradisi ‘naskir’ alias nasionalis-Kiri seperti Njoto), berbeda dari partai-partai Kiri kekinian. Namun, pada akhirnya, di antara kedua golongan itu hanya terdapat perbedaan penekanan saja. Kasusnya berbeda bila dibandingkan dengan Kiri ‘Wahabi’ seperti Ted Simpleton dan sekelompok kecil yang cenderung saya sebut sebagai ‘Kiri-Kiri kontra-produktif’.
Demikianlah kenangan saya akan Wijaya Herlambang. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya tengah menulis buku tentang politik kebudayaan antikomunis kontemporer atau tentang evolusi tradisi liris dalam kesusastraan Indonesia, saya akan teringat Wijaya—petualangan kami bersama menggempur budayawan bermental abon dan buku-buku yang belum pernah dituliskan.***