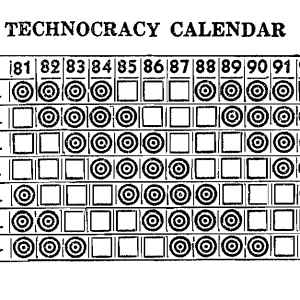MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) ke 33 yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, semestinya menjadi momen penting bagi perdamaian. Selayaknya, jika memang ingin mencatatkan sejarah, ajang pertemuan para nahdliyin ini digunakan untuk membahas permasalahan bangsa. Mulai dari isu sektarian yang makin mengkhawatirkan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas pendidikan melalui pondok pesantren dan isu tentang rekonsiliasi 65.
Isu terakhir barangkali salah satu yang paling tidak populer di antara isu-isu yang lain. Apalagi setelah NU mengeluarkan buku Benturan NU-PKI sebagai jawaban atas wacana rekonsiliasi kepada korban pembunuhan 1965. Wakil Ketua Umum PBNU, As’ad Said Aly,mengatakan, pembuatan buku dilakukan karena ada desakan agar NU meminta maaf kepada korban pembunuhan 1965. Alasannya menarik, menurut As’ad, “Ada yang mendiskreditkan NU dan mendelegitimasikan NU.” Gerakan neoliberal, ujar As’ad lagi, sebagai biang keladi untuk mendiskreditkan NU. “Ada liberalisasi agama, ingin kebebasan agama a la barat. Agar penghujatan atas Tuhan itu boleh dan hujatan atas agama itu boleh,” katanya.
Sebagai salah satu organ dengan masa sangat besar, NU pun masih memiliki ketakutan terhadap ideologi. Gerakan neoliberal yang dimaksud ini juga semestinya bisa ditelisik lebih jauh, dijabarkan dan dipertanyakan sosoknya. Ketua tim penulisan buku putih Abdul Mun’im DZ mengatakan, buku Benturan NU-PKI memaparkan tragedi 1965 dari sudut pandang NU dalam menghadapi PKI sebagai kelompok “bughot” (subversif). Jika demikian maka semestinya ada usaha untuk membuka kembali dokumen sejarah terkait relasi NU dan mereka yang tertuduh PKI.
Memang sejauh ini masih ada silang sengketa tentang keterlibatan NU sebagai organ dalam pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Asvi Warman Adam, peneliti sejarah politik LIPI mengatakan, akar permasalahan gerakan NU-PKI harus dirunut dari tahun 1948 dan 1965. Asvi beranggapan, benturan NU-PKI yang pertama dimulai sebelum tahun 65, ketika aksi sepihak PKI/Barisan Tani Indonesia (BTI). “Ada UU yang mengatur tentang pembatasan tanah warga, land reform. Itu mengatur tanah yang bisa dikuasai warga saat itu, pelaksanaan UU ini didukung oleh PKI dan BTI,” katanya.
Sejauh ini Nahdlatul Ulama masih menjadi salah satu lembaga yang konsisten membela kemanusiaan dan akal sehat. Ketika kelompok lain gemar mengkafirkan dan menyesatkan, NU masih menjadi organ yang kerap melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas. Bahkan banyak intelektual muda mereka yang menjadi pembela kelompok Syiah, Ahmadiyah dan kristen. Namun masih sedikit yang bersuara tentang korban 65.
Salah satu tugas besar intelektual NU, saya kira, adalah untuk meluruskan persepsi tentang komunisme yang sinonim dengan ateisme. Karena selama komunis dianggap sinonim dengan ateis maka pembenaran terhadap pembantaian kelompok PKI pada 65 akan tetap dilakukan. Sejauh ini beberapa kelompok masyarakat masih berpikir bahwa pembantaian 65 merupakan bagian dari penegakan aqidah yang membantai kaum murtad.
Isu 65 memang masih sangat sensitif. Tidak terhitung penulis, intelektual dan kelompok masyarakat yang disakiti dan diserang tanpa ada pembelaan. Beberapa waktu lalu, acara arisan keluarga dan anak-anak eks tahanan politik (tapol) 65 yang dilangsungkan di Yogyakarta, dibubarkan kelompok tertentu. Pembubaran tersebut sempat diwarnai dengan aksi pemukulan terhadap salah satu peserta arisan dan hingga saat ini tidak ada tindakan dari pihak kepolisian.
Kelompok yang membawa label agama juga kerap melakukan penyerangan terhadap kelompok minoritas, termasuk keluarga korban 65. Nahdlatul Ulama sejauh ini masih menjadi kelompok yang cukup netral, malah pada satu titik, menjadi teladan dengan melakukan pendekatan personal terhadap keluarga yang diberi label PKI.
Beberapa kawan saya berkelakar, jika kamu ingin melakukan tindakan kriminal, seperti membunuh, merampok, atau memperkosa tuduh saja korban kamu sebagai syiah, ahmadiyah atau komunis niscaya kamu akan selamat dari jeratan hukum. Saya menolak percaya hal ini, namun melihat bagaimana negara berpihak, saya pesimis bahwa memang negara ini ada untuk membela warga negaranya.
Gus Dur pada 14 Mei 2000 dalam acara Secangkir Kopi, TVRI mengatakan bahwa pengertian rekonsilasi yang benar adalah mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Di sinilah letak keadilan yang harus ditegakkan di Bumi Nusantara. Belum tentu orang-orang yang dituduh komunis bersalah sehingga akhirnya dihukum mati. Sikap ini adalah sebuah terobosan penting dalam usaha menegakkan suara jernih dalam kebisingan sejarah.
Namun, sayang, inisiatif Gus Dur untuk melakukan rekonsiliasi kerap ditentang dan dianggap angin lalu. Bahkan permintaan maafnya tidak ada yang mau mengakui, apakah permintaan maaf itu diberikan atas nama presiden atau atas nama NU. Kini setelah Gus Dur mangkat, hampir tak ada suara dari tubuh NU untuk kembali membahas usaha rekonsiliasi ini. Apapun itu, semoga muktamar kali ini berjalan lancar. Dan siapapun kelak yang memimpin NU semoga bisa membawa kebaikan.***