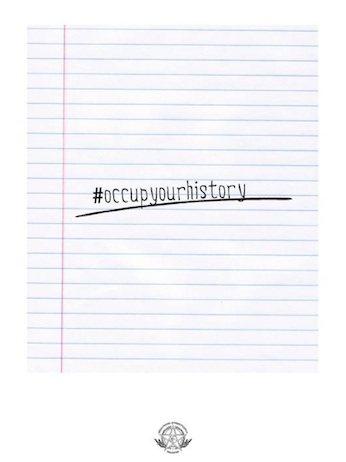1932. BUNG Karno menulis di Harian Ra’jat, ‘….kita bukan saja harus menentang kapitalisme asing, tetapi harus juga menentang kapitalisme bangsa sendiri.’ Bagi Bung Karno, kapitalisme harus ditentang karena ‘…menyebabkan kapitaalaccumulatie, kapitaal-concentratie, kapitaalcentralisatie, dan industrieel reserve armee. Kapitalisme mempunyai arah kepada verelendung, yakni menyebarkan kesengsaraan.’
Saat itu kita masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda, yang menurut Bung Karno, ‘…menjalankan kapitalisme dan yang dijalani kapitalisme, adalah berlainan darah, berlainan kulit, berlainan natie , berlainan kebangsaan.’ Konsekuensinya, ‘Antithese di dalam negeri jajahan adalah, oleh karenanya, terutama sekali bersifat antithese nasional.’
Dalam konteks sebagai bangsa terjajah, maka bagi Bung Karno titik berat perjuangan bukan pertama-tama melawan kapitalisme sebagai sebuah stelsel atau sistem yang eksploitatif, tapi mendahulukan perjuangan pembebasan nasional dari tindasan kolonial Belanda. Bukan perjuangan melawan kelas kapitalis keseluruhan yang menjadi prioritas, tetapi perjuangan melawan kapitalis asing. ‘Pusarnya kita punya perjuangan sekarang haruslah didalam memerangi imperialisme asing itu dengan segala tenaga kita nasional, dengan segala tenaga-kebangsaan, yang hidup di dalam sesuatu bangsa yang tak merdeka dan yang ingin merdeka!’ Kerjasama kelas (antara buruh dan kapitalis domestik, marhanen dan non-marhaen domestik), dengan demikian, adalah sebuah kemutlakan dalam situasi saat itu.
Agustus 1945. Indonesia merdeka. Kolonialis Belanda yang berlainan darah, kulit dan bangsa sudah tergusur. Revolusi pembebasan nasional, yang bisa kita sebut juga sebagai revolusi politik, sudah terjadi. Yang tinggal adalah stelsel kapitalisme yang kekuasaannya semakin kuat dan hegemonik. Tidak ada kekuatan lain, baik secara ekonomi, sosial dan budaya, yang sanggup menandingi kedigdayaan kapitalisme. Ketika sebagian kalangan berbicara tentang ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah, sesungguhnya itu hanya varian lain dari kapitalisme. Di India, kalangan Hindu fanatik gencar mempromosikan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Hinduisme, yang sebenarnya juga hanyalah wajah lain dari kapitalisme. Secara sosial-kultural, hubungan buruh-majikan adalah hubungan sosial yang paling dominan ketimbang hubungan-hubungan sosial lain, seperti hubungan budak-tuan budak atau hamba-tuan hamba.
Setelah 1945, apakah kapitalisme yang semakin kuat ini dijalankan hanya oleh kapitalis bangsa sendiri? Tentu saja tidak! Karenanya keliru jika kita mengikuti mentah-mentah petuah Bung Karno, bahwa setelah merdeka dari kekuasaan kapitalis asing kini saatnya kita memusatkan diri melawan kapitalis bangsa sendiri. Kapitalisme senantiasa ditandai oleh kerjasama dan kompetisi. Karena itu, memang benar terdapat fraksi-fraksi di dalam kelas kapitalis: misalnya fraksi kapitalis asing dan kapitalis domestik; atau fraksi kapitalis dagang dan fraksi kapitalis industri; atau fraksi kapitalis monopoli-keuangan dan fraksi kapitalis non-monopoli. Tetapi pada dasarnya mereka tidak berada dalam ruang dan hubungan yang terisolasi satu sama lain. Tidak ada kapitalis domestik yang bisa eksis hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya tidak ada borjuis nasional yang bersifat progresif, yang sepenuhnya istiqomah membangun ekonomi nasional demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Tujuan utama seluruh kapitalis adalah mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa terinterupsi. Sebaliknya, kapitalis internasional tidak mungkin bisa sukses dalam mengembangkan bisnis di luar teritorialnya tanpa bekerjasama dengan kapitalis domestik.
Di sisi lain koin yang sama, spirit utama penggerak kemajuan kapitalisme adalah kompetisi. Di bidang produksi, kompetisi antara buruh vs kapitalis, sementara di bidang pemasaran kompetisinya antara sesama kapitalis untuk memenangkan penguasaan pasar. Di titik ini, demi memenangkan kompetisi tersebut, para kapitalis menggunakan segala cara untuk mengalahkan lawan-lawannya. Jika persuasi lebih menguntungkan, maka dipilihlah cara ini. Kalau rasisme yang efektif untuk mengalahkan lawannya, maka digunakanlah isu rasisme. Kalau agama lebih efektif sebagai cara memenangkan persaingan, maka digunakanlah isu agama. Kalau nasionalisme terbukti lebih mujarab, maka digunakanlah slogan-slogan nasionalistik yang membakar itu sebagai senjatanya. Jika kekerasan militer adalah cara mudah dan murah untuk membungkam lawan, maka digunakanlah cara ini. Jika iklan yang bohong sekalipun lebih efektif, maka media inilah yang dipakai. Dalam banyak kasus, isu-isu ini seringkali digunakan secara berbarengan untuk mengalahkan kompetitornya.
Dengan keniscayaan kerjasama dan kompetisi dalam kapitalisme, maka yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah momen-momen sejarah (waktu, tempat, kekuatan dan hubungan produksi yang sedang eksis) dimana kerjasama dan kompetisi itu berlangsung. Maka ketika kita mendengar orang-orang berbicara tentang ‘Awas bahaya Asing dan Aseng’ maka kita mesti harus segera bertanya dan menyelidiki: kepentingan ekonomi-politik apa di balik penyebaran isu-isu ini? Siapa yang diuntungkan darinya? Demikian juga ketika kita mendengar tuntutan untuk pelaksanaan bisnis perbankan syariah, asuransi syariah dan segala jenis label syariah, pertanyaan serupa harus kita segera ajukan. Tujuannya agar kita tidak terpedaya dengan hal-hal yang hanya tampak di permukaan atau di hadapan mata kita belaka. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita mengetahui soal-soal yang lebih esensial, hal-hal yang lebih dalam dari sekadar yang bisa dicerap oleh panca indera kita.
Agustus 2015. Kemerdekaan kita memasuki usia 70 tahun. Dalam usia yang tidak lagi belia itu, kita tahu dan sadar bahwa tugas-tugas sejarah kita masih jauh dari kata selesai. Meminjam istilah Tan Malaka, kemerdekaan kita belumlah kemerdekaan yang 100%, karena kita masih hidup dalam stelselnya kapitalisme. Stelsel yang, kata Bung Karno, ‘menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan-tariff, peperangan, dan kematian,–pendek kata menyebabkan rusaknya susunan-dunia yang sekarang ini.’
Bersediakah kita memikul tanggung jawab sejarah ini?***