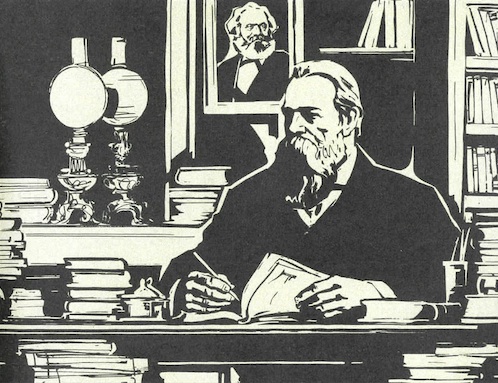BERBICARA soal Marxisme di Indonesia itu susah. Perkaranya bukan semata bahwa ada larangan legal terhadap penyebarluasan Marxisme, tetapi juga—dan terutama—karena kita kerapkali gagal memilah konteks pembicaraan itu sendiri. Pembicaraan tentang aspek-aspek teoretis Marxisme, misalnya, sering dianggap sebagai sikap ‘tidak membumi’ atau tak kenal ‘akar rumput’. Pembicaraan tentang aspek-aspek kultural dan populer budaya muda-mudi masa kini, contoh lainnya, malah dibaca sebagai sikap ‘kurang Marxis’ atau tak punya ‘keberpihakan’. Penerimaan semacam itu abai terhadap konteks yang melatari pengucapan pernyataan tersebut. Orang yang mendiskusikan teori-teori Marxis bukan berarti hanya mengamini teori dan merendahkan praktik. Karena ia sedang berbicara dalam konteks diskursus teoretis (di seminar, jurnal, dll.), maka ia tak semestinya dituntut untuk menggebrak meja dan mengajak aksi sekarang juga. Orang yang berbicara tentang kultur hipster juga bukan berarti serta-merta kurang Marxis. Sebab ia mungkin tengah mencoba mendakwahkan Marxisme secara kontekstual—mencoba merakit suatu budaya ‘hipster komunis’, misalnya. Dalam ranah diskusi dan debat, penerimaan yang abai konteks semacam itu menjalar lebih luas lagi. Orang yang berbicara tentang ‘kebenaran Marxisme’ kerap dianggap mau ‘memonopoli kebenaran’ atau ‘menekan perbedaan’ atau ‘menindas sang Liyan’. Penerimaan semacam ini merancukan persoalan benar-salah dan persoalan baik-buruk—merancukan epistemologi dan etika. Menyatakan bahwa “menurut saya, pendapat x benar” tidak sama dengan menyatakan: “diam kau, dasar bodoh”. Pernyataan tentang kebenaran atau kesalahan suatu pandangan justru merupakan titik berangkat diskusi dan debat, bukan titik akhirnya.
Secara umum, penerimaan-penerimaan semacam itu dilatari oleh kegagalan dalam mengidentifikasi modalitas pernyataan: dalam konteks dan melalui cara apa suatu pernyatan dilontarkan. Kegagalan dalam menangkap modalitas pernyataan inilah yang jadi penyebab susahnya berbicara tentang Marxisme, bahkan di antara sesama Marxis sekalipun. Begitu banyak kesalah-pahaman yang akarnya sepele: kekeliruan dalam mengartikan jenis-jenis pernyataan. Kalau ini benar, maka akar dari kesalah-pahaman dan pertikaian itu sebenarnya cuma permasalahan bahasa—dengan kata lain, masalah semu (pseudo-problem) sebab kedua belah pihak hanya bertikai dalam cara mengartikan pernyataan tetapi sebetulnya sepakat dengan substansi persoalan itu sendiri. Begitu setiap kata diklarifikasi dan modalitas pernyataannya dieksplisitkan, masalah-masalah itu akan lenyap. Perdebatan antar sesama Marxis kerapkali berakar pada pseudo-problem semacam itu. Yang seringkali membikin perkaranya agak pelik adalah bahwa kita tak selalu bisa menuntut klarifikasi modalitas pernyataan sejak mula. Bayangkan dilema yang dihadapi seorang kawan ketika ia dituduh ‘kurang Marxis’ sewaktu ia tengah bekerja perlahan-lahan menumbuhkan kultur ‘hipster komunis’. Kawan ini tentu saja bisa mengklarifikasi modalitas pernyataannya: apa yang saya wacanakan ini adalah upaya untuk menerbitkan simpati pada Marxisme di kalangan muda yang apatis pada politik. Namun dengan menyatakan itu, cover-nya terbongkar dan muda-mudi unyu itu segera bubar sembari berceloteh seperti Inong dalam The Look of Silence: “Ah, politik.” Akan tetapi, kalau ia tidak mengklarifikasi itu (demi mengamankan aktivitas propaganda halusnya), ia akan makin dikecam oleh sesama Kiri sebagai ‘kurang Marxis’: “tuh kan, lihat, dia ga bisa membalas apa-apa waktu kubilang dia sebenarnya bukan Marxis.” Lalu seorang yang lain akan menimpali: “Jleb!” Dilema serupa juga dialami oleh kawan-kawan yang memilih untuk melakukan intervensi ke dalam politik elektoral.
Dua tahun mengisi rubrik ini, permasalahan itulah antara lain yang paling sering saya jumpai. Mengartikulasikan Marxisme yang revolusioner sekaligus tidak vulger, yang sadar politik sekaligus melek budaya, memang bukan pekerjaan gampang. Dari perspektif non-Marxis atau anti-Marxis, pekerjaan semacam itu akan dipandang ‘dogmatis’ atau dianggap sebagai pekerjaan ‘Marxis puritan’. Sementara dari perspektif Ultra-Kiri, pekerjaan seperti itu akan dipandang ‘revisionis’ atau ‘bukan Marxis’. Sebagian menduga akar permasalahannya ada pada pendidikan intra-organisasi yang kurang berkembang. Memang, salah satu mata pelajaran pokok dalam tradisi kursus politik kita—mata pelajaran ‘MDH’—masih menggunakan bahan yang amat tua: potongan-potongan verbatim dari kuliah Tentang Marxisme yang disampaikan Aidit di Akademi Ilmu Sosial Aliarcham pada tahun 1962. Seakan-akan dunia telah berganti rupa, kecuali pelajaran MDH. Namun kita tak bisa menimpakan kesalahan sepenuhnya pada pendidikan formal dalam organisasi.
Keruwetan pemahaman soal Marxisme sebagian besar berakar pada prasangka, baik itu prasangka revolusioner maupun konservatif. Dalam prasangka revolusioner yang tak terasah, Marxisme disamakan dengan kumpulan tindakan heroik anti-kemapanan yang tercatat dalam almanak revolusi-revolusi besar dunia. Menjadi seorang Marxis, dalam prasangka ini, adalah menjadi sejenis Batman. Dalam prasangka konservatif, Marxisme diartikan sebagai doktrin usang yang merusak tradisi, menyangkal keunikan individu, disertai penerapan yang selalu hiper-birokratis dan totaliter. Menjadi seorang Marxis, dalam prasangka ini, tak ubahnya menjadi Zhdanov. Kedua prasangka ini berpangkal pada rendahnya produksi pengetahuan Marxis di Indonesia. Di satu sisi, penerbitan buku-buku Kiri yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri masih sangat kecil jumlahnya. Sepertinya banyak yang gemar bicara Marxisme, nge-tweet soal Marxisme, tetapi sedikit yang bersedia menulis soal Marxisme. Yang banyak adalah buku-buku Kiri dari luar dengan mutu terjemahan yang lumayan ‘brutal’. Di sisi lain, banjir informasi dari internet, melalui situs-situs donlot pdf gratis misalnya, seperti menghasilkan lonjakan wawasan Marxis yang amat terfragmentasi. Hari-hari ini, banyak yang bisa menyebut-nyebut Zizek, Badiou dan segala macam pemikir Marxis paling kontemporer tetapi kesulitan ketika diminta mengartikulasikan gagasannya secara sistematis, belum lagi untuk mengambil sikap mandiri. Rendahnya produksi pengetahuan Marxis ini mengakibatkan berkembang-biaknya prasangka-prasangka keliru soal Marxisme.
Marxisme yang berkembang di era Aidit dan Njoto adalah Marxisme yang dibangun dalam iklim Perang Dingin dan tradisi Soviet. Marxisme yang berkembang saat ini adalah Marxisme yang mesti mencari identitasnya sendiri sepeninggal Soviet dan Perang Dingin. Marxisme hari ini tak hanya berhadapan dengan kapitalisme neoliberal, tetapi juga mesti merumuskan hubungannya dengan konjungtur sosial yang amat beragam, mulai dari populisme, pascamodernisme, fundamentalisme agama, budaya pop anak muda, seni rupa pasca-avant-garde, temuan-temuan neurosains, ekonomi pasca-ekuilibrium, fisika partikel, logika nilai-jamak dan Haruki Murakami. Marxisme hari ini, singkatnya, mesti ditemukan kembali. Inilah yang saya tuliskan pada edisi pertama rubrik Logika, 28 Desember 2012. Penemuan kembali atas Marxisme bukan berarti revisi atas Marxisme. Menemukan kembali Marxisme, menurut saya, berarti merumuskan syarat-syarat yang membuat Marxisme benar adanya—menunjukkan bagaimana kebenaran Marxisme dijamin oleh struktur kenyataan: dimungkinkan oleh struktur logis dunia, struktur ontologis semesta fisik hingga akhirnya dikonfirmasi oleh struktur sosio-politiko-kultural kenyataan. Penghancuran atas PKI—pembumi-hangusan seluruh tradisi intelektual Marxisme Indonesia—membuat upaya penemuan Marxisme di Indonesia terhenti. Sekarang tugas generasi pasca-1965 lah untuk meneruskan upaya penemuan kembali Marxisme kita.
Marxisme begitu perkasa, sebab ia benar—demikian kata Lenin. Tugas kita kini adalah mencari tahu apa yang membuatnya benar. Tugas inilah yang selama ini kita kerjakan di lapangan praktik. Setiap aksi politik Marxis merupakan sumbangan terhadap upaya mengkonfirmasi kebenaran Marxisme. Tugas inilah juga yang selama ini dikerjakan lewat penelitian-penelitian empiris bersendikan pendekatan Marxis. Namun yang tak kurang pentingnya ialah kerja-kerja teoretis untuk menemukan kembali Marxisme. Pada edisi pertama rubrik ini, saya menulis bahwa rute teoretis ‘penemuan kembali Marxisme’ sulit dijalankan dalam seri artikel, bahwa apa yang lebih masuk akal untuk dikerjakan dalam rubrik ini ialah analisis logis atas konsep-konsep Marxis. Namun dua tahun berlalu dan keperluan bagi penemuan kembali Marxisme kian mendesak: mutu diskusi Marxis tak kunjung membaik, prasangka-prasangka katrok juga masih bertebaran dan perkembangan teori Marxis di Indonesia seperti jalan di tempat. Karena itu, saya tak melihat jalan keluar lain: proyek ‘penemuan kembali Marxisme’ mesti segera dimulai.
Kajian teoretis atas Marxisme yang ada sampai hari ini kebanyakan dibangun melalui model eksegesis: pembacaan atas teks-teks Marx dan para penerusnya. Dengan kata lain, kajiannya mirip dengan tradisi ‘tafsir Taurat’ atau ‘tafsir Injil sinoptik’—membaca teks-teks sakral lalu mempelajari tradisi komentar terhadap teks-teks itu. Tentu saja, sebagai pengantar ke dalam tradisi pemikiran Marxis, tak ada yang salah dengan cara mengkaji seperti itu. Saya sendiri mulanya belajar Marxisme melalui metode eksegesis. Namun pengembangan atas tradisi teoretis Marxisme sulit terwujud kalau kita hanya berkubang dalam telaah teks. Malah, efek samping yang kadang muncul dari cara mengkaji seperti itu adalah munculnya argumen-argumen berbasis otoritas tekstual: teori x benar karena “ada tertulis dalam Das Kapital bahwa …”. Model argumentasi semacam ini tak akan membawa kita ke mana-mana dan malah menjadi pangkal dogmatisme dan involusi teori Marxis. Apa yang kita perlukan, dalam konteks ini, terutama ialah analisis konseptual atas Marxisme dalam terang temuan-temuan teoretis terbaru di berbagai bidang. Namun, karena Marxisme bukanlah satu-satunya pendekatan yang ada di dunia ini dan banyak bidang-bidang kajian yang tumbuh di luar cakupan permasalahan yang dibahas Marxisme, maka program analisis konseptual itupun perlu diperluas. Kita mesti membuktikan secara logis tak hanya bagaimana Marxisme benar tentang struktur kenyataan yang mau dijelaskannya, tetapi juga bagaimana Marxisme mungkin benar. Artinya, kita mesti merekonstruksi secara konseptual struktur kenyataan, termasuk wilayah kenyataan yang tak terbahas oleh Marxisme selama ini. Dengan kata lain, kajian teoretis atas Marxisme mensyaratkan rekonstruksi filsafat dalam mendedahkan struktur logis, ontologis dan epistemologis dari totalitas kenyataan itu sendiri.
Celakanya, dalam kondisinya sekarang, filsafat kontemporer tak banyak membantu kita di sini. Filsafat kontemporer telah berjalan menuju kebuntuan. Hal ini terjadi baik di dalam tradisi filsafat Kontinental maupun Analitik. Ada tiga fenomena yang menunjuk pada fakta di muka:
- Filsafat kontemporer telah terbentur pada analisis parsial tentang segmen-segmen kenyataan yang amat spesifik dan gagal merumuskan analisis terpadu tentang semua fenomena parsia itul. Dalam tradisi Analitik, kegagalan ini terjadi karena spesialisasi kajian filsafat yang kehilangan tautannya dengan peta besar permasalahan filsafat. Dalam tradisi Kontinental, sebaliknya, kegagalan ini terjadi karena sekalipun hendak membicarakan totalitas fenomena dalam sekali rengkuh, metode analisisnya tetap terjangkar pada cakrawala problematik yang spesifik dari salah satu ranah keberadaan.
- Sebagian karena gagal merumuskan analisis terpadu atas segala fenomena, filsafat kontemporer gagal merekonsiliasikan dualitas-dualitas konseptual yang diwarisinya dari sejarah filsafat: Ada dan pikiran, materialitas dan idealitas, alam dan kebudayaan, objektivitas dan subjektivitas, keniscayaan dan kehendak bebas, dst. Umumnya, tradisi Analitik lebih menekankan sisi pertama dengan mengorbankan yang kedua; sebaliknya tradisi Kontinental menekankan yang kedua sembari membuang yang pertama.
- Filsafat kontemporer kehilangan fungsi khasnya. Kekhasan filsafat terletak dalam kemampuannya memberikan hipotesis tentang dunia. Karena ketiadaan analisis terpadu dan terjebak ke dalam salah satu kutub dualitas konseptual yang menstrukturnya, filsafat kontemporer gagal memenuhi fungsinya dalam memberikan hipotesis yang koheren tentang dunia. Hipotesis yang dihasilkan oleh filsafat kontemporer cenderung fragmentaris: cocok untuk satu bidang, tapi gagal total di bidang lain. Akibatnya, tak ada gambaran yang memadai tentang kenyataan secara utuh. Pembicaraan tentang ‘matinya filsafat’ merupakan gejala dari hilangnya fungsi khas filsafat dalam era kontemporer.
Ketiga fenomena ini menunjuk pada fakta buntunya refleksi filsafat kontemporer. Inilah yang menyebabkan mengapa kendati pascamodernisme sudah mulai sering dikritik, tak ada wawasan filosofis baru yang menggantikannya dengan skala yang kurang-lebih sama komprehensifnya. Kita masih hidup di era pasca-pasca-modernisme, sebuah era yang ditandai oleh respon kritis—sekaligus keterkungkungan dalam—pascamodernisme. Kita menatap cakrawala terdepan filsafat kontemporer dan kita tak melihat apa-apa.
Kebuntuan yang dihadapi filsafat kontemporer bermuara pada lenyapnya apa yang sampai abad ke-19 dikenal sebagai sistem filsafat. Lenyapnya metode berfilsafat yang sistematik menyebabkan munculnya rupa-rupa fenomena di muka. Apabila kita menoleh ke belakang, kita akan menemukan deretan sosok seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Spinoza dan Hegel yang masing-masing merumuskan refleksi filsafatnya dalam bingkai sistem. Mereka semua, dengan satu atau lain cara, berupaya mengajukan hipotesis yang koheren tentang dunia dengan mendamaikan dualitas-dualitas konseptual filsafat. Sosok terakhir yang masih berfilsafat dalam kerangka sistem adalah Marx—sang pembangun sistem filsafat terakhir, sang pencari ‘hukum gerak masyarakat’ melalui kerangka ontologi materialis. Namun sistem-sistem filsafat semacam itu, dalam kondisi asli yang diwariskan para perumusnya, saat ini amat lemah karena kerapkali bertopang pada pengandaian yang dewasa ini telah terbukti keliru, khususnya dalam terang temuan-temuan parsial filsafat kontemporer di berbagai bidang kajian spesifik. Pada saat yang bersamaan, filsafat kontemporer yang bercorak non-sistem juga tak mampu menghadirkan konsepsi alternatif tentang kenyataan yang luas cakupannya setara dengan sistem-sistem tersebut. Karenanya, rekonstruksi atas Marxisme mensyaratkan rekonstruksi atas filsafat kontemporer itu sendiri: mewujudkan sistem filsafat Marxis yang dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan temuan-temuan terbaru filsafat kontemporer.
Mengapa kita memerlukan ‘sistem filsafat’? Buat kita yang hidup di alam pascamodern, ide tentang ‘sistem’ itu saja sudah pasti memicu kecurigaan. Namun kecurigaan ini terbukti berbiaya tinggi. Dicampakkannya upaya untuk membangun sistem, kita ditelan dalam kerancuan tak berujung tentang hubungan antar domain wacana. Yang sering terjadi adalah penggunaan perspektif yang tertanam dalam suatu domain wacana untuk meneropong domain wacana lainnya. Contohnya adalah penggunaan kriteria etis (baik vs buruk atau otentik vs mainstream) untuk mendekati permasalahan epistemologis (benar vs salah), atau penggunaan kriteria estetis (indah vs jelek atau sublim vs banal) untuk mendekati permasalahan politik. Karena tak memiliki wawasan tentang struktur pengandaian yang merajut keseluruhan domain filsafat sebagai sistem, kita kerapkali menempatkan domain-domain tertentu (yang statusnya sebetulnya derivatif) untuk mengevaluasi dan mengkonstruksi domain-domain yang sebetulnya lebih fundamental. Penggunaan kriteria etis untuk meneropong dan membangun konsepsi ontologis tentang keseluruhan kenyataan, misalnya, bertumpu pada kerancuan tentang fundamen kenyataan itu sendiri: bagaimana mungkin etika menjadi prinsip pembimbing ontologi jika ontologi itu sendiri sejatinya berurusan dengan totalitas kenyataan yang lebih luas (alam semesta) daripada totalitas kenyataan etis (semesta tindakan manusia)? Namun, hal-hal sederhana macam itu kerapkali dilupakan. Ini terbukti dalam perdebatan-perdebatan soal Marxisme dan teori-teori sosial kontemporer yang terjadi di Indonesia (perdebatan saya dengan Goenawan Mohamad, misalnya).
Kita dapat memperjelasnya melalui contoh dari sejarah musik. Piano Sonata no. 23 karya Beethoven, misalnya, adalah bangunan musikal yang dibentuk lewat satu instrumen saja. Kesannya memang mendalam. Namun dari segi kompleksitas dan mutu harmoni, karya itu sama sekali bukan saingan Simfoni no. 8 bikinan Mahler yang mencakup seribu instrumen. Finale dalam simfoni tersebut betul-betul menelan habis sonata Beethoven. Sementara Beethoven cuma bisa menawarkan Angst, Mahler menunjukkan apa itu musik. Demikian juga dalam filsafat. Orang yang berfilsafat tanpa wawasan tentang sistem boleh jadi menghasilkan komposisi yang terkesan indah. Ia bekerja dengan salah satu cabang filsafat derivatif, seperti filsafat politik atau etika, bahkan estetika. Namun dari situ ia mendeduksikan kesimpulan yang cakupannya berpretensi merengkuh persoalan ontologis, epistemologis dan logis. Ini seperti seorang librettist yang mengira dirinya seorang komponis: mengarang kata-kata dan dengan itu merasa telah menciptakan musik. Seorang komponis atau konduktor harus bisa menguasai beberapa alat musik sekaligus. Minimal ia mampu memainkan piano dan biola. Ia mesti tahu warna suara dan rentang nada dari seluruh jenis alat musik. Demikian pula, seorang yang hendak berfilsafat secara sistematis semestinya tak hanya tahu kritik sastra, tetapi juga ilmu logika, fisika, kimia, biologi, dst. Filsuf adalah seperti konduktor. Agar mampu membunyikan kebenaran semesta yang terkandung dalam partitur, ia mesti menyelami seluk-beluk bunyi berbagai alat musik. Ia mesti tahu kapan cello masuk, kapan timpani berhenti, kapan oboe merayap di celah-celah bunyi. Filsuf mesti tahu arsitektur ilmu-ilmu dan taksonomi cabang-cabang filsafat: bagaimana sistematika pengandaian yang menstruktur hubungan antar ilmu pengetahuan dan luas klaim filsafat seturut yurisdiksi cabang-cabangnya. Ia tak bisa mengandalkan ilmu kritik sastra dan filsafat estetika untuk membangun konsepsi tentang kenyataan. Untuk membangun kenyataan, ia setidaknya memerlukan wawasan soal fisika dan matematika (dalam konteks ilmu-ilmu) serta ontologi dan logika (dalam konteks filsafat). Singkatnya, laku berfilsafat hanya bertanggung-jawab kalau itu diwujudkan dalam bingkai sistem. Jika tidak begitu, apa yang akan muncul hanyalah kepongahan yang berkedok kerendahan hati.
Para filsuf hingga abad ke-19 bekerja dalam bingkai sistem. Alasannya, sebagian, bersifat sosiologis. Pada masa itu, pembagian kerja akademis belumlah serinci sekarang. Belum ada sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, fisika, kimia, biologi, dst. Yang ada pada waktu itu, khususnya di abad ke-17, adalah filsafat alam, filsafat politik, filsafat sosial, dst. Inilah antara lain yang menyebabkan para filsuf di masa lalu memiliki wawasan sistem yang amat kuat. Leibniz adalah ahli matematika, sekaligus teologi, logika, metafisika, Hume adalah sejarawan, pemikir politik, etika, epistemologi dan metafisika, Kant adalah astronom, pemikir geografi, selain juga pemikir politik, etika, estetika, metafisika dan epistemologi. Marx sendiri sekarang kerap dipersepsi sebagai sosiolog, ekonom, filsuf, ilmuwan politik, teoretisi budaya, dsb. Corak sistematis refleksi filsafat mereka kemudian terkikis oleh pembagian kerja akademis: fisikawan mengurus fisika, ekonom bicara ekonomi, filsuf bicara filsafat. Pada abad ke-20, pembagian kerja itu makin rinci lagi: profesor teknik pangan yang pakar dalam ilmu fermentasi kedelai berbicara dengan sesama pakar fermentasi kedelai, profesor filsafat yang ahli dalam kajian tentang filsafat hukum perpajakan berbicara dengan koleganya sendiri—biarkan kapitalisme yang mengurus link and match antar berbagai bidang kajian yang teramat spesifik dan tak bisa berbicara satu sama lain itu. Lenyapnya sistem filsafat berjalan seayun dengan konsolidasi kapitalisme neoliberal.
Namun Indonesia adalah sebuah pengecualian. Di sini seperti tak ada kespesifikan kajian filsafat yang mencirikan pendidikan filsafat di Eropa, Australia atau Amerika. Semuanya umum-umum saja. Kalaupun ada bidang kepakaran yang spesifik, sayangnya bidang tersebut tidak betul-betul bidang (tema), melainkan kepakaran terhadap tokoh tertentu. Dalam kondisi semacam ini, penulis filsafat jadi sulit dibedakan dari penulis biografi. Kalau sudah begitu, kultur berfilsafat cenderung menjadi kultur epigon atau budaya ‘fans club’. Alih-alih lingkaran kajian epistemologi atau etika, apa yang lebih sering kita temui di sini adalah temu-kangen antar groupie Zizek atau antar Heideggerean posse maupun komunitas penghayat pascamodernisme. Akan tetapi, di lain pihak, kondisi sosiologis Indonesia juga sangat memungkinkan tumbuhnya pemikiran tentang sistem. Pasalnya, di Indonesia, seseorang yang hendak hidup sebagai filsuf kontemporer mesti jadi filsuf temporer: kadang filsuf, kadang bukan. Kadang menulis tentang realisme in re dalam filsafat matematika, kadang menulis kritik sastra, kadang menjadi penulis seni rupa, juru transkrip diskusi-diksusi LSM, komentator politik, dosen kontrak untuk mata kuliah ‘menulis kreatif’, kadang pula jadi tukang bikin sagu keju atau nastar untuk parsel lebaran dan natal. Di Indonesia, orang yang ingin jadi filsuf dan hidup, mesti pandai-pandai mengatur subsidi-silang: menulis artikel politik di koran atau kritik sastra untuk mensubsidi penelitian filsafat, mengerjakan rias pengantin untuk menutup biaya fotokopi berjilid-jilid Cambridge History of Philosophy. Namun justru dari sinilah wawasannya tentang kesaling-terkaitan antar berbagai aspek kenyataan—cikal-bakal konsepsi tentang sistem—terbentuk. Kesadaran akan hubungan antar cabang ilmu dan kebudayaan justru tumbuh ketika sang filsuf dikondisikan secara ekonomis. Menariknya, justru inilah juga kondisi yang serupa di Eropa abad ke-17. Spinoza bekerja sebagai tukang asah lensa kacamata untuk membiayai penulisan traktat Ethica, ordine geometrico demonstrata. Setiap jam lima pagi, Descartes mesti bekerja sebagai guru les Ratu Swedia tentang topik yang dibencinya, yakni cinta—pekerjaan yang juga membuatnya mengidap pneumonia akut dan mati sesak nafas. Singkatnya, menjadi filsuf di Indonesia hari ini sama seperti menjadi filsuf di Eropa abad ke-17. Berkah tersembunyi di balik itu ialah bahwa prakondisi material bagi perumusan sistem filsafat telah tercapai di Indonesia—filsuf mesti belajar berpikir tentang kesaling-hubungan antar berbagai aspek kenyataan dalam sistem filsafat kalau tak mau mati kelaparan atau jadi birokrat kampus.
Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana sistem filsafat Marxisme itu dirancang? Kita tidak bisa berangkat dari problematik klasik Marxisme: dialektika, materialisme, perjuangan kelas, dsb. Sebagai sistem filsafat, Marxisme yang saya bayangkan mesti dapat memberi ruang pada apa-apa yang berada ‘di luar’ domain diskursus Marxisme tradisional: permasalahan-permasalahan di luar ilmu sosial seperti Ada, esensi, kebenaran, makna, kesadaran, dsb. Rekonstruksi atas Marxisme sebagai sistem filsafat kontemporer mesti dimulai dari ‘luar’ domain Marxisme tradisional. Maka pertanyaan umumnya menjadi:
Dunia macam apakah yang diandaikan demikian rupa sehingga Marxisme benar adanya? – atau –
Seandainya Marxisme benar, maka dunia seperti apakah yang disyaratkan oleh kebenaran tersebut?
Artinya, kita berupaya mencari tahu struktur ontologis, logis, epistemologis, politis dan etis dari kenyataan yang membuat Marxisme benar adanya. Pencarian semacam ini tidak bisa dilakukan secara ringkas dan selektif, melainkan mesti melibatkan interogasi ulang atas seluruh kategori filsafat mulai dari metafisika dan logika sampai dengan filsafat politik dan etika.
Inilah substansi dari proyek penemuan kembali Marxisme. Saya merasa bahwa Marxisme hanya dapat ditemukan kembali dengan cara dilupakan terlebih dahulu. Inilah yang saya tawarkan: melupakan dan membuang semua konsep dan fraseologi Marxis, memulai lagi semuanya dari nol, dari problem paling dasar filsafat seperti Ada dan sifat-sifatnya, dan dari situ mendeduksikan hasilnya sampai ke taraf filsafat politik dan etika. Namun mengapa perlu melupakan Marxisme terlebih dulu? Di sini terletak pertaruhan besar kita:
- Kalau Marxisme benar adanya dan kenyataan memang seperti yang digambarkan oleh Marxisme, maka pada tiap-tiap akhir rekonstruksi itu kita akan menjumpai komponen-komponen konseptual Marxisme dan pada akhir seluruh proses ini kita akan menemukan kembali Marxisme. Dengan kata lain: jika Marxisme benar adanya, maka melupakannya tak akan mengubah kebenarannya.
- Kalau Marxisme keliru atau kenyataan ini tidak seperti yang digagas oleh Marxisme, maka pada akhir rekonstruksi filsafat sistematik ini kita tidak akan menemukan Marxisme sama sekali. Dengan kata lain: jika Marxisme salah, maka melupakannya berarti menunjukkan kesalahannya.
Seperti sang narator dalam novel Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, kita mesti melupakan Marxisme dan mengingatnya kembali secara baru—dan dengan itu membawa sekaligus bukti bagi kebenarannya. Artinya, kita tidak bisa mengasumsikan terlebih dahulu kebenaran Marxisme dan konsep-konsepnya. Kita mesti membuang itu semua dan mulai dari nol, dari refleksi filsafat paling elementer dan jauh dari hiruk-pikuk semesta wacana Marxisme tradisional. Kita mesti turun ke medan perdebatan yang steril dari Marxisme dan merumuskan simpulan-simpulan yang kita temukan—bersenjatakan nalar semata—sebagai benar adanya. Inilah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk merumuskan ulang Marxisme sebagai sistem filsafat kontemporer. Marxisme baru terbukti benar jika seluruh simpulan yang didapat berdasarkan nalar semata itu membawa kita kepadanya.
Namun, seandainya benar, Marxisme yang akan kita temukan di akhir proses ini bukanlah Marxisme tradisional yang lazim dikenal. Marxisme yang akan ditemukan ialah Marxisme yang lahir baru, yang telah disucikan dari segala kekeliruan dan keruwetan konseptualnya selama ini. Yang akan hadir, seandainya Marxisme benar, adalah Marxisme yang mampu memberi ruang pada apa yang berada ‘di luar’-nya. Apa yang akan hadir ialah sebuah filsafat Marxisme yang ditopang oleh metafisika, logika, epistemologi, filsafat bahasa, filsafat akal budi, filsafat ilmu, filsafat politik dan etika. Jadi hasil akhir dari proyek ini tidak hanya rekonstruksi Marxisme baru, tetapi juga suatu sistem filsafat yang merupakan sintesis dari puncak-puncak perdebatan filsafat kontemporer. Hanya dengan cara inilah Marxisme dapat ditemukan kembali. Kebenaran Marxisme baru akan terkonfirmasi apabila kita berhasil memberikan pembuktian ekstra-Marxis.
Ini memang bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan fokus dan penelitian yang lama. Pekerjaan ini hanya dapat dituangkan dalam beberapa jilid buku. Saya sendiri membayangkan akan ada setidaknya empat buku:
Buku I : Ontologi dan Logika
Buku II : Epistemologi dan Filsafat Bahasa
Buku III : Filsafat Akal Budi dan Filsafat Ilmu
Buku IV : Filsafat Sosial dan Politik
Apa yang akan tersaji dalam keempatnya bukanlah pengantar, melainkan buku yang memuat deduksi kategoris atas simpulan-simpulan perdebatan terkini di masing-masing cabang filsafat. Tujuannya adalah merumuskan hipotesis terpadu tentang dunia yang diturunkan dari prinsip-prinsip murni ontologi dan logika. Karena luasnya wilayah kajian yang perlu dipelajari, penulisan keempat buku itu mungkin akan memakan waktu sekitar empat tahun atau lebih.
Untuk memenuhi tugas itulah saya memutuskan untuk berhenti menjadi penulis tetap rubrik Logika. Inilah tulisan terakhir saya di rubrik ini. Selanjutnya, rubrik ini saya serahkan kepada Dede Mulyanto yang akan mengisi rubrik Logika secara rutin mulai Januari 2015. Ia adalah juga seorang kamerad Indoprogress dan pengajar antropologi di Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Selain itu, ia juga memiliki wawasan filsafat ilmu sosial yang sangat mumpuni, disiplin akademik yang kokoh dan rekam-jejak penulisan buku-buku Marxis yang panjang. Dede akan menggantikan saya mengelola rubrik ini, sementara saya membantu kerja penyuntingan Jurnal Indoprogress cetak sembari mengerjakan penelitian ‘penemuan kembali Marxisme kita’. Terima kasih sudah mau membaca tulisan saya selama ini. Selamat tahun baru dan sampai jumpa lagi di tahun 2020.***
31 Desember 2014