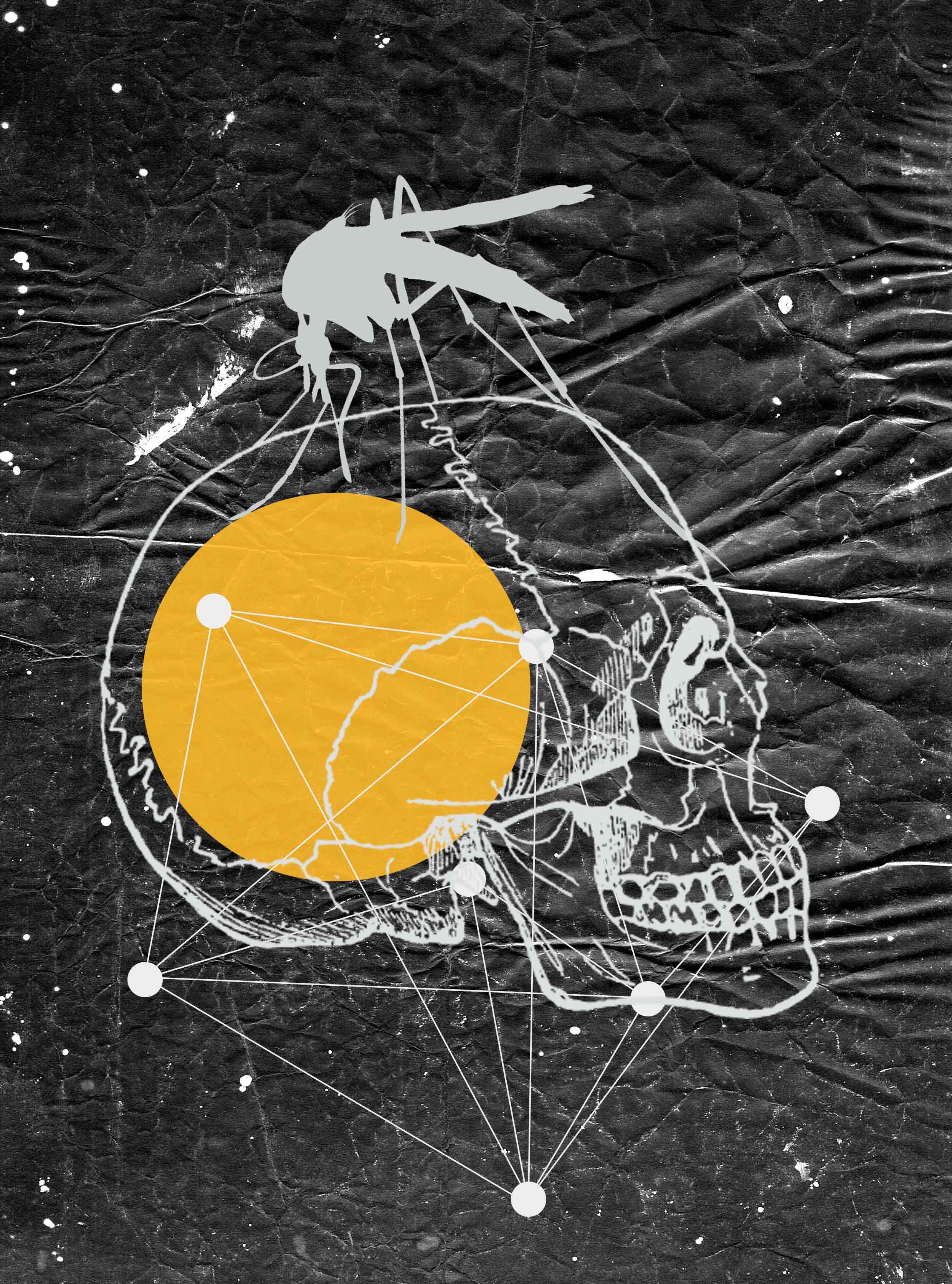NAMAKU Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.
“Ku,” seru teman-temanku, “Kenapa kamu suka jadi benalu?”
Mengapa teman-temanku bisa ngomong begitu, akan kuceritakan padamu.
***
DI suatu Oktober yang kerontang, pembantaian itu terjadi di hari Sabtu. Seratusan orang berarak menuju Tegalirik, desa terbarat di kelurahan ini. Orang-orang itu sebelumnya telah berhasil kuprovokasi. Mereka, beriman baru kemarin sore, percaya saja pada hasutan yang kuembuskan.
Awalnya, kupikir aku mesti menyiapkan dalil-dalil yang lama tak kubuka. Meski oleh banyak orang aku dibilang alim nan saleh dan mereka percaya petuahku mentah-mentah seperti mereka percaya pada ibunya, terakhir kali buka Kitab Suci seingatku sepuluh tahun yang lalu. Setelah membaca habis Kitab dua kali, aku merasa tak memerlukannya lagi. Hanya di saat-saat tertentu aku jinjing Kitab itu, tapi tidak membukanya, sekadar untuk meyakinkan orang-orang bahwa pendapatku memang mengacu padanya.
Tapi untuk urusan kali ini aku merasa tak perlu membawa-bawa Kitab. Orang-orang itu langsung terbakar begitu aku menyelesaikan orasiku. Aku tak kehilangan apa pun kecuali suaraku yang jadi serak beriak. Namun itu tak jadi soal. Segelas limun segar segera mereka, orang-orang dungu itu, sodorkan padaku, yang lalu kutandaskan dengan bunyi nyaring.
Selebihnya, kuasa setanlah yang mengatur. Di depan barisan, aku terus mengompori mereka dengan maki-makian bernada religius. Kalau perlu, aku bawa-bawa nama Tuhan setelah menyerukan nama-nama penghuni kebun binatang. Tapi, entah kenapa, tak ada yang protes padaku karena nama Tuhan disandingkan dengan penghuni kebun binatang.
Kami menemukannya tengah bersantai di beranda. Hidup sebagai wiraswasta membuatnya libur sepanjang minggu. Ia tampak hidup amat sejahtera. Mobilnya lima, rumahnya gedongan belaka, pembantu-pembantunya makmur semua.
Pria itu dulu pernah hendak kami usir dari kampung. Orang aneh dengan ibu yang tak kalah aneh. Satu-satunya doktor di kampung, bahkan di kecamatan. Di usia semuda itu, kami baca di koran-koran sini, dialah doktor termuda di negeri ini. Memang tak mengherankan. Otaknya memang encer luar biasa. Sampai-sampai guru-guru pun berdecak kagum padanya. Tatkala pulang dari studinya di Inggris, ternyata sifat anehnya tak jua menghilang. Balik kampung, ia bahkan berani mengajarkan agama baru kepada para tetangga. Agama baru itu mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya makhluk mandiri, yang tak butuh apa pun dan siapa pun, selain upayanya sendiri. Sinting.
Melihat kami yang datang berbondong-bondong, ia bangkit dari kursinya. Raut itu, raut keramahan yang aku benci, kini ditingkahi sedikit rona keheranan. Sebelum kata terucap dari mulutnya, batu seukuran kepalan tangan meluncur ke kepalanya. Darah berceceran. Sebelum ia sanggup memahami apa yang terjadi, seseorang berteriak dari belakangku, “Kafir! Tumpas dia sebelum menyesatkan seluruh warga!” Suara itu seolah memiliki kekuatan magis yang mampu menerbangkan batu-batu ke pria itu saja. Tak ayal, ia, tak lagi berbentuk manusia, jadi bulan-bulanan kami semua.
Beberapa orang merangsek ke dalam rumah dan menemukan perempuan-perempuan yang menjerit. Melihat mereka, aku jadi bernafsu. Kuperkosa mereka satu per satu sementara orang-orang lain mengantre di belakang. Setelah semua kebagian, kami bereskan perempuan-perempuan itu, kami kirim ke neraka. Kemudian kami menyalakan api dan membakar rumah itu dan semua kekayaan yang selalu bikin aku iri hati. Semua orang berjingkrak bersuka ria. Setan-setan menari bersama. Aku tak perlu lagi membawa-bawa nama Tuhan dalam urusan ini. Karena ternyata dukungan setan melebihi apa yang aku inginkan.
Mengapa nasib wiraswasta itu begitu, akan kuceritakan padamu.
***
MALAM itu, setiap orang yang merasa dirinya laki-laki mesti keluar dari rumah masing-masing. Lusa peringatan tujuhbelasan dan jalanan kampung belum sedikit pun dipermak. Entah sejak kapan, atau kenapa, jalanan kampung harus dipermak untuk menyambut hari kemerdekaan. Apakah seremoni selalu berarti kesemarakan?
Aku sebenarnya tidak tertarik pada acara semacam ini. Selain bosan, aku merasa lebih baik mengerjakan sesuatu yang lebih berarti di rumah. Aku tipikal orang yang tak bisa berbasa-basi di depan banyak orang, mengobrolkan sesuatu yang tak jelas juntrungannya. Ya, aku merasa, acara ini lebih banyak ngomongnya ketimbang kerjanya. Gotong-royong macam mana yang kau harapkan ketika segelintir orang berpeluh-peluh saking capainya bekerja sementara yang lain berleha-leha dengan kuas yang tak pernah sekali pun diusap-usapkan?
Dan inilah aku. Terpaksa keluar dari rumah supaya eksistensiku sebagai lelaki diakui.
Dengan kuas di tangan kanan dan sapu lidi di tangan kiri, aku menuju Paidi yang tengah mengaduk kapur di ember. “Kamu bawa ini, Man, dan laburlah jalan yang sebelah sana,” katanya sembari menyerahkan ember bagianku. Aku menuju jalan yang belum terjamah orang. Aku sapu pinggirannya dari debu agar kapur yang kukuaskan melekat dengan sempurna.
Jam sebelas pekerjaan sepakat diakhiri. Sepakat karena tiada lagi orang berkuas atau bersapu lidi yang terlihat bekerja. Orang-orang berkumpul di depan pos untuk menikmati makanan ringan. Awalnya ketawa-ketiwi melulu. Obrolan biasa yang mempercakapkan Liga Inggris, keadaan sawah yang terus-menerus paceklik, atau pengalaman-pengalaman lucu di pabrik. Aku hanya mendengarkan saja lantaran aku benar-benar buta sepakbola, tak paham seluk-beluk pertanian, dan tidak pernah bekerja di pabrik.
Semakin malam, suasana mendadak jadi mencekam. Entah apa masalahnya, Pak Dar mengumpat kasar kepada Pak Cung yang duduk di dekatnya. Pak Cung yang tidak terima lantas berdiri seraya balas mengumpat tak kurang kasarnya. Pak Dar pun berdiri. Kami semua berdiri melihat urat mereka sama-sama menegang. Sebelum salah seorang mendaratkan bogem mentahnya, kami dengan sigap memisahkan mereka. Mereka masih terus mengumpat setelah diajak pulang ke rumah masing-masing.
Tongkrongan belum bubar sehabis insiden itu. Telah lama tertanam di otakku, jangan pernah meminta diri sebelum ada yang mengundurkan diri. Aku bertahan dengan pikiran itu, takut diolok-olok sebagai anak rumahan kendati jam dinding sudah menunjuk pukul satu dini hari. Ketika Pak San agaknya hendak pulang, kulihat inilah kesempatanku untuk menyudahi kumpul-kumpul tak bermutu ini.
Baru dua langkah mengayun, seseorang meneriakiku, “Mau ke mana, Man?” Aku menoleh, ternyata ada orang yang paham gelagatku. Dia Aku, si pembual. Orang yang doyan ngomong meski tak pernah mengerti apa yang ia omongkan. Aku tak menyahut. Buat apa, pikirku.
“Mau kelon sama ibumu, Man?” Dia berseru keras sekali. Semua orang ketawa terbahak-bahak. Dadaku bergolak, tapi aku masih punya otak.
“Lihat anak kuliahan zaman sekarang. Tak doyan begadang. Tongkrongannya di rumah melulu,” tambahnya bikin kupingku panas. Ketawa mereka semakin kencang setelah menemukan bahan obrolan baru. Sejauh yang kukira, orang-orang itu tak pernah bermasalah denganku. Sikap mereka selalu sopan meski bagiku sangat membosankan.
Di saat tertentu, aku memahami sikap mereka yang menyunggingkan senyum sinis ketika bercakap denganku. Aku berusaha, selalu berusaha, supaya kalimat yang keluar dari mulutku terdengar berlogat sama seperti mereka. Tapi rupanya buat mereka aku terlalu sok kota, karena kurang bisa berbahasa dengan memakai langgam kampung. Mereka pun, sangkaku, semakin tak suka padaku lantaran hobiku yang suka mengurung diri di rumah, enggan bercakap-cakap dengan tetangga. Tapi, apa yang salah dengan itu? Bukankah aku tak pernah mengganggu mereka?
Aku berjalan tersaruk-saruk sambil masygul: semua orang serasa memusuhiku. Sejak saat itu, aku merasa diriku sebatang kara saja di dunia ini. Tak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya dan mau percaya padaku, selain diriku dan ibuku sendiri.
Mengapa aku bisa menyimpulkan seperti itu, ada baiknya kuceritakan padamu.
***
TIBA-TIBA anakku datang dengan menangis sesenggukan. Sungguh tak biasa. Musim ujian seperti sekarang selalu jadi saat yang asyik baginya. Tak pernah ia merasa kesulitan mengerjakan soal-soal itu.
Tapi inilah yang terjadi: putra semata wayangku mengiba padaku dengan bercucuran airmata. Kutanya ada apa dia malah menjawab, “Bu, aku tak mau sekolah lagi.”
Bagai mendengar petir di siang bolong, aku mencoba tenang. Ada apa, tanyaku lagi. Dan dia pun bercerita. Di sekolah, katanya, Pak Guru memintanya jadi pembohong. “Man, kamu kan pintar. Kalau mau balas jasa gurumu, gunakan kepintaranmu untuk membantu teman-teman lulus ujian,” kata Pak Guru seperti ditirukan anakku.
Pada saat ujian, Pak Guru telah menyiapkan distribusi jawaban. Kertas jawaban anakku ditunjukkan kepada teman yang duduk di belakangnya, yang lantas menyalin dan memperbanyak jawaban itu di kertas buram. Kertas inilah yang kemudian diedarkan ke semua kelas. Buat murid kelas sebelah, salinan lembar jawaban diserahkan di toilet atau ditaruh di pot bunga.[i] Aku benar-benar kaget mendengar ceritanya.
Esoknya, aku mendatangi sekolah dan mengadukan perkara anakku. Di luar dugaan, Kepala Sekolah malah membentak dan mengataiku egois. Aku lari ke Komite Sekolah dan perlakuan serupa yang aku terima. Aku pergi ke Dinas Pendidikan tapi mereka juga melakukan hal yang sama. “Kalau mau pintar sendirian, Anda tidak cocok tinggal di sini. Negara ini bukan tempat orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aku bin Atang yang bekas penatar P-4 itu dengan sinis.
Sesampainya di rumah, aku mendapati rumahku telah porak-poranda. Beberapa tetangga dekat menjelaskan, serombongan orangtua muridlah pelakunya. Aku mencari anakku dan menemukannya sedang meringkuk di bawah pohon mangga. “Bu,” katanya, “semua orang tak suka melihat orang-orang jujur seperti kita hidup bahagia.”
Mengapa anakku bisa sampai bilang begitu, terpaksa kuceritakan padamu.
***
ENAM tahun berlalu sejak pembantaian itu. Enam tahun sudah aku menjadi peminta-minta. Adakah yang salah dengan meminta-minta? Bukankah negara ini negara gotongroyong yang harus menolong siapa pun yang pantas ditolong? Dan peminta-minta sepertiku bukankah sudah selayaknya ditolong oleh siapa saja yang merasa dirinya penolong?
Namun aku tak mengerti tabiat masyarakat akhir-akhir ini. Semakin hari, semakin banyak orang menutup pintunya dari peminta-minta sepertiku. Sejumlah daerah melarang keras warganya memberi sesuatu kepada peminta-minta. Gerbang besi dibangun tinggi-tinggi demi menghalau kedatanganku. Orang-orang menganggapku benalu. Anak-anakku pun malu memiliki orangtua sepertiku. Hidupku tambah sepi, tambah hampa. Malam apa lagi.[ii]
Demikian laporan ini kutulis. Semoga berguna buat siapa pun yang membaca. Namaku Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.
Pleburan, 25062012, 11.31
Mangkang, 01012014, 09.13
___________________________
*AP Edi Atmaja, lahir di Kendal pada 17 Juni 1990, mengelola galeri tulisan Sastra Kelabu.
[i] Narasi diperoleh dari pemberitaan majalah Tempo, edisi 20-26 Juni 2011.
[ii] Sajak “Sendiri” oleh Chairil Anwar.