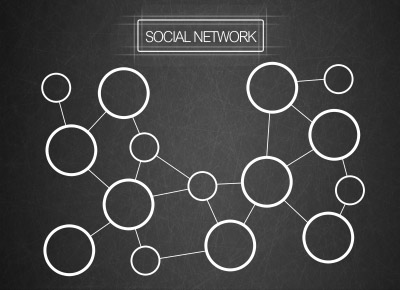PADA Desember 2010, Tunisia, sebuah negara di kawasan Timur Tengah, diguncang oleh perubahan revolusioner. Pemerintahan diktator yang telah berkuasa puluhan tahun berhasil digulingkan oleh gerakan massa yang sangat luas. Dalam waktu singkat, virus revolusi ini menyerang Dunia Arab lainnya, seperti Yaman, Jordania, juga Sudan. Tapi yang paling fenomenal adalah tergulingnya diktator Mesir, Hosni Mubarak.
Gelombang revolusi yang melanda Dunia Arab ini, berbeda dengan revolusi-revolusi sebelumnya yang pernah ada. Pembedanya adalah kemunculan media sosial dalam memobilisasi massa, menyebarkan pesan dan informasi. Kehadiran media sosial tak pelak telah membelah para penganjur revolusi ke dalam dua kelompok, yang oleh sosiolog Paolo Gerbaudo sebut sebagai kelompok techno-optimist dan kelompok techno-pessimist. Bagi kelompok pertama, revolusi Arab Spring membuktikan betapa pentingnya peran media sosial seperti facebook dan twitter. Bagi mereka, media sosial bukan lagi sekadar alat untuk membangun dan menyukseskan revolusi, tapi revolusi itu sendiri tak mungkin terjadi tanpa keberadaan media sosial. Karena itu revolusi Arab Spring ini disebut juga dengan nama Facebook Revolution.
Dengan media sosial, massa rakyat yang terpencar-pencar secara geografis dan politik bisa dimobilisasi dan dipersatukan oleh satu isu bersama. Dengan media sosial, revolusi tak lagi membutuhkan sebuah organisasi yang berbentuk vertikal, yang dipimpin oleh sebuah garis ideologis yang jelas, program-program politik yang tepat, strkutur organisasi yang ketat, serta pemimpin yang kharismatik. Melalui media sosial, organisasi yang cocok adalah yang bersifat horisontal, dengan ideologi yang beragam, organisasi yang longgar tanpa kepemimpinan politik yang berwibawa. Yang kita butuhkan adalah isu bersama yang disebarkan dan diorganisasikan lewat facebook dan twitter.
Tetapi, bagi kalangan techno-pessimist, peran media sosial dalam revolusi Arab Spring dan gerakan-gerakan rakyat lainnya terlalu dilebih-lebihkan. Bagi mereka, media sosial tidak lebih sekadar alat, alat, dan alat. Sementara revolusi adalah sebuah pekerjaan politik yang riil, yang dibangun melalui serangkaian pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi fisik, pengorganisiran-pengorganisiran massa, dan demonstrasi-demonstrasi yang berkelanjutan. Revolusi tidak mungkin terjadi hanya ketika orang bergabung dalam facebook walaupun jumlahnya jutaan, apalagi hanya dengan mengandalkan twitter. Revolusi bukan pekerjaan satu malam saja, yang tanpa sengaja meledak karena ada orang yang membuat grup facebook atau mentwit sesuatu secara iseng. Di mata kaum techno-pessimist, revolusi tidak mungkin bisa ditwiterkan (the revolution will not be tweeted). Kudeta militer terhadap presiden Mesir hasil pemilu Mohammed Morsi, pada Juni 2013 lalu adalah bukti dari gagalnya apa yang disebut ‘revolusi tanpa kepemimpinan (leaderless revolution).’
Lalu bagaimana sikap kita terhadap media sosial? Bagi kita hubungan media sosial dan pembangunan gerakan bersifat dialektis. Gerakan sosial-politik yang kuat hanya mungkin jika ada organisasi yang kuat. Itu berarti harus ada ideologi yang jelas, ada organisasi yang berakar pada basis massa, dan ada kepemimpinan yang kuat. Dan pembangunan organisasi yang kuat ini akan menjadi lebih mudah jika kita bisa menggunakan media sosial ini seefektif mungkin: sebagai alat penyebaran informasi, alat mobilisasi massa, dan lebih penting lagi sebagai medium pengorganisiran massa.
Melalui media sosial kita kabarkan kepada massa: ‘Ayo berkumpul, berdiskusi, mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk menuntut hak-hak kita yang diabaikan penguasa selama ini!!!’***