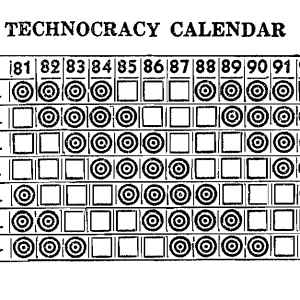Melanjutkan Diskusi Antonius Made Tony Supriatma
ARTIKEL Made Tony tentang Teror Sipil Sebagai Proxy, dengan sangat jernih menunjukkan betapa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islamis selama ini, ternyata didukung dan difasilitasi oleh Negara. Uraian dan kesimpulan Made Tony ini dengan telak mematahkan argumen bahwa ‘Negara kalah di hadapan kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu.’ Karena itu meminta agar Negara jangan kalah di hadapan FPI dan MMI telah salah ‘sejak dalam pikiran.’
Konsekuensi politik dari kesimpulan Made Tony ini sesungguhnya sangat radikal: ‘adalah keliru menuntut negara bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok Islamis tersebut.’ Saya sependapat dengan kesimpulan Made Tony, tetapi ingin mengambil jalan berbeda untuk tiba pada kesimpulan tersebut.
Transisi yang gagal
Sebenarnya, sejak tahun 2002 lalu, Thomas Carothees dalam artikelnya The End of the Transition Paradigm, yang dimuat dalam Journal of Democracy, telah menulis bahwa transisi demokrasi telah gagal. Dari studinya di hampir 100 negara yang betul-betul dipertimbangkan berada dalam periode ‘transisional,’ mungkin tidak lebih dari 20 negara yang nyata-nyata sedang berada pada rute menuju demokrasi. Sementara mayoritasnya tidak mengalami sukses berdemokrasi yang baik.
Dengan menggunakan parameter ‘demokrasi liberal’ mayoritas negara yang mengalami transisi itu, menurut Carothers terjebak pada apa yang disebutnya ‘zona politik abu-abu/the political gary zone.’ Maksudnya, negara-negara tersebut memang memiliki atribut dan kehidupan politik demokratis, seperti adanya ruang politik yang terbatas bagi partai-partai oposisi dan masyarakat sipil yang independen, pemilu yang reguler, pers yang bebas, tapi partisipasi warganya di luar mekanisme voting untuk memenangkan kepentingannya sangat rendah, terlampau seringnya penyalahgunaan hukum oleh pejabat pemerintah, pemilu yang diragukan legitimasinya, serta kepercayaan publik yang sangat rendah pada lembaga-lembaga negara.
Faktor lain yang menyebabkan transisi demokrasi mengalami kegagalan, menurut Carothers, karena negara-negara tersebut mengidap sindrom dominant power politics, yaitu terjadinya kekaburan antara kekuasaan negara dan partai berkuasa (atau kekuatan politik yang berkuasa). Akibatnya, korupsi dalam skala besar-besaran tak terhindarkan, kroni kapitalisme menggejala di kalangan elite, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik kembali marak terjadi. Menurut Carothers, sindrom dominan power politics ini sangat tampak di tiga wilayah, yakni di sub-sahara Afrika, negara-negara bekas Uni Sovyet, dan Timur Tengah pada pertengahan dekade 1980an. Jika Carothers menulis ulang artikelnya ini, maka sudah pasti ia akan memasukkan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dalam daftarnya ini.
Sayangnya Carothers tidak membicarakan faktor-faktor mendasar yang menyebabkan transisi hanya melahirkan ‘demokrasi formal.’ Made Tony sebenarnya telah menyinggungnya, karena negara a la Weberian tidak pernah ada di Indonesia. Pada titik inilah, saya ingin menantang analisa Made Tony ini.
Pengejawantahan Konsepsi Weberian
Pada dasarnya, mayoritas negara-negara yang mengalami transisi tidak hanya menghadapi krisis legitimasi politik, tapi bersamaan dengannya juga sedang diterpa krisis ekonomi yang parah. Dan riset-riset empiris menunjukkan, krisis politik yang berakhir dengan tumbangnya rejim-rejim otoritarian, diawali dengan ketidakmampuannya dalam memepertahankan stabilitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Latin, misalnya, krisis politik dimulai dengan krisis yang dialami oleh model pembangunan berorientasi impor (industrialisasi substitusi impor) yang diadopsi oleh rejim-rejim kediktatoran junta militer di kawasan tersebut.
Karena itu, dalam masa transisi persoalannya tidak saja bagaimana membangun sistem politik yang demokratis, juga soal membangun sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Itu pula sebabnya, pertanyaan utama para transitolog dan aktivis prodemokrasi adalah ‘bagaimana mencapai titik imbang antara keterbukaan politik dan kemakmuran ekonomi?’ Atau ‘bagaimana membangun dan mempertahankan tradisi berdemokrasi sembari membuka akses bagi mayoritas kaum miskin atas kesejahteraan?’ Dalam pertanyaan yang berbeda, ‘setelah rakyat memasuki era kebebasan sipil dan politik, adakah jaminan mereka memiliki akses yang adil pada sumber daya-sumber daya ekonomi yang langka: lapangan kerja yang tersedia, daya beli yang terjangkau, dan kemakmuran yang merata?’
Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh mendasar. John Sheahan, dalam analisanya terhadap masa depan transisi demokrasi di Brazil mengatakan, ‘peluang untuk mengonsolidasikan kebebasan politik akan terjamin atau malah terancam oleh kualitas kebijakan ekonomi yang diambil oleh rejim yang berkuasa.’ Studi yang sangat populer dilakukan oleh Adam Przeworski, yang menunjukkan bahwa demokrasi yang miskin ditandai oleh pendapatan per kapita kurang dari $1.000 per tahun.
Jika studi-studi empiris ini kita terima, maka pertanyaan lanjutannya, ‘bagaimana jalan untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita lebih dari $1.000 per tahun itu? Di sini, kita memasuki sebuah perdebatan ideologis (yang pura-pura diacuhkan atau malah di nista). Sebagian besar para transitolog semacam Przeworski percaya bahwa kemakmuran hanya akan dicapai jika pasar dibebaskan dari intervensi negara, sehingga tercipta kompetisi yang akan menghasilkan efisiensi dan produktivitas ekonomi yang tinggi, menciptakan sebuah masyarakat yang terdiferensiasi, dan perluasan ke arah pluralisme sosial dan pluralisme politik. Dengan kata lain, kebebasan dan pluralisme politik hanya mungkin eksis dalam sistem ekonomi pasar bebas. Dalam bahasa Przeworski, inilah transisi yang mengambil jalan ‘modernisasi melalui internasionalisasi/modernization via internationalization,’ atau yang populer disebut strategi Neoliberalisme.
Dalam kasus Indonesia, resep ini diadopsi secara utuh dan sistematis. Transisi yang terjadi duabelas tahun lalu, tidak hanya membebaskan ruang politik, mendesentralisasi kekuasan, membangun lembaga-lembaga politik demokratis, meminggirkan tentara dari parlemen, atau memberikan kebebasan pada pers, tapi juga memprivatisasi BUMN, meliberalisasi sektor perdagangan, jasa, dan keuangan, serta memberikan keleluasaan pada korporasi untuk mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam di wilayah-wilayah tertentu.
Kembali pada studinya Carothers, ternyata sebagian besar negara-negara yang menjalani transisi tersebut mengambil jalan yang diusulkan Przeworski, yaitu strategi modernisasi melalui internasionalisasi atau strategi neoliberalisme. Kebijakan neoliberal yang dijalankan secara agresif (di Rusia dan Amerika Latin, misalnya), ternyata berhasil menjerumuskan tingkat pendapatan mayoritas penduduknya ke tingkat yang sangat rendah: akses yang semakin terbatas pada sumber-daya-sumberdaya ekonomi, serta tingkat kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Ini artinya, politik liberal yang coba dijalankan gagal karena mengidap borok bawaan: kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Lalu, dimana posisi negara dalam strategi ini? Di sini, menurut saya, menoleh kepada Max Weber penting dilakukan. Dalam perspektif Weberian, ekonomi dan politik (dalam istilah Weberian ‘pasar’ dan ‘negara’) berhubungan secara eksternal, terpisah, dan saling berhadap-hadapan dan salah satu di antaranya memiliki logika yang independen. Misalnya, pasar punya logikanya sendiri yakni bersifat ekspansionis dengan tujuan menumpuk kekayaan sebesar-besarnya tanpa batas, sementara negara logikanya terbatas pada suatu wilayah geografis tertentu yang tujuannya untuk melayani kepentingan warga negaranya (harap dicatat, negara di sini adalah negara nasional, bukan negara imperial dalam pengertian Marxis). Implikasinya, pengaturan negara atas pasar jelas bertentangan dengan logika kapital yang bersifat global dan bebas melanglangbuana kemana saja itu. Konsekuensinya, jika ingin pasar bekerja maka harus diupayakan agar negara semakin melemah dan hanya berfungsi sebagai regulator yang memuluskan bekerjanya logika kapital. Dalam bahasa Friedrich von Hayek, ‘peran negara bukan untuk mengintervensi spontaneous order yang muncul dalam pasar, justru sebaliknya, negara harus melindungi spontaneous order tersebut dari intervensi manusia, apakah itu dari para politisi atau kelompok-kelompok kepentingan seperti serikat buruh.’
Berdasarkan uraian ini, jika Made Tony mengatakan bahwa Indonesia tidak mengenal konsep negara Weberian dalam kaitannya dengan penggunaan alat-alat kekerasan secara monopolistik sehingga kemudian menggunakan teror sipil sebagai proxy, saya justru melihat bahwa munculnya kelompok-kelompok vigilante macam FPI tersebut adalah konsekuensi dari pengejewantahan konsep Weberian itu sendiri. Lagi pula, tindak kekerasan negara sebenarnya tidak berkurang derajatnya dibandingkan dengan masa-masa orde baru berkuasa. Misalnya, dalam aksi-aksi petani, buruh, dan masyarakat adat, alat-alat kekerasan negara digerakkan secara besar-besaran untuk menghadapi aksi-aksi tersebut. Penggunaan alat-alat kekerasan negara juga berlangsung secara intensif dan massif di wilayah-wilayah tertentu seperti Papua. Yang terjadi adalah semacam pembagian tugas antara FPI dan Polisi/TNI: FPI bertugas menghadapi isu-isu kultural-horisontal, sementara polisi dan TNI bertanggung jawab membereskan isu-isu vertikal-struktural.
Di sini, penggunaan alat-alat kekerasan negara dan non-negara secara massif ini harus dilihat sebagai konsekuensi dari tidak terdamaikannya konflik antara kebebasan politik dan ketidakadilan ekonomi yang melekat pada masa transisi ini. Konsekuensi politiknya kemudian, perjuangan untuk melawan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI dan MMI, misalnya, bukan dengan cara menuntut pembubaran kelompok-kelompok ini, karena hari ini FPI bubar, besok segera muncul FPI-Sejahtera atau MMI-Moderat. Perlawanan terhadap FPI ‘harus diletakkan sebagai bagian dari perlawanan terhadap sistem ekonomi politik yang memberikan peluang pada berkembang-biaknya kelompok-kelompok ini: Kapitalisme-neoliberal.’***
Coen Husain Pontoh, mahasiswa ilmu politik di City University of New York (CUNY)