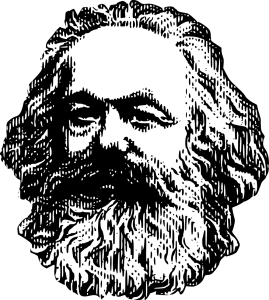Teori Nilai
TEORI nilai Marx merupakan salah satu teorinya yang paling rumit sekaligus paling kontroversial. Jika kita bisa melewati diskusi mengenai teori ini dengan lancar, maka diskusi mengenai topik-topik lainnya dalam Capital menjadi lebih mudah.
Teori nilai seringkali disebut berbarengan sebagai Teori Nilai Kerja (TNK). Menariknya, Marx sendiri tidak pernah menyebut teori nilai sebagai TNK. Sebutan ini pertama kalinya digunakan para pengritiknya dari kalangan ekonom mainstream, seperti Eugen von Böhm-Bawerk. Menjadi tambah populer ketika ekonom Marxist Rudolf Hilferding, memberikan kritik atas kritiknya Böhm-Bawerk terhadap Marx tersebut (Hiroyoshi, 2005:81).
TNK menjadi kontroversial, karena posisinya yang sangat fundamental dalam bangunan teori ekonomi politik Marx. Seperti dikemukakan Andrew Glyn, konsepsi tentang nilai, keuntungan, dan eksploitasi (value, profit and exploitation), merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan ekonomi Marxist. Dua pilar lainnya adalah teori tentang proses kerja (the labour process) dan teori tentang akumulasi kapital dan krisis (capital accumulation and crises) (Glyn in Eatwall et.al, 1990:274-75). Hal senada dikemukakan Rubin (1990:xxix) bahwa teori tentang pemujaan komoditi (commodity fetishism) dan lebih khusus lagi TNK, merupakan basis dari keseluruhan sistem ekonominya Marx. Lebih lanjut dikatakannya, hanya setelah kita menemukan basis dari TNK, barulah kita bisa memahami apa yang Marx tulis dalam bab pertama Capital Volume I (ibid:61). Mungkin ini sebabnya, mengapa Fine dan Harris (1979:34) sampai mengatakan, ‘menolak TNK sama artinya dengan menolak metode Marx.’
Karena posisinya yang sangat fundamental itu, TNK menjadi sasaran empuk para pengritik teori ekonomi Marxis. Di kalangan Marxis sendiri perdebatan mengenai teori ini tak kalah serunnya. Namun demikian, tulisan ini tidak akan masuk pada kontroversi itu. Tujuan tulisan ini untuk menunjukkan bagaimana Marx menjabarkan teori nilai dan melihat lebih jauh esensi dari teori ekonomi politik Marxis.[1]
***
Baik, mari kita mulai Kajian ini dengan mengutip geografer David Harvey. Dalam salah satu buku terkenalnya The Limits to Capital Harvey mengatakan, kita tidak akan bisa menafsirkan apa itu nilai (value) tanpa terlebih dahulu memahami pengertian tentang nilai-guna (use-value) dan nilai-tukar (exchange-value). Demikian sebaliknya, mustahil menafsirkan dua nilai terakhir tanpa memahami apa itu nilai. Masih menurut Harvey, Marx tidak pernah memperlakukan masing-masing konsep itu secara terisolasi, tapi senantiasa memfokuskan ketiganya dalam sebuah relasi yang mungkin: antara nilai-guna dan nilai-tukar, antara nilai-guna dan nilai, dan antara nilai-tukar dan nilai ((2006:2).

Kita ikuti perlahan maksud Harvey ini. Dalam kapitalisme, tujuan utama dari produksi komoditi bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, melainkan untuk mengakumulai keuntungan setinggi-tingginya tanpa henti melalui pasar. Melalui pasar itulah orang lantas memenuhi kebutuhannya. Misalnya, ketika seorang kapitalis membuka usaha restoran, tujuan utamanya bukanlah memberi makan orang yang belum makan, melainkan menjual hasil masakannya itu kepada pembeli yang bisa membayar sesuai harganya. Tetapi, agar komoditi itu bisa dipertukarkan/diperjualbelikan maka komoditi tersebut pertama-tama harus memiliki nilai-guna. Dalam contoh pengusaha restoran tadi, nilai-guna masakannya itu adalah untuk mengenyangkan si pembeli. Dengan demikian, nilai-guna berurusan dengan persoalan personal, soal selera individual. Semakin masakan itu enak dan mengenyangkan si pembeli individual, maka ia akan sukarela mengeluarkan uangnya untuk membeli masakan tersebut.
Dan seperti yang telah kita diskusikan di bagian pertama Kajian ini, baik nilai-guna maupun nilai-tukar melekat pada satu komoditi yang sama. Dengan begitu, komoditi bukanlah sebuah barang kepemilikan yang bersifat ‘natural,’ melainkan barang kepemilikan yang bersifat ‘sosial.’ Artinya, hanya dalam masyakat dimana barang-barang itu dipertukarkan maka barang tersebut memiliki nilai-tukar, yakni barang tersebut merupakan komoditi (Heinrich, 2012:40). Kalau kita ambil contoh masakan di atas, maka masakan tersebut memiliki ‘bentuk natural’ karena ia terdiri dari sejumlah barang seperti nasi, ikan, sayur, sambal, air, dst yang terasa enak dan mengenyangkan. Tetapi, masakan tersebut berubah menjadi ‘bentuk sosial’ karena masakan itu telah menjadi komoditi, bahwa masakan itu dipertukarkan dan karenanya ia memiliki ‘nilai-tukar.’ Singkatnya, masakan itu menjadi komoditi tidak dicirikan oleh masakan itu sendiri melainkan oleh sistem sosial dimana masakan (barang) itu eksis (ibid., h.41). Dalam hal ini Marx sedang membicarakan tentang sistem sosial (masyarakat) kapitalis.
Nah, sekarang kalau kita pergi ke pasar maka di sana kita jumpai seribu satu macam jenis komoditi yang saling dipertukarkan setiap harinya. Jika Anda tertarik dan punya uang maka komoditi itu segera berpindah tangan menjadi milik Anda. Dan ada begitu banyak orang seperti Anda yang lalu-lalang di pasar, baik teman, keluarga, handai-tolan, maupun orang yang sama sekali tidak kita kenal.
Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan beragam jenis komoditi itu bisa saling dipertukarkan? Misalnya, jika sepasang sepatu di tukar dengan sekilo beras, dan semeter kain, dst, apa yang membuat pertukaran itu menjadi mungkin? Atau, apa yang menyebabkan saya atau Anda membeli celana jeans dan orang lain membeli jam tangan, serta orang lainnya lagi membeli buku? Tentu saja jawabannya karena barang-barang itu memiliki nilai. Dalam contoh di atas, maka sepasang sepatu itu memiliki nilai yang setara dengan sekilo beras dan semeter kain. Artinya, barang-barang ini memiliki nilai yang sama. Ketika Anda beli celana jeans dan orang lain beli jam tangan, maka pada diri Anda dan orang lain tersebut kedua barang itu memiliki nilai yang sama.
Tetapi, apa nilai yang sama yang melekat pada komoditi yang saling dipertukarkan tersebut? Jauh sebelum Marx, para ahli ekonomi politik coba memberikan jawaban bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya (usefulness): untuk barang yang sangat berguna buat kita maka kita bersedia membayarnya seberapa pun besar ongkos yang dibutuhkan. Bahkan, jika perlu, nyawa kita dan nyawa orang lain kita korbankan. Begitu sebaliknya, jika barang tersebut kurang kegunannya buat kita, jelas kita tak akan membelinya atau kalau terpaksa maka kita akan menawar barang tersebut semurah mungkin. Masuk akal bukan? Tetapi yang masuk akal tidak berarti benar.
Adalah bapaknya ekonom Adam Smith yang menunjukkan ketidakbenaran hal yang masuk akal itu, melalui pemisalannya tentang air. Katanya, tidak ada yang membantah betapa bermanfaatnya air buat kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air, tetapi nilai air sesungguhnya sangat kecil (jika Smith hidup di zama kita, tentu ia akan merevisi contohnya tentang air ini, sebab kini air telah menjadi komoditi seperti halnya beras). Bandingkan dengan berlian, dimana manfaatnya buat kita terbatas (kita tak akan mati jika tak pakai berlian) tetapi nilainya sangat besar (Heinrich, op.cit, h.42). Kenapa bisa demikian?

Marx mengatakan, ketiga komoditi itu bisa saling dipertukarkan karena ketiganya memiliki skala (magnitude) yang identik. Selanjutnya ia mengatakan: (1) validitas nilai-tukar sebuah komoditi tertentu mengekspresikan sesuatu yang setara; (2) nilai-tukar tidak bisa tidak melainkan sebuah corak ekspresi (mode of expression), ‘bentuk yang tampak (form of appearance),’ dari isi yang berbeda (Capital, h.127). Ia memberikan contoh, jika dua produk dipertukarkan, katakanlah 1kg baja ditukar dengan 1 karung jagung, maka pertukaran di antara keduanya terjadi karena ada sesuatu yang merepresentasikan kesetaraan, sehingga 1kg baja = 1karung jagung, dan kesetaraan yang melekat pada masing-masing produk itu, sejauh masih dalam konteks nilai-tukar, bisa diredusir pada produk yang ketiga (Capital, ibid). Sederhananya, jika kualitas bersama itu tidak ada, tidak mungkin terjadi pertukaran di antara barang-barang tadi.
Sampai di sini, gagasan Marx tentang pertukaran ini bisa ditelusur akarnya pada pemikiran Aristoteles, yang mengatakan, pertukaran tidak akan terjadi tanpa kesetaraan (equality), dan kesetaraan tidak mungkin ada tanpa adanya standar ukuran yang sama (commensurability).
Apa standar ukuran yang sama itu? Menurut Marx, elemen yang sama itu tidak bisa berbentuk geometrik, fisikal, kimiawi, atau komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh alam. Misalnya, ukuran alamiah itu adalah panjang, berat, kepadatan, warna, ukuran, sifat molekul, dsb. Apakah 1kg beras sama kualitasnya dengan 1kg emas, yang memungkinkan keduanya dipertukarkan? Tentu saja tidak! Singkatnya, apapun yang membuat kualitas fisik atau kimiawi yang melekat pada komoditi, pasti menentukan nilai guna komoditi tersebut, karena itu memiliki nilai-guna relatif, tetapi itu bukan nilai-tukar. Nilai-tukar, mesti dipisahkan (abstracted) dari apapun yang mengandung kualitas fisik alami dari komoditi (Mandel, 2006:36).
‘Kita telah melihat, ketika komoditi berada dalam hubungan pertukaran, nilai-tukar mereka manifes (menjelma) pada dirinya sendiri sebagai sesuatu yang secara total independen dari nilai-guna mereka. Tetapi, jika kita memisahkan nilai-guna komoditi tersebut, yang tetap darinya adalah nilai, sebagai sesuatu yang baru saja didefinisikan. Oleh sebab itu, faktor bersama dalam hubungan pertukaran, atau di dalam nilai-tukar sebuah komoditi, adalah nilai itu sendiri’ (Capital, h.128).[2]
Dengan demikian, nilai tukar tidak lain adalah corak ekspresi yang dibutuhkan (necessary mode of expression), atau bentuk yang tampak (form of appearance) dari nilai (Capital, loc.cit). Tetapi, darimana nilai itu berasal? Di sinilah Marx menimba inspirasinya dari Adam Smith dan David Ricardo. Kembali pada contoh air dan berlian yang dikemukakan Smith sebelumnya, berlian menjadi lebih bernilai dari air karena ‘kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi kedua barang ini berbeda.’ Lebih konkretnya adalah ilustrasi paling terkenal dari Smith berikut,
‘Jika dalam sebuah masyarakat yang hidupnya tergantung pada berburu, sebagai contoh, maka biasanya ongkos (cost) kerja untuk membunuh berang-berang (beaver) adalah dua kali lipat ketimbang yang dibutuhkan untuk membunuh rusa (deer), maka satu berang-berang seharusnya nilainya sama dengan dua ekor rusa. Adalah wajar jika apa yang biasanya diproduksi selama dua hari atau dua jam kerja, semestina dihargai dobel dengan apa yang biasanya diproduksi dalam satu hari atau satu jam kerja’ (Vianello, in Eatwell et.al, op.cit, 233) .
Ricardo sendiri mengatakan, ‘nilai sebuah komoditi, atau kuantitas dari setiap komoditi lainnya yang memungkinkannya dipertukarkan, tergantung pada kuantitas relatif dari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditi tersebut, bukan pada besar-kecilnya kompensasi yang dibayarkan kepada buruh tersebut’ (Meek, 1956:97). Di sini, baik Smith maupun Ricardo mengidentikkan nilai dengan kerja.
Konsep ini kemudian diadopsi Marx. Dalam karyanya Value, Price anf Profit (VPP) ia secara jelas mengatakan substansi sosial bersama yang dikandung oleh komoditi yang saling dipertukarkan itu adalah kerja. ‘Untuk memproduksi sebuah komoditi,’ tulisnya dalam VPP, ‘maka dibutuhkan tenaga kerja untuk itu atau ada kerja yang dikeluarkan terhadapnya’ (Zarembka, ed., 2000:14). Ia memberikan contoh: satu ons emas, satu ton besi, seperempat kg terigu, dan 20 yards sutra, adalah nilai-tukar dengan ukuran yang setara. Sebagai nilai-tukar, jika perbedaan kualitatif dari nilai-guna ketiganya dihilangkan, maka yang tersisa dari ketiganya adalah representasi jumlah yang setara dari kerja yang sama (Critique, h.29). Tesis ini dipertegasnya dalam Capital, bahwa nilai-guna atau barang yang berguna hanya memiliki nilai karena kerja manusia dalam bentuk abstrak atau disebut juga waktu kerja sosial (social necessary labour) yang melekat atau termaterialisasikan ke dalamnya (Capital, h.129). Dalam VPP ia menjelaskan dengan kalimat yang berbeda,
‘Dan aku mau bilang tidak hanya Kerja (Labor), tetapi Kerja Sosial (Social Labor). Manusia yang memproduksi sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya, untuk dikonsumsinya sendiri, maka ia menciptakan sebuah produk, tapi bukan sebuah komoditi. Sebagai produser yang mandiri ia tidak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan masyarakat. Tetapi untuk memproduksi komoditi, maka manusia tidak hanya memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu, tetapi kerjanya itu sendiri harus menjadi bagian dan paket dari keseluruhan total kerja yang dikeluarkan masyarakat. Kerja itu mesti disubordinasikan di bawah Pembagian kerja dalam masyarakat (Division of labor within society). Tetapi ini tak akan berarti apa-apa tanpa pembagian kerja yang lain, dan bagian itu dibutuhkan untuk menyatukan mereka’ (Zarembka, op.cit, 14; huruf miring dari Marx).[3]
‘Sebuah benda bisa memiliki nilai-guna tanpa memiliki nilai. Dalam hal ini, adalah benda apapun yang bisa memuaskan kebutuhan manusia tapi tidak dimediasi melalui kerja. Udara, tanah perawan, padang rumput, hutan yang belum terjamah, dst, bisa dimasukkan dalam kategori ini’ (Capital, h. 131).[4]
Apa yang dimaksud dengan waktu kerja sosial ini? Marx menjawab,
‘Waktu-kerja sosial yang dibutuhkan socially necessary labour-time ) itu adalah waktu-kerja yang diperlukan untuk memproduksi setiap nilai-guna di bawah kondisi-kondisi produksi yang normal dalam masyarakat dan dengan rata-rata derajat keahlian dan intensitas kerja yang lazim dalam masyarakat (Capital, h.129).[5]
Tapi, kini kita dihadapkan pada pertanyaan baru, bagaimana mengukur kerja abstrak tersebut? Kita telah tahu bahwa nilai-guna tidak bisa dijadikan ukuran, karena nilai-guna merupakan hubungan personal antara manusia dengan benda. Karena saya suka I-phone dan Anda lebih tertarik pada Blackberry, maka ukuran nilai-guna ini tidak bisa menjelaskan mengapa komoditi secara konsisten dipertukarkan dalam rasio yang stabil. Ini berbeda dengan kerja manusia yang melekat pada komoditi yang bisa diukur secara obyektif, yang secara kuantitas diukur berdasarkan durasi kerja atau waktu kerja (labour-time) dan tenaga kerja itu sendiri diukur dalam skala tertentu seperti jam, hari, minggu, dst. (Capital: h.129).
Tetapi, jika nilai sebuah komoditi diukur berdasarkan waktu kerja yang dibutuhkan (necessary-labour time) untuk memproduksinya, di sini kita akan langsung berhadapan dengan soal yang membuat kita tampak bodoh: semakin lambat (idle), malas (lazy), dan tidak terampilnya seorang buruh (unskilled labor/simple labor)), maka semakin besarlah nilai dari komoditi yang diproduksinya, karena semakin panjang waktu yang dihabiskannya untuk memproduksi komoditi tersebut. Sebaliknya, nilai dari komoditi yang dihasilkan oleh buruh terampil (skilled labor/complex labor) lebih kecil karena waktu yang digunakan untuk memproduksi komoditi tersebut lebih kurang.
Untuk memperjelas pertanyaan ini, mari kita lihat ilustrasi matematis dari Edward B. Aveling berikut: katakanlah V adalah simbol dari nilai, dan Q adalah simbol dari kuantitas kerja yang melekat pada komoditi. Karena nilai sebuah komoditi bergantung pada kerja manusia yang melekat padanya, maka makin besar Q, makin besar pula V; begitu sebaliknya.
Hubungan ini disimbolkan menjadi V ∞ Q.
Kini, kita masukkan variabel produktivitas kerja, yang oleh Aveling diberi simbol P. Jika P berkurang, maka waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditi (Q) bertambah, dengan demikian, V juga bertambah; sebaliknya, jika P bertambah maka Q berkurang dan otomatis V pun berkurang. Artinya, V tidak berkaitan langsung dengan P tetapi, merupakan kebalikannya.
Hubungan kedua ini disimbolkan menjadi V ∞ 1/P.
Jika kedua pernyataan ini digabung, V ∞ Q dan V ∞ 1/P, maka kesimpulannya, nilai sebuah komoditi berhubungan langsung dengan kuantitas waktu kerja yang melekat padanya dan berkebalikan dengan produktivitas kerja yang ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi-kondisi fisik dan sosial, dsb. (Avelling, 2005:2-3).
Apa konsekuensi logis dari teori ini? Karena nilai komoditi ditentukan oleh waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, maka buruh akan berlomba-lomba untuk menjadi malas dan enggan untuk meningkatkan kertrampilannya agar bayarannya semakin besar. Tidak ada motivasi berprestasi, karena tidak ada insentif bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Kesimpulannya, teori nilai Marx bukan hanya lucu tapi sepenuhnya salah karena tidak mengindahkan kualitas individual dari setiap pekerja.
Konsekuensi lain dari teori ini adalah direduksinya tenaga kerja terampil (skilled labour) menjadi tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Meek (op.cit:168) memberikan contoh terhadap masalah ini: rata-rata tingkat keterampilan (average degree of skill) boleh jadi dominan di satu industri pada waktu tertentu, tapi menjadi subordinatif di waktu yang lain; dan keseimbangan harga komoditi yang diproduksi oleh buruh yang relatif lebih terampil secara umum lebih mahal, dalam hubungannya dengan jumlah jam kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, ketimbang dengan komoditi yang diproduksi oleh buruh yang relatif tidak terampil.
Bagaimana Marx menjelaskan soal ini? Menyambung penjelasannya soal nilai, dalam Value, Price, and Profit, Marx mengatakan,
‘Kamu mungkin masih ingat bahwa aku menggunakan kata ‘kerja sosial,’ dan banyak hal yang berkaitan dengan kualifikasi ‘sosial’ ini. Dengan mengatakan bahwa nilai sebuah komoditi ditentukan oleh kuantitas kerja yang dipekerjakan atau yang mengkristal di dalamnya, kita maksudkan kuantitas kerja yang dibutuhkan untuk produksi dalam masyarakat yang ada, di bawah rata-rata kondisi produksi sosial tertentu, dengan intensitas rata-rata masyarakat saat itu, dan rata-rata ketrampilan buruh yang dipekerjakan. Ketika di Inggris, mesin tenun datang berkompetisi dengan tenun tangan, maka pada yang pertama hanya setengah waktu kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan sejumlah benang tenun menjadi kapas atau kain. Tukang tenun tangan yang miskin kini terpaksa bekerja 17 atau 18 jam sehari, ketimbang bekerja selama 9 atau 10 jam sehari seperti sebelumnya. Namun demikian produk dari 20 jam kerjanya kini hanya merepresentasikan 10 jam kerja, atau 10 jam dari kerja sosial yang dibutuhkan untuk mengkonversi sejumlah tertentu kapas menjadi bahan-bahan tekstil. Produk dari 20 jam, dengan demikian tak lagi bernilai dibandingkan dengan produk yang dihasilkannya dalam 10 kerja sebelumnya’ (Zarembka, op.cit, h.16; huruf miring dari Marx).[6]
Dari kutipan ini kita temui dua keadaan: pertama, jika kuantitas kerja sosial yang dibutuhkan terealisasi dalam pengaturan komoditi yang memiliki nilai-tukar adalah konstan, nilai dari komoditi tersebut adalah juga konstan. Jika perusahaan A secara konstan memiliki 10 orang buruh untuk memproduksi 100 kemeja setiap harinya, maka nilai dari produksi kemeja tersebut tidak berubah. Kini kita masukkan unsur perkembangan teknologi ke dalam perusahaan A tersebut, maka konsekuensinya perusahaan A yang mempekerjakan 10 orang buruh tersebut kini memproduksi 200 kemeja setiap harinya dengan waktu kerja yang jauh lebih sedikit ketimbang sebelumnya. Akibatnya, nilai tambah dari kemeja tersebut semakin berkurang, sehingga hasilnya kemudian nilai dari komoditi tersebut juga semakin rendah.
Dari kutipan ini kita temui dua keadaan: pertama, jika kuantitas kerja sosial yang dibutuhkan terealisasi dalam pengaturan komoditi yang memiliki nilai-tukar adalah konstan, nilai dari komoditi tersebut adalah juga konstan. Jika perusahaan A secara konstan memiliki 10 orang buruh untuk memproduksi 100 kemeja setiap harinya, maka nilai dari produksi kemeja tersebut tidak berubah. Kini kita masukkan unsur perkembangan teknologi ke dalam perusahaan A tersebut, maka di sini perusahaan A dihadapkan pada dua pilihan: (1) jika ia ingin mempertahankan jumlah produksinya 100 kemeja setiap harinya, maka ia harus mengurangi jumlah buruhnya dari 10 menjadi kurang dari 10 orang; (2) ia mempertahankan 10 buruhnya tapi jam kerjanya dikurangi; atau (3) ia mempertahankan 10 buruhnya dengan jam kerja yang seperti semula dan hasilnya kini perusahaannya memproduksi 200 kemeja setiap harinya. Apapun pilihannya, nilai komoditi tersebut kini tidak lagi konstan, dimana nilai dari kemeja tersebut menjadi lebih rendah.
Kedua, Marx selalu berbicara tentang sistem produksi kapitalisme dalam sebuah totalitas, bukan bagian per bagian, atau wilayah per wilayah secara terisolasi. Ketika ia mengatakan waktu kerja sosial yang dibutuhkan, hal itu bermakna waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi nilai dalam sebuah totalitas sistem sosial kapitalistik yang eksploitatif, kompetitif, revolusioner, ekspansif, serta krisis internal yang tak terdamaikan antara produk yang semakin tersosialisasi versus akumulasi profit yang makin tersentralisasi. Dengan demikian, ketika perusahaan A dalam contoh di atas mengintrodusir input teknologi dan hukum kerja yang baru, maka perusahaan lainnya yang memproduksi barang sejenis dengan perusahaan A juga akan melakukan hal yang sama agar tetap eksis dalam sistem ini. Demikian seterusnya hal ini berlangsung pada level cabang produksi, wilayah, negara, dan seterusnya. Karena tingkat teknologi, modus organisasi produksi, dst., relatif serupa, maka jam kerjanya juga tak jauh berbeda dan bisa dirata-rata.
Tetapi masih ada hal yang belum begitu terang di sini, yakni penekanan Marx kerja sosial. Apakah yang dimaksudkannya adalah antitesa kerja individual? Di sini, kita kerap bertemu dengan kesalahpahaman luar biasa dalam memahami teori nilai Marx. Jika kita membaca teori nilai secara vulgar, bahwa nilai komoditi diukur dari berapa banyak jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, maka kita pada akhirnya akan menempatkan jumlah kerja itu ke dalam lajur biaya (cost) produksi dalam tabel cost-benefit. Artinya, kita kemudian menempatkan tenaga kerja setara dengan faktor-faktor produksi lainnya, seperti mesin, tanah, bangunan, dst. Tanpa sadar kita kembali pada postulat ekonomi non-Marxis bahwa nilai sebuah komoditi ditentukan oleh seberapa bergunanya barang itu buat kita.
Dalam bahasa Heinrich(op.cit, 45-47), jika nilai sebuah komomditi dilihat terutama pada seberapa banyak waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditi tersebut, maka Marx sesungguhnya tidak pernah melangkah lebih jauh dari pandangannya para ekonom klasik. Judul bukunya bukan lagi Capital A Critique of Political Economy, melainkan Capital An Explanation of Political Economy. Penjelasan yang berangkat dari posisi ini pada akhirnya membuat kita terjebak pada pertimbangan-pertimbangan rasional individu yang terisolasi. Ekonom neoklasik modern juga bertolak dari pengandaian yang sama bahwa maksimalisasi kegunaan individual (utility-maximizing individual), merupakan titik berangkat untuk menjelaskan hubungan pertukaran yang berbasis pada estimasi kegunaan. Dari titik berangkat individu yang terisolasi ini, baik ekonom klasik maupun neoklasik kemudian berusaha menjelaskan keseluruhan perkembangan masyarakat. Pada mula dan akhirnya adalah individu
Menurut Heinrich, Marx sebaliknya mengatakan bahwa masyarakat bukanlah hasil dari penjumlahan individu-individu yang terisolasi satu sama lain, sehingga kualitas individu menentukan kualitas masyarakat. Yang fundamental bagi Marx adalah hubungan sosial (social relations) dimana individu itu melekat, sehingga individu di sini mesti menyesuaikan dirinya dengan kondisi-kondisi sosial dimana ia eksis. Jika ia gagal menyesuaikan diri maka ia akan tergilas dari hubungan sosial tersebut.
‘Dalam produksi sosial dari keberadaannya, manusia tak terelakkan masuk ke dalam hubungan tertentu, yang independen dari keinginannya, yakni hubungan produksi yang sesuai dengan tahapan tertentu perkembangan kekuatan produksi materialnya’ (Critique, h.21).[7]
Mari kita ambil contoh konkret berikut. Dalam kapitalisme, untuk bisa hidup individu tersebut harus mengikuti logika masyarakat kapitalis, bahwa produksi terutama ditujukan untuk akumulasi kapital tanpa batas yang dimediasi oleh pasar yang impersonal. Sebagai pengusaha, misalnya, Anda tidak bisa seenak perutnya menjual komoditi Anda tanpa mengindahkan tingkat harga, bunga bank, dan persaingan dengan pengusaha lainnya yang ada di sekeliling Anda. Jika Anda tidak peduli dengan kondisi-kondisi tersebut, misalnya, dengan menjual barang lebih mahal dari pesaing Anda atau menjual barang semurah-murahnya karena rasa belas kasih pada si miskin, maka bisa dipastikan bisnis Anda akan gulung tikar. Dengan demikian, untuk bisa memenangkan kompetisinya di pasar maka Anda harus terus-menerus meningkatkan produktivitas kerja buruh setinggi-tingginya dengan tingkat upah serendah-rendahnya. Eksploitasi kapital terhadap buruh dengan demikian merupakan keniscayaan terlepas dari urusan moral individu kapitalis. Demikian juga bagi seorang buruh individual. Ia memang seorang individu bebas, ia bisa bekerja atau tidak bekerja sekehendak hatinya tanpa ada yang bisa memaksanya. Tapi, untuk bisa hidup dan meningkatkan potensi-potensi kemanusiaannya, mau tak mau ia harus bekerja, menjual tenaganya kepada si kapitalis. Tapi, ia pun bisa berhenti dari pekerjaannya pada individu kapitalis tertentu dan pindah ke individu kapitalis lainnya sesuka hatinya. Ia bebas berpindah dari satu kapitalis ke kapitalis lainnya, tapi ia tidak bisa keluar dari sistem produksi kapitalis tersebut. Di sini pertimbangan rasionalitas individual menyesuaikan dirinya dengan kondisi hubungan sosial yang melingkupinya.
Dengan kata lain, teori nilai Marx tidak berurusan dengan pertimbangan-pertimbangan mereka yang terlibat dalam proses pertukaran secara individual. Tidak juga nilai sebuah komoditi berkorespondensi dengan waktu kerja sosial yang dibutuhkan untuk produksi hanya karena mereka yang terlibat dalam pertukaran menghendakinya. Apa yang hendak Marx tuju dengan teori ini adalah menjelaskan struktur sosial yang khusus dimana individu harus menyesuaikan diri dengannya, tanpa menghiraukan apa yang sebenarnya mereka pikirkan (huruf miring dari Heinrich). Singkatnya, teori nilai bukanlah ‘bukti’ bahwa tindakan pertukaran individual ditentukan oleh produktivitas waktu kerja sosial yang dibutuhkan. Sebaliknya, ia hendak menjelaskan karakter sosial khusus dari kerja yang memproduksi komoditi. Dari sini kita kemudian bisa mengetahui perbedaan Marx dengan kalangan ekonom klasik dan neoklasik:
‘Adam Smith mengobservasi satu tindakan pertukaran dan bertanya bagaimana akhir dari pertukaran bisa ditentukan. Marx melihat hubungan pertukaran individual sebagai bagian dari totalitas masyarakat – sebuah totalitas dimana reproduksi masyarakat diperantarai oleh pertukaran – dan bertanya apa artinya ini bagi kerja yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat’ (Heinrich, 47).
Dari pemaparan Heinrich ini, maka penjelasan Rubin bahwa ‘teori nilai tidak berurusan dengan kerja sebagai sebuah faktor teknikal produksi, tapi dengan aktivitas kerja orang-orang sebagai basis bagi kehidupan sosial, dan dengan bentuk-bentuk sosial dalam mana kerja itu hadir’(ibid:82) menjadi benar adanya. Dengan kata lain, esensi dari teori nilai adalah menempatkan hubungan antar manusia sebagai hal yang pertama dan terutama, bukan hubungan antara manusia dengan benda, apalagi hubungan di antara benda-benda. Ronald E. Meek (opcit: 145), memberikan deskripsi yang menarik soal esensi ini, dengan menekankan bahwa nilai, bagi Marx, menampakkan dirinya dalam wujud ekspresi hubungan produksi di antara manusia (production relation between man) dalam masyarakat kapitalis. Inilah inti dari ekonomi Marxian,
‘ilmu ekonomi tidak berurusan dengan benda-benda tapi dengan hubungan di antara person, dan pada akhirnya, hubungan di antara kelas-kelas; namun demikian, hubungan tersebut selalu melekat pada benda-benda dan tampak sebagai benda-benda’ (Engels in Howard & King, 1985:43; huruf miring dari Engels).
***
Sekarang, kita memasuki satu persoalan lain berkaitan dengan kerja ini. Ketika Marx bicara kerja, maka yang terang ia bicara adalah kerja yang memproduksi komoditi yang melulu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisikal, yakni barang-barang yang bersifat material. Bagaimana dengan mereka yang bekerja tapi tidak memproduksi barang-barang material? Misalnya, mereka yang bekerja di sektor jasa pelayanan dan keuangan, seperti sopir taksi, teller bank, penjaga keamanan, atau konsultan bisnis?
Perkara kerja imaterial ini, terutama dalam perkembangan kapitalisme finansial saat ini, dianggap tidak bisa lagi dijelaskan oleh teori nilai Marx. Dan karena itu Marxisme tidak lagi relevan, karena unit analisanya adalah kapitalisme industrial yang terbatas pada lokasi pabrik tertentu.
Untuk mengatasi soal ini, mari kembali menengok tesis Harvey yang tertera pada bagian awal artikel ini. Awalnya kita mengetahui bahwa komoditi memiliki dua aspek: nilai-guna dan nilai-tukar. Agar komoditi bisa dipertukarkan maka ia harus memiliki nilai-guna, yang disebut sebagai nilai-guna sosial. Nilai-tukar itu sendiri merupakan pencerminan dari sesuatu, yang kata Marx, pencerminan dari nilai. Dan nilai tidak lain adalah waktu kerja sosial yang dibutuhkan. Tetapi nilai tidak berarti apapun kecuali jika ia berhubungan kembali dengan nilai-guna. Nilai-guna dengan demikian adalah kebutuhan sosial bagi nilai.
Nah berkaitan dengan kerja imaterial, jika kita membatasinya sekadar bahwa ia memiliki nilai-guna, maka terang sudah bahwa aktivitas pelayanannya itu bukan sebuah komoditi. Tapi, sekali lagi, ini bukan definisi Marx, melainkan definisinya ekonom non-Marxis. Bagi Marx, seperti yang telah kita diskusikan di atas, komoditi tidak dicirikan bentuk naturalnya (kini bisa kita tambahkan bentuk fisikalnya) melainkan oleh sistem sosial dimana komoditi itu eksis. Ketika aktivitas pelayanan itu telah diperjualbelikan, secara otomatis ia merupakan komoditi. Tentu saja ada perbedaan antara produk material dan produk imaterial, yakni pada hubungan temporal antara produksi dan konsumsi (Heinrich, op.cit., h.44). Jika pada produk material maka ia harus diproduksi terlebih dahulu lalu dikonsumsi, sementara produk imaterial antara tindakan produksi dan konsumsi terjadi secara berbarengan.
¶
Kepustakaan:
Ernest Mandel, An Introduction to Marxisr Economic Theory, Pathfinder Press, 2006.
David Harvey, The Limits to Capital, Verso, 2006.
———-, A Companion To Marx’s Capital, Verso,2010.
Hayashi Hiroyoshi, Marx’s Labor Theory of Value A Defense, iUniverse, Inc., 2005.
I.I. Rubin, Essays on Marx’s Theory of Value, Black Rose Books, 1990.
John Eatwell et.al., (ed.), Marxian Economics, W.W. Norton & Company, Inc, 1990.
Karl Marx, A Contribution To The Critique of Political Economy, International Publisher, NY, 1989.
———-, Capital Volume I, Penguin Books, 1990.
M.C. Howard & J.E. King, The Political Economy of Marx, New York University Press, 1988.
Paul Zarembka, Value, Capitalist Dynamics, and Money, Emerald Group Publishing, 2000.
Ronal L. Meek, Studies in the Labor Theory of Value, Monthly Review Press, 1956.
[1] Bagi yang tertarik mendalami lebih jauh perdebatan soal TNK ini, sila baca Paul M. Sweezy (ed), Karl Marx and the Close of His System by Eugen von Bӧhm-Bawerk & Bӧhm-Bawerk’s Criticism of Marx by Rudolf Hilferding, Augustus M. Kelley, NY, 1949; sebuah uraian singkat mengenai perdebatan di kalangan Marxis sendiri, lihat Alfredo Saad-Filho, The Value of Marx Political economy for contemporary capitalism, Routledge, London and NY, 2002; buku lain yang menampilkan perspektif berbeda dalam membahas capital adalah yang diedit oleh Richard Westra and Alan Zuege, Value and the World Economy Today Production, Finance and Globalization, Palgrave MacMillan, 2003; dan Diane Elson (ed.), Value The Representation of Labour in Capitalism, Humanities Press Inc., New Jersey, 1979.
[2] Kutipan aslinya, ‘We have seen that when commodities are in the relation of exchange, their exchange value manifests itself as something totally independent of their use-value. But if we abstract from their use-value, there remains their value, as it has just been defined. The common factor in the exchange relation, or in the exchange-value of the commodity, is therefore its value.’
[3] Kutipan aslinya: ‘And I say not only Labor, but Social Labor. A man who produces an article for his own immediate use, to consume it himself, create a product, but not a commodity. As a self-sustaining producer he has nothing to do with society. But to produce a commodity, a man must not only produce an article satisfiying some social want, but his labor itself must form part and parcel of the total sum of labor expended by society. It must be subordinate to the Division of Labor within Society. It is nothing without the other divisions of labor, and on its part is required to integrate them.’
[4] Kutipan aslinya, ‘A thing can be a use-value without being a value. This is the case whenever its utility to man is not mediated through labour. Air, virgin soil, natural meadows, unplanted forests, ets, fall into this category.’
[5] Kutipan aslinya, ‘Socially necessary labour-time is the labour-time required to produce any use-values under the conditions of production normal for a given society and with the average degree of skill and intensity of labour prevalent in that society.’
[6] Kutipan aslinya: ‘You will recollect that I used the word “Social labor,” and many points are involved in this qualification of “social.” In saying that the valuer of a commodity is determined by the quatity of labor worked up or crustalized in it, we mean the quantity of labor necessary for its production in a given state of society, under certain social average conditions of production, with a given social average intensity, and average skill of the labor employed. When, in England, the power-loom came to compete with the hand-loom, only half the former time of labor was wanted to convert a given ampunt of yarn into yard of cotton or cloth. The poor hand-loom weaver now worked seventeen or eighteen hours daily, instead of the nine or ten hours he had worked before. Still the product of twnty hours of his labor represented now only ten social hours of labor, or ten hours of labor socially necessary for the conversion of a certain amount of yarn into textile stuff. His product of twenty hours had, therefore, no more values than his former product of ten hours.’
[7] Teks asli: ‘In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production..’