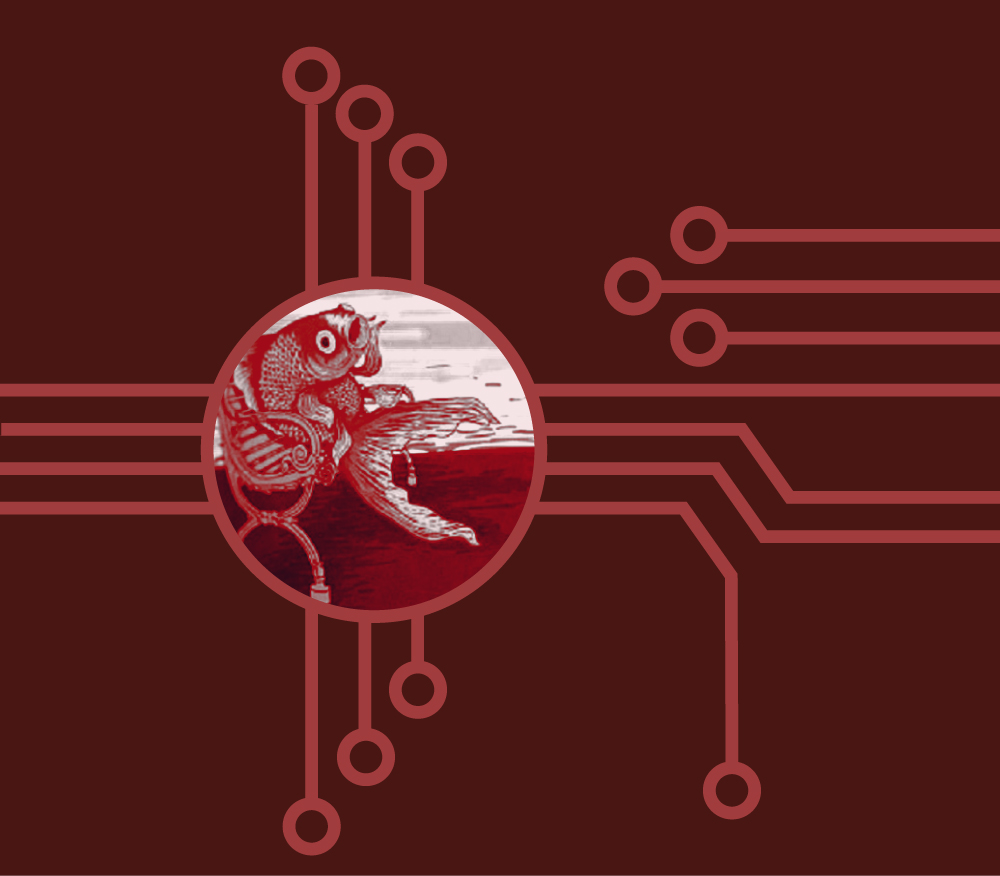KETIKA INTERNET mulai merasuki kehidupan kita, masih jarang ditemukan sebuah karya sastra yang mengangkat atau setidaknya menyinggung dengan signifikan Generasi Maya atau fenomena internet. Minimal secara tersirat menceritakan fenomena generasi tersebut. Novel Semusim, dan Semusim Lagi (2013) karya Andina Dwifatma, pada hemat saya, mengisi kekurangan tersebut.
Semusim diceritakan oleh tokoh Aku, seorang gadis 17 tahun, dengan gaya kilas balik; dimulai dari kelulusan gadis tersebut dari bangku SMA hingga dirawatnya ia di sebuah sanatorium untuk orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Semua narasi dimuntahkan oleh tokoh Aku. Hanya pada beberapa bagian saja ada narasi dari pihak di luar tokoh Aku, itu pun serba sedikit dan selalu dalam kerangka peresapan tokoh Aku.
Sejak kecil tokoh Aku hidup bersama ibunya, dokter ahli bedah otak yang cukup sibuk. Bagi tokoh Aku, mereka bukan hidup bersama, melainkan sekadar serumah. Sejak kecil hingga berumur 17 tahun, Aku dan Ibunya tidak sering berkomunikasi. ‘Tatap muka’ antara Aku dan sang ibu jarang terjadi. Namun demikian, ada satu hal penting yang membuat sang ibu berarti bagi Aku, yakni fasilitas yang disediakannya:
Ia tidak pernah cerewet soal uang dan fasilitas. Sebuah rak besar memenuhi satu sisi dinding kamarku, dari langit-langit sampai lantai, berisi segala jenis buku yang kumau. Sejak SMP aku dipasangkan komputer dan jaringan internet sendiri yang bebas kupakai 24 jam. Kukira alasan pertama, dan utama, anak-anak wajib menghormati orangtuanya, adalah karena orangtualah yang membayar internet mereka (Dwifatma, 2013: 41).
Penuturan ini, selain mengemukakan dingin dan renggangnya hubungan Aku dengan sang ibu, juga menegaskan betapa sentralnya internet dalam kehidupan Aku. Hal ini tampak lebih jelas ketika kita memperhatikan cara Aku ‘menghadapi dunia’. Refleksi ini disarikan dari pengalamannya sebelum terbang meninggalkan kota kediamannya menuju kota lain, yang masih satu pulau, untuk mengunjungi Ayahnya (yang ia namai Joe). Penerbangan tersebut adalah penerbangan pertamanya:
Malam sebelum berangkat, aku menghabiskan waktu dengan browsing sebanyak mungkin mengenai penerbangan. Ini kebiasaanku sejak SMP. Setiap kali aku akan melakukan sesuatu untuk pertama kali, aku akan mencari informasi dari internet, sebanyak mungkin agar aku merasa siap. Aku tidak suka menghadapi sesuatu dalam keadaan tidak tahu apa-apa; itu membuatku gugup dan gelisah (Dwifatma, 2013: 41).
Bagi Aku, Internet adalah teman, senjata, dan tameng untuk menghadapi dunia luar. Aku bisa digolongkan sebagai pengguna internet dengan kepentingan informasi (Information utility), yaitu untuk mencari informasi seperti informasi produk, informasi perjalanan, cuaca, informasi tentang film, musik, buku, berita, informasi sekolah, informasi kesehatan, pemerintah, informasi keuangan, informasi pekerjaan, atau informasi tentang politik, dll. Dengan kata lain, untuk menghadapi ‘realitas yang sesungguhnya’ Tokoh Aku terlebih dahulu mengintip realitas tersebut melalui ‘realitas maya’.
Pentingnya internet bahkan mengalahkan buku bagi Aku. Pada kutipan di atas kita tahu bahwa fasilitas yang diberikan Ibunya bukan hanya internet tetapi juga rak besar berisi segala buku yang disukainya. Dengan buku, yang dihadapi manusia adalah teks. Dengan internet manusia menghadapi hiperteks; teks berstruktur nonlinier yang berinteraksi dengan teks-teks lain serta grafis, suara, film, animasi, dsb. Di antara keduanya, Tokoh Aku lebih menganggap penting internet. Maka, buku yang begitu banyak itu sebenarnya menjadi sumber pengetahuan kelas dua baginya. Yang utama dan pertama adalah internet. Lebih jauh lagi, internet-lah yang membuat tokoh Aku merasa pede menghadapi dunia. Fenomena seperti inilah yang hendak saya labeli sebagai Generasi Maya. Generasi Maya adalah generasi yang menggunakan perangkat utama internet untuk berhadapan dengan dunia, realitas di luar mereka. Generasi Maya galibnya adalah kelanjutan dan bentuk paling radikal dari generasi digital.
Sebagai bentuk temutakhir dari generasi digital, tentu ciri-ciri dunia visual/dunia citra mengemuka pula. Di dalam Semusim hal ini nampak jelas. Dalam ‘kedongkolannya’ merasa hidup dengan orang asing di bawah satu atap, Tokoh Aku lantas membangun imajinasi tentang ibu kandungnya. Sosok ibu kandung yang asli itu lantas disematkannya pada karakter Agen Scully, salah satu tokoh dalam X-Files, sebuah serial televisi Amerika yang sempat juga diputar di salah satu televisi swasta Indonesia. Video klip sebuah lagu menjadi lebih penting bagi Tokoh Aku ketimbang lirik atau nada-nada dari lagu tersebut. Perhatikan gambarannya tentang lagu Selamat Malam dari Evie Tamala, “aku hafal lirik lagunya, dan aku suka bagaimana si penyanyi terlihat begitu sedih dan sendu padahal ia hanya mengucapkan selamat malam kepada pacarnya yang mau tidur” (Dwifatma, 2013: 15). Perhatikan juga bagaimana Aku menggambarkan perasaannya ketika mendapatkan surat dari ayahnya. Ia membayangkan sang ayah duduk pada sebuah tempat tersembunyi dan memanggilnya bak adegan khas dalam film-film era Humphrey Bogart. Perhatikan juga pemaparan Aku tentang mobil Peugeot:
Aku selalu suka mobil Peugeot karena mungil dan punya lampu depan seperti mata binatang, sehingga dengan plat mobil yang terletak di tengah-tengah bemper, ia seperti kumbang besar yang sedang nyengir. Aku suka gagasan tentang hewan yang ramah dan suka tersenyum (Dwifatma, 2013: 43).
Betapa sebuah imajinasi tentang mobil dan binatang yang hanya mungkin disumbangkan oleh sebuah film kartun dengan tokoh mobil yang punya ciri manusia. Film, sebuah bentuk pengejahwantahan kebudayaan visual yang paling populer, memang berhamparan dan bertebaran di keseluruhan Semusim.
Menggunakan referensi dari teks lain sebagai corak ekspresi literer merupakan strategi yang cukup lumrah dalam penulisan sastra kontemporer. Kita mengenalnya sebagai intertekstualitas. Cara penuturan ini memang menantang dan bisa membentuk penokohan secara lebih canggih. Dalam Semusim, Ia bisa menunjukkan betapa beragamnya pengetahuan Aku (atau, luasnya referensi sang penulis) selain itu juga merangsang pembaca untuk mencari lebih jauh, masuk lebih dalam pada pembacaan-pembacaan lebih lanjut. Permainan intertekstualitas sejatinya hendak mengatakan bahwa tak ada sebuah teks yang tunggal; sebuah teks senantiasa menjadi bermakna dalam hubungannya dengan teks yang lain.
Namun terkadang terlalu naif dan terburu-buru ketika kita mengatakan bahwa strategi meminjam film, lagu untuk membangun karakter atau menggambarkan suasana adalah permainan intertekstualitas. Permainan intertekstualitas sejatinya hendak mengatakan bahwa realitas yang sesungguhnya tak bisa terkatakan sehingga untuk memahaminya kita harus mencari pemahaman dari teks yang lain. Dalam beberapa karya-karya sastra, intertekstualitas ini terasa sebagai sebuah strategi yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Dalam negeri kita bisa menyebut cerpen-cerpen A. S. Laksana sebagai salah satu contohnya. Haruki Murakami pun bermain-main dengan strategi literer ini dan, agaknya, menjadi pengaruh yang terlalu besar bagi Semusim.
Kita bisa mengendus kesamaan antara Murakami, terkhusus dalam Norwegian Wood (2005), dengan Semusim. Penokohan Toru Watanabe dalam Norwegian Wood hampir mirip dengan Aku dalam Semusim. Mereka sama-sama suka membaca, suka mendengarkan musik, dan suka menyendiri. Mereka juga jatuh cinta dan bercinta di usia muda. Dalam Norwegian Wood, permasalahan kejiwaan mendapat tempat yang cukup sentral. Begitu juga pada Semusim. Jika Norwegian Wood menjadikan lagu ‘Norwegian Wood’ dari The Beatles sebagai ‘soundtrack’ utama cerita, bahkan diangkat menjadi judul, di Semusim ‘soundtrack’ utamanya adalah ‘Blowin’ In the Wind’ dari Bob Dylan–yang agaknya juga terpengaruh oleh Hardboiled Wonderland and the End of the World, novel Murakami yang lain, yang menjadikan lagu-lagu Bob Dylan sebagai ‘soundtrack’. Judul “Semusim dan Semusim Lagi” justru diambil dari sebaris puisi Sitor Situmorang yang menyumbangkan apa-apa untuk keseluruhan cerita. Terkesan hanya dicomot begitu saja.
Keserba-permukaan dan Kesosialan yang Alpa
Keanehan pertama yang muncul dalam novel ini tentu saja adalah penyebutan penuh rasa hormat dari tokoh Aku secara berulang-ulang pada Larry Page dan Sergey Brin. Kedua penemu mesin pencahari google ini terkesan begitu berjasa untuk hidup Aku. Larry Page dan Sergey Brin yang memberi tahu tata cara perkemahan Pramuka, Larry Page dan Sergey Brin yang memberi tahu tentang beberapa jurnal ternama yang disingkat menjadi JOE. Seolah-olah segala yang dimunculkan oleh google adalah kerja dari kedua orang itu saja. Padahal sejatinya kita tahu kedua orang itu hanya menciptakan mesin pencari dan masih banyak orang lain yang bekerja di bidang lain yang lantas memasukkan entri-entri tertentu.
Imajinasi tentang keriwehan kerja dan kerja-sama yang memungkinkan internet dan kesaling-terhubungannya menjadi konsumsi kita tak dipunyai Aku. Dalam penghormatan dan ketergantungan yang begitu tinggi pada internet, imajinasi Aku tentang kerja di balik internet ternyata tak ada. Dengan kata lain, watak sosial dari manusia yang akan selalu menampak dalam kerja bidang apa pun juga, tak terkecuali internet, tak ada sama sekali dalam isi kepala Aku.
Melalui intuisi Marxian kita bisa berkata bahwa realitas manusia dan dunianya yang sesungguhnya tak diindahkan oleh Semusim. Menurut Marx, keadaan alamiah manusia adalah kerja dan di dalam kerja itu selalu dan senantiasa menampak watak kesosialan manusia. Dengan kesosialan yang memungkinkan kerja inilah manusia menghadapi dunia. Demikian Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The German Ideology:
Premis pertama dari seluruh sejarah manusia ialah keberadaan individu-individu manusia yang hidup. Dengan demikian fakta utama untuk bertahan [hidup] adalah pengorganisasian yang bersifat fisik dari individu-individu ini dan konsekuensi relasi mereka dengan alam (Marx dan Engels, 1991: 42).
Perkara kesosialan memang menjadi masalah utama Tokoh Aku. Perhatikan ketika J.J. Henri dan Aku bercakap-cakap tentang musik blues. Ketika J.J. Henri menjelaskan bahwa musik blues adalah musik budak sehingga lirik-liriknya menggambarkan keadaan-keadaan yang dialami kaum marjinal, Aku menimpali bahwa semua manusia adalah budak sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. Di sini Aku membelokkan permasalahan pertentangan kelas, penindasan, menjadi masalah eksistensial individu. Padahal, dua hal ini jelas-jelas berangkat dari titik tolak yang sangat berbeda. Pertentangan kelas dan perlawanan atas penindasan, yang secara tersirat nampak dalam penjelasan J.J. Henri tentang blues, berangkat dari pemahaman bahwa manusia itu makhluk sosial dan semua manusia setara. Sedangkan eksistensialisme individualis, yang secara tersirat ada dalam penjelasan Aku selanjutnya, berangkat dari pengandaian bahwa manusia itu lahir sebagai individu yang sendirian dan merdeka. Dengan demikian, sekali lagi, perihal kesosialan ternyata alpa di dalam Semusim. Kesosialan disisihkan sedemikian rupa dan yang dikedepankan adalah perihal individualisme.
Tendensi penyisihan akan kesosialan ini ternyata bukan sekadar ‘visi’ Aku, melainkan bisa juga dikatakan sebagai ‘visi’ pengarang. Tentu saja di sini kita mengesampingkan bahwa setiap suara yang diutarakan dalam sebuah karya adalah perwakilan suara sang pengarang. Tetapi, yang saya maksudkan adalah dengan kutipan berikut hal itu semakin meyakinkan bahwa penyisihan kesosialan itu bukan sekadar karakter dari satu tokoh saja, melainkan bisa menjadi karakter dari keseluruhan cerita karena hal yang sama muncul pula dalam pandangan tokoh yang lain, yakni tokoh Muara. Perhatikan apa yang diungkapkan Muara ketika membicarakan perihal karya seni. Muara menjauhkan ‘realitas sesungguhnya’ sebagai sumber dari karya seni itu sendiri:
Sebuah karya seni,….,adalah genius pada dirinya. Sebagai penikmat, kitalah yang hebat karena bisa menangkap kegeniusannya. Seniman yang menghasilkannya hanyalah media yang memungkinkan karya itu lahir ke dunia, ibarat Maria melahirkan Yesus. Blowin’ In The Wind sudah ditakdirkan menjadi karya hebat yang menemani pergerakan warga kulit hitam pada akhir tahun 60-an (Dwifatma, 2013: 98).
Pertanyaan kita ketika membaca bagian ini adalah lantas apa ontologi, pendasaran, dari lahirnya karya seni? Apakah karya seni dibayangkan sebagai sebuah entitas yang bebas merdeka, lepas sama sekali dari apa pun, ada di sebuah tempat yang entah, dan oleh takdir datang pada suatu ketika? Apakah dia benar-benar lepas sama sekali dari peristiwa sosial—di dalam kutipan di atas peristiwa pergerakan warga kulit hitam—dan hanya datang sekonyong-konyongnya pada sebuah peristiwa tertentu?
Analogi yang digunakan Muara malah semakin memperkeruh usaha kita memahami, “…ibarat Maria melahirkan Yesus”. Analogi ini membuat karya seni seakan-akan sesuatu yang mistik, yang berada di luar dunia kita, barangkali di Surgaloka. Penulis, melalui Muara, menghancurkan dua hal penting dalam seni, yakni seniman dan kesosiologisan seni itu sendiri. Karya seni dipandangnya sebagai sesuatu yang tidak bisa tidak mistik, independen, dan tak berasal dari dunia. Sebuah klaim atau pemikiran yang bahkan tidak pernah ada pada pemikir-pemikir paling mistik dan teologis dalam sejarah filsafat seperti pada tradisi Skolastik Abad Pertengahan Eropa.
Lantas, kita bisa bertanya, dalam era Aku yang sudah melek internet—sebuah materialisasi dari kemajuan sains yang selalu berusaha mencari jawaban melalui penelitian yang cermat pada hal-hal material—bagaimana mungkin pernyataan yang bersifat mistik ini masih saja muncul? Padahal kita tahu dalam sejarah pemikiran, yang mistik selalu hadir ketika manusia tidak bisa dengan nalarnya sendiri mampu memecahkan sebuah masalah. Berlari kepada hal yang mistik sesungguhnya ciri ketakmampuan nalar manusia.
Kedangkalan bukan sekali itu saja muncul. Alkisah, Aku selalu menyebutkan buku Mimpi-mimpi Einstein dengan penuh hormat dan bahkan sudah membacanya sebanyak 1.000 kali. Einstein, kita tahu, adalah ilmuwan yang merumuskan teori relativitas dalam bidang fisika. Dan kita pun tahu, buku Mimpi-mimpi Einstein berisi tentang beberapa cerita seputar mimpi Einstein tentang waktu. Dengan membaca buku ini berkali-kali, apakah seseorang sebegitu bodohnya untuk tidak memahami sebuah kenyataan alam yang sederhana bahwa bumi-lah yang mengelilingi matahari dan bukan matahari yang mengelilingi bumi? Perhatikan ungakapan tentang senja yang puitis dari Aku:
Bola besar berwarna oranye itu semakin turun, turun, dan turun, seolah-olah di bawah sana ada seseorang yang menariknya dengan tali yang tak tampak. Dan semakin turun, semakin tua warnanya (Dwifatma, 2013: 61).
Dengan menggunakan ungkapan ‘turun’ untuk menggambarkan semakin hilangnya matahari di cakrawala, imajinasi Tokoh Aku yang menggambarkan hal itu tentu saja adalah bumi berada tetap di tempatnya dan mataharilah yang meninggalkannya. Padahal, jangankan Einstein, jauh sebelumnya, pada abad ke-15 M, Nicolas Cusa sudah menyatakan bahwa bumi haruslah senantiasa bergerak seperti juga benda langit lainnya sehingga pemahaman bahwa bumi adalah pusat Alam Semesta mulai dipertanyakan. Sekali lagi, kecanggihan dalam Semusim hanya tampak di permukaan namun di kedalamannya, kebodohanlah yang tampak. Jika pun alasannya untuk mengejar sebuah penggambaran yang puitis, saya kira realitas sesungguhnya—yakni bumilah yang mengelilingi matahari—bisa saja digambarkan dengan puitis. Kita bisa mencobanya demikian, “Bola besar berwarna oranye itu semakin hilang, hilang, dan hilang, seolah-olah ia mendorong bumi pergi menjauhinya, bagaikan kekasih yang tak mau pasangannya ikut menderita bersamanya.”
Kedangkalan pemahaman pun muncul ketika kita membaca kutipan-kutipan dari ranah filsafat dalam Semusim. Salah satu yang paling menonjol adalah pencatutan pemikiran Marcus Aurelius, seorang pemikir Stoik aliran filsafat zaman Romawi, yang dikutip oleh tokoh imajiner ciptaan Aku, Sobron. Alkisah, Aku berada di dalam tahanan polisi karena menikam Muara. Ia kalut menghadapi keadaan itu. Sobron datang dan mengutip Marcus Aurelius yang berbicara tentang realitas atau apa pun yang terjadi haruslah terjadi demikian. Marcus Aurelius memang membedakan antara ‘hal-hal yang tergantung pada manusia’ dan ‘hal-hal yang tak tergantung pada diri manusia’. Namun, untuk sampai pada penerimaan akan ‘apa yang tegantung pada manusia’ dan ‘apa yang tidak tergantung pada manusia’ ini, seseorang harus menjalankan sebuah laku hidup meditasi filosofis. Karena kedua pembedaan itu bisa dilakukan manusia ketika ia punya cara berpikir yang tepat untuk menghadapi peristiwa (Adot, 1998: 82-83).
Di dalam Semusim Aku tak terlihat sedikitpun melakukan sebuah meditasi filosofis, sehingga tidak bisa tidak, Sobron mengutip Marcus Aurelius hanya sebagai sebuah kata-kata indah, sebagai penghiburan atau motivasi alih-alih sebagai tawaran sebuah cara berpikir. Lantas, kenapa harus Marcus Aurelius dan bukan Mario Teguh? Supaya Semusim tampak lebih berbobot! Kutipan dari Mario Teguh pun tak ada yang berubah dari jalan cerita Semusim. Kutipan-kutipan filsafat dengan demikian hanya bunga-bunga penghias bangunan cerita, tanpa dipahami apa logika berpikir yang ditawarkannya, tanpa ada sedikit pun sumbangsih pemikiran itu untuk bangunan cerita. Sayang sekali.
Di sinilah salah satu wajah janus realitas maya internet kembali mengemuka. Internet, dunia maya, menghamparkan begitu banyak informasi pada Generasi Maya. Sehingga Generasi Maya begitu terpesona dan begitu merasa sudah mengetahui banyak hal dan memiliki pengetahuan tentang pelbagai hal itu. Padahal mereka justru hanyalah mendapatkan kedangkalan tumpukan infromasi atau sekadar susunan-susunan kalimat dengan kata-kata indah tetapi bukan pengetahuan. Hubert L. Dreyfus sudah sejak 2001 (tahun terbit bukunya On The Internet: Thinking In Action) mewanti-wanti hal ini (Supelli, 2013: 6).
Kegilaan sebagai Konsekuensi Generasi Maya?
Aku yang terasing dari kesosialan, terjejali tumpukan sampah informasi, terlepas dari ‘realitas sesungguhnya’, pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Kenyataan literer ini barangkali bisa dengan gampang kita jawab bahwa kecanduan terhadap internet memang sekarang dianggap sebagai salah satu gejalah klinis kelainan psikologis (Supelli, 2013: 5). Dengan demikian Aku, setidaknya sejak ia di bangku SMP, sudah mengalami kelainan psikologis. Tetapi kelainan psikologis berbeda dengan skyzofrenia atau gejala bipolar. Kedua jenis penyakit ini pengobatannya harus dilakukan melalui perawatan dokter dan jika cukup akut harus dilakukan terapi di rumah sakit jiwa.
Setelah Aku menikam Muara, ia divonis mengalami gangguan kejiwaan dan pada akhirnya dirawat di sebuah sanatorium untuk ODMK. Kelainan psikologis pada Aku menjadi semakin akut ketika ternyata Muara yang telah menciumnya, telah bercinta dengannya ternyata tidak mau bertanggung jawab, bahkan merayunya untuk menggugurkan bayi di kandungannya, meski pada akhirnya kita tahu bahwa kehamilannya itu pun hanya imajinasi Aku semata. Kenyataan literer yang patut dicatat adalah Muara merupakan orang pertama dan satu-satunya, setidaknya sampai akhir cerita, yang intim dan dekat dengan Aku. Muara dengan demikian adalah kontak sosial intim pertama Aku. Ternyata, kontak sosial ini tidak mencintainya dan bahkan tidak mau bertanggung jawab atas hasil dari perbuatannya. Inilah peristiwa yang memicu gangguan jiwa pada Aku.
Tokoh Aku sebelum pertemuan dengan Muara kita tahu adalah orang yang hanya bersentuhan dengan dunia melalui internet. Dengan demikian ia adalah contoh dari Generasi Maya yang begitu bertopang hidupnya pada ‘realitas maya’; suatu peristiwa atau entitas yang efeknya nyata tetapi tidak nyata sebagai fakta. Dan ‘realitas maya’ adalah ‘realitas sesungguhnya’ yang dihadirkan tidak dengan utuh. Aku juga adalah sosok yang terjejali begitu banyak informasi permukaan yang dianggapnya sebagai pengetahuan. Sosok yang berada dalam dua keadaan ini ketika bertemu dengan wajah ‘realitas sesungguhnya’—yang diwakilkan dengan interaksinya yang nyata dengan tokoh Muara—mendapatkan bahwa ternyata realitas yang dibayangkannya selama ini—yang dibangun oleh ‘realitas maya’—tidak benar seratus persen.
Dengan terus berinteraksi dengan ‘realitas sesungguhnya’ melalui ‘realitas maya’, manusia sesungguhnya menumpulkan kemampuan tubuh manusia yang penting, yakni berpartisipasi di dalam sebuah risiko. Padahal, upaya menghadapai berbagai risiko, yang hanya mungkin dilakukan dengan terlibat sungguh dalam ‘realitas sesungguhnya’, tubuh manusia belajar terus menerus untuk menanggulangi risiko (Pando, 2013: 14). Dengan terus bersembunyi di tengah ‘realitas maya’, Tokoh Aku menumpulkan kemampuan tubuhnya untuk menghadapi risiko ini. Alhasil, ketika berhadapan dengan ‘realitas sesungguhnya’ dengan risiko-risikonya, tubuh Tokoh Aku belum kuat untuk menghadapinya. Ia pun mengalami gangguan kejiwaan.
Generasi Maya hidup di jagad informasi dengan internet sebagai lokomotifnya. Mereka digampangkan segala sesuatnya, mereka dipermudah mengendus informasi yang berhamparan begitu banyaknya. Namun keterlenaan pada ‘realitas maya’ yang membawa pelupaan akan ‘realitas sesungguhnya’ membawa dampak-dampak yang cukup genting nan krusial. Pertama Generasi Maya bisa terjebak pada jagad visual dan kesulitan membahasakan secara langsung ‘realitas sesungguhnya’ yang ada di depan matanya. Kedua, informasi yang begitu beragam dan begitu banyaknya yang menampak padanya menunpulkan daya analitis dari Generasi Maya. Alhasil, begitu banyak yang bisa dibicarakan oleh mereka namun begitu sedikit yang mereka ketahui sampai ke akar-akarnya. Ketiga ketika Generasi Maya yang begitu bergantung pada ‘realitas maya’ bersinggungan dengan ‘realitas sesungguhnya’ dengan segala macam risiko yang berkelindan di dalam ‘realitas sesungguhnya’ dampaknya bisa fatal; contoh dari Semusim adalah kegilaan.
Inilah Wajah Janus Generasi Maya; generasi yang sedang tumbuh dan mekar di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Segala fasilitas tersaji di depan mata, segala kemudahaan tersedia di tangannya. Namun di saat itu ia pun rentan tercerabut dari ‘realitas sesungguhnya’ lantaran terlalu percaya pada ‘realitas maya’. Wajah Janus memiliki sisi indah rupawan dan sisi buruk rupa. Percaya dan bergantung sepenuhnya pada ‘realitas maya’ membawa kita pada kehilangan sense akan kesosialan dan keaktualan. Kita pun menatap sisi buruk rupa Wajah Sang Janus. Menempatkan ‘realitas maya’ sebagai sekadar instrument untuk memahami ‘realitas sesungguhnya’ sehingga sense akan kesosialan dan keaktualan tak hilang dari kebertubuhan kita barangkali membawa kita pada sisi jelita Wajah Sang Janus. Atau jangan-jangan kita akan terus-menerus secara dialektis berada di antara dua tegangan itu?
* Berto Tukan adalah mahasiswa Program Magister STF Driyarkara dan redaktur majalah kebudayaan online Lembar Kebudayaan IndoProgress. (berto.tukan@gmail.com)
** Versi lebih panjang dari tulisan ini pernah dipublikasikan di Jurnal Ultima Humaniora, edisi keempat, September 2014.
Daftar Bacaan
Adot, Pierre. The Inner Citadel, diterjemahkan oleh Michael Chase, London: Harvard University Prerss (1998).
Baudrillard, Jean. Simulations, New York: Semiotext(e) (1983).
Beardsley, Monroe C. Aesthetics from Cllasical Greece to The Present: A Short History, Alabama: University of Alabama Press (1985).
Cohen-Solal, Annie. Jean-Paul Sartre: A Life, diterjemahkan oleh Anna Cancogni, New York: The New Press (2005).
Dwifatma, Andina. Semusim, dan Semusim Lagi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2013).
Hill, David T. dan Krishna Zen. The Internet in Indonesia’s New Democracy, Oxon: Routledge (2005).
Macherey, Pierre. A Theory of Literary Production, diterjemahkan oleh Geoffrey Wall, London: Routledge & Kegan Paul Ltd. (1978).
Marx, Karl dan Friedrich Engels. The German Ideology: Part One, diedit oleh C. J. Arthur, London: Lawrence & Wishart (1991).
Montgomery, Kathryn C. Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in The Age of the Internet, Cambridge: The MIT Press (2007).
Murakami, Haruki. Norwegian Wood, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (2005).
Postman, Neil. Menghibur Diri Sampai Mati: Mewaspadai Media Televisi, diterjemahkan oleh Inggita Notosusanto. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (1995).
Prasetyo, Arif Bagus. “Tamzil tentang Zaman Citra: Perihal Segugusan Cerpen Nukila Amal,” dalam Zen Hae (peny.), Tamzil Zaman Citra: Bunga Rampai pemenang Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2007, Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta (2007): 3-29.
Shields, Rob. The Virtual, London: Routledge (2003).
Suryajaya, Martin. Materialisme Dialektis: Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogyakarta: Resist Book (2012).
Jurnal dan Majalah:
Oktavianti, Riliana. “Makna Menubuh dalam Dunia Maya,” Jurnal Filsafat Driyarkara Tahun XXXIV No. 3/2013: 55-66.